Mpu Kuturan dalam Teks Tutur
on
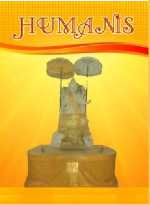
p-ISSN: 2528-5076, e-ISSN: 2302-920X
Terakreditasi Sinta-3, SK No: 105/E/KPT/2022 Vol 27.3. Agustus 2023: 301-313
Mpu Kuturan in Tekt Tutur
I Nyoman Suka Ardiyasa
STAH N Mpu Kuturan Singaraja, Bali, Indonesia
Email korespondensi: suka.ardiyasa@stahnmpukuturan.ac.id
Info Artikel
Masuk:20 Januari 2023
Revisi: 10 Juli 2023
Diterima:20 Juli 2023
Terbit:31 Agustus 2023
Keyword :
Mpu Kuturan; Text Tutur
Kata Kunci : Mpu Kuturan;
Teks Tutur
Corresponding Author:
I Nyoman Suka Ardiyasa email:
suka.ardiyasa@stahnmpukutu ran.ac.id
DOI:
Abstract_______________________________________________
Manuscripts that mention Mpu Kuturan are found in various genres, such as speech texts, babad, usadha, kalpasastra, and inscription texts. The purpose of writing this scientific article is to explain in depth about the character Mpu Kuturan contained in the text Tutur of the Gedong Kirtya Singaraja collection. The analysis was carried out using a qualitative text method approach, also known as text interpretation research. The results of the research conducted obtained information that Mpu Kuturan, as a religious figure, had revitalized the Besakih temple and also taught the teachings of the Purana Tatwa, the Dewa Tatwa, the Widhisastra, Kusumadewa, Padma Bhuwana Prakempa, and Tingkahin Angwangun Kahyangan. Meanwhile, the ideology of Mpu Kuturan as an architect was found in Mpu Kuturan's thoughts on managing and perfecting the Besakih area, designing the establishment of Depangih méru, and managing palemahan with the concept of catur loka pala.
Abstrak
Naskah-naskah yang menyebutkan Mpu Kuturan dijumpai pada berbagai generé seperti naskah tutur, babad, usadha, kalpasastra dan naskah prasasti. Tujuan penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk menjelaskan secara mendalam tentang tokoh Mpu Kuturan yang dimuat dalam naskah tutur koleksi Gedong Kirtya Singaraja. Analisis dilakukan dengan pendekatan metode teks kualitatif atau yang dikenal sebagai penelitian tafsir teks. Hasil penelitian yang dilakukan memperoleh informasi bahwa Mpu Kuturan sebagai tokoh agama telah melakukan revitalisasi pura Besakih, juga mengajarkan ajaran Purana Tatwa, Dewa Tatwa, Widhisastra, Kusumadewa, Padma Bhuwana Prakempa dan Tingkahing Angwangun Kahyangan. Sedangkan ideologi Mpu Kuturan sebagai arsitek dijumpai dari pemikiran Mpu Kuturan dalam menata dan menyempurnakan kawasan Besakih, merancang pendirian pelinggih méru dan menata palemahan dengan kosep catur loka pala.
-
I. PENDAHULUAN
Masyarakat Bali sangat menghormati Mpu Kuturan karena dia berperan penting dalam mengatur sistem religius Bali. Pada tahun 927 çaka atau 1005
Masehi, dia melakukan banyak hal untuk merevitalisasi pura-pura yang ada di Bali, termasuk melakukan pemlaspasan dan mengubah bentuk Pura Besakih. Dipercaya bahwa Mpu Kuturan telah
mengubah cara pemujaan, menurunkan Pasek dan kaum Bendésa. Dia juga merekomendasikan penggunaan mantra dalam bahasa Sansekerta dan Bali (Shastri, 1986:50).
Banyak naskah menyebutkan Mpu Kuturan atas peranannya dalam berbagai aspek tokoh, seperti dalam Prasasti, Babad, Usadha, Kanda, Kalpasastra, dan Tutur. Dia disebut sebagai tokoh agama, peng-usadha, dan akhirnya menjadi pejabat kerajaan yang bergelar Senāpati Kuturan, yang merupakan posisi penting di kerajaan pada waktu itu. Salah satu naskah mengatakan bahwa Mpu Kuturan membangun méru di Besakih. Hal ini seperti yang disebutkan dalam naskah tutur koleksi Gedong Kirtya dengan Nomor III B/24/753 yang berjudul Mpu Kuturan, disebutkan Nihan lingira Mpu Kuturan riŋ Majapait, duk aŋawaŋuna méru riŋ Basakih yang bermakna inilah sabda Mpu Kuturan di Majapahit, ketika akan membangun méru di Besakih. Kalimat tersebut terdapat di awal kalimat yang dilanjutkan dengan jenis dan tata cara pendirian méru di Besakih. Penjelasan yang sama juga dapat dijumpai dalam naskah lontar yang berbentuk tutur dengan Nomor 172 IIIb/2 dengan judul Empu Kuturan Koleksi Gedong Kirtya yang terdiri atas 14 lembar naskah lontar pada halaman pertama baris kedua disebutkan tentang Mpu Kuturan yang mendapatkan penugrahan widhi sastra berupa pengetahuan agama yang dibawa ke Bali untuk menata tatanan masyarakat Bali.
Pada lembar kelima baris pertama dari naskah Babad Usana Bali yang dikumpulkan oleh Pusat Dokumentasi Bali dengan Nomor Kal 75, disebutkan bahwa Mpu Kuturan membantu menyempurnakan sejumlah kahyangan yang ada di Bali, termasuk kahyangan tiga, sad kahyangan, dan Besakih, yang merupakan kahyangan tertinggi. Ketiga naskah menunjukkan bahwa Mpu Kuturan berkontribusi pada penyebaran
konsep keagamaan kepada masyarakat Bali dan mengajarkan mereka untuk membangun tempat suci, seperti méru dan pura kahyangan lainnya. Ini sejalan dengan apa yang dikatakan Watra bahwa Mpu Kuturan membantu menggabungkan kepercayaan Siwa, Budha, Waisnawa, dan sekte lain di Bali, yang kemudian diikuti oleh paruman di Bedahulu Gianyar, yang setuju bahwa konsep tri murti merupakan tanda penyatuan sekte-sekte tersebut (Watra, 2018: 118).
Berbeda dengan yang termuat dalam naskah prasasti, ditemukan istilah Senāpati Kuturan yang merupakan jabatan struktural pemerintah Bali Kuno yang tergabung dalam lembaga kerajaan yang disebut Pakirakira I Jro Makabéhan. Jabatan pada kerajaan Bali Kuno berdasarkan hirarkinya atau garis perintahnya dan wilayahnya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu (1) jabatan tingkat pusat dan jabatan tingkat desa. Jabatan tingkat pusat yang jabatannya diakui oleh seluruh wilayah kerajaan terdiri atas (a) Raja/Maharaja/Haji, (2) Senāpati, (3) Samgat, dan (4) Mpungku. Jabatan Sen, Samgat dan Mpungku, sedangkan jabatan pada tingkat desa terdiri atas: (1) Rama adalah orang yang bertugas memimpin sebuah Karāman, (2) Sang Mathāni adalah orang bertugas mengurus tanah di desanya, (3) Mañuratang adalah orang yang bertugas mencatat keadaan desanya (sekretaris desa), dan (4) Juru Krtta Deśa adalah orang yang bertugas menjaga keselamatan dan keamanan desanya (Wiguna, 2008: 18). Sesuai dengan pembagian tersebut Senāpati Kuturan jelas merupakan jabatan yang sangat penting, bahkan seperti yang diungkapkan Parimartha jabatan Senāpati Kuturan dapat disebut sebagai wakil raja dalam hubungannya ke bawah (masyarakat) (Parimartha, 2003: 12).
Śri Mahārāja Haji Jayapangus, yang berkuasa dari tahun 1099 Saka (1178 M) hingga 1103 Saka (1181 M), menulis banyak Prasasti Bali, termasuk Prasasti
Sukawana, Prasasti Langgahan, Prasasti Bwahan, dan Prasasti Sembiran, yang menggambarkan Mpu Kuturan sebagai seorang Senāpati yang sangat berkuasa dan dihormati di seluruh wilayah kerajaan. Tata cara upacara diatur oleh Senāpati Kuturan, pejabat kerajaan. Banyak jenis naskah yang menyebutkan Mpu Kuturan dan Senāpati Kuturan menunjukkan bahwa tokoh ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Bali di masa lalu. Oleh karena itu, artikel ilmiah ini akan membahas Mpu Kuturan yang termuat dalam Teks Tutur dan berusaha untuk memberikan gambaran tentang sosok Mpu, yang telah dikenal dari masa ke masa dalam berbagai ideologi dan telah banyak mewujudkan tonggak dalam berbagai tradisi.
METODE DAN TEORI
Penelitian ini menggunakan pendekatan teks kualitatif, juga dikenal sebagai penelitian tafsir teks. Pendekatan ini menggunakan teks terikat untuk menafsirkan dan memahami apa yang mereka katakan dalam suatu konteks, ruang, dan masa tertentu. Penelitian ini fokus pada naskah tutur. Metode pengumpulan data terdiri dari pemetaan naskah-naskah yang memuat Mpu Kuturan, khususnya genre tutur yang ada di koleksi perpustakaan Gedong Kirtya Singaraja. Data primer dan sekunder adalah sumber penelitian ini. Data primer berasal dari teks tutur yang berisi Mpu Kuturan, sedangkan data sekunder berasal dari sumber data tambahan seperti foto, alih aksara, arsip, dan lainnya. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan proses alih aksara dan terjemahan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.
Setelah data yang terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisis melalui tahapan kerja metode filologi yang diterapkan dalam penelitian ini bukanlah metode stemma yang melacak wujud teks
asal, namun berpijak pada ciri-ciri khas teks dan kondisi pernaskahan Bali yang tidak selalu memungkinkan menerapkan metode stemma, terutama karena tidak ditemukan adanya kesalahan bersama dalam naskah-naskah yang menyebutkan keberadaan Mpu Kuturan dalam teks yang telah dipetakan sebelumnya. Sehubungan dengan itu, naskah asli tidak akan dicari, namun diarahkan untuk menentukan naskah yang autoritatif, yakni naskah yang dianggap paling baik dari semua naskah yang ada, terutama dari segi isi dan bahasanya (Djamaris, 2002:15).
HASIL DAN PEMBAHASAN
-
1. Gedong Kirtya Sebagai Sumber Naskah Tutur
Perpustakaan Gedong Kirtya merupakan Perpustakaan lontar yang cukup tua berdiri sejak tahun 1928. Sejarah berdirinya Gedong Kirtya tidak bisa dipisahkan dari nama tokoh Belanda, Ahli Linguistik yang telah menetap di Bali yang bernama H.N.Van der Tuuk. Beliau adalah Ahli Linguistik di bidang bahasa Bali, Jawa Kuno, Melayu dan bahasa daerah lainnya. Perjalanan karir dari H.N.Van der Tuuk dengan bekerja di Batak sebagai peneliti dan ahli bahasa Batak. Van der Tuuk menghabiskan sekitar 40 tahun lamanya mempelajari bahasa Bali dan Jawa Kuno, mengoleksi berbagai manuskrip lontar dan salinannya. Dalam melakukan penelitiannya di Bali H.N.Van der Tuuk ditemani dan dibantu oleh para Sastrawan kidung, tembang dan kakawin. Perjalanan dalam kurun waktu 40 tahun tersebut berhasil menghimpun naskah-naskah lontar yang ada di Bali dan Lombok. Van der Tuuk wafat tanggal 17 Agustus 1888 (Sugi Lanus, dkk, 2019: 2).
Pada kisaran tahun 1928-an, residen pemerintah Belanda di Bali dan Lombok yang bernama L.J.J Caron datang ke Bali bertemu dengan para raja dan tokoh agama untuk berdiskusi mengenai
kekayaan sastra (lontar) yang ada diseluruh Bali. Pertemuan tersebut berlangsung di Kintamani pada tanggal 2 Juni 1928 yang melahirkan sebuah Yayasan (stiching) tempat penyimpanan manuskrip lontar yang dimotori oleh para peneliti manuskrip pada masa itu, seperti Dr. R. Ng. Purbacaraka, Dr. W.r. Stuterheim, Dr. R Goris, Dr. Th Pigeaud, Dr. C. Hooykaas. Sementara petugas aktif adalah para pendeta dan raja-raja seBali dan Lombok secara aktif mendukung kegiatan ini, baik bantuan material tertutama bantuan akses menyalin berbagai manuskrip lontar yang disimpan di rumah penduduk, baik kaum bangsawan dan pendeta, yang pada masa itu sangat menyakralkan koleksi manuskripnya.
Setelah pertemuan tersebut, pada 14 September 1928, kelompok ini secara resmi membuka perpustakaan pertama mereka di Bali dengan nama "Kirtya Lefrink-Van der Tuuk". Namanya diambil dari asisten residen pemerintah Belanda di Bali yang sangat tertarik dengan kebudayaan Bali dan Lombok, dan "Van der Tuuk" diambil dari nama seorang ahli linguistik yang sangat tertarik dengan bahasa Bali. Raja Buleleng, I Gusti Putu Djelantik, pertama kali menggunakan kata "kirtya". Namun, kata "kirtya" berasal dari kata Sanskerta "krtya", yang berarti "usaha" atau "jerih payah" (Sugi Lanus, dkk, 2019: 3).Manuskrip lontar di Bali terdiri atas berbagai jenis dan terbagi menjadi beberapa kelompok tertentu. Pengelompokan manuskrip ini disesuaikan dengan kandungan isi naskah maupun ragam bentuk yang membangun naskah, umumnya ragam bentuk prosa dan tembang. Gedong Kirtya sendiri memiliki koleksi manuskrip lontar yang beragam, dan memiliki sistem pengelompokan tersendiri untuk koleksinya. Gedong Kirtya mengelompokan koleksi manuskripnya menjadi tujuh kelompok, di antaranya sebagai berikut:
-
1. Kelompok Weda, meliputi lontar-lontar yang berisi: (a) Weda-Weda yang terwariskan di Bali, memakai bahasa Sansekerta, Jawa Kuno dan Bali; (b) Mantra yang menurut perkembangannya berasal dari Jawa dan Bali; (c) Kalpasasastra adalah ajaran, pedoman, petunjuk praktis, dan penjelasan fungsi upacara-upacara keagamaan.
-
2. Kelompok Agama, meliputi lontar-lontar yang berisi: (a) Palakerta yang berisikan tentang peraturan dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan seperti:
Dharmasastra, Kertasima dan Awig-awig; (b) Sesana, buku petunjuk
tentang panduan kesucian dan landasan moral unluk menjalani tugas dan profesi; (c) Niti adalah ajaran menyangkut hukum ataupun perundang-undangan yang
dipergunakan pada zaman kerajaan.
-
3. Kelompok Wariga, meliputi lontar-lontar yang berisi: (a) Wariga yaitu pengetahuan tentang astronomi dan astrologi, perhitungan baik-buruk hari untuk dipakai pedoman upakara, perjalanan, upakara; (b) Tutur pada umumnya berbentuk upadesa (petuah berbentuk dialog antara guru dan murid) berisi ajaran filsafat, pengetahuan tentang makrokosmos dan mikrokosmos, kegaiban, dan membahas hal-hal yang erat hubungannya dengan keagamaan secara lebih mendalam; (c) Kanda yaitu tentang ilmu bahasa, bangunan, mitologi, dan ilmu pengetahuan khusus; (d) Usadha pengobatan tradisional, baik pendekatan herbal dan black magic.
-
4. Kelompok Itihasa terdiri dari lontar-lontar yang terdiri dari: (a) Parwa yang ditulis dalam bentuk prosa; (b) Kakawın adalah tembang dalam metrum India Kuno dan Jawa Kuno; (c) Kidung adalah kesusastraan yang terdiri dari Tembang Tengahan
(Sekar Madya) dengan bahasa Kawi atau Jawa Kuno Tengahan; dan (d) Geguritan adalah kesusastraan yang terdiri dari Sinom, Pangkur, Dandanggula tembang macapat seperti, dan sebagainya, yang ditulis dalam Bahasa Kawi dan Bali.
-
5. Kelompok Babad, meliputi lontar-lontar yang berisi: (a) Pabancangah, Babad, Usana adalah kesusastraan yang berisi asal-usul kekeluargaan dan silsilah; (b) Riwayat yang mengandung unsur sejarah seperti : Harsawijaya, Panji Wijayakrama, Rangga Lawe (mula berdirinya kerajaan Majapahit), serta riwayat runtuhnya kerajaan-kerajaan yang diubah dalam bentuk tembang seperti: Rusak Buleleng, Rereg
Gianyar, Uwug Badung; (c)
Pengeling-eling adalah catatan-catatan lepas perseorangan, raja-raja, pendeta, atau leluhur, yang berisi angka tahun dan peristiwa.
-
6. Kelompok Tantri, meliputi lontar-lontar yang berisi: (a) Ceritra-ceritra dengan induknya berasal dari kesusastraan India Kuno (berbahasa Sansekerta); (b) Tantri Kamandaka; (c) Satwa Pagantihan Bali (Folklore) ceritra-ceritra rakyat dengan pengaruh Tantri dan ataupun asli Bali.
-
7. Kelompok Lelampahan, meliputi lontar-lontar yang terdiri dari lakon-lakon yang dipergunakan dalam pertunjukan pertunjukan gambuh, pementasan wayang, teater arja, dan lain sebagainya.
Seluruh data pada buku ini adalah manuskrip-manuskrip yang mengandung "teks sejarah" dalam kelompok 5 (V)
pada koleksi Gedong Kirtya. Identitas dan penomoran manuskrip dalam buku ini mengikuti alfabet judul dengan menyertakan nomor-nomor yang sistematisasinya mengikuti penomoran
kropak (kotak kayu) penyimpanan sebagaimana terdapat di Gedong Kirtya.
-
2. Identitas Naskah Tutur
-
a. Naskah Mpu Kuturan Nomor
Naskah 753.IIIb
Naskah berjudul Mpu Kuturan ini merupakan naskah koleksi Gedong Kirtya dengan nomor 753.IIIb yang tersedia dalam bentuk Lontar dan Alih Aksara. Pada bagian kanan atas naskah berisikan tulisan Mpu Kuturan pemberian Pedanda Ketoet Boeroean dari Pagesangan Lombok. Naskah ini terdiri atas 5 (lima) lembar lontar yang berisikan tulisan bolak-balik beraksara Bali berbahasa Kawi. Ukuran masing-masing lembar naskah ini adalah 50,2 x 3,4 cm dan kondisi naskah masih utuh sehingga mudah dibaca. Setiap lembar naskah ini berisi 4 baris tulisan yang ditulis dari kiri ke kanan, panjang naskah ini adalah 51 cm dan lebar 3,2 cm.
Isi naskah ini tentang tata cara pembuatan pedagingan untuk pelinggih dimana pedagingan itu terdiri atas 4 jenis logam, yaitu perak, tembaga, emas, besi serta menggunakan permata mata utama. Pedagingan itu juga memiliki tingkatan-tingkatan seperti tingkatan utama, tingkatan madya dan tingkatan nista. Naskah ini juga menguraikan tentang bentuk-bentuk pedagingan seperti bentuk binatang (bebek, bedawangnala, udang dan bintang lainnya yang digunakan dalam upacara ngelinggihang.
Naskah yang berjudul Hempu Kuturan merupakan naskah koleksi Gedong Kirtya yang juga tersedia dalam bentuk Naskah Lontar dan Alih Aksara. Naskah ini terdiri atas 61 Lembar Lontar dengan kondisi masih sangat terawat. Ukuran naskah ini memiliki panjang 51
cm dan lebar 3,8 cm. Naskah ini bersumber dari Griya Sibang Kaler yang tertulis pada pojok kanan naskah sebagai berikut “Druwen Geria Sibang Kaler, Abyansemal, Badung”. Ukuran masing-masing lembar naskah ini adalah 50,2 x 3,4 cm dan kondisi naskah masih utuh sehingga mudah dibaca. Setiap lembar naskah ini berisi 4 baris tulisan yang ditulis dari kiri ke kanan. Naskah ini berisikan tentang Peran Mpu Kuturan dalam melakukan penyempurnaan Pura-Pura yang ada di Bali serta bebantenan yang digunakan dalam rangka Piodalan.
Naskah tutur adalah naskah yang berisikan tentang ajaran-ajaran yang erat hubungannya dengan keagamaan dan etika. Naskah ini biasanya cendrung berisikan tatacara melakukan kegiatan keagamaan seperti sarana upakara yang harus dipakai, mantra yang harus diucapkan serta larangan-larangan yang harus dihindari oleh umat dalam melaksanakan berbagai ritual upacara. Berikut adalah jumlah penyebutan Mpu Kuturan dalam naskah tutur koleksi Gedong Kirtya:
Pada naskah Mpu Kuturan Nomor Naskah 753.IIIb menyebutkan nama Mpu Kuturan sebanyak 9 kali yaitu pada lembar 2a sebanyak 4 kali, pada lembar 5a 1 kali, pada lembar 6b sebanyak 1 kali, pada 7a sebanyak 1 kali, dan lembar 13a sebanyak 2 kali. Pada lembar 2a disebutkan sebagai berikut:
2a. ”Nihan widhisāstra anugraha Widhi Bhatara Jagatnatha ri sira Mpu Kuturan, yatika ana adji sastrāgama katama dé Sang Prabhu ring jagat, sangké pawarah Mpu Kuturan aran
witéng wilatikta, duking sira Mpu Kuturan kautus maring Besakih, ngwangun meru ring Besakih panembah ing ratu Bali”. Katular méru ring Besakih méru mas ring Giri Sumeru, mwang lingga ning parhyangan bumi sami pikandania, waluya ring Giri Mahāméru, muwang lingga ning pasamuan agung, matata lingga ning méru, ana cendet aluhur ring Besakih, ana akasa wakya bhatara Jagatkarana, agama adji Bali Purana tattwa dé Sang Mpu Kuturan.
Terjemahannya :
2a. Inilah Widhi Sastra wahyu dari Bhatara Jagatnatha kepada Mpu Kuturan, sehingga adalah pengetahuan tentang sastra agama yang diwarisi oleh Para Raja di Dunia, dari ajaran Mpu Kuturan yang berasal dari Majapahit; ketika Mpu Kuturan diutus datang ke Besakih membangun di Besakih, sebagai tempat pemujaan raja Bali, meniru meru emas di Gunung Semeru, serta lingga tempat suci di dunia beserta seluruh prihalnya, seperti di Gunung Mahameru, demikian pula altar Pesamuan Agung yang diatur penataanya posisi meru ada yang pendek ada yang tinggi di Besakih; adalah sabda dari langit yang diturunkan oleh Bhatara Jagatkarana yaitu aturan yang disebut Aji Bali Purana Tattwa kepada Mpu Kuturan.
Selanjutnya pada lembar 5a disebutkan sebagai berikut :
Wus tinunggwéng papan dénira Mpu Kuturan ginawa maring Bali Rajya, mangda pageh silakrama ning sang catur warna ring Bali, aywa salah surup paran ing sembah katama tekéng dlaha.
Selanjutnya pada lembar 6 b disebutkan sebagai berikut:
Yan wong sudra olih nambet pratima emas, mirah, parab Bhatara Manikukir, yogya satrehnya sudra ika
nembah nungsung, mangkana ling sira Mpu Kuturan tinunggwing papan.
Selanjutnya pada lembar 7a bagian akhir disebutkan sebagai berikut :
Kéwala ana né tan wenang nembah nyungsung, sang prabu, sang ksatria Mantri, Punggawa, Triwangsa, réh widhi ika kasambut olih wang sura janma, kéwala madwa aji wenang nembah nyungsung, mangkana ling sira Mpu Kuturan.
Selanjutnya pada lembar 13a disebutkan sebagai berikut:
niti sakeng dewatatwa, tingkaḥ ngwangun palinggiḥ widhi, mangda tan harohara niti ring widhi. padmasaṇa rong tri, palinggiḥ Ida mpu tribhuwana, gĕdong jampel palinggih mpu magata-magati. hana palinggiḥ bale tĕngaḥ saka pat, palinggiḥ Ida mpu ngaruraḥ; hana gĕdong mañjangan salwang,
palinggan Ida mpu kuturan; hana palinggiḥ bale rong tiga, palungguḥ Ida bhaṭara sinuhun ring gunung Agung; hana gĕdong pañimpĕnan, wenang maka pañimpĕnan bantĕn haturan mwang panganggene ring kahyangan ne sarwa utama; hana bale paruman palinggiḥ ngaturang pasucyan bhaṭara rangken wali, ring bhaṭara kawitan kabeḥ; hana gĕdong singhaśari; palinggihanya watĕk widyadara-widyadari mahyanghyang, rayunan putiḥ kuning, sĕkar sarwwa mĕrik, lĕngawangi, buratwangi, rantasan putiḥ kuning, mangkana krama ning madewatatwa, saking niti pawarah sira mpu kuturan.
Terjemahanya :
Aturan berdasarkan lontar dewa tattwa, tatacara membangun altar untuk memuja Tuhan, agar tidak melanggar aturan yang diwahyukan
oleh Tuhan. Padmasana yang ruangannya tiga tempat berstananya Ida Mpu Tribhuwana; Gedong Jampel (Gedong yang memiliki 2 ruangan) sebagai stana memuja Mpu Maganta-Maganti. Ada juga altar/bale tengah yang memiliki empat tiang sebagai stana Ida Mpu Ngarurah. Ada/Gedong Menjangan Saluwang sebagai stana Ida Mpu Kuturan. Ada Altar Suci Bale Rong 3 (Gedong yang mempunyai 3 ruangan) sebagai tempat berstananya Sang Hyang Tiga. Altar Sanggar Agung sebagai tempat berstananya Ida Bhatara Sinuhun di Gunung Agung. Ada Gedong Penyimpenan boleh digunakan sebagai tempat menyimpan sajen serta kain-kain yang digunakan untuk menghias di Pura tersebut, menyimpang benda-benda penting di Pura bersangkutan. Ada juga Bale Paruman sebagai tempat mempersembahkan pesucian ke hadapan para dewa. Ada Gedong Singhasari tempat berstananya Widyadara- Widyadari ketika bercengkrama, sesajen yang dipersembahkan, nasi berwarna putih dan kuning, kembang yang beraroma wangi, minyak wangi burat wangi kain yang dilipat berwarna putih kuning. Demikianlah tata cara yang termuat dalam Dewa Tattwa aturan yang diajarkan oleh Mpu Kuturan.
Lontar Mpu Kuturan Nomor B/2/172 koleksi Gedong Kirtya ini berisikan tentang Pralinggan Widhi atau Prelambang Dewata yang terbuat dari permata emas perak maupun uang kepeng, selanjutnya ada ciri-ciri dari pretima tersebut bila didapatkan oleh Sang Catur Wangsa bila brahmana yang telah menguasai ajaran dharma dan ksatria utama yang mendapatkan pretima berbentuk/menyerupai dewa Jagatnata setelah diupacarai boleh disembah oleh Raja dan pejabat kerajaan bila seorang Wéisya mendapatkan pretima kemudian
diupacarai boleh dijunjung oleh kaum Wéisya dan Sudra, bila Sudra yang mendapatkan pretima hanya boleh disungsung oleh Sudra saja. Pretima yang didapatkan oleh Sang Sadhaka disebut Pretima Bhatara Jagatnatha; yang didapatkan oleh sang ratu disebut Bhatara Pasupati, yang didapatkan oleh ksatria disebut Bhatara Putrajaya, yang didapatkan oleh Weisya disebut Bhatara Manik Gumawang, yang didapatkan oleh Sudra disebut Bhatara Manik Ukir. Kemudian naskah ini juga berisi tata krama sang ratu Bali ketika membangun méru yang atapnya bertingkat 11 maupun yang bertingkat 9 agar wajib menyediakan sawah sebagai jaminan/ bukti. Menguraikan juga tentang tata cara Sang Catur Warna membangun Prahyangan di Desa Pakraman. Kemudian uraian tentang pertanda-pertanda buruk yang terjadi di Kahyangan (pura) juga disertai juga upakara dan sejajen menetralisasi pertanda buruk tersebut. Naskah ditutup dengan tata krama bersembhyang pada sebuah Pura atau Kahyangan.
Secara umum naskah ini menyebutkan nama Mpu Kuturan sebanyak 2 (dua) kali yang terdapat pada lembar judul dan pada lembar 2a. Berikut adalah kalimat yang menunjukkan penyebutan nama Mpu Kuturan.
Nihan lingira Mpu Kuturan ring Majapait, duk angawanguna meru ring Basakih, Kramania: yan meru tumpang 5, tumpang 7, tumpang 9, tumpang 11, Ikang mangkana, ana padagingania inenah ngkana. Nihan patatania: yan matumpang 11, ring dasarnia mési pinda prabot manusa mawadah kawali waja, tekaning siap-mas mwang slaka; Kacang mas kacang-slaka; tumpeng-mas tumpeng slaka; sampian-mas sampian-slaka; panyeneng-mas panyeneng slake,
bebek-mas bebek slaka, ring dasar pisan badawang-mas badawang-slaka; naga-mas naga slaka, pada marata mirah, tekéng pripih mas slaka tembaga, jaum 4 katih mas slaka tambaga wesi; mwah podi mirah kwehnia manut wilangan ing tumpang. pripih teka ning jaum ika mawadah rapetan putih, tur madaging wangi.
Terjemahannya :
Inilah sabda Mpu Kuturan di Majapahit, ketika akan mendirikan méru di Besakih, tata caranya sebagai berikut: Jika méru dengan atap bertingkat 5, atap bertingkat 7, atap bertingkat 9, atap bertingkat 11, adalah pedagingan yang diletakkan di sana. Berikut susunannya jika méru dengan atap bertingkat 11, di bagian pondasi berisi segala bentuk prabotan manusia menggunakan wadah kuali baja, dilengkapi dengan emas berbentuk ayam maupun perak, emas yang berbetuk kacang, perak berbetuk kacang emas berbentuk tumpeng, emas berbentuk tembaga, emas berbentuk sampian, emas berbentuk panyenengan, emas berbentuk bebek, perak berbentuk slaka. Di bagian dasar sekali emas berbetuk kura-kura dan perak berbentuk kura-kura dan perak berbentuk naga, emas berbentuk naga. Masing-masing menggunakan permata merah, dilengkapi dengan lembaran emas dan lembaran perak, lembaran tembaga, empat batang jarum yang terbuat masing-masing emas, perak, tembaga, besi, serta mirah podi jumlahnya sesuai dengan jumlah tingkat atapnya. (jika tumpeng 11 berisi 11 buah, jika tumpeng 9 berisi 9 buah, jika bertumpang 7 berisi 7 buah dan jika bertumpang 5 berisi 5 buah. Lembaran logam tersebut beserta jarum diletakan pada satu
wadah cangkir keramik berwarna putih, yang diisi wangi-wangian.
Naskah ini secara umum berisikan ajaran Mpu Kuturan tentang tatacara pembuatan pedagingan pada pelinggih méru dan pelinggih-pelinggih lainnnya seperti Pelinggih Padmasana, Gedong Tarib, Gedong Sari dan Pelinggih lainnya. Pembuatan pedagingan harus terdiri atas 4 jenis logam yaitu perak, tembaga, emas, besi serta menggunakan permata mata utama. Pedagingan itu juga memiliki kelas-kelas yaitu utama, madya,nisata. Naskah ini juga menguraikan tentang bentuk-bentuk pedagingan yang menyerupai binatang seperti bentuk bebek, benawang, udang. Pada bagian akhir teks disebutkan hanya orang-orang yang sudah mawinten yang berhak untuk ngayabang/muput
pelaksanaan pendem pedagingan.
-
4. Ideologi Mpu Kuturan dalam Naskah Tutur
-
a. Ideologi Mpu Kuturan sebagai Tokoh Agama
Tokoh agama atau rohaniawan/ agamawan selalu menarik untuk diungkap sebab mereka memberi warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat sejak masa lampau hingga kini. Bagi masyarakat Bali kuna khususnya para tokoh agama tersebut diberikan gelar seperti Bhiksu, Mpu, Rsi Mahābrahmāna, Dang Acārya (rohaniawan atau tokoh agama Siwa Hindu) dan Dang Upadhyaya (rohaniawan untuk agama Budha). Pada naskah tutur disebutkan Mpu Kuturan memberikan konsep tentang tata cara pendirian méru beserta dengan pedagingan yang harus diisi ketika mendirikan sebuah méru. Hal ini termuat jelas dalam naskah lontar Nomor 172/III yang berjudul Empu Kuturan, pada naskah ini Mpu Kuturan memberikan panugrahan terkait dengan konsep Pemujaan Pesamuan Agung berupa meru yang tingginya berbeda-beda sesuai dengan tumpang (tingkatan)
yang telah di atur berdasarkan jumlahnnya. Naskah ini juga Mpu Kuturan berisikan tentang ajaran tata cara pembuatan pralinggan widhi atau pretima yang terbuat dari permata mas maupun uang kepeng, tingkatan dari pretima tersebut didasarkan atas catur wangsa sehingga setiap pretima yang digunakan di Pura dibuat dan disesuaikan catur wangsa dari pembuat pretima tersebut.
Jika seorang wéisya mendapatkan pretima kemudian diupacarai boleh dijunjung oleh kaum wéisya dan sudra, bila sudra yang mendapatkan pretima hanya boleh disungsung oleh sudra saja. Pretima yang didapatkan oleh Sang Sadhaka disebut Pretima Bhatara Jagatnatha; yang didapatkan oleh sang ratu disebut Bhatara Pasupati, yang didapatkan oleh ksatria disebut Bhatara Putrajaya, yang didapatkan oleh Weisya disebut Bhatara Manik Gumayang, yang didapatkan oleh Sudra disebut Bhatara Manik Ukir. Pendirian méru oleh Mpu Kuturan juga disebutkan dalam naskah lontar Nomor IIIb/24/ 753 yang berjudul Mpu Kuturan, menyebutkan ajaran Mpu Kuturan tentang tata cara pendirian méru di Besakih yang bertingkat 5, bertingkat 7, bertingkat 9, atap bertingkat 11 serta ajaran Mpu Kuturan terkait sarana upakara yang digunakan dalam mendirikan dan mengupacarai sebuah bangunan meru.
Kutipan dari naskah tutur tersebut telah memberikan keyakinan bahwa Mpu Kuturan memiliki andil besar sebagai tokoh agama yang sangat dihormati pada zamannya telah memberikan ide dan gagasan untuk membangun dan merevitalisasi pura yang telah ada sebelumnya. Pada naskah tutur dengan judul Mpu Kuturan B/2/172 juga disebutkan ajaran Mpu Kuturan dalam memberikan penganugrahan dalam menginisiasi berdirinya padma tiga yang diyakani merupakan stana dari Ida Mpu Tribhuwana, sedangkan Gedong Jampel
atau Gedong yang memiliki ruangan 2 diyakini sebagai stana Mpu Maganta-Maganti. Selanjutnya tempat stana dari Mpu Kuturan adalah Gedong Menjangan Saluwang. Pada bidang ajaran agama Mpu Kuturan memberikan panugrahan dalam bentuk ajaran Dewa Tattwa yang berisi tentang tata cara pendirian Pura serta Bhatara siapa saja yang patut dipuja. Naskah Mpu Kuturan, Nomor B/2/172 Mpu Kuturan disebutkan mengajarkan ajaran Widhi Sastra tentang sastra agama atau ajaran agama yang perlu diwariskan kepada para Raja. Ketenaran Mpu Kuturan bukan saja karena telah melakukan berbagai aktivitas seperti tersebut di atas, melainkan beliau juga menerbitkan sejumlah kitab suci yang dipakai sebagai acuan dalam berperilaku keagamaan dan meniti kehidupan di masyarakat.
Beberapa kitab suci hasil karya beliau adalah: (1) Purana Tatwa yang berisi tentang sejarah kisah perjalan para mpu beserta ajaran-ajarannya. (2) Dewa Tatwa berisi tentang sejarah Para Dewa, tata-cara memelihara dan menyucikan kembali suatu bangunan suci setelah dicemari oleh warganya. Selain itu juga berisi tentang etika kepemangkuan berupa ketentuan dan aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pamangku pura sesuai dengan ajaran yang ditulis oleh Sangkul Putih. Juga berisi tentang ketentuan berlaku dan sanksi yang dikenakan kepada orang yang melahirkan anak kembar buncing. (3) Widisastra berisi tentang asal usul dunia ini mulai dari semasih dalam keadaan kosong. Selanjutnya menyebutkan tentang keberadaan pura Sad Kahyangan dan para dewa yang berstana di masing-masing pura tersebut dan tata cara memujanya. Kesemua dewa/bhatara tersebut merupakan prabhawa Ida Sang Hyang Widhi Wasa, sehingga setiap raja yang berkuasa di Bali wajib hukumnya memuja Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan harus mengenal
tata cara upacaranya. (4) Menyempurnakan Kitab Kesuma Dewa yang berisi antara lain tentang keberadaan para bhatara di jagat raya ini dan Gunung Mahameru yang menjulang sampai ke langit. Gunung tersebut tempat Dewata Nawasanga bertemu. Juga menyebutkan keberadaan pura Sad Kahyangan tempat berstananya para dewa tersebut. (5) Padma Bhuwana berisi tentang tata cara dan upacara membangun kahyangan tempat suci. Mulai dari struktur pura, bentuk pelinggih dan bangunan, jenis-jenis pedagingan untuk setiap pelinggih beserta bhatara yang berstana di setiap pelinggih tersebu. Yang paling banyak dimuat di dalam lontar tersebut adalah berbagai jenis upakara. Isi dari lontar ini hampir sama dengan Padma Bhuwana-Prekempa dan Tingkahing Angwangun Kahyangan.
Mpu Kuturan sebagai arsitek dapat ditemukan dalam beberapa naskah seperti dalam Lontar Mpu Kuturan, Nomor B/2/172 koleksi Gedong Kirtya menyebutkan bahwa Mpu Kuturan adalah tokoh Senāpati yang merevitalisasi dan memperluas Kahyangan Besakih serta memberikan tatacara membangun méru di Bali. Kedatangan Mpu Kuturan dari Jawa untuk membangun Pura Besakih dan memperlebar kawasan Besakih yang difungsikan untuk memuja para Raja di Bali. Selanjutnya Mpu Kuturan juga menawarkan pendirian méru di Pura Besakih dengan meniru konsep Gunung Seméru yang sangat tinggi dan agung di Pulau Jawa. Mpu Kuturan juga dalam merancang palemahan Pura Besakih menjadi tujuh mandala sebagai lambang sapta loka. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Wiana (2009) bahwa Pura Penataran Agung Besakih terdiri atas tujuh mandala, dan pada
mandala ke tujuh tidak ada bangunan suci atau pelinggih. Jadi benar-benar kosong sebagai lambang sunia loka. Selanjutnya menurut David J. Stuart-Fox (2010) menyatakan bahwa Pura Penataran Agung Besakih terbagi menjadi 6 (enam) teras. Dengan demikian kedua pembagian tersebut adalah bersesuaian. Pembagian menjadi mandala berkaitan dengan nilai spiritual, sedangkan teras penekanannya lebih kepada fisik. Itulah sebabnya tidak ada teras ke-7, karena memang pada teras ke-7 tidak terdapat bangunan suci.
Pembagian sapta mandala oleh Mpu Kuturan tidak hanya berhenti sampai di sana, kini pelemahan Pura Besakih terus mengalami penambahan seiring dengan perkembangan dan peningkatan jumlah umat Hindu. Hingga kini dapat dijumpai 13 méru di Pura Besakih. Keberadaan méru tersebut diyakini hingga kini merupakan hasil pemikiran Mpu Kuturan. Selanjutnya pada naskah Nomor IIIb.753 berjudul Mpu Kuturan koleksi Gedong Kirtya disebutkan bahwa Mpu Kuturan selain sebagai pendesain bentuk dari méru juga telah mempersiapkan pedagingan yang harus ditanam pada pondasi meru yang akan dibuat.
Mpu Kuturan menjelaskan dengan rinci apa yang harus dimasukkan ke dalam méru berdasarkan tingkat méru. Pada penataan ruang, Mpu Kuturan juga memperkenalkan ajaran catur loka pala pura. Catur loka pala (dala) adalah empat Pura yang mengitari Padma Tiga dengan empat arah mata angin sebagai penyade (penghubung). Pura Gelap berada di timur, mewakili Ida Bhatara Iswara; Pura Ulun Kulkul berada di barat, mewakili Ida Bhatara Mahadewa; Pura Batu Madeg berada di utara, mewakili Ida Bhatara Wisnu; dan Pura Kiduling Kreteg berada di selatan, mewakili Ida Bhatara Brahma. Keem Selanjutnya, ajaran pura catur loka pala (dala) diadopsi menjadi empat pura untuk melindungi dan menjaga keamanan pulau Bali: Pura
Lempuyang di timur, Pura Luhur Batukaru di barat, Pura Puncak Mangu di utara, dan Pura Andakasa di selatan.
Mpu Kuturan menciptakan konsep catur loka pala (dala), yang masih digunakan hingga hari ini. Mpu Kuturan membangun pura catur loka pala, yang hingga saat ini berdiri sebagai pura pangider bhuwana di Besakih. Pura ini dibangun di atas gunung sebagai kiblat pembangunan, dengan Pura Peninjauan masih digunakan sebagai tempat suci untuk memuja Mpu Kuturan.
Konsep catur loka pala adalah keputusan untuk menggunakan Gunung sebagai lokasi pembangunan pura, yang dianggap dapat mewakili seluruh penjuru mata angin. Konsep ini digunakan sebagai awal pembangunan sad kahyangan Bali dan juga berlaku untuk status pura, karena pura dibangun di seluruh penjuru mata angin.
SIMPULAN
Mpu Kuturan sebagai tokoh besar pada masanya termuat dalam berbagai naskah seperti naskah tutur, babad, usadha, kalpasastra dan prasasti. Hal ini menunjukan pengaruh Mpu Kuturan yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat sehingga dijumpai dalam berbagai genere naskah Bali. Mpu Kuturan dalam naskah tutur dijumpai sebagai tokoh agama yang sangat mumpuni dibidangnya. Hal ini dibuktikan dari banyaknya karya fundamental sebagai seorang ahli agama seperti revitalisasi pura Besakih, pembuatan pelinggih méru, penataan kawasan suci dengan konsep catur loka pala dan sapta mandala. Di samping itu Mpu Kuturan mengajarkan ajaran purana tatwa, dewa tatwa, widhisastra, kusumadewa, padma bhuwana prakempa dan tingkahin angwangun kahyangan. Sedangkan Ideologi Mpu Kuturan sebagai arsitek dijumpai dari pemikiran Mpu Kuturan dalam menata dan menyempurnakan kawasan Besakih,
merancang pendirian pelinggih méru dan menata palemahan dengan konsep catur loka pala.
DAFTAR PUSTAKA
Ardiyasa, I. N. S. (2018). Peran Mpu Kuturan dalam Membangun Peradaban Bali (Tinjauan Historis, Kritis). Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya, 2(1)..
Bagus, I Gusti Ngurah dan Ida Bagus Agastia. (1977). Sekilas tentang Kesusastraan Bali. Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Baroroh, Siti Baried dkk.(1994). Pengantar Teori Filologi. Badan Penelitian dan Publikasi Fakultas (BPPP) Seksi Filologi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
David J. Stuart Fox. (2010). Pura Besakih; Pura, Agama.
Terjemahan.Denpasar: Udayana
Pres.
Duija, I Nengah dkk. (2015). Penelusuran Sejarah Śri Mahārāja Haji Japangus. Gianyar : Pemerintah Kabupaten Gianyar IHDN Denpasar.
Djamaris, Edwar. (2002). Metode Penelitian Filologi. Jakarta: CV Monasco.
Endraswara, Suwardi. (2003).
Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
Goris. R. (1948). Sejarah Bali Kuna. Singaraja : Tanpa Penerbit.
Goris. R. (1954). Prasasti Bali I. NV. Masa Baru Bandung.
Goris. R. (1954). Sekte-Sekte di Bali. Jakarta : Bhratara.
Semadi Astra. (1997). Birokrasi Pemerintahan Bali kuno Abad XIIXIII sebuah kajian Efigrafis (disertasi tidak diterbitkan). Yogyakarta : Universitas Udayana.
Shastri, N.D Pandit. (1963). Sedjarah Bali Dwipa. Denpasar : Bhuana Saraswati.
Santhiastini, N. K. D., Suardiana, I. W., & Antara, I. G. N. Teks Tutur Angkus Prana: Kajian Struktur Dan Semiotika.
Suarjaya, I. W. (2018). Mpu Kuturan Berjasa dalam Menjaga Adat Budaya dan Agama
Hindu. Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya, 2(1).
Sugi Lanus, dkk, (2019). Khasanah Manuskrip Sejarah Koleksi Gedong Kirtya Jilid 1. Direktorat Sejarah, Direktorat JendEral Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Suweta, I. M. (2020). Teks Lontar Tutur Rare Angon (Kajian Filosofis Hindu Tentang Eksistensi
Manusia). Genta Hredaya: Media Informasi Ilmiah Jurusan Brahma Widya STAHN Mpu Kuturan Singaraja, 4 (1), 1-10.
Suweta, I. M. (2020). Karma phala dan pangruwatan dalam teks lontar
tutur lebur gangsa. Maha Widya
Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, dan Ilmu Komunikasi, 4 (1), 1-10.
Watra, I Wayan. (2018). Tri Murti Ideologi Sosio-Religius
Mempersatukan Sekte-Sekte Di Bali. Dharmasmrti Jurnal ilmu Agama dan Kebudayaan,
8.114.121.https://doi.org/10.32795/ ds.v9i2.153.
Zoetmulder. PJ. (2011). Kamus Jawa Kuna Indonesia Cetakan 11. Jakarta : PT Gramedia.
Parimartha, I Gede. (2003). Memahami Desa Adat, Desa Dinas dan Desa Pakraman. Universitas Udayana : Denpasar.
Patera, I Wayan. (2009). Samuantiga dalam Dinamika Kehidupan Sekte-Sekte di Bali. Artikel Ilmiah yang diterbitkan dalam Buku Dinamika Sosial Masyarakat bali dalam Lintasan Sejarah. Fakultas Sastra Universitas Udayana.
Refrensi Naskah
-
1. Naskah Mpu Kuturan Nomor Naskah 753.IIIb Koleksi Gedong Kirtya.
-
2. Naskah Mpu Kuturan Nomor Naskah 753.IIIb Koleksi Gedong Kirtya.
-
3. Naskah Hempu Kuturan Nomor Naskah 4875/Ic. Koleksi Gedong Kirtya.
-
4. Naskah Kaputusan Mpu Kuturan Nomor Naskah 3752/IIId Koleksi Gedong Kirtya.
-
5. Naskah Sri Purana Nomor T/XIX/8/Dokbud Koleksi Pusat Dokumentasi Bali.
-
6. Naskah Taru Premana Nomor IIId 1854/12 Koleksi Gedong Kirtya.
-
7. Naskah Dharma Pemacul Nomor
Ic.3317. Koleksi Gedong Kirtya.
-
8. Naskah Babad Pasek Gelgel Nomor
Va 955/6 Koleksi Gedong Kirtya.
Discussion and feedback