Kata Yen dalam Bahasa Bali: Suatu Tinjauan Sederhana
on
Ji¾J⅜lMS.
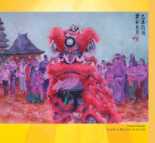
Journal of Arts and Humanities
p-ISSN: 2528-5076, e-ISSN: 2302-920X
Terakreditasi Sinta-4, SK No: 23/E/KPT/2019
Vol 26.2 Mei 2022: 271-276
Kata Yén dalam Bahasa Bali: Suatu Tinjauan Sederhana
I Wayan Teguh
Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia Email korespondensi: wayanteguh38@yahoo.co.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 20 Desember 2022
Revisi: 3 Februari 2022
Diterima: 17 Maret 2022
Keywords:
yén word; conjunction;
preposition; lexical meaning;
grammatical meaning
The word yén (Balinese) has a meaning parallel to the words if and if (Indonesian). One of the characters of the word yén is as a conjunction. In addition, the word yén also has a character like a preposition. The word yén (Balinese) only has a function and meaning in a syntactic structure. The word yén (Balinese) which functions as a conjunction has similarities and differences with the word yén which is characterized as a preposition. In this case both belong to the category of particles. In addition, it also only has a function and meaning in a syntactic structure. The difference is that yén as a subordinate conjunction connects words or phrases that have the potential to become clauses. On the other hand, yén which is characterized as a preposition is followed by a group of words or words that are potential phrases. That is, the conjunction yén is discussed at the sentence level, while yén which is similar to a preposition is discussed at the phrase or word group level.
Abstrak
Kata kunci:
kata yén; konjungsi; preposisi; makna leksikal; makna
gramatikal
Corresponding Author:
I Wayan Teguh
Email:
DOI:
Kata yén (bahasa Bali) memiliki makna sejajar dengan kata jika dan kalau (bahasa Indonesia). Salah satu karakter kata yén adalah sebagai konjungsi. Selain itu, kata yén juga memiliki karakter seperti preposisi. Kata yén (bahasa Bali) hanya memiliki fungsi dan makna dalam struktur sintaksis. Kata yén (bahasa Bali) yang berfungsi sebagai konjungsi memiliki persamaan dan perbedaan dengan kata yén yang berkarakter sebagai preposisi. Dalam hal ini keduanya sama-sama tergolong ke dalam kategori partikel. Di samping itu, juga hanya memiliki fungsi dan makna di dalam struktur sintaksis. Perbedaannya adalah yén sebagai konjungsi subordinat menghubungkan kata atau frasa yang potensial menjadi klausa. Sebaliknya, yén yang berkarakter sebagai preposisi diikuti oleh kelompok kata atau kata yang potensial sebagai frasa. Artinya, konjungsi yén dibicarakan pada tataran kalimat, sedangkan yén yang mirip dengan preposisi dibicarakan pada tataran frasa atau kelompok kata.
PENDAHULUAN
Sudaryanto (1978/1979:1) menyatakan bahwa kata yang terklasifikasi konjungsi dan preposisi termasuk ke dalam kata nonreferensial,
sedangkan Moeliono (1988:230) menyebutnya partikel atau kata tugas. Kehadiran kata tugas atau partikel atau kata nonreferensial tidak menyatakan makna leksikal, tetapi menunjukkan
makna gramatikal. Salah satu kata yang tergolong partikel dalam bahasa Bali adalah kata yén. Kata yén (bahasa Bali) sejajar dengan kata jika dan kalau (bahasa Indonesia). Oleh karena itu, kata yén hanya memiliki fungsi dan makna dalam struktur sintaksis.
Dalam tinjauan sederhana ini dideskripsikan kata yén (bahasa Bali), baik yang berfungsi sebagai konjungsi maupun yén yang berfungsi sebagai preposisi. Kerangka teori yang digunakan dalam tinjauan ini adalah teori sintaksis struktural deskriptif. Artinya, perhatian difokuskan pada bentuk, susunan, dan hubungan antarsatuan lingual. Jadi, teori ini memberikan perhatian secara eksplisit terhadap berbagai unsur kebahasaan sebagai suatu struktur atau sistem. Dalam hal ini pengamatan difokuskan pada perilaku sintaksis dan aspek semantik kata yén (bahasa Bali). Aspek semantik dalam tinjauan sederhana ini terkait dengan kemungkinan terjadinya perubahan makna apabila struktur klausa atau kalimat diubah.
Pembahasan dalam tinjauan sederhana ini ditekankan pada persamaan dan perbedaan antara kata yén yang berfungsi sebagai konjungsi dan kata yén yang berfungsi sebagai preposisi. Artinya, dilihat persamaan dan perbedaannya, baik dari struktur (sintaksis) maupun makna (semantik). Dengan demikian, diharapkan dapat diketahui identitas, ciri, dan fungsinya masing-masing.
METODE
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Artinya, kata yén (bahasa Bali) dikaji dan diseskripsikan seperti adanya. Pendeskripsian itu semata-mata berdasarkan fakta kebahasaan atau fenomena-fenomena yang ada secara empiris pada para penuturnya. Dengan demikian, hasilnya merupakan deskripsi yang menggambarkan data secara
sistematis. Hal itu sesuai dengan pemahaman yang dikemukakan oleh Sudaryanto (1988:62) dan Djajasudarma (1993:8—9).
Metode yang digunakan pada tahapan pengumpulan data lisan adalah metode simak dan metode cakap (Sudaryanto, 1993:132). Dalam operasionalnya metode simak diwujudkan dengan teknik sadap sebagai teknik dasar, sedangkan teknik simak libat cakap dan teknik catat sebagai teknik lanjutannya. Metode cakap dapat digunakan pada tahapan pengumpulan data karena penulis merupakan penutur (asli) bahasa Bali. Dalam operasionalnya metode cakap diwujudkan dengan teknik pancing sebagai teknik dasar, sedangkan teknik cakap semuka dan teknik rekam sebagai teknik lanjutannya. Pengumpulan data tulis dilakukan dengan pengamatan terhadap sumber data yang telah ditetapkan. Dalam hal ini intuisi kebahasaan penulis sebagai penutur asli bahasa yang diteliti (bahasa Bali) memegang peranan penting. Artinya, dengan intuisi kebahasaan yang dimiliki, penulis dapat menentukan kata yén sebagai preposisi dan kata yén sebagai konjungsi.
Data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan dianalisis dengan metode distribusional (Sudaryanto, 1982:13; 1985:5). Metode ini dilaksanakan dengan menghubungkan fenomena-fenomena dalam bahasa yang dianalisis (Djajasudarma, 1993:60), yaitu bahasa Bali. Penggunaan metode ini didasarkan pertimbangan bahwa setiap unsur bahasa berhubungan dan membentuk satu kesatuan yang padu (the whole unified) (de Saussure dalam Djajasudarma, 1993:60). Hasil analisis data disajikan dengan metode informal dan metode formal (Sudaryanto, 2015:72).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam tinjauan sederhana ini kata yén (bahasa Bali) dibagi atas dua kelompok,
yaitu kata yén yang berfungsi sebagai konjungsi dan kata yén yang berfungsi sebagai preposisi. Wedhawati dkk. (1980:190) menyatakan bahwa kehadiran konjungsi yén ‘jika, kalau’ membentuk struktur subordinatif, misalnya Adin tiang sing nyak meblanja yén sing baang pipis ‘Adik saya tidak mau berbelanja jika tidak diberikan uang’. Dalam konstruksi ini yén sing baang pipis ‘jika tidak diberikan uang’ merupakan klausa anak. Di samping itu, yén juga diklasifikasikan sebagai konjungsi tidak setara (Ramlan, 1980/1981:20). Dalam hal ini yang dimaksud dengan konjungsi subordinatif atau konjungsi tidak setara adalah konjungsi yang berfungsi menghubungkan dua unsur sintaksis berupa klausa yang tidak memiliki status sama (Sudaryanto, 1991:117). Kehadirannya berfungsi untuk mengenali klausa terikat dan menyambungkan dengan klausa utama dalam kalimat bertingkat (Kridalaksana, 1982:92). Di samping itu, kehadiran konjungsi subordinat selalu diikuti oleh sebuah klausa. Dalam tinjauan sederhana ini klausa tersebut disebut klausa anak. Kehadiran kluasa anak itu selalu dalam kalimat majemuk yang sekurang-kurangnya mempunyai dua predikat. Predikat kedua merupakan bagian dari predikat pertama.
Konjungsi yén (bahasa Bali) sejajar dengan jika dan kalau (bahasa Indonesia), yaitu menyatakan hubungan kesyaratan (Wedhawati dkk., 1980:154). Di pihak lain konjungsi yén ‘jika, kalau’ disebut sebagai penanda hubungan penerang (Sudaryanto, 1991:117—118). Artinya, klausa anak merupakan sesuatu yang dikatakan, dipikirkan, didengar, disadari, diyakini, diketahui, dinyatakan, dijelaskan, atau dikemukakan oleh klausa induk (Ramlan, 1981:57). Oleh karena itu, konjungsi yén ‘jika, kalau’ dapat menyatakan hubungan ‘syarat’, ‘pengandaian’, ‘keragu-raguan’, ’kemungkinan’, ‘berakibat’, dan ‘isi’.
Berikut beberapa tipe hubungan yang ditandai oleh konjungsi yén.
-
(1) Tiang tusing bani mayah yén barange tonden kirima.
‘Saya tidak berani membayar kalau barang itu belum dikirim.’
Klausa anak pada kalimat (1) yén barange tonden kirima ‘kalau barang itu belum dikirim’ berposisi di sebelah kanan klausa induk. Klausa anak pada (1) merupakan pengisi fumgsi keterangan. Hal ini terbukti, yaitu urutannya dapat diubah dari sebelah kanan klausa induk ke sebelah kiri klausa induk dan sebaliknya, seperti tampak di bawah ini. (1a) Yén barange tonden kirima, tiang tusing bani mayah.
‘Kalau barang itu belum dikirim, saya tidak berani membayar.’
Kehadiran konjungsi yén ‘kalau’, ‘jika’ pada konstruksi (1) bersfat wajib. Artinya, apabila konjungsi yén itu dilesapkan, informasi yang dinyatakan dalam kalimat tersebut tidak padu. Di samping itu, hubungan maknanya juga tidak jelas. Oleh karena itu, contoh (1) tidak dapat diubah menjadi kalimat (1b) berikut.
-
*(1b) Tiang tusing bani mayah, barange tonden kirima.
Ketidakhadiran yén dalam konstruksi (1b) ini mengubah makna. Maksudnya, tanpa yén konstruksi (1b) dapat bermakna ‘sebab’ atau ‘karena’, sedangkan yén menyatakan makna ‘syarat’.
Berdasarkan contoh (1), (1a), dan (1b) di atas diketahui bahwa yén pada kalimat (1) bersifat wajib. Dikatakan demikian karena pelesapan konjungsi yén menyebabkan kalimat tidak berterima.
-
(2) Yén tiang dadi ragane, tiang kel meli montor.
‘Seandainya saya menjadi Anda, saya akan membeli sepeda motor.’
Klausa anak pada (2) yén tiang dadi ragane ‘seandainya saya menjadi Anda’ merupakan pengisi fungsi keterangan. Dikatakan demikian karena posisi klausa anak itu dapat diubah dari sebelah kiri
klausa induk ke sebelah kanan klausa induk dan sebaliknya. Dengan demikian, contoh (2) dapat diubah menjadi kalimat di bawah ini.
(2a) Tiang kel meli montor yén tiang dadi ragane.
‘Saya akan membeli sepeda motor seandainya saya menjadi Anda’
Kehadiran konjungsi yén pada kalimat (2) bersifat wajib. Artinya, apabila konjungsi yén dilesapkan, hubungan makna kalimat itu tidak jelas, seperti kalimat di bawah ini.
-
*(2b) Tiang dadi ragane, tiang kel meli montor.
‘Saya menjadi Anda, saya akan membeli sepeda motor.’
-
(3) Tiang sangsaya yén ragane sing maan ngatehang tiang.
‘Saya khawatir kalau-kalau Anda tidak dapat mengantarkan saya.’
Klausa anak yén ragane sing maan ngatehang tiang ‘kalau-kalau Anda tidak dapat mengantarkan saya’ merupakan pengisi fungsi pelengkap. Kehadiran klausa anak itu diisyaratkan oleh verba pengisi predikat klausa induk. Dengan demikian, struktur kalimat (3) tidak dapat diubah menjadi kalimat berikut.
-
*(3a) Yén ragane sing maan ngatehang tiang, tiang sangsaya.
‘Kalau-kalau Anda tidak dapat mengantarkan saya, saya khawatir’
Kehadiran konjungsi yén pada kalimat (3) bersifat wajib. Artinya, apabila konjungsi yén dilesapkan, hubungan informasi kalimat itu tidak padu. Di samping itu, hubungan makna yang dinyatakan juga tidak jelas, seperti kalimat di bawah ini.
-
*(3b) Tiang sangsaya, ragane sing maan ngatehang tiang.
‘Saya khawatir, Anda tidak dapat mengantarkan saya.’
-
(4) Ragane da malaib-laiban yén nganti labuh.
‘Anda angan berlari-lari kalau sampai jatuh’
Konjungsi yén pada konstruksi (4) menandai hubungan ‘kemungkinan berakibat’. Kehadiran yén dalam kalimat (4) dapat diperluas dengan kata nganti. Klausa anak yén nganti labuh ‘kalau sampai jatuh’ merupakan pengisi fungsi keterangan’ Posisinya dapat diubah dari urutan sebelah kanan klausa induk ke urutan sebelah kiri klausa induk dan sebaliknya. Pada permutasian ini maknanya semakin jelas jika digunakan konjungsi yén diperluas dengan nganti sehingga bentuknya menadi yén nganti. Dengan demikian, kalimat (4) dapat diubah menjadi kalimat berikut.
(4a) Yén nganti labuh, ragane da malaib-laiban.
‘Kalau sampai jatuh, Anda jangan berlari-lari.’
Kehadiran konjungsi yén pada kalimat (4) bersifat wajib. Dengan demikian, konjungsi yén tidak dapat dilesapkan sehingga membentuk kalimat di bawah ini.
-
*(4b) Ragane da malaib-laiban, labuh.
‘Anda jangan berlari-lari, jatuh’
-
(5) Putu Oka ngorahang yén Ketut Dewi juara 1.
‘Putu Oka berkata kalau Ketut Dewi juara 1’.
Konjungsi yén pada kalimat (5) ini menandai hubungan ‘isi’. Kehadiran klausa anak pada hubungan ‘isi’ ini diisyaratkan oleh verba pengisi predikat klausa induk. Klausa anak pada konstruksi (5) selalu berposisi di sebelah kanan klausa induk. Dengan demikian, struktur kalimat (5) tidak dapat diubah menjadi kalimat di bawah ini.
-
*(5a) Yén Ketut Dewi juara 1, Putu Oka ngorahang.
‘Kalau Ketut Dewi juara 1, Putu Oka berkata.’
Berdasarkan fungsi sintaksis, dapat dikatakan bahwa klausa yén Ketut Dewi juara 1 ‘kalau Ketut Dewi juara 1’ pada kalimat (5) merupakan pengisi fungsi pelengkap. Kehadiran konjungsi yén pada (5) bersifat wajib. Artinya, apabila
konjungsi yén itu dilesapkan, informasi yang disampaikan tidak tegas. Oleh karena itu, kalimat (5) tidak dapat diubah menjadi seperti di bawah ini.
-
*(5b) Putu Oka ngorahang Ketut Dewi juara 1.
‘Putu Oka berkata Ketut Dewi juara 1’.
Dalam pembahasan di atas telah diuraikan yén sebagai konjungsi. Pada uraian berikut dibahas yén yang berkarakter preposisi. Kehadiran yén berkarakter preposisi ini selalu menandai sebuah frasa (Moeliono, 1988:230). Preposisi yén ‘jika, kalau’ ini mampu membentuk ikatan eksosentris
(Kridalaksana, 1982:137). Di pihak lain, Ramlan (1980:179) menyatakan bahwa yén ‘jika, kalau’ mampu sebagai penanda yang merangkaikannya dengan unsur lain sebagai petandanya. Artinya, preposisi yén tidak diikuti oleh kelompok kata sebagai klausa, tetapi diikuti oleh kata atau sekelompok kata yang berupa frasa. Hal itu dapat dilihat pada contoh berikut. (6) Semerne Made Geria yén masan panes nyat.
‘Sumur Made Geria kalau musim kemarau kering.’
Kata yén ‘jika’, ‘kalau’ pada kalimat (6) berkedudukan sebagai penanda yang menghubungkannya dengan frasa masan panes ‘musim kemarau’ sebagai petandanya sehingga membentuk frasa preposisional yén masan panes ‘kalau musim kemarau’. Kelompok kata masan panes ‘musim kemarau’ tergolong frasa endosentrik dengan kata masan ‘musim’ sebagai modifikasinya, sedangkan panes ‘kemarau’ sebagai inti atau pusatnya. Oleh karena itu, jelas bahwa masan panes ‘musim kemarau’ tidak berpotensi sebagai klausa, tetapi hanya berpotensi sebagai frasa. Dikatakan demikian karena kehadirannya tidak mampu sebagai penguasa, artinya pada umumnya tidak dapat menuntut hadirnya objek, keterangan, bahkan pelengkap
(Sudaryanto, 1983:79—80).
Berdasarkan fungsi sintaksisnya frasa preposisional yén masan panes ‘kalau musim kemarau’ merupakan pengisi fungsi keterangan. Posisi fungsi keterangan itu dapat diubah sehingga membentuk kalimat (6a) sebagai berikut. (6a) Yén masan panes semerne Made Geria nyat.
‘Kalau musim kemarau sumur Made Geria kering’.
Apabila dilihat dari segi makna yang dinyatakannya, preposisi yén pada kalimat (6) menandai hubungan ‘syarat’.
Perubahan konstruksi Semerne Made Geria yén masan panes nyat. ‘Sumur Made Geria kalau musim kemarau kering’ menjadi Semerne Made Geria nyat yén masan panes ‘Sumur Made Geria kering kalau musim kemarau’ menunjukkan terjadi perubahan posisi kata nyat ‘kering’. Artinya, semula kata nyat berposisi di sebelah kanan atau setelah yén masan panes menjadi di sebelah kiri atau sebelum yén masan panes. Akan tetapi, yén tetap berfungsi sebagai preposisi.
SIMPULAN
Berdasarkan tinjauan sederhana di atas diketahui bahwa kata yén (bahasa Bali) yang berfungsi sebagai konjungsi memiliki persamaan dan perbedaan dengan kata yén yang berkarakter sebagai preposisi. Persamaan keduanya adalah sama-sama terklasifikasi ke dalam kategori partikel. Di samping itu, juga memiliki fungsi dan makna di dalam struktur sintaksis saja. Perbedaannya adalah yén sebagai konjungsi subordinat menghubungkan kata atau frasa yang potensial menjadi klausa. Sebaliknya, yén yang berfungsi sebagai preposisi diikuti oleh kelompok kata atau kata yang potensial sebagai frasa. Artinya, konjungsi yén dibicarakan pada tataran kalimat, sedangkan preposisi yén dibicarakan pada tataran frasa atau kelompok kata.
Kata yén membentuk frasa preposisional, seperti yén masan panes ‘kalau musim kemarau’ dan yén masan dingin ‘kalau musim dingin’. Frasa masan panes ‘musim kemarau’ dan masan dingin ‘musim dingin’ tergolong frasa endosentrik, yaitu masan ‘musim’ sebagai modifikasinya, sedangkan panes ‘kemarau’ dan dingin ‘dingin’ sebagai intinya.
DAFTAR PUSTAKA
Allan, Keith, (2001). Natural Language Semantics. Oxford: Blackwell.
Beratha, N. L. (2012). Frasa Bahasa Bali Kuna dan Perkembangannya ke Bahasa Bali Modern. Jurnal Kajian Bali.
Djajasudarma, T. Fatimah. (1993). Metode Linguistik (Ancangan Metode Penelitian dan Kajian). Bandung: Eresco.
Kridalaksana, Harimurti. (1982). Kamus Linguistik. Jakarta: Gramedia.
Moeliono, Anton M. (1988). Tata Bahasa Baku Bahasa
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Ramlan, M. (1980). Kata Depan dalam Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Karyono.
Ramlan, M. (1980/1981). “Laporan Penelitian Kata Penghubung dalam Bahasa Indonesia Dewasa Ini”. Yogyakarta: Lembaga
Penelitian Universitas Gadjah Mada.
Ramlan, M. (1981). Ilmu Bahasa Indonesia: Sintaksis.
Yogyakarta: Karyono.
Sudaryanto. (1978/1979). “Laporan Penelitian Peranan Sistematik Beberapa Kata Nonreferensial
dalam Bahasa Indonesia”.
Yogyakarta: PPPT UGM.
Sudaryanto. (1983). Predikat-Obek dalam Bahasa Indonesia
Keselarasan Pola-Urutan.
Jakarta: Djambatan.
Sudaryanto. (1991). Tata Bahasa Baku Bahasa Jawa. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
Sudaryanto. (2015). Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa:
Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistis. Yogyakarta: Sanata Dharma
University Press.
S u dipa, I Nengah. (2004). Verba Bahasa Bali: Sebuah Analisis Metabahasa Semantik Alami. Disertasi prodi Linguistik, Universitas Udayana
Wedhawati dkk. (1980). “Laporan Penelitian Kata Tugas Bahasa
Jawa”. Yogyakarta: Proyek
Penelitian Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Discussion and feedback