Ritual Rajasuya Penanda Kuasa Era India Kuno
on
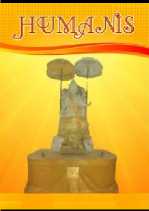
HUMANIS
Journal of Arts and Humanities
p-ISSN: 2528-5076, e-ISSN: 2302-920X
Terakreditasi Sinta-3, SK No: 105/E/KPT/2022
Vol 27.4. Nopember 2023: 507-517
Ritual Rajasuya Penanda Kuasa Era India Kuno
Rajasuya Rituals Marking Power in Ancient India
I Nyoman Duana Sutika, I Ketut Ngurah Sulibra Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia Email Korespondensi: duana_sutika@unud.ac.id, ngr_sulibra@unud.ac.id
Info Artikel
Masuk: 14 Oktober 2023
Revisi: 9 Nopember 2023 Diterima:19 Nopember 2023 Terbit: 30 Nopember 2023
Keywords: ritual; rajasuya;
sabhaparwa; power
Abstract
This research reveals social realities in narrative literary works about the ruler's desire to achieve power, glory and glory. Rituals rajasuya in a piece of text sabhaparwa this is interesting to highlight because it is always preceded by war between rulers and is an archaic cultural tradition of the Ancient Indian era. This ritual is carried out more to legitimize power. The theory used is reception theory to discover, interpret and concretize what is expressed and implied. Data processing was carried out using the descriptive analysis method, namely describing the results obtained assisted by the hermeneutic method to understand the text. Search results show that the text sabhaparwa this is still appreciated by the Balinese people by carrying out intensive copying with the aim of making these texts known, read and interpreted by readers. Text parva including sabhaparwa This is adapted prose and shows its dependence on quotations from original works in Sanskrit Abstrak
Kata kunci: ritual; rajasuya; sabhaparwa; kekuasaan
Corresponding Author:
I Nyoman Duana Sutika, email:
DOI:
Penelitian ini mengungkap realitas sosial dalam karya sastra naratif tentang hasrat penguasa dalam meraih kekuasaan, kejayaan dan kemuliaan. Ritual rajasuya dalam penggalan teks sabhaparwa ini menarik untuk diangkat karena senantiasa didahului oleh perang antar penguasa menjadi tradisi budaya arkais era India Kuno. Ritual ini dilaksanakan lebih kepada legitimasi kekuasaan. Teori yang digunakan adalah teori resepsi untuk menemukan, menafsirkan dan mengkonkretkan apa yang tersurat dan tersirat. Pengolahan data dilakukan dengan metode deskriptif analisis, yaitu mendeskripsikan hasil yang diperoleh dibantu dengan metode hermeneutik untuk memahami teks. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa teks sabhaparwa ini masih diapresiasi oleh masyarakat Bali dengan melakukan penyalinan-penyalinan secara intensif yang bertujuan agar teks-teks tersebut dapat dikenal, dibaca, dan dimaknai oleh pembacanya. Teks parwa termasuk sabhaparwa ini merupakan prosa yang diadaptasi dan menunjukkan ketergantungannya dengan kutipan-kutipan dari karya asli dalam bahasa Sanskerta
PENDAHULUAN
Salah satu naskah kuno yang menguraikan tentang ritual rajasuya adalah Sabhaparwa. Naskah tersebut rupanya masih tetap dipelihara, dikoleksi dan diapresiasi seirama dengan tumbuhnya karya-karya baru dalam kesusastraaan Bali. Selain Gedong Kirtya, naskah-naskah kuno juga disimpan di perpustakaan-perpustakaan lain, seperti Pusdok, Unit Lontar Universitas Udayana dan koleksi pribadi lainnya. Zoutmulder (1983) seorang fakar sastra sangat mengapresiasi dan memberi penghargaan luar biasa kepada Bali yang telah menyelamatkan naskah-naskah kuno, terutama karya sastra yang berbahasa Jawa Kuno. Karya sastra tersebut tidak hanya disimpan sebagai koleksi, tetapi disalin, ditiru dan dikembangkan kembali mengikuti tradisi yang berlaku.
Karya sastra dapat dianggap sebagai cermin kehidupan manusia sebagai faktual sastra. Perang dan asmara adalah tema cerita yang selalu menarik diangkat dalam karya sastra. Kedua tema ini merupakan cerminan kehidupan manusia dalam realitas yang acapkali dialami oleh manusia pada umumnya. Hampir setiap konflik tercipta dari pergulatan asmara dan perang pada diri sendiri dan antar sesama. Demikian pula yang terjadi pada cerita Sabhaparwa, sebuah konflik yang sengaja diciptakan untuk pencapaian sebuah ambisi penguasa. Kekuasaan, kejayaan, dan kemuliaan sebagai euporia yang selalu diupayakan oleh seorang raja besar Yudistira.
Dalam wacana umum tokoh Yudistira dapat dianggap sebagai tokoh idola karena kebijaksanaannya didalam memerintah negeri Indraprasta. Tetapi secara kontradiktif juga mempunyai ambisi, dan hasrat untuk menjadi raja diraja. Ambisi yang disebut Piliang (2006) sebagai hasrat, adalah sebuah dorongan untuk mencari sesuatu yang
lebih atau melampaui. Upaya untuk mewujudkan keinginannya itu hanya dapat dilakukan dengan jalan perang, menguasai dan menaklukkan wilayah lain demi mendapatkan harta yang melimpah. Krisna merupakan salah satu tokoh penting dan memegang kunci terselenggaranya ritual rajasuya. Semua gagasan dan ide cemerlang bermuara pada tokoh Krisna. Anom (1956) menyebutkan bahwa tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Krisna bila menyatukan kekuatan dengan Arjuna dan Bima. Ketiga tokoh ini bila bersatu padu dapat membentuk kekuatan luar biasa untuk mengalahkan musuh-musuh Indraprasta, karena dalam diri Krisna melekat politik, pada Arjuna terletak kemenangan dan pada Bima terdapat kekuatan. Secara keseluruhan kisah Sabhaparwa berakhir pada pembuangan atau pengusiran panca pandawa ke hutan atas kekalahan dirinya dalam permainan dadu melawan korawa. Namun demikian penelitian ini berhenti pada pelakssanaan ritual rajasuya saja.
METODE DAN TEORI
Metode dianggap sebagai cara-cara, strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya (Ratna, 2006). Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, penyediaan data dilakukan mulai dari penelusuran naskah di berbagai sumber penyimpanan naskah, seperti perpustakaan dan pemilik naskah atau pemerhati sastra di masyarakat. Untuk mendapatkan data yang otentik dilakukan wawancara dengan informan, melakukan dialog, merekan untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang naskah. Wawancara dilakukan mengikuti pola Suprayogo dan Tabroni (2001) mengacu hal-hal: (1) mereka yang diwawancarai adalah orang yang memiliki pengetahuan dan mendalami
situasi serta mengetahui informasi yang diperlukan; (2) pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan keadaan atau ciri khas yang dimiliki orang yang diwawancarai; (3) antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai saling berdiskusi tentang apa yang diketahui oleh masing-masing pihak. Setelah data terkumpul, teks dibaca secara teliti untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan materi penelitian ini. Kedua, analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif Moleong (1996), yaitu analisis teks untuk mengetahui strukturnya, kemudian memahami lebih lanjut gejala sosial budaya yang berada di luar karya sastra tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan metode deskriptif analisis menurut Jaya (2021), yaitu menyusun atau mendiskripsikan hasil temuan berupa data atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi maupun catatan lapangan. Pengolahan data dibantu dengan metode hermeneutik atau penafsiran untuk memahami teks. Ketiga, penyajian hasil analisis data dilakukan dengan metode informal mengikuti arahan Sudaryanto (1993), yaitu penyajian hasil analisis data dengan menggunakan kata-kata yang berisi rincian hasil analisis data.
Teori yang digunakan adalah teori resepsi, yaitu bagaimana pembaca memberikan makna terhadap karya sastra yang dibacanya. Resepsi dikemukakan Listiyorini (2019) merupakan aktivitas yang terjadi ketika seorang individu melihat atau membaca suatu teks kemudian memicu pemaknaan yang ia simpulkan berdasarkan latar belakang sosial budaya yang ia miliki. Endraswara (2008) mengemukakan bahwa resepsi sastra pada dasarnya merupakan penyelidikan reaksi pembaca terhadap teks, penelitian sastra yang memusatkan pada proses hubungan teks dan pembaca. Hal senada diungkapkan Junus (1985) bahwa resepsi sastra memberi kebebasan pada pembaca untuk
memberikan maknanya kepada suatu teks. Dengan teori resepsi dinyatakan Medera (1990) pembaca menemukan, menafsirkan dan mengkonkretkan apa yang tersurat dan tersirat dalam karya sastra.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan hasil penelusuran bahwa teks parwa masih digemari oleh masyarakat Bali. Teks-teks parwa ini masih disalin oleh masyarakat secara intensif yang bertujuan agar teks-teks tersebut dapat dikenal, dibaca, dipahami dan tentu untuk dimaknai oleh pembacanya. Karya sastra parwa ini tersebar terutama di perpustakaan-perpustakaan, seperti Gedong Kirtya, Pusdok Denpasar, Unit Lntar Universitas Udayana, toko-toko buku dan pada tangan-tangan pemerhati sastra lainnya. Teks parwa secara keseluruhan merupakan prosa yang diadaptasi dan menunjukkan ketergantungannya dengan kutipan-kutipan dari karya asli dalam bahasa Sanskerta. Dari delapan belas parwa (astadasaparwa) yang membangun epos Mahabharata hanya berjumlah sembilan parwa yang sampai ke tangan kita (Agastia, 1994).
Sabhaparwa merupakan salah satu dari sembilan parwa yang sampai kini masih diapresiasi oleh masyarakat pencinta sastra Bali khususnya, dengan melakukan penyalinan dan translitrasi teks tersebut agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat pembaca. Bentuk apresiasi ini ditunjukkan oleh I Gusti Ketut Anom melalui hasil kreativitasnya yang telah menyalin Sabhaparwa ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 1974. Hal yang sama dilakukan I Gusti Made Widia pada tahun 2016 karena kecintaannya yang mendalam terhadap teks Sabhaparwa.
Sabhaparwa adalah penggalan cerita Mahabharata yang menceritakan tentang kemasyuran dan keindahan balai
persidangan (balai paseban/sabha) kerajaan Indraprasta yang dibuat oleh raksasa Asura Maya atas perintah Krisna. Usai dibangun, Yudistira mengundang semua brahmana untuk diberikan berkah, dijamu sepuasnya agar turut mendoakan dan mengucapkan syukur atas keberhasilan pandawa. Dalam acara tersebut hadir Rsi Narada sebagai tamu undangan yang melakukan percakapan dengan Yudistira. Inilah awal keinginan Yudistira yang berhasrat melaksanakan ritual rajasuya setelah melakukan percakapan dengan Rsi Narada yang mengungkapkan, hanya raja yang kuat yang mampu melaksanakan ritual sebagaimana pernah dilakukan oleh raja Hariscandra sebelumnya. Dalam pelaksanaan rajasuya, raja Hariscandra telah menghadiahkan berbagai macam perhiasan, makanan, pakaian lima kali lebih banyak daripada yang diminta kepada brahmana dan orang-orang yang hadir pada ritual tersebut. Setelah itu akhirnya raja Hariscandra ikut rombongan Batara Indra hidup berbahagia di sorga tanpa kembali ke dunia. Mendengar cerita dari Rsi Narada, menggugah hati Yudistira untuk mengikuti jejak raja Hariscandra. Lebih-lebih Rsi Narada juga menyampaikan pesan ayahnya Pandu di sorga agar Yudistira secepatnya melaksanakan kurban agung rajasuya ini agar bisa meniru jejak raja Hariscandra.
Ritual rajasuya hanya dapat dilakukan bila didukung oleh adanya harta yang melimpah. Untuk dapat mewujudkan semua itu hanya dapat dilakukan dengan menundukkan atau menaklukkan raja-raja negeri sekitar Indraprasta untuk memperoleh upeti dan menguasai harta benda para hartawan. Berbekal hasil rampasan dari negeri Magada sebelumnya, seperti senjata, persekutuan, dan angkatan perang masing-masing panca pandawa membagi diri menaklukkan negeri-negeri
sekitarnya. Secara serentak Arjuna ditugaskan berangkat menuju Utara, Bima menundukkan negeri-negeri di sebelah Timur, Sahadewa menundukkan negeri-negeri sebelah Selatan dan Nakula bertugas menundukkan negeri-negeri di sebelah Barat, sementara Yudistira tingggal di Kandawaprasta (Indraprasta).
Keempat pandawa masing-masing mampu mengumpulkan harta benda, emas, berlian dan hasil bumi lainnya. Selanjutnya pada waktu yang baik Yudistira dinobatkan menjadi raja diraja bersamaan dengan pelaksanaan upacara rajasuya tersebut. Semua undangan hadir dari berbagai negeri ikut menyaksikan ritual tersebut. Upacara rajasuya berlangsung hidmat hampir tanpa halangan, disaksikan oleh para hadirin. Semua kaum brahmana, ksatria, wesia dan sudra lainnya memberi selamat atas keberhasilan Yudistira yang telah mencapai kemuliaan dan kemasyuran.
Sinopsis
Cerita ini diawali oleh tokoh raksasa Asura Maya yang memohon kepada Arjuna agar berkenan menerima persembahan atas kebaikannya telah menyelamatkan dirinya. Arjuna menyuruh agar Asura Maya meminta persembahan tersebut sesuai dengan yang diminta Krisna. Kresna menyuruh agar Asura Maya membuat balai penghadapan atau balai paseban (sabha) yang indah dan megah untuk dipersembahkan kepada Yudistira. Asura Maya lalu mulai membangun balai penghadapan sesuai dengan yang diinginkan Krisna, dengan bahan setumpuk intan diperoleh dari sekitaran gunung Kailasa.
Balai penghadapan ini dibuat Asura Maya selama empat belas bulan. Saat sabha ini usai dibangun, Yudistira mengundang semua brahmana untuk diberikan berkah, dijamu sepuasnya agar turut mendoakan dan mengucapkan syukur atas keberhasilan pandawa. Turut
hadir Rsi Narada yang memuji keindahan balai persidangan (sabha) kepunyaan Yudistira yang tidak ada tandingannya. Dalam percakapan tersebut Rsi Narada mengungkapkan, dulu ketika perayaan sabha Indra di sorga, hanya raja Rsi Hariscandra satu-satunya raja yang hadir. Ini karena Hariscandra mempunyai kemuliaan dan keutamaan, yang sebelumnya telah berhasil melaksanakan kurban rajasuya, menunjukkan dirinya sebagai raja kuat. Selain bercerita tentang kemuliaan Raja Hariscandra, Rsi Narada juga menyampaikan pesan raja Pandu ayahnya di sorga, yang berkehendak agar Yudistira secepatnya melaksanakan kurban agung bernama rajasuya meniru jejak raja Hariscandra.
Mendengar cerita dari Rsi Narada, tergugah hati Yudistira untuk mengikuti jejak raja Hariscandra. Atas dorongan dan dukungan Krisna serta empat saudaranya, Yudistira menyusun strategi dan rencana yang matang mengikuti saran Krisna. Pertama yang dilakukan adalah menundukkan negeri Magada atau raja Jarasanda. Setelah raja Jarasanda terbunuh langkah berikut yang dilakukan adalah menaklukkan raja-raja negeri sekitar untuk mendapatkan upeti dan menguasai harta benda para hartawan. Berbekal hasil rampasan dari negeri Magada, seperti senjata, persekutuan, dan angkatan perang masing-masing panca pandawa membagi diri menaklukkan negeri-negeri sekitarnya.
Setelah keempat pandawa berhasil menundukkan negeri sekitar dan kembali membawa harta benda yang melimpah, penobatan rajasuya segera dilaksanakan. Semua brahmana, ksatria, waisia, dan golongan sudra lainnya yang ada di wilayah kerajaan Indraprasta diundang untuk datang menghadiri upacara rajasuya tersebut. Demikian juga rajaraja taklukannya semuanya turut diundang. Pada hari terakhir penobatan rajasuya, tibalah saatnya Yudistira
memberikan “arghya”, sebuah persembahan penghormatan pertama kepada Krisna atas petunjuk Bisma. Akan tetapi Sisupala menentang keputusan ini dan mencela Bisma dengan alasan Krisna bukan seorang raja, dan juga bukan seorang guru/pendeta. Dengan congkaknya Sisupala menghina Bisma dan Krisna hinggga kesabaran Krisna tidak bisa dibendung. Sisupala akhirnya dibunuh tanpa ampun oleh Krisna di depan para hadirin pada upacara rajasuya tersebut. Upacara rajasuya kemudian berlangsung hidmat disaksikan para hadirin sekalian. Semua kaum brahmana, ksatria, wesia dan sudra lainnya akhirnya berpamitan setelah memberi selamat atas keberhasilan Yudistira mencapai kemuliaan dan kemasyuran dalam melaksanakan upacara rajasuya.
Strategi dan Struktur yang Dibangun dalam Mewujudkan Ritual Rajasuya
Dari gambaran cerita di atas dapat diulas tafsirkan bahwa ritual rajasuya merupakan upacara yang dilakukan pada zaman India Kuno oleh penguasa yang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Seorang raja yang mampu menundukkan raja-raja lain di seluruh wilayah India sehingga dapat dianggap sebagai maha raja atau raja diraja. Rokhman (2016) menyebutkan secara struktural kekuasaan raja tersebut diperoleh karena ia menerima legitimasi, baik legitimasi moral, agama, maupun kebenaran. Seorang raja atau penguasa adalah ia yang mampu menunjukkan kekuatan, kekuasaan dan keunggulannya pemimpin wilayah lainnya.Nawawi (2020) menyebut kekuasaan adalah probabilitas seorang aktor dalam suatu hubungan sosial dalam menjalankan kehendaknya sendiri kendatipun mendapatkan perlawanan.
Yudistira adalah sosok yang memiliki kekuatan yang luar biasa kerena
didukung oleh empat saudaranya dan Krisna. Ia yakin mampu membangun ritual rajasuya walaupun harus diawali dengan perang. Perang untuk mendapatkan harta benda, emas, berlian sebagai sarana yadnya dalam pemberian sedekah kepada para tamu undangan, para brahmana, seluruh raja dan rakyat saat ritual rajasuya dilaksanakan. Dalam gambaran normatif sebuah ritual bertujuan lebih kepada pemurnian, pemulihan yang diarahkan pada transformasi dalam diri manusia dan alam. Akan tetapi ritual rajasuya ini bukan ritual biasa, karena di dalamnya tersirat ambisi, hasrat dari seorang penguasa besar untuk meraih cita-cita tertingi menjadi maha raja atau raja diraja. Ritual ini memelukan harta yang berlimpah dan hal ini hanya mampu dilakukan oleh seorang maharaja atau raja diraja yang mempunyai kekuatan yang luar biasa.
Ritual rajasuya dapat dianggap sebagai ritual berbingkai kekuasaan, karena dilaksanakan oleh raja yang mampu menundukkan atau mengalahkan raja-raja lain untuk mendapatkan utpeti yang melimpah. Untuk dapat memperoleh semua itu, selain kekuatan diperlukan strategi sebagai siasat agar segala sesuatu yang direncanakan berhasil.
Langkah awal yang dilakukan Yudistira dalam membangun ritual rajasuya ini adalah memperhitungkan kekuatan diri dan kekuatan lawan. Atas saran Krisna, ritual rajasuya ini dapat dilaksanakan bila didahului dengan mengalahkan dan membunuh raja Magada bernama Jarasanda. Raja Jarasanda adalah raja kuat yang telah menyandera atau menahan 86 raja untuk dipersembahkan kepada Rudra dalam memenuhi nazarnya. Ini bagian dari strategi Krisna untuk mendapatkan dukungan dan keuntungan dari raja-raja dalam memuluskan gagasannya
melaksanakan ritual rajasuya. Strategi yang dilakukan menaklukkan Jarasanda adalah dengan menyamar datang ke negeri Magada, seperti dalam kutipan Sabhaparwa (1974) berikut.
,...Sementara itu masuklah ke ibu kota Krisna, Arjuna, dan Bima dengan menyamar menjadi brahmana snataka,...
Kedatangan Krisna, Bima dan Arjuna ke negeri Magada menyamar sebagai brahmana snataka atau orang suci pengemis untuk mengelabui rakyat Magada. Dengan begitu Jarasanda tidak waspada dan terjebak oleh kepercayaan dirinya yang mampu mengalahkan semua musuh-musuhnya,
Kehadiran Krisna, Bima dan Arjuna yang menyamar sebagai brahmana snataka atau seorang brahmin (orang suci), hanyalah bagian dari strategi Krisna agar dapat membunuh raja Magada Jarasanda tanpa menimbulkan perang antar kerajaan. Strategi Krisna ini berhasil gemilang karena raja Jarasanda terpancing amarahnya melakukan perang tanding satu lawan satu hanya dengan Bima. Dalam perang tanding tersebut Bima berhasil membunuh Jarasanda sekaligus mendapat keuntungan harta kekayaan persembahan dari raja-raja taklukan Jarasanda dan dukungan rajaraja taklukan tersebut atas kebebasan dirinya dari cengkraman Jarasanda.
Setelah menundukkan raja Magada, Yudistira menugaskan keempat saudaranya secara serentak agar memimpin menaklukkan raja-raja di empat penjuru untuk mendapatkan utpeti berupa harta benda demi kelangsungan ritual rajasuya, seperti kutipan Sabhaparwa (1974) berikut.
Begitulah Arjuna berangkat menuju Utara, mengendarai kereta keindraan yang diperolehnya dari Agni, sang Bima ke Timur, Sahadewa ke Selatan, Nakula ke Barat. Masing-masing memimpin angkatan perang yang
besar untuk menaklukkan bendahara hartawan. Sementara Yudistira tinggal di Kandawaprasta.
Keberangkatan Arjuna ke wilayah Utara bersama pasukannya menundukkan puluhan wilayah kerajaan, seperti Kulinda, Anarta, Kalakuta, Raja Sumandala Bagadata dan wilayah-wilayah kerajaan pegunungan Himalaya lainnya. Demikian juga keberangkatan Bima ke sebelah Timur juga menaklukkan wilayah kerajaan, seperti Pancala, Candaka, Dasarna, Cedi dan puluhan wilayah lainnya. Hal yang sama dilakukan oleh Sahadewa yang ditugaskan menundukkan daerah kerajaan di sebelah Selatan menundukkan negeri Nisada, kota Mahismati, suku Kalamuka dan lain-lainnya. Tidak kalah dengan Nakula yang menaklukkan berpuluh-puluh negeri-negeri di sebelah Barat,seperti negeri pegunungan Kartikeya, negeri darsana, Trigata dan lain-lainya.
Beberapa pemimpin-pemimpin wilayah awalnya ada yang mencoba melakukan perlawanan atau penolakan atas penundukan wilayahnya. Tetapi mereka semua para pemimpin wilayah tersebut akhirnya menyerah dan menyatakan tunduk serta bersedia menyerahkan utpeti sesuai dengan yang diminta. Di antaranya juga ada beberapa pemimpin wilayah yang dengan sukarela menyerahkan harta bendanya, tanpa diawali dengan peperangan, karena ada hubungan kekerabatan dengan pandawa.
Keberhasilan menundukkan wilayah sekitar menjadi syarat guna memperoleh harta benda sebagai sarana dalam ritual rajasuya tersebut. Penundukan atas wilayah lain, pada pespektif tertentu dapat dianggap mengandung unsur-unsur pemaksaan bagi sebuah kekuasaan. Secara struktural disebutkan Rokhman (2016) bahwa kekuasaan tersebut, diperoleh karena ia menerima legitimasi, baik legitimasi moral, agama, maupun
kebenaran. Walaupun secara kontradiktif Ratna (2013) menyebutkan bahwa kekuasaan dipahami mengandung tujuan negatif. Oleh karenanya ekspansionisme dan penundukan Yudistira atas negeri sekitar tidak dianggap melanggar hukum kekuasaan karena bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
Kekuasaan dan tahta merupakan hasil dari sebuah proses yang beriringan dengan peperangan. Piliang (2006) menyebutkan bahwa kekuasaan memiliki hubungan simetris dengan libidinal, sebagai hasrat kepada sesuatu yang sifatnya imaterial, seperti citra, harga diri, kekaguman diri sendiri sebagai dorongan pemuasan sang ego. Untuk dapat melakukan ritual rajasuya, perang tidak dapat dihindari. Oleh karenanya ritual yang kerap diselenggarakan oleh para raja di zaman India Kuno ini hanya mampu dilaksanakan oleh raja-raja yang cukup kuat, didukung oleh kekuatan militer dalam menaklukkan wilayah atau pemimpin daerah lainnya.
Penundukan wilayah, selain mendapatkan harta benda, emas, berlian juga legitimasi merupakan syarat terpenting dari sebuah kekuasaan bahwa seorang penguasa berusaha mendapatkan pengakuan yang dapat membuktikan dirinya sebagai orang yang layak menempati posisi itu. Legitimasi membuahkan kepercayaan diri pada seorang penguasa yang diikuti oleh kepatuhan atas rakyatnya. Kekuasaan menurut Sugiharto (2008) bagaikan dewa penyebar kenikmatan, ia merasuki daya logis-rasional manusia menggerogotinya dari dalam sehingga yang tampak hanya daya emosi yang rakus. Hasrat berkuasa tersebut ditandai oleh rinsip-prinsip ekspansionisme, penguasaan, penundukan, penekanan, perendahan, dan eksploitasi (Piliang, 2009). Oleh karena itu merujuk pendapat Barker (2005) bahwa untuk melaksanakan ritual (rajasuya), kekuatan itu tumbuh dan lahir
dari sebuah kapiler yang terajut dalam serat-serat tatanan sosial.
Hasrat dan Motivasi Ritual Rajasuya
Sabhaparwa dan juga parwa lainnya oleh sebagian masyarakat dapat dianggap sebagai sastra sejarah karena teks tersebut mengungkapkan fakta-fakta yang merujuk pada tempat-tempat (setting) yang ada di India. Tidak hanya gunung Himalaya, tetapi lokasi-lokasi, seperti Kuruksetra tempat perang Bharatayuda terjadi, dan tempat-tempat lainnya banyak disebut-sebut dalam cerita Mahabharata dan Sabhaparwa khususnya. Demikian pula tradisi ritual rajasuya ini merupakan bagian dari proses sejarah yang mungkin pernah dilaksanakan pada zaman India Kuno.
Rajasuya merupakan rangkaian ritual yang lebih menggambarkan pada hasrat hidup seorang raja atau pemimpin atau penguasa untuk menuju puncak kepuasan. Hal ini berkaitan dengan ambisi berkuasa seseorang yang oleh Rokhman (2016) dinyatakan melekat pada setiap manusia, dan menjadi penanda insani yang bersifat abadi. Nietzsche (dalam Wibowo, 2009) bahkan menegaskan bahwa esensi kehidupan itu sendiri adalah kehendak untuk berkuasa. Dorongan untuk berkuasa itu juga terdapat dalam diri orang yang paling tidak berkuasa. Kehendak untuk berkuasa dengan demikian bukan hanya merujuk pada upaya seseorang yang tidak berkuasa untuk meraih kekuasaan, tapi juga berarti pembesaran kekuasaan melalui kekuasaan demi penguasaan. Kekuasaan hanya dapat mempertahankan dirinya hanya jika ia mengambil alih dan menguasai yang lain. Kekuasaan untuk mengakumulasi kekuasaan adalah khas dalam fenomena kehidupan.
Persoalan kekuasaan hadir pada tiap interaksi. Manusia satu dengan manusia lain dihubungkan oleh kekuasaan: menguasai, dikuasai atau kedua-duanya.
Dengan kekuasaan akan memperoleh keuntungan sosial berupa rasa hormat, wibawa, kekaguman, atau semacamnya. Secara sederhana, kekuasaan adalah kemampuan dan pengakuan yang dimiliki subjek untuk menggerakkan dan mengarahkan subjek lain untuk tujuan-tujuan tertentu. Dengan mengacu pada gagasan Nietzsche (dalam Atmadja, 2010) bahwa kehendak berkuasa merupakan penggerak prilaku manusia. Memperoleh kekuasaan merupakan wujud keinginan manusia yang tidak terhingga, dan kekuasaan tersebut ada dimana-mana yang oleh Ritzer (dalam Atmadja: 2010) disebutkan bukan karena ia berkaitan dengan segala sesuatu, melainkan ia berasal dari mana-mana. Selain itu ambisi berkuasa sebagaimana diungkapkan Rokhman (2016) melekat pada tiap manusia, menjadi penanda insani yang tampaknya akan abadi.
Kehendak untuk berkuasa inilah yang menggerakkan hati Yudistira untuk menyelenggarakan ritual rajasuya ini. Keinginan besar Yudistira untuk menyelenggarakan ritual rajasuya selain tumbuh dari hasrat pribadinya, juga dikuatkan oleh harapan dan dorongan leluhurnya (ayahnya Pandu di sorga) yang menitip pesan kepada Rsi Narada agar Yudistira segera menyelenggarakan ritual ini. Ayahnya Pandu sangat yakin anaknya (Yudistira) mampu melaksanakan ritual rajasuya ini karena didukung oleh saudara-saudaranya.
Dalam teks Sabhaparwa tidak menjelaskan secara rinci tentang proses dan sarana serta prasarana dari ritual rajasuya tersebut. Akan tetapi ritual rajasuya yang digambarkan lebih kepada proses menuju kekuasaan puncak bagi seorang raja dan dapat mencapai hasil dari proses itu.
Keinginan awal Yudistira melaksanakan ritual rajasuya lebih didorong oleh cerita Rsi Narada tentang raja Hariscandra yang sebelumnya telah
berhasil melaksanakan ritual tersebut sehingga ia mampu bersatu dengan alam kedewataan. Konon raja Hariscandra mampu memberikan sedekah atau hadiah berlimpah lima kali lebih banyak dari yang diminta orang, menghadiahkan berbagai macam perhiasan, makanan, pakaian kepada para brahmana dan seluruh lapisan masyarakat lainnya. Keberhasilan ritual rajasuya yang dilakukan raja Hariscandra seperti diungkapkan oleh Bagawan Narada menginspirasi dan memberi dorongan kuat Yudistira untuk melakukan ritual yang sama. Pada dasarnya ritual rajasuya ini dapat dikatakan lebih bermuara pada unjuk kekuasaan dan untuk memperoleh kemasyuran dan legitimasi dari raja-raja penguasa wilayah lainnya.
Seorang raja yang mampu menyelenggarakan ritual rajasuya seperti yang dilakukan raja Hariscandra dapat dianggap sebagai raja yang telah mencapai puncak segalanya. Oleh karenanya setiap raja mendambakan hal ini atau bercita-cita bisa melaksanakan ritual rajasuya ini. Akan tetapi hanya seorang raja terpilih, seorang raja atau penguasa yang mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk menundukkan negeri sekelilingnya atau negeri sekitarnya yang mampu menyelenggarakan ritual rajasuya ini, seperti dalam kutipan Sabhaparwa (1974) berikut.
Kesimpulan dari upacara rajasuya itu bila diselenggarakan dalam kedaulatan kerajaan akan menghasilkan semua upacara termasuk pula aghnihotra. Oleh karena itu rajasuya disebut penakluk segala.
Kekuasaan yang diperoleh Yudistira tidak hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi atas dukungan dan kerjasama yang direkatkan dengan semua potensi kekuatan yang dimiliki. Hal yang mendorong Yudistira merasa yakin mampu melaksanakan ritual rajasuya
karena ia didukung selain oleh saudara-saudaranya, juga Krisna yang senantiasa siap mendampinginya. Hal ini tertuang dalam teks Sabhaparwa (1974) berikut.
...,lalu Yudistira bersabda “hamba bermaksud menyelenggarakan upacara rajasuya. Tetapi yadnya ini tak dapat dilangsungkan menurut kehendak sendiri saja. Walaupun para sahabat, penasehat dan saudara-saudara hamba semua menganjurkan agar melangsungkan upacara itu, hamba minta pertimbangan tuanku. Hamba akan menurut petunjuk tuanku hanya tuanku sajalah, oh Sri Kresna.
Selain keempat saudaranya, Krisna merupakan sosok yang selalu berperan untuk kesuksesan pandawa. Tidak saja urusan ritual rajasuya semata, tetapi keberhasilan pandawa dalam berbagai hal termasuk kemenangannya dalam perang Bharatayuda adalah atas hasil peran penting dan dukungan dari sosok Krisna sendiri. Ritual rajasuya ini bukan sekedar upacara aghnihotra atau upacara persembahan kepada dewa Agni atau dewa api (vedic ritual), tetapi di balik semua itu terpendam hasrat yang lebih besar, yaitu sebuah kuasa atas kuasa sebagai raja diraja. Seorang tokoh dengan kualitas unggul, seperti Yudistira niscaya mampu memerankan peran lebih banyak untuk melakukan hal-hal besar dibandingkan dengan tokoh biasa atau tokoh raja lainnya.
Kekuasaan yang diperoleh Yudistira berbanding lurus dengan kekuatan, karena kekuasaan hanya milik bagi mereka yang kuat sebagaimana yang terjadi pada hukum rimba umumnya. Bourdieu (2007) mengutip pendapatnya Plato menguraikan bahwa kekuasaan haruslah dimaknai sebagai kesanggupan meyakinkan orang lain agar melakukan apa yang sesuai menurut kehendak orang itu. Inilah bagian dari kemampuan Yudistira yang berhasil menyerap aspirasi rakyat dan orang-orang di
sekelilingnya sehinga memperoleh kekuasaan puncak sebagai penguasa di atas penguasa karena dalam dirinya terdapat potensi yang luar biasa. Hasil akhir secara faktual yang diperoleh dari ritual rajasuya adalah kepuasan puncak atas diri termanifestasi dalam kebanggaan, sanjungan, pujian dan bentuk lainnya mengatasnamakan kesuksesan tertinggi bagi seorang maha raja atau raja diraja atas capaiannya tersebut.
SIMPULAN
Sabhaparwa merupakan parwa kedua dari delapan belas parwa (astadasaparwa) yang mengisahkan tentang keberhasilan pandawa membangun balai paseban atau balai penghadapan (sabha). Atas rasa syukur pandawa semua brahmana diundang turut mendoakan atas keberhasilan pandawa. Kehadiran Rsi Narada sebagai tamu undangan adalah awal keinginan Yudistira untuk melaksanakan ritual rajasuya setelah melakukan percakapan tentang raja Hariscandra yang sebelumnya berhasil melaksanakan ritual tersebut. Yudistira merasa yakin atas dirinya yang mampu melaksanakan ritual rajasuya sebagaimana dilaksanakan oleh raja Hariscandra. Yudistira adalah sosok yang memiliki kekuatan yang luar biasa kerena didukung oleh saudara-saudaranya dan Krisna.
Ritual rajasuya merupakant ritual berbingkai kekuasaan, karena hanya dapat dilaksanakan oleh raja kuat yang mampu menundukkan raja-raja lain untuk mendapatkan utpeti yang melimpah. Keberhasilan menundukkan wilayah sekitar menjadi syarat guna memperoleh harta benda sebagai sarana dalam ritual rajasuya tersebut. Kekuasaan dan tahta merupakan hasil dari sebuah proses yang beriringan dengan peperangan. Oleh karena itu ritual rajasuya yang kerap diselenggarakan
oleh raja-raja di zaman India Kuno ini hanya mampu dilaksanakan oleh raja yang kuat, yang mampu menaklukkan wilayah atau pemimpin daerah lainnya. Penundukan wilayah, selain
mendapatkan harta benda, emas, berlian juga legitimasi merupakan syarat terpenting dari sebuah kekuasaan bahwa seorang penguasa berusaha mendapatkan pengakuan yang dapat membuktikan dirinya sebagai orang yang layak menempati posisi itu.
DAFTAR PUSTAKA
Agastia, IBG. (1994). Kesusastraan
Hindu Indonesia (Sebuah
Pengantar). Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
Anom, I Gusti Ketut. (1980). Sabha Parwa. Denpasar: Kumara
Yowani
Atmadja, Nengah Bawa. (2010). Komodifikasi Tubuh Perempuan Joged Ngebor Bali. Denpasar: Program Studi Magister dan
Doktor Kajian Budaya Unversitas Udayana bekerjasama dengan
Pustaka Larasan
Barker, Chris. (2005). Cultural Studies, Teori dan Praktik. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
Barker,Chris dan Emma A. Jane. (2021). Kajian Budaya Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fashri, Fauzi. (2007). Penyingkapan Kuasa Simbol, Apropriasi Reflektif Pemikiran Pierre Bourdieu. Yogyakarta: Juxtapose.
Jaya, I Made Laut Mertha. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata. Yogyakarta:
Quadrant
Listiyorini, Miftaqul. (2019). Analisis
Resepsi Orang Tua Terhadap Unsur Bullying Dalam Serial Animasi Doraemon Di Rcti (Skripsi Universitas Bhayangkara Surabaya)
Moleong, Lexi J. (1996). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nawawi. (2020). Kepemimpinan Kiai dalam Membangun Komitmen Organisasi (Studi Multi Kasus Pesantren Rakyat Al Amin Sumberpucung Malang dan Pondok Pesantren Ngalah Purwosari Pasuruan) (Disertasi IAIN Jember)
nusantarainstitute.com. (2020), 16 Mei). Lakon Wayang Purwa Sesaji Raja Suya Karya Ki Purbo Asmoro. Diakses pada 19 Desember 2022, dari https://www.nusantarainstitute.co m/lakon-wayang-purwa-sesaji-raja-suya-karya-ki-purbo-asmoro/
Pendit, Nyoman S. (1980). Mahabharata Sebiah Perang Dasyat Medan Kurukshetra. Jakarta: Bharata
Karya Aksara.
Piliang, Yasraf Amir. (2006). Dunia Yang Dilipat, Tamasya
Melampaui Batas-batas
Kebudayaan. Yogyakarta:
Jalasutra.
Piliang, Yasraf Amir. (2009). Posrealitas, Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika. Yogyakarta&Bandung: Jalasutra.
Ratna, Nyoman Kuta. (2006). Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar.
Ratna, Nyoman Kuta. (2013). Glosarium 1.250 Entri Kajian Sastra, Seni, dan Sosial Budaya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rokhman, Fathur dan Surahmat. (2016). Politik Bahasa Penguasa. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Sudaryanto. (1993). Metode dan Analisa Bahasa. Jakarta: Duta Wacana University Press.
Sugiharto, Bambang. (2008). Humanisme dan Humaniora. Yogyakarta: Jalasutra.
Suprayogo dan Tobroni. (2001). Metodologi Penelitian Sosial Agama. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Teeuw. A. (1988). Sastra dan Ilmu Sastra, Pengantar Teori Sastra. Jakarta: PT. Girimukti Pasaka.
Wibowo, A.Setyo, dkk. (2009). Para Pembunuh Tuhan. Yogyakarta: Kanisius.
Zoetmulder p.j. (1983). Kalangwan Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang. Jakarta: Djambatan
Discussion and feedback