Sesapan: Wacana Pelestarian Lingkungan, Mohon Keselamatan, dan Menjinakkan Binatang Piaraan dalam Teks Sastra Lisan di Bali
on
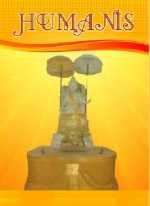
HUMANIS
Journal of Arts and Humanities
p-ISSN: 2528-5076, e-ISSN: 2302-920X
Terakreditasi Sinta-3, SK No: 105/E/KPT/2022
Vol 27.4. Nopember 2023: 424-433
Sesapan: Wacana Pelestarian Lingkungan, Mohon Keselamatan, dan Menjinakkan Binatang Piaraan dalam Teks Sastra Lisan di Bali
Sesapan: Discourse on Environmental Conservation, Asking for Safety, and Taming Pets in Oral Literary Texts in Bali
Luh Putu Puspawati, I Wayan Suardiana, dan I Made Suastika
Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Indonesia
Email korespondensi: pt_puspawati@unud.ac.id; i.suardiana@unud.ac.id;
Info Artikel
Masuk: 13 Oktober 2023
Revisi: 30 Oktober 2023
Diterima:10 Nopember 2023 Terbit: 30 Nopember 2023
Keywords: Sesapan discourse; verbal expressions; environmental conservation; asking for safety; taming animals
Kata kunci: Wacana sesapan; ungkapan lisan; pelestarian lingkungan; mohon keselamatan; menjinakkan binatang
Corresponding Author: Luh Putu Puspawati emal:
DOI:
Abstract
This research is aimed at examining the potential of Balinese oral literature in strengthening traditional values in the context of national development, especially in for Human Resources. The data collection method was carried out by tracking oral texts in several lontar texts and printed texts in the form of books in libraries. Qualitative data about sesapan is 'dissected' using hermeneutic theory. Data were analyzed using descriptive analytical methods assisted by inductive techniques. Data presentation is carried out using informal methods using description techniques. The research shows that the text of Sesapan has religious value for preserving the environment, asking for safety, and taming domestic animals. Maintaining a good environment will ensure the life of creatures on earth. People use sesapan texts when they use things in nature, such as when cutting down trees, carrying out activities in certain places that are considered haunted, when an earthquake occurs, and so on.
Abstrak
Penelitian ini ditujukan untuk menelisik potensi sastra lisan Bali dalam menguatkan nilai-nilai tradisi dalam konteks pembangunan Nasional, khususnya di bidang Sumber Daya Manusia (SDM). Metode pengumpulan data dilakukan dengan melacak teks-teks lisan yang sudah dituliskan dalam beberapa teks lontar maupun teks cetakan berupa buku di beberapa perpustakaan yang menyimpan data tentang sesapan. Data kualitatif tentang sesapan ‘dibedah’ menggunakan teori hermeneutik. Data dianalisis dengan metode deskriptif analitik dibantu teknik induktif. Penyajian data dilakukan dengan metode informal dengan teknik deskripsi. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagai sebuah wacana lisan teks sesapan memiliki nilai religius untuk pelestarian lingkungan, mohon keselamatan, dan menjinakkan binatang piaraan. Pemeliharaan lingkungan yang baik akan menjamin kehidupan makhluk yang ada di muka bumi. Teks sesapan umumnya diucapkan oleh masyarakat ketika mereka memanfaatkan segala sesuatu di
alam, seperti ketika menebang pohon, melakukan aktivitas di tempat tertentu yang dianggap angker, ketika terjadi gempa bumi, dan sebagainya.
PENDAHULUAN
Kearifan lokal Nusantara sangat beragam bentuk, fungsi, dan nilainya. Hampir semua sisi kehidupan bangsa Indonesia diwarnai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai itu pada dasarnya memiliki kesamaan seNusantara. Oleh karena demikian, dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa yang berkarakter Nusantara kita memiliki akar budaya yang sama. Kehidupan bercocok tanam sebagai salah satu bentuk peradaban modern leluhur kita, yang kita warisi setelah zaman purba misalnya, kini kita diwariskan tradisi bertani yang sangat mapan. Demikian juga luasnya hamparan huma dan ladang yang kita warisi sampai saat ini merupakan bukti betapa luhurnya budi leluhur kita dalam memertahankan dunia pertanian sebagai sarana memertahankan ketahanan pangan. Budaya membuat sawah dan sarana saluran pengairan yang tidak mudah, dengan peralatan yang tidak secanggih saat ini adalah merupakan kearifan lokal Nusantara yang telah berlangsung berabad-abad. Demikian pula dengan tradisi melaut nenek moyang kita yang demikian tangguh. Keberadaan itu dapat berlangsung karena kuatnya iman dan tangguhnya budi nenek moyang kita sebagai pendahulu.
Tindakan dan pemikiran masyarakat merepresentasikan nilai-nilai budaya yang melingkupinya. Setyani (2012: 282) menyebutkan bahwa nilai-nilai budaya yang paling umum bagi suatu bangsa dan negara terkait dengan nilai etis, estetis, dan religius. Representasi nilai-nilai tersebut tertuang dalam berbagai segi kehidupan dan bentuk karya-karya seninya, antara lain karya tulis, karya lukis, seni pahat, tabuh, dan seni tari. Untuk mengetahui bahwa suatu bangsa
dan negara memiliki nilai-nilai tinggi (adiluhung) dan berbudaya, dapat dilihat dari perilaku keseharian dan pemikiran masyarakat yang terimplementasi dalam bentuk-bentuk karyanya.
Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki peradaban yang adiluhung, memiliki beragam nilai-nilai budaya. Nilai-nilai itu tertuang dalam bentuk tulis dan lisan. Dalam tataran tulis, yang tertatahkan dalam prasasti, misalnya, kita dapat bukti bahwa tradisi tulis Nusantara itu sudah tercatat sejak tanggal 25 Maret 804 pada prasasti Sukabumi dengan bahasa Jawa Kuna (Zoetmulder, 1985: 3). Selanjutnya, dalam perkembangannya, tulisan-tulisan yang berbahasa Jawa Kuna dengan alas tulis yang dikembangkan yang awalnya dari tanah liat, batu, tembaga, perak, dsb., merambah ke alas lontar, kulit kayu, nipah kita dapatkan sekitar abad ke-9 (Marsono, 2012: 25). Sastra Jawa Kuna mengalami puncak kejayaannya sekitar abad ke-9 sampai dengan abad ke-15. Selain itu, kejayaan peradaban lisan Nusantara juga patut dibanggakan karena sebagai salah satu aset warisan leluhur yang mampu memberikan wawasan kepada generasi bangsa. Peradaban lisan patut diteliti dan diselamatkan karena perannya sebagai salah satu 'pencatat' perjalanan sejarah peradaban bangsa. Keberadaan kelisanan sekarang telah terdesak oleh arus deras urbanisasi dan modernisasi, meskipun belakangan, tradisi lisan -dalam hal ini termasuk Paribasa (Pribahasa)- telah memiliki peran penting dalam penyusunan sejarah peradaban suatu bangsa (Warman, 2000: viii dalam Lim Pui, dkk, Ed.).
Perkembangan tradisi lisan memiliki sejarah yang sangat panjang, sejalan dengan perkembangan sejarah peradaban
manusia. Dalam konteks folklor, tradisi lisan ini pertama kali diperkenalkan oleh William John Toms, seorang ahli kebudayaan antik (antiquarian) Inggris. Istilah folklor ia tulis pertama kali dalam bentuk surat terbuka dalam majalah The Athenacum No. 982, 22 Agustus 1846 dengan nama samaran Ambrose Merton. Waktu itu yang dimaksud dengan folklor menyangkut hal yang berhubungan dengan sopan santun, takhayul, balada, dan sebagainya dari masa lampau, yang sebelumnya disebut dengan istilah antiquities, popular antiquities, atau popular literature (Endraswara, 2010: 11). Selanjutnya, dalam perkembangannya sampai saat ini, segala bentuk peninggalan budaya manusia non-tulis digolongkan ke dalam tradisi lisan. Tradisi lisan termasuk sesapan (salah satu bagian dari Paribasa (Pribahasa) di Bali, mendasari peradaban manusia menuju pada peradaban tulis yang memiliki peran sama kuat untuk menjaga peradaban umat manusia sehingga patut dilestarikan!
Di Bali, sesapan setakat ini masih mendapat tempat dalam peradaban masyarakatnya. Ia dimanfaatkan dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali sampai saat ini meskipun Bali telah mengalami perubahan budaya yang cukup pesat. Pemanfaatan sesapan yang merupakan ungkapan lisan dalam keseharian masyarakat Bali mengingat masyarakat Bali seperti kebanyakan masyarakat di Nusantara masih kental dengan budaya religius. Sesapan, bagi masyarakat Bali, bukanlah ungkapan biasa, ia adalah sebuah harapan, sebuah doa yang diperuntukkan kepada penguasa dunia yang tak kasat mata. Dengan mengucapkan sesapan, masyarakat suku Bali akan terhindarkan dari segala mara bahaya, tercapai harapannya. Sebab, sesapan adalah sebuah spirit lewat bahasa oral dan ungkapan tubuh untuk
memohon sesuatu di luar kemampuan tubuh.
METODE DAN TEORI
Penelitian “Sesapan: Wacana
Pelestarian Lingkungan, Mohon
Keselamatan, dan Menjinakkan Binatang Piaraan dalam Teks Sastra Lisan di Bali” dilakukan dengan menerapkan metode dan teknik sesuai dengan tahapan penelitian. Data penelitian ini adalah data kualitatif yang didapatkan dengan menerapkan metode studi pustaka. Metode dalam pengumpulan data berupa metode simak dibantu dengan teknik catat, dan simpan berupa file (Mahsun, 2017: 92). Teori yang digunakan sebagai ‘pisau bedah’ dalam analisis data adalah hermeneutika. Metode ungkap pesan pada tahapan analisis data digunakan metode deskriptif-analitik, yakni
pendeskripsian fakta-fakta (data) secara naratif dengan teknik deduktif-induktif. Pada tahapan penyajian hasil menggunakan metode informal, yaitu dengan menarasikan hasil analisis berdasarkan kata-kata secara deskriptif. Pada tahapan ini digunakan teknik deduktif-induktif atau sebaliknya, induktif-deduktif untuk menggali makna yang terkandung dalam setiap ungkapan bahasa yang tersurat dalam teks. Hasil dari pembahasan sesapan dapat berupa: (1) Wacana Pelestarian Lingkungan; (2) Wacana Mohon Keselamatan; dan (3) Wacana Menjinakkan Binatang Piaraan. Ketiga bagian sesapan itu, kemudian dapat dibedakan lagi menjadi beberapa bagian. Wacana Pelestarian Lingkungan diwakili oleh Sesapan Menebang Kayu. Wacana Mohon Keselamatan dapat dipilah menjadi sesapan (a) mohon jimat, (b) mengusir sesuatu, dan (c) terhindar dari sesuatu.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Ruang Lingkup Sesapan
Sesapan adalah teks lisan yang setakat ini di Bali masih dilestarikan. Sebagai sebuah wacana lisan ia memiliki nilai religius untuk pelestarian lingkungan, mohon keselamatan, dan menjinakkan binatang piaraan. Sebagai sebuah warisan budaya lisan, teks sesapan penting untuk disebarluaskan dan diteliti untuk memahami seberapa jauh nalar dan kiat masyarakat untuk sadar lingkungan dan kesadaran diri sebagai insan Tuhan. Pemeliharaan lingkungan yang baik akan menjamin kehidupan makhluk yang ada di muka bumi ini semakin lama. Selain itu, kesadaran akan kebesaran Tuhan oleh sekalian umat manusia di muka bumi ini juga merupakan sisi yang sama penting dengan pemeliharaan lingkungan sebagai ciptaan-Nya!
Sesapan, merupakan salah satu ungkapan lisan dari delapan belas ungkapan lisan yang dimiliki oleh masyarakat Bali (Suardiana, 2007: 15). Teks ini merupakan doa yang diperuntukkan bagi penguasa alam (manifestasi Tuhan) untuk memohon perlindungan. Selain itu, teks ini umumnya juga diucapkan oleh masyarakat ketika mereka mau memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam, seperti ketika menebang pohon, melakukan aktivitas di tempat tertentu yang dianggap angker, ketika terjadi gempa bumi, angin ribut, dan sebagainya.
Sebagai sebuah ungkapan, sesapan memiliki makna untuk menata kehidupan supaya lebih baik dengan memelihara alam, terhindar dari mara bahaya, dan memiliki kekuatan secara teks dan konteks untuk meyakinkan diri. Dengan mengucapkan sesapan ketika kita melakukan sesuatu aktivitas yang berlaku universal, secara naluri kita memiliki keyakinan bahwa yang kita lakukan telah
mendapat rido dari-Nya dan kita aman untuk melakukannya.
Ungkapan lisan berupa sesapan, di Bali secara linguistik tidak sekadar sebagai ungkapan kosong, namun memiliki makna yang cukup dalam yang sangat mendesak untuk diteliti dan disebarluaskan untuk mengisi pembangunan dalam konteks Nusantara. Sebagai sebuah kearifan lokal ia memiliki makna untuk mengisi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan sejalan dengan teks-teks lisan sejenis di Nusantara.
Sesapan dalam Kesusastraan Bali
Dunia sesapan dalam Kesusastraan Bali termasuk ke dalam Paribasa (pribahasa). Cervantes (dalam Danandjaja, 1994: 28) mendefinisikan peribahasa sebagai kalimat pendek yang disarikan dari pengalaman yang panjang. Kalimat pendek tersebut menurut Russel merupakan kebijakan orang banyak juga merupakan cermin kecerdasan seseorang. Walaupun peribahasa merupakan kebijakan orang banyak tetapi tidak semua orang menguasai peribahasa dan menggunakannya secara aktif (Ibid).
Dalam khazanah sastra Nusantara, peribahasa banyak terdapat di berbagai suku. Khususnya peribahasa Indonesia, keberadaannya sebenarnya berasal dari peribahasa Melayu. Karena bahasa dan sastra Melayu merupakan cikal-bakal bahasa dan sastra Indonesia maka sastra Melayu dikenal sebagai kesusastraan Indonesia lama. Menurut Fang (2011: 2) sastra Melayu disebutnya dengan istilah sastra rakyat.
Peribahasa masuk wilayah tradisi lisan yang memiliki bentuk murni lisan. Termasuk dalam genre ini antara lain (a) bahasa rakyat (folk speech) seperti logat, julukan, pangkat tradisional, dan gelar kebangsawanan, (b) ungkapan seperti peribahasa, pepatah, dan pemeo, (c) pertanyaan tradisional (teka-teki), (d)
puisi rakyat, seperti pantun, gurindam dan syair, (e) cerita prosa rakyat, seperti mite, legenda, dan dongeng, dan (f) nyanyian rakyat (Sukatman, 2012: 6).
Sebagaimana lazimnya peribahasa, sesapan berbentuk kalimat deskriptif yang memiliki satu pengertian yang utuh. Menurut Tinggen (1988: 29), sesapan kata dasarnya sapa lalu didwipurwakan dan mendapatkan akhiran -(a)n menjadi sesapan, yang artinya perihal menegur atau menyapa. Isinya kebanyakan mengandung maksud permohonan atau memanjatkan doa ke hadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Mahaesa) atau kepada makhluk halus demi untuk keselamatan si pemohon. Ucapan berupa sesapan ini muncul akibat seseorang sebelumnya pernah mendapat petaka, seperti pernah digigit ular, menjumpai makhluk halus, bahkan ada anggota keluarga pernah tersambar petir. Agar terhindar dari hal-hal tadi maka seseorang akan mengucapkan sesapan ketika melintas di semak belukar, di kegelapan malam, bahkan ketika ada halilintar menggelegar.
Menurut Ginarsa (1984: 89), mendefinisikan sesapan tidak jauh beda dengan pengertian sebagaimana diberikan oleh Tinggen (1988: 29); Tim Penyusun, 2006: 27 -- 29). Sesapan, menurutnya menyangkut perihal menegur atau menyapa. Asal katanya dari kata sapa (sapa). Isinya kebanyakan mengandung maksud permohonan atau panjatan doa terhadap Ida Sanghyang Widhi, atau kepada orang-orang halus lainnya demi untuk keselamatannya. Hal ini diakibatkan kemungkinan dahulu kerap mendapat bencana, halangan kematian dan sebagainya. Dengan demikian, sesapan lebih bermakna harapan dari penyapa (seseorang) agar terhindar dari suatu bahaya. Karena harapan itu ditujukan kepada Tuhan atau makhluk gaib maka kata-kata yang digunakan dalam sesapan umumnya
kata-kata yang agak sopan dan cenderung halus. Namun, ada juga sesapan yang diucapkan dengan kata-kata kapara atau kata-kata biasa.
Pengucapan sesapan dilakukan tidak menghitung waktu dan tempat. Hal ini berkaitan dengan situasi dan kondisi dari seseorang yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Ketika sedang bepergian di siang hari yang terik, misalnya, tiba-tiba turun hujan lebat disertai dengan gemuruh serta kilatan halilintar. Agar terhindar dari kilatan petir seseorang akan mengucapkan sesapan. Demikian pula ketika bepergian di malam hari, tiba-tiba melewati tempat yang dianggap angker, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan, seseorang yang paham dengan budaya lokal (baca: Bali) akan mengucapkan sesapan.
Bentuk-bentuk Sesapan
Bentuk-bentuk sesapan dalam kebudayaan Bali dapat dibedakan dalam tiga bagian, yaitu: (1) Wacana Pelestarian Lingkungan; (2) Wacana Mohon Keselamatan; dan (3) Wacana Menjinakkan Binatang Piaraan. Ketiga bagian sesapan itu, kemudian dapat dibedakan lagi menjadi beberapa bagian. Wacana Pelestarian Lingkungan diwakili oleh Sesapan Menebang Kayu. Wacana Mohon Keselamatan dapat dipilah menjadi sesapan (a) mohon jimat, (b) mengusir sesuatu, dan (c) terhindar dari sesuatu.
-
a. Wacana Sesapan Pelestarian
Lingkungan dalam Menebang Kayu
Sesapan, tidak saja diucapkan ketika melintas di tempat-tempat keramat, ketika terjadi peristiwa alam yang menakutkan, seperti halilintar, angin ribut (badai), juga diucapkan ketika menebang kayu. Adapun sesapan orang menebang kayu adalah sebagai berikut.
"Ratu Betara Sangkara, titiang nglungsur taru duéné, mangda titiang
nénten tulah!" (Tim Penyusun, 2006: 27).
Terjemahannya:
"Paduka Hyang Sangkara, hamba mohon pohon kayu milik Paduka (untuk ditebang), agar hamba tidak kualat!"
Sesapan ini diucapkan tidak semata-mata untuk memohon kayu kepada yang empunya (dalam hal ini Hyang Sangkara), yang menurut kepercayaan Hindu diyakini sebagai Dewa yang memelihara tumbuh-tumbuhan yang ada di seluruh pelosok bumi ini, namun juga bertujuan untuk penghormatan kepada tumbuh-tumbuhan dan penyelamatan alam. Sebagai makhluk hidup, pepohonan juga berhak untuk 'dimanusiakan' seperti layaknya manusia. Ia berhak untuk hidup. Untuk itu, manusia layak membiakkan, memelihara, dan menghormatinya demi menjaga lingkungan tempat manusia tinggal. Sebagai ciptaan Tuhan, sangat wajar manusia menghormati pepohonan, dan ketika memanfaatkannya untuk menata kehidupan, ketika akan ditebang atau dirabas disertai ucapan berupa sesapan. Dengan menyapa, berarti kita ingat akan Tuhan, ingat akan fungsi pepohonan bagi kehidupan dan lingkungan. Untuk itu, setelah menyapa dengan sesapan ketika menebang, aktivitas selanjutnya, hendaknya
dilanjutkan dengan menanam pohon yang baru agar lingkungan terjaga kelestariannya.
-
b. Wacana Sesapan Mohon
Keselamatan
Wacana sesapan mohon
keselatamatan dapat dibagi menjadi:
Sesapan Mohon Jimat
Kehidupan sebagai manusia tidak dapat dilepaskan dengan kekuatan lain yang ada di sekitar kita. Untuk itu, agar terjadi keharmonisan di antara kita baik kaitannya dengan hubungan yang vertikal
maupun horizontal, penting dilakukan akselerasi dengan hal-hal yang positif. Bagi leluhur kita dahulu akselerasi itu diwujudkannya dalam sebuah guyub tutur yang disebut sebagai sesapan. Sesapan yang memiliki fungsi untuk memohon jimat dapat dilihat dalam petikan berikut.
"Ratu Betara Brahma titiang nunas pasikepan mangda rahayu rarén titiangé ring margi!" (Tim Penyusun, 2006: 28; Ginarsa, 1984: 90).
Terjemahannya:
"Paduka Hyang Brahma, hamba mohon jimat (pelindung diri) agar bayi hamba selamat dalam perjalanan!"
Sesapan ini diucapkan ketika seseorang akan mengajak anak kecil atau bayi ke luar pekarangan rumah, kemudian diambilkan arang dapur untuk dicontrengkan pada dahi si anak atau si bayi membentuk tanda tambah (tapak dara) atau dapat berupa kulit bawang merah yang ditempelkan di tempat yang sama dengan simbol yang sama pula. Pengucapan sesapan ini berbarengan dengan pembuatan simbol tapak dara pada dahi si anak atau si bayi! Sarana lainnya, dapat berupa daun kayu dedap. Ambil potongan pucuk daun dedap, kemudian disuntingkan pada telinga si anak atau si bayi dengan sesapan sebagai berikut.
"Ih, kayu sakti tiang nunas sikepan mangda rahayu tiang ring margi!" (Ginarsa, 1984: 90).
Terjemahannya:
"Hai kayu sakti, saya minta jimat agar saya selamat di jalan!"
Sesapan Mengusir Sesuatu
Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat hidup mandiri tanpa peran manusia lainnya. Untuk itu, hidup sebagai manusia kita harus banyak berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan sosialisasi diri agar dapat mengenal lingkungan dengan baik. Untuk
itu, kemudian muncul sikap hidup yang komunal bukan individu. Kehidupan secara kolektif itu diperkuat dengan membentuk perkumpulan yang di Bali disebut dengan sekaa. Perkumpulan dalam bentuk sekaa itu muncul mulai dari tingkat terkecil, yaitu keluarga, kelompok, lingkup banjar, bahkan sampai ke tingkat desa. Pada zaman dahulu, kehidupan di Bali diwarnai oleh beragam bentuk perkumpulan yang disebut sekaa ini.
Sejalan perubahan zaman, perkumpulan yang disebut sekaa mulai terkikis akibat berubahnya orientasi dan profesi masyarakat yang dahulunya menjadi petani berubah di bidang sektor jasa. Orientasi uang selalu menjadi tujuan dan tolok ukur. Kehidupan sosial mulai tergerus, demikian pula bentuk wacana lisannya semakin pudar pula. Salah satunya adalah wacana sesapan dalam mengusir sesuatu ini. Dahulu, ketika ada salah satu anggota keluarga menderita sakit, misalnya, keluarga dekat, bahkan tetangga akan berdatangan untuk menunggui, tidak saja di siang hari namun juga di malam hari.
Menunggui orang sakit di malam hari, lebih-lebih bagi yang menderita sakit keras, merupakan hal yang sangat menggelisahkan. Untuk itu, dengan banyaknya anggota keluarga yang ikut menunggui merupakan dorongan tersendiri bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga yang sedang menderita sakit untuk tabah menerima cobaan.
Ketika sedang menunggui keluarga yang sakit parah tadi kemudian tiba-tiba ada suara Katak Puru (Dongkang, bhs Bali), "Krok, Krok", maka orang Bali akan berujar dengan wacana sesapan seperti berikut.
"Ih, Dongkang, apa enot Iba sangkan mamunyi krok-krok? Yén ada anak makeneh rahayu mai, baang ia, né baanga ja ngidih basé apakpakan. Yan ia makeneh jelé,
cotot suba matanné apang borang!" (Ginarsa, 1984: 90-91).
Terjemahannya:
"Hai kamu Katak Puru, apa yang kamu lihat sehingga bersuara krok-krok? Bila ada orang bermaksud jahat ke mari berilah ia jalan, ini aku berikan kamu sirih sekunyahan. Apabila ia bermaksud jahat, patuklah matanya supaya buta!"
Wacana sesapan di atas diucapkan oleh mereka yang sedang menunggui keluarganya yang sedang menderita sakit secara spontan. Setelah mengucapkan kata-kata itu mereka umumnya membuatkan 'Tampinan', yaitu terbuat dari daun sirih yang dilelat yang didalamnya sudah diisi kapur sirih, buah pinang, gambir, tembakau (sarana makan sirih). Tampinan tadi dilempar ke arah suara Katak Puru. Tujuan dari pembuatan sarana dan sesapan seperti itu adalah untuk mengusir segala mara bahaya akibat godaan dari makhluk jahat agar si sakit segera sembuh!
Persoalan sekarang, sudah jarang orang yang mengunyah sirih, sehingga ketika ada peristiwa semacam itu terjadi maka akan sulit mencari perlengkapan untuk makan sirih tadi karena sudah jarang orang yang memakan sirih, kecuali di pedesaan. Mungkin, dapat direkayasa, ketika memiliki anggota keluarga yang sedang sakit keras, lebih-lebih penyakit yang diderita non-medis, sudah selayaknya anggota keluarga itu menyediakan sarana untuk mengunyah sirih tadi sebagai persiapan siapa tahu ada kejadian yang tidak terduga sehingga memungkinkan mengucapkan wacana sesapan.
Sesapan Terhindar dari Sesuatu
Hidup sebagai manusia tidak terlepas dari berbagai godaan, baik godaan yang kasat mata maupun yang tidak tampak. Godaan yang tidak tampak oleh mata
kepala telanjang umumnya dapat berupa godaan dari sesama manusia, makhluk halus, maupun alam gaib. Agar terhindar dari mara bahaya akibat dari godaan yang tidak kasat mata tadi, kearifan lokal Bali memberikan sebuah wacana penolaknya berupa sesapan sebagai berikut.
"Kaki, Kaki Bentuyung, eda sabanina tiang, tiang Cucun Kakiné!" (Ginarsa, 1984: 89).
Terjemahannya:
"Kakek, Kakek Bentuyung, janganlah Saya dibuat terkejut (disambar) (karena) Saya adalah cucu Kakek!"
Sesapan di atas diucapkan ketika sedang hujan turun yang disertai dengan halilintar yang menggelegar. Agar terhindar dari sambaran petir, kearifan lokal Bali dalam bentuk sesapan di atas umum diucapkan oleh masyarakat Bali. Selain mengucapkan wacana sesapan, juga dibarengi dengan melemparkan benda dari logam, seperti pisau, parang, dan sebagainya yang terpenting ada unsur logamnya. Bila dicermati kearifan lokal Bali yang diaktualisasikan lewat sesapan agar terhindar dari sambaran petir, tampaknya memiliki kekuatan secara kasat mata maupun kekuatan secara ilmiah. Secara kasat mata, dengan mengucapkan kata-kata permohonan seperti "...janganlah Saya disambar..." memberikan kekuatan bathin kepada pemohon bahwa dalam dirinya telah tertanam rasa aman tidak akan tersambar petir. Dengan demikian, ketika terjadi petir saat mereka sedang bekerja di tempat lapang, seperti sawah, tegalan, atau tempat lapang lainnya, misalnya, mereka sudah merasa aman dari sambaran petir.
Secara ilmiah, dapat dibuktikan dari prilaku ikutan yang dilakukan setelah selesai mengucapkan kata-kata sesapan tadi, yakni mereka langsung melemparkan benda-benda dari logam, seperti besi. Dengan melemparkan
benda-benda yang memiliki kekuatan listrik, seperti besi, secara langsung mereka juga sudah terhindar dari sambaran petir karena kemungkinan bisa saja petir akan menyambar benda-benda dari logam dimaksud. Persoalan ilmiah lain patut disebarkan pula kepada masyarakat bahwa yang terpenting lagi ketika ada kilatan petir mereka tidak berada di tempat lapang sendirian dan agar ada benda-benda lain yang lebih tinggi dari mereka di sekitarnya.
-
c. Wacana Sesapan Menjinakkan
Binatang Piaraan
Binatang ternak merupakan salah satu mitra kerja manusia. Tanpa keberadaan binatang ternak, manusia tidak bisa hidup layak dan nyaman. Sapi, kerbau, kuda, onta bahkan gajah adalah binatang ternak yang memiliki tenaga besar. Kekuatan besar mereka penting kita kelola agar dapat bermanfaatguna bagi kehidupan. Sebagai binatang dengan kekuatan besar, ada kalanya mereka berprilaku di luar kemampuan kita untuk menaklukkannya, meskipun mereka telah lama dipelihara oleh manusia. Tidak saja binatang dengan kekuatan besar yang susah kita taklukkan, namun ada kalanya binatang dengan kekuatan di bawah kekuatan manusia sulit kita taklukkan, seperti kera, anjing, misalnya.
Keberhasilan menaklukkan binatang piaraan yang tidak jinak menjadi jinak merupakan kebahagiaan tersendiri bagi peternak. Binatang ternak yang susah dijinakkan, akan berusaha dijinakkan dengan menggunakan kekuatan wacana berupa sesapan terutama ayam seperti di bawah ini.
"Yén ilang sakané né, wastu iba tusing ilang!" (Ginarsa, 1984: 91). Terjemahannya:
"Bila tiang ini hilang, semoga kau tidak hilang!"
Sebelum mengucapkan sesapan di atas, ekor ayam itu dipotong sedikit, lalu dikelilingkan tiga kali pada salah satu tiang rumah. Selain wacana sesapan penjinak ayam, kearifan lokal Bali juga masih banyak menyimpan sesapan penjinak binatang piaraan, namun belum banyak yang diungkapkan. Untuk itu, penting diadakan penggalian dan pencatatan demi lestarinya khazanah budaya yang adiluhung itu!
Ungkapan bahasa di atas, menurut penafsiran Lyotard atas konsep permainan bahasa Wittgenstein, bahwa bahasa memang bukan suatu gejala yang tunggal, melainkan merupakan suatu gejala historis yang memiliki karakter dasar yang bersifat lokal dan spesifik (Kaelan, 2009: 335). Dalam konteks ucapan sesapan di atas maka dapat dikatakan bahwa penafsiran bahasa sesapan oleh masyarakat Bali dimaknai sebagai sebuah ungkapan yang bukan tunggal, tetapi sampai saat ini masih diyakini kebertuahannya bagi kehidupan masyarakat Bali.
SIMPULAN
Di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat hidup manusia lebih mudah untuk menaklukkan alam, kearifan lokal mampu bersaing untuk memberikan arti bagi kehidupan itu sendiri. Kearifan lokal Bali berupa wacana Sesapan memiliki kekuatan gaib untuk melindungi manusia dari segala godaan hidup. Oleh karena demikian, penting untuk direkonstruksi dan dilestarikan demi menjaga khazanah budaya lisan tersebut.
Memudarnya kemampuan dan keinginan generasi muda Bali untuk menggunakan bahasa ibunya di tengah-tengah gerusan budaya global, dapat disiasati dengan mengadakan wujud teks yang bervariatif sehingga dalam 'kejenuhan' budaya, ada banyak pilihan teks untuk mereka baca. Salah satu wujud
teks itu adalah teks Sesapan yang mengungkapkan tentang masalah wacana pelestarian lingkungan, mohon
keselamatan, dan menjinakkan binatang piaraan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan.
DAFTAR PUSTAKA
Antara, I Gde Nala, dkk. (2013). Kamus Bali - Indonesia beraksara Latin dan Bali. Denpasar : Badan Pembina Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Provinsi Bali.
Darma Putra, I Nyoman. (2000). Tonggak Baru Sastra Bali Modern.
Yogyakarta: Duta Wacana
University Press.
Endraswara, Suwardi. (2010). Folklor Jawa Macam, Bentuk, dan Nilainya. Penaku: Jakarta.
Fang, Liaw Yock. (2011). Sejarah Kesusastraan Melayu Klasik.
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor
Indonesia.
Ginarsa, Ketut. (1984). Paribasa Bali. Denpasar: C.V. Kayumas.
Granoka, Ida Wayan, dkk. (1996). Tata Bahasa Baku Bahasa Bali.
Denpasar: Pemerintah Provinsi
Daerah Tingkat I Bali.
Kaelan, (2009). Filsafat Bahasa Semiotika dan Hermeneutika.
Yogyakarta: Penerbit “Paradigma”.
Keraf, A. Sonny. (2010). Etika Lingkungan Hidup. Jakarta: Buku Kompas.
Kurniawan, A.C. (2012). “Mitos Pernikahan Ngalor Ngulon di Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar”. Disertasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Lim Pui P. Huen, dkk, Ed. (2000). Sejarah Lisan di Asia Tenggara Teori dan Metode. Diindonesiakan dari judul aslinya "Oral History in Southeast in Asia: Theory and
Method" oleh R.Z. Leirissa. Jakarta: Pustaka LP3ES.
Mahsun. (2017). Metode Penelitian Bahasa Tahapan, Strategi, Metode, dan Tekniknya. Depok: Rajawali Pers
Marsono. (2012). "Sastra Jawa Kuna Sebagai Sumber Sastra Nusantara: Jawa Baru". Prosiding Seminar "Sastra Jawa Kuna Refleksi Dulu, Kini, dan Tantangan ke Depan" Editor: I Made Suastika dan I Nyoman Sukartha. Denpasar: Cakra Press.
Partami, Ni Luh, dkk. (2016). Kamus Bali-Indonesia. Denpasar: Balai Bahasa Provinsi Bali.
Purnama, I Gede Gita. (2020). “Melacak Jejak Kepengarangan Sastrawan Bali Modern Pra Kemerdekaan”. E-Jurnal Humanis, Fakultas Sastra dan Budaya Unud. Vol 24 No 4 (2020)
Putri, DAE. (2016). “Kearifan Ekologi Masyarakat Bayung Gede dalam Pelestarian Hutan Setra Ari-Ari di Desa Bayung Gede, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli”. E-Jurnal Humanis. Volume 15. No.2. Mei 2016
Setyani, Turita Indah. (2012). "Sembah Catur dalam Serat Wedhatama Merupakan Dasar Perilaku Berbangsa dan Bernegara"
Prosiding Kearifan Lokal dan
Pendidikan Karakter yang
disajikan dalam Konferensi
Internasional Budaya Daerah ke-2 (KIBD II) Denpasar, 22-23 Februari 2012).
Suardiana, I Wayan. (2007). "Paribasa Bali". Paper dalam Lokakarya Bahasa Bali bagi Guru-guru SD --SMA se-Kodya Denpasar yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
Sukatman. (2012). Butir-butir Tradisi Lisan Indonesia Pengantar Teori
dan Pembelajarannya. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
Suweta, I Made. (2019). “Bahasa Bali dalam Eksistensi Kebudayaan Bali”. Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya. Vol. 3, No. 2, September 2019
Suwija, I Nyoman. (2018). “Sistem Sapaan Bahasa Bali Menurut Hubungan Kekerabatan”.
Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 20, No. 2, Juli 2018.
Tim Penyusun. (2006). Paribasa Bali. Denpasar: Dinas Kebudayaan
Provinsi Bali Badan Pembina Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Provinsi Bali.
Tim Penyusun. (2006). Tata Bahasa Bali. Denpasar: Dinas Kebudayaan
Provinsi Bali, Badan Pembina Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali Provinsi Bali.
Tinggen, Nengah. (1988). Paribhasa Bali. Singaraja: U.D. Rhika.
Warna, I Wayan. (1993). Kamus Bali-Indonesia. Denpasar: Dinas
Pengajaran Daerah Tingkat I Bali.
Wibawa, IPBM. (2016). “Geguritan
Padem Warak: Analisis Bentuk, Fungsi, dan Makna”. E-Jurnal Humanis, Fakultas Sastra dan Budaya Unud. Vol 15. 2 Mei 2016
Zoetmulder, P.J. (1985). Kalangwan Sastra Jawa Kuna Selayang Pandang. Jakarta:Djambatan.
Discussion and feedback