Makanan Jepang, Identitas, Kuasa dalam Novel Sasamakura Karya Saiichi Maruya
on
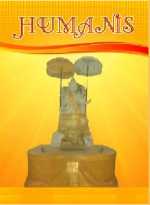
Journal of Arts and Humanities
p-ISSN: 2528-5076, e-ISSN: 2302-920X
Terakreditasi Sinta-3, SK No: 105/E/KPT/2022
Vol 27.3. Agustus 2023: 285-300
Makanan Jepang, Identitas, dan Kuasa di dalam Novel Sasamakura Karya Saiichi Maruya
Japanese Food, Identity, and Power in Saiichi Maruya’s Novel “Sasamakura"
Esther Risma Purba
Universitas Brawijaya, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur
Email korespondensi: estherpurba@ub.ac.id
Info Artikel
Masuk:19 Juli 2023
Revisi: 5 Agustus 2023
Diterima:12 Agustus 2023
Terbit:31 Agustus 2023
Keywords: Nihon ryōri ʻJapanese foodʼ; identity;
Yamato damashii ʻJapanese Spiritʼ; Japanese; power
Kata kunci: makanan Jepang; identitas; Yamato damashii ʻJiwa Jepangʼ; orang Jepang; kekuasaan
Corresponding Author:
Esther Risma Purba
Email: estherpurba@ub.ac.id
DOI:
Abstract
The discourse of Yamato damashii 'Japanese Spirit' or ʻJapanese Soulʼ constructs the knowledge about "Japanese people", "Japanese culture" and "nationalism." This paper discusses Saiichi Maruyaʼs novel entitled Sasamakura. The analysis focuses on Hamada, the major character. The analysis is carried out by using a critical paradigm, by dismantling the aspect of power that constructs the meaning of Japanese food by using Stuart Hall's theory of identity and Michel Foucault's work on the discursive construction of power/knowledge. This research found that, food that originally belonged to foreigners, was shed from its original identity through reintegration and reproduction to become what is called Japanese cuisine. What is known as nihon ryōri or washoku occupies a more special position because it is considered has deep roots in Japanese history, with cooking and serving techniques, authentic, and does not mix with other cultures that are considered inferior. Therefore, Japanese people who are considered to have a Japanese identity are expected to represent Yamato damashii 'Japanese Soul' when they choose to eat nihon ryōri and eat in a predetermined manner or etiquette.
Abstrak
Diskursus identitas Yamato damashii ʻJapanese Spiritʼ atau ʻJiwa Jepangʼ mengonstruksi pengetahuan mengenai “orang Jepang”, “budaya Jepang” dan “nasionalisme”. Penelitian ini berfokus pada tokoh utama, Hamada dan dilakukan dengan menggunakan paradigma kritis, yakni membongkar aspek kuasa yang mengkonstruksi identitas Jepang lewat makanan dengan menggunakan teori identitas Stuart Hall dan teori relasi kuasa Foucault. Melalui reintegrasi dan penciptaan kembali, makanan yang awalnya milik asing, dilepas dari identitas awalnya untuk menjadi masakan yang disebut masakan Jepang. Keberadaan pihak lain, yakni Barat melalui makanan menjadi pihak yang dianggap berbeda sehingga diposisikan berhadapan dengan Jepang. Apa yang disebut sebagai nihon ryōri atau washoku menduduki posisi yang lebih istimewa karena muatan sejarah peradaban makanan yang diklaim memiliki sejarah yang panjang, asli, dan tidak bercampur dengan budaya lain yang dianggap liyan atau inferior. Oleh karena itu, orang Jepang yang dianggap
memiliki identitas kejepangan, dianggap merepresentasikan Yamato damashii ʻJiwa Jepangʼ apabila memilih memakan nihon ryōri dan makan dengan cara atau etiket yang telah ditetapkan.
PENDAHULUAN
Di dalam sejarah kehidupan manusia, makanan memiliki peranan penting di dalam beragam ritual. Oleh manusia, makanan dibuat, disajikan, dan dinikmati untuk menyampaikan keinginan, harapan, dan rasa syukur. Menurut Aoyama (2008), makanan difungsikan sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perasaan tertentu, merepresentasikan pandangan religi, politik, dan filsafat. Makanan juga dapat menggambarkan kebencian, ketakutan dari si pembuat dan penikmatnya, dan dapat ditolak untuk dimakan karena alasan-alasan tertentu.
Makanan juga dihadirkan dalam karya sastra sebagai media bagi pengarangnya untuk menyampaikan pesan-pesan melalui karakter di dalam cerita. Aoyama (2008) mengutip pernyataan kritikus sastra Terry Eagleton dari buku Consuming Passions: Food in the Age of Anxiety yang mengatakan bahwa makanan, seperti halnya karya sastra, tampak seperti sebuah objek, tetapi sebenarnya makanan merupakan sebuah relasi. Artinya, makanan bukan sekedar objek yang diam, tetapi mengekspresikan bagaimana manusia memaknai relasi dengan sekitarnya, yakni sesama manusia dan lingkungan tempat ia berada.
Aoyama juga menambahkan, makanan merupakan “a window on the political”. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa makanan juga dapat menjadi jalan bagi kita untuk melihat bagaimana manusia membangun cita-cita ideal, memutuskan pilihan-pilihan tertentu di tengah lingkungannya. Makanan yang dibuat dan dinikmati tersebut tidak diciptakan dengan mudah, tetapi dapat menempuh perdebatan,
dibandingkan, dinegosiasikan antara pihak-pihak yang memiliki relasi yang tidak seimbang. Dengan kata lain, makanan yang dibuat, disajikan, dan disantap, sesungguhnya dapat merepresentasikan kepentingan yang diusung oleh pihak tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa makanan menjadi representasi dari identitas tertentu yang dicita-citakan, tidak saja di dalam level individu, tetapi juga di level pembicaraan tentang identitas kolektif yang dibangun atas dasar etnis dan bangsa.
Menurut Hobsbawm & Ranger (1983), membuat dan menikmati makanan sekaligus menjadi bentuk dari nasionalisme terhadap negara. Karena identitas yang direpresentasikannya, makanan menjadi media untuk membedakan antara “kita” dengan the Other “yang Lain”. Pembedaan dilakukan dengan disengaja melalui proses seleksi, memproduksi ulang, dan ‘rekayasa’ tradisi dan budaya sebuah bangsa.
Jepang menjadi negara yang giat mengupayakan makanan tradisional mereka yang mereka sebut sebagai nihon ryōri atau washoku untuk dicatat dan diakui oleh dunia internasional. Pada tanggal 5 December 2013, washoku, secara resmi didaftarkan sebagai warisan budaya takbenda oleh United Nation, Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Washoku didaftarkan sebagai “praktik masyarakat dalam memproduksi, memproses, menyiapkan, dan mengonsumsi makanan yang didasarkan pada seperangkat keterampilan, pengetahuan, praktik, dan tradisi yang menyeluruh dan seksama. Washoku merupakan praktik yang dihidupkan oleh jiwa yang murni yang
menghormati alam dan menjadi praktik hidup berkelanjutan yang menjaga harmoni dengan alam (UNESCO, 2013). Lebih lanjut lagi dinyatakan bahwa washoku “dipraktikkan oleh seluruh wilayah negara Jepang dan telah tertanam sebagai pola dalam kehidupan sehari-hari yang berfungsi secara sosial untuk meneguhkan identitas orang Jepang, mempererat hubungan kekeluargaan dan persatuan sebagai masyarakat Jepang. Washoku berperan dalam menciptakan kehidupan yang sehat melalui makanan bergizi yang seimbang dan tradisi yang dipraktikkan dan dirawat bersama” (UNESCO, 2013).
Karakteristik washoku, sejarah, bahan-bahan, cara pemilihan bahan, cara penyajian, dan cara menyantapnya juga dijelaskan secara rinci di dalam laman Kementrian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (MAFF-Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries) Jepang. Washoku tidak hanya tentang masakan, tetapi juga meliputi kue manis (wagashi), teh, dan sake sebagai minuman nasional (https://www.maff.go.jp/e/data/publish/at tach/pdf/index-25.pdf). Hal ini menunjukkan bahwa washoku telah dirumuskan secara resmi oleh negara.
Dari definisi tersebut tampak adanya cita-cita untuk mendapat pengakuan bahwa Jepang memiliki peradaban budaya kuliner dengan sejarah panjang, dibuat dengan ketrampilan dan pengetahuan yang tinggi. Selain itu, ada upaya untuk menunjukkan bahwa tradisi tersebut sangat terjaga hingga diklaim semua orang Jepang di seluruh negri membuat dan menyantapnya. Washoku lebih dari sekedar makanan untuk alasan kesehatan dan hidup, tetapi ia memiliki peran sebagai nilai-nilai luhur yang merekatkan persatuan orang Jepang. Dari penjelasan di situs UNESCO tersebut, Washoku menjadi sebuah diskursus tentang identitas bangsa yang diklaim diusung bersama. Isu tentang
nasionalisme menjadi mengemuka ketika berbicara tentang hal-hal yang mempererat rasa kesatuan dan yang menjadi kesadaran bersama.
Dengan penekanan terhadap “tradisi yang terjaga” dan “diyakini dan dipraktekkan/dikonsumsi” ada upaya menekankan identitas budaya makanan bangsa Jepang yang memiliki keaslian, kemurnian, dan keunikan. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah tidak ada pertemuan lebih dari satu budaya dalam apa yang diklaim sebagai makanan asli Jepang? Bagaimana makanan tradisional Jepang dikonstruksi dengan kepentingan yang bersifat ideologis, dengan dasar argumen adanya nilai-nilai luhur (religi, budaya, sejarah, sosial) yang dikandungnya sehingga ia menjadi identitas budaya yang harus diusung bersama untuk membedakan “kita” sebagai bangsa Jepang dengan “mereka”yang bukan Jepang?
Penelitian ini menelaah tentang identitas Jepang yang disebut dengan Yamato damashii (Jiwa Jepang atau Semangat Jepang) yang direpresentasikan melalui makanan/minuman dan diusung oleh tokoh-tokoh dalam novel dan yang dipersoalkan oleh tokoh utama. Novel yang diteliti berjudul Sasamakura karya dari penulis Saiichi Maruya (1925-2012) yang ditulis pada tahun 1965 dan diterbitkan pada tahun 1966. Maruya telah memenangkan penghargaan Akutagawa Prize, Kawabata Prize, Tanizaki Prize, Noma Literary Prize, dan lainnya untuk karya-karyanya. Penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi di bidang sastra di Jepang. Puncaknya pada tahun 2011, ia dianugrahi the Order of Culture, oleh Kaisar Jepang.
Maruya disebut sebagai penulis yang kritis menanggapi situasi sosial, budaya, dan politik di tahun 1960-an (Keene, 2002). Isu tentang identitas masih menjadi tema yang banyak dibicarakan dan dipersoalkan di berbagai belahan
dunia di tengah situasi batas-batas yang menjadi cair dan interaksi dari beragam budaya menjadi dimungkinkan. Karena itu, penelitian ini mengulas tema yang relevan dibicarakan saat ini.
Penelitian ini memiliki beberapa manfaat: pertama diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana makanan bermuatan politik yang terkait kekuasaan. Kedua, pembelajar budaya Jepang diharapkan dapat menanggapi secara kritis diskursus atau wacana identitas kejepangan, masih perlukah memelihara diskursus identitas yang berdasarkan pada atribut budaya masa lalu di tengah situasi pertemuan budaya yang begitu cepat dan batas-batas etnis, ras, agama tidak lagi memadai atau bahkan tidak diperlukan untuk membentuk komunitas yang terbayang. Ketiga, pembelajar budaya Jepang dapat secara kritis menanggapi praktik-praktik budaya yang diklaim sebagai identitas asli karena jika ditelusuri, identitas dan budaya tidak lepas dari praktik kekuasaan yang berpotensi memanipulasi kebenaran dan melanggengkan kekuasaan. Pencampuran beberapa budaya dari etnis atau bangsa yang berbeda (hibridisasi) dalam kenyataannya memang terjadi dan dijalani, tetapi kita menjumpai kenyataan di mana hibridisasi tersebut disangkal.
Penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman bahwa praktik budaya dari bangsa lain juga dapat turut berkontribusi pada pembentukan identitas pada level personal dan peradaban suatu bangsa. Dengan demikian, klaim tentang “keaslian” yang mungkin diciptakan oleh budaya dominan untuk berkuasa atas budaya dari kelompok yang tidak dominan, dapat selalu dikritisi. Keempat, selama ini, pembelajar dalam kajian Jepang, menanggapi diskursus “Jepang yang indah yang masih melestarikan budaya” sebagai kekhasan dan keunggulan Jepang, yakni sebagai bangsa yang masih memelihara budaya tradisional. Pemikiran semacam ini
mengabaikan potensi-potensi yang dapat memperkaya keberagaman identitas yang sebenarnya telah ada, tetapi menjadi tidak terpikirkan karena kecenderungan menjeneralisasi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai sejarah penciptaan Yamato damashii dan dapat meninjau secara kritis ketika nama tersebut diproduksi kembali dalam acara bertema budaya yang mengusung identitas budaya Jepang.
Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus pada isu tentang identitas dari apa yang disebut “Makanan/minuman Jepang” atau yang di dalam novel Sasamakura ini disebut nihon ryōri atau washoku. Konteks situasi sosial dan politik pada tahun 1965 di dalam novel akan ditelaah untuk mengetahui bagaimana kekuasaan beroperasi dalam mengonstruksi dan memelihara diskursus identitas
kejepangan.
Terkait novel Sasamakura, peneliti menemukan artikel-artikel singkat dan esai yang ditulis di koran oleh kritikus. Melalui esainya yang dimuat di dalam koran Yomiuri bulan Agustus 1966, Hirano (1997) menyatakan bahwa dengan membuat tokoh bekerja di universitas swasta konservatif yang berhaluan kanan dan latar politik Jepang yang diwarnai pemberontakan kelompok berhaluan kiri yang melakukan gerakan menentang kehidupan kampus yang konservatif, Maruya dianggap berhasil membuat konflik muncul dan berkembang.
Yamazaki (1997) dalam artikelnya yang berjudul Chohei hikisha ga hiki shita mono “Desertir adalah orang yang melarikan diri” menjelaskan bahwa Sasamakura mengangkat tema tentang kecemasan identitas (aidentitii no fuan) melalui konflik yang ia sebut antara kesadaran sebagai jiga ‘diri’ dengan kesadaran sebagai kokka ‘bangsa’. Akan tetapi, Yamazaki tidak mengemukakan kritikannya terhadap diskursus identitas kejepangan melalui makanan yang
dipersoalkan di dalam novel Sasamakura. Purba (2016) meneliti Sasamakura dengan menyoroti paham yang mengedepankan kepentingan kelompok (shūdan shugi) yang diusung oleh orangorang di lingkungan tokoh utama dan lembaga tempat ia bekerja. Akan tetapi, penelitian tersebut bersifat mendeskripsikan kepentingan kelompok yang direpresentasikan dalam beberapa elemen dan perilaku yang dikonstruksi sebagai identitas budaya tanpa meninjau secara kritis mengapa elemen dan perilaku tersebut diusung dan dipraktekkan. Selain itu, penelitian tersebut tidak menyoroti bagaimana kekuasaan beroperasi dalam mengonstruksi identitas dan sama sekali tidak membicarakan identitas yang direpresentasikan melalui makanan dan minuman. Penelitian-penelitian yang mengangkat Sasamakura belum ada yang membahasnya dengan menekankan aspek relasi kuasa-pengetahuan sebagai aspek penting dalam produksi diskursus identitas di kehidupan sehari-hari tokoh utama Hamada, khususnya yang terkait makanan dan minuman.
Adapun penelitian yang meninjau diskursus tentang identitas dalam budaya Jepang secara kritis, juga dilakukan oleh Maghfira dan Purba (2023). Penelitian tersebut membongkar diskursus mengenai gender yang mengatur peran perempuan Jepang. Di masa pemerintahan Meiji (1868-1912), diskursus tersebut pernah menjadi ideologi yang diatur oleh negara melalui kurikulum pendidikan. Hingga tahun 2023 ini, diskursus tersebut masih berdampak dalam kesempatan di bidang ekonomi dan politik yang mana Jepang di dalam Indeks Kesenjangan Gender Global berada pada posisi ke-125 menurut World Economy Forum (Wake, 2023). Dari contoh tersebut tampak bagaimana diskursus mengenai identitas beroperasi dalam kehidupan sehari-hari.
Identitas selalu mengalami
transformasi, peninjauan ulang,
kontestasi, dipengaruhi oleh relasi kuasa, yang berkaitan dengan tempat, waktu, sejarah dan kebudayaan sehingga menjadi isu yang tidak pernah selesai. Ketika negara/masyarakat memaksakan diskursus yang mengatur makna dan mengorganisir tindakan, menyebabkan suara individu yang menyuarakan kepentingan individu tidak mendapat tempat dalam perdebatan.
Oleh karena itu, penelitian “Makanan Jepang, Identitas, dan Kuasa di dalam Novel Sasamakura Karya Saiichi Maruya” ini akan mengungkapkan permasalahan identitas kejepangan yang dipersoalkan tokoh utama: relasi kuasa yang
beroperasi dalam mengonstruksi
diskursus identitas kejepangan melalui makanan/minuman. Penelitian ini dilakukan melalui realitas diskursus identitas Yamato damashii ‘Japanese Spirit’ yang mengkonstruksi
pengetahuan mengenai “orang Jepang”, “Budaya Jepang” dan “nasionalisme” yang diangkat oleh tokoh utama sebagai korpus penelitian dan situasi sosial politik tahun 1965 yang melatarbelakangi permasalahan di dalam novel.
METODE DAN TEORI
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan paradigma kritis yang disajikan dalam bentuk deskripsi. Menurut Arikunto (2010), penelitian deskriptif adalah penelitian yang datanya dikumpulkan berdasarkan
faktor yang mendukung objek
penelitian untuk selanjutnya dianalisis (di dalam Zahrah & Purba, 2022). Sumber data penelitian adalah berupa data formal, yakni kata-kata, kalimat, diskursus dan setelah data-data tersebut dideskripsikan, selanjutnya akan
dilakukan analisis. Permasalahan di dalam penelitian ini didekati dengan pendekatan kritis, yakni relasi kuasa yang
memandang bahwa budaya atau tradisi memuat aspek kepentingan atau
kekuasaan; konsep identitas yang di dalam kajian budaya-budaya (cultural studies) dipandang sebagai hal yang dinamis; dan mengkritisi paham yang melihat identitas sebagai hal yang asli dan tidak berubah.
Korpus primer dari penelitian ini adalah novel Sasamakura (sebanyak 420 halaman) karya Saiichi Maruya yang ditulis tahun 1965 dan diterbitkan tahun 1966. Korpus sekunder berbentuk pengumpulan data yang berhubungan dengan diskursus identitas kejepangan (Yamato damashii) yang
direpresentasikan melalui makanan dan minuman. Diskursus identitas Yamato damashii meliputi konsep budaya, etnisitas, dan nasionalisme.
Penelitian ini menggunakan kerangka berpikir Stuart Hall (1932 - 2014) tentang identitas dan Michel Foucault (1926 -1984) tentang relasi kuasa. Stuart Hall (1996) menjabarkan relasi antara national culture ‘budaya nasional’ dengan national identities ‘identitas nasional’. Menurut Hall, elemen budaya dan politik menjadi unsur pembangun dari identitas nasional. Usaha-usaha untuk membuat identitas nasional yang memiliki identitas yang satu dan seragam, dalam pandangan Hall ia sebut sebagai usaha menolak elemen-elemen
keberagaman yang terdapat di dalam sebuah bangsa.
Hall (1991) berargumen bahwa budaya nasional merupakan usaha yang tidak hanya sekedar alat pemersatu, bahkan lebih jauh lagi budaya nasional menghubungkan beragam individu dan kelompok di dalam sebuah struktur kekuasaan. Dengan kata lain, apa yang disebut sebagai diskursus budaya nasional, tidak lepas dari hasil konstruksi di dalam relasi kuasa yang di dalamnya melibatkan pemaksaan, ketegangan, dan penolakan (resistensi).
Diskursus identitas mengenai budaya dan bangsa, lebih lanjut dapat dijelaskan dengan pemikiran Foucault. Diskursus (discourse) dan kuasa/pengetahuan (power/knowledge) dipahami sebagai penjelasan, pendefinisian, pengklasifikasian, dan pemikiran tentang orang, pengetahuan, dan sistem abstrak pemikiran. Pemikiran tersebut ia jelaskan di dalam bukunya yang berjudul Discipline and Punish: “Kekuasaan menciptakan pengetahuan…pengetahuan dan kekuasaan saling mempengaruhi secara langsung satu sama lain” (Lubis, 2012). Foucault menjelaskan pengetahuan adalah apa yang dikumpulkan dan diputuskan benar oleh sekelompok orang. Jadi, ada kekuasaan/kekuatan (power) yang menentukan kebenaran. Kebenaran bukanlah sesuatu yang sudah ada, melainkan hasil konstruksi budaya dalam jaringan kuasa. Menurut Foucault (di dalam Ramadhani & Purba (2021), jika ada sekelompok orang dapat meyakinkan banyak orang untuk percaya tentang apa yang mereka katakan, maka itu lebih penting daripada kebenaran itu sendiri.
Pemikiran Foucault tentang diskursus dan relasi kuasa/pengetahuan akan bermanfaat untuk mengenali dan membongkar aturan-aturan dan praktek-praktek yang memproduksi pernyataan yang bermakna (identitas, bangsa, nasionalisme) pada satu rentang sejarah tertentu, yakni pada masa 1965 yang menjadi latar waktu dan sosial di dalam novel yang menjadi objek penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Klaim Keunikan dan Keaslian pada Makanan dan Minuman
Klaim ini muncul ketika Hamada berhadapan dalam suasana pesta. Di dalam beberapa kali kesempatan di pesta tersebut, klaim identitas kejepangan muncul melalui pernyataan dengan penyebutan “Yamato damashii” dan
“Japan Spiritto”. Narator menceritakan bahwa acara dihadiri oleh 2 direktur universitas dan pegawai-pegawai lain di seluruh departemen yang ada di fakultas tempat tokoh utama Hamada bekerja. Pegawai lain yang keberadaannya disebut di dalam teks adalah Kabag Administrasi Pengajaran, Kabag Keuangan, asisten juru ketik di bagian Administrasi Pengajaran, dan Nishi (rekan sesama juru ketik) yang berusia lebih muda setahun dari Hamada tetapi lebih dahulu dipekerjakan. Jika dilihat dari jabatan orang-orang yang disebut dalam teks yang akan diulas berikut ini, maka Kabag Administrasi Pengajaran dan Kabag Keuangan adalah orang yang jabatannya lebih tinggi dari Hamada. Hamada diceritakan duduk di sudut ruangan sendirian sambil minum wiski dan air. Ketika asisten juru ketik dari bagian Administrasi Pengajaran hendak
menuangkan sake ke dalam gelas Hamada, ia berhenti dan sedetik kemudian berkata:
Data 1:
「あ、浜田さんは水割りだったな」 “Oh, Pak Hamada minum wiski dengan air es ya.”
Hamada:「そうなんだよ」(Maruya, 2014, hal.2) “ya, betul.”
Kepala keuangan yang melihat adegan tersebut menawarkan bir dengan suara yang menunjukkan dia sudah sangat mabuk.
Data 2:
「おう、ビールどうだ?」
“Eh, bagaimana dengan bir?” Hamada: あれは腹が張って」 Bir (itu) bikin perut kembung.” (Maruya, 2014, hal 123)
Mendengar tanggapan Hamada, Kabag Keuangan berkata dengan nada mengejek:
Data 3:
「日本料理とウィスキーじゃ、合わ んだろう」
“Makanan Jepang dan Wiski itu perpaduan yang tidak cocok, kan?” (Maruya, 2014, hal 124)
Hamada dengan jelas tidak
menyembunyikan kesukaannya terhadap budaya Barat. Sembari mengamati gelas wiski yang ia minum, Hamada mengatakan:
Data 4:
「ええ、西洋かぶれでしてね。これ は舶来ウィスキ―じゃないけれど」 (Maruya, 2014, hal 126)
“Saya menyukai hal-hal terkait Barat meskipun ini bukan wiski impor.”
Di dalam rangkaian dialog data 1-4 tersebut, Maruya menggunakan minuman dan makanan serta budaya yang mengiringinya untuk menunjukkan karakterisasi tokoh-tokoh di dalam karya. Hamada menjadi satu-satunya orang yang tidak minum sake dan memilih wiski dengan alasan menyukai minuman Barat. Orang lain yang terlibat di dalam komunikasi dengan Hamada, meminum sake karena minuman itu diperlakukan sebagai pendamping Nihon ryori (makanan tradisional Jepang).
Bagi orang di sekitar Hamada, sake lah dan bukan wiski yang merupakan pasangan yang cocok untuk makanan Jepang. Dari dialog tersebut, identitas sake, selain ditentukan oleh faktor-faktor yang melekat padanya (terbuat dari beras yang difermentasikan, mengandung lebih dari 20% alkohol, terbuat dari beras terbaik dan air pegunungan yang murni), juga dibentuk oleh faktor di luar sake, yakni kelompok masyarakat yang membuat dan yang meminum sake. Sake diperlakukan sebagai representasi dari identitas Jepang, sedangkan wiski menjadi representasi dari identitas Barat. Selain itu, identitas sake juga diciptakan
berdasarkan faktor di luar sake yang dinilai memiliki atribut yang bertentangan atau berbeda, yakni wiski.
Sebagaimana yang dijelaskan oleh Woodward (1997), identitas dapat dibangun melalui relasi yang menghubungkan subjek diri dengan sosok liyan (the Other) atau sosok pembanding di luar dirinya. Relasi tersebut menekankan perbedaan yang berbentuk oposisi biner. Di dalam dialog tersebut, sake dibandingkan dengan wiski, maka Hamada yang memilih sake diperlakukan sebagai sosok yang “yang Lain” atau liyan.
Dari dialog tersebut tampak bagaimana identitas ditandai oleh adanya anggapan atau kesadaran akan perbedaan. Perbedaan itu mengakibatkan munculnya sistem klasifikasi yang berdasarkan pada tegangan kutub-kutub berlawanan, atau oposisi biner. Oposisi biner tersebut tampak dari, sake/wiski, Jepang/Barat, Hamada/orang lain, makanan Jepang/makanan Barat, Jiwa Jepang/Jiwa bukan Jepang. Wiski dianggap tidak cocok bukan karena faktor-faktor di dalam diri wiski itu sendiri, misalnya karena kandungan wiski dapat menghasilkan senyawa berbahaya jika diminum bersama dengan makanan Jepang, atau wiski akan meniadakan kandungan gizi pada makanan Jepang jika dinikmati bersama. Wiski oleh orang lain di sekitar Hamada ditolak karena faktor di luar diri wiski itu sendiri, yakni minuman yang diproduksi oleh Barat, yakni Rusia.
Pernyataan “makanan Jepang dengan wiski itu tidak cocok” dapat dibaca bagaimana sake diperlakukan sebagai minuman yang memiliki posisi superior daripada wiski. Di dalam sejarah, Jepang berhasil mengalahkan Rusia di dalam perang tahun 1905 dan kemenangan tersebut menjadi awal kebangkitan nasionalisme Jepang yang meyakini kemampuannya mengalahkan Barat (Koda, 2005). Sake menduduki
posisi istimewa dalam budaya Jepang, tidak saja karena sejarah panjang yang dimilikinya, tetapi juga mitos-mitos relijius yang semakin mengukuhkan legitimasinya. Di dalam panduan resmi tentang washoku yang diunggah oleh Kementrian Pertanian Kehutanan, dan Perikanan Jepang (MAFF), sake dijelaskan sebagai “minuman nasional” Jepang yang “melengkapi sajian menu tradisional Jepang menjadi menarik dan menenangkan jiwa” (https://www.maff.go.jp/e/data/publish/at tach/pdf/index-25.pdf).
Di Jepang, sake merupakan elemen penting di dalam perayaan dan minum sake menjadi aktivitas sosial yang merekatkan hubungan. Hamada menolak minum sake, bukan karena ia tidak menyukainya, dan juga bukan karena alasan yang terkait kesehatan, seperti yang ia gunakan sebagai alasan tidak minum bir. Ia memilih wiski dengan alasan hal-hal yang terkait Barat. Penolakan Hamada untuk minum sake menjadi hal yang ditertawakan oleh rekan-rekannya yang mengejeknya karena ia ‘berbeda’ dengan orang lain di pesta itu. Orang lain memperlakukan sake sebagai elemen yang melekat bersama dengan makanan Jepang.
Dari dialog tersebut tampak bagaimana makanan dan minuman dikaitkan dengan persoalan identitas budaya yang diklaim unik, yakni sake adalah unik sehingga tidak bisa disejajarkan untuk menjadi pengganti dari wiski untuk mendampingi makanan Jepang. Sake dan wiski menjadi 2 elemen yang saling berhadapan/bertentangan. Persoalan cocok dan tidak cocok adalah lepas dari persoalan selera dan lebih cenderung ditentukan oleh konstruksi untuk melanggengkan klaim keunikan di dalam budaya tradisi kuliner Jepang.
Sebaliknya, Hamada dengan terang-terangan dan lebih jauh membawa sake kepada persoalan ideologis dan menegaskannya pilihan berdasarkan
keinginannya melalui pilihan kata, “Saya menyukai hal-hal terkait Barat meskipun ini bukan wiski impor.” Ia lebih mengedepankan pilihan berdasarkan suka dan tidak suka. Di dalam budaya Jepang yang mengatur pola-pola berinteraksi dengan yang lain, persoalan suka dan tidak di level personal akan dikesampingkan demi mengikuti kebiasaan atau aturan kelompok yang disepakati atau yang berlaku secara umum.
Pilihan terhadap apa yang dipilih dan disukai dapat menjadi penanda identitas. Dalam hal ini, Hamada lebih mengedepankan identitas pribadinya daripada identitas Jepang yang diusung kelompok sebagaimana yang ditunjukkan oleh yang lain. Warren Belasco dalam bukunya yang berjudul Food: The Key Concepts mendefinisikan tentang makanan nasional sebagai identitas (Farina, 2021). Ia menjelaskan bahwa apa yang disebut sebagai makanan nasional melibatkan seperangkat protokol, mulai dari bahan-bahan tertentu yang ditetapkan oleh penguasa, cara menyiapkan, cara memberi rasa atau bumbu, seperangkat etiket ketika menyantapnya, dan seperangkat cara mendistribusikan bahan mulai dari alam atau ladang hingga disajikan untuk di makan. Dari apa yang dipilih oleh Hamada, menunjukkan ia tidak merepresentasikan dirinya sebagai bagian dari bangsa Jepang karena ia memilih dan menyantap makanan dengan cara yang berbeda dengan orang lain di pesta.
Kita mengenal peribahasa “Kita adalah apa yang kita makan” (We are what we eat), sebuah peribahasa yang telah menjadi kajian bagi antropolog untuk menjelaskan bagaimana makanan (atau minuman) menjadi representasi dari identitas personal. Makanan tidak lagi sekedar sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi melalui makanan dapat digali pembentuk identitas dengan melihatnya dari sudut pandang sejarah,
politik, dan sosial. Pernyataan Hamada pada data 4: 「ええ、西洋かぶれでし てね。これは舶来ウィスキ―じゃな いけれど」(Maruya, 126) “(Saya) menyukai hal-hal terkait Barat meskipun ini bukan wiski impor”, menunjukkan sikapnya yang sengaja memilih produk Barat, dan menjadikannya sebagai identitas personalnya yang berbeda dengan orang lain di sekitarnya. Hamada telah ‘merusak’ keseragaman, kesatuan identitas yang diklaim bersifat esensialis, yakni identitas bangsa Jepang, yaitu selaku orang Jepang, maka sudah semestinya menikmati sake ketika menyantap hidangan Jepang.
Reintegrasi dan Reproduksi Identitas Barat di dalam Makanan Jepang
Di dalam pesta itu, orang-orang selain Hamada menyantap makanan paha ayam goreng dengan minuman bir dan sake. Narator mahatau kemudian menceritakan Hamada yang mempertanyakan apakah makanan berupa paha ayam goreng yang sedang ia makan itu sungguh tepat disebut sebagai makanan Jepang, dan mengapa jika itu makanan Jepang, dianggap cocok dinikmati bersama bir (juga minuman Barat) sedangkan paha ayam goreng dan wiski dianggap tidak cocok. Menyebut masakan (paha ayam goreng) yang diperkenalkan oleh Barat sebagai masakan Jepang menimbulkan pertanyaan bagaimana sebuah produk budaya asing kemudian dianggap sebagai masakan Jepang dan diperlakukan sebagai representasi budaya Jepang.
Bangsa Jepang dalam sejarahnya, sempat mengenal daging sebagai makanan untuk dikonsumsi sejak bangsa Portugis masuk ke Jepang pada abad ke-16. Pengaruh agama Budha yang kuat secara politik dan budaya, membuat konsumsi daging hewan merupakan hal yang dilarang. Akan tetapi, sejak Era Restorasi Meiji (1868 – 1912) masa di mana Jepang secara terbuka menerapkan
peradaban Barat, masyarakat Jepang yang mengkonsumsi makanan Barat mulai banyak ditemui (Cwiertka, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa sebuah makanan tidak dapat sepenuhnya dapat diklaim sebagai makanan yang asli dibuat oleh suatu bangsa jika kita menelusuri kembali asal muasalnya.
Mintz (2007) berpendapat bahwa kita perlu membedakan antara inovasi dari makanan yang dikirim (masuk) dengan inovasi dari makanan yang diterima oleh orang lokal. Makanan kemudian mengalami proses reproduksi, yang mulanya berasal dari budaya asing, dalam proses sejarahnya kemudian lambat laun menjadi dianggap sebagai bagian dari kuliner budaya setempat. Jika melihatnya dari kacamata esensialis, masakan paha ayam goreng tidak dapat dikategorikan sebagai masakan Jepang asli karena awal mulanya berasal dari masakan Barat, yakni Portugis. Klaim keaslian dengan sendirinya runtuh jika asal mula makanan ditinjau kembali.
Di dalam konteks sosial tahun 1965 (tahun ketika novel ditulis), masakan paha ayam goreng disantap dengan minuman sake dan bir. Pernyataan Kabag Keuangan kepada Hamada dengan nada suara mengejek, 「日本料理とウィスキ ーじゃ、合わんだろう」 ‘Masakan Jepang dengan Wiski itu perpaduan yang tidak cocok, kan?’ menunjukkan bagaimana masakan yang menjadi representasi identitas Jepang (paha ayam goreng) ditandingkan dengan minuman Wiski yang merupakan representasi dari identitas Barat. Hamada memilih wiski, bukan karena faktor kualitas “wiski impor”, tetapi sebagai cara untuk menyuarakan posisinya di dalam wacana makanan yang lepas dari posisi biner: makanan/minuman Jepang vs makanan/minuman bukan Jepang (Barat). Kabag Pengajaran yang mengatakan「日 本料理とウィスキーじゃ、合わんだ ろう」(Maruya: 124) “Makanan Jepang
dan Wiski itu perpaduan yang tidak cocok, kan?” dapat dibaca di dalam pemaknaan oposisi biner terkait rasa, yakni pemaknaan makanan Jepang di mana hal yang terkait Jepang memiliki posisi superior dibanding wiski sehingga wiski tidak akan cocok dengan masakan Jepang.
Makanan Jepang yang disebut oleh Kabag Keuangan tersebut merujuk pada washoku, yakni makanan Jepang yang didaftarkan di UNESCO dan dijelaskan sebagai makanan Jepang dengan tradisi yang terjaga keasliannya. Menurut Cwiertka dan Yasuhara (di dalam Farina, 2021), perumusan washoku yang meliputi bahan-bahannya, cara membuat, menyajikan, dan mengonsumsinya, merupakan penafsiran yang dipaksakan, dan bahkan sebuah upaya memanipulasi untuk membangun rumusan khusus mengenai apa yang disebut tradisi kuliner Jepang. Kata washoku sendiri merupakan sebuah kata yang baru diciptakan di zaman Meiji (1868-1912) dan memiliki arti “makanan Jepang” atau yang di dalam literatur berbahasa Inggris disebut “Japanese food.” Penciptaan tersebut sebagai upaya untuk menandingi keberadaan makanan yang diperkenalkan oleh negara-negara Barat yang dinamakan yōshoku (Farina, 2021).
Seiring dengan gencarnya budaya Barat yang masuk pada masa Meiji (1868-1912), pandangan mengenai mengonsumsi daging dengan superioritas ras kulit putih perlahan-lahan mulai mempengaruhi persepsi terhadap masakan Barat. Pada akhirnya, pemerintah kekaisaran menetapkan daging sebagai konsumsi utama tentara dan juga rakyat umum untuk menciptakan bangsa dan tentara yang kuat dan sehat (Cwiertka, 2004).
Dari penjelasan tersebut, kita dapat melihat bagaimana makanan dikonstruksi sebagai diskursus identitas nasional yang melibatkan relasi kuasa. Melalui peraturan-peraturan, negara merumuskan
makanan/minuman apa yang baik dan benar, yang mana yang disebut sebagai “elemen Jepang” sebagai panduan untuk rakyatnya. Negara juga mengeluarkan larangan-larangan untuk membatasi “yang bukan Jepang” untuk tidak memiliki panggung di tengah diskursus kejepangan yang terus dikonstruksikan.
Selain sake, hal yang perlu menjadi perhatian di dalam dialog tersebut adalah bir (data 2). Bir menjadi minuman alternatif selain sake dan teh hijau untuk mendampingi sajian makanan Jepang. Berbeda dengan sake yang memiliki mitos dan sejarah panjang sebagai minuman yang diciptakan oleh orang Jepang di Jepang, bir diperkenalkan oleh Barat.
Sejarah hadirnya bir di Jepang dimulai ketika sebuah perusahaan Belanda memproduksi bir untuk kalangan mereka sendiri di kota Nagasaki selama periode Edo (1603-1868). Setelah kepemilikian diambil-alih oleh orang Jepang, pada tahun 1888, produksi pertama dengan nama bir Jepang mulai dipasarkan (Kirin Biiru KK ed., 1984). Sejak itu, bir menjadi minuman yang disukai di Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa, bir direkayasa sebagai minuman Jepang. Bir dikonstruksi sebagai minuman yang cocok untuk mendampingi makanan Jepang. Bir di Jepang diperkenalkan oleh bangsa Belanda yang di dalam sejarah, merupakan mitra dagang dan tidak pernah terlibat di dalam perang.
Melalui kuasa, pemimpin pemerintahan mengonstruksikan sebuah mitos mengenai sake yang menjadi sebuah pengetahuan yang diterima rakyat. Mitos sake menjadi kebenaran untuk mengonstruksikan beras Jepang (bahan dasar sake) dan sake sebagai elemen yang harus dipelihara untuk memposisikan Jepang dalam identitas yang kuat menghadapi beras atau minuman yang “liyan”. Makanan asing diterima tidak semata-mata karena pertimbangan
kesehatan, tetapi didomestifikasi untuk diklaim sebagai masakan Jepang.
Dari penjelasan sisi sejarah tersebut, dapat dilihat bagaimana klaim “identitas Jepang” adalah merupakan proses
konstruksi yang melibatkan relasi kuasa, melalui peran pemerintah dalam
menyeragamkan asumsi mengenai
“masakan dan minuman Jepang”, yang bukan produk Barat. Cwiertka (2004) menjelaskan, di dalam proses penerimaan budaya Barat selama Restorasi Meiji (1868-1912), negara secara tegas menyeragamkan rasa dan membangun apa yang kemudian disebut sebagai “masakan nasional dan modern Jepang.” Pendomestifikasian makanan asing
dengan diklaim sebagai makanan Jepang, menunjukkan cara bagaimana relasi kuasa/pengetahuan beroperasi, yakni menghilangkan identitas awal dan atribut budaya yang menyertainya untuk kemudian dikonstruksi sebagai identitas baru yang lepas dari pemaknaan sebelumnya.
Makan dan Minum sebagai Disiplin
Bagaimana sake menjadi
representasi dari identitas yang diusung oleh orang-orang di sekitar Hamada dan yang ditolak oleh Hamada, kembali terlihat di dalam percakapan berikut. Hamada meneguk habis wiski di gelasnya dan memberi syarat menolak sake dari Nishi dengan menempatkan tangannya menutupi gelas. Melihat adegan itu, Kabag Keuangan yang sebelumnya berkomentar terhadap pilihan Hamada dengan mengatakan ‘masakan Jepang tidak cocok berpadu dengan wiski’, kembali berkata:
Data 6
「この人はジャパン・スピリットは 駄目なんだよ」
“(Kalau) Orang yang satu ini, Jiwa Jepang memang tidak cocok dengannya!” (Maruya, 2014. Hal 127)
Pernyataan Kabag Keuangan, “(Kalau) orang yang satu ini, Jiwa Jepang memang tidak cocok dengannya!” menunjukkan bagaimana minuman sake menjadi representasi dari Yamato damashii ‘Jiwa Jepang’. Jiwa Jepang merupakan ideologi yang meliputi elemen etnisitas, budaya, dan nasionalisme yang mendapat legitimiasi di dalam ajaran Shinto. Ideologi ini menjadi alat pemersatu untuk menggalang semangat berperang melawan Cina, Korea, dan Barat dan menduduki Asia (Dower (1993).
Nasionalisme Jepang merupakan hasil dari bersatunya politik dengan agama yang dibangun melalui ‘ideologi negara’ (kokutai) dan ‘Jiwa Jepang’ (Yamato damashii). Yamato damashii ‘Japanese Spirit’, di masa perang membentuk nasionalisme yang menekankan peradaban yang mengungguli bangsa lain. Identitas orang Jepang diklaim ditandai dengan pemikiran, pola perilaku, dan produk budaya yang memiliki karakter unik, yakni Yamato damashii ‘Jiwa Jepang’ yang diklaim tidak dimiliki bangsa lain (Saaler, 2016).
Di kalangan esensialis, Yamato damashii menjadi ekspresi dari identitas budaya Jepang yang dimiliki oleh orang dengan ras Jepang. Jiwa Jepang di dalam dialog tersebut diperlakukan sekaligus menjadi ekspresi dari identitas personal. Dalam pemikiran esensialis, identitas personal dibentuk oleh identitas dominan, yakni kelompok di mana seseorang tinggal. Dalam hal ini, Hamada yang merupakan ras Jepang, oleh orang-orang di sekitarnya di tengah pesta tersebut, diharapkan merepresentasikan identitas dominan, yakni etnis Jepang sehingga ia dianggap semestinya dapat cocok dengan Yamato damashii ‘Jiwa Jepang’. Dari sini tampak bahwa ideologi Yamato damashii yang dibentuk di masa perang, tetap beroperasi melalui diskursus di masa pascaperang dan Jepang telah
menjadi negara yang menjunjung demokrasi.
Akan tetapi, Hamada menolak mengusung identitas kolektif tersebut sehingga ia dianggap sebagai orang yang tidak cocok dengan Jiwa Jepang. Ia bahkan sengaja meneguk habis wiski di gelasnya dan meski gelas telah kosong, ia tidak berniat untuk menerima sake. Sebenarnya, ia dengan mudah dapat menolak sake dengan alasan ia masih memiliki wiski di dalam gelasnya. Akan tetapi, secara demonstratif, ia menolak sake yang ditawarkan padanya dengan menutup mulut gelas dengan tangannya.
Foucault (1984) menjelaskan bahwa dalam hubungannya dengan orang lain, ada terlibat kekuasaan. Ia menjelaskan bahwa aktivitas makan melibatkan relasi dengan orang lain. Menurutnya, makan merupakan perwujudan etika moral bila kita merasa terikat dengan aturan makan yang disepakati masyarakat tempat kita berada. Dengan moral yang kita usung, kita akan merasa bersalah ketika melanggar aturan tersebut. Aturan makan merupakan wujud kekuasaan yang hadir dalam bentuk disiplin (disciplinary power). Tindakan Hamada tersebut dapat disebut sebagai tindakan yang bukan tipikal orang Jepang karena ia merusak harmoni (wa) dari relasi sosial yang terbangun di dalam komunikasi. Mengutip pendapat Foucault, aktivitas makan yang dilakukan oleh Hamada merupakan cara ia menunjukkan ketidaksamaan mengenai moral dengan rekan kerjanya. Ia tidak merasa bersalah, ia malah secara terang-terangan menunjukkan penolakannya bahkan terhadap atasannya.
Di dalam percakapan tersebut
terlihat bagaimana sake menjadi representasi dari Jepang, sedangkan wiski merupakan representasi dari Barat. “Sake adalah kami”, yakni “sake adalah Jepang”, sedangkan “wiski adalah Liyan”, yakni “wiski adalah bukan Jepang”. Hamada dengan sengaja menunjukkan
kesukaannya terhadap hal-hal yang terkait Barat, dengan mengatakan:
Data 6
ええ、西洋かぶれでしてね。これは 舶来ウィスキ―じゃないけれど」
“Ya, (Saya) menyukai hal-hal terkait Barat meskipun ini bukan wiski impor”(Maruya, 2014, 126).
Dari pernyataan Hamada tersebut, terlihat bagaimana Hamada tidak menekankan faktor kualitas (enak atau tidak) dari wiski tersebut. Ia lebih mengutamakan wiski sebagai
representasi dari budaya Barat yang ia usung sehingga ia tidak
mempermasalahkan jika wiski tersebut bukan wiski impor.
Minuman bukan Sake sebagai Liyan/Inferior
Tindakan Hamada yang menolak minum sake dan memilih wiski terjadi kembali dalam adegan berikutnya. Narator mahatahu menceritakan bahwa pesta kemudian semakin ramai karena diisi dengan nyanyian Mars Tentara yang diiringi oleh suara petikan alat musik Samisen. Hamada yang sudah mabuk oleh wiski dapat mendengar suara seorang perempuan yang menawarkan segelas besar sake sambil mengelus lutut Hamada:
Data 7
「お飲みなさいよ、ぐっと。轟沈な の?」…
“Yang kamu butuhkan adalah minuman yang bagus. Cobalah teguk sake ini banyak-banyak. Kau tampak sudah mabuk dan kepayahan.” (Maruya, 2014, hal 132).
Dari ucapan perempuan tersebut dapat terlihat bagaimana pemaknaan dengan oposisi biner kembali dimunculkan, yang mana sake dinilai sebagai minuman yang tidak akan membuat Hamada menjadi
mabuk atau kepayahan. Sebaliknya, minuman wiski dianggap telah membuat Hamada mabuk. Sake dinilai lebih baik daripada wiski sehingga sake ditawarkan untuk diminum untuk mengatasi situasi kepayahan Hamada. Sake berada di posisi superior yang dihadapkan dengan wiski yang inferior yang menyebabkan Hamada mabuk.
Namun, Hamada berkata:
Data 8
「水割りにしてくれよ。おれは大和 魂のほうは駄目なんだ。」
“Tolong berikan aku wiski campur air es. Jiwa Jepang (itu) memang tidak cocok denganku.” (Maruya, 2014, 133)
Di dalam percakapan tersebut, Hamada memposisikan dirinya sebagai orang yang tidak cocok dengan Yamato damashii ‘Jiwa Jepang’.
Michael Carr secara leksikografi meneliti tentang definisi Yamato-damashii di dalam kamus bahasa Jepang modern yang diterbitkan oleh 4 penerbit, Daijisen (Shōgakukan,1986), Daijirin (S anseidō, 1988), Nihongo
Daijiten (Kōdansha, 1989),
dan Kōjien (Iwanami, 1991). Ia
menyatakan bahwa penyebutan Yamato damashii merupakan terminologi yang digunakan dalam ideologi ultra-nationalistik yang merumuskan
karakteristik dan mental orang (etnis dan ras) yang ditanamkan sebagai sebuah kesadaran (consciousness) menjadi orang Jepang (Carr, 1994). Hamada menyatakan ia memiliki kesadaran yang menilai Yamato damashii bukan menjadi karakter dan mental yang ia miliki.
Di dalam percakapan tersebut, Hamada mengekspresikan identitas personalnya, yakni apa yang ia suka dan yang ia anggap tepat bagi dirinya melalui pilihan meminum wiski dan menolak sake. Meminjam wacana “rice as self” yang dijelaskan dalam kajian makanan
Jepang oleh antropolog Jepang Ohnuki-Tierney (1993), dapat dikatakan bahwa bagi Hamada wiski merupakan “wisky as self” dan ia menolak wacana “sake as self” yang bagi orang-orang di pesta yang minum sake merupakan representasi dari Jiwa Jepang.
Di sini terlihat bagaimana Yamato damashii ‘Jiwa Jepang’ saling
dikontestasikan dengan Barat yang direpresentasikan melalui masakan paha ayam goreng sebagai masakan Jepang dengan bukan masakan Jepang; dan sake dengan wiski. Melalui tindakan dan pernyataan Hamada, pembaca diajak berpikir kembali mengenai klaim keunikan dan keaslian, bahwa klaim tersebut di dalam sejarah melibatkan relasi kuasa dengan cara melalui wacana dan pendomestifikasian. Sake menjadi identitas esensialis dari apa yang disebut sebagai Yamato damashii ‘Jiwa Jepang’. Di dalam peristiwa tersebut, Hamada menjadi “yang Lain” di tengah keberadaan orang-orang yang semuanya mengusung identitas kejepangan.
Menurut Foucault (1984), makan menjadi bentuk disiplin apabila kita ditanamkan dengan kebiasaan makan tertentu atau dibentuk secara jasmani untuk makan dengan cara tertentu. Karena sudah menjadi kebiasaan, etiket atau cara makan dengan aturan yang sudah ditanamkan akan sulit untuk dihindari karena makanan menjadi sarana untuk terhubung secara tubuh, emosi, dan diri. Cara makan yang ditentukan merupakan bentuk kekuasaan beroperasi. Namun, sebaliknya Hamada, ia menolak bentuk pendisiplinan tersebut dengan menolak unsur-unsur makanan yang semestinya sebagai orang Jepang dengan budaya Jepang, tidak ia campurkan.
Beberapa contoh data yang telah dijelaskan menunjukkan bagaimana Hamada mengedepankan identitas
personal yang ia pilih. Ia menolak mengusung identitas kejepangan dan menjadi berbeda dengan orang lain di
tempat kerjanya. Atasan hingga rekan kerjanya, menunjukkan pilihan makanan dan cara menyantapnya sebagai cara mereka merepresentasikan identitas kejepangan yang oleh atasan Hamada disebut Yamato damashii ‘Jiwa Jepang’.
Di akhir novel, Hamada dipindahkan dari universitas tempat ia bekerja di Tokyo ke sekolah di daerah kecil. Namun, Hamada menolak dan memilih keluar dari universitas dan menyadari bahwa ia merupakan ryushuu no hazukashime wo uketa hito ‘orang yang mendapat sanksi sosial dari masyarakat’ (Maruya, hal 241). Ia diperlakukan sebagai liyan karena berbeda dengan orang Jepang lain yang mengusung identitas kejepangan Yamato damashii ‘Jiwa Jepang’.
SIMPULAN
Makanan Jepang di dalam percakapan antara tokoh utama Hamada dan orang-orang di lingkungan kerjanya, menjadi media tentang identitas budaya dan bangsa dikontestasikan, diperbandingkan, dan sekaligus dinilai keunggulannya terhadap yang lain. Makanan Jepang diciptakan, dikonsumsi, diyakini, dan diproduksi ulang sebagai cara untuk menunjukkan identitas sebagai orang Jepang yang memiliki Yamato damashii atau Japan Spiritto ‘Jiwa Jepang’. Makanan dan minuman Jepang menjadi pihak yang superior, sedangkan pihak yang berbeda, yang bukan dari Jepang, yakni Barat dipandang sebagai pihak yang inferior atau the Other ‘liyan’.
Maruya melalui Hamada juga mempersoalkan diskursus tentang “keaslian” dari produk budaya Jepang yang di dalam dialog dihadirkan melalui masakan paha ayam goreng. Masakan paha ayam goreng mulanya adalah masakan Barat yang kemudian diklaim sebagai “masakan Jepang” (nihon ryōri).
Berbeda dengan nasi dan minuman sake yang memiliki sejarah panjang hingga menjadi bagian dari mitologi terbentuknya bangsa Jepang, masakan paha ayam goreng belum memiliki sejarah yang panjang untuk disebut sebagai masakan Jepang dan tidak memiliki makna suci.
Melalui reintegrasi dan reproduksi, paha ayam goreng yang awalnya milik asing, dilepas dari identitas awalnya untuk menjadi masakan yang disebut masakan Jepang. Hal ini juga menunjukkan bagaimana relasi kuasa beroperasi dengan menghilangkan identitas awal hingga bahkan menjadi tidak dikenali asal muasalnya.
Tindakan Hamada yang menolak memadukan makanan dengan minuman dan menolak cara makan sesuai aturan dalam tradisi Jepang, dapat disimpulkan sebagai cara Hamada membongkar kekuasaan yang beroperasi dalam bentuk disiplin mengenai aturan makan. Hal tersebut juga dapat dibaca sebagai cara Hamada menolak identitas kejepangan melalui representasi makanan/minuman.
UCAPAN TERIMA KASIH
Publikasi penelitian ini didukung dengan pembiayaan dari skema DPP/SPP.
DAFTAR PUSTAKA
Aoyama, T. (2008). Reading Food in
Modern Japanese Literature.
Hawai’i: University of Hawai’I Press.
Carr, M. (1994). Yamato-
Damashii "Japanese Spirit"
Definitions. International Journal of Lexicography, 7(4):279-306.
doi:10.1093/ijl/7.4.279
Cwiertka. K. J. (2004). Western Food and the making of the Japanese nation-state. The Politics of Food, ed. Marianne Lien and Brigitte Nerlich, 121-149. Oxford: Berg.
Cwiertka, K. J. & Ewa Machotka (eds).
(2018). Consuming Life in
PostBubble Japan: A
Transdisciplinary Perspective.
Amsterdam: Amsterdam University Press. Diakses dari doi:
10.5117/9789462980631/ch04
Farina, F. (2021). The politics of washoku: Japan’s
gastronationalism and
gastrodiplomacy. Food issues 食事. Interdisciplinary Studies on Food in Modern and Contemporary East Asia, pp. 93-107. Firenze
University Press. DOI
10.36253/978-88-5518-506-6.09
Foucault, M. (1984). On the Genealogy of Ethics: An Overview of Work in Progress. In The Foucault Reader: An Introduction to Foucaultʼs Thought, Paul Rabinow (ed.).
London: Penguin.
Hall, S. (1991). The Local and the Global: Globalization and Ethnicity. A. D. King (ed.). Culture Globalization and the WorldSystem: Contemporary Conditions for the Representation of Identity. London: Macmillan, 19-40.
Hall, S. (1996). Questions of Cultural Identity. Sage Publications.
Hardiman, F. B. (2016). Membongkar Rezim Kepastian. Yogyakarta: PT Kanisius.
Hirano, K. (1997). Sasamakura. Gunzō Nihon no Sakka 25 Maruya Saiichi. Tokyo: Shōgakukan.
Hobsbawm, E. J., & Ranger, T.O. (1983). The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
Keene, D. (2002). Grass for My Pillow. Ney York: Columbia University Press.
Kirin Biiru KK ed. (1984). Biiru to Nihonjin [Beer and the Japanese]. Tokyo: Sanseidō.
Koda, Y. (2005). The Russo-Japanese War—Primary Causes of Japanese Success. Naval War College Review: Vol. 58: No. 2, Article 3.
Available at: https://digital-
commons.usnwc.edu/nwc-review/vol58/iss2/3.
Lubis, A. Y. (2012). Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial-Budaya Kontemporer.
Depok: Departemen Filsafat FIB UI.
Ministry of Agriculture, Forestry, and Fisheries (MAFF). (2020). Your Guide to Japanese Cuisine, Sake, and Food Culture.
https://www.maff.go.jp/e/data/publi sh/attach/pdf/index-25.pdf
Maghfira, C., & Purba, E. (2023).
Wacana Gender dan Relasi Kuasa dalam Cerpen Kuzuha No Issei Karya Matsuda Aoko. Humanis, 27(2), 110-123.
doi:10.24843/JH.2023.v27.i02.p01
Maruya, S. (2014). Sasamakura [Grass for My Pillow]. Cetakan ke-19. Tokyo: Shinchosha.
Mintz, S.W. (2007). Asiaʼs contributions to World Cuisine: A Beginning inquiry. Di dalam Food and Foodways in Asia: Resouces, tradition, and cooking, ed. Sidney C.H. Cheung and Tan Chee-Beng. London and New York: Routledge, 201-210.
Ohnuki-Tierney, E. (1993). Rice as Self: Japanese Identities through Time. Princeton: Princeton University
Press
Purba, E.R. (2016). Tiada tempat bagi kebebasan individu dalam novel Sasamakura karya Saiichi Maruya. Prosiding Seminar Sosiologi Sastra, UI Depok: 10-11 Oktober 2016.
http://susastrafib.wphost2.ui.ac.id/ wp-content/uploads/81/2017/01/16
Ramadhani, A.F. & Purba, E.R. (2021). War in Ippeisotsu by Katai Tayama. 107-119. VOl 6 No 2. JAPANEDU: Jurnal Pendidikan
dan Pengajaran Bahasa Jepang. https://doi.org/10.17509/japanedu.v 6i2.39022
Saaler, S. (2016). Nationalism and history in contemporary Japan. The Asia-Pasific Journal, 14(7).
Diakses dari
https://apjjf.org/2016/20/Saaler.htm l
UNESCO. 2013. “Nomination file no. 00869, For inscription in 2013 on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity”. Washoku, traditional dietary cultures of the Japanese, notably for the celebration of New Year - intangible heritage - Culture Sector - UNESCO.
Wake, Shinya. (2023). Japan sinks to low of 125th in global gender gap ranking. The Asahi Shinbun, 21
Juni 2023.
https://www.asahi.com/ajw/articles/ 14937882
Woodward, K. (1997). Identity and Difference. SAGE Publications.
Zahrah, S., & Purba, E. (2022).
Cinderella Weight: Tirani Standar Kecantikan dan Body Image di Kalangan Wanita Muda
Jepang. Humanis, 26(4), 400-412. doi:10.24843/JH.2022.v26.i04.p09
Discussion and feedback