Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan dan Prospek Pengaturannya dalam Ius Constituendum
on
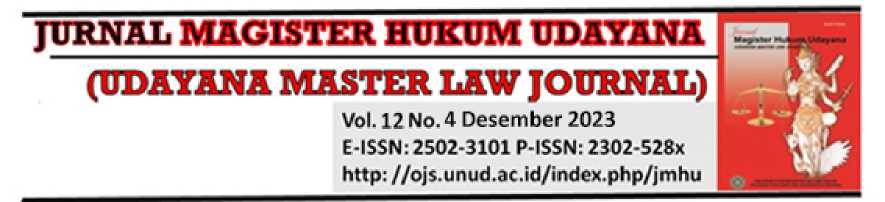
Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan dan Prospek Pengaturannya dalam Ius Constituendum
Mailinda Eka Yuniza1, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita2, Ni Putu Maetha Maharani3
1Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, E-mail: mailinda@ugm.ac.id.
2Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, E-mail: ni.nengah.dhea.riska@mail.ugm.ac.id
3Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, E-mail: maethamaharani@mail.ugm.ac.id
Info Artikel
Masuk: 28 Oktober 2022
Diterima: 27 Desember 2023
Terbit: 30 Desember 2023
Keywords:
Source of Authority;
Attribution; Delegation;
Mandate; Job Creation Law
Kata kunci:
Sumber Kewenangan; Atribusi;
Delegasi; Mandat; Undang-
Undang Cipta Kerja
Corresponding Author:
Mailinda Eka Yuniza, E-mail:
DOI:
10.24843/JMHU.2023.v12.i0
4.p7.
Abstract
ISSN: 1978-1520
-
I. Pendahuluan
Konsekuensi dari bentuk negara hukum salah satunya ialah penyelenggaraan pemerintah yang harus didasarkan atas kewenangan yang sah. Sumber kewenangan pemerintah ini haruslah diatur dalam peraturan perundang-undangan guna memenuhi aspek legalitasnya. Pada tataran hukum positif di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sumber kewenangan pemerintah ialah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Adpem) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Isi dari UU Adpem sendiri menjelaskan bahwa terdapat tiga sumber kewenangan pemerintah, yakni atribusi, delegasi, dan mandat.
Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Adpem, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Sementara, dalam Pasal 1 angka 23 UU Adpem memberikan definisi delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. Kemudian pada Pasal 1 angka 24 UU Adpem diatur bahwa mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
Kendati pengaturan mengenai sumber kewenangan telah diatur secara letterlijk dalam peraturan perundang-undangannya, dalam pelaksanaannya pengaturan mengenai ketiganya penuh dengan kerancuan. Hal ini dibuktikan dengan adanya gugatan kepada pemerintah terkait dengan ketidakjelasan sumber kewenangannya dalam bertindak. Misalnya, pengaturan atribusi dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 UU Adpem, sebagaimana telah dijelaskan di atas telah terdapat limitasi bahwa kewenangan yang diberikan harus diturunkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang. Hal tersebut berarti bahwa tidak boleh ada atribusi yang dilakukan selain melalui UUD dan UU. Pada sisi lainnya, Indonesia memiliki 88 Lembaga Non Struktural (LNS) atau yang sering disebut sebagai State Auxiliary Organs yang terdiri dari 39 LNS yang dibentuk melalui Undang-Undang, 8 LNS dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah, dan 41 LNS dibentuk melalui Keputusan Presiden.1 Jika merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (2) UU Adpem, maka kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah merupakan kewenangan delegasi. Secara letterlijk, UU Adpem tidak mengatur mengenai kewenangan yang diberikan oleh Keputusan Presiden, apakah masuk ke dalam perolehan kewenangan secara atribusi atau delegasi. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagaimana dengan kewenangan LNS yang diperoleh dari Keputusan Presiden. Mungkinkah hal tersebut menjadikan LNS terkait tidak memiliki kewenangan
secara atribusi maupun delegasi. Padahal, secara kelembagaan LNS tersebut berkontribusi besar dalam pelayanan kebutuhan publik dan juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Pada dasarnya, pengaturan tentang atribusi, delegasi, dan mandat mengandung gap, yakni ketidakjelasan posisi wewenang yang diberikan selain yang dimuat dalam UUD, UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan/atau Peraturan Daerah. Hal ini misalnya terjadi pada pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang ditandatangani oleh Kepala KPP menggunakan “atas nama Direktur Jenderal Pajak”, sementara ada Peraturan Dirjen / KepDirjen Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 terkait pelimpahan wewenang kepada Kepala KPP untuk menandatangani SKPKB tersebut. Pada kasus tersebut, wewenang yang diberikan kepada Kepala KPP tidak dapat dikatakan sebagai atribusi ataupun delegasi karena produk pelimpahan wewenangnya hanya sebatas PerDirjen/KepDirjen. Namun, jika ingin dikatakan mandat juga belum tentu karena Kepala KPP bukan merupakan pelaksana harian (plh) maupun pelaksana tugas (plt) dari Direktur Jenderal Pajak.
Telah terdapat berbagai penelitian mengenai sumber kewenangan. Pertama, penelitian oleh Marwan dan Julianthy yang berjudul “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.2 Penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2018 dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip otonomi daerah, pemerintahan daerah mempunyai hak untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan di daerah, yakni urusan pemerintahan konkuren. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut harus diatur dengan peraturan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. Marwan dan Julianthy mengajukan saran agar pengaturan mengenai pelaksanaan kewenangan atribusi seharusnya diatur dengan Peraturan Daerah karena materi muatan Peraturan Daerah salah satunya adalah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Penelitian tersebut memiliki sudut pandang yang hampir sama dengan penelitian ini, yakni menilai limitasi produk hukum pemberian kewenangan secara atribusi dan delegasi merupakan suatu persoalan. Di sisi lain, penelitian oleh Marwan dan Julianthy memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena penelitian oleh Marwan dan Julianthy hanya fokus pada perolehan kewenangan bagi pemerintah daerah, sementara penelitian ini akan membahas lebih komprehensif mengenai sumber perolehan kewenangan seluruh lembaga negara, tidak hanya terbatas pada pemerintah di tingkat daerah.
Penelitian lain mengenai sumber kewenangan ialah penelitian oleh Susanto yang berjudul “Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan”.3 Penelitian tersebut dipublikasikan pada tahun 2020 dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa wewenang atribusi merupakan wewenang yang langsung diberikan atau ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan saat pembentukan badan pemerintahan. Wewenang delegasi merupakan bentuk pelimpahan wewenang setelah wewenang atribusi dibentuk atau ditetapkan. Wewenang mandat merupakan bentuk penugasan (dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan) dan bukan sebagai pelimpahan. Penelitian oleh Susanto
tersebut dilakukan sebelum UU Cipta Kerja diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Selain itu, penelitian oleh Susanto menyatakan bahwa wewenang atribusi merupakan wewenang yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, sementara dalam penelitian ini akan dibahas secara lebih tegas bahwa menurut ius constitutum, kewenangan atribusi hanya diatur dalam UUD dan/atau UU. Pada penelitian ini justru limitasi produk hukum yang mengatur pemberian kewenangan yang akan menjadi topik utama pembahasan.
Berbagai penelitian tentang sumber kewenangan telah dipublikasikan sebelum perubahan UU Adpem dilakukan dalam UU Cipta Kerja yang terakhir diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Telah lama, persoalan sumber kewenangan ini kurang mendapat perhatian yang khusus padahal persoalan sumber kewenangan merupakan hal yang urgent untuk dibahas. Ketika suatu Keputusan Tata Usaha Negara dikeluarkan atau tindakan pemerintahan dilakukan tanpa sumber kewenangan yang sah maka hal tersebut menjadi bentuk penyalahgunaan wewenang, tepatnya bertindak sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UU Adpem. Jika terjadi penyalahgunaan wewenang berupa bertindak sewenang-wenang, maka KTUN dan/atau tindakan yang dikeluarkan tanpa dasar kewenangan dinyatakan tidak sah oleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, berbagai kerancuan dan permasalahan tentang sumber kewenangan harus mendapat perhatian khusus. Dengan beberapa kali perubahan undang-undang tentang administrasi pemerintahan, ketentuan tentang sumber kewenangan ini sama sekali tidak dibahas dan disempurnakan dalam perubahan UU Adpem sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Penelitian ini mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana hukum positif (ius constitutum) mengatur tentang sumber kewenangan dan berbagai permasalahan mengenai sumber kewenangan pemerintah di Indonesia, serta bagaimana pengaturan yang ideal terkait sumber kewenangan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwasanya dalam ius constitutum, pengaturan tentang sumber kewenangan masih belum sempurna dan memerlukan perbaikan untuk menyelesaikan berbagai gap yang terjadi dalam praktik pemerintahan. Pada penelitian ini juga akan diusulkan pengaturan yang ideal mengenai ketentuan tentang sumber kewenangan pemerintah yang dapat diadopsi atau dijadikan rujukan oleh para pembentuk undang-undang dalam rangka melakukan perubahan peraturan tentang administrasi pemerintahan.
Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yakni penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep.4 Peneliti akan menguraikan tentang konsep dasar kewenangan pemerintah kemudian dihubungkan dengan ius constitutum untuk menemukan legal gap nya sehingga
dapat diperbaiki dalam ius constituendum. Penelitian ini menggunakan pendekatan: statute approach, conceptual approach dan analytical approach. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan, analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, dan tidak tumpang tindih, efektif serta sistematis dengan harapan memudahkan pembaca dalam melakukan interpretasi dan pemahaman hasil analisis.5
Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana Peneliti biasanya sudah mempunyai gambaran awal tentang permasalahan yang diteliti.6 Pada penelitian ini, Peneliti sudah memiliki gambaran awal tentang praktik pelaksanaan peraturan soal sumber kewenangan yang kerap kali menimbulkan kerancuan. Oleh karena itu, dengan melakukan komparasi terhadap ketentuan berbagai peraturan perundang-undangan, konsep dasar sumber kewenangan, dan ketentuan tentang sumber kewenangan dari beberapa negara, Peneliti bermaksud untuk membantu merumuskan ketentuan tentang sumber kewenangan dalam ius constituendum.
-
3. Hasil dan Pembahasan
-
3.1. Ius Constitutum dan Permasalahan Mengenai Sumber Kewenangan Pemerintah di Indonesia
-
Kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum administrasi negara, bahkan menurut Stroink dan Steenbek, kewenangan merupakan konsep inti dalam hukum administrasi negara itu.7 Lebih lanjut, wewenang pemerintahan merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu untuk menimbulkan dan menghapuskan suatu akibat hukum yang terwujud dalam suatu hak dan kewajiban pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.8
Menurut Ridwan, pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, sehingga tersirat bahwa kewenangan pemerintah dalam negara hukum hendaknya berasal dari peraturan perundang-undangan.9 Indonesia sebagai negara hukum sejatinya telah mengatur mengenai sumber kewenangan pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sesuai ketentuan Pasal 11 UU Adpem, kewenangan diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan/atau mandat. Atribusi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata ad tribuere yang artinya “memberikan kepada”.10 Kemudian, delegasi juga berasal dari
bahasa latin delegare yang artinya “melimpahkan”.11 Istilah mandat juga berasal dari bahasa latin mandare yang artinya “memerintahkan”.12
Adapun sumber-sumber kewenangan pemerintah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
TABEL 1
TABEL KOMPARASI SUMBER KEWENANGAN
|
No |
Aspek |
Atribusi |
Delegasi |
Mandat |
|
1. |
Diatur pada |
Pasal 1 angka 22 |
Pasal 1 angka 23 |
Pasal 1 angka 24 |
|
2. |
Definisi |
Pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang |
Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi |
Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. |
|
3. |
Perolehan Wewenang |
wewenangnya baru |
|
|
|
Perpres, atau Perda; dan c. Sifat wewenangnya telah ada sebelumnya |
tugas rutin | |||
|
4. |
Pengalihan Wewenang |
Tidak dapat didelegasikan kecuali diatur dalam UUD NRI 1945 dan/atau UU |
Tidak dapat didelegasikan lebih lanjut, kecuali ditentukan lain |
Pengalihan kewenangan tidak diatur, namun penerima mandat tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan strategis yang berdampak pada perubahan status hukum organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran |
Dari sumber-sumber kewenangan di atas terdapat limitasi-limitasi sebagaimana atribusi merupakan pemberian kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. Sementara itu, delegasi yang hanya dapat ditetapkan melalui PP, Perpres, atau Perda. Hal tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai pemberian kewenangan kepada suatu Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak diatur dalam UUD, UU, PP, Perpres, ataupun Perda apakah kemudian secara mutatis mutandis termasuk mandat. Hal tersebut tidak bisa dijawab dengan mudah karena pemberian kewenangan secara mandat juga diatur secara tegas dalam UU Adpem. Sebagaimana telah digambarkan dalam tabel bahwa kriteria mandat yakni merupakan pelaksanaan tugas rutin. Lebih lanjut UU Adpem menjabarkan Pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas pelaksana harian (plh) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara dan pelaksana tugas (plt) yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
Namun, tidak semua kewenangan dapat memenuhi persyaratan atribusi, delegasi, maupun mandat sebagaimana yang didefinisikan dalam UU Adpem. Kejelasan sumber kewenangan merupakan salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan untuk melihat apakah suatu kewenangan memenuhi persyaratan atribusi, delegasi, atau mandat.
Contohnya, pembuatan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang ditandatangani oleh Kepala KPP menggunakan “atas nama (a.n.)13 Direktur Jenderal Pajak”. Pada kasus a quo, sebelumnya telah ada Peraturan Dirjen / KepDirjen Pajak Nomor KEP-146/PJ/2018 terkait pelimpahan wewenang kepada Kepala KPP untuk menandatangani SKPKB tersebut. Sekilas dilihat mungkin dengan mudah orang menganggap sumber kewenangannya berasal dari mandat karena ada istilah “a.n.” dan karena pelimpahan wewenang tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen / KepDirjen bukan UUD, UU, PP, Perpres, ataupun Perda sehingga tidak memenuhi kriteria atribusi dan delegasi. Namun jika ditelusuri syarat pemberian mandat maka tidak dapat dipahami semudah itu. Berikut analisisnya:
-
1. Bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Mandat apabila: a. ditugaskan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan di atasnya; dan b. merupakan pelaksanaan tugas rutin.
-
2. Bahwa kata “dan” tersebut menunjukkan bahwa kedua syaratnya harus terpenuhi.
-
a. Poin a terpenuhi karena Kepala KPP memang diberi tugas oleh Pejabat yang statusnya lebih tinggi (di atasnya), yakni Direktur Jenderal Pajak.
-
b. Poin b tidak terpenuhi karena Kepala KPP bukan merupakan pelaksana harian (plh) maupun pelaksana tugas (plt) dari Direktur Jenderal Pajak.
Kondisi tersebut menyebabkan keabsahan dari SKPKB diragukan karena sumber kewenangan yang diperoleh pihak yang menandatangani tidak jelas apakah dari atribusi, delegasi, atau mandat. Uraian di atas menunjukkan bahwa kejelasan mengenai sumber kewenangan sangat penting untuk diluruskan karena berimplikasi pada sah atau tidaknya keputusan yang dikeluarkan.
Permasalahannya, apabila pada hukum positif telah dilimitasi bahwa atribusi hanya bisa diberikan oleh UUD atau UU, penting untuk menilik keabsahan kewenangan-kewenangan baru yang timbul pada peraturan yang diterbitkan tidak dengan UU dan UUD namun hanya dengan PP, Keppres atau Keputusan Kepala Daerah seperti Gubernur dan Bupati agar dapat disebut sebagai atribusi (memenuhi ketentuan atribusi). Pada dasarnya, konsep atribusi yang dilimitasi melalui UUD dan UU merupakan refleksi Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi yang dalam setiap pengambilan keputusan dalam pembentukan produk hukumnya melibatkan rakyat, dalam hal ini diwakili DPR sebagai legislator bertugas yang dapat memberikan approval (mewakili rakyat) dalam pembuatan UU itu sendiri. Beda halnya dengan pembentukan PP dan Perpres yang notabene dibentuk langsung oleh pemerintah dengan mekanisme yang berbeda dengan pembuatan UU. Ketiadaan approval dari rakyat dalam hal ini yang dimaksud adalah DPR, menjadi dasar mengapa atribusi harus didasarkan dengan UUD atau UU karena dianggap merepresentasikan approval rakyat terhadap pemberian kewenangan tersebut.
Kendati telah diatur secara limitatif dan letterlijk dalam hukum positif Indonesia, konsepsi mengenai sumber kewenangan pemerintah tersebut justru bertolak belakang
dengan fakta di lapangan bahwa penerapan sumber kewenangan tersebut tidak berlaku secara absolut dan menimbulkan kerancuan. Pada atribusi, dibatasi secara jelas bahwa pemberian kewenangan harus didasarkan pada UUD atau UU, maka apabila pada UUD atau UU tidak terdapat klausa pasal yang secara letterlijk memberikan penunjukan pemberian kewenangan kepada pejabat atau badan pemerintahan untuk melakukan Tindakan pemerintah, maka sejatinya tidak ada atribusi dan kewenangan yang sah di dalamnya.
Namun pada faktanya hanya 39 dari 88 Lembaga Non Struktural (LNS) atau yang sering disebut sebagai State Auxiliary Organs yang didirikan dengan Undang-Undang. Sisanya sejumlah 8 LNS didirikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan 41 lainnya didirikan dengan Keputusan Presiden (Keppres), padahal sejumlah LNS tersebut memiliki kewenangan dan kontribusi besar dalam pelayanan kebutuhan publik dalam menjalankan pengawasan terhadap pemerintahan yang sejatinya secara konkret sudah merupakan bentuk dari atribusi itu sendiri. Selain itu, sejumlah lembaga daerah pun juga dibentuk dengan menggunakan Perda misalnya Majelis Desa Adat di Bali yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Maka secara de facto, pelimpahan kewenangan berupa atribusi sebenarnya dapat berjalan sekalipun peraturan yang menjadi dasarnya bukan UUD maupun UU.
Definisi yang limitatif tidak hanya pada atribusi, namun juga pada delegasi yang menyebutkan kewenangan melalui delegasi harus diturunkan dengan produk hukum berjenis tertentu, yakni PP, Perpres, atau Perda. Namun nyatanya, limitasi ini justru memberikan kondisi kekosongan hukum atau tidak tercovernya kondisi eksisting pada kasus a quo. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa delegasi berasal dari bahasa Latin delegare yang artinya melimpahkan. Konsep wewenang delegasi dengan demikian adalah wewenang pelimpahan.14 Wewenang delegasi harus didahului oleh wewenang atribusi, artinya badan/pejabat pemerintahan dapat melakukan pendelegasian wewenang jika UUD dan/atau UU telah membentuk dan memberi wewenang kepada badan/pejabat pemerintahan tersebut terlebih dahulu. Tanpa ada atribusi maka tidak ada delegasi. Di sisi lain, konsep mandat dengan ketiadaan peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat lebih mengandung makna penugasan, bukan pelimpahan wewenang. Delegasi harus diartikan pelimpahan wewenang, sedangkan mandat diartikan penugasan.15 Hal itulah yang mendasari mengapa pada mandat tidak terdapat peralihan tanggung jawab dan tanggung gugat dari pemberi mandat kepada penerima mandat karena secara konseptual mandat lebih berbentuk penugasan, bukan pelimpahan kewenangan yang utuh.
Jika merujuk pada teori-teori mengenai syarat sahnya KTUN, misalnya Van Der Pot membagi syarat sahnya KTUN menjadi dua golongan yakni syarat materiil dan syarat formil.16 Syarat materiil sahnya KTUN terdiri dari:
-
1. Alat negara yang membuat ketetapan harus berkuasa
-
2. Dalam kehendak alat negara yang membuat ketetapan tidak boleh ada kekurangan
-
3. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu
-
4. Ketetapan harus dapat dilakukan, dan tanpa melanggar peraturan-peraturan lain menurut “isi dan tujuan” sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar ketetapan itu.
Sementara syarat formilnya terdiri dari:
-
1. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan persiapan dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan, harus dipenuhi
-
2. Ketetapan harus diberi bentuk yang ditentukan
-
3. Syarat-syarat yang ditentukan berhubung dengan dilakukan ketetapan harus dipenuhi
-
4. Jangka waktu yang ditentukan antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya ketetapan dan diumumkannya ketetapan itu, tidak boleh dilewati.
Berdasarkan syarat materiil dan formil yang dikemukakan Van Der Pot, Utrecht merangkumnya menjadi 4 syarat sahnya KTUN, yakni:
-
1. Ketetapan harus dibuat oleh alat (organ) yang berkuasa (bevoeghd) membuatnya
-
2. Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring), maka pembentukan kehendak itu tidak boleh memuat kekurangan juridis (geen juridische gebreken in de wilsvorming)
-
3. Ketetapan harus diberi bentuk (vorm) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan cara (prosedure) membuat ketetapan itu, bilamana cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut
-
4. Isi dan tujuan ketetapan harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar
Dalam tataran norma, syarat sah dari suatu keputusan dapat ditemui pada Pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) yang berbunyi:
-
(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
-
a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
-
b. dibuat sesuai prosedur; dan
-
c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
-
(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.
Berdasarkan praktik, pendapat ahli dalam tataran teoritis, dan peraturan perundang-undangan dapat dilihat suatu benang merah bahwasanya syarat sahnya keputusan pastinya harus ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau berkuasa untuk
membuatnya. Oleh karena itu, pelimpahan wewenang merupakan poin yang amat penting untuk menilai keabsahan suatu keputusan.
Mengenai akibat hukum yang dapat terjadi apabila suatu Keputusan tidak memenuhi syarat sah, disampaikan oleh Marbun sebagai berikut:17
-
1. Batal karena hukum
Akan berakibat keputusan yang dibatalkan itu berlaku surut, terhitung mulai saat tanggal dikeluarkannya keputusan yang dibatalkan itu. Keadaan dikembalikan pada keadaan semula sebelum dikeluarkannya keputusan tersebut (extunc) dan akibat hukum yang telah ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada.
-
2. Batal mutlak
Apabila pembatalan terhadap keputusan itu dapat dituntut oleh setiap orang.
-
3. Batal nisbi
Keputusan yang pembatalannya hanya dapat dituntut oleh orang-orang tertentu saja
-
4. Keputusan yang dapat dibatalkan
Keputusan yang hanya baru dapat dinyatakan batal, setelah pembatalan oleh hakim atau instansi yang berwenang membatalkannya dan pembatalannya tidak berlaku surut. Dengan demikian bagi hukum perbuatan dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dianggap pernah ada dan sah, sampai dengan dikeluarkannya putusan pembatalan (exnunc), kecuali jika undang-undang menentukan lain.
-
5. Keputusan yang dapat dibatalkan mutlak
-
6. Keputusan yang dapat dibatalkan nisbi
Sementara itu Hadjon menyampaikan bahwa keputusan yang tidak sah dapat berakibat batal demi hukum, batal, dan dapat dibatalkan, yang selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:18
-
1. Nietigheid van rechtswege (batal karena hukum)
“Nietigheid van rechtswege” artinya bagi hukum akibat suatu perbuatan dianggap tidak ada tanpa perlu adanya suatu keputusan yang membatalkan perbuatan tersebut.
-
2. Nietig (batal)
“Nietig” berarti bahwa bagi hukum perbuatan yang dilakukan dianggap tidak ada. Konsekuensinya, bagi hukum akibat perbuatan itu dianggap tidak pernah ada.
-
3. Vernietigbaar (dapat dibatalkan)
“Vernietigbaar” berarti bagi hukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan lain yang kompeten.
Pasal 19 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian, pada Pasal 19 ayat (2) UU a quo diatur bahwa Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketentuan yang perlu digaris bawahi dari Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) ialah berkaitan dengan keputusan dan/atau tindakan yang melampaui wewenang, sewenang-wenang, maupun yang mencampuradukkan wewenang semuanya harus diuji melalui pengadilan dan telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya terkait tidak sahnya keputusan dan/atau tindakan yang dikarenakan melampaui wewenang, sewenang-wenang, maupun yang mencampuradukkan wewenang akibatnya ialah tidak sah dan dapat dibatalkan. Pernyataan tersebut diperkuat dengan bunyi Pasal 66 ayat (1) UU a quo yang mengatur bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh hakim atau badan lain yang diberikan kewenangan untuk itu.
Pada dasarnya, sah atau tidaknya kewenangan yang dimiliki oleh LNS yang hanya didirikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres), maupun sejumlah lembaga daerah yang hanya didirikan melalui Perda, dimana kewenangannya dilimpahkan secara atribusi tanpa melalui UUD maupun UU menjadi pertanyaan, dan sebagai konsekuensi, Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut turut dipertanyakan keabsahannya. Namun, apabila melihat ketentuan pada UU Adpem, sah atau tidaknya keputusan dan/atau tindakan akibat kewenangan rancu yang dimiliki oleh LNS yang hanya didirikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres), maupun sejumlah lembaga daerah yang hanya didirikan melalui Perda tersebut tidak dapat semata-mata dinilai atau diputuskan. Konsekuensinya, Keputusan dan/atau Tindakannya tidak dapat semata-mata dibatalkan. Perlu putusan pengadilan untuk menguji dan memutuskan keabsahan kewenangan tersebut.
-
3.2. Pengaturan yang Ideal terkait Sumber Kewenangan Pemerintah
H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt menyampaikan pendapatnya tentang apa yang dimaksud dengan atribusi, delegasi, dan mandat, sebagai berikut:
-
a. Atributie: toekenning van een besturesbevoegheid door een wetgever aan een besturursorgaan
-
b. Delegatie: overdracht van een het ene bestuursorgaan aan een ander
-
c. Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid names hem uitoefenen door een ander
Definisi tersebut di atas kemudian diartikan oleh Ridwan HR, yakni atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.19
Sementara, menurut J.G. Brouwer pada atribusi, kewenangan diberikan kepada suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya.20 Pendapat ahli lainnya menyebutkan bahwa Atribusi biasa disebut sebagai Original Legislator. Atribusi menunjuk kepada Kewenangan Asli atas dasar ketentuan Hukum Tata Negara. Atribusi merupakan wewenang untuk membuat Keputusan (Besluit) yang langsung bersumber kepada Undang-Undang dalam arti Materiil.21 Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pembentuk konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden sebagai yang melahirkan undang-undang dan di tingkat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah. Selain itu dalam atribusi terdapat juga istilah delegated legislator, seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.22 Dengan demikian dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (atributaris).
Sedangkan, pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya.23 Pelimpahan ini adalah pelimpahan yang secara eksplisit dinyatakan dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik mengenai adresat yang dituju untuk membentuknya, maupun bentuk instrumen/perangkat hukumnya sekaligus materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.24 Berkenaan
dengan mandat, Stroink dan Steenbeek menyatakan bahwa pada mandat tidak dibicarakan penyerahan wewenang, tidak pula pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun yang ada hanyalah hubungan internal.25 Jadi yang ditekankan disini ialah atribusi merupakan “kewenangan asli” dan bukan merupakan bentuk delegasi dari kewenangan yang ada sebelumnya. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa atribusi tidak didefinisikan secara kaku yakni harus bersumber dari produk hukum tertentu (seperti UUD atau UU). Begitupula dengan delegasi, poin utamanya ialah pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun produk hukum pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya seharusnya dapat diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan uraian di atas, Penulis mencoba merumuskan sebuah kesimpulan dari berbagai uraian teoritis di atas mengenai sumber kewenangan berupa atribusi, delegasi, dan mandat. Tabel berikut akan menjelaskan tentang perbandingan antara pengaturan saat ini (ius constitutum), kajian teoritis, dan usul perubahan dari Penulis yang harapannya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam rangka revisi UU Cipta Kerja.
TABEL 2
TABEL KOMPARASI SUMBER KEWENANGAN ANTARA IUS CONSTITUTUM, KAJIAN TEORITIS DAN USULAN SOLUSI
|
Sumber Kewenangan |
Ius Constitutum |
Kajian Teoritis |
Usulan Perubahan (Solusi) |
|
Atribusi |
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang; b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. |
Kewenangan yang asli dan tidak diambil dari kewenangan mana pun sebelumnya. |
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Atribusi apabila: a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang, dan/atau Peraturan Daerah; dan b. merupakan Wewenang baru atau sebelumnya tidak ada. Bunyi pasal pada huruf c penulis rasa kurang efektif karena |
25 Theresia Ngutra, “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” Jurnal Supremasi XI, no. 2 (2016): 193–210, https://www.jurnalhukum.com.
|
bersifat repetitif. | |||
|
Delegasi |
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
|
Pelimpahan wewenang, maka seharusnya ada kewenangan lain terdahulu yang diambil dan dilimpahkan |
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila: a. diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya melalui Peraturan perundang-undangan.
Dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa yang dimaksud peraturan perundang-undangan mengacu pada ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selain UU dan UUD karena UU dan UUD merupakan produk hukum untuk memberikan kewenangan atribusi. |
Secara umum, limitasi bentuk peraturan perundang-undangan yang diatur dalam UU Adpem lah yang menjadi poin utama permasalahan pengaturan tentang sumber kewenangan. Oleh karena itu, usulan perubahan yang Penulis rumuskan hanya untuk ketentuan tentang atribusi dan delegasi yang sebelumnya dilimitasi produk hukum pemberian wewenangnya, maka dari itu ketentuan mandat tidak menjadi fokus dalam penulis sebab dalam ketentuan UU Adpem mandat tidak dilimitasi produk hukumnya seperti atribusi dan delegasi.
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa kondisi saat ini, produk hukum pemberian wewenang pada atribusi dilimitasi hanya sebatas UUD 1945 dan/atau Undang-Undang. Dalam usulan perubahan, Penulis memperluas limitasi produk hukum yang dapat mengatur atribusi menjadi UUD 1945, Undang-Undang, dan/atau Peraturan Daerah. Selain itu, Penulis menghapus poin c pada ketentuan atribusi karena di awal pasal telah disebutkan bahwa yang memperoleh wewenang melalui atribusi adalah Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, yang pada peraturan eksisting saat ini masih repetitif.
Kemudian, perlu dipertegas bahwa poin perbedaan antara atribusi dan delegasi terletak pada sumber kewenangannya, yakni jika atribusi adalah kewenangan orisinil/baru yang belum pernah diatur di peraturan mana pun sebelumnya. Sementara, delegasi merupakan wewenang hasil pelimpahan atau sebelumnya telah ada dan tidak ada penciptaan wewenang dalam delegasi. Oleh karena itu, dalam hal pemberian wewenang melalui delegasi maka harus dinyatakan sumber kewenangan asalnya. Sehingga, dalam usulan perubahan, Penulis menambahkan poin bahwa perolehan wewenang delegasi harus dinyatakan sumber kewenangan asalnya. Aspek penting inilah yang belum diakomodir pada peraturan eksisting.
Dengan ketentuan baru ini, maka kedepannya diharapkan pembuatan LNS yang mana memberikan kewenangan baru yang sebelumnya belum ada patut patuh menggunakan produk hukum UU karena sifat kewenangannya merupakan atribusi yang memberikan kewenangan baru pada lembaga tersebut dan tidak diturunkan atau dilimpahkan kewenangan dari pejabat mana pun sebelumnya. Sehingga, dengan saran ini akan lebih jelas juga mana yang merupakan atribusi dan delegasi sebab pada ketentuan delegasi mengharuskan juga memberikan keterangan adanya pelimpahan kewenangan dari pejabat tertentu kepada pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan secara jelas.
Kondisi eksisting pengaturan sumber kewenangan di Indonesia yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang masih menghadapi permasalahan-permasalahan pada praktik administrasi pemerintahan. Hal tersebut berpengaruh pada keabsahan kewenangan lembaga pemerintah dalam mengeluarkan keputusan maupun melakukan tindakan. Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan tanpa dasar kewenangan dikategorikan sebagai bentuk bertindak sewenang-wenang yang membawa akibat hukum tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk mencegah dan meminimalisir adanya berbagai keputusan dan tindakan yang dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh putusan pengadilan, maka pengaturan tentang sumber kewenangan perlu disempurnakan. Penyempurnaan tersebut diperlukan agar seluruh kewenangan yang dijalankan oleh pemerintah memiliki sumber yang jelas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan keputusan dan/atau tindakan menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan. Konsep pengaturan sumber kewenangan dalam UU Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sejatinya belum dapat mengakomodir seluruh kewenangan pemerintah sehingga perlu dilakukan redefinisi terhadap atribusi, delegasi dan mandat guna kepastian hukum di masa yang akan datang.
Ucapan terima Kasih (Acknowledgments)
Terima kasih kami ucapkan kepada Unit Riset dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada atas pendanaan yang diberikan dalam penelitian ini, jajaran proof-reader, reviewer dan editorial Jurnal Magister Hukum Udayana yang telah berkontribusi dalam proses publikasi penelitian kami.
Daftar Pustaka
Abdulkadir, Muhammad. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
Adelia, Tita. “State Auxiliary Organs, Dibutuhkan Atau Dibubarkan.” State Auxiliary Organs, Dibutuhkan Atau Dibubarkan? 2015.
Bambang Waluyo. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
E. Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Nejurgeri Padjajaran, 1960.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
_______. Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi - Cetakan ke-9). Jakarta: Rajawali Press, 2016.
Ilmar, Aminuddin. Hukum Tata Pemerintahan. Jakarta: Kencana, 2014.
Marbun, S.F. Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administratif Di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
Philipus M Hadjon. Kebutuhan Akan Hukum Administrasi Umum, Dalam Hukum Administrasi Dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti, 2012.
Setiawan Yudhi dan Boedi Djatmiko Hadiatmodjo. “Cacat Yuridis dalam Prosedur sebagai Alasan Peradilan Tata Usaha Negara”. Jurnal Equality, vol. 13, no. 1 (2008): 1–9.
Marwan, Ali, dan Evlyn Martha Julianthy. “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” Jurnal Legislasi Indonesia, 2019, 1–8. https://doi.org/10.31219/osf.io/utw97.
Ngutra, Theresia. “Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” Jurnal Supremasi XI, no. 2 (2016): 193–210.
Rokhim, Abdul. “Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State).” Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum XIX, no. 36 (2013): 136–48.
Sihotang, Githa Angela, . Pujiyono, and Nabitatus Sa’adah. “Diskresi Dan Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas Dalam Situasi Darurat.” Law Reform 13, no. 1 (2017): 60. https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15951.
Susanto, Sri Nur Hari. “Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan.” Administrative Law and Governance Journal 3, no. 3 (2020): 430–41. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9530.
Syamsuddin, Ahmad Rustan. “Pembuktian Penyalahgunaan Wewenang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa.” Jambura Law Review 2, no. 2 (July 2020): 161–81.
Zaelani. “Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation of Authority The Estabilshment of Legislation Regulation).” Jurnal Legislasi Indonesia 9, no. 1 (2012): 119–34.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
852
Discussion and feedback