Status Hukum Perempuan dalam Keluarga Akibat Perceraian pada Perkawinan Nyerod Di Bali
on
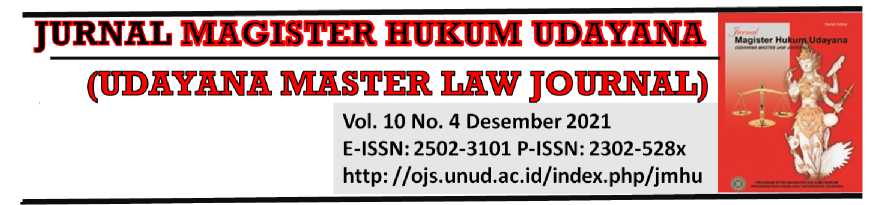
Status Hukum Perempuan dalam Keluarga Akibat Perceraian pada Perkawinan Nyerod Di Bali
Ni Nyoman Sukerti1, I Gusti Ayu Agung Ariani2
1Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: nym_sukerti@unud.ac.id
2Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: agung_ariani@unud.ac.id
Info Artikel
Masuk : 16 September 2021
Diterima : 28 Desember 2021
Terbit : 31 Desember 2021
Keywords :
legal status; woman; late marriage; divorce; Bali
Kata kunci:
Status Hukum; Perenpuan; Kawin Nyerod; Cerai; Bali
Corresponding Author:
Ni Nyoman Sukerti, e-mail : nym_sukerti@unud.ac.id
DOI :
10.24843/JMHU.2021.v10.i04.
p15
Abstract
This study aims to find and analyze the legal status of women who marry into the family in the event of a divorce and society's views on their nationality. This is an empirical legal research with a non-doctrinal approach, which emphasizes field data. The data were collected using interview techniques, the data were processed and analyzed in a qualitative way and the findings were presented in descriptive analytical form.The findings of the study show that women suffer from divorce, have clear and unclear legal status. Obviously, accepted by parents and family, returned as family members. It is not clear because the parents and their families did not accept returning to their original home so that their status was floating (ngambang). It is not clear who will have a very fatal impact in the future in terms of his death, who is responsible, especially according to custom and religion. The public's view of their nationality varies greatly, namely a small proportion is still extreme by considering that they are no longer a tri-wangsa dynasty, but those who are more do not question it. This is reflected in the Balinese language used to communicate, there is no change. Against the extreme conditions where there are still Balinese people who uphold outdated customary values, it is not in line with the State law on Human Rights (women).
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis tentang status hukum perempuan kawin nyerod dalam keluarga dalam hal terjadi perceraian dan pandangan masyarakat terhadap kewangsaannya. Ini penelitian hukum empiris dengan pendekatan non doktrinal, yang menekan pada data lapangan. Data dikumpulkan dengan teknik interview, data diolah dan dinalisis dengan cara kualitatif serta temuannya dipresentasikan dalam bentuk deskriptif analitis.Temuan penelitian menunjukan bahwa perempuan nyerod yang bercerai, status hukumnya ada yang jelas dan tidak jelas. Jelas karena diterima oleh orang tua dan keluarga, kembali sebagai anggota keluarga. Tidak jelas karena kembali ke rumah asal tidak diterima oleh tua dan keluarganya sehingga statusnya menggatung (ngambang). Tidak jelas membawa dampak yang sangat fatal ke depannya dalam hal kematiannya, siapa yang bertanggung jawab terutama secara adat dan agama. Pandangan masyarakat terhadap kewangsaannya, sangat bervariasi yakni sebagian kecil masih bersifat ekstrim dengan menganggap bukan lagi sebagai wangsa tri wangsa, tetapi yang lebih banyak tidak mempermasalahkannya. Hal tersebut tercermin dari bahasa Bali yang dipakai berkomunikasi tidak ada perubahan. Terhadap kondisi yang ekstrim dimana masih adanya warga masyarakat Bali yang menjujung
tinggi nilai-nilai adat yang sudah usang, tidak selaras dengan hukum Negara tentang Hak Asasi Manusia (perempuan).
Perkawinan adalah suatu tahapan atau fase hidup yang dialami oleh hampir setiap insan manusia di dunia tak tercuali di Indonesia umumnya, di Bali khususnya. Masalah perkawinan selalu menarik untuk dikaji karena pada fase ini, hidup manusia mendapat cobaan yang tidak ringan.1 Hal yang dimaksud adalah tentang gagalnya sebuah perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Pada awalnya setiap orang yang melakukan perkawinan, tidak direncanakan akan berakhir dengan perceraian. Membina rumah tangga untuk melanjutkan keturunan dalam keluarga agar tidak mengalami kepunahan (camput, Bali) adalah merupakan tujuan utama dari suatu perkawinan. Gagalnya sebuah perkawinan dapat menimbulkan beberapa akibat. Dalam kepustakaan hukum lumrah disebut dengan istilah putusnya perkawinan. Putusanya perkawinan diatur pada Pasal 38, intinya dapat dikemukakan karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan Pengadilan.2
Perkawinan putus karena kematian dan atas putusan Pengadilan tidak menjadi bagian atau tidak dibahas dalam kajian ini, melainkan hanya akan mengkaji akibat hu kum atas perceraian terkait status perempuan dalam keluarga dan masyarakat yang kawin nyerod (turun wangsa) pada masyarakat Bali. 3 Perkawinan nyerod adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh perempuan tri wangsa (brahmana, ksatriya, dan weisia) dengan laki-laki yang dipandang wangsanya lebih rendah, bisa saja perempuan brahmana dengan laki-laki kesatria, weisia, dan jaba wangsa.4 Dapat juga terjadi antara perempuan ksatriya dengan laki-laki weisia dan jaba wangsa dan antara perempuan weisia dengn laki-laki jaba wangsa. Perlu dijelaskan, di Bali sebenarnya tidak dikenal kasta sebagaimana yang lasim dikalangan masyarakat akan tetapi yang ada adalah warna atau golongan. Bagi sebagian besar orang Bali masih terpatri begitu kuat akan istilah kasta tersebut, sebagai mana dikenal di India. Hal tersebut membuat bingung sebagian orang Bali di jaman kekinian. Kasta dilihat karena fungsinya dari seseorang atau kelompok tertentu. Jadi istilah atau nama yang dikenal di Bali adalah warna, wangsa atau golongan.
Dari semua jenis perkawinan yang dilakukan tersebut, yang paling signifikan mana kala terjadi dalam wangsa yang berbeda, yaitu golongan laki-laki jaba, hal mana dapat menimbulkan kegonccangan dalam masyarakat. Di jaman lampau mana kala terjadi perkawinan seperti itu dapat dikenakan sanksi berupa hukuman mati dengan cara
menenggelamkan di laut pasangan yang kawin tersebut. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Jiwa Atmaja bahwa penurunan kasta bagi mempelai perempuan, hukuman buang ke luar Bali (selong) bagi kedua mempelai, bahkan sampai hukuman labuh gni dan labuh batu.5 Hukuman labuh gni adalah hukuman dengan cara membakar hidup-hidup yang kawin, sementara labuh batu adalah hukuman dengan memberi pemberat batu kepada pasangan mempelai kemudian ditenggelamkan di laut. Di jaman kekinian hal hal itu faktanya tidak ada lagi, akan tetapi secra simbolis masih ada yang mentaatinya. Larangan perkawinan demikian secara yuridis formal tidak berlaku lagi sudah begitu lama dengan Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951. Peneliti sendiri belum lahir, larangan tersebut sudah ada, disinilah letak ironisnya pada masyarakat Bali. Begitu kuat mentaati hokum adat dimasa lampau, membawa dampak pada perempuan yang nyerod terlebih mana kala terjadi perceraian. Akibatnya pada keluarga dan masyarakat pada perempuan yang bersangkutan.
Perkawinan putus akibat perceraian dapat menimbulkan beberapa akibat hukum yakni akibat bekas suami istri, anak-anaknya, dan harta kekayaan yang timbul selama perkawinan berlangsung. Bekas suami dan bekas istri dapat kawin lagi, sementara anak-anaknya yang belum dewasa akan dipelihara oleh ibunya, sedangkan penguasaan terhadap harta perkawinan atau harta Bersama itu tergantung pada kesepakatan bekas suami istri yang bersangkutan. Khusus untuk menguasaan harta perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan sudah diatur secara jelas pada Pasal 37. Pada intinya dapat dijelaskan mana kala terjadi perceraian, maka harta perkawinan tunduk pada hukumnya masing-masing. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Surojo Wignjodipuro, bahwa bekas suami istri tersebut masing-masing dapat kawin lagi.6 Sementara Suriyaman Mustari Pide mengungkapkan bahwa perceraian dapat berakibat dimana si perempuan dapat kawin lagi.7 Terkait penelitian ini difokuskan pada akibat terhadap bekas istri dalam perkawinan nyerod di Bali baik yang berkaitan dengan status dalam keluarga dan juga masalah kewangsaan keluarga dan dalam masyarakat adat.
Terkait dengan perkawinan nyerod, sukerti menguraikan dengan memakai istilah perkawinan beda wangsa yang merupakan budaya hukum masyarakat Bali dari jaman lampau sampai kini, perkawinan mana antara perempuan tri wangsa dengan laki-laki jaba wangsa. Pada perkawinan ini, perempuan tri wangsa dimaknai mempunyai posisi atau derajat yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki jaba wangsa, sehingga laki-laki jaba wangsa patut dijatuhi hukuman yang berat karena dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.8
Perkembangan jaman dan kemajuan tingkat pendidikan nampaknya tidak begitu berpengaruh terhadap budaya hukum masyarakat Bali terkait hal tersebut.
Sehubungan dengan hal itu maka menimbulkan dilema teterhadap status perempuan. Terkait dengan itu maka permasalahannya adalah; 1. Bagaimanakah status hukum perempuan kawin nyerod dalam keluarga dan masyarakat dalam hal terjadinya perceraian? dan, 2. Bagaimana pandangan masyarakat dengan kewangsaan perempuan akibat dari percerian dalam perkawinan nyerod tersebut? Fokus atau secara khusus tujuan dari penelitian ini adalah mencari dan menemukan serta menjelaskan tentang status perempuan yang kawin nyerod dalam keluarga dan masyarakat dalam hal terjadinya perceraian. Di samping itu, juga akan digali pandangan masyarakat adat terhadap kewangsaan perempuan yang kawin nyerod dalam hal terjadinya perceraian.
Penelitian tentang status hukum perempuan dalam keluarga akibat perceraian pada perkawinan nyerod di Bali menggunakan penelitian hukum empiris. Focus penelitian ini, tentang status hukum perempuan nyerod bercerai dalam keluarga. Terkait dengan itu, Mukti Fajar menguraiakan, keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari keadaan social masyarakat dan perilaku manusia dalam Lembaga hukum tersebut.9 Sehubungan dengan itu, sebagai penelitian empiris maka ditekankan data primer. Data dikumpulkan dengan metode wawancara yang dilengkapi dengan interview guide, selanjutnya diolah dengan kualitatif, kemudian temuannya dipresentasikan secara deskriptif analitis.
Secara umum pada hukum perkawinan dikenal beberapa system. Adapun system perkawinan dimaksud yaitu system indogami, system exogami dan system eliutherogami. Di samping dikenal system perkawinan juga dikenal bentuk-bentuk dari perkawinan. Adapun bentuk dari pada perkawinan secara umum perkawinan jujur, semenda dan bebas. Selain system, bentuk ada juga cara melakukan perkawinan. Cara-cara perkawinan yaitu dengan cara lamaran atau meminang (ngidih; Bali), belarian atau kawin lari (ngerorod; Bali), dan kawin bawa lari (melegandang; Bali). 10
Kawin dengan cara lamaran adalah cara perkawinan atau suatu cara dimana calon pasangan sudah sepakat untuk melaksanakan perkawinan pada hari yang sudah disepakati. Artinya dua belah pihak tidak ada masalah dalam segala hal. Sangat berbeda dengan cara perkawinan lari bersama, dimana pada cara ini ada salah satu pihak tidak menghendaki adanya perkawinan.11 Hal itu pada umumnya yang tidak menghendakinya adalah keluarga dari pihak perempuan. Selain hal itu ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan ditempuhnya cara lari bersama yaitu menghindari keharusan adat, mengirit biaya dan juga waktu. Dalam perkawinan
dengan membawa lari atau kawin paksa, dimana adanya paksaan terhadap perempuan pada umumnya gadis dari laki-laki yang mau kawin tersebut. Cara yang terakhir ini sudah tidak lagi di jaman sekarang di samping tidak selaras dengan hukum Negara juga tidak relevan dengan situasi di jaman kekinian yang sangat tidak manusiawi.
Terkait dengan perempuan kawin nyerod, pada umumnya dilakukan dengan cara lari bersama atau kawin lari, tetapi di jaman sekarang ada kalanya kawin nyerod dilakukan dengan lamaran tetapi sifatnya kasuistis. Hal tersebut diungkap oleh Sukerti bahwa perkawinan nyerod yang sering disebut perkawinan beda wangsa tidak melulu dilakukan dengan cara kawin lari, artinya ada juga yang dilakukan dengan cara lamaran.12 Perkawinan nyerod tidak seangker di masa lampau, hal mana disebabkan adanya perkembangan di segala aspek kehidupan masyarakat, terutama adanya perubahan paradigm dalam memandang perkawinan tersebut. 13 Dalam menjalani perkawinan tidak selamanya berjalan sebagaimana awal terjadi perkawinan, melainkan ada kalanya gagal dalam kehidupan berumah tangga. Gagal dalam berumah tangga yang difokuskan dalam penelitian ini adalah adanya perceraian dalam perkawinan nyerod. Sehubungan dengan hal tersebut hasil penelitian menunjukan bahwa sangat bervariasi, ada yang diterima dengan baik dengan melakukan upacara pengembalian statusnya sebagai gadis, terhadap kasus seperti ini hanya ditemukan dua kasus, tetapi yang paling banyak dijumpai adalah statusnya yang tidak jelas.14 Terhadap kasus yang tidak jelas ini, hasil penelitian menunjukan bahwa perempuan nyerod ada yang diterima oleh orang tua dan keluarganya tetapi terbatas dari segi kemanusiaan. Hal mana karena perempuan dimaksud hanya diajak tanpa begitu saja tanpa ada upacara apa adat dan agama, bahkan boleh dibilang dipandang sebagai orang lain yang hidup menumpang di rumah asal (umah bajang). Ada juga kasus, dimana si janda nyerod, setelah kematiannya diminta oleh anak-anaknya untuk diupacarai secara adat dan agama.
Mencermati nasib perempuan kawin nyerod sangatlah memperihatinkan, mengingat hukum adat yang masih kuat mengikat kehidupan masyarakat Bali. Hukum adat dibuat oleh masyarakat di masa lampau, ada kalanya tidak cocok dengan kehidupan masyarakat di jaman sekarang. Hal mana dikarenakan masyarakat sudah mengalami perkembangan, dimana hukum sebagai konstruksi social seharusnya juga mengalami perubahan. Hukum adat sebagai hukum local tidak boleh bertentangan hukum Negara dalam hal ini Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 9 ayat 2, secara garis besarnya dapat dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Mencermati ketentuan tersebut, dimana setiap warga negara berhak hidup nyaman dan aman, nampaknya kehidupan seperti itu menyentuh pada perempuan kawin nyerod yang cerai. Tidak sedikit kasus, terkait perempuan demikian mempunyai status yang tidak jelas (ngambang, Bali) di rumah asal. Inilah inti atau fokus kajian dalam penelitian.
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 Desember 2021, 869-879
Status perempuan yang tidak jelas tersebut membawa kondisi yang tidak nyaman dan aman lahir dan batin bagi perempuan yang bersangkutan. Terkait dengan itu maka status hukum seseorang itu harus jelas, terlebih setelah adanya perceraian. Perempuan juga manusia yang tidak boleh dilanggar haknya untuk hidup aman dan nyaman, apapun statusnya apakah sebagai anak, ibu, istri, maupun janda. Oleh karena itu hukum adat sebagai the living law tidak boleh bertentangan dengan hukum Negara yakni Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum adat boleh hidup asal tidak bertentangan dengan hukum negara, kedua hukum hidup haromis berdampingan dalam lapangan sosial yang sama.
Berbicara tentang pandangan masyarakat, tidak lain berbicara tentang budaya hukum masyarakat. Budaya hukum adalah pandangan, sikap, dan prilaku kelompok terhadap peraturan yang sedang berlaku. Sehubungan dengan itu juga dipandang perlu mengemukakan tentang batasan dari budaya hukum tersebut. Lawrence M. Friedman dalam Achmad Ali, mengemukan kultur hukuum adalah suasana pikiran social dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan. 15 Hilman Hadikusuma mengemukakan, budaya hukum adalah menunjukan tentang pola prilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.16 Sementara Satjipto Rahardjo dalam Derita Prati Rahayu mengemukan bahwa budaya hukum adalah sebagai landasan bagi dijalankannya atau tidak suatu hukum positif di dalam masyarakat karena pelaksanaan hukum positif banyak ditentukan oleh sikap, pandangan serta nilai yang dihayati.17
Sehubungan dengan budaya hukum masyarakat terhadap kewangsaan perempuan kawin nyerod hasil penelitian sebagai berikut; dari beberapa responden yang diwawancarai didapat jawaban yang sangat variatif. Untuk perkawinan nyerod dilakukan dengan cara meminang (memadik) dan lari bersama (ngerorod) terdapat perbedaan. Untuk perkawinan nyerod yang dilakukan dengan cara meminang, para pihak tidak menjadikannya masalah terutama orang tua dari kedua belah pihak karena sangat memahami situasi di jaman kekinian begitu berbeda dibandingkan dengan jaman dahulu. Artinya pada cara ini adanya persetujuan dari kedua orang tua ke dua belah pihak calon mempelai. Di samping itu para orang tua sudah memahami tentang adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada cara perkawinan seperti ini tidak dilakukan upacara patiwangi. Patiwangi artinya harumnya hilang atau mati, maksudnya bau harum si perempuan dihilangkan agar sama dengan si laki-laki. Maknanya adalah upacara penurunan wangsa si perempuan agar sama dengan wangsanya dengan si laki-laki. Sementara perkawinan beda wangsa dengan cara lari bersama, dimana perkawinan dilakukan tidak ada persetujuan dari salah satu pihak orang tua dan dapat juga dari kedua orang tua calon mempelai. Terhadap cara perkawinan ini, beberapa responden dilakukan upacara patiwangi, bahkan ada seorang
responden menuturkan bahwa dia “dibuang” ke laut. Makna dibuang hanyalah simbolis, walaupun sebuah makna simbolis, itu mencerminkan bahwa perempuan yang kawin nyerod dipandang tidak kerabatnya lagi, pada hal sebuah perkawinan itu merupakan hubungan hokum. Sebuah hubungan hokum selamanya sesuai dengan yang direncanakan oleh para pihak. Dilihat dan dicermati dari sudut perubahan tata bahasa, pada perkawinan dengan cara meminang, tidak terjadi perubahan bahasa, dalam arti dimana setelah si perempuan kawin nyerod, bahasa yang digunakan sehari-hari masih seperti biasanya, akan tetapi sebaliknya pada perkawinan dengan cara lari bersama dimana terjadi perubahn tata bahasa sehari-hari yang sangat menyolok misalnya tidak lagi memanggil ayah dan ibunya dengan sebutan aji dan biang sebagaimana pada saat ia masih gadis. Dengan demikian sangat eronis dan telah terjadi diskriminasi verbal terhadap anaknya. Hal demikian mencerminkan bahwa golongan tri wangsa menganggap dirinya berada di atas golongan jaba wangsa. Ini bermula dari cara melihat 5 (lima) jari-jari tangan dalam mengibaratkan wangsa tersebut secara vertical sehingga ada atas bawah. Seharusnya melihatnya secara horizontal sesuai fungsinya. Hal inilah yang kurang dipahami oleh beberapa orang di jaman kekinian. Perlakuan yang diskriminasi terhadap sesama tidak sesuai dengan ketentuan Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam hal terjadinya perceraian dalam kawin nyerod, hasil penelitian menunjukan bahwa perempuan nyerod kemudian bercerai dan diterima secara baik-baik oleh orang tua dan keluarganya dibuatkan upacara tertentu untuk mengembalikan status kewangsaannya yakni berstatus tri wangsa. Perlakuan yang demikian tidak mencerminkan perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap seorang perempuan kawin nyerod yang bercerai, karena membuat istilah nyerod adalah manusia, maka ia juga mengembalikan pada status semula atau pada wangsa semula. Bagi perempuan nyerod yang pulang tanpa ada perbuatan hukum pengembalian status, kondisi yang demikian sangat memprihatinkan bagi perempuan Bali Hindu di jaman milenial. Jaman berubah, masyarakat mengalami perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan tetapi dalam hal hukum adat masih tetap dipertahankan oleh sebagian besar anggota masyarakat adat. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhtarom, bahwa dari keseluruhan dinamika system hokum tampak dalam seluruh respon yang mengintervensi, baik berupa permintaan ataupun tuntutan dari masyarakat. Dibalik tuntutan atau permintaan dari masyarakat tersebut, selain kepentingan terlihat juga faktor-faktor lain seperti nilai-nilai, ide, sikap, keyakinan, harapan-harapan, motif dan pendapat mengenai hukum.18
Terhadap kondisi yang demikian sangat relevan dikaji dari teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Dinyatakan, hukum terdiri dari tiga komponen; struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.19 Kondisi tersebut juga relevan dikaji dengan teori Semi-Aoutonomus. Teori Semi-Aoutonomus (Sosial Field Theory) yang dikemukakan Sally Falk Moor, berdasarkan reori tersebut dinyatakan bahwa setiap kelompok social mempunyai kapasitas dalam menciptakan mekanisme-mekanisme pengaturan sendiri (self regulation) dengan disertai kekuatan-kekuatan yang memaksa. Bidang yang kecil dan untuk sebagian otonomi itu dapat menghasilkan aturan-aturan dan adat istiadat serta simbol-simbol yang bersal dari
dalam.20 Di lain pihak, bidang tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan, keputusan-keputusan dan kekuatan-kekuatan lain yang berasal dari luar yang mengelilinginya21. Inti dari teori tersebut adanya dua peraturan hukum dalam kehidupan atau lapangan social yang sama yaitu hukum negara atau hukum nasional dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat (the living law), dimana kedua peraturan tersebut berlaku secara bersama-sama dalam masyarakat.
Budaya hukum masyarakat adat, lebih mentaati dan menghomati hukum adat dari pada hukum nasional dalam perkawinan beda wangsa terutama perkawinan yang dilakukan dengan cara lari bersama. 22 Artinya dimana beberapa individu dalam masyarakat masih mentaati aturan hukum adat dimasa lampau yang melarang adanya perkawinan beda wangsa khususnya dimana sang lelaki dari golongan jaba wangsa tersebut. Dimana larangan perkawinan beda wangsa tersebut secara yuridis formal sudah tidak berlaku lagi yang diatur dapam Keputusan DPRD Bali No. 11 Tahun 1951.23 Ini mencerminkan bahwa hukum adat kuat dan sebaliknya hokum Negara atau hokum nasional lemah. Sementatara berdasarkan teori system hukum, budaya hukum masyarakat yang masih mentaati aturan adat dalam hal perkawinan beda wangsa, jelas menunjukan prilaku yang menghindari aturan hokum Negara yang berlaku. Budaya hokum yang demikian sesuai dengan pendapat dari Didik Suriono, bahwa budaya hukum masyarakat merupakan barometer utama dalam proses penegakan hukum.24 Sementara Jamiat Alkadol juga menyatakan bahwa budaya hokum birokrasi sebagai faktor utama yang menyebabkan prilaku birokraso yang buruk. 25 Terkait dengan budaya hukum dalam hal penegakan hukum baik hukum negara maupun hukum yang hidup dalam masyarakat sangat memegang peranan, sehingga hukum sulit mencapai tujuannya yaitu keadilan. Dikaji dari perspektif gender, budaya hukum masyarakat yang masih mempermasalahkan perkawinan nyerod mencerminkan diskriminasi gender dalam masyarakat. Hal tersebut sangat tidak sejalan dengan tujuan dari Inttruksi Presiden RI No. 9 Tahun 2000 tentang Pengharusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasioanl (PUG). Dimana diamanahkan dalam peraturan tersebut tentang adanya kesetaraan dan keadilan gender dalam dalam segala kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam hal perkawinan nyerod dan hal terjadinya perceraian, dimana perempuan dipandang tidak sebagai anggota keluarganya. Sangat eronis, dijaman, tingkat pendidikan, dan lain-lainnya sudah mengalami perkembangan
yang sangat signifikan dan bahkan ada yang sudah menjelajah ke flanet lain (bulan), masih ada orang yang mempermalahkan perkawinan perempuan nyerod yang bercerai.
Dari keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan, dimana dalam terjadinya perceraian pada perkawinan nyerod, ada dua versi mengenai status perempuan nyerod yaitu ada yang melakukan upacara mengembalikan statusnya seperti waktu gadis dan ada juga yang tidak jelas statusnya, karena alasan manusiawi dia diajak di rumah asalnya. Terhadap kondisi demikian dapat timbul masalah kedepannya terkait dengan kematiannya nanti. Sementara pandangan masyarakat terhadap kewangsaan perempuan nyerod tersebut bervariasi, dalam hal adanya upacara pengembalian kewangsaan jelas tidak menimbulkan masalah, sebaliknya masalah timbul pada perempuan nyerod yang statusnya tidak jelas, dimana masyarakat tetap memandang sebagai orang bukan tri wangsa, walaupun mereka pulang ke rumah dan tinggal menetap di rumah asal.
Ucapan terima Kasih (Acknowledgments)
Banyak terima kasih diucapkan kepada: 1 Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana, 3. Rektor Universitas Udayana, atas bantuan pendanaan sehingga penelitian ini dapat terlaksana. Di samping itu terimakasih juga disampaikan kepada kepada mahasiswa, informan dan responden atas bantuannya sehingga penelitian ini dapat terlaksana sesuai rencana.
Daftar Pustaka
Buku
Ahmad Ali. Keterpurukan Hukum Di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
Hadikusuma, Hilman. Antropologi Hukum Indonesia. Alumni, 1986.
Jiwa, Atmaja. Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali. Denpasar: Udayana University Press, 2008.
Mukti Fajar, ND, and Y Achmad. Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
Pide, A Suriyaman Mustari, and M SH. Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang. Prenada Media, 2017.
Rahayu, Derita Prapti. Budaya Hukum Pancasila. Thafa Media, 2014.
Wignjodipuro, Surojo. Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1980.
Jurnal
Adnyani, Ni Ketut Sari. “Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 5, no. 1 (2016). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha. v5i1.8284.
Akadol, Jamiat. “Budaya Hukum Sebagai Faktor Pendorong Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerah Di Indonesia.” Jurnal Magister Hukum Udayana 7, no. 1 (2018).
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 Desember 2021, 869-879
https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i01.p02.
Anggraini, Putu Maria Ratih, and I Wayan Titra Gunawijaya. “Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan Di Bali.” Pariksa 2, no. 1 (2020).
Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, and Anak Agung Istri. “Eksistensi Otonomi Desa Pakraman Dalam Perspektif Pluralisme Hukum.” Jurnal Magister Hukum Udayana 7, no. 3 (2014).
https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p13.
Hemamalini, Kadek, and Untung Suhardi. “Dinamika Perkawinan Adat Bali.” Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan 14, no. 27 (2016): 36–47.
https://doi.org/https://doi.org/10.32795/ds.v14i27.45.
Mahardini, Ni Made Dwi, and David Hizkia Tobing. “Perempuan Hindu-Bali Yang Nyerod Dalam Melakukan Penyesuaian Diri.” Jurnal Psikologi Udayana 4, no. 2 (2017): 390–98. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JPU.2017.v04.i02.p14.
Moore, Sally Falk. “Hukum Dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom Sebagai Suatu Topik Studi Yang Tepat.” Dalam Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, Penyunting TO Ihromi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
Muhtarom, M Muhtarom M. “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Dalam Masyarakat.” Suhuf 27, no. 2 (2015): 121–44.
Pursika, I Nyoman. “Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif Dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki Di Bali.” Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1, no. 2 (2012). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v1i2.4497.
Rudita, I Made. “Hak Asasi Manusia Dan Perkawinan Hindu.” Jurnal Advokasi 5, no. 1 (2015).
Suardana, Ida Ayu Radinia Asri. “Gambaran Konflik Interpersonal Dan Intrapersonal Perempuan Hindu-Bali Yang Menjalani Perkawinan Turun Wangsa (Nyerod).” Universitas Airlangga, 2020.
Sudarma, I Putu. “Bias Gender Dalam Perkawinan Beda Wangsa Pada Masyarakat Hindu Di Bali.” Harmoni 14, no. 3 (2015): 158–65.
Sukerti, Ni Nyoman, and IGAA Ariani. “Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 7, no. 4 (2018): 516–28.
https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p07.
Sukriono, Didik. “Penguatan Budaya Hukum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia.” Padjadjaran Journal of Law 1, no. 2 (2014).
https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a2.
Sumartika, I Wayan, Diah Gayatri Sudibya, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “Hukum Perkawinan Berbeda Kasta Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Analogi Hukum 1, no. 3 (2019): 396–400.
Widetya, Alit Bayu Chrisna. “Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan Dari Perkawinan Nyerod Beda Kasta Menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali.” Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015.
Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengharustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
879
Discussion and feedback