Posisi Buton dalam Arus Sejarah Indonesia
on

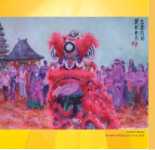
p-ISSN: 2528-5076, e-ISSN: 2302-920X
Terakreditasi Sinta-4, SK No: 23/E/KPT/2019 Vol 26.2 Mei 2022: 215-226
Posisi Buton dalam Arus Sejarah Indonesia
Heru Mulyanto
Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia Email korespondensi: yarinda.bunnag@outlook.co.id
Info Artikel
Abstract
Masuk: 31 Maret 2022
Revisi: 5 Mei 2022
Diterima: 18 Mei 2022
Keywords: position; Buton;
Indonesian history
Buton is a local kingdom that has not been widely discussed in Indonesian history. This sultanate has a uniqueness that is rarely owned by other sultanates in the archipelago. One of these uniquenesses is the ties of cooperation between Buton and the VOC in many fields. Because of this, Buton is often considered a traitorous sultanate. This study was written to map the position of the Sultanate of Buton in terms of economy, politico-government, trade, defense, and diplomacy (including relations with the VOC) in Indonesian history. The critical history method was used in writing this article by using related research literature sources. It was concluded that the Buton government was in a unique position compared to other sultanates because the sultan was elected by the people and was not hereditary. Meanwhile, Buton's shipping and trade strategy remained at the point of Nationalism even though cooperation with the VOC was established here. Buton's government structure indicates that the position of this sultanate is at a modern stage compared to the sultanates in Java and Kalimantan.
Abstrak
Kata kunci: posisi; Buton; sejarah Indonesia
Corresponding Author:
Heru Mulyanto
email:
DOI:
Buton merupakan kerajaan lokal yang belum banyak dibahas dalam sejarah Indonesia. Kesultanan ini memiliki keunikan yang jarang dimiliki oleh kesultanan-kesultanan lain di Nusantara. Salah satu keunikan tersebut adalah ikatan kerjasama yang dijalin Buton bersama VOC di banyak bidang. Karena hal tersebut, Buton sering dianggap sebagai kesultanan pengkhianat. Penelitian ini ditulis untuk memetakan posisi Kesultanan Buton ditinjau dari segi ekonomi, politik-pemerintahan, perdagangan, pertahanan, dan diplomasi (termasuk hubungan dengan VOC) dalam sejarah Indonesia. Metode sejarah kritis digunakan dalam penulisan artikel ini dengan menggunakan sumber-sumber pustaka penelitian terkait. Didapatkan kesimpulan bahwa pemerintahan Buton berada pada posisi unik dibandingkan dengan kesultanan-kesultanan lainnya karena sultan dipilih oleh rakyat dan tidak turun-temurun. Sementara strategi pelayaran dan perdagangan Buton tetap berada pada titik Nasionalisme walaupun kerjasama dengan VOC dijalin di sini. Struktur pemerintahan Buton menandakan bahwa posisi kesultanan ini telah berada pada tahap yang modern dibanding kesultanan-kesultanan di Jawa dan Kalimantan.
PENDAHULUAN
Kesultanan Buton merupakan kesultanan yang yang tidak banyak direkonstruksi dalam historiografi sejarah Indonesia. Sebelum 1999, hampir tidak ada sejarawan yang berfokus dalam menuliskan sejarah dinamika Kesultanan Buton dalam sejarah Indonesia kecuali Susanto Zuhdi. Beliau memulainya dengan menulis sebuah disertasi berjudul Labu Rope Labu Wana: Sejarah Butun Abad XVII–XVIII. Disertasi tersebut menandai munculnya konsep baru dalam sejarah Indonesia, khususnya dalam sejarah maritim Sulawesi.
Dalam historiografi sebelumnya, Buton diposisikan oleh Sartono Kartodirdjo dalam bukunya, Pengantar Sejarah indonesia Baru 1500–1900: Dari Emporium Sampai Imperium sebagai bagian dari wilayah aneksasi Kesultanan Ternate (Kartodirdjo, 1988). Namun, tulisan Susanto Zuhdi memperbaiki kekeliruan tersebut dengan penjelasan lebih lanjut mengenai konsep Labu Rope–Labu Wana yang menjadi pertanda bahwa sebenarnya Buton tidak seutuhnya menjadi bagian dari Kesultanan Ternate ataupun Kesultanan Gowa. Buton merupakan kesultanan independen yang mengirim upeti kepada Ternate dengan tujuan menghindari aneksasi dari Ternate. Namun di sini, Ternate menganggap upeti yang dibayarkan Buton sebagai pertanda ketundukan. Oleh karena adanya ancaman dari Rope/haluan (Kesultanan Gowa) dan Wana/buritan (Kesultanan Ternate), Buton melihat VOC sebagai pelindung, sebelum kemudian akhirnya bekerja sama dengan VOC agar mencapai posisi Labu Rope– Labu Wana (keamanan dalam pelayaran ke Haluan dan ke Buritan) (Zuhdi, 1999).
Berangkat dari konsep yang dikemukakan Zuhdi tersebut, penelitian ini ditulis untuk menilik lebih lanjut kedudukan Kesultanan Buton dalam sejarah Indonesia: Di mana posisinya
dalam perdagangan jalur rempah? Apakah ada kemiripan politik Buton dengan pemikiran politik modern? Di manakah posisi Buton dalam bidang pertahanan jika dibandingkan dengan pertahanan kesultanan lain? dan pembahasan lainnya yang mencerminkan posisi buton di tengah-tengah dinamika kolonial dalam sejarah Indonesia. Tulisan ini menawarkan kebaruan konsep pemikiran berupa pembahasan mengenai posisi Kesultanan Buton dilihat dari bidang ekonomi, politik-pemerintahan, perdagangan, pertahanan, dan diplomasi dengan membandingkan poin-poin serupa yang dialami kesultanan-kesultanan lain di Nusantara.
Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang lingkup spasial yang terfokus pada provinsi Sulawesi Tenggara (tepatnya Kepulauan Buton) dan memiliki lingkup material, yaitu penggambaran posisi geopolitik, ekonomi, pertahanan, perdagangan dan diplomasi Buton, dalam sejarah Indonesia. Sedangkan untuk lingkup temporalnya, penelitian ini membahas wilayah Buton sejak tahun 1600an hingga 1960an. Lingkup tersebut dipilih karena perdagangan VOC di Sulawesi dimulai pada abad ke-17, termasuk Buton yang kala itu dipimpin oleh Sultan La Elangi (sultan ke-4 Buton).
METODE DAN TEORI
Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yaitu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman, dokumen-dokumen dan peninggalan masa lampau yang otentik dan dapat dipercaya, serta membuat interpretasi dan sintesis atas fakta-fakta tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya (Gottscalk dalam Herlina, 2020). Penggunaan sumber sekunder dianggap relevan dalam tulisan ini karena pada dasarnya, penelitian ini bertujuan membangun konstruksi pemikiran baru
mengenai Buton dalam arus sejarah dari penelitian-penelitian sebelumnya.
Langkah heuristik dilakukan dengan menelurusi karya-karya sejarah terkait Buton, yang dalam hal ini didasari oleh disertasi Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum. Verifikasi ekstern dilakukan dengan tiga pertanyaan: Apakah sumber tersebut memanglah sumber yang kita kehendaki? Apakah sumber tersebut asli atau turunan? dan Apakah sumber tersebut masih utuh, atau telah disunting? (Herlina, 2020). Sedangkan, verifikasi intern dilakukan dengan menguji fakta sejarah yang telah dituliskan sebelumnya dengan melakukan pembandingan sumber. Interpretasi sumber sekunder dilakukan dengan auffassung1 dan darstellung2. Historiografi dituangkan dalam bentuk artikel jurnal dengan novelty (kebaruan penelitian) berupa pembangunan konsep baru tentang kedudukan dan sumbangsih Buton dalam sejarah Indonesia.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kesultanan Buton dalam tulisan ini dipetakan kedudukannya mengguakan indikator bidang perdagangan, politik-pemerintahan, hubungan diplomatik, ekonomi, dan pertahanan sebagai tolok ukur. Bidang perekonomian dipilih sebagai indikator pengukur karena perekonomian tak dapat dilepaskan dari kehidupan suatu pemerintahan (baik berbentuk kerajaan ataupun pemerintahan modern) dan kehidupan bermasyarakat. Sistem pengelolaan perekonomian yang digunakan masing-masing kerajaan/kesultanan tentunya berbeda pula. Seperti misalnya, kerajaan Mataram Kuno yang perekonomiannya bertumpu pada produksi beras, menerapkan sistem pemungutan pajak dan memberlakukan pembagian wilayah administratif. Ada
pula Kesultanan Banten yang bersumber dari perdagangan lada. Hal inilah yang digunakan sebagai pembanding untuk menentukan posisi dan pola
perekonomian Buton jika dibandingkan dengan kesultanan-kesultanan lainnya.
Bidang politik-pemerintahan juga dinilai mampu menunjukkan kedudukan pemerintahan Buton. Poin-poin yang dianalisis di sini adalah cara-cara pemilihan sultan, undang-undang adat Buton sebagai dasar negara, dan birokrasi pemerintahan Buton. Dipilihnya
indikator di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola-pola politik Kesultanan Buton serta juga untuk mengetahui pemikiran politik seperti apa yang diterapkan Buton. Sama seperti bidang perekonomian, pembahasan pada bidang politik-pemerintahan juga akan mengambil perbandingan dengan beberapa kesultanan lainnya di Nusantara.
Selain ekonomi dan politik-pemerintahan, bidang diplomasi dirasa perlu dibahas pula dalam
menggambarkan kiprah Buton di antara kesultanan-kesultanan lain ataupun dengan VOC. Seperti yang dijelaskan pada uraian pendahuluan, Susanto Zuhdi telah mengungkap pola hubungan Buton yang berupa sekutu-seteru. Seperti yang 3 telah dibahas oleh Sartono Kartodirdjo3 bahwa, sedikit sekali kesultanan di Nusantara yang bersedia bersekutu dengan VOC dan Buton menjadi salah satunya. Subbab ini akan
membandingkan pola diplomasi Buton-VOC dengan kerajaan lain yang pernah bersekutu dengan VOC–Banten,
Mataram, Ternate dan lain-lain–untuk memetakan posisi serta menjelaskan dampak yang terjadi pasca dilakukannya kontrak diplomasi dengan VOC.
Bidang perdagangan dibahas di sini untuk mendeskripsikan komoditas utama yang dihasilkan Buton dibanding kerajaan-lain. Selain itu, dibahas pula respons Buton terhadap penetapan jalur-jalur dagang resmi oleh VOC untuk menguasai jaringan Laut Indonesia Timur. Respons Buton yang akan dibahas pada subbab ini akan menjadi cerminan keberpihakan Buton kepada VOC ataukah kepada prinsip Nasionalisme.
Satu bidang terakhir yang digunakan sebagai penunjuk posisi Buton adalah bidang pertahanan. Bidang ini dibahas untuk mengetahui strategi Buton dalam menghadapi serangan-serangan Ternate, Gowa, ataupun VOC di saat statusnya sebagai seteru. Hal ini dilakukan untuk mengetahui taktik Buton sehubungan dengan statusnya sebagai kerajaan kecil yang berbeda dengan kesultanan-kesultanan seperti Makassar, Banjar, Mataram, dan lainnya yang merupakan kesultanan besar dan memiliki kekuatan lebih besar dari Buton.
Posisi Bidang Perdagangan Buton
Pola-pola perekonomian kerajaan tradisional di Indonesia seperti yang telah banyak diketahui, selalu berdasar pada perdagangan. Tidak ada jalur yang dapat membentuk jaringan hubugan antarkerajaan saat itu tanpa melalui pelayaran. Buton sebagai salah satu kesultanan maritim memanfaatkan jalur laut sebagai perajut hubungan diplomasi dengan berbagai pihak melalui perdagangan.
Secara topografis, Buton bukanlah merupakan daerah yang subur seperti Maluku dan Banten yang dapat menghasilkan rempah dalam jumlah besar. Komoditas perdagangan Kesultanan Buton lebih cenderung pada ekspor budak yang dihasilkan dari Buton Utara. Dalam sumber lain, dikatakan bahwa budak-budak dari Buton diekspor hingga ke Jawa dan Batavia untuk dipasarkan di Ommelanden (sekarang kawasan Bogor-Depok) (Kanumoyoso,
2011). Namun, jika dilihat lebih saksama, Buton berada di persimpangan jalur-jalur pelayaran Indonesia timur yang memungkinkan untuk pembukaan pelabuhan transit. Beberapa ciri pelabuhan transit yang baik menurut Zuhdi (1999) adalah yang memiliki bentang alam baik, memiliki pasar lokal sebagai penyuplai pangan, berpotensi menjadi emporium besar, dan dapat menjadi tempat perakitan barang-barang dari feeder point.
Dukungan faktor geografis lain bagi Buton untuk menjadi pusat perdagangan adalah letaknya yang berada di antara dua jaringan laut besar (sistem Laut Flores dan sistem Laut Banda) yang banyak dilewati kapal-kapal dagang. Dengan dikelilingi oleh daerah-daerah penghasil rempah seperti Maluku dan Nusa Tenggara Timur dan berada di dua lajur perdagangan besar, membuat Buton menempati posisi strategis sebagai pelabuhan entrepot.
Banjarmasin yang sama-sama sebagai pelabuhan transit diambil sebagai perbandingan di sini. Bilamana dicermati lebih lanjut, Bajarmasin masih memiliki potensi sebagai penghasil rempah berupa kayumanis dan lada, sedangkan Buton hampir tidak memiliki potensi rempah-rempah. Banjarmasin merupakan pelabuhan transit dan ekspor-impor yang terletak di pertemuan Sungai Barito dan Sungai Negara (Susilowati, 2004) dan berhubungan dengan jaringan Laut Jawa secara tidak langsung, sedangkan Buton secara langsung berhubungan dengan dua jaringan laut sekaligus (Laut Flores dan Banda) dan berada di persimpangan jalur dagang internasional yang membuat Buton selangkah lebih unggul dibanding Banjarmasin.
Selain itu, Pelabuhan Emmahaven (sekarang Teluk Bayur) di Pantai Barat Sumatera yang berstatus sebagai pelabuhan prasarana layak pula dijadikan perbandingan dengan Banjarmasin dan Baubau (Buton) untuk memetakan perdagangan Buton.
Dibandingkan dengan Banjarmasin dan Baubau, Emmahaven merupakan pelabuhan prasarana yang sengaja dibangun pemerintah Hindia-Belanda untuk menunjang kegiatan ekspor Batubara dari tambang Ombilin (Asnan, 2009). Eksistensi Emmahaven tidak seperti Baubau dan Banjarmasin yang telah ada sejak era awal kesultanan. Peruntukan Emmahaven juga hanya untuk menunjang satu jenis kegiatan ekspor saja, (hanya ekspor batubara) tidak seperti Baubau di Buton yang melayani transaksi segala jenis komoditas dagang.
Dengan demikian, kesimpulan pertama yang dapat ditarik adalah perdagangan Buton dapat dibilang menempati posisi strategis secara potensi sebagai entrepot maupun secara geografis, ditandai dengan letaknya yang berada di jalur dagang internasional. Tak seperti Banjarmasin yang letaknya menjorok di pedalaman dan statusnya masih sebagai pelabuhan yang diusahakan (Susilowati, 2004). Tak juga seperti Teluk Bayur yang kejayaannya tidak bertahan lama dan letaknya tidak berada pada zona jaringan perdagangan internasional (pantai barat Sumatera).
Di sisi lain, keberpihakan Buton (terhadap VOC atau terhadap rakyatnya) juga dapat dinilai berdasarkan respons raja-raja Buton terhadap pembatasan jalur dagang oleh VOC dan pembatasan komoditas dagang yang boleh ditransaksikan. VOC sebagai sekutu Buton tentunya menginginkan agar Buton tetap berpihak pada VOC. Hal tersebut dilakukan dengan menetapkan pembatasan hubungan dagang dengan Johor dan Banjarmasin dan melarang perdagangan komoditas pala, lada, kain lena dan candu (Zuhdi, 1999). Namun, apa yang dilakukan sultan Kaimuddin saat itu adalah tetap memperbolehkan perdagangan ke Johor dan Banjarmasin berlangsung dan tetap menerima supply candu dari Mandar, lada dari Banjar, dan
lain-lain. Indikasi di atas menandai adanya kecenderungan sultan Buton untuk menghalangi taktik VOC dan tetap mendukung perdagangan rakyatnya dengan bebas.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan kedua, bahwa Buton tetap cenderung berpihak pada prinsip Nasionalisme (secara sudut pandang perdagangan) meskipun sedang berada pada posisi terikat dengan kumpeni.
Posisi Bidang Politik-Pemerintahan Buton
Politik-pemerintahan kesultanan ini dapat dibilang unik jika dibandingkan dengan kesultanan-kesultanan lain di Nusantara. Pasalnya, kesultanan-kesultanan di Nusantara biasanya dipimpin oleh raja-raja yang dalam kepemimpinannya didasarkan pada genealogi (pewarisan takhta). Artinya, apabila seorang raja telah meninggal/habis jabatannya sebagai raja, maka beliau akan digantikan oleh keturunan/menantunya. Namun, Buton menerapkan prinsip yang berbeda. Pasalnya, semenjak Buton berubah menjadi kerajaan Islam, ia menggunakan apa yang disebut dengan sistem Murtabat Tujuh4 yang berarti kekuasaan sultan diatur dengan pemilihan secara demokratis dan pelantikan, bukan diwariskan turun-temurun. Sistem ini pertama kali diterapkan semenjak raja keenam yang bergelar “Sultan” yang bernama Lakila Ponto yang kala itu menggantikan mertuanya (masih menerapkan sistem pewarisan tahta) (Zuhdi dkk, 1996). Murtabat Tujuh adalah refleksi wujud tuhan yang hakiki yang dicerminkan melalui tujuh tingkatan
dalam pemerintahan. Tingkatan pertama hingga ketiga ditempati oleh tiga golongan bangsawan utama kesultanan, sedangkan empat tingkatan yang lain diduduki oleh jabatan sapati (perdana menteri), kanepulu (hakim agung), kapitalao (raja laut), dan sorawolio (menteri pertahanan), dan sultan ditempatkan pada posisi antara tiga tingkat yang pertama dan empat yang kedua (Zuhdi, 2014).
Penulis mengambil contoh
kesultanan lainnya di Nusantara, Mataram misalnya yang dianggap dapat mewakili mayoritas bentuk pemerintahan kesultanan Islam di Nusantara. Dalam struktur pemerintahan Kesultanan Mataram, sistem yang dianut adalah Dewa-Raja yang berarti kekuasaan tertinggi di seluruh negeri dipegang oleh sultan yang juga bergelar
Panatagama/pemimpin agama (Van den Berg dalam Kartodirdjo, 1987; Arif dan Rahman, 2011). Sedangkan, Buton menerapkan sistem Murtabat Tujuh untuk menggeser adanya peran ganda pada raja seperti yang terjadi pada Kesultanan Mataran. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh adanya konsep bahwa hanya Tuhan yang satu-satunya wujud hakiki. Tidak boleh ada manusia yang bergelar/disamakan posisinya sebagaimana Dewa-Raja.
Dalam pelaksanaannya, sistem pemilihan sultan Buton masih mensyaratkan ketentuan jenis kelamin, seperti yang dijelaskan Susanto Zuhdi: Adapun kriteria sultan adalah: (1) Berasal dari golongan kaomu, (2) Harus
berkelamin laki-laki, (3) memiliki sifat-sifat siddiq, amanah, tabligh, fathanah (Zuhdi, 2014).
Dalam kutipan di atas, terlihat jelas bahwa unsur ketidakadilan gender masih terdapat dalam tradisi pemilihan sultan Buton. Dalam hal ini, pemerintahan Buton masih memiliki kesamaan dengan sistem penetapan sultan pada Kesultanan Mataram, di mana posisi sultan tidak boleh ditempati oleh perempuan (hal
tersebut masih berlangsung hingga pemerintahan Yogyakarta saat ini).
Bilamana dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang diterapkan Indonesia modern saat ini, pemilihan sultan Buton kurang lebih sama seperti pemilu modern, di mana calon pemimpin yang lebih dari satu, diikat oleh beberapa kriteria (harus WNI, tidak pernah dipidana, dsb).
Dapat disimpulkan dari perbandingan di atas, bahwa Buton memiliki kelebihan di bidang pemerintahan yang membuat pemerintahan Buton berada pada posisi yang lebih modern daripada pemerintahan kesultanan lainnya. Yaitu, posisi sultan yang lebih fleksibel untuk ditempati rakyat lainnya, tidak hanya dari keturunan sultan saja (ditandai dengan telah dilakukannya pemilihan sultan). Selain itu, struktur parlemen Buton menunjukkan modernitasnya pada masa Sultan La Elangi (1597-1631), dimana saat itu ditetapkan posisi eksekutif (diduduki masyarakat kaomu), legislatif (diduduki kaum walaka), dan yudikatif (boleh diduduki kaum kaomu dan walaka) (Iriani dan Sritimuryani, 2021) layaknya Trias Politika.
Posisi Bidang Diplomasi Buton
Seperti yang telah disiggung pada subbab sebelumnya, Buton merupakan kesultanan yang menandatangani kontrak kerjasama dengan VOC. Seperti yang telah banyak diketahui pula, VOC sering terlibat dalam urusan internal kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan tak jarang dari kerajaan-kerajaan tersebut yang menjalin kontrak dengan VOC. Ada baiknya penjelasan di bidang diplomasi dimulai dari pemaparan mengenai hubungan diplomatik Buton-Ternate-Gowa.
Ternate memulai intervensinya terhadap Buton pada tahun 1627 dengan dikirimnya kapten laut Ali ke wilayah sekitar Ternate untuk dijadikan vasal/negara bawahannya (Zuhdi, 1999). Wilayah sekitar Ternate yang dimaksud
adalah wilayah yang masuk dalam ekspansi Gowa: Buton, Sula, Banggai, Manado, Tambuku, dan lain-lain. Pengaruh Ternate makin terasa di Buton pada 1652 saat Sultan Mandarsyah dari Ternate mengawini anak perempuan Saparagau (Mantan Sultan Buton). Hal tersebut tentunya adalah taktik politik Ternate untuk menurunkan Sultan Buton yang kala itu dijabat oleh Mardan Ali (La Cila) dan mencampuri politik Buton. Lebih lanjut, Sultan Mandarsyah menganeksasi Pulau Muna (salah satu wilayah Buton) yang kemudian diprotes oleh Buton sebagai penembusan terhadap batas-batas wilayah Buton.
Sementara itu, hubungan Gowa-Buton hampir sama kondisinya. Gowa berpotensi mengancam Buton karena ambisinya untuk menguasai perdagangan di Indonesia Timur dengan mencari pengaruh dari kerajaan-kerajaan kecil seperti Buton. Sementara VOC pun juga demikian. Sebagai langkah antisipasi untuk terhindar dari serangan Gowa, Buton menjalin hubungan dengan VOC (yang merupakan musuh Gowa) pada masa Sultan La Elangi (sultan keempat). Dapat dilihat bahwa tindakan Gowa lebih agresif dibandingkan Ternate, dengan ditandai oleh penyerangan besar-besaran Gowa terhadap Buton ketika Buton berada pada status quo (tanpa sultan) antara 1619-1631.
Bertolak dari uraian di atas, dapat diamati bahwa VOC adalah media pelindung bagi Buton dari aneksasi Ternate dan Gowa. Ditandai dengan Sultan La Elangi (Dayanu Ikhsanuddin) yang menyambut VOC secara penuh dengan menandatangani perjanjian dengan Apollonius Scotte (mewakili gubernur Belanda) pada 5 Januari 1613 (Mujabuddawat, 2015).
Diplomasi Buton-VOC berbeda jika dibandingkan dengan Ternate yang samasama bersekutu dengan VOC, di mana Sultan Mandarsyah dari Ternate pada awalnya bersikap lunak terhadap
kedatangan VOC. Sebelum kemudian, VOC menguasai Seram dan perlawanan dari golongan anti-VOC di Ternate pun meledak (Kartodirdjo, 1987).
Dapat dilihat bahwa tidak seluruh bagian dari Kesultanan Ternate menerima kehadiran VOC. Manila dan Kalimana yang merupakan saudara Sultan Mandarsyah tetap menentang VOC sebelum akhirnya terusir dari Maluku. Sedangkan untuk kasus Buton, perpecahan dalam kerajaan juga terjadi, namun lebih dilatarbelakangi oleh perebutan tahta Raja, daripada menentang VOC. Buton tidak memusuhi VOC secara agresif seperti Ternate, namun lebih bewujud pada pelanggaran perjanjiannya dengan VOC. Contohnya, penahanan kapal Rust en Werk oleh Buton sebagai bentuk pengingkaran terhadap perjanjiannya dengan VOC. Biarpun begitu, kontrak dengan VOC tetap harus dilanjutkan seperti yang dilakukan Sultan Mardan Ali yang melanjutkan kontrak oleh pendahulunya, La Elangi (Marhini dkk, 2020).
Kesultanan-kesultanan lain yang juga sempat menandatangani perjanjian dengan VOC seperti Banten dan Makassar dijelaskan sebagai pembanding di sini. Makassar aktif dalam menentang VOC di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin, sedangkan Banten dipimpin oleh Ageng Tirtayasa. Keduanya samasama menolak kehadiran kumpeni di dalam kerajaan mereka, namun taktik devide et impera berhasil menghancurkan Banten dari dalam. Bidang diplomasi Banten terhadap VOC kurang lebih sama seperti Ternate, di mana terdapat pihak yang menolak kehadiran VOC (S. Ageng Tirtayasa) dan juga ada pihak yang bekerjasama dengan VOC (Sultan Haji). Dapat disimpulkan, bahwa posisi diplomasi Buton sejak awal telah menempati posisi sulit karena terjepit di tengah-tengah dua kekuatan besar dan terpaksa menjalin ikatan dengan VOC. Namun begitu, status bidang diplomasi
Buton mirip seperti bidang perdagangannya yang tetap menentang VOC dalam beberapa hal, dan mendukung pihak rakyat. Manfaat yang didapat Buton dari taktik tersebut ialah, Buton selamat dari taktik devide et impera VOC yang menghancurkan sebuah kesultanan dari dalam karena Buton memiliki status sebagai sekutu VOC.
Sedangkan Banten Makassar, dan Ternate sejak awal tidak mengkehendaki berdiplomasi dengan VOC karena mereka adalah kesultanan yang kuat. Tetapi tetap saja VOC dapat mengakses bagian internal kesultanan-kesultanan tersebut dan menguasainya karena terdapat pihak internal kerajaan yang pro-VOC.
Posisi Bidang Perekonomian Buton
Untuk memetakan posisi bidang perekonomian kesultaan ini, perlu dibahas terlebih dahulu letak geografis kesultanan Buton dengan melihat pula letak geografis kesultanan-kesultanan lain sebagai perbandingan. Hal ini bertujuan untuk melihat potensi ekonomis yang ditawarkan oleh bentang alam wilayah terkait.
Pulau Buton terletak di wilayah Sulawesi Tenggara dekat dengan laut Banda dan Laut Flores seperti yang telah dijabarkan di subbab sebelumnya. Dengan demikian, potensi ekonomis yang ditawarkan bentang alam tersebut adalah pelayaran dagang. Namun, timbul permasalahan baru. Buton bukan merupakan kesultanan yang subur dan jarang sekali memiliki rempah-rempah. Hanya wilayah Buton Timur yang dikenal memiliki sedikit potensi cengkeh dan pala (Marhini dkk, 2020). Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar wilayah pulau Buton merupakan batu karang (Iwan, 2016). Maka dari itu, komoditas dagang yang memungkinkan adalah penjualan tenaga kerja berupa budak dari Buton Utara dan tenaga pengangkut (awak kapal), umbi-umbian,
dan jagung (Kanumoyoso, 2011; Muliadin Iwan, 2016). Berbanding terbalik dengan Banten yang wilayah kekuasaannya membentang dari Barat pulau Jawa hingga ke Lampung. Dari segi geografisnya, perekonomian Banten bertumpu pada hasil panen lada dari pedalaman Lampung yang diangkut melalui Sungai Tulang Bawang dan kemudian dijual hingga Tiongkok dan Eropa.
Kesimpulan pertama yang dapat ditarik yaitu berdasakan potensi SDA, bidang perekonomian Buton menempati posisi sulit karena miskin akan hasil alam jika dibanding dengan Banten, tetapi memiki peluang besar di bidang geografis yang membuat Bau-Bau menjadi pusat transit Internasional.
Selain Banten, kerajaan Mataram dianggap perlu disandingkan karena memiliki kemiripan dalam sumber pendapatan perekonomian, yaitu perpajakan. Mataram merupakan kesultanan agraris yang memiliki lahan persawahan yang luas. Sehingga dalam prakteknya, aspek tanah dikenai pajak pula. Perpajakan di Kesultanan Mataram terbagi menjadi 5: pajak penduduk, pajak tanah, pajak upeti, dan pajak bea cukai (Suryani, 2021). Sementara Banten menerapkan sistem pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang wajib dibayar yang meliputi pajak pelabuhan dan cukai ekspor-impor, sementara pajak tak langsung berupa upeti (Karma, 2017).
Pendapatan ekonomi dari pajak di Kesultanan Buton sendiri dimulai sejak masa sultan keempat dan kelima dengan dibuatnya posisi tunggu weti sebagai pemungut pajak. Pajak yang dipungut dalam Kesultanan Buton berbentuk tanah atau kebun milik rakyat yang disisihkan (Zuhdi dkk, 1996). Dalam perkembangannya, jabatan tunggu weti berkembang menjadi Bonto Ogena yang berjumlah dua orang yang masing-masing memungut pajak dari Timur dan Barat Buton.
Kesimpulan kedua yang dapat ditarik adalah, Buton memiliki kesamaan dengan Banten dan Mataram (dan mungkin kesultanan-kesultanan lainnya) yang sama-sama memungut pajak sebagai pendapatan. Namun, terdapat perbedaan, di mana Banten dan Mataram memanfaatkan pajak sebagai pendapatan utama, sedangkan pajak di Buton hanya sebagai pendapatan sampingan.
Posisi Bidang Pertahanan Buton
Bilamana dilihat dari sudut pandang keamanan, Buton adalah kesultanan yang jauh dari kata aman, melihat banyaknya konflik-konflik yang terjadi di wilayah Indonesia Timur, Buton dapat dengan mudah menjadi salah satu sasaran. Maka dari itu, sultan-sultan Buton membuat dua model strategi pertahanan. Pertama, menjalin hubungan baik dengan bangsa Belanda dan kerajaan-kerajan yang berpotensi menjadi ancaman bagi Buton. Kedua, membuat sebuah sistem pertahanan yang disebut sebagai Sistem Pertahanan Empat Penjuru Berlapis.
Strategi pertahanan yang pertama erat hubungannya dengan bidang diplomasi karena melibatkan perjanjian-perjanjian dengan kumpeni. Kontrak pertama Buton yang bernama Janji Baana (berarti “kontrak pertama”) ditandatangani oleh Dayanu Iksanuddin (La Elangi), sultan keempat Buton. Perjanjian tersebut dijalin bersama Kumpeni yang diwakili oleh Appolonius Schotte. Implementasi dari pakta tersebut adalah kedua belah pihak sama-sama menyatakan komitmen untuk saling membantu dan memerngi musuh satu sama lain. Tiga dari lima poin komitmen VOC dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut: (1) Memberikan bantuan dan perlindungan kepada Kerajaan Buton bila mendapat serangan, (2) Tidak mengganggu dan menyulitkan rakyat Buton dalam urusan agamanya, (3) Berjanji secepat-cepatnya menjadi penengah pada raja Makassar, agar mau
meniadakan semua permusuhan terhadap Buton.
Sedangkan tiga dari sembilan janji Buton terhadap VOC adalah: (1) Memerangi musuh-musuh Kerajaan Ternate dan juga VOC, (2) Memberikan tentara bantuan kepada VOC bila nanti berangkat ke Solor sesudah perjanjian ini selesai ditandatangani, dengan tumpangan di atas kora-kora, (3) Pengawasan penetapan harga atas kebutuhan bahan pokok sehari-hari yang dimufakati supaya dipegang teguh.5 (Muliadin Iwan, 2016: 58-60).
Dengan adanya perjanjian tersebut, Buton telah terhindar dari ancaman Ternate dan secara tidak langsung telah menjalin kerjaama dengan Ternate pula karena secara politis, Ternate telah menjadi sekutu VOC. Selain itu, terbuka pula peluang untuk meminimalisir ancaman dari Makassar karena pada butir ketiga kontrak Janji Baana, VOC juga berkomitmen untuk menengahi perseteruan Buton-Makassar. Bukti nyata dari perjanjian tersebut di atas terwujud dalam koalisi antara pasukan Buton-VOC-Ternate yang bekerja sama dalam mengusir pasukan Portugis di Solor pada tahun 1613 (Marhini dkk, 2020). Namun sayangnya, beberapa kali bantuan yang diberikan VOC datang terlambat ketika Buton diserang Gowa.
Sedangkan strategi pertahanan Buton yang kedua disebut sebagai “Sistem
Pertahanan Empat Penjuru Berlapis”
yang terdiri dari:
-
1. Patalimbona (benteng inti yang melindungi keraton sultan).
-
2. Bhisa Patamiana (memantau
pergerakan musuh menggunakan penginderaan batin orang-orang terpilih).
-
3. Matana Soromba (empat kampung pertahanan terluar).
-
4. Barata (kerjasama antar kerajaan mitra Buton.
Sejatinya, Barata adalah
memberikan status kepada wilayah-wilayah tertentu sebagai penjaga kestabilan dan keamanan negara. Terdapat beberapa wilayah yang termasuk dala kategori Barata, yaitu Muna, Tiworo, Kalingsusu dan Kaledupa (Zuhdi, dkk, 1996). Wilayah-wilayah di atas (kecuali Muna) mulai ditetapkan sebagai Barata pada rezim Sultan La Elangi. Hanya Muna yang masih menentang. Muna Selatan kemudian digabung dengan Buton saat Sultan Murhum yang berasal dari Muna diangkat sebagai Sultan Buton. Empat wilayah barata di atas saling menguatkan apabila terjadi serangan dari luar.
Banyak sekali peninggalan-
peninggalan Buton di bidang pertahanan yang berwujud benteng. Beberapa di antaranya adalah Benteng Koncu, Benteng Liwu, benteng kombeli, dan Benteng Takimpo. Benteng-benteng di atas sejatinya, meniru figur benteng-benteng Portugis dan Belanda yang berbentuk persegi panjang dan memiliki pos pemantauan di setiap sudutnya (Hasanuddin, 2020).
Kesimpulan pertama dari paparan di atas adalah bahwa Buton merupakan kerajaan yang pandai dalam menjalin aliansi dengan kesultanan sekitar untuk menangkal serangan dua kerajaan besar yang mengapitnya (Gowa dan Ternate) dan pandai mengimbangi strategi perbentengan lawan dengan mengadopsi model yang sama.
Posisi pertahanan Buton terbilang lebih aman apabila dibandingkan dengan pertahanan Kesultanan Banten. Pasalnya, Buton mengurangi ancaman dari musuh di sekitarnya dengan diplomasi dan aliansi. Didukung dengan pembangunan benteng. Sementara Banten tidak demikian, dan lebih condong kepada perjuangan gerilya dan sabotase terhadap kapal-kapal dagang VOC. Bentuk sabotase tersebut dengan melakukan serangan-serangan kecil ke pelabuhan, dan merampas kapal dagang VOC. Selain itu, Banten menolak secara keras kehadiran VOC dengan membuka perdagangan bebas di pelabuhan-pelabuhan Banten agar monopoli VOC terdesak oleh bangsa-bangsa asing lain yang ingin berdagang dengan Banten (Indriani, 2020). Banten juga berusaha melemahkan VOC dengan mendukung pemberontakan Trunojoyo di Mataram, sehingga perhatian VOC teralih pada wilayah Vorstenlanden (wilayah Mataram) dibandingkan dengan Banten (Indriani, 2020).
Selain strategi offensif seperti di atas, strategi defensif juga digunakan Banten dengan membangun pertahanan gawe kuta baluwarti bata kalawan kawis yang artinya membangun kota benteng dengan batu bata dan karang (Wibowo, 2018). Pertahanan tersebut dibangun di sekeliling kota Serang yang kala itu merupakan kota pelabuhan di Teluk Banten.

Gambar 1. Peta Pelabuhan di Teluk Banten Sumber: Tubagus Wibowo, 2018.
Strategi-strategi pertahanan Banten di atas terbukti tidak efektif, dibuktikan dengan jatuhnya Banten oleh pengkhianatan sultan Haji terhadap Sultan Ageng Tirtayasa. VOC tetap dapat melakukan penetrasi dengan memanfaatkan “orang dalam” dari Banten (Sultan Haji).
Dengan demikian, kesimpulan keseluruhan dari bidang pertahanan Buton dibandingkan dengan pertahanan Kesultanan di Jawa (Banten diambil sebagai contoh) yaitu, Buton memiliki aspek geografis yang lebih tidak aman dibanding Banten, namun Buton dapat memposisikan dirinya agar tidak dianeksasi oleh kekuatan dari luar dengan cara mendekati dan melobi musuh-musuhnya. Sedangkan Banten yang wilayah kerajaannya lebih besar dan lebih kuat, cenderung lebih radikal dan tidak memperhatikan keberpihakan orang-orang “dalam” kerajaan yang mengakibatkan VOC dapat mengadu domba Banten dari dalam. Dapat dikatakan, Buton menempati posisi lemah secara geografis, namun kuat pada poisisi strategi pertahanan.
SIMPULAN
Secara keseluruhan, Buton merupakan kesultanan minoritas dengan sedikit potensi sumber daya alam dan menempati wilayah yang tidak aman. Namun, kepandaian raja-raja Buton dalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada membuat kesultanan ini dapat menempati posisi ekonomi yang menguntungkan, perdagangan yang menempati posisi strategis, pertahanan yang aman (dengan dukungan pihak lain), dan politik-pemerintahan yang terbilang modern. Sedangkan untuk bidang diplomasi, Buton menempati posisi yang sulit karena diapit oleh kekuatan-kekuatan besar yang memaksanya menjalin persekutuan. Namun, bidang diplomasi Buton lebih unggul dibanding kesultanan-kesultanan
lain karena berhasil mencegah intervensi VOC lebih dalam ke bagian internal kerajaan, sehingga tidak diadu domba dan terpecah belah layaknya kesultanan-kesultanan di Jawa. Tak heran, Kesultanan Buton dapat bertahan hingga waktu yang cukup lama sampai kebubarannya pada tahun 1960.
Dengan demikian, telah diperoleh konsep pemikiran baru mengenai posisi Buton di antara kesultanan-kesultanan lain di Nusantara pada abad XVII-XVIII dengan mempertimbangkan indikator bidang perdagangan, politik-
pemerintahan, hubungan diplomatik, ekonomi, dan pertahanan yang telah dipaparkan di atas di atas. Kesimpulan dari penelitian ini dapat dijadikan, dasar untuk penelitian berikutnya dengan topik serupa baik yang sifatnya rekonstruktif maupun dekonstruktif terkait dinamika Kesultanan Buton.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih penulis ucapkan pada segenap dewan editor dan reviewer Jurnal Humanis Universitas Udayana yang telah mengkritisi artikel ini dengan saksama dan cepat, sehingga artikel ini dapat dipublikasikan. Terima kasih penulis ucapkan pula pada Prof. Dr. Susanto Zuhdi, M.Hum atas
bimbingannya dan juga berkat adanya karya beliau mengenai Sejarah Butun Abad XVII-XVIII, artikel ini dapat ditulis dan dipublikasikan.
DAFTAR PUSTAKA
Asnan, Gusti. 2009. "Pelabuhan‐
Pelabuhan Kota Padang Tempo Doeloe". Amoghapasa Edisi 13/Tahun XV, hlm: 17-20.
Hasanuddin. 2020. “Forts on Buton Island: Centres of Settlement,
Government and Security in Southeast Sulawesi.” in Forts and Fortification in Wallacea, edited by Sue O’Connor, Andrew
McWilliam dan Sally Brockwell. Canberra: ANU Press.
Indriani, H. (2020). Strategi Sultan Ageng Tirtayasa dalam
Mempertahankan Kesultanan
Banten.
https://doi.org/10.31219/osf.io/gn dc6.
Iriani dan Sritimuryati. 2021. "La Elangi Sultan Buton ke IV". Attoriolog Jurnal Pemikiran Kesejarahan dan Pendidikan Sejarah Vol. 19 No. 2, hlm: 98-111.
Kanumoyoso, Bondan. 2011. "Beyond The City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 16841740". Disertasi. Universiteit Leiden.
Karma. 2017. "Usaha Sultan Ageng Tirtayasa dalam Membangun Ekonomi Kesultanan Banten Abad XVII". Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
Kartodirdjo, Sartono. 1987. Pengantar Sejarah Indonesia Baru 15001900: Dari Emporium Sampai Imperium. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.
Lubis, Nina Herlina. 2020. Metode Sejarah: Edisi Revisi 2020.
Bandung: Satya Historika.
Marhini, La Ode; Syahrun dan Asniati. 2020. "Peranan Sultan Mardan Ali di Kesultanan Buton: 1647 -1654 M". Jurnal Idea Of History Vol 03 Nomor 1, hlm 13-23.
Mujabuddawat, Muhamad Al. 2015. "Kejayaan Kesultanan Buton
Abad ke-17 dan 18 dalam
Tinjauan Arkeologi Ekologi. Jurnal Kapata Arkeologi Vol 11, No 1, hlm: 21-32.
Muliadin, Iwan. 2016. "Pasang-Surut Hubungan Buton–VOC: Studi
Masa Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi (1751-1752, dan 1760-1763). Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah.
Rahman, Aulia Arif. 2011. "Islam dan Budaya Masyarakat Yogyakarta ditinjau Dari Perspektif Sejarah". El Harakah Jurnal Budaya Islam Vol. 13 No. 1, hlm: 1-16.
Suryani, Mardian. 2021. "Perkembangan dan Kebijakan Perekonomian Kerajaan Mataram pada Masa Pemerintahan Sultan Agung". Jurnal Nuansa Vol. XIV No. 2, hlm: 206-217.
Susilowati, Endang. 2004. "Pasang Surut Palayaran Perahu Rakyat di Pelabuhan Banjarmasin, 18801990". Disertasi. Universitas Indonesia.
Wibowo, Tubagus Umar Syarif Hadi. 2018. "Gawe Kuta BaluwartiBata Kalawan Kawis: Sebuah Konsep Historis dan Simbolis". Jurnal Candrasangkala Vol. 4, No. 1, hlm: 69-80.
Zuhdi, Susanto. 1996. Kerajaan Tradisional Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton. Jakarta:
Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan RI.
______________. 1999. "Labu Rope-Labu Wana: Sejarah Butun Abad XVII-XVIII". Disertasi.
Universitas Indonesia.
______________. 2014. Nasionalisme, Laut, dan Sejarah. Depok: Komunitas Bambu.
Discussion and feedback