Deteriorasi Aspek Perlindungan Lingkungan Hidup Akibat Pembatasan Partisipasi Publik dalam Proses Amdal Pasca UU Cipta Kerja
on
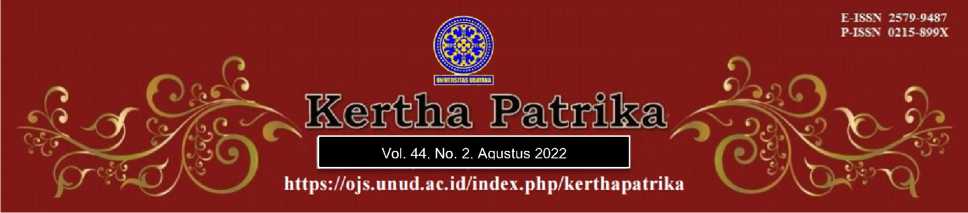
Deteriorasi Aspek Perlindungan Lingkungan Hidup Akibat Pembatasan Partisipasi Publik dalam Proses Amdal Pasca UU Cipta Kerja
Dewi Ari Shia Wase Meliala,1 Shisca Elvetta2
-
1Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, E-mail: dewi19001@mail.unpad.ac.id
-
2 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, E-mail: shisca19001@mail.unpad.ac.id
Info Artikel
Received : 20th September 2021
Accepted : 19th April 2022
Published : 30th August 2022
Keywords :
EIA, Public Participation, Job
Creation Act
Kata kunci:
Amdal, Partisipasi Publik, UU Cipta Kerja
Corresponding Author:
Abstract
Every development activity must always adhere to the principles of sustainable development in the context of implementing environmental protection. Therefore, it is necessary to have a form of study on every business activity that has an important impact on the environment, through an EIA mechanism as an instrument of preventive environmental administration. Seeing the important impact on the environment, it will be a concern and responsibility of all parties (the public) to be involved in the EIA process until making decisions of environmental feasibility as an embodiment of the participatory principle. However, after the Job Creation Act, the involvement of public participation in the EIA process is considered to have been reduced. Based on this problem, this study aims to determine the concept of public participation in environmental permit and the implications of Job Creation Act on the role of public participation in the EIA process. This study uses a normative juridical method in the form of an analysis of the principles, rules, and provisions of laws and regulations, also accompanied by a relevant approach. The result of the study shows that there are three forms of restrictions on public participation in the EIA process after the Job Creation Act. First, restrictions on the preparation stage that only involve directly affected communities. Second, restrictions on community elements in the Environmental Feasibility Test Team, and third is restrictions due to the objection provision that have been removed. These three forms of restrictions by and by affect the reduction of environmental protection.
Abstrak
Setiap aktivitas pembangunan harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, setiap usaha kegiatan yang memiliki dampak penting pada lingkungan memerlukan suatu bentuk kajian melalui sebuah mekanisme Amdal sebagai instrumen administrasi lingkungan yang bersifat preventif. Melihat adanya dampak penting pada lingkungan, tentunya akan menjadi kepentingan dan tanggung
Dewi Ari Shia Wase Meliala, Email :
DOI :
10.24843/KP.2022.v44.i02.p.06
jawab semua pihak (publik) untuk dapat terlibat di dalam proses Amdal hingga pengambilan keputusan kelayakan lingkungan sebagai perwujudan dari asas partisipasif. Pasca UU Cipta Kerja, keterlibatan partisipasi publik dalam proses Amdal dinilai telah direduksi. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep partisipasi publik dalam perizinan lingkungan dan implikasi UU Cipta terhadap peranan partisipasi publik dalam proses Amdal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berupa analisis terhadap asas, kaidah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, juga disertai dengan pendekatan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk pembatasan partisipasi publik dalam proses Amdal pasca UU Cipta Kerja. Pertama, pembatasan pada tahap penyusunan yang hanya melibatkan masyarakat terdampak langsung. Kedua, pembatasan unsur masyarakat di dalam Tim Uji Kelayakan Lingkungan. Ketiga, pembatasan akibat dihapusnya ketentuan upaya keberatan. Dimana ketiga bentuk pembatasan ini yang pada akhirnya berpengaruh terhadap tereduksinya aspek perlindungan lingkungan hidup.
Manusia dan lingkungan adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Ketika manusia lahir dan mengenali lingkungan sebagai tempat keberadaannya pertama kali, maka disanalah ketergantungan terhadap lingkungan pun bermula. Namun sejatinya ketergantungan tersebut merupakan sebuah interaksi yang bersifat dua arah. Dimana manusia sebagai mikrokosmos dan lingkungan tempatnya bernaung berperan sebagai makrokosmos secara tidak langsung telah menggariskan manusia yang tidak akan pernah mampu untuk melepaskan ketergantungannya terhadap lingkungan, pun sebaliknya lingkungan terhadap manusia.1 Pada awalnya relasi antara manusia dan lingkungannya berjalan secara seimbang dan ideal. Namun, akhir-akhir ini hubungan tersebut terjalin kurang harmonis dikarenakan pemikiran revolusioner manusia yang cenderung bersifat eksploitatif terhadap lingkungan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya kekeliruan manusia dalam memandang keterkaitannya dengan lingkungan yang menganggap dirinya terpisah dari lingkungan.2
Pola pikir eksploitatif menempatkan lingkungan sebagai objek yang seringkali diposisikan sebagai sasaran pendayagunaan secara masif oleh manusia. Hal ini secara tidak langsung telah mengisyaratkan adanya pergeseran pandangan masyarakat dalam memandang lingkungan. Dimana menurut Otto Seomarwoto3, terdapat 2 (dua) golongan pandangan manusia dalam memandang lingkungan. Pertama ialah pandangan imanen, yaitu pandangan yang meyakini bahwa manusia dan sistem biosfik sekitarnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena adanya keterkaitan
hubungan fungsional. Pandangan yang kedua adalah pandangan transenden, yaitu pandangan yang meyakini walaupun manusia secara ekologi menyatu dengan lingkungannya, tetapi manusia tetap bagian yang terpisah dari lingkungan. Hal ini dikarenakan manusia menganggap bahwa eksistensi lingkungan hanya untuk didayagunakan seluas-luasnya bagi kepentingan dirinya.4 Pada awalnya, Indonesia meyakini bahwa pandangan yang dianut dalam memandang lingkungan ialah pandangan imanen, dimana kehadiran lingkungan terasa sangat berpengaruh bagi kehidupan. Sehingga lingkungan harus digunakan dengan sebaik-baiknya serta dilestarikan untuk kepentingan masa yang akan datang. Namun, seiring berkembangnya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, pandangan tersebut perlahan-lahan telah bergeser menuju pandangan transenden. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka kerusakan lingkungan hingga deforestasi setiap tahunnya.5
Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai jenis sektor sejatinya merupakan sebuah proses berkesinambungan yang tak ubahnya menimbulkan dampak tertentu bagi lingkungan namun juga sangat memegang kendali terhadap perbaikan pencapaian standar hidup masyarakat. Namun demikian, hal tersebut tidak lantas dapat menjadi alat justifikasi untuk mengorbankan lingkungan. Jika memandang fenomena demikian menggunakan pandangan transenden, tentunya harus terdapat mekanisme preventif yang diciptakan sebagai instrumen perlindungan terhadap lingkungan atas segala dampak yang ditimbulkan dari pembangunan. Atas dasar itulah lahir sebuah konsepsi yang dikenal dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun 1969 dengan menggunakan istilah Environtmental Impact Assessment yang menjadi alat dalam menyusun dan merancang langkah preventif terhadap segala kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas pembangunan.6 Hal ini bermakna bahwa segala aktivitas manusia yang menimbulkan perubahan dan dampak signifikan terhadap lingkungan, harus melalui serangkaian tahap pengkajian terlebih dahulu guna mengidentifikasi segala dampak yang akan timbul baik yang merugikan ataupun bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tentunya tantangan pola pembangunan yang berusaha menyelaraskan antara orientasi keuntungan dengan kebutuhan sosial lingkungan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dimana keterlibatan masyarakat adalah salah satu prinsip dasar dari proses Amdal yang berhasil.7 Melalui keikutsertaan masyarakat dalam proses Amdal, tidak hanya memberikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang dampak lingkungan, tetapi juga memberikan transparansi dalam perizinan lingkungan yang nantinya akan diterbitkan.
Sebagai pihak yang memiliki potensi terdampak paling besar dari adanya aktivitas pembangunan yang melibatkan lingkungan dan alam, manusia sudah barang tentu harus terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan hingga pelaksanaan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung ataupun tidak langsung.8 Hal ini sejatinya telah sejalan dengan asas partisipatif yang terkandung dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut “UU PPLH”). Dimana dengan adanya asas ini, telah membuka ruang bagi seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam proses penyusunan Amdal hingga pengumuman penerbitan surat izin lingkungan atau yang saat ini telah berganti menjadi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.9 Namun tentunya keikutsertaan masyarakat dalam setiap proses tersebut, hanya dapat terealisasikan apabila mekanisme yang diatur dalam regulasi juga menghendaki demikian.
Pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal hingga penerbitan izin sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dimana dalam regulasi ini diatur mengenai keterlibatan dan pengikutsertaan masyarakat terhadap setiap proses Amdal dalam penerbitan izin lingkungan. Dalam proses Amdal yang diatur dalam UU PPLH sendiri terdapat 3 (tiga) tahapan yang kesemua prosesnya melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari tahap penyusunan, penilaian, hingga tahap pengumuman dari penerbitan izin usaha.10 Semenjak disahkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang selanjutnya disebut “UU Cipta Kerja”), beleid ini serentak telah mengubah beberapa substansi pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya yakni mereduksi keterlibatan masyarakat dalam proses Amdal.11 Hal ini tercermin melalui perubahan definisi masyarakat yang dirumuskan dalam UU Cipta Kerja yang secara tidak langsung turut mereduksi ruang keikutsertaan masyarakat sendiri dalam setiap proses penyusunan Amdal hingga penerbitan izin. Perubahan-perubahan inilah yang sejatinya sangat meresahkan berbagai kalangan khususnya para pegiat lingkungan. Dimana undang-undang yang diharapkan dapat merampingkan birokrasi demi mempercepat laju investasi, rupanya tampak tidak beriringan dengan peningkatan kualitas dan harapan hidup serta lingkungan.12
Dengan demikian, penelitian kali ini bertujuan untuk membedah filosofi dan hakikat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan serta menganalisis aturan-aturan perubahan dalam UU Cipta Kerja yang berpotensi terhadap pelemahan perlindungan lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun identifikasi masalah yang akan menjadi objek pengkajian dalam penelitian kali ini, ialah 1) Bagaimana konsep partisipasi publik dalam perizinan lingkungan? dan 2) Bagaimana implikasi UU Cipta Kerja terhadap peranan partisipasi publik dalam proses Amdal?
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang menerangkan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan juga pendekatan konseptual (conceptual approach) yang mencakup analisis terhadap asas dan kaidah hukum yang didasari pada ilmu pengetahuan terkait yang relevan sebagai bahan komparasi dan pengembangan pemikiran dalam analisis ini. Adapun objek dari penelitan hukum normatif sendiri terdiri atas bahan hukum yang bersifat kualitatif berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan sumber hukum primer sendiri didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan sumber hukum sekunder sendiri didasarkan atas hasil-hasil pengkajian literatur hukum dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.
-
3. Hasil Dan Pembahasan
-
3.1. Konsep Partisipasi Publik dalam Perizinan Lingkungan
-
3.1.1. Hakikat Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan
-
-
Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan lingkungan sejatinya telah menjadi ciri yang selalu melekat pada sistem peraturan lingkungan yang ada di seluruh dunia selama beberapa dekade terakhir.13 Dimana keterlibatan publik ini kerap dianggap sebagai salah satu syarat pengambilan keputusan yang demokratis sekaligus dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas dari suatu keputusan.14 Dalam hal tersebut, partisipasi publik jelas sangat memengaruhi kualitas dari suatu keputusan lingkungan karena terdapat informasi-informasi lokal bersifat kedaerahan yang dalam hal ini hanya diketahui oleh masyarakat setempat. Faktanya, ruang keterlibatan masyarakat tersebut acap kali dibatasi oleh serangkaian mekanisme yang mereduksi peran serta masyarakat dengan berbagai alasan, seperti analisis risiko berbasis teknis, pertimbangan besaran biaya dan manfaat yang dibutuhkan, serta adanya gagasan yang menyatakan bahwa masyarakat tidak memiliki keahlian tertentu yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan.15 Sehingga fenomena seperti inilah yang menciptakan eksistensi partisipasi publik menjadi sangat ambigu dan menimbulkan tantangan dalam praktiknya.
Eksistensi pelibatan publik dalam penerbitan suatu keputusan lingkungan sejatinya telah diatur melalui Prinsip 10 Deklarasi Rio, dimana dikatakan bahwa penanganan terbaik dari permasalahan lingkungan ialah dengan melibatkan partisipasi masyarakat yang peduli dan terdampak pada tingkat yang relevan. Bahkan di tingkat nasional, setiap individu harus dipastikan memiliki akses untuk memperoleh informasi mengenai lingkungan yang dimiliki oleh otoritas publik.16 Berdasarkan penjabaran tersebut
sejatinya terkandung 3 (tiga) hak prosedural dalam kaitannya dengan keputusan pemerintah tentang lingkungan, yakni hak atas akses terhadap informasi, partisipasi, dan keadilan.17 Sehingga dalam hal ini negara harus turut serta mendorong kesadaran partisipasi publik, alih-alih menutup aksesibilitas informasi tersebut kepada khalayak umum.18
Hakikat dari partisipasi publik sejatinya inheren dengan konsep pengambilan keputusan yang demokratis.19 Dimana orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi serta berkontribusi dalam membentuk suatu keputusan yang akan memengaruhi lingkungan tempat mereka bernaung. Adapun proses partisipasi masyarakat ini memiliki berbagai macam model yang bergantung pada aliran demokrasi di suatu negara. Seperti misalnya proses partisipasi pada negara dengan aliran demokrasi konstitusional yang menggunakan metode penyatuan berbagai preferensi individual masyarakatnya hingga kemudian dilakukan pemungutan suara. Proses partisipasi yang dianut oleh negara dengan aliran liberalisme menekankan pada adanya proses konsultasi serta analisis pertimbangan terkait biaya-manfaat. Di lain sisi, terdapat juga aliran demokrasi deliberatif yang lebih menekankan pada adanya komunikasi atas tiap argumentasi dan rasionalisasi hingga terciptanya proses tukar pikiran antara masyarakat.20 Dari ketiga aliran ini, efektivitas dari dampak yang ditimbulkan tentunya akan bervariasi. Salah satu model yang selama ini cukup memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pengambilan keputusan lingkungan dan sekaligus telah menjadi role model dalam tata kelola hukum dan lingkungan21 ialah penerapan partisipasi demokrasi deliberatif. Dimana model ini menerapkan pengambilan keputusan yang didasarkan oleh adanya konsensus melalui diskursus yang bertujuan untuk menerima dan menghasilkan pendapat yang rasional dari masyarakat.22
Disamping itu, terdapat juga suatu pendekatan yang mencoba untuk membedah hakikat dari keterlibatan masyarakat secara konseptual terhadap kesuksesan pembangunan serta keberlanjutan lingkungan, yaitu pendekatan partisipatoris. Pendekatan partisipatoris sejatinya merupakan bentuk pendekatan yang menjadi ciri utama dari sifat pembangunan bottom-up yang selama ini diaplikasikan pada aktivitas pembangunan di Indonesia.23 Pada dasarnya pendekatan partisipatif dalam konsep pembangunan, menginisiasi sebuah proses yang berasal dan bermula dari masyarakat, ditujukan oleh masyarakat, dan dilakukan oleh masyarakat. Dari hal tersebut, diperoleh 2 (dua) perspektif yang terkandung dalam makna partisipatoris. Pertama, terdapat proses yang melibatkan partisipasi masyarakat setempat dalam memilih, merancang,
merencanakan hingga melaksanakan suatu proyek atau program yang kedepannya akan berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan setempat. Kedua ialah, adanya umpan balik atau respon yang disampaikan masyarakat yang pada hakikatnya merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan.24
Definisi partisipasi bila merujuk pada Food and Agriculture Organization25, termuat beberapa makna, yakni:
-
a. Partisipasi sebagai bentuk kesukarelaan masyarakat untuk berkontribusi dalam suatu kegiatan atau proyek;
-
b. Partisipasi adalah upaya pemekaan serta peningkatan kemampuan masyarakat dalam menanggapi suatu kegiatan atau proyek;
-
c. Partisipasi sebagai suatu proses aktif dimana masyarakat setempat berkesempatan untuk berinisiatif serta memiliki kebebasan untuk mengutarakannya;
-
d. Partisipasi adalah bentuk diskursus yang dibangun antara masyarakat setempat dengan pamangku kepentingan agar terjalin transfer informasi antara para pihak;
-
e. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat terhadap perubahan yang mereka kehendaki secara sukarela; dan
-
f. Partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat terhadap segala bentuk pembangunan diri, kehidupan, alam dan lingkungannya.
Sehingga dari beberapa penjabaran makna partisipasi tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa pembangunan dengan pendekatan partisipatoris merupakan pembangunan yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk peran serta yang merupakan refleksi dari keterlibatan seluruh stakeholders. Beberapa pengalaman praktis telah membuktikan bahwa model perencanaan yang mengandalkan konsep partisipatoris dengan pendekataan bottom-up yang berorientasi pada proses, terbukti memiliki kelebihan-kelebihan seperti26:
-
a. Data yang terkumpul akan dikaji dan akan digunakan secara langsung oleh pemakai data atau masyarakat;
-
b. Pemecahan masalah yang disusun untuk mengantisipasi kendala dikemudan hari, dapat langsung dicoba dan diterapkan selama berlangsungnya proses tersebut;
-
c. Terjadi proses transfer kepentingan antara stakeholders sehingga terciptanya iklim yang saling memahami terhadap konteks kebudayaan hingga perubahan kondisi;
-
d. Kemudahan dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang akan dapat dipahami secara langsung oleh mereka yang turut serta dalam proses perencanaan; dan
-
e. Merangsang kepekaan masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dikarenakan semakin memahami permasalahan yang berpotensi terjadi di kemudian hari.
Walaupun pada praktiknya pendekatan partisipatoris ini menghabiskan waktu yang cukup panjang dan proses yang alot untuk mencapai tujuan, namun jika melihat dari hasil yang ditawarkan oleh metode ini, justru dapat menghasilkan data yang relevan
dan representatif terhadap apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh para stakeholders.27 Risiko serta tantangan dalam menyepakati suatu rencana pembangunan pada hakikatnya bergantung pada kemunculan konflik kepentingan diantara pihak yang terlibat, baik itu masyarakat, penyandang dana hingga pemerintah. Sehingga dengan demikian, walaupun pendekatan ini dipandang cukup menguras waktu, namun hasil yang akan didapatkan akan sepadan terhadap keberlanjutan proses pembangunan.
Tereduksinya partisipasi masyarakat hingga pelibatan para ahli yang cenderung diunggulkan dalam perumusan Amdal yang dapat ditemukan dalam rumusan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya, pada akhirnya berujung pada pertanyaan apakah pendekatan demokratis yang selama ini dianut dalam UU PPLH telah tergeser secara perlahan oleh pendekatan teknokratis? Pertanyaan tersebut merupakan respon yang wajar terhadap perubahan ketentuan mengenai pembatasan ruang lingkup masyarakat hingga pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal di UU Cipta Kerja, secara khusus pada tahapan penilaian Amdal. Dalam ketentuan di UU Cipta Kerja, peran Komisi Penilai Amdal (KPA) yang bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal diganti oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup (TUKLH). Dimana tim ini merupakan gabungan dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.28 Terdapat beberapa unsur yang hilang jika dibandingkan dengan komposisi tim KPA yang terdapat dalam UU PPLH. Adapun tim KPA sendiri terdiri atas instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak hingga organisasi lingkungan hidup, serta dengan bantuan pakar independen.29
Dengan dibatasinya keterlibatan masyarakat hingga organisasi lingkungan hidup dalam salah satu tahapan penyusunan Amdal ini, ditambah lagi dengan melihat komposisi dari tim TUKLH dalam rumusan UU Cipta Kerja, telah menunjukkan adanya pergeseran pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Amdal secara holistik. Dimana pendekatan demokratis yang dulunya sarat dalam setiap substansi di UU PPLH lambat laun bergeser ke pendekatan teknokratis yang dapat dijumpai dalam UU Cipta Kerja. Pendekatan teknokratis dalam konteks pengambilan keputusan lingkungan ini bermakna bahwa pengambilan suatu keputusan lebih tepat untuk diserahkan kepada sekelompok orang yang memiliki keahlian ilmiah yang relevan dan juga kepada orang yang memiliki keahlian teknis secara khusus pada bidang tersebut.30 Dimana pendekatan ini dipercaya dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan jelas lebih unggul dalam hal efisiensi waktu.31 Pendekatan teknokrasi setidaknya dapat diidentifikasi melalui adanya 2 (dua) pemaknaan terhadap pendekatan tersebut. Pertama, adanya kecenderungan dari pemerintah untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada pihak yang memiliki keahlian ilmiah dan/atau teknologi tertentu dalam hal pengambilan keputusan politis. Kedua, dimana pada akhirnya para ahli
teknologi ini dipandang sebagai suatu entitas organisasi politik yang memiliki peranan secara normatif untuk dapat membuat dan menghasilkan sebuah keputusan yang relevan.32
Teknokrasi di dalam sebuah organisasi politik pada dasarnya merupakan bentuk dari otoritarianisme, dimana proses demokrasi diserahkan secara utuh kepada mereka yang memiliki keahlian ilmiah dan teknis tertentu. Salah satu pendukung pendekatan ini ialah James Lovelock, dimana ia berpandangan bahwa dalam menanggapi isu lingkungan, hal yang paling dibutuhkan ialah adaptasi. Mengingat bahwa permasalahan lingkungan adalah masalah yang membutuhkan penanganan segera, maka sejatinya hanya ada sedikit waktu yang dapat dioptimalkan untuk melakukan adaptasi dalam menanggapi isu lingkungan tersebut. Dalam hal ini Lovelock memandang bahwa pendekatan demokratis harus digantikan dengan rezim eko-otoritarianisme, dimana dalam hal ini pihak yang berkuasa akan memaksakan hal-hal yang dipandang perlu kepada masyarakat.33 Namun lebih daripada itu, terdapat sejumlah pertimbangan yang lebih mengkhawatirkan terhadap pengadopsian teknokrasi baik ke dalam bentuk organisasi politik atapaun kecenderungan dominasi dari pemerintahan yang berkuasa. Mengutip pandangan yang diutarakan oleh Bob Taylor, dimana dikatakan bahwa apabila perumusan suatu kebijakan dan keputusan dikendalikan semata-mata oleh para ahli atau elit tertentu, kebijakan tersebut pasti mewakili kepentingan, perhatian, dan nilai dari sebagian kecil kelompok masyarakat saja.34 Dengan mencabut proses demokrasi, maka hal ini juga sekaligus menghilangkan mekanisme yang sejatinya dapat membantu memeriksa dan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.
Selain adanya dominasi dari para ilmuwan atau ahli-ahli teknis dalam perumusan suatu keputusan lingkungan, teknokrasi juga identik dengan kritik karena dianggap menghilangkan peran masyarakat dalam perumusan dan pengambilan keputusan lingkungan. Dalam penelitiannya, James Ferguson menunjukkan fenomena teknokrasi dalam pembuatan suatu kebijakan yang berbasis data dan bukti ilmiah. Dalam hal ini Ferguson menyebut fenomena teknokrasi ini sebagai mesin anti-politik. Dimana teknokrasi ini berusaha menihilkan political nature dari proses perumusan kebijakan publik.35 Karena itu, mesin anti-politik ini pada akhirnya telah menghadirkan kebijakan-kebijakan yang sangat teknis dan rasional serta menghilangkan unsur-unsur politis (depolitisasi) dalam setiap permasalahan yang ada. Para teknokrat cenderung mengklaim bahwa kebijakan yang mereka rumuskan, merupakan keputusan yang berbasis pengetahuan, bebas nilai dan tentunya rasional, dengan menghilangkan aspek-aspek politis dalam penentuan suatu kebijakan walaupun pada kenyataannya jelas terdapat persoalan politis dalam proses perumusan kebijakan tersebut. Ferguson sangat meyakini bahwa dengan merajalelanya fenomena ini, akan berimplikasi terhadap gagalnya produk kebijakan yang dihasilkan.36
Pada akhirnya, pengetahuan ahli seharusnya tidak menghasilkan suatu solusi ideal dengan kesepakatan penuh seluruh pihak terhadap keputusan tersebut. Karena pada hakikatnya dalam musyawarah apapun, baik dalam hal menyepakati tentang prosedur, prinsip, etika, atau kebijakan berkaitan dengan lingkungan hingga perdebatan mengenai paradigma ekologi, tentu akan terdapat unsur keraguan yang memicu terjadinya diskursus.37 Sangat penting untuk memandang bahwa suatu keputusan tidak boleh dianggap final tanpa adanya sebuah kontestasi. Sehingga kecenderungan pendekatan teknokratis yang memprioritaskan pengetahuan ahli sejatinya telah melanggar kemerdekaan masyarakat dalam mendapatkan hak serta menunaikan kewajibannya. Alih-alih mengasumsikan ’satu untuk semua solusi’, orientasi terhadap ketidaksepakatan dalam merumuskan suatu kebijakan, sejatinya akan lebih kompatibel dengan dinamika kehidupan masyarakat di lapangan.38 Dimana orientasi ini menghadirkan diskursus guna menciptakan kesepakatan yang sekaligus menunjukkan pentingnya persinggungan pemikiran yang dapat membantu memahami lingkungan dari multiperspektif.
-
3.2. Implikasi UU Cipta Kerja terhadap Peranan Partisipasi Publik dalam Amdal
3.2.1. Regulasi mengenai Amdal Pasca UU Cipta Kerja
Perjalanan pembentukan undang-undang yang diinisiasi oleh pemerintah pusat pada tahun 2020, yaitu UU Cipta Kerja, secara sah telah diundangkan dan berlaku sejak tanggal 2 November 2020. UU Cipta Kerja ini merupakan suatu pembaruan dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia karena dibentuk dengan menggunakan teknik legislasi omnibus law. Teknik tersebut digunakan untuk membentuk sebuah produk hukum yang cakupannya telah memuat banyak materi pokok atau subjek bahasan dengan merevisi dan/atau menggabungkan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur secara terpisah. Adapun teknik omnibus law ini dipilih karena memiliki daya tarik yang dianggap dapat mengatasi permasalahan serta hambatan dalam berinvestasi dan berusaha, yang diyakini pemerintah disebabkan oleh terlalu banyaknya peraturan (over regulation) dan tumpang tindihnya peraturan (overlapping).39 Maka dari itu, dibentuklah UU Cipta Kerja ini sebagai realisasi dalam upaya memperbaiki permasalahan sistem regulasi tersebut sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.40 Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah pusat bersama DPR sepakat untuk melakukan penyederhanaan dalam prosedur perizinan berusaha di Indonesia guna memberikan kemudahan bagi para pelaku ekonomi melalui pembentukan UU Cipta Kerja ini.
Penyederhanaan perizinan berusaha yang diatur dalam UU Cipta Kerja ini salah satunya tercermin melalui deregularisasi terhadap sektor perizinan lingkungan. Deregularisasi tersebut dilakukan dengan dimuatnya perubahan ketentuan mengenai materi sektor perizinan lingkungan di dalam UU Cipta Kerja yang secara langsung mengakibatkan beberapa ketentuan yang diatur dalam UU PPLH menjadi diubah dan diganti oleh kententuan baru dalam UU Cipta Kerja. Bentuk upaya penyederhanaan
tersebut dilakukan dengan mengubah standar perizinan berusaha menjadi berbasis risiko berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usahanya41, mulai dari tingkat risiko rendah, menengah, hingga tingkat risiko tinggi. Disamping itu, basis risiko pun dikenakan terhadap ketentuan perizinan lingkungan yang berdampak pada pengaturan Amdal. Sebagaimana perubahan pengertian Amdal dalam UU Cipta Kerja, bahwa Amdal hanya diberlakukan terhadap usaha atau rencana kegiatan yang berdampak penting pada lingkungan hidup. Sementara bagi usaha atau rencana kegiatan yang tidak berdampak penting, cukup dengan memenuhi standar UKL-UPL.42 Adapun mengenai kriteria dampak penting tersebut kini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut “PP PPPLH”) yang disusun menjadi lebih rinci dari ketentuan UU PPLH sebelumnya.
Meskipun diatur lebih rinci dalam peraturan pelaksananya, namun tidak lantas menjadikan suatu peraturan dapat dikatakan sempurna atau lebih baik. Dimana nyatanya, peraturan yang kini berlaku telah banyak mendapat kritikan sejak proses penyusunannya. Kritik tersebut salah satunya tertuju pada adanya pembatasan atau pengurangan bahkan menghapuskan bentuk partisipasi publik di dalam kententuan-ketentuan mengenai proses pelaksanaan Amdal. Contohnya penghapusan unsur masyarakat terdampak sebagai kriteria dampak penting wajib Amdal. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa Amdal dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap usaha kegiatan yang memberikan dampak penting terhadap lingkungan. Dampak penting sendiri adalah perubahan yang sangat mendasar pada lingkungan hidup43 yang kriterianya diuraikan pada Pasal 8 PP PPPLH. Merujuk pada pasal tersebut, kini besarnya jumlah masyarakat terdampak tidak lagi menjadi salah satu dari kriteria dampak penting yang sebelumnya diatur pada UU PPLH ditentukan sebagai kriteria dampak penting wajib Amdal.
Masyarakat sejatinya merupakan pihak yang paling berisiko terkena dampak dari suatu usaha kegiatan, khususnya bagi penduduk setempat yang berada dalam satu wilayah dengan lokasi usaha kegiatan. Selain itu, penduduk juga memiliki peran yang krusial sebagai bagian dari dalam penegakkan perlindungan lingkungan hidup. Salah satunya, peran dalam keterlibatan selama proses Amdal dari suatu usaha kegiatan yang direncanakan sebagai prasyarat diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup. Dalam mendapatkan persetujuan lingkungan sejatinya terdapat berbagai kepentingan dari para pihak, baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha, masyarakat terdampak, hingga lembaga/aktivis lingkungan, yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pembuatannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan sektor perizinan lingkungan merupakan hal yang sensitif, terutama bagi masyarakat terdampak. Selain dari penghapusan besaran masyarakat terdampak dari kriteria dampak penting, terdapat ketentuan lain mengenai pembatasan partisipasi publik pasca dibentuknya UU Cipta Kerja yang menjadi sorotan lainnya, yaitu pembatasan peranan partisipasi masyarakat di dalam proses Amdal. Apabila merujuk pada naskah akademik UU Cipta Kerja, dapat diketahui masalah pembatasan keterlibatkan masyarakat tersebut disebabkan karena adanya anggapan bahwa masyarakat merupakan faktor penghambat investasi oleh
sebagian pihak yang berkepentingan.44 Berikut gambaran singkat proses Amdal sejak proses penyusunan hingga diperolehnya keputusan terhadap uji kelayakan Amdal.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dalam UU PPLH maupun perubahannya Pasal 22 ayat (2) dalam UU Cipta Kerja, dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan peran dari masyarakat. Namun, terdapat perbedaan yang terlihat dari kategori masyarakat yang dapat dilibatkan dalam penyusunan dokumen Amdal. Pada UU PPLH, pihak yang wajib diikutsertakan yaitu pemerhati lingkungan dan masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal selain daripada masyarakat terdampak45. Sementara pasca UU Cipta Kerja, masyarakat yang dapat dilibatkan yaitu hanya bagi masyarakat yang terkena dampak langsung oleh rencana kegiatan usaha.46 Adapun untuk pemerhati lingkungan hidup, peneliti, atau LSM hanya dapat dilibatkan apabila bertindak sebagai pembina maupun pendamping terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung tersebut. Artinya, keterlibatan masyakarat yang tidak terdampak langsung seperti pemerhati lingkungan, peneliti, maupun LSM bukan lagi menjadi pihak yang wajib ada dalam proses penyusunan Amdal pasca UU Cipta Kerja.
Proses pelibatan masyarakat dalam Amdal pada tahap penyusunan formulir kerangka acuan pasca UU Cipta Kerja ini dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu dengan pengumuman rencana usaha kegiatan dan konsultasi publik.47 Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengumuman, masyarakat yang terkena dampak langsung berhak untuk mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha kegiatan. Selain itu, pengajuan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha kegiatan juga dapat disampaikan oleh masyarakat yang terdampak langsung melalui konsultasi publik yang akan diadakan oleh penanggungjawab usaha kegiatan.
Berbeda halnya dengan masyarakat yang terkena dampak langsung, masyarakat yang tidak terdampak langsung hanya diberikan hak untuk menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapannya terhadap suatu rencana usaha kegiatan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan hidup dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman dipublikasikan pada sistem informasi dokumen lingkungan hidup.48 Oleh karena itu, apabila masyarakat yang tidak terdampak langsung ini tidak menjadi pembina maupun pendamping masyarakat yang terkena dampak langsung, maka mereka tidak dapat memberikan masukan ataupun melakukan komunikasi dua arah dengan penanggung jawab usaha kegiatan. Selain daripada itu, selama proses pelibatan masyarakat dalam penyusunan Amdal pun tidak ada ketentuan yang mengharuskan penanggung jawab rencana usaha kegiatan tersebut
untuk menjawab atau menanggapi masukan yang telah diberikan oleh masyarakat. Sehingga tidak menutup kemungkinan menjadi celah yang dapat menyebabkan masyarakat hanya bisa menunggu hasil dari penilaian Amdal pada tahap selanjutnya, tanpa ada kejelasan yang diterima.
UU Cipta Kerja turut mengubah ketentuan mengenai para pihak yang akan melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal, yang semula bernama Komisi Penilai Amdal berubah menjadi Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Awalnya, KPA yang diatur dalam Pasal 29 ayat 1 UU PPLH ini dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya yang terdiri atas unsur: 1. Instansi lingkungan hidup;
-
2. Instansi teknis terkait;
-
3. Pakar dibidang pengetahuan terkait jenis usaha kegiatan yang dikaji;
-
4. Pakar dibidang pengetahuan terkait dampak dari jenis usaha kegiatan yang dikaji;
-
5. Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
-
6. Organisasi lingkungan hidup.
Sementara pasca UU Cipta Kerja ini, TUKLH dibentuk oleh suatu lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat yang terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Dengan demikian, penilaian Amdal pasca UU Cipta Kerja dilakukan tanpa mengikutsertakan kembali adanya unsur peran masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang berpotensi terkena dampak langsung, mereka pun tidak lagi menjadi unsur dari tim penilai sehingga tidak dapat menggunakan hak suaranya sebagaimana yang diatur sebelumnya di dalam UU PPLH.
Proses penilaian dokumen Amdal berdasarkan Pasal 44 ayat (2) PP PPPLH dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahap penilaian administrasi dan substansi. Pada tahap administrasi, penilaian lebih ditujukan mengenai kesesuaian rencana usaha kegiatan, persetujuan teknis, serta keabsahan tanda bukti-bukti berkas.49 Adapun penilaian terhadap substansi meliputi 3 (tiga) hal50, yaitu uji tahap proyek, uji kualitas kajian dokumen Andal, dan persetujuan teknis. Dimana dalam kedua tahapan penilaian tersebut, hanya TUKLH yang diatur memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap dokumen Amdal. Sementara pelibatan masyarakat pemerhati lingkungan dan yang berkepentingan lainnya dikecualikan apabila pada dokumen Amdal telah memuat saran, pendapat, dan tanggapan pada tahap penyusunan formulir kerangka acuan Amdal.51 Padahal, masyarakat terdampak langsung membutuhkan pendampingan dari pihak-pihak yang lebih memahami permasalahan lingkungan, seperti dari pemerhati atau aktivis lingkungan. Sehingga proses penilaian tersebut menimbulkan kondisi yang tidak seimbang diantara para pihak yang berkepentingan, khususnya bagi
masyarakat terdampak langsung yang tidak memiliki kekuasaan. Dengan ketentuan mekanisme seperti demikian, pada proses penilaian dokumen Amdal pasca UU Cipta Kerja pun telah menunjukkan adanya pembatasan terhadap keterlibatan publik untuk ikut berpartisipasi dan mendapatkan haknya atas informasi serta berpendapat.
Sesuai dengan perubahan Pasal 22 ayat (3) dalam UU Cipta Kerja, dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha kegiatan. Kriteria kelayakan tersebut diantaranya meliputi:52
-
1. Kesesuaian lokasi rencana usaha kegiatan dengan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan terkait pemanfaatan ruang;
-
2. Kesesuaian rencana usaha kegiatan dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam;
-
3. Rencana usaha kegiatan yang tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan; dst.
Setelah melalui proses tahapan penilaian dokumen Amdal serta evaluasi, TUKLH akan menyampaikan rekomendasi keputusan hasil yang menyatakan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana usaha kegiatan yang diajukan oleh penanggung jawab usaha kegiatan. Rekomendasi tersebut kemudian akan dijadikan bahan pertimbangan bagi menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk menetapkan surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.53 Dimana surat keputusan yang ditetapkan itu merupakan bentuk dari persetujuan lingkungan dan prasyarat penerbitan perizinan berusaha. Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak diterbitkannya surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan, masyarakat akan menerima pengumuman tersebut melalui sistem informasi lingkungan hidup ataupun cara lainnya yang diatur dalam Pasal 50 PP PPPLH.
Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa UU Cipta Kerja tidak memberikan ruang kesempatan bagi masyarakat untuk meninjau terlebih dahulu hasil uji kelayakan dokumen Amdal sebelum surat keputusan tersebut diterbitkan. Hal ini dicerminkan dari ketentuan perubahan dalam UU Cipta Kerja yang telah menghapuskan ketentuan pada Pasal 26 ayat 4 UU PPLH yang sebelumnya telah memberikan hak bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal sebelum diteruskan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Pada akhirnya, hal tersebut turut meniadakan hak masyarakat untuk mengajukan upaya keberatan kepada TUKLH.
-
3.2.2. Implikasi Pembatasan Partisipasi Publik dalam Amdal terhadap Deteriorasi Aspek Perlindungan Lingkungan Hidup
Lingkungan hidup dipandang sebagai kesatuan ruang dengan segala unsur yang mendukungnya. Menurut pendapat Prof. Munadjat Danusaputro, lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk manusia dan tingkah
perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup, serta kesejahteraan manusia beserta jasad-jasad hidup lainnya.54 Selaras dengan pendapat tersebut, UU PPLH juga mendefinisikan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam, kelangsungan perikehidupan, serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.55 Oleh karena itu, menjaga keberlanjutan dari lingkungan hidup harus dilakukan secara menyeluruh, terlebih dalam menghadapi permasalahan benturan berbagai kepentingan yang timbul dari usaha kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Setiap kegiatan usaha yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus selalu memegang teguh amanat dari Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain dari melihat keuntungan secara ekonomi (economically viable), suatu kegiatan usaha juga harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap lingkungan (environmentally sound) sehingga akhirnya dapat diterima secara social (socially acceptable).56 Dimana 3 (tiga) aspek tersebut merupakan kerangka segitiga dari pilar pembangunan berkelanjutan yang telah diterima secara luas, yang digambarkan sebagai berikut:57
Economic
• Sustainable growth
• Capital efficiency
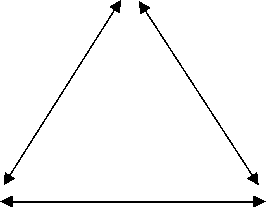
Ecological
-
• Ecosystem integrity
-
• Natural resources
-
• Biodiversity
-
• Carrying capacity
Social
-
• Equity
-
• Social mobility
-
• Participation
-
• Empowerment
Sebagai turunan dari UUD 1945 yang kemudian menjadi payung hukum dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, ketentuan Pasal 12 UU PPLH mengatur bahwa pada dasarnya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam diperbolehkan sepanjang pemanfaatan yang dimaksud dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka pemanfaatan lingkungan hidup untuk suatu usaha kegiatan, pelaku usaha harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan dasar perizininan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko sebagai legalitas bahwa kegiatan usaha tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Sebagaimana tujuan dibentuknya UU Cipta Kerja, persyaratan untuk mendapatkan perizinan berusaha kini mendapat penyederhanaan yang salah satunya dilakukan
terhadap persetujuan lingkungan. Persetujuan lingkungan sendiri merupakan istilah baru yang digunakan pasca diundangkannya UU Cipta Kerja sebagai pengganti dari ketentuan izin lingkungan yang diatur dalam UU PPLH. Berdasarkan perubahan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dalam UU Cipta Kerja, persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau daerah. Adapun bagi rencana kegiatan usaha berdampak penting, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, harus telah melalui uji kelayakan Amdal lebih dahulu untuk mendapat keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai bentuk persetujuan lingkungan. Sehingga Amdal berfungsi sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk mengambil keputusan terkait dengan surat uji kelayakan lingkungan hidup terhadap rencana usaha kegiatan sebagai syarat diberikannya persetujuan lingkungan.
Dalam sistem perizinan lingkungan, Amdal merupakan salah satu instrumen administrasi di dalam penegakan hukum lingkungan58 yang bersifat preventif melalui serangkaian tahapan sebagai bentuk pengawasan/kontrol terhadap risiko dampak suatu usaha kegiatan. Secara teoritis, pengawasan ini mengandung beberapa makna diantaranya menjaga dan mengatur tindakan pemerintah sesuai batas kekuasaannya sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat, kesesuaian antara tindakan dengan ketentuan yang ditetapkan, pencegahan terhadap penyimpangan, serta adanya perbaikan/koreksi melalui tindakan hukum seperti pembatalan atau pemulihan atas penyimpangan yang terjadi.59 Dimana pengawasan ini ditujukan terhadap tindakan pemerintah yang diberi hak dan kewenangan untuk mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yang dalam hal ini sebagai bagian dari pihak penilai Amdal dan pengambil keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagai prasyarat terbitnya persetujuan lingkungan. Dengan kata lain, pengawasan ini bertujuan agar adanya kepatuhan para aparatur pemerintah yang bertugas dengan masyarakat, termasuk pelaku usaha dan pemerhati lingkungan, guna mencapai kemanfaatan dan menjaga orientasi tetap pada kepentingan publik atas keputusan yang diambil.
Pada dasarnya, antara para pihak yang terlibat dalam proses pelaksanaan Amdal, yaitu pemerintah, pelaku usaha, masyarakat terdampak langsung, hingga pemerhati lingkungan, sejatinya membentuk suatu keseimbangan kepentingan.60 Dalam arti pada proses yang menyangkut kepentingan publik ini, tidak ada kedudukan yang menjadi subjek prioritas atau saling berkompetisi untuk didahulukan. Hal itu dikarenakan masing-masing pihak memegang peranan kendali serta tanggung jawab yang sama untuk melindungi keberlangsungan lingkungan hidup. Namun, tidak menutup kemungkinan potensi gesekan antarkepentingan yang berujung pada konflik dapat terjadi, baik secara vertikal maupun horizontal. Berdasarkan hal tersebut, guna memastikan keputusan yang diambil tetap berorientasi kepada kepentingan publik, maka partisipasi publik menjadi kunci penting sebagai pihak yang berkepentingan sekaligus pengawas untuk ikut berperan selama proses penyusunan kerangka Amdal
hingga dihasilkannya keputusan kelayakan lingkungan61 sebagaimana hakikat dari partisipasi publik sebagai perwujudan demokrasi lingkungan.
Meskipun telah ada pemahaman dan kesepakatan bersama mengenai peran penting dari partisipasi publik dalam sektor perizinan lingkungan, namun upaya pembatasan partisipasi publik hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang belum sepenuhnya teratasi. Kasus sengketa antara para nelayan Muara Angke, Kuat, Gobang, Tri Sutrisno, dan Mohammad Tahir sebagai penggugat bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) melawan Pemerintah DKI Jakarta sebagai tergugat, dapat dijadikan sebagai contoh pelaksanaan penerbitan perizinan lingkungan yang membatasi peranan dari partisipasi publik di dalamnya.62 Dimana salah satu poin yang menjadi dasar pengajuan gugatan adalah tidak adanya keterbukaan informasi dan proses penyusunan Amdal yang tidak partisipatif karena tidak melibatkan nelayan dalam rangka akan dilakukannya reklamasi di Pulau G oleh PT Muara Wisesa. Atas dasar tersebut, pada tanggal 15 September 2015 para penggugat mengajukan gugatan kepada PTUN untuk meminta pembatalan izin pelaksanaan reklamasi Pulau G. Setelah melalui proses selama 7 (tujuh) bulan, Adhi Budi Sulistyo selaku ketua majelis hakim akhirnya menyatakan SK yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta itu batal dan tidak sah melalui putusan No. 193/G/LH/2015/PTUN-JKT. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim diantaranya adalah pertimbangan atas penyusuan Amdal yang tidak partisipatif. Menurut hakim, dasar pertimbangan tersebut dikarenakan oleh:
-
a. Pengumuman melalui media cetak Indopos dan sosialiasi yang dilakukan oleh PT Muara Wisesa pada tahun 2012 tidak cukup partisipatif dan transparan karena tidak dilakukan secara intens. Disamping itu, masyarakat Muara Angke pun menyatakan tidak puas dan belum sepakat terhadap rencana pembangunan proyek reklamasi;
-
b. Berdasarkan Notulen Pembahasan Tim Teknis Penilai Amdal DKI Jakarta, masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh tidak dilibatkan dan diikutsertakan dalam pembahasan dokumen Amdal oleh Tim Teknis DKI Jakarta;
-
c. Pemrakarsa dianggap telah melanggar tata cara pengikutsertakan masyarakat dalam proses Amdal secara teknis karena tidak adanya pembahasan penetapan wakil masyarakat sebagaimana yang ditentukan PermenLH No. 17 Tahun 2012;
-
d. Ragam keterlibatan masyarakat harus diperhatikan sehingga saran, pendapat, dan tanggapan secara substantif benar-benar mewakili aspirasi masyarakat.
Disamping itu, hakim pun tidak menemukan adanya bukti-bukti dari pihak tertugat yang menunjukkan bahwa pengumuman yang dilakukan PT Muara Wisesa telah sesuai dengan Pasal 32 UU PPLH dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Berdasarkan dasar-dasar pertimbangan tersebut, hakim memutuskan bahwa izin lingkungan yang dimiliki oleh PT Muara Wisesa telah cacat
formil dikarenakan proses selama penyusunan Amdal yang tidak transparan dan partisipatif.
Kasus di atas merupakan bentuk pelaksanaan proses Amdal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa bentuk pembatasan partisipasi publik sejatinya bahkan dapat terjadi disaat substansi peraturannya telah mengatur hal yang seharusnya dilakukan. Seperti halnya yang terdapat dalam ketentuan di UU PPLH yang telah mengatur mengenai pelibatan masyarakat dalam setiap proses penyusunan hingga penerbitan Amdal. Namun disatu sisi, dalam implementasinya tidak dipungkiri masih kerap terjadi beberapa penyimpangan baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pemrakarsa dari Amdal itu sendiri. Maka dari itu, tidak heran ketika awal mula kemunculan wacana UU Cipta Kerja yang hendak mengubah dan mencabut beberapa regulasi, telah menimbulkan respon yang beragam. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, telah banyak pihak mengkritisi perubahan pada sektor perizinan lingkungan karena penyederhanaan peraturan dan mekanisme melalui perubahannya di dalam UU Cipta Kerja yang justru berimplikasi pada hilangnya hak-hak publik untuk turut serta menjadi bagian dalam pengambilan keputusan kelayakan lingkungan, seperti Amdal. Seharusnya memasukkan pengaturan tentang Amdal dalam cakupan undang-undang bertujuan dalam rangka meningkatkan kepastian prosedur, memperjelas hak dan wewenang, serta sebagai instrumen penegakan lingkungan yang mengikat secara hukum.63 Namun, apabila peraturan yang dibuat ternyata tidak mencerminkan prinsip tersebut, maka akan berdampak pada meningkatnya risiko pada keputusan lingkungan yang dibuat dengan pertimbangan yang tidak tepat karena adanya pembatasan-pembatasan peran dari publik sebagai pengawas.
Sedikitnya, ada 3 (tiga) bentuk pembatasan partisipasi publik selama proses pelaksanaan Amdal pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Pertama, pembatasan publik pada tahapan penyusunan Amdal yang hanya melibatkan masyarakat terdampak. UUD 1945 sendiri mengamanatkan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Landasan konstitusional tersebut menjadi dasar yang fundamental atas jaminan hak setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam menyuarakan pendapatnya mengenai rencana atau kegiatan usaha pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Disamping itu, dasar tersebut pun menujukkan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, melainkan juga setiap warga masyarakat, baik individu maupun kelompok. Sehingga, sejatinya masyarakat yang tidak terdampak langsung pun seharusnya memiliki hak untuk dilibatkan. Terlebih mengingat khususnya masyarakat awam masih banyak yang kurang memahami dan kompeten berkenaan dengan masalah lingkungan sehingga peranan pemerhati lingkungan atau LSM sangat diperlukan keberadaannya. Dengan membatasi keterlibatan hanya bagi masyarakat terdampak, artinya telah terjadi pelanggaran terhadap hak masyarakat lainnya sebagai bagian dari entitas yang menempati lingkungan hidup tersebut. Selain itu, pembatasan ini pun akan berdampak pada berkurangnya kualitas aspirasi dan pertimbangan publik kepada pemerintah dalam pengambilan keputusan lingkungan.
Kedua, pembatasan publik pada unsur penilai Amdal. Tahapan penilaian Amdal merupakan tahapan yang paling strategis dan berpengaruh terhadap hasil keputusan kelayakan Amdal. Akan tetapi, pasca UU Cipta Kerja ini penilai Amdal yang terbentuk dalam TUKLH hanya terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat, tanpa ada unsur dari masyarakat. Padahal peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan pun tidak terlepas dari perannya sebagai pengambil keputusan, artinya masyarakat juga memiliki suatu hak suara dalam forum pengambilan keputusan mengenai kelayakan Amdal. Sehingga apabila merujuk pada konsep pendekatan dalam proses pelaksanaan Amdal, menunjukkan bahwa pasca berlakunya UU Cipta memang terjadi suatu pergeseran pendekatan ke arah teknokratis terhadap model yang kini diterapkan.
Menurut Suparto Wijoyo, tindakan pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan harus bertumpu pada good environmental governance, yang salah satu prinsipnya adalah adanya keterbukaan publik.64 Bentuk dari keterbukaan publik diantaranya dapat meliputi akses terhadap dokumen, informasi, pengambilan keputusan, serta sarana konsultasi dalam proses pembuatan kebijakan. Disamping itu, dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio pun dimaklumatkan bahwa setiap warga masyarakat seharusnya memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan informasi dan mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.65 Berdasarkan prinsip tersebut, seyogyanya negara yang menganut pada sistem good environmental governance dan mengadopsi Prinsip 10 Deklarasi Rio akan memperhatikan pelibatan peran serta masyarakat ke dalam unsur penilai Amdal untuk pengambilan keputusan lingkungan terhadap dokumen Amdal sebagai instrumen di sektor perizinan lingkungan.
Ketiga, pembatasan publik dengan dihapusnya upaya keberatan terhadap dokumen Amdal. Keberatan merupakan upaya awal dari penegakan hukum administrasi yang penting dan mendasar. Hal itu karena upaya keberatan lebih ditujukan kepada tindakan mencegah dampak risiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan akibat diterbitkannya keputusan kelayakan lingkungan hidup.66 Dengan kata lain, upaya keberatan ini bertujuan agar para pihak pengambil keputusan dapat mempertimbangkan kembali potensi risiko yang akan terjadi dari suatu usaha kegiatan berdasarkan hasil penilaian dari dokumen Amdal. Pada ketentuan sebelumnya, hak masyarakat untuk mengajukan keberatan sejatinya tertuang dalam Pasal 65 UU PPLH yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Selain itu, Pasal 26 ayat (4) PPLH pun menegaskan setiap masyarakat dapat mengajukan keberatan terhadap dokumen Amdal. Sementara pasca UU Cipta Kerja berlaku, hak masyarakat dalam melakukan upaya keberatan telah dihapuskan sehingga mengakibatkan hanya tersisa satu jalan bagi masyarakat untuk mengajukan pembelaan atas ketidaksetujuannya terhadap hasil penyimpangan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Jalan yang tersisa tersebut adalah dengan mengajukan gugatan administrasi kepada lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk meminta pembatalan keputusan lingkungan sebagai suatu keputusan tata usaha negara.
Akan tetapi, kiranya perlu diulas terlebih dahulu apakah hak masyarakat mengajukan gugatan ke PTUN masih dapat dilakukan mengingat perubahan dalam UU Cipta Kerja justru telah menghapus ketentuan Pasal 38 UU PPLH yang menyatakan izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan PTUN. Banyak orang berpikiran penghapusan pasal tersebut sama dengan menghapus hak setiap masyarakat untuk mengajukan gugatan. Namun, sejatinya antara izin lingkungan dalam UU PPLH dengan persetujuan lingkungan dalam UU Cipta memiliki persamaan konsep atau makna. Menurut Alexander Charles Kiss dan Dinah Shelton, persetujuan lingkungan juga merupakan wujud kekuasaan formal dari tindakan pemerintah, diantaranya berupa izin, lisensi, dan sertifikasi.67 Selain itu, dalam UU Cipta Kerja pun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa persetujuan lingkungan menjadi objek yang dikecualikan untuk digugat ke PTUN. Oleh karena itu, persetujuan lingkungan tetap merupakan bentuk dari keputusan administrasi negara68 yang merujuk pada UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan.
Meskipun demikian, terdapat konsekuensi dari jalan upaya yang hanya melalui gugatan kepada PTUN. Dalam hukum acara peradilan tata usaha negara terdapat asas praduga rechmatig, yaitu vermoden van rechmatigheid atau praesumptio iustae cause. Artinya, setiap tindakan dari penguasa harus selalu dianggap sah hingga ada putusan yang membatalkannya.69 Oleh karena itu, gugatan terhadap keputusan persetujuan lingkungan tidak akan lantas menunda pelaksanaan dari keputusan tersebut. Sehingga selama putusan belum dijatuhkan, usaha kegiatan yang telah mendapat persetujuan tetap dapat berjalan. Akibatnya bentuk penegakan terhadap lingkungan hidup bukan lagi bersifat preventif, melainkan represif dalam bentuk pemulihan bilamana terjadi adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Amdal merupakan sarana yang fundamental dalam upaya perlindungan lingkungan hidup sebagai langkah preventif terhadap setiap usaha kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Untuk menghasilkan Amdal yang baik, maka peran partisipasi publik jelas sangat diperlukan dalam pengambilan suatu keputusan lingkungan yang demokratis. Namun, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam UU Cipta kerja ini sarat akan pembatasan terhadap hak-hak dari publik untuk terlibat dalam proses Amdal, yaitu (1) pembatasan publik pada tahapan penyusunan Amdal yang hanya melibatkan masyarakat terdampak langsung, (2) pembatasan publik pada Tim Uji Kelayakan Lingkungan yang terdiri atas unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat, tanpa ada unsur dari masyarakat, dan (3) pembatasan publik akibat dihapusnya upaya keberatan terhadap hasil penilaian dokumen Amdal yang menyebabkan masyarakat harus menempuh penyelesaian sengketa melalui PTUN sebagai satu-satunya jalan. Pembatasan-pembatasan tersebut
pada akhirnya dapat menimbulkan risiko besar terhadap menurunnya aspek kualitas keputusan lingkungan, yaitu tidak mencerminkan kepentingan suara publik yang demokratis. Selain itu, penyederhanaan proses berusaha melalui pemangkasan pengambilan keputusan tanpa peranan partisipasi publik akan berimplikasi terhadap peningkatan risiko dampak lingkungan hidup akibat suatu usaha kegiatan karena hanya mengedepankan percepatan, tanpa memperhatikan pertimbangan publik secara matang.
Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Buku
Danusaputra, M. (1980). Hukum Lingkungan, Buku 1: Umum, Bandung: Binacipta.
Fadhli, M., Mukhlish, & Lutfi, M. (2016). Hukum & Kebijakan Lingungan, Malang: UB Press.
Husin, S. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika.
Machin, A. (2013). Negotiating climate change: Radical democracy and the illusion of consensus. Zed Books Ltd.
Mikkelsen, Britha. (2011). Metode penelitian partisipatoris dan upaya pemberdayaan: Panduan bagi praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
Rahmadi, T. (2015). Hukum Lingkungan di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers, p. 17.
Serageldin, IN. (1996). Sustainability and the Wealth of Nation: First Steps in an Ongoing Journey, Washington DC: The World Bank.
Siahaan, N.H.T. (2006). Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Cet. I. Jakarta: Pancuran Alam.
Sukirno. (2018). Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat, Cetakan Kesatu. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Jurnal
Armeni, C. (2016). Participation in environmental decision-making: Reflecting on planning and community benefits for major wind farms. Journal of Environmental Law, 28(3), 415-441, doi: 10.1093/jel/eqw021.
Baber, W. F., & Bartlett, R. V. (2020). A rights foundation for ecological democracy. Journal of Environmental Policy & Planning, 22(1), 72-83.
Baihaki, M. R. (2021). Persetujuan Lingkungan Sebagai Objectum Litis Hak Tanggung Gugat Di Peradilan Tata Usaha Negara (Telaah Kritis Pergeseran Nomenklatur Izin Lingkungan Menjadi Persetujuan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). Majalah Hukum Nasional, 51(1), 1-20, https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.137.
Dudayev, R. (2016). Anotasi Putusan Perkata Tata Usaha Negara antara KUAT, CS. Melawan Pemerintah DKI Jakarta Tentang Pembatalan Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Jurnal Hukum Lingkungan. 3(1).
Ernawati, E., & Kurniawan, T. (2002). Partisipasi Publik, Konsep dan Metode. MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan, 18(1), 1-30.
Effendi, A. (2013). Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Perspektif, 18(1), 14-22, http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v18i1.110.
Kumar Dara, P., Reddy, T. B., & Gelaye, K. T. (2017). Public participation in environmental impact assessment-legal framework. International Journal of Research -GRANTHAALAYAH, 5(5), 270–274,
https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v5.i5.2017.1858.
Machin, A., & Smith, G. (2014). Ends, Means, Beginnings: Environmental Technocracy, Ecological Deliberation or Embodied Disagreement. Ethical Perspectives, 21(1), 4772.
Nugroho, W., Nurlinda, I., Nugroho, B. D., & Hadi, I. (2017). Judge optics on environmental dispute dispute objects, expiration and community participation principles in the issuance of environmental document processing on the case of kendeng. Jurnal Cita Hukum, 5(2), 331-362,
https://doi.org/10.15408/jch.v5i2.7093.
Pickering, J., Bäckstrand, K., & Schlosberg, D. (2020). Between Environmental and Ecological Democracy: Theory and Practice at the Democracy-Environment Nexus. Journal of Environmental Policy & Planning, 1(22), 1-15.
Putra, A. (2020). “Penerapan Omnibus Law dalam Upaya Reformasi Regulasi”, Jurnal Legilasi Indonesia, 17(1), 1-10.
Richardson, B. J., & Razzaque, J. (2006). Public Participation in Environmental DecisionMaking. Environmental Law for Sustainability, 6, 165-194.
Rusdiana, D., & Nugraha, S. (2021). Identifikasi Pelanggaran AMDAL Mega Proyek Wisata Pulau Komodo Nusa Tenggara Timur. Jurnal Identitas, 1(1), 42-52.
Rusdina, A. (2015). Membumikan Etika Lingkungan Bagi Upaya Membudayakan Pengelolaan Lingkungan yang Bertanggung Jawab. Jurnal Istek, 9(2), 244-263.
Susila Wibawa, K. C. (2019). Mengembangkan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Pembangunan Berkelanjutan. Administrative Law and Governance Journal, 2(1), 79–92, https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.79-92.
Website Resmi
Dendy Raditya Atmosuwito. (2020, Sep 23). Teknokrasi Jelas Masih Perlu tapi Bukan Versi Orde Baru. Retrieved from http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-
2/politik-sains-kebijakan/1418-teknokrasi-jelas-masih-perlu-tapi-bukan-versi-orde-baru, diakses 23 Juli 2021.
DW Made for Minds. (2021, Feb 26). Analisis: Pandemi COVID-19 Tahun 2020 'Menghancurkan' Hutan Dunia. Retrieved from
https://www.dw.com/id/pandemi-covid-19-tahun-2020-menghancurkan-hutan-dunia/a-56710524, diakses pada 23 Juli 2021.
Grita Anindarini Widyaningsih. (2021, Jan 11). Partisipasi Publik dalam Penyusunan Amdal Pasca UU Cipta Kerja pada Diskusi Publik “Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker”. Retrieved from https://leip.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Partisipasi-Masyarakat-Dalam-Amdal-Pasca-UUCK-ICEL-110121-compressed.pdf, diakses 25 Juli 2021.
Lembaga Kajian dan Advokasi Independen Peradilan. (2021, Jan 12). Diskusi Publik “Izin Lingkungan Hidup UU Ciptaker. Retrieved from https://leip.or.id/diskusi-publik-izin-lingkungan-hidup-uu-ciptaker/#_ftn3, diakses pada 25 Juli 2021
UN Environment. (2018). Assessing Environmental Impacts - A Global Review of Legislation, Nairobi, Kenya, p. 3. Retrieved from https://www.unep-wcmc.org/resources-and-data/assessing-environmental-impacts--a-global-review-of-legislation, diakses pada 28 Juli 2021.
Regulasi
Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Fao Forestry, Food And Agriculture Organization Of The United Nations, Paper 90, 1998.
Deklarasi Rio
Jurnal Kertha Patrika, Vol. 44, No. 02 Agustus 2022, h. 209-231
Discussion and feedback