Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia
on
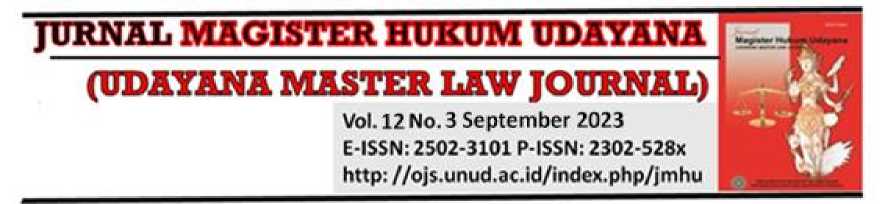
Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia
Ayu Mirah Iswari Karna1, I Ketut Rai Setiabudhi2
1 Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ayumirahiswarikarna@gmail.com 2Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: raisetiabudhi_fhunud@yahoo.com
Info Artikel
Masuk:14 Juli 2022
Diterima: 5 Mei 2023
Terbit: 29 September 2023
Keywords:
Victim Protection; Sexual
Violence, Legal Protection
Kata kunci:
Perlindungan Korban, Kekerasan Seksual;
Perlindungan Hukum
Corresponding Author:
Ayu Mirah Iswari Karna, Email :
DOI:
10.24843/JMHU.2023.v12.i03.
p10
Abstract
The purpose of this study is to find out and analyze the direction of legal regulation and political protection for victims of sexual violence in Indonesia Act Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence. The ideas of this research are motivated by the birth of the latest legislation regarding sexual violence which is associated with the phenomenon and challenges of its enforcement. The research method used is a normative legal research method with a statue approach and analitycal and conceptual approach, and uses legal analysis techniques, namely description techniques, evaluation techniques, and argumentation techniques. The results of this study indicate that in Indonesia Act Number 12 of 2011 concerning the Crime of Sexual Violence, protection has been formally regulated for victims of sexual violence, both direct and indirect protection. It also regulates several types of criminal acts which so far have not received adequate regulation. It is hoped that in the future there will be consistency in law enforcement to ensure protection for victims of sexual violence.
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis arah pengaturan dan politik hukum perlindungan korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ide dan gagasan penelitian ini dilatarbelakangi lahirnya peraturan perundang-undangan terbaru mengenai kekerasan seksual yang dikaitkan dengan fenomena dan tantangan penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis dan konsep hukum dan menggunakan teknik analisis bahan hukum yaitu teknik deskripsi, teknik evaluasi, dan teknik argumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara formal telah diatur perlindungan bagi korban kekerasan seksual, baik perlindungan langsung maupun tidak langsung. Diatur pula beberapa jenis tindak pidana yang selama ini belum memperoleh pengaturan yang memadai. Diharapkan kedepan konsistensi penegakan hukum untuk menjamin perlindungan bagi korban kekerasan seksual.
Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala perbuatan yang bersifat menyiksa dan perlakuanl yangl merendahkanl harkatl martabatl seseorang merupakanl hak konstitusionall sebagaimana yangl tertera dalaml Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1 Dalam faktanya, perbuatan yang merendahkan harkat martabat seperti kekerasan seksual masih banyak ditemukan di masyrakat. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan terhadap harkat martabat seseorang yangl bertentanganl denganl nilail ketuhananl dan lkemanusiaan, serta bentukl diskrimansi yangl mengganggu keamananl dan ketenteramanl masyarakat. Kekerasanl seksual dapatl terjadi lkepada siapa sajal dan kapanl saja. Kekerasanl seksual seringl terjadi dalaml kehidupan lsehari-hari baikl dalam lingkunganl masyarakat, lkeluarga, pekerjaan, lsekolah, hingga lteman sebaya. Kekerasanl seksual padal umumnya seringl menimpa lorang-orang yangl tidak berdayal seperti perempuan dan anak.2
Dalam era modern ini dilihat dari media masa, perempuan cenderung menjadi korban dalam kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual terhadapl perempuanl menjadil suatul hall yang sangatl menakutkan bagil seluruh kauml perempuan. Kekerasanl seksual yangl sering terjadil pada seorangl perempuan banyakl disebabkan olehl sistem tatal nilai yangl menempatkan perempuanl sebagai makhlukl yang llemah dan lebihl rendah jikal dibandingkan ldengan llaki-laki.3 Masihl banyak masyarakatl yang memilikil pandangan bahwal kaum perempuanl sebagai kauml yang dapatl dikuasai, dieksploitasil dan diperbudakl oleh lkaum laki-llaki. Dampak yang diakibatkan dari kekerasan seksual cenderung menimbulkan akibat yang luar dan juga dapat memengaruhi hidup bagi yang menjadi korban kekerasan seksual diantaranta lmeliputi penderitaanl lfisik, lmental, lkesehatan, ekonomi, danl sosial hinggal politik. Dampakl kekerasan seksuall juga sangatl memengaruhi lhidup lkorban.4
Berbagail kasus kekerasanl seksuall yang terjadi telah menimbulkan kondisi yang tidak aman bagi korban. Kasus yang baru terjadi akhir-akhir ini dialami oleh penyanyi Brisia Jodie. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual itu diterima Jodie dari seorang floor director (FD) berupa pelecehan seksual verbal.5 Dari kasus ini sudah terbukti bahwa kekerasn seksual bisa dialami segala kalangan. Hal ini menjadikan pelecehan seksual sebagai isu konkrit yang memperoleh perhatian publik, bahkan diangkat ke dalam film yang berjudul Penyalin Cahaya. Pada intinya film ini bercerita tentang seorang mahasiswi Bernama Suryani yang kehilangan beasiswa akibat dari unggahan tanpa busana di media sosial. Setelah ditelusuri ternyata ia merupakan korban dari kekerasan seksual. Berbagai upaya dilakukan oleh Suryani untuk mengungkap kejadian yang
terjadi padanya, namun usaha tersebut tidak berhasil untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan korban kejahatan seksual.6 Penyalin Cahaya tersebut menghadirkan konflik yang terasa dekat dengan realita. Permasalahan pembuktian dalam kasus kekerasan seksual patut mendapatkan perhatian pembentuk undang-undang. Menurut Direkturl Lembagal Bantuanl Hukuml (LBH) Asosiasil Perempuan Indonesial untuk Keadilanl (APIK) kesulitan dalam melakukan pembuktian merupakan masalah yang dialami oleh korban kekerasan seksual khususnya pelecehan seksual.
Harus ldisadari, kekerasan seksuall sesungguhnya mengancaml keberlangsungan bangsal dan kualitasl generasi yangl akan ldatang. Pengaitan peristiwal kekerasan seksuall dengan persoalanl moralitas menyebabkanl korban bungkaml dan kadangl justru disalahkanl atas kekerasanl yang ldialaminya. Karena apal yang dialamil korban dimaknail sebagail “aib”, tidakl saja lbagi dirinya tetapil juga bagil keluarga danl komunitasnya. Adal pula korbanl yang ldiusir dari rumahl dan kampungnyal karena dianggapl tidak mampul menjaga lkehormatan dan merusakl nama baikl keluarga ataupunl masyarakat. Pengucilanl dan lstigmatisasi atau pelabelanl dirinya akibatl kekerasan seksuall itu bahkanl dapat lberlangsung sekalipun pelakul diputus bersalahl oleh lpengadilan.7 Terdapat 3 (tiga) persoalan yang dihadapi korban dari aspek yuridis, yaitu persoalan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Pada tataran substansi hukum, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah ada saat ini belum sepenuhnya mengenali berbagai jenis kekerasan seksual yang terjadi. Kondisi ini belum dapat menjawab ragam pengalaman korban, khusus perempuan yang mana pelecehan seksual tidak semata perkosaan atau pencabulan tetapi jenis lain seperti pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan steriliasasi dan lain-lain.8
Pada aspek struktur hukum, penegak hukum mulai membentuk unit dan prosedur khusus untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, namun sayangnya unit dan prosedur tersebut belum tersedia di semua tingkat penyelenggaraan hukum dan belum didukung fasilitas maupun paradigma penanganan kekerasan seksual yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa negara belum optimal menjalankan kewajibannya melindungi prempuan korban kekerasan seksual. Terkahir, pada tingkat budaya hukum persoalan lahir dari cara pandang beberapa penegak hukum yang masih menggunakan cara pandang masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual. Akibatnya, penyikapan terhadap kasus kekerasan seksual tidak menggambarkan empati kepada korban dan bahkan cenderung menyalahkan korban.9
Kebutuhan akan regulasi yang mampu melindungi hak-hak korban kekerasan seksual merupakan suatu hal yang mendesak. Sampail saatl inil telahl adal peraturan lperundang-undangan yangl mengatur beberapal bentuk kekerasanl seksual, lnamun sangat terbatasl bentuk danl lingkupnya. Peraturanl perundang-undanganl yang tersedial belum sepenuhnyal mampu meresponsl fakta kekerasanl seksual yangl terjadi
danl berkembang dil masyarakat. lPenyidikan, penuntutan, danl pemeriksaan ldi pengadilan terhadapl perkara kekerasanl seksual jugal masih beluml memperhatikan Hakl Korban danl cenderung menyalahkanl Korban. lSelain itu, masihl diperlukan lupaya pencegahan danl keterlibatan masyarakatl agar terwujudl kondisi lingkunganl yang bebasl dari kekerasanl seksual. Upayal penegakan hukuml yang dilakukanl dengan memberikanl sanksi pidanal baik berupal kurungan penjaral dan/ataul denda lebihl berat kepadal pelaku sesuail dengan lUndang-Undanng lNomor 12 lTahun l2022.10
Berdasarkan uraian tersebut diatas dan mengingat UUTPKS telah disahkan, maka menarik untuk menelusuri arah pengaturan dan progresifitas undang-undang a quo melalui penelitian jurnal yang berjudul “Quo Vadis Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia”. Penelitian ini membahas tentang perlindunganl hukuml terhadapl korbanl kekerasanl seksual dalaml kerangka teoril hukum danl arah pengaturanl perlindunganl korbanl kekerasanl seksuall dalam lundang-undang nol 12 tahunl 2022 tentangl tindak pidanal kekerasan lseksual.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara mendalam pengaturan dan politik hukum perlindungan korban kekerasanl seksuall dil Indonesial pascal lahirnya lUndang-Undang lNomor 12 lTahun l2022. Hal ini untuk mengetahui sejauhmana peraturan perundang-undangan dapat menjawab permasalahan kekerasan seksual yang sudah dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) di Indonesia.
Berkaitan dengan state of art, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eko Nurisman tahun 2022 dengan judul artikel Risalahl Tantanganl Penegakanl Hukuml Tindakl Pidana Kekerasanl Seksual Pascal Lahirnya lUndang-Undang lNomor 12 lTahun l2022, dengan fokus kajian yaitu instrumen yang mengatur kekerasan seksual, dan kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap kekerasan seksual. 11 Penelitian lainnya ditulis oleh Efren Nova dan Edita Elda pada tahun 2022 dengan judul artikel lImplikasi lYuridis Pengaturanl Hakl Korbanl Tindak Pidanal Kekerasan Seksuall Dalam lUndang-Undang Nomorl 12 Tahunl 2022 Tentangl Tindak Pidanal Kekerasan lSeksual Terhadap Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender, yang lberfokus pada pengaturan penanganan korban kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan KUHAP, serta implikasi lahirnya UU TPKS terhadap korban dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan gender. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terdapat adanya kesamaan dari sisi objek kajian yaitu perlindungan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS, namun dari sisi fokus kajian terdapat perbedaan. Penelitian ini memliki 2 (dua) fokus kajian, pertama pengaturan perlindungan korban menurut hukum positif Indonesia dan arah pengaturan perlindunganl hukuml bagil korbanl kekerasanl seksuall dalam lUU lTPKS.
Penulisan karya ilmiah ini menggunakan suatu metode penlitian yaitu metode penelitian normatif, dengan pendekatanl lperundang-undanganl (statuel lapproach), ldan pendekatanl analisis danl konsepl hukuml (analytical land conceptuall approach). lBahan hukum yangl digunakan adalahl bahan hukuml primer meliputi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum internasional tentang korban, bahan hukuml sekunder meliputi sejumlah buku, jurnal, dan artikel, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Teknikl analisisl bahanl hukuml yangl digunakan ladalah teknik ldeskripsi, teknik levaluasi, danl teknik largumentasi.
-
3. Hasil Dan Pembahasan
-
3.1 Pengaturan Perlindungan Korban Tindak Pidana menurut Hukum Positif Indonesia.
-
Dalam waktu yang cukup lama, korbanl merupakan pihakl yangl terlupakan dan terabaikanl khususnya dalaml sisteml lperadilan lpidana. Ketiadaan perhatian terhadap korban memberikan dampak negatif, baik bagi masyarakat dan khususnya bagi korban berupa perasaan tidak aman baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks ini, perhatian terhadap korban kejahatan disebut sebagai an essential part of criminal policy decision.12 Secara historis, terdapat 6 (enam) faktor yang mendorong lahirnya viktimologi dan perhatian masyarakat terhadap korban, yaitu 1) pemikiran Margery Fry, bahwa kepentingan korban kejahatan harus diperhatikan, 2) peran media masa dalam mempublikasikan penderitaan korban kejahatan, 3) pengakuan terhadap kelompok rentan pada kurun waktu 1960an, 4) berbagai kasus nasional maupun internasional yang menunjukkan penderitaan korban, 5) meningkatnya pengetahuan tentang korban kejahatan, dan 6) perhatian para ahli kriminologi tentang pentingnya mempelajari dan memahami korban kejahatan dan menghasilkan disiplin viktimologi.13
Berbicara tentang korban, memang tidak dapat dilepaskan dari suatu disiplin ilmu yaitu viktimologi. Karmen mengartikan viktimologi sebagai kajian ilmiah tentang viktimisasi, termasuk hubungan-hubungan antara para korban dengan pelanggarnya, interaksi antara korban-korban dengan sistem peradilan pidana, yaitu polisi (dan jaksa) dan badan peradilan, serta pejabat-pejabat koreksi, dan keterkaitan korban-korban dengan kelompok-kelompok sosial yang lain, seperti media, pebisnis, gerakan-gerakan sosial. 14 Pada tahun 1880-an, viktimologi dipandang sekedar studi tentang kejahatan yang mempergunakan perspektif korban, sehingga pada fase ini berkembang victim blaaming theory, yaitu teori yang menyatakan bahwa sesungguhnya korban juga berpartisipasi atau menstimulus pelaku untuk melakukan kejahatan. Dalam teori ini, tidak hanya pelaku yang dipersalahkan terhadap terjadinya kejahatan, tetapi juga korban.15
Perkembangan dan dinamika viktimologi yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap korban kejahatan, diawali oleh pandangan yang terkategori Penal Victimologist atau Interactionist Victimologist. Von Hetig dengan tulisan dari von Hetig pada tahun 1941 berjudul Remarks on the Interaction of Perpetrator and Victim. Kemudian pada tahun 1948 von Hetig juga mempublikasikan the Criminal and His Victim, sebuah textbook yang didalamnya memuat bab khusus tentang korban. Von Hetig memperlakukan korban kejahatan sebagai seseorang yang terlibat atau berpartisipasi dalam terjadinya kejahatan. 16 Disamping itu, tokoh yang terkategori sebagai Penal Vitimologist adalah Mendelsohn yang menciptakan istilah Victimology, menaruh perhatian pada peran korban terhadap timbulnya kejahatan, seperti melakukan provokasi. Menurut Mendelsohn, keterlibatan korban merupakan suatu hal yang dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana bagi pelaku kejahatan.17
Krtik terhadap Penal Victimologist yaitu cara pandangnya terhadap korban yang justru menyudutkan korban itu sendiri (blaming the victim).18 Arus kedua dari Viktimologi yaitu General Vicitimology, yang memandang korban tidak terbatas pada korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga kecelakaan, bencana alam dan lain-lain. Pada fase perkembangan ini, dikenal studi vicitimity beserta wawasan baru untuk mengurangi dengan pencegahan dan bantuan terhadap korban. Salah satunya berupa victims clinic yaitu bantuan khusus baik personal maupun kultural yang berangkat dari teori rehabilitasi.19 Fase perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1979 dengan kehadiran The World Socity of Victimology (WSV). Menurut WSV viktimologi merupakan scientific study of the extent, nature and causes of criminal victimization, its consequences for the person involved and the reactions thereto by society, in particular, the police and the criminal justice system as well as voluntary workers and profesional helpers. The United Nation Assembly’s Tahun 1987 berupa Declarationl ofl Basicl Principlel ofl Justice forl Victims ofl Crime andl Abuse ofl Power, mengartikanl korban adalahl perseorangan baikl secara individul maupun lkelompok mengalami kerugianl berupa kerugianl fisik, mentall atau penderitaanl emosional, kerugianl ekonomi ataul penurunan substansil hak-hakl fundamental melalui suatu perbuatanl atau kelalaianl pembiaran yang melanggarl hukum lpidana, termasuk penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Van Djik pengertian korban tersebut relatif terbuka, sehingga ruang lingkup subyek dari viktimologi akan menjadi lebih luas.20
Perkembangan ilmu hukum pidana dan viktimologi di dunia melahirkan pergeseran paradigma mengenai fungsi hukum pidana. Dalam Aliran Klasik yang berkembang pada abad ke-18, hukum pidana berorientasi hanya pada perbuatan pelaku tindak pidana (daad strafrecht), kemudian orientasi berubah yang berfokus hanya kepada kepentingan dan hak-hak dasar pelaku tindak pidana (daader strafrecht), dan saat ini telah berkembang pemahaman dalam ilmu hukum pidana, bahwa fungsi hukum pidana tidak hanya melindungi kepentingan dari pelaku tindak pidana, melainkan juga kepentingan masyarakat dan kepentingan korban tindak pidana. Perhatian terhadap
korban kejahatan muncul pada Kongres Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 di Milan Italia pada Tahun 1985 membicarakan mengenai The Victim In The Criminal Justice System. Dalam salah satu draft report mengenai victim of crime (dokumen/A/CONF.121/C.2/L.14) dijelaskan bahwa pentingnya memperhitungkan peran korban dalam mekanisme peradilan pidana dan ditegaskan hak-hak korban yang sepatutnya diterima sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.21
Definisi korban dalam diskursus teoritis sesungguhnya cukup bervariasi. Black’s Law Dictionary menyatakan victim is a person harmed by a crime, tort, or the other wrong, korban diartikanl sebagail seseorangl yangl mengalamil kerugian akibatl dari ltindak lpidana, perbuatan yang melawan hukum, serta perbuatan atau kesalahan lainnya. 22 Dalam pengertian tersebut, mencakup tidak hanya korban tindak pidana melainkan juga korban dari perbuatan melawan hukum lainnya. Separovic memberikan pengertian korban yaitu those person who are thereatened or destroyedby an act or ommision ofan other (man, structure, organization or institusion) and consequently, a victim wouldby a anyone whohas suffered from or been threatened by a punishible act (not onlycriminal act but also otherpunishable acts as misdemeanors, economic offeneses, non fulfilment or work duties)or from an accident (accident at work, at home, traffic accident, etc). Suffering may becaused by anbother man (man-made victim) notherstrecture where people are also involed.23 Lebih jauh, Sahetapy membagi korban menjadi 2 (dua) jenis, yaitu a) Korban akibat perbuatan manusia, Korban akibat perbuatan manusia dapat menimbulkan perbuatan kriminai (misalnya korban kejahatan perkosaan, korban kejahatan poiitik) dan yang bersifat non kriminai {perbuatan perdata) misalnya korban dalam ganti rugi tanah, korban dalam bidang administratif dan Iain-Iain sebagainya.; b). Korban di luar perbuatan manusia, Korban akibat di luar perbuatan manusia seperti bencana alam dan sebagainya.24
Legislasi Indonesia secara normatif telah memberikan definisi tentang korban. Undang-Undangl Nomorl 13l Tahunl 2006 tentangl Perlindungan Saksil dan lKorban (selanjutnya disebut UU 13/20016) mendefinisikan korbanl sebagai orangl yang menderital secara lfisik, mental, ldan/atau kerugianl ekonomi yangl diakibatkan olehl suatu tindakl pidana. Selanjutnyal secara lkhusus, Undang-Undangl Nomorl 12 Tahunl 2022 tentangl Tindakl Pidana lKekerasan Seksuall (selanjutnya disebutl UU lTPKS) mengartikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Pasal 149 menyatakan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana.
Berdasarkan beberapa pengertian korban tersebut, setidaknya, terdapat 3 (tiga) unsur dalam ldefinisi lkorban, lyaitu 1) korbanl adalahl orangl ataul sekelompok lorang, 2) adanyal penderitaanl fisikl maupun lmental, dan lkerugian lekonomi, 3) penderitaan
dan kerugian tersebut diakibatkan oleh adanya suatu tindak pidana. Dalam lingkup pengertian tersebut, pengertian korban dalam kedua regulasi tersebut, masuk dalam kategori Special Viktimologi karena secara khusus membicarakan korban dalam pengertian korban kejahatan. 25 Unsur-unsur tersebut semakin menegaskan bahwa korban merupakan pihak yang paling dirugikan, dan layak menerima perhatian dan perlindungan. Sehingga tepat yang dikemukakan Muladi, bahwa perlindungan dan perhatian terhadap korban adalah bagian paling esensial dalam kebijakan kriminal (an essential part of criminal policy decision).26
Urgensi perlindungan korban merupakan prioritas yang sudah sepatutnya mendapat perhatian oleh para penegak hukum dan pembentuk undang-undang. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap korban harus bersifat menyeluruh dan menjamin perlindungan hak-hak fundamental korban pada setiap jenjang peradilan pidana. 27 Perlindungan bagi korban harus ditujukan sebagai langkah dan upaya untuk mengurai berbagai hambatan yang dihadapi korban selama ini, sehingga dengan terurainya berbagai hambatan dapat menciptakan suatu kebenaran yang hakiki.28 Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa perlindungan korban, dapat dimaknai dalam 2 (dua) bentuk, pertama, perlindungan korban diartikan sebagai perlindungan hukum agar seseorang tidak menjadi korban kejahatan. Makna yang pertama ini berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, perlindungan korban ldimaknai sebagail upayal untukl mendapatkanl jaminan hukuml atas lpenderitaan/kerugian lyang dialami.29 Menurut Arif Gosita hak-hak korban secara umum antara lain: 1) korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, 2) berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pelaku (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya), 3) berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya apabila koeban meninggal dunia, 4) berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi, 5) berhak mendapat kembali hak miliknya, 6) berhak menolak menjadi saksi apabila berpotensi membahayakan dirinya, 7) berhak mendapat perlindungan dari ancaman pelaku, dan 8) berhak mendapat bantuan hukum dan berhak menggunakan upaya hukum.30
Terdapat 2 (dua) model pengaturan perlindungan bagi korban kejahatan, yaitu 1) model hak-hak prosedural (the prosedural rights model) dan model pelayanan (the service model), sebagai berikut:
-
a. Model hak-hak prosedural, korban memiliki hak untuk berperan aktif dalam penyelesaian perkara pidana diantaranya hak untuk mengadakan tuntutan pidana, hak untuk didengar pada setiap tingkatan pemeriksaan, termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diberikan pelepasan bersyarat juga hak mengadakan perdamaian.
-
b. Model pelayanan, standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh para penegak hukum, korban dipandang sebagai sasaran
khusus yang harus dilayani dalam kegiatan penegakan hukum atau penyelesaian perkara pidana.31
Berbicara perlindungan korban di Indonesia secara prinsip tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam Teori Negara Hukum, baik yang dikemukakan oleh Julius Stahl dengan konsep rechtstaat dan oleh A.V. Dicey dengan konsep the rule of law, maupun gagasan Negara Hukum Pancasila, selalu menempatkan prinsip perlindungan terhadap hak asasi manusia dan prinsip persamaan dihadapan hukum (equality before the law) sebagai salah satu unsur dari negara hukum. Sebagaimana diketahui, Julius Stahl menyatkaan bahwa, konsep Negara Hukum (rechtstaat) memuat elemen sebagai berikut:
-
a. Perlindungan hak asasi manusia
-
b. Pembagian kekuasaan
-
c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
-
d. Peradilan Tata Usaha Negara32
A.V. Dicey mengungkapkan konsep Negara Hukum terdiri dari 3 (tiga) unsur sebagai berikut:
-
a. Supremacy of Law
-
b. Equality before the Law
-
c. Due Process Of Law33
Selanjutnya gagasan Negara Hukum Pancasila merupakan konsep yang disarikan dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Dalam dimensi tersebut, gagasan Negara Hukum Pancasila merupakan perpaduan antara konsep rechtstaat, konsep the rule of law, dan Pancasila. Menurut Hamdan Zoelva, Negara Hukum Pancasila memuat elemen spesifik yang berbeda dengan konsep lainnya yaitu adanya prinsip ketuhanan dan prinsip musyawarah.34 Berkaitan dengan gagasan Negara Hukum Indonesia atau Negara Hukum Pancasila, Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa Negara Hukum Pancasila sepatutnya memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya bukan justru sebaliknya.35
Pengaturan perlindungan korban dalam hukum positif di Indonesia, tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam UUD NRI 1945 khususnya pada bab tentang hak asasi manusia. Dalam konteks jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan
bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali.
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya Pasal 28G menegaskan hak setiap orang atas rasa aman, perlindungan dari ancaman dan rasa takut dan bebas dari segala bentuk penyiksaan atau atau perkuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Pasal 28H ayat (2) menentukan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Lebih lanjut, penegasan perlindungan korban diatur pula dalam Pasal 28I ayat (2) yakni mengenai hak setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif tersebut.
Selanjutnya UU 13/2006 berangkat dari salah esensi quality before the law sebagai salah satu elemen dalam negara hukum. Dalam UU 13/2006 diatur secara eksplisit bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban. Bahkan Pasal 1 angka 1 UU 13/2006 memberikan pengertian khusus, yang dimaksud dengan Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Adapun prinsip dan asas yang menjadi landasan perlindungan korban, yaitu a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b) rasa aman, c) keadilan, d) tidak diskriminatif, dan e) kepastian hukum.
Hak-hak korban diatur secara terperinci dalam UU 13/2006 yang kemudian diperluas dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU 31/2014). Adapun hak-hak tersebut yaitu : a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, c) memberikan keterangan tanpa tekanan, d) mendapat penerjemah, e) bebas dari pertanyaan yang menjerat, f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus; g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, i) mendapat identitas baru, j) mendapatkan tempat kediaman baru, k) memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, l) mendapat nasihat hukum; dan/atau m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
Pasal 6 UU 31/2014 juga mengatur secara khusus hak tambahan bagi korban pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Ketentuan esensial mengenai perlindungan korban, dimuat dalam pasal 10 UU 31/2014 yang menentukan bahwa korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Yang dimaksud dengan memberikan
kesaksian tidak dengan iktikad baik antara lain memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, dan permufakatan jahat.
Penegasan perlindungan korban juga terlihat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP). Penjelasan Umum KUHP menegaskan bahwa penyusunan KUHP ini dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan tentang korban kejahatan yang berkembang pasca Perang Dunia II, yang menaruh perhatian besar pada perlakuan yang adil terhadap Korban kejahatan. Berdasarkan dasar pembentukan KUHP tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan korban kejahatan di Indonesia dewasa ini dan kedepan akan memperoleh perhatian yang serius.
Undang-Undangl Nomorl 12l Tahunl 2022 tentangl Tindak Pidanal Kekerasan lSeksual (selanjutnya disebut lUU lTPKS) dibuat sebagai reaksi atas isu-isu kekerasanl seksual dil lIndonesia. Penjelasanl Umum UUl TPKSl menjabarkan bahwa secara normatif, tindak pidanal kekerasanl seksuall telah diaturl dalam peraturanl perundang-undangan, namun dengan ruang lingkup yang limitatif. Disamping itu, peraturan perundang-undanganl tersebutl sudahl tidak sesuail dengan kebutuhanl dan perkembangan tindak pidana kekerasan seksual di masyarakat, ditambah dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan yang belum memperhatikan hak-hak korban, bahkan cenderung menyalahkan korban.36
UU TPKS merupakan upaya pembaharuan hukum pidana, khususnya mengatasi permasalahan tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya pembaharuan hukum tersebut mencakup 5 (lima) tujuan, yakni:
-
1. Mencegahl segalal bentukl lkekerasan lseksual;
-
2. Menangani, melindungi, danl memulihkan lKorban;
-
3. Melaksanakanl penegakan hukuml dan lmerehabilitasi lpelaku;
-
4. Mewujudkanl lingkungan tanpal kekerasan lseksual; danl
-
5. Menjaminl ketidakberulangan lkekerasan lseksual.
Pembaharuan hukum pidanal padal hakikatnya dimaknai sebagai upayal untuk melakukanl peninjauanl danl pembentukanl kembalil (reorientasi danl reformulasi) hukuml yang sesuail dengan lnilai-nilai lsosio-politik, lsosio-filosofis, danl sosio-kuktural. 37 Bardal Nawawil Arief lmenambahkan, pembaharuanl hukum lpidana ditempuh melaluil pendekatan yangl berorientasi padal kebijakan (policyl oriented approach) dan pendekatanl yang berorientasil pada nilail (valuel oriented lapproach).38
Kerangkal pembaharuanl hukum pidanal yangl melandasi pembentukan UU TPKS juga berangkat dari policy oriented approach dan value oriented approach. Dalam perspektif
pendekatan kebijakan, UU TPKS dibentuk sebagai upaya untuk merealisasikan kelima tujuan diatas. Dalam konteks teoritis, tujuan dibentuknya UU TPKS dilingkupi oleh 3 (tiga) bentuk perlindungan, yakni perlindungan terhadap korban, perlindungan terhadap pelaku, dan perlindungan terhadap masyarakat. Perlidungan terhadap korban dalam UU TPKS dirumuskan secara umum yakni menangani, melindungi, dan memulihkan korban. Declarationl Ofl Basicl Principlesl Ofl Justice Forl Victims Ofl Crime And Abuse Ofl Powerl mendefinisi korbanl sebagai seseorangl yang secaral individu maupun kelompok lmengalami kerugianl baik fisikl maupun mentall (physical or mental injury) kerugian emosional, ekonomi, kerusakan substansiall dari haklfundamentall lmereka, sebagail akibat tindakanl atau kelalaianl yang melanggar hukum lpidana.
Ide besar dibantuknya UU TPKS sebagaimana diuraikan dalam naskah akademik adalah memberikan fokus kepada korbanl kekerasanl seksuall khususnyal padal anak danl perempuanl sebagai kelompok yang rentan dalam masyarakat. Pada hakikatnya memang kepentinganl korbanl kejahatanl merupakanl bagianl utama, yangl menurut Andrewl Ashworth primaryl an offencel against thel victim andl only secondarilyl an loffence against thel wider comunityl or lstate, artinya pentingnya memberikan perlindungan bagi korban, dikarenakan pelanggaran utama terjadi pada korban, selanjutnya baru pelanggaran terhadap masyarakat dan negara.39
UU TPKS pada hakikatnya ditujukan sebagai respon terhadap pelaksanaan hukum yang selama ini merugikan korban, penegakan hukum yang berpedoman pada doktrin blaming the victim yakni menempatkan korban kejahatan sebagai faktor utama lahirnya kejahatan itu sendiri. Doktrin blaming the victim ini secara empiris telah mempengaruhi aparat penegak hukum khususnya dalam menindaklanjutil kasusl yangl dialami perempuanl korban lkekerasan lseksual. Disamping itu dengan beranjak pada perkembangan viktimologi, UU TPKS mencoba menggeser pemahaman tentang korban, dengan mengistilahkan korban menjadi penyintas, yang memilikil hakl untuk mengetahuil situasil kasusnya, terlibatl dalam prosesl peradilan, dan dipertimbangkan situasi, kondisi, danl kepentingannya dalaml upaya penjatuhanl pidana lyang berkeadilan.40
Urgensi perlindungan korban kekerasan seksual dapat dipahami melalui data Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Tahun 2019 yang dirilis oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (selanjutnya disingkat Komnas Perempuan), tampak kekerasan seksual terhadap perempuan di tahun 2018 sejumlah 5.509 kasus dengan rincian, 2988 kasus terjadi di ranah domestik dan 2521 kasus terjadi di ranah komunitas/publik.41 Selanjutnya berdasarkan data yang termuat dalaml Catatanl Akhirl Tahunl (CATAHU) Komnasl Perempuan Tahunl l2020, jumlahl kekerasanl seksuall terhadapl perempuan tahunl 2019 sebanyakl 2087 lkasus lpada ranah personal dan 3602 kasus terjadi pada
ranah komunitas/publik. 42 Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2020l Komnasl Perempuanl menerimal 955l kasus kekerasan seksual yangl terjadi dil ranah lRT/RP maudpunl ranah lpublik. Tidak semual korban lkekerasan seksual mendapatl keadilan danl pemulihan daril berbagai dampak kekerasan lseksual yang ldialaminya. Banyak hambatanl mulai daril peraturan lperundang-undangan, lcara kerja danl persfektif aparatl penegak hukuml hingga tidakl terintegrasinya lsistem hukum pidanal dengan sisteml pemulihan danl budaya yangl mempersalahkan lkorban. 43 Setahun terakhir, berdasarkan data yang dirilis dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2020, merujuk data pengaduan ke Komnas Perempuan dan lembaga layanan pada 2021, bentuk kekerasan yang dialami korban berjumlah 16.162, salah satunya kasus kekerasan seksual dengan jumlah 4.660 kasus (28.8%) kekerasan seksual.
Disamping data kasus tersebut, urgensi perlindungan korban juga didasarkan pada regulasi yang belum berpihak kepada korban. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) sebagai basis hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana diketahui dibentuk dalam upaya memberikan perhatian dan perlindungan kepada pelaku kejahatan, khususnya hak asasi manusianya. Oleh karena itu, apabila mencermati Penjelasan Umum dan pasal-pasal dalam KUHAP, maka dominan ditemukan pengaturan mengenai perlindungan terhadap tersangka/terdakwa. Sebaliknya, pengaturan yang menyangkut perlindungan terhadap korban kejahatan sangat minim, bahkan terkesan tidak ada. Kondisi regulasi tersebut, disorot dan dikritik sangat tajam dalam Naskah Akademik UU TPKS, bahwa kondisi hukuml acaral pidanal dalam lKUHAP ltidak mengatur lhak-hakl korbanl atas keadilan secara komprehensif dan eksplisit. Hak-hak tersebut seperti hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk dilindungi kerahasiannya, hak atas jaminan keamanan, hak untuk dilayani dengan baik tanpa diskriminasi dan sebagainya.
UU TPKS hadir dengan semangat konstitusional yaitu untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang khususnya perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Pentingnya perlindungan tersebut karena kekerasan seksual telah menjadi momok yang menakutkan, tindakan kekerasan yangl merendahkanl martabat manusial danl bertentangan ldengan nilai lketuhanan, serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat. Materi muatan UU TPKS mengatur beberapa terobosan, sebagai berikut:
-
1. Pengkualifikasian jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual
-
2. Pengaturanl hukuml acaral khususl mulail dari tahapl penyidikan, lpenuntutan, dan pemeriksaanl di lsidang lpengadilan
-
3. Hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemilihan sebagai kewajiban negara dan pemberian Restitusi oleh pelaku kepada korban lkekerasan lseksual, ldan
-
4. Penyelesaianl tindakl pidana kekerasanl seksual yangl tidak diperbolehkan menggunakan pendekatan keadilan restoratif kecuali untuk pelaku anak.
Kualifikasi Tindakl Pidanal Kekerasanl Seksuall dalam UUl TPKS dapatl dikatakan sangat komprehensif karena diatur secara rinci dan sesuai dengan fakta empiris mengenai perkembangan jenis tindak kekerasan seksual. Dalam Pasal 4 UU TPKS, dijabarkan Tindakl Pidanal Kekerasanl Seksuallterdiri latas:
-
a. Pelecehanl seksual lnonfisik
-
b. Pelecehanl seksual lfisik
-
c. Pemaksaanl kontrasepsil d. Pemaksaanl sterilisasil e. Penyiksaanl seksuall f. Eksploitasil seksuall g. Perbudakanl lseksual; danl h. Kekerasanl seksuall berbasis lelektronik.
Selainl tindak pidanal tersebut diatas, UU TPKS juga mengatur tindak pidana lain yang termasukl Tindakl Pidanal Kekerasanl lSeksual, meliputi: la. perkosaan; lb. perbuatan lcabul; c. persetubuhanl terhadap lAnak, perbuatan cabull terhadap lAnak, dan/ latau eksploitasi seksuall terhadap lAnak; d. perbuatanl melanggar kesusilaan yang bertentanganl dengan kehendakl Korban; le. pornografi yangl melibatkan Anak atau pornografil yang secaral eksplisit memuatl kekerasan danl eksploitasi lseksual; f. pemaksaanl pelacuran; lg. tindak pidanal perdagangan orangl yang ditujukanl untuk eksploitasil seksual; lh. kekerasan seksuall dalam lingkupl rumah ltangga; i. ltindak pidana pencucianl uang yangl tindak pidanal asalnya merupakanl Tindak lPidana Kekerasan lSeksual; dan lj. tindak pidanal lain yangl dinyatakan secaral tegas lsebagai Tindak Pidanal Kekerasan Seksuall sebagaimana diaturl dalam ketentuanl peraturan perundang-lundangan.
Kemudianl UUl TPKS jugal mengaturl tindak pidanal lain yangl berkaitanl dengan tindak pidana kekerasanl lseksual, yaitu perbuatanl yangl dengan sengajal mencegah, merintangi, atau menggagalkanl secara langsungl atau tidakl langsung lpenyidikan, penuntutan, ldan/atau pemeriksaanl di sidangl pengadilan terhadapl tersangka, terdakwal atau lsaksi. Ketentuan yangl mengatur tindakl pidanal tersebut dimuat dalam Pasal 19, yang secara teoritis disebut obstruction of justice atau perbuatan yang menghalang-halangil suatul prosesl peradilan lpidana. Istilah lobstruction of ljustice merupakanl terminologi hukuml yangl sering diterjemahkan sebagail tindak pidana menghalangi proses hukum. Eddy OS. Hiariej menjelaskan, dalaml konteksl hukuml pidana, obstruction ofl justice diartikanl sebagai perbuatanl baik aktifl maupun lpasif, yangl dilakukanl denganl maksudl ataul memiliki motifl untuk menghambatl proses hukuml yang dilakukanl oleh lpenegak lhukum.44 Shinta Agustina dkk., obstruction of justice diartikan sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum yang dapatl berupal memberikanl keteranganl lpalsu, menyembunyikan lbukti-bukti, ataupun mencelakai ataul mengintimidasi lpara lsaksi.
Obstruction of justice tergolong perbuatan melawan hukum karena menghambat penegakan hukum, dan proses pencarian kebenaran dan keadilan, hambatan ini dapat merusak citra penegakan hukum.45 Pengaturan obstruction of justice dalam UU TPKS
menunjukkan keseriusan negara dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual, sama halnya dengan tindak pidana korupsi yang juga memuat tindak pidana obstruction of justice. Dengan pengaturan tersebut, diharapkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang di pengadilan terbebas dari gangguan serta mampu mengungkap tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi.
Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU TPKS, mengadopsi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).46 Pengaturan SPPT-PKKTP dalam UU TPKS menunjukkan kekhususan dari undang-undang ini sebagai lex specialis dalam penanganan kasus kekerasan seksual. SPPT-PKKTP merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi perempuan dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.47 Prinsip-prinsip yang terkandung dalam SPPT-PKKTP, yaitu:
-
a. Perlindungan dan penegakan atas Hak Asasi Manusia
-
b. Kesetaraan dan keadilan jender
-
c. Prinsip non diskriminasi.
Berdasarkan tiga prinsip tersebut, SPPT-PKKTP diwujudkan dalam berbagai cara antara lain 1) koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak/instansi yang berwenang dalam memberi pelayanan terhadap korban yang cepat dan memahami kebutuhan korban, 2) pengalokasian dana yang efektif bagi pihak/instansi tersebut, dimuali dari pendampingan, penyidikan, pemeriksaan, dan pemulihan bagi korban, 3) partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses peradilan, 4) penyediaan sumber daya manusia yang memahami konteks permasalahan dan penanganan yang berspektif gender, 5) penyediaan ruang pemeriksaan khusus di setiap tingkat pemeriksaan.48
Aspek lainnya adalah berkaitan dengan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual yang dianggap menyulitkan korban kejahatan. Pasal 184 KUHAP mengatur keterangan 1 (satu) orang saksi tidak dapat dijadikan dasar pembutkian. Untuk itu, dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dibutuhkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Padahal faktanya, untuk membuktikan adanya tindak pidana kekerasan seksual, khususnya kekerasan seksual non fisik sangat sulit untuk menemukan alat bukti, selain keterangan dari korban kejahatan. Disamping aspek normatif, aspek budaya hukum juga menjadi faktor penghambat penegakan ltindak pidanal kekerasanl seksuall di lIndonesia. Aspek inil juga menjadi perhatian utama yang dibahas dalam Naskah Akademik UU TPKS. Fakta-fakta mengenai sikap ltindak penegakl hukuml yangl tidakl berpihak padal lkorban, seperti menyalahkan korban, menganggap kekerasan seksual adalah permasalahan pribadi, dan tidak memberikan upaya pelayanan yang baik.
Pasal 24 UU TPKS menentukan jenis-jenis alatl buktil yangl lebih luasl dibandingkanl alatl bukti yanglditentukan dalaml Pasal l184 lKUHAP. Jenis-jenisl alatl bukti yangl ditentukan dalaml UU TPKS adalah sebagai berikut:
-
1. alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP;
-
2. informasil elektronikl ldan/ataul dokumenl elektronik yangl diatur ldalam peraturan lperundang-lundangan;
-
3. barangl bukti yangl digunakan untukl melakukan tindakl pidana ataul sebagai hasill Tindak Pidanal Kekerasan Seksuall dan/ataul benda ataul barang lyang berhubungan denganl tindak lpidana ltersebut.
Alatl buktil dalam hukum acara pidana, yaitu Pasal 184 KUHAP hanya mengatur 5 (lima) jenis alat bukti yang diakui, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Perluasan jenis alat bukti tersebut, seharusnya dapat memudahkan korban dan penegak hukum untuk mengungkap Tindak PidanalKekerasanl Seksuall yangl lterjadi. Terlebih Pasall 25 ayatl (1) UUl TPKSl telah menegaskanl bahwa keteranganl saksi/korbanl ditambah denganl 1l (satu) alatl bukti lainnyal yang lsah, sudah cukupl untuk membuktikanl terdakwa lbersalah.
Pengaturan dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPKS tersebut pada hakikatnya memuat ketentuan khusus, yang berbeda dengan stelsel pembuktian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang mengenal teori pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijstheorie). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, teori ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang membuat hakim memperoleh keyakinan. Dalam Negatief Wettelijk Stelsel memuat 2 (dua) syarat, yaitu:
-
a. wettelijk, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang;
-
b. negatief, artinya dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti yang diberikan,tapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.49
Pengesampingan sistem pembuktian yang dimuat dalam Pasal 183 KUHAP memang dimungkinkan, apabila terdapat ketentuan khusus yang mengatur sistem pembuktian pada tindak pidana tertentu. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur pembalikan beban pembuktian.50 Pengesampingan ini dalam dimensi teoritis memperoleh legitimasi melalui asas preferensi hukum lex specialis derogate legi generalis, yang artinya undang-undang yang mengatur ketentuan khusus mengesampingan undang-undang yang mengatur umum.
Ketentuan tersebut setidaknya telah menjawab kesulitan korban dan penegak membuktikan adanya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dikarenakan keterbatasan jenis alat bukti yang dapat dijadikan dasar mengungkap kebenaran, khususnya dalam konteks pelecehan secara nonfisik, yang pembuktiannya tidak bisa lhanya menggunakanl alatl buktil yangl ada dalaml Pasal l184 lKUHAP, melainkan harus melalui bantuan seorang psikiater. Adanya Pasal 25 ayat (1) tersebut memberikan
jaminan bahwa keterangan korban ditambah dengan keterangan seorang psikiater bahwa korban mengalami kerugian mental akibat pelecehan seksual nonfisik, maka dengan keyakinannya, hakim sudah dapat menyimpulkan telah terjadi pelecehan seksual secara nonfisik.
Arah perlindungan terhadap korban dalam UU TPKS, secara eksplisit dimuat dalam BAB V tentang Hak Korban, Hak Keluarga Korban, dan Saksi. Terdapat 3 (tiga) klasifikasi Hak Korban yang terdiri dari:
-
a. hakl atasl perlindungan
-
b. hakl atasl penanganan, ldan
-
c. hakl atasl pemulihan
Pemenuhanl hakl korbanl merupakanl tangunggjawab negaral dan dilaksanakanl sesuai denganl kebutuhan danl kondisi lkorban. Penegasan ini sejalan denganl Pasall 28Il ayatl (4) lUUD NRI l1945 yang menyatakanl bahwa lperlindungan, pemajuan, lpenegakan, dan pemenuhanl hak asasil manusial menjadi tanggungjawabl negaral terutama lpemerintah.
Hak Korban atas penanganan ditegaskan dalam Pasall 68l UU TPKS meliputi : hak atasl informasil terhadapl seluruhl proses danl hasil lPenanganan, Pelindungan, dan Pemulihan, lhak mendapatkan dokumenl hasil lPenanganan, hak atasl layanan hukum, hak latas penguatan lpsikologis, hak atasl pelayanan kesehatanl meliputi pemeriksaan, tindakan, danl perawatan lmedis, hak atasl layanan danl fasilitas sesuaildengan lkebutuhan khusus lKorban, dan hakl atas penghapusanl konten bermuatanl seksual untukl kasus lkekerasan seksual denganl media lelektronik. Selanjutnya Hakl atas Perlindunganl diatur ldalam Pasal l69 UU TPKS, 3 (tiga) diantaranya yang penting adalah pelindunganl daril sikapl danl perilakul aparat penegakl hukum yangl merendahkan lKorban, Pelindungan ldari kehilangan pekerjaan, mutasi lpekerjaan, pendidikan, danl Pelindungan lKorban dan/atau pelapor daril tuntutan pidanal atau gugatanl perdata atasl Tindak lPidana Kekerasan Seksuall yang ltelah ldilaporkan. Adanya Hakl Korban atasl perlindungan dari sikap penegak hukum dan tuntutan pidana tidak akan ada lagi viktimisasi dan kriminalisasi terhadap korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Disamping itu, dengan jaminan ini maka akan semakin banyak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berani melapor dan memperjuangkan hak-haknya.
Arah perlindungan korban kekerasan seksual, selain atas penanganan dan perlindungan, juga hak atas pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU TPKS. Hak atas penanganan meliputi : rehabilitasi medis, rehabilitasi mental dan sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi dan reintegrasi sosial. Berdasarkan uraian mengenai pengaturan dalam UU TPKS, sesungguhnya pengaturan perlidungan korban telah termuat secara komprehensif. Ditambah sistem/stelsel pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual, menambah optimisme korban dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual itu sendiri. Tantangan kedepan setelah adanya UU TPKS, adalah tentang pelaksanaannya di masyarakat. Terdapat suatu ungkapan, bahwa seindah-indahnya kata dalam undang-undang, tidak akan ada artinya apabila tidak dapat diterapkan dalam masayrakat. Terlepas dari implementasinya kedepan, kehadiran UU TPKS patut diapresiasi sebagai langkah konkrit dan progresif dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana kekerasan seksual.
Pengaturan perlidungan korban dalam sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari dinamika viktimologi dan ilmu hukum pidana yang melahirkan konsep daad-daader strafrecht. Perlindungan korban di Indonesia memperoleh justifikasi konstitusional dalam UUD NRI 1945 khususnya pada Pasal 1 ayat (3) dan bab hak asasi manusia. Selanjutnya diundangkannya UU 13/2006 jo. UU 31/2014 secara khusus mengatur perlindungan korban dan secara terperinci mengatur hak-hak korban. Ketentuan esensial mengenai perlindungan korban, dimuat dalam pasal 10 UU 31/2014 yang menentukan bahwa korban tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Ditambah adanya paradigma baru mengenai perlindungan korban dalam KUHP baru, yang diharapkan memberikan optimisme perlindungan korban kedepan. Lahirnya UU TPKS yang mengatur secara spesifik mengenai berbagai bentuk perlindungan korban kekerasan seksual, secara sosiologis beranjak dari berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Pengaturan perlindungan korban kekerasan seksual dalam UU TPKS patut diapresiasi dengan berbagai ketentuan yang lebih berpihak pada korban dan sepenuhnya menghapus paham blamming the victim. Dari sisi sistem, UU TPKS telah mengadopsi SPPT-PKKTP yang lahir sebagai perjuangan atas sistem peradilan yang memihak pada keadilan gender. Selain itu, diatur pula stelsel/sistem pembuktian yang memudahkan pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual. Serta pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pemenuhan hak-hak korban, diharapkan memantik keberanian korban dan aparat negara memberantas tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.
Berdasarkan uraian diatas, Penulis dapat memberikan beberapa rekomendasi, baik kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, dan masyarakat. Kepada pemerintah pusat penulis menyarankan agar peraturan pelaksana atas UU TPKS segera diterbitkan agar dapat menjadi pedoman penerapannya. Disamping itu, Pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait juga wajib terlibat aktif dalam memenuhi hak-hak korban. Disamping itu, perlu dilakukan berbagai bentuk pembinaan dan sosialisasi kepada penegak hukum agar sungguh-sungguh memahami ratione d’etre dari UU TPKS. Kepada penegak hukum, penulis berharap dapat memahami sepenuhnya spirit dan roh dalam UU TPKS, serta melaksanakan penegakan hukum yang berpihak pada korban. Kepada masayarakat dalam arti luas, penulis menyarankan agar berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual, dengan cara yang paling mudah yaitu tidak menjadi pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Selanjutnya agar memahami dan menghormati sepenuhnya hak-hak korban kekerasan seksual serta tidak memberikan stigma yang negatif kepada korban.
Daftar Pustaka
Ali, Mahrus. Viktimologi. 1st ed. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2020.
Arif, Barda Nawawi. “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.” Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” Gagasan Negara Hukum. Majalah Hukum Nasional, 2006.
astoto, sri suhartati. “Eksistensi Viktimologi Dalam Penyelesaian Ganti Rugi.” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 8, no. 18 (2001): 212–24.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol8.iss18.art15.
Darmadi, A A Ngurah Oka Yudistira. “Konsep Pembaharuan Pemidanaan Dalam Rancangan KUHP.” Jurnal Magister Hukum Udayana 2, no. 2 (2013): 44212.
Dijk, Van. “Introducing Victimology Caring for Crime Victims Publication Date:” Selected Proceedings of the Ninth International Symposium on Victimology, 1999, 1–12.
Dwiati, I. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana.” Universitas Diponogoro, 2007.
Effendy, Marwan. “Pembalikan Beban Pembuktian Dan Implementasinya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan 39, no. 1 (2009): 1. https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no1.201.
Fikri, Fayidla Nurul, Keysha Shira Zafirah, Risma Siti Istikomah, Salsabila Zahra, and Husnita Akhyar Hasibuan. “Penyalin Cahaya: Analisis Jenis Pelecehan Seksual Pada Film Penyalin.” Cinematology: Journal Anthology of Film and Television Studies 2, no. 2 (2022): 32–47.
Hiariej, Eddy O.S. “KPK Dan Perintang Peradilan,” January 23, 2018.
https://antikorupsi.org/id/article/kpk-dan-perintang-peradilan.
Huda, M. Choirul. “Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Progresif.” Universitas Islam Indonesia, 2018.
Junianto, Johan Dwi. “Obstruction of Justice Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Media Iuris 2, no. 3 (2019): 335–52.
Komnas Perempuan. “Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan, Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan.” Jakarta, 2020.
-
— ——. “Kertas Kebijakan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.” Jakarta, 2005.
-
— ——. “Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Kekerasan Seksual Sebagai Komitmen Negara.” Jakarta, 2019.
-
— ——. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dpr Ri. Vol. 105, 2017.
https://www.dpr.go.id/doksileg/proses2/RJ2-20170201-043128-3029.pdf.
-
— ——. “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi; Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawanin Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19.” Jakarta, 2021.
Kurnianingsih, Sri. “Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja.” Buletin Psikologi 11, no. 2 (2003).
Lugianto, Adil. “Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana.” Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana 43, no. 4 (2014): 553–59. https://doi.org/10.14710/mmh.43.4.2014.553-559.
Mannika, Ghinanta. “Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan.” CALYPTRA 7, no. 1 (2018): 2540–53.
Muladi. “Hukum Pidana Dan Perlindungan Bagi Korban Kejahatan.” Jurnal Perlindungan 1, no. 4 (2014): 3–12. www.lpsk.go.id.
Mulyadi, Lilik. “Upaya Hukum Yang Dilakukan Korban Kejahatan Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana Dalam Putusan Mahkamah Agung RI.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 1, no. 1 (2012): 1–34.
Mustofa, Muhammad. “Viktimologi Posmodern.” Jurnal Kriminologi Indonesia 13, no. 2 (2017): 57–62.
Nurisman, Eko. “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 2 (2022): 170–96.
https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196.
Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 61–72.
Sibarani, Sabungan. “Pelecehan Seksual Dalam Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.” SOL JUSTISIO 1, no. 1 April (2019): 98–108.
Sophia, Maharani Siti. “Aksesibilitas Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana.” Jurnal Perlindungan Edisi 4 (2014).
Zoelva, Hamdan. “NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA.” Jakarta: Jurnal Sekretariat Negara RI, 2009. https://zoelvapartners.id/negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila/.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomorl 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksil dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomorl 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksil dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
Undang-Undangl Nomorl 12l Tahunl 2022 tentangl Tindak Pidanal Kekerasan lSeksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).
631
Discussion and feedback