Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring
on
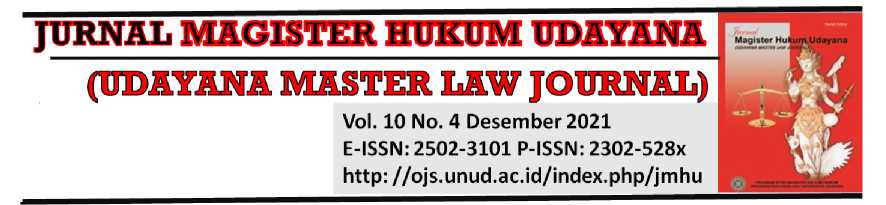
Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring
Putu Satria Satwika Anantha1, Ibrahim R2
1Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: satria.anantha@gmail.com 2Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: ibrahim_r@unud.ac.id
Info Artikel
Masuk: 14 September 2021
Diterima: 26 Desember 2021
Terbit: 31 Desember 2021
Keywords:
Job Creation; Land; Domein
Verklaring
Kata kunci:
Cipta Kerja; Pertanahan;
Domein Verklaring
Corresponding Author:
Putu Satria Satwika Anantha, E-mail:
DOI:
10.24843/JMHU.2021.v10.i04. p14
Abstract
The purpose of this research was to find out and analyze the legal certainty of the Job Creation Law against the LoGA on land clusters and the power of law against the conflict between the Job Creation Law and the UUPA on the land cluster. This research used normative research where a review of applicable laws and regulations is carried out and uses secondary data as the main data. The study indicated that, the following conclusions can be formulated: (1) Article 137 paragraph (1) of the Job Creation Law has deviated from the provisions of Article 2 paragraph (4) of the UUPA which explains that the State's right to control above its implementation can be empowered to the community customary law; and (2) The establishment of the Job Creation Law can serve as a red carpet for private entrepreneurs to get land cheaply and even free of charge, by making plans to increase investment in Indonesia, which is contained in Article 127 of the Job Creation Law.
Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap UUPA pada klaster pertanahan dan kekuatan hukum terhadap konflik Undang-Undang Cipta Kerja terhadap UUPA pada klaster pertanahan tersebut. Penulisan jurnal ini digunakan jenis penelitian normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja ini telah menyimpang dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menjelaskan Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada masyarakat-masyarakat hukum adat; dan (2) Pembentukan UU Cipta Kerja ini bisa sebagai karpet merah pada pengusaha swasta mendapatkan tanah secara murah bahkan gratis, dengan menggadang-gadang untuk peningkatan insvestasi di Indonesia, yang termuat pada pasal 127 UU Cipta Kerja.
Undang-Undang Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA, konsep hak menguasai negara ini diperinci dan diperluas pengertiannya.1 Menurut Boedi Harsono, UUPA mempunyai dua subtansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua membangun hukum agraria nasional. Dengan berlakunya UUPA, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum agraria di Indonesia, terutama hukum dibidang pertanahan. Perubahan yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya.2
Hak menguasai dari negara, dilihat dari sejarah pembentukan UUPA mengajarkan bahwa hak menguasai negara (yang mencakup kewenangan negara untuk menetapkan peruntukan dan pemanfaatan sumber daya agraria termasuk hak orang atau kelompok masyarakat atas tanah) merupakan abstraksi dari Hak ulayat. UUPA pada dasarnya merupakan penjabaran dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 yang mengatur kewenangan negara atas tanah, menyebutkan bahwa sebagai hukum tanah nasional, dalam UUPA dikenal adanya tiga entitas tanah yaitu :
-
a. Tanah Negara, hubungan penguasaannya disebut hak menguasai (oleh) Negara, kewenangannya bersifat publik;
-
b. Tanah Ulayat, hubungan penguasaannya disebut Hak ulayat, subjeknya Masyarakat Hukum Adat dan kewenangannya bersifat publik dan keperdataan.
-
c. Tanah Hak yang dapat dipunyai oleh orang perorangan atau badan hukum, kewenangannya bersifat keperdataan. Macam-macam hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 UUPA.3
Menurut Moh. Hatta, Masyarakat Hukum Adat menganggap tanah merupakan tempat tinggal para leluhur serta tempat kuburan mereka saat meninggal nanti.4 Di sisi lain negara secara tegas telah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUPA yang menentukan bahwa : Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dalam konsep dasar pemikiran hak menguasai tanah negara atas tanah, pada dasarnya tanah adalah milik rakyat Indonesia dan negara merupakan penjelmaan dari rakyat yang mempunyai hak untuk mengatur penggunaannya agar dapat mengejar
kemakmuran rakyat. 5 Ketentuan Pasal 3 di atas tetap harus dimaknai bahwa kepentingan suatu masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas dan hak ulayatnya dan pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas. Menurut A. Suriyaman Mustari Pide, bahwa ada 3 (tiga) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu :6
-
1. Magis Religius, yang mengandung arti bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap halhal gaib). Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiusitas yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.
-
2. Communal (Commun). Asas commun mengandung arti mendahulukan kepentingan sendiri. Masyarakat hukum adat mempunyai pemikiran
bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan dan setiap kepentingan individu
sewajarnya disesuaikan dengan kepentingankepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakatnya.
-
3. Contan. Sifat ini mengandung arti sebagai keserta mertaan, utamanya dalam hal pemenuhan prestasi. Sifat kontan memberi pengertian bahwa suatu tindakan berupa perbuatan nyata, perbuatan simbolis atau pengucapan akan menyelesaikan tindakan hukum bersamaan dengan waktunya.
Lahirnya Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut UU Cipta Kerja, menjadi perdebatan pada klaster pertanahan terhadap UUPA. UU Cipta Kerja saat ini menganut teori domein verklaring yang dianut pada jaman penjajah Belanda dahulu, teori ini mengartikan pada waktu itu pada dasarnya semua tanah dimiliki oleh pemerintah kecuali untuk tanah tersebut seseorang dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik dari tanah. 7 Sejarahnya, konsep ini merupakan buatan pemerintah kolonial Belanda untuk menghapus konsep domein verklaring yang diterapkan oleh pemerintah kolonial untuk merebut tanah yang dikuasi masyarakat hukum adat. Permasalahan ini berkaitan pada pasal 2 UUPA mengenai Hak Menguasai Negara yang menjadi petaka baru bagi Masyarakat Adat. Dengan terciptanya UU Cipta Kerja ini menjadikan alat hukum baru perampas tanah rakyat karena telah melanggar Pasal 33 Ayat (3) dan (4) UUD 1945, mengenai kewajiban Negara atas sumber agraria Indonesia agar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui demokrasi ekonomi.8
Tercipatanya UU Cipta Kerja yang merugikan masyarakat hukum adat ini tidak menciptakan hukum yang menguntungkan bagi rakyatnya akan tetapi hanya
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 Desember 2021, 857-868
menguntungkan kalangan tertentu saja. Menurut Maria S.W Sumardjono mengemukakan bahwa dasar berpijak untuk pembuatan kebijakan di masa yang akan datang adalah :9
-
1. Prinsip-prinsip dasar yang diletakkan oleh UUPA orientasinya perlu dipertegas dan dikembangkan, sehingga dapat diterjemahkan sebagai kebijakan yang konseptual, sekaligus operasional dalam menjawab berbagai kebutuhan dan dapat menuntut ke arah perubahan yang dinamis.
-
2. Perlu adanya persamaan persepsi bagi pembuat kebijakan dengan berbagai hal yang prinsipiil, sehingga tidak akan menunda jalan keluar dari berbagai permasalahan yang ada. Dalam hal ini pembuat kebijakan harus senantiasa menghindari adanya pengaturan yang menimbulkan multi tafsir, sehingga dapat ditentukan dan dikembangkan kebijakan pertanahan sesuai dengan keberagaman permasalahan yang ada.
-
3. Perlu dilakukan prioritas dalam penerbitan kebijakan, untuk menghindari kesan adanya pembuatan kebijakan yang bersifat parsial.
-
4. Diperlukan adanya kebijakan di bidang pertanahan yang jelas yang menunjukkan hubungan antara prinsip kebijakan, tujuan serta sasaran yang hendak dicapai. Hal ini perlu mengingat setiap kebijakan yang dikeluarkan akan menimbulkan akibat hukum sebagai akibat dari kebijakan itu sendiri.
Dalam hal mendasar masyarakat adat juga membutuhkan kepastian hukum untuk kedepannya bisa mendapatkan hak yang sepantas diperolehnya mengenai tanah ini. Terlebih lagi diwilayah pedesaan banyaknya tanah yang tidak memiliki sertifikat tanah. Sehingga terciptanya UU Cipta Kerja pada klaster pertanahan ini akan menjadi polemik kedepannya bagi masyarakat adat.
Dari paparan masalah diatas maka diangkatlah karya ilmiah Kepastian Hukum Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Domein Verklaring. Dengan rincian rumusan masalah yaitu : Bagaimana kepastian hukum UU Cipta Kerja terhadap UUPA pada klaster pertanahan hukum adat ? dan Bagaimana asas menguasai negara bagi penanaman modal terhadap konflik UU Cipta Kerja terhadap UUPA pada klaster pertanahan ? Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum UU Cipta Kerja terhadap UUPA pada klaster pertanahan dan kekuatan hukum terhadap konflik UU Cipta Kerja terhadap UUPA pada klaster pertanahan tersebut. Sebelumnya terdapat penelitian yang mirip dengan tulisan ini, yaitu : Penelitian dari Hendra Sukarman dengan judul “Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus Law”, dengan rumusan masalah : (1) Bagaimanakah konsep keadilan diterapkan dalam pengaturan agraria di Indonesia? dan (2) Bagaimanakah keadilan yang terjadi pasca di sahkannya Undang-Undang Omnibus-law? 10 Kemudian terdapat pula penelitian jurnal yang mirip yaitu : Penelitian dari Geraldus Sulianto dengan judul “Penguasaan Tanah Bekas Hak Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria (Studi Kasus Putusan Makamah Agung Nomor: 1401 K/Pdt/2018)”, dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap warga yang menguasai tanah
bekas Hak Eigendom Verponding secara fisik setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria dan yang sudah diterbitkannya sertipikat atas nama PT. Asuransi Jiwasraya (Persero).11 Membandingkan secara seksama kedua penelitian dari Hendra Sukarman dan Geraldus Sulianto memiliki rumusan masalah serta topik pembahasan yang berbeda dengan tulisan ini. Dimana tulisan ini memfokuskan pada kepastian hukum UU Cipta Kerja terhadap UUPA pada klaster pertanahan. Sehingga tulisan ini memiliki orisinalitas tersendiri dalam kajian penelitian hukum.
Penulisan jurnal ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan jenis pendekatakan yang penulis gunakan ialah pendekatan perundang-undangan dan pendekatatan analisis konsep hukum.12 Pendekatan perundang-undangan, digunakan karena yang penulis teliti adalah aturan hukum yaitu Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjadi fokus sentral dalam penelitian ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan konsep-konsep hukum yang disertai dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya, yang relevan dengan judul yang penulis angkat. Teknik analisis yang digunakan yaitu deskripsi, interprestasi dan argumentasi.13
-
3. Hasil dan Pembahasan
Dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat serta pengakuan dari negara lain. 14 Sebagaimana disebutkan bahwa unsur negara mencakup dari rakyat, wilayah dan pemerintahan yang mana ketiga unsur tersebut merupakan syarat mutlak berdiri sebuah organisasi disebut negara. Negara melalui otoritas kekuasaannya mempunyai hak dan kekuasaan dalam mengakomodir maupun merekayasa negara tersebut dengan tujuan kesejahteraan masyarakatnya. Rekayasa yang terbangun dalam sebuah sistem legalisasi tersebut didudukkan dalam posisi sebagai hukum tertinggi sehingga masyarakat patuh dan menjalankan setiap kebijakan negara tersebut. Hal itu disebut dengan konstitusi.15
Hal ini juga senada dengan cita hukum negara Republik Indonesia yang mengadopsi teori negara hukum, dimana tujuan negara hukum yaitu mensejahterakan rakyatnya. Tujuan negara hukum secara umum yaitu :
-
1. membatasi kekuasaan Negara
-
2. menjamin kesejahteraan rakyat
-
3. melindungi HAM
-
4. menjamin kekuasaan presiden
-
5. memberi kebebasan individu.16
Landasan konstitusional bagi pembentukan politik dan Hukum Agraria nasional, telah diatur di dalam Pasal 9 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya bagi diri sendiri maupun keluarganya. Politik hukum berhubungan dengan kebijaksanaan untuk menentukan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan ideologi penguasa. Semula konsep ini dibuat untuk menghapus konsep domein verklaring yang diterapkan oleh pemerintah kolonial untuk merebut tanah yang dikuasi masyarakat hukum adat. Pada perkembangannya, HMN ini dalam penerapannya hampir sama dengan konsep domein verklaring pada masa kolonial.17
Merujuk pada landasan di atas, maka negara mempunyai legalitas dalam menyelenggarakan kewenangan dibidang agraria. Wewenang negara dibidang agraria yaitu:
-
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut.
-
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang
orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
-
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang
orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.18
Dalam perkembangannya, hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mengalami perubahan dengan ditetapkannnya Permen Nomor 10 Tahun 2016 yang memberi kesempatan kepada KMHA maupun masyarakat yang berada pada Kawasan Tertentu sebagai pemegang hak komunal atas tanah, yang pengaturannya diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Permen Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa subjek dari pemohon hak komunal yaitu:
-
a. Masyarakat Hukum Adat;
-
b. Mayarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu;
Tujuan wewenang itu diberikan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan serta kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, adil dan makmur.19 Hak Milik Negara merupakan bagian dari hak bangsa yang beraspek publik. Aspek publik memposisikan negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep ini berbeda dengan penguasaan atas tanah pada konsep feodal
dimana raja sebagai pemilik (domein) tanah. Hak Milik Negara juga bukan konsep komunis, dimana tanah dimiliki secara bersama seluruh rakyat sehingga menututup sama sekali peluang adanya penguasaan individu. Penguasaan tanah oleh negara merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mensejahterakan rakyat melalui pemanfaatan sumber-sumber agraria. Konsep tersebut dilakukan untuk mendistribusikan sumber-sumber agraria lebih adil sehingga terjadi pemerataan dalam pemanfaatannya. Hak Milik Negara lahir selain untuk kesejahteraan, sesungguhnya merupakan mekanisme untuk melindungi rakyat Indonesia dari penindasan-penindasan oleh individu maupun kelompok yang berkepentingan.
Dalam UU Cipta Kerja Pasal 137 ayat (1) Sebagian kewenangan hak menguasai dari negara berupa tanah dapat diberikan hak pengelolaan kepada :
-
a. Instansi Pemerintah Pusat;
-
b. Pemerintah Daerah;
-
c. Badan Bank Tanah;
-
d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
-
e. Badan hukum milik Negara daerah; atau
-
f. Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.
Dalam Pasal 137 ayat (1) UU Cipta Kerja ini telah menyimpang dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menjelaskan Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Dalam UU Cipta kerja tidak dijelaskan bahwa yang berhak menguasai tanah negara yaitu masyarakat hukum adat, sehingga UU Cipta Kerja telah melanggar hak konstitusional masyarakat adat, khususnya Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang dan pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Disharmoni (ketidakharmonisan) peraturan perundang-undangan juga terjadi karena egoisme sektoral kementerian/ lembaga dalam proses perencanaan dan pembentukan hukum.20 Secara implisit, dalam UU Cipta Kerja asas domein verklaring ini akan kembali diberlakukan kembali, dalam hal ketidak jelasan kepemilikan tanah adat dan akan menyebabkan tanah adat dapat jatuh menjadi tanah Negara.
Permasalahan UU Cipta Kerja Teori yang menyimpang dengan ketentuan UUPA berkaitan dengan teori stufenbau atau yang dikenal juga dengan teori perjenjangan norma merupakan teori hukum yang dikemukakan oleh penganut paham hukum murni yakni Hans Kelsen.21 Menurut Hans Kelsen terkait teori Stufenbau atau teori perjenjangan norma Norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis
dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam artian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seharusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma dasar (grundnorm).22
-
3.2 Asas Menguasai Negara Bagi Penanaman Modal Terhadap Konflik UU Cipta Kerja Terhadap UUPA Pada Klaster Pertanahan
Kata Tanah Negara seperti hal sebutan tanah yang lain-misalnya tanah milik dan sebagainya-hal ini menunjukan suatu status hubungan hukum tertentu antara obyek dan subyeknya yang dalam konteks ini lebih kepada hubungan kepemilikanatau kepunyaan antara subyek dan obyek yang bersangkutan. 23 Pemberian sesuatu hak penguasaan atas tanah kepada seseorang atau badan hukum dilekati dengan wewenang yang ada pada hak penguasaan atas tanah tersebut. Mengenai wewenang dinyatakan oleh Sumardji, yaitu wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht).24
Menurut Pasal 2 Ayat (2) UUPA menentukan rumusan Pembatasan kekuasaan Negara atas tanah, diantaranya:
-
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan dan pemeliharaan
-
b. Menentukan hubungan hukum
-
c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum.
Dalam sejarah hukum pertanahan di Indonesia diperlakukan 3 (tiga) teori penguasaan tanah yakni teori eropa, teori adat dan teori hukum nasional.25 Dalam hal penguasaan tanah untuk Penanaman Modal maka terlebih dahulu di lihat dari pemegang Haknya Penanaman Milik Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Bila pemegang hak ini adalah Perusahaan Asing maka Jenis Hak Atas Tanah yang bisa diberikan adalah Hak Pakai, sedangkan bila untuk Penanaman Modal Dalam Negeri maka bisa diberikan dengan status Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Untuk Penanaman Modal Dalam Negeri bisa mendapatkan Hak Guna Bangunan. Bedasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah selanjutnya disebut PP Nomor 40 Tahun 1996 yang menjadi subjek pemegang Hak Guna Bangunan adalah Warga Negara Indonesia dan Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
Sehingga Akta yang dapat diberikan kepada pemilik Penanaman Modal Dalam Negeri yaitu Akta Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik atau Tanah Negara. Sesuai dalam pasal 35 ayat (1) UUPA menjelaskan Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Selanjutnya pada ayat (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.
Pasca berlakunya UU Cipta Kerja ini akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Pertama dampak bagi rakyat dengan pekerjaan sebagai petani, atas dasar mengurangi regulasi birokrasi yang begitu panjang, tetapi hanya menguntungkan para pemodal yang melakukan investasi saja karena membahayakan sendi ekonomi kerakyatan, khususnya para petani yang akhirya hanya bergantung sebagai petani penggarap saja. Adapun yang Kedua UU Cipta Kerja tidak berpihak pada masyarakat yang lemah posisi ekonominya, antara lain rakyat kecil dan masyarakat hukum adat, reformasi agraria dianggap tidak penting khususnya terhadap redistribusi lahan bagi petani dan penguasaan tanah ulayat oleh pengusaha perkebunan, redistribusi adalah distribusi kembali pendapatan masyarakat berpenghasilan lebih tinggi ke masyarakat berpenghasilan lebih rendah.26 Program redistribusi tanah ini untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Sehingga landreform merupakan sebuah alat perubahan sosial dalam perkembangan ekonomi, selain merupakan manifestasi dari tujuan politik, kebebasan, dan kemerdekaan suatu bangsa.27 Akan tetapi UU Cipta Kerja menimbulkan keraguan kepada masyarakat terhadap proses redistribusi ini karena tujuannya bukan untuk memerdekakan rakyat melainkan kepada pemodal/investor. Dampak yang Ketiga pada fungsi sosial atas tanah sesuai yang diamanatkan pasal 6 UUPA menjelaskan bahwa, “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Pasal tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai salah satu asas hukum tanah yang diistilahkan asas fungsi sosial hak atas tanah. Keberadaan asas fungsi sosial hak atas tanah dalam hukum tanah menjadi landasan fundamental bagi terwujudnya tanah yang bermanfaat bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat di negara kesejahteraan.28 Kedepannya UU Cipta Kerja ini hanya menghasilkan fungsi ekonomi saja, yang menyebabkan terjadi tumpang tindih pengaturan, UU Cipta Kerja klaster Pertanahan berpotensi mengganti ketentuan dalam UUPA bukan sebagai pelengkap dan penyempurna UUPA.
Untuk Penanaman Modal Asing hanya mendapatkan Hak Pakai saja. Bedasarkan pasal 39 PP Nomor 40 Tahun 1996 yang menjadi subyek dan dapat mempunyai hak pakai adalah:
-
a. Warga Negara Indonesia;
-
b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia;
-
c. Departemen Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah
Daerah;
-
d. Badan-badan keagamaan dan sosial;
-
e. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
-
f. Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia;
-
g. Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional.
Keberadaan Bank Tanah diatur dalam pasal 125 sampai dengan pasal 135 UU Cipta Kerja. Bank Tanah adalah badan khusus yang mengelola tanah, dan berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Pembentukan “bank tanah” ini bisa sebagai karpet merah pada pengusaha swasta (oligarki) mendapatkan tanah secara murah bahkan gratis, lewat regulasi yang dibuat pada UU Ciptaker dengan menggadang-gadang untuk peningkatan insvestasi di Indonesia, pasalnya pada pasal 127 UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa “badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit”. Frase “nonprofit” ini menimbulkan asumsi kesempatan besar pada pengusaha swasta atau pemodal besar (oligarki) untuk mendapatkan tanah secara murah atau bahkan gratis. Sehingga Akta yang dapat diberikan kepada pemilik Penanaman Modal Asing Perjanjian yang saling menguntungkan kedua belah pihak yaitu Akta Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik atau Tanah Negara.
Mengutip dari pandangan Jhon Austin dan Van Kan yang memberikan pandangan bahwa tujuan hukum merupkan semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum. Bagi mereka tujuan hukum hanyalah semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (legal certainty), yang mempresepsikannya hanya sebagai “kepastian undang-undang”, padahal realitasnya diluar perundang-undangan masih ada hukum yang lain, seperti halnya yaitu hukum kebiasaan (country law).29
Hasil penelitian ini menjelasakan bahwa melihat dari Pasal 9 ayat (2) UUPA yang tujuan wewenangnya diberikan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan serta kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia. Akan tetapi dalam Pasal 137 ayat (1) UU Cipta Kerja ini telah menyimpang dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) UUPA. Dalam UU Cipta kerja tidak dijelaskan bahwa yang berhak menguasai tanah negara yaitu masyarakat hukum adat, sehingga UU Cipta Kerja telah melanggar hak konstitusional masyarakat adat. Serta Pembentukan UU Cipta Kerja ini bisa sebagai karpet merah pada pengusaha swasta atau penanam modal asing dalam mendapatkan tanah secara murah bahkan gratis, dengan menggadang-gadang untuk peningkatan insvestasi di Indonesia, termuat pada pasal 127 UU Cipta Kerja dijelaskan bahwa “badan bank tanah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat transparan, akuntabel, dan nonprofit”. Frase
“nonprofit” ini menimbulkan asumsi kesempatan besar pada pengusaha swasta atau pemodal besar untuk mendapatkan tanah secara murah atau bahkan gratis.
Daftar Pustaka
Buku
Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
B, Harsono. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Universitas Trisakti, 2000.
Bachriadi, Dianto, Maria Ruwiastuti, and Noer Fauzi. Penghancuran Hak Masyarakat Adat Atas Tanah: Sistem Penguasaan Tanah Sengketa Dan Politik Hukum Agraria. Jakarta: KPA, 1997.
Fuady, Munir. “Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum.” Jakarta: Kencana, 2013.
Mahfud, M D. “Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi.” Yogyakarta: Gama Media, 1999.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
Pide, A Suriyaman Mustari, and M SH. Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang. Prenada Media, 2017.
Sihombing, B F. “Evolusi Kebijakan Pertanahan Dalam Hukum Tanah.” Indonesia. Cet 2 (2005).
Sumardjono, Maria S. Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi Dan Implementasi. Penerbit Buku Kompas, 2006.
Jurnal
Agustiwi, S H, and Asri MH. “Hukum Dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia.” Ratu Adil 3, no. 1 (n.d.): 220776.
Ardani, Ni Ketut. “Kepastian Hukum Hak Komunal Ditinjau Dari Pasal 16 Ayat (1) H Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.” Udayana University, 2017.
D, Hadiatmojo B. “Tanah Negara Dan Wewenang Pemberian Haknya.” Jurnal Keadilan 6, no. 1 (2012).
Dirgantara, Pebry. “Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik.” Acta Comitas, Jurnal Hukum Kenotariatan, n.d.
Doly, Denico. “Kewenangan Negara Dalam Penguasaan Tanah: Redistribusi Tanah Untuk Rakyat (The Authority Of The State In Land Tenure: Redistribution Of Land To The People).” Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 8, no. 2 (2017): 195–214.
Maladi, Yanis. “Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia.” Masalah-Masalah Hukum 41, no. 3 (2012): 432–42.
Pardede, Marulak. “Hak Menguasai Negara Dalam Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Peruntukannya.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, no. 4 (2019): 405–20.
Rejekiningsih, Triana. “Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis Dan Penerapannya Di Indonesia).” Yustisia Jurnal Hukum 5, no. 2 (2016): 298–325.
Santoso, Urip. “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Penguasaan Atas Tanah.” Jurnal Dinamika Hukum 12, no. 1 (2012): 186–96.
Sukarman, Hendra, and Wildan Sany Prasetiya. “Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law.” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 9, no. 1 (2021): 17–37.
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 10 No. 4 Desember 2021, 857-868
Sulianto, Geraldus, and Hanafi Tanawijaya. “PenguasaanTanah Bekas Hak Eigendom Verponding Setelah Berlakunya Undang–Undang Pokok Agraria (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1401 K/Pdt/2018).” Jurnal Hukum Adigama 3, no. 2 (2020): 470–91.
Suriadinata, Vincent. “Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 115–32.
Susetio, Wasis. “Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria.” Lex Jurnalica 10, no. 3 (2013): 18020.
Zainuddin, Zainuddin, and Zaki Ulya. “Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah Di Aceh.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 1 (2018): 139–52.
Zakie, Mukmin. “Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda.” Legality: Jurnal Ilmiah Hukum 24, no. 1 (2016): 40–55.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
Website
Kompas.com. “Apa Itu Redistribusi Pendapatan?” Accessed May 10, 2021.
https://www.kompas.com/skola/read/2021/04/07/141204069/apa-itu-redistribusi-pendapatan.
Walhi. “Membedah UU Cipta Kerja Di ‘Klinik Omnibus Law.’” Accessed December 26, 2020. https://www.walhi.or.id/membedah-uu-cipta-kerja-di-klinik-omnibus-
law.
868
Discussion and feedback