Mereposisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Suatu Keterlemparan (gowerfen-sein) dalam Mitos Modernitas
on
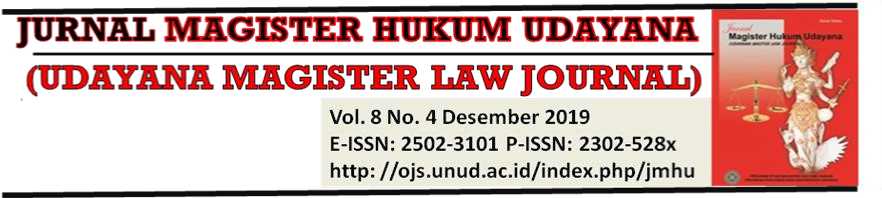
Mereposisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Suatu Keterlemparan (gowerfen-sein) dalam Mitos Modernitas
Rocky Marbun1
1Fakultas Hukum Universitas Pancasila, E-mail: rocky_marbun@univpancasila.ac.id
Info Artikel
Masuk: 1 Agustus 2019 Diterima: 15 Nopember 2019
Terbit: 31 Desember 2019
Keywords:
Criminal Justice System; Myth of modernity; Victim; Throwness
Kata kunci:
Sistem Peradilan Pidana; Mitos modernitas; Korban;
Keterlemparan
Corresponding Author:
Rocky marbun, Email:
rocky_marbun@univpancasila.a c.id
DOI:
10.24843/JMHU.2019.v08.i04.p07
Abstract
Myths in the modern era are things that are considered like truth. It arises through the process of hegemony and dialectical domination by the authority in history. So, myth is a phenomenon of common sense without criticism. The state's presence in the criminal justice process as a grand narrative identified with the interests of victims and society, in general, is common sense without criticism. This study aims to reveal whether the myth of modernity is a representation of victims in the Criminal Justice System. This study uses a normative juridical method based on secondary data with several models of approaches, including conceptual approaches, philosophical approaches, and critical approaches. The result of this research shows the phenomenon of objectification and reification of the people as victims in the Criminal Justice System in Indonesia.
Abstrak
Mitos dalam era modern merupakan hal-hal yang diandaikan begitu saja sebagai suatu kebenaran. Hal tersebut tampil melalui proses hegemoni dan dominasi dalam dialektika otoritas dalam sejarah. Sehingga, mitos merupakan suatu fenomena common sense tanpa kritik. Kehadiran negara dalam proses peradilan pidana sebagai narasi tunggal (grand narrative) yang diidentikan dengan kepentingan korban dan masyarakat secara umum, merupakan common sense tanpa kritik. Penelitian ini ditujukan untuk membongkar apakah mitos modernitas tersebut merupakan representasi korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berbasis kepada data sekunder dengan beberapa model pendekatan, antara lain pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, dan pendekatan kritis. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya fenomena objektivikasi dan reifikasi terhadap masyarakat sebagai korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.
dan pandangan positif—yang menginginkan hakim melakukan penggalian unsur-unsur subjektif dari korban dan tidak hanya sekadar kewenangan absolut dari Penuntut Umum/Negara.1
Desakan secara nasional maupun internasional yang kemudian menjadi salah satu landasan politik hukum bagi diakomodirnya kepentingan korban justru ditandai dengan fenomena sosial berupa gerakan reformasi total, sebagaimana kemudian dinormatifkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia [UU No. 26/2000]. Yang kemudian disusul dengan berbagai peraturan perundang-undangan, hingga terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [UU No. 13/2006] sebagaimana telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [UU No. 31/2014].
Demikian pula dengan peraturan pelaksana mengenai perlindungan hukum terhadap korban, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi [PP No. 02/2002], Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat [PP No. 03/2002] dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Saksi dan Korban [PP No. 44/2008].
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sebenarnya kita dapatlah mempertanyakan apakah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [UU No. 8/1981—atau kenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)] dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP] tidak mengenal perlindungan hukum terhadap korban?
Pasal 14 c ayat (1) KUHP, sebagai teks klasik, yang menegaskan bahwa Hakim memiliki kewenangan—yang diwakili dengan kata ‘boleh’, untuk menjatuhkan putusan yang mengandung syarat khusus untuk mengganti kerugian sebagai akibat yang muncul dari terjadinya suatu tindak pidana. Demikian pula pengaturan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 95 KUHAP yang pula mengatur pemberian ganti kerugian. Walaupun Peneliti tidak terlalu bersepakat dengan pandangan yang mendasarkan kepada Pasal 77 sampai dengan Pasal 95 KUHAP sebagai isyarat adanya perlindungan terhadap korban.2
Perkembangan terbaru dari perjalanan rasionalitas atas perlindungan terhadap korban adalah masuknya konsep ‘restorative justice’ dalam sistem hukum di Indonesia, sebagaimana diaturnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [UU No. 11/2012]. Sehingga, UU No. 11/2012 tersebut ‘seharusnya’ telah mematahkan pihak-pihak yang menegasikan eksistensi korban dalam Sistem Peradilan Pidana—walaupun masih bersifat parsial. Artinya, pada
peristiwa tindak pidana umum belum menjadi suatu konvensi (kesepakatan) untuk diterapkan semangat dari restorative justice tersebut.
Walaupun demikian, rasanya patut diapresiasi langkah Kapolri dengan mengeluarkan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative justice) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana [SE Kapolri No. 08/2018]. Permasalahannya adalah bagaimana implementasi keseluruhan peraturan perundang-undangan tersebut?
Menurut Zulkipli dalam penelitiannya yang berjudul “Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi manusia Yang Berat” mengungkapkan 3 (tiga) putusan pengadilan yang tidak memuat unsur kompensasi dan restitusi kepada korban. 3 Penelitian yang terbaru dilakukan oleh Raymundus Loin dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) di Perbatasan”, yang mengkaji 26 (dua puluh enam) putusan pengadilan di Provinsi Kalimantan, dimana hasilnya adalah tidak ada satupun yang memuat unsur kompensasi dan/atau restitusi.4
Begitu banyak peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dengan fokus kepada pengakomodiran kepentingan korban, baik yang berbasis restorative justice maupun yang tidak, namun dalam ranah praktik peradilan pidana, seolah kekayaan keilmuan hukum tersebut dicabut dari akarnya. Sehingga, seolah-olah Ilmu Hukum hanya membahas hal-hal yang bersifat pragmatisme semata. Oleh karena, hukum pada tataran praktis, bergantung kepada implementasi dari fiksi hukum. Akibatnya, norma-norma hukum tersebut mengalami kekaburan dalam praxis-nya, yang hanya berlaku pada satu sisi semata yaitu masyarakat, dan keberlakukannya tidak memunculkan kewajiban bagi penegak hukum.
Tentunya, hal tersebut di atas memunculkan berbagai pertanyaan, apakah yang terjadi? Mengapa sekian banyak peraturan perundang-undangan—semenjak dari tahun 2000, hingga keluarnya SE Kapolri No. 8/2018, ilmu hukum hanya berjaya di ranah teoretis, dan tidak di ranah praxis? Sebagaimana dijelaskan oleh Ade Saptomo— Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jakarta, yang menjelaskan bahwa hakim, jaksa dan pengacara merupakan lulusan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum, namun mengapa pada praktik menjadi berbeda.5
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ini bertujuan untuk membongkar narasi-narasi tunggal (grand narative) yang bersembunyi di balik Teori Fiksi Hukum sebagai suatu mitos dengan pengandaian begitu saja sebagai kebenaran praxis dalam Sistem Peradilan Pidana. Sehingga, penelitian ini akan mengarahkan kepada praxis Ilmu Hukum yang bersifat emansipatoris bagi masyarakat luas.
ISSN: 1978-1520
-
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, oleh karena, penelitian ini memfokuskan kepada penelaahan yang bertitik tolak dari kekaburan norma6. Penelitian ini pula menggunakan beberapa model pendekatan penelitian yaitu philosophical approach, statute approach, conceptual approach, serta critical approach. Adapun teknik penelusuran terhadap bahan-bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, dengan model analisis kajian yang menggunakan analisis kualitatif (penafsiran/interpretasi) untuk menggali kedalaman makna baik secara filosofis maupun konseptual terhadap norma hukum dan sikap penegak hukum—sebagai konsekuensi dari penggunaan critical approach.
Diskursus mengenai apakah itu ‘mitos’ tidaklah dimaksudkan untuk membahas hal-hal yang bersifat mistis, irrasional, dan khayal. Adalah Max Horkheimer dan Theodor W. Adorno yang menjelaskan sebagai berikut:7
“Kami percaya bahwa bagian-bagian ini akan memberikan sumbangan pada kejernihan terhadap pemahaman teoritik, sejauh kami menunjukkan bahwa sebab utama dari pengungkapan kembali pencerahan ke dalam mitologi adalah tidak diusahakan sebanyak di dalam mitologi-mitologi nasionalis, pagan dan modern lain yang disusun secara tepat untuk menyusun sebuah pengembalian semacam ini, tetapi di dalam Pencerahan itu sendiri ketika dilumpuhkan oleh ketakutan terhadap kebenaran. Di dalam hal ini, kedua konsep ini dipahami tidak semata-mata secara historis-kultural (geistesgeschichtlich) tetapi secara nyata. Demikian juga Pencerahan mengungkapkan gerakan aktual dari masyarakat sipil secara keseluruhan di dalam aspek idenya sebagaimana yang ada di dalam individu-individu dan lembaga-lembaga, sehingga kebenaran tidak semata-mata kesadaran rasional tetapi sama juga bentuk yang diasumsikan di dalam kehidupan nyata. Anak peradaban modern yang patuh dirasuki oleh sebuah ketakutan menyimpang dari fakta-fakta yang, di dalam tindakan persepsi itu juga, konvensi-konvensi dominan tentang ilmu pengetahuan, perdagangan dan politik – seperti klik – telah terbentuk; kecemasannya tidak lain daripada ketakutan terhadap penyimpangan sosial. Konvensi-konvensi yang sama merumuskan gagasan tentang kejelasan linguistik dan konseptual di mana seni, sastra dan filsafat sekarang harus memuaskan. Sejak gagasan ini menyatakan pernyataan negatif terhadap fakta-fakta atau terhadap bentuk-bentuk dominan dari pemikiran sebagai formalisme yang tidak jelas atau – terutama – asing, dan oleh karena itu tabu, ia mengutuk semangat peningkatan kegelapan. Adalah ciri khas dari kesakitan itu bahwa bahkan pembaharu yang bermaksud baik yang menyarankan pembaharuan, dengan adopsinya pada mode kategorisasi yang tersembunyi dari filsafat buruk yang ia sembunyikan, menguatkan kekuasaan dari tatanan mapan itu juga yang diusahakan untuk dirusak. Kejelasan palsu adalah hanya nama lain dari mitos; dan mitos selalu
tidak jelas dan mencerahkan sekaligus: selalu menggunakan alat-alat keakraban dan pembebasan yang lurus untuk menghindari kerja konseptualisasi.”
Peneliti memang dengan sengaja menampilkan pandangan dari kedua filsuf dari Mahzab Frankfurt—yang konsen mengkonstruksikan Teori Kritis, secara utuh walaupun tidak dipungkiri ada permasalahan penterjemahan secara gramatikal dari teks aslinya. Namun demikian, menurut Peneliti masih dapat kita simpulkan apa yang dimaksud oleh kedua filsuf tersebut, dengan merujuk kepada ahli filsafat lainnya.
Konstruksi dari Teori Kritis yang dikemukakan oleh Mahzab Frankfurt memiliki ketertujuan sebagai suatu model kritik terhadap rasionalitas instrumental yang menjadi patologi modernitas, dengan tujuan untuk menganalisis masalah sosial, yang bertopang pada kehendak manusia untuk membebaskan diri dari dikotomi rasio murni dan praxis sosial. Cara tersebut ditempuh untuk mewujudkan transformasi sosial yang terbebaskan dari mitos modernitas yang semu dan instrumental.8
Maka, untuk memahami intensi dasar dari kedua filsuf tersebut, menjadi sangat menarik ketika kita mencermati interpretasi F. Budi Hardiman 9 atas pandangan mereka yang menjelaskan bahwa Horkheimer mengkritik asumsi-asumsi dasar dari Teori Tradisional—paham positivistik semenjak era Cartesian hingga Kant, yang diandaikan begitu saja masuk ke dalam kenyataan sosial sebagai objeknya. Sehingga Teori Tradisional tersebut menjadi ideologis dalam arti melestarikan kemapanan struktur sosial yang pada hakikatnya menindas, dengan tiga cara, yaitu (1). mengandaikan pengetahuan bersifat universal dan ahistoris, (2). mengandaikan bersifat netral sehingga menghalangi pemikir untuk mempertanyakan struktur sosial yang tidak adil, dan (3). mencabut teori dari ranah praxis.
Akibatnya, cara pandang suatu ilmu pengetahuan ‘seolah-olah’ lepas dari kepentingan-kepentingan. Hal tersebut tentunya merupakan suatu hal yang menyesatkan, oleh karena, menurut Jürgen Habermas bahwa dalam daya kekuatan refleksi diri, pengetahuan dan kepentingan adalah satu. 10 Artinya, pengetahuan-pengetahuan tersebut diletakkan pada posisi puncak tanpa tersentuh oleh daya kritik. Kalaupun tersentuh, maka pengetahuan-pengetahuan tersebut tidak tergoyahkan, oleh karena, ditumbuhkembangkan berbasis kepada hegemoni dan dominasi kekuasaan.
Menurut Antonio Gramsci, hegemoni merupakan sebuah dominasi oleh satu kelompok yang lain, tanpa menggunakan, kekerasan sebagai instrumennya, sebagai gagasan yang diarahkan oleh strata sosial yang mendominasi terhadap strata sosial yang inferior atau dikuasai. Gramsci pula menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan common sense dan tidak memberatkan. Hegemoni memiliki tujuan untuk membuat masyarakat percaya dengan prinsip-prinsip, norma-norma dan hukum yang dipandang sebagai hal yang dapat memberikan kesejahteraan umum, walaupun memiliki makna sebaliknya.11
Penggiringan opini—sebagai sesuatu hal yang benar apa adanya, melalui hegemoni sangat berbeda dengan indoktrinasi. Pengetahuan tersebut disebarluaskan dan dikonstruksikan berbasis kepada rasionalitas ilmiah oleh setiap intelektual organik dan intelektual tradisional. Sehingga, proses penyebarluasan hingga sampai kepada suatu tataran ideologis tersebut, bersembunyi dibalik kekuasaan, yaitu kekuasaan intelektual yang berada pada kelompok yang mendominasi.
Menurut Gramsci, kekuatan hegemonik tersebut bekerja untuk meyakinkan individu dan kelas sosial untuk berlangganan nilai-nilai sosial dan norma-norma sistem eksploitatif yang inheren. Ini adalah bentuk kekuatan sosial yang bergantung pada kesukarelaan dan partisipasi, daripada ancaman hukuman karena ketidaktaatan. Hegemoni muncul sebagai “common sense” yang memandu pemahaman duniawi kita sehari-hari.12 Lebih lanjut Gramsci menjelaskan bahwa sebelum menggunakan paksaan dan kekuasaan, maka Negara berusaha membuat aturannya dapat diterima oleh semua kelas. 13 Pada posisi inilah, negara memanfaatkan tangan-tangan dari para intelektual untuk merancang dan merumuskan aturan-aturan tersebut, serta melalui proses pengajaran-pengajaran berbasis kepada ketersebaran doktrin. Para intelektual itu sendiri merupakan pihak yang memiliki otorisasi dalam menciptakan pandangan-pandangan ilmiah yang persuasif, maka ada unsur relasi kuasa pula dari sudut pandang intelektual.
Kekuasaan yang muncul karena adanya relasi-relasi dari berbagai kekuatan akan berlangsung secara absolut dan mengeyampingkan aspek kesadaran manusia. Oleh karena, menurut Michel Foucault, kekuasaan tersebut hanya merupakan strategi untuk menentukan sistem, aturan, susunan dan regulasi yang muncul dari relasi internal dari kekuatan-kekuatan tersebut.14 Apabila kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan, maka pemegang kekuasaan guna melanggengkan kekuasaannya, akan mengontrol pengetahuan yang tumbuh dan berkembang di sekitar kekuasaannya.
Teori Fiksi Hukum atau Fiksi Hukum, Peneliti letakan sebagai mitos modernitas yang utama dalam Politik Hukum dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Kita semua mengetahui dan memahami fungsi dari fiksi hukum yaitu guna menjamin adanya legal certainty (kepastian hukum) di dalam masyarakat. Sehingga, asumsinya adalah ketika penegakan hukum mengandung kepastian hukum, maka akan tercipta kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Berdasarkan keinginan tersebut, negara melalui alat kekuasaannya menghegemoni dan mendominasi masyarakat melalui suatu adagium “setiap orang dianggap mengetahui undang-undang”. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [UU No. 12/2011] yang menegaskan sebagai berikut:
“Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-Undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:
-
a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
-
b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
-
c. Berita Negara Republik Indonesia;
-
d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
-
e. Lembaran Daerah;
-
f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
-
g. Berita Daerah.
Mengapa Fiksi Hukum diletakan sebagai suatu mitos modernitas? Beranjak dari pandangan J.A. Pontier yang menjelaskan bahwa kegiatan penemuan hukum merupakan tindakan otoritas publik (tindakan pemerintah, overheidshandelen) dan merupakan monopoli otoritas publik (overheidsmonopolie) sehingga dapat memperoleh bantuan menggunakan kekerasan. 15 Artinya, keseluruhan tindakan hukum yang berbasis kepada pola penalaran dan penafsiran terhadap norma hukum merupakan tindakan absolut dari pejabat publik—dalam hal ini Aparat Penegak Hukum pun merupakan Pejabat Publik.
Sehingga, menurut Agus Surono, ketidaktahuan akan keberlakuan suatu undang-undang yang dilanggar tidak termasuk sebagai alasan pemaaf atau “ignorantia legis excusat neminem”.16 Dalam konteks sebagai pelanggar Undang-Undang, rasanya hal tersebut masih dapat dipahami—walaupun terpaksa, namun dalam konteks pemenuhan hak? Maka, sebenarnya negara berkelit untuk menjalankan kewajibannya. Oleh karena, dalam fiksi hukum yang semula ditujukan kepada suatu bentuk pelanggaran aturan hukum oleh masyarakat—yang memang tujuannya adalah masyarakat berperilaku yang ajeg, menjadi adalah kewajiban masyarakat untuk mengetahui hak-haknya secara mandiri.
Padahal Pasal 96 ayat (1) UU No. 12/2011 memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh masukkan baik secara lisan dan/atau tertulis, yang mekanismenya diatur melalui Pasal 96 ayat (2) UU No. 12/2011 yaitu melalui (a). rapat dengar pendapat umum, (b). kunjungan kerja, (c). sosialisasi dan/atau (d). seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
Anehnya, Kementerian Hukum dan HAM ketika melaksanakan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan mekanisme diskusi yang dilaksanakan di Hotel Grage Horizon Pantai Panjang Kota Bengkulu.17 Sedangkan, amanah UU No. 12/2011 jelas membedakan antara sosialisasi dengan diskusi, dimana tidak ada masyarakat awam yang hadir.
ISSN: 1978-1520
Atau misalnya yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang bahaya pornografi di lingkungan pendidikan yang bertempat di Hotel Grand Asrilia, Buah Batu.18
Kedua contoh sosialisasi di atas, tetap merupakan salah satu upaya mempertahankan fiksi hukum sebagai mitos, oleh karena, bebannya kemudian beralih dari negara kepada peserta sosialisasi. Pertanyaannya sekarang adalah apakah para peserta melanjutkan estafet tersebut? Ketika tidak berlanjut, siapakah yang akan dimintakan pertanggungjawaban dari amanah undang-undang? Ketika tidak berlanjut, bagaimana tanggung jawab negara melalui alat kelengkapannya terhadap masyarakat yang menjadi korban?
Persoalan-persoalan tersebut, seolah-olah diandaikan begitu saja kepada suatu kebenaran yang diyakini bahwa masyarakat wajib mencari tahu sendiri mengenai hak-haknya melalui Fiksi Hukum. Terhadap hal tersebut, menjadi menarik pandangan dari Bentham—sebagai seorang positivitis, menegaskan bahwa fiksi, berdiri dalam hubungan yang jauh lebih rumit dengan pemahaman kebenaran atau kenyataan daripada oposisi sederhana fakta terhadap fiksi yang tersirat. Sehingga, Bentham mengecam fiksi hukum tersebut sebagai kepalsuan dan kebohongan.19
Mungkin agak sedikit arbitrer, Peneliti memasukkan pula kajian Sistem Peradilan Pidana sebagai salah satu dari mitos-mitos yang diandaikan begitu saja berkembang dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Namun demikian, gejala yang mengarahkan kepada sifat-sifat ideologis menjadi mitos sudah dipupuk semenjak lama dalam tataran teoretis yang menghegemoni—jika tidak dapat disebut mendominasi.
Pandangan doktrin secara nasional yang berkaitan dengan komponen dari Sistem Peradilan Pidana sudah merupakan sesuatu hal yang telah menjadi common sense, antara lain misalnya menurut Mardjono Reksodiputro yang menegaskan bahwa dibutuhkan kerjasama antar komponen dalam suatu sistem—dalam hal ini adalah peradilan pidana, guna ketercapaian tujuan, terutama instansi-instansi sebagai berikut:20
-
1. Kepolisian;
-
2. Kejaksaan;
-
3. Pengadilan; dan
-
4. Lembaga Pemasyarakatan.
Menurut Romli Atmasasmita, institusi dalam sistem peradilan pidana yang memiliki legitimasi, baik berdasarkan kebijakan pidana (criminal policy) maupun yang mengacu kepada praktik penegakan hukum, terdiri dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, serta Legislator.21
Adapun M. Yahya Harahap yang mengacu kepada kerangka landasan dalam kegiatan implementasi criminal justice system, adalah wujud dari “fungsi gabungan” (colection of function), maka mengajukan komposisi dari sub-sistem dari Sistem Peradilan Pidana adalah:22
-
1. Legislator;
-
2. Polisi,
-
3. Jaksa,
-
4. Pengadilan, dan
-
5. Lembaga Pemasyarakatan, serta
-
6. Badan yang berkaitan, baik yang ada di lingkungan pemerintahan atau di
luarnya.
Keseragaman komponen atau sub-sistem, pula diungkapkan oleh Indriyanto Seno Adji, yang membagi lembaga pelaksanaan menjadi 4 (empat) institusi, yaitu:23
-
1. Lembaga Kepolisian;
-
2. Lembaga Kejaksaan;
-
3. Lembaga Peradilan; dan
-
4. Lembaga Pemasyarakatan.
Rusli Muhammad, pula mengungkapkan hal yang senada, bahwa sebagai suatu sistem, dalam Sistem Peradilan Pidana terdiri dari entitas-entitas sebagai institusi penegak hukum yang menjalankan fungsinya dalam praktik peradilan pidana antara lain adalah institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Pemasyarakatan.24
Sekarang, mari kita lihat doktrin secara internasional, dimana menurut Jeremy Travis, dimana dalam Sistem Peradilan Pidana selain terdiri dari Polisi, Jaksa, dan pengadilan, dan penjara, Jeremy Travis pula memasukkan lembaga masyarakat sebagai entitas.25 Artinya, Jeremy Travis membedakan antara Penjara dengan Lembaga Masyarakat Sedangkan Philip. P. Purpura menegaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) merupakan suatu sistem yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.26
ISSN: 1978-1520
Adapun Neil C. Chalin, pada mula komponen dari Sistem Peradilan Pidana hanyalah terdiri dari Polisi dan Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan yang timbul di dalam tata kehidupan masyarakat pada tingkat local government. Criminal Justice System tersebut tidak menempatkan Jaksa (prosecutor) dalam sistem itu, mengingat Jaksa dianggap sebagai bagian dari sub-sistem peradilan (court) dengan segala aktivitasnya di peradilan.27
Demikian pula pandangan yang dikemukakan oleh Larry J. Siegel yang menjelaskan komponen Sistem Peradilan Pidana terdiri dari perkumpulan lembaga-lembaga yaitu kepolisian, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan lain-lain.28
Tentunya dapat dibenarkan secara logis bahwa lembaga-lembaga tersebut sebagai suatu institusi resmi dari negara yang hadir mewakili kepentingan korban. Benarkah demikian?
3.4. Pembahasan
Korban, secara normatif, memiliki makna orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (vide Pasal 1 angka 3 UU No. 31/2014). Oleh karena itu, UU No. 31/2014 memuat begitu banyak hak yang wajib diberikan kepada korban, diantaranya adalah kompensasi dan restitusi.
Permasalahannya adalah pemberian ganti kerugian tersebut bukanlah merupakan tindakan komunikatif yang bersifat langsung. Tindakan komunikatif yang dikonstruksikan dalam PP No. 44/2008 merupakan tindakan komunikatif yang melibatkan pihak otoritas, yaitu LPSK, Penuntut Umum dan Pengadilan. Artinya, korban memang tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam Sistem Peradilan Pidana.
Ketika keseluruhan kajian mengenai Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem, maka pada hakekatnya, hanya berfokus kepada dua permasalahan, yaitu pertama, mengkaji entitas yang akan dilibatkan dalam suatu sistem; dan kedua, mengkaji mengenai normativisasi prosedur-prosedur dan cara-cara dalam melaksanakan peradilan pidana.
Apabila memang demikian kontruksi logikanya, maka akan memunculkan kekhawatiran, apakah korban mengetahui bagaimana proses permohonan ganti kerugian tersebut? Berdasarkan 26 (dua puluh enam) putusan pengadilan yang dikemukakan oleh Raymundus Loin dan 3 (tiga) putusan pengadilan yang dikemukakan oleh Zulkipli, tidak ada satupun permohonan restitusi atau kompensasi yang dimuat dalam tuntutan dan putusan pengadilan. Padahal, sebagai pejabat publik—dalam perspektif welfare state sebagaimana termuat dalam Alinea IV UUD NRI 1945, memiliki fungsi pengayom bagi masyarakat. Sehingga, Penuntut Umum —yang menjadikan fiksi hukum sebagai pra-anggapan atau prasangka (vorurteil), menjadi bersikap pasif.
Memang, PP No. 44/2008 memberikan peluang kepada korban dan/atau keluarga korban menggunakan jasa hukum seorang Advokat. Namun itu pun, kembali kepada
seberapa jauh pemahaman seorang Advokat dalam memahami mekanisme permohonan restitusi dan/atau kompensasi tersebut.
Hal tersebut menunjukkan kepada kita, bahwa politik hukum pidana dalam kaitannya dengan rancang bangun Sistem Peradilan Pidana tetap menciptakan distingsi dan distansi antara korban dengan Sistem Peradilan Pidana. Distingsi dan distansi tersebut menjadi suatu common sense dalam Sistem Peradilan Pidana ketika dipisahkan dan dibedakan dengan praktik peradilan pidana, baik secara teoretis maupun secara praxis.
Seseorang yang telah menjadi korban dari suatu tindak pidana tidak dapat menuntut—atau dengan bahasa yang lebih halus adalah meminta, kepada Penuntut Umum untuk membuat suatu keputusan agar memasukkan permohonan restitusi ke dalam tuntutan, ataupun secara langsung kepada pengadilan. Oleh karena, institusi Kejaksaan atau institusi Kepolisian tersebut memahami penegakan hukum pidana terlepas dari fungsinya sebagai organ pemerintahan. Pun demikian, dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan [UU No. 30/2014] mencabut kewajiban bagi Kepolisian dan Kejaksaan untuk mensosialisasikan setiap tindakan dan/atau keputusan kepada masyarakat ketika berhubungan dengan “Keputusan yang menyangkut penegakan hukum”.
Pada akhirnya, reposisi korban adalah hal yang sia-sia ketika mitos-mitos yang tumbuh subur dan berkembang di lingkungan institusi penegakan hukum tidak memperoleh kritik yang dekonstruktif. Konstruksi Sistem Peradilan Pidana yang demikian hanya menciptakan hierarki oposisi biner yaitu Aparat Penegak Hukum dan Pelaku Tindak Pidana, sedangkan dalam terjadinya suatu peristiwa pidana, justru memunculkan oposisi-oposisi biner lainnya yang tidak dipertimbangkan yaitu korban.
Mitos bahwa Negara cq Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum sebagai perwakilan dari Masyarakat—dalam hal ini korban, semakin tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena, adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 033/PUU-XIV/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang memberikan tafsir konstitusi terhadap Pasal 263 ayat (1) KUHAP dimana Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.
Artinya, secara yuridis normatif—pada awalnya, Jaksa Penuntut Umum masih dapat melakukan interpretasi berbasis kepada kepentingan korban, namun semenjak munculnya putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum sebagai perpanjangan tangan Negara untuk mengakomodir kepentingan korban, menjadi hilang. Yang hilang tersebut hendaknya dipahami sebagai kepentingan Korban, dan bukan kepentingan Negara.
Apabila konstruksi argumentasinya adalah Permohonan Peninjauan Kembali merupakan hak dari Terdakwa untuk melakukan upaya hukum luar biasa, maka argumentasi tersebut, pun dapatlah dianggap sebagai mitos yang dilanggengkan melalui konsep hegemoni dan dominasi. Konsep hegemoni terhadap mitos tersebut bekerja berbasis kepada doktrin-doktrin dari Ahli Hukum yang melakukan interpretasi historis atas perbandingan antara KUHAP dan HIR, berkaitan dengan kekuasaan dan kewenangan yang absolut dalam HIR, sehingga KUHAP dipandang sebagai pembatasan atas kekuasaan dan kewenangan dari Aparat Penegak Hukum (APH) masa lalu.
Mengacu kepada kondisi-kondisi di atas, maka sebenarnya masih dapat melakukan suatu perbantahan atas doktrin tersebut, dimana perseteruan antara Jaksa Penuntut
Umum dengan Kuasa Hukum Terdakwa, sangat dimungkinkan munculnya kemenangan di pihak Kuasa Hukum Terdakwa oleh beberapa faktor, yaitu pertama, ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum dalam mendalilkan tuntutannya—namun bukan berarti fakta sosialnya harus diabaikan; kedua, proses pembuktian dalam persidangan perkara pidana—selain didasarkan kepada dua alat bukti yang sah, menjadi sangat bergantung kepada ‘keyakinan hakim’ yang memberikan ‘seolah-olah’ objektif namun sebenarnya merupakan putusan yang bersifat subjektif. Oleh karena, suatu keyakinan merupakan hal yang bersifat mental dalam dirinya.
Sehingga, konsep dominasi terhadap mitos tersebut, sudah dicanangkan semenjak proses legislasi hingga diundangkannya KUHAP dengan menerapkan Pasal 3 KUHAP, sehingga memang kewenangan Jaksa Penuntut Umum dibatasi melalui Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang ternyata mengandung kekaburan norma hukum. Itulah penyebabnya Jaksa Penuntut Umum pada perkara tertentu melakukan interpretasi yang cukup progresif. Namun demikian, konsep dominasi melalui perundang-undangan dikuatkan dengan konsep hegemoni dari para ahli hukum, bahwa KUHAP tidak boleh ditafsirkan, selain menggunakan penafsiran gramatikal—yang anehnya justru menggunakan model gramatika-leksikal.
Keseluruhan pola penafsiran yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum berbasis kepada kewenangannya, justru memunculkan perilaku dan model komunikasi yang bersifat biner. Kemampuan rasio—termasuk pengaruh dari budaya hukum institusi, untuk memahami kewenangan dan wewenang—berbasis peraturan perundang-undangan, yang dimiliki Aparat Penegak Hukum justru memunculkan sikap mental dan perilaku yang diwujudkan dalam bentuk bahasa-bahasa penolakan untuk mengambil keputusan yang seharusnya. 29 Kondisi yang demikian, sebenarnya merupakan suatu kajian yang menarik dalam ranah psikolinguistik, dimana menurut Field, yang menjelaskan bahwa psycholinguistics explores the relationship between the human mind and language.30
Berdasarkan hal tersebut, maka tidaklah mengherankan ketika setiap Aparat Penegak Hukum—dalam kaitannya dengan Fiksi Hukum, mengambil posisi yang hanya berdasarkan pemaknaan yang sempit atas kewenangan dan wewenang yang dimilikinya.
4. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka mitos-mitos modernitas dalam Sistem Peradilan Pidana, selalu dipertahankan untuk menjaga status quo dari Aparat Penegak Hukum (APH). Dengan berlindung di balik makna dari Fiksi Hukum, Aparat Penegak Hukum (APH) bekerja berdasarkan kewenangan dan wewenangnya secara
gramatikal-leksikal. Artinya, kewajiban memahami perundang-undangan untuk mencapai hak-hak masyarakat—khususnya korban, hanya dibebankan kepada yang berkepentingan semata. Hal tersebut dibuktikan dengan dimunculkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengakomodir kepentingan korban, yang tidak diakomodir oleh Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Namun demikian, eksistensi LPSK itu sendiri tidaklah mandiri, oleh karena, sosialisasi—sebagai akibat dari fiksi hukum, tidak dilaksanakan secara langsung, namun diarahkan kepada komponen-komponen dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri. Sedangkan masyarakat—dalam hal ini korban, bukanlah merupakan entitas dari Sistem Peradilan Pidana. Oleh karena itu, Aparat Penegak Hukum—khususnya Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, dengan mengacu kepada Teori Fiksi Hukum, seharusnya berperan aktif untuk memasukkan unsur kompensasi dan restitusi baik dalam berkas penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutannya. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari diakomodirnya Teori Fiksi Hukum dan pelaksanaan fungsi melayani dan fungsi mengayomi dari Aparat Penegak Hukum.
Berdasarkan kesimpulan tersebutlah, maka perlu kiranya melakukan rekonstruksi komponen Sistem Peradilan Pidana dengan memasukkan Masyarakat—khususnya Korban, sebagai suatu entitas.
Daftar Pustaka
Buku
Adji, I.S. (2001). Arah Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji, S.H & Rekan.
Adji, I.S. (2011). KUHAP Dalam Perspektif. Jakarta: DIADIT MEDIA.
Atmasasmita, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana.
Diantha, I. M. P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Prenada Media.
Faruk. (2010). Pengantar Sosiologi Sastra: Dari Strukturalisme Genetik sampai Post-Modernisme. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Foucault, M. (2000). Seks dan Kekuasaan. Jakarta: Gramedia.
Harahap, M.Y. (2004). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika.
Hardiman, F.B. (2009). Kritik Ideologi. Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas. Yogyakarta: Kanisius.
Hardiman, F.B. Horkheimer dan Teori Kritis, makalah dipresentasikan dalam Kelas Filsafat Kontemporer, Serambi Salihara, Sabtu, 18 Maret 2017.
Horkheimer, M, & Adorno, T.W. (2014). Dialektika Pencerahan. Mencari Identitas Manusia Rasional. Yogyakarta: IRCiSoD.
Muhammad, R. (2011). Sistem Peradilan Pidana Indoensia. Yogyakarta: UII Press.
Pontier, J.A. (2008). Rechtsvinding (Penemuan Hukum). Bandung: Jendela Mas Pustaka.
Reksodiputro, M. (2007). Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
Siegel, L.J. (2010). Introduction to Criminal Justice. Belmont-USA: Wadsworth.
Sunaryo, S. (2005). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press.
Surono, A. (2013). Fiksi Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia.
Travis, J. Summoning the Superheroes. Harnessing Science and Passion to Create a More Effective and Humane Respone to Crime, dalam Mauer, M. & Epstein, K. [Ed]. (2012). To Build a Better Criminal Justice System. 25 Experts Envision the Next 25 Years of Reform, USA: The Sentencing Project.
Jurnal
El Aidi, A., & Yechouti, Y. (2017). Antonio Gramsci’s Theory of Cultural Hegemony in Edward Said’s Orientalism. GALAXY International Multidisiciplinary Research Journal, 6(5), 1-10.
Mahaswa, R.K. (2017). Merajut Teori Kritis, Jurnal Cogito, 4(1), 75.
Natsir, N. (2017). Hubungan Psikolinguistik dalam Pemerolehan dan Pembelajaran Bahasa. RETORIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya, 10(1). 20-29.
https://doi.org/10.26858/retorika.v10i1.4610
Stolzenberg, N. M. (1999). Bentham's Theory of Fictions—A “Curious Double Language”. Law & Literature, 11(2), 223-261.
https://doi.org/10.1080/1535685X.1999.11015598
Stoddart, M.C.J. Ideology, Hegemony, Discourse: A Critical Review of Theories of Knowledge and Power. Social Thought & Research, Vol. 28, 201. Retrieved From https://pdfs.semanticscholar.org/f66b/93d70a3ba41d23704c25d24f0e1a82935d 0e.pdf/ (Diunduh 01 Agustus 2019)
Stoddart, M. C. (2007). Ideology, hegemony, discourse: A critical review of theories of knowledge and power. Social Thought & Research, 191-225.
Tesis dan Disertasi
Mudzakkir. (2001). Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pdana. Disertasi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
Zulkipli. (2011). Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi manusia Yang Berat. Tesis pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Loin, R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) di Perbatasan. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya.
Online/World Wide Web:
“Sosialisasi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Melalui Seminar dan Diskusi”, diakses pada https://bengkulu.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/2634-sosialisasi-lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban-melalui-seminar-dan-diskusi
Press Release Konfrensi Press Sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Lingkungan Pendidikan, Siaran Pers Nomor: B-136 /Set/Rokum/MP 01/12/2016, diakases pada
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1284/sosialisasi-undang-undang-nomor-44-tahun-2008-tentang-pornografi-di-lingkungan-pendidikan
538
Discussion and feedback