Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
on
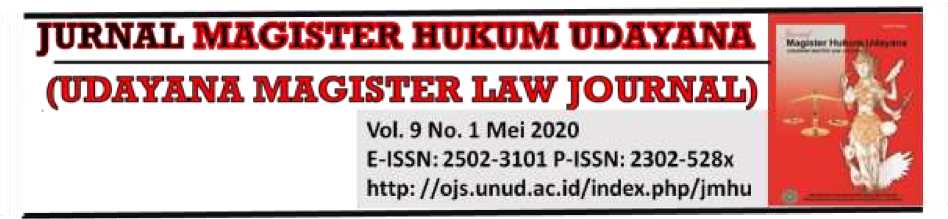
Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Ashari Setya Marwah Adli1
1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: asharisetya@gmail.com
Info Artikel
Masuk: 16 Juni 2019
Diterima: 2 Pebruari 2020
Terbit: 31 Mei 2020
Keywords:
Inheritance; Adat; Islam
Kata kunci:
Waris; Adat; Islam
Corresponding Author:
Ashari Setya Marwah Adli, Email: asharisetya@gmail.com
DOI:
10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p
06
Abstract
Based on Law No.3/2006, the choice of law or optional right to deciding the kind of law to solving the inheritance dispute in the court for Muslims has abolished. It’s force the Muslims to solve their inheritance dispute in Religious Court and using the Islamic Law. On the other side, legal pluralism in the inheritance law has existed. It causes the unjustice issue for the Muslim community because the Muslims can’t solve their inheritance dispute with adat law in the court. This research using the normative legal research method. This research has the purpose to know the abolishment consequences of the choice of law in the Inheritance dispute and to know how the executorial power of adat inheritance decision. Based on this research, the Law No.3/2006 force the Muslims to solve their inheritance dispute with Islamic Law, so that’s raising the unjustice issue. To answer this injustice issue, the choice of law or the optional right for the inheritance dispute is must be allowing or the parties can choose National Court as their forum. Then, how about the executorial power in the adat decision regarding the adat inheritance dispute. In this case, the court has to support adat decision and support the execution of adat decision regarding adat inheritance dispute.
Abstrak
Berdasarkan UU No.3/2006, pemilihan hukum atau hak opsi untuk menentukan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris dihapuskan, hal ini memaksa umat Islam untuk menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama dengan menggunakan hukum Islam. Padahal masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia. Hal ini menimbulkan masalah ketidakadilan di masyarakat, terutama bagi umat Islam di Indonesia, karena bagi umat Islam tidak diperkenankan menyelesaikan sengketa waris secara adat di ranah Litigasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui konsekuensi dari penghapusan pemilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris dan untuk mengetahui kekuatan eksekutorial atas keputusan waris adat. Dari hasil penelitian, berdasarkan UU No.3/2006 ternyata memaksa umat Islam yang ingin menyelesaikan sengketa waris harus menggunakan hukum Islam sehingga menimbulkan isu ketidakadilan. Sehingga, untuk menjawab isu ketidakadilan ini, harusnya pemilihan hukum atau Hak Opsi dalam sengketa waris
dibuka kembali atau para pihak dapat memilih jalur Pengadilan Negeri. Kemudian, bagaimana dengan kekuatan eksekutorial dalam hal terdapat putusan adat mengenai penyelesaian sengketa waris adat, maka Pengadilan wajib membantu penyelesaian sengketa adat yang telah diputus secara adat dengan membantu pelaksanaan eksukusi putusannya.
-
1. Pendahuluan
Soal waris sering kali menimbulkan polemik dan bisa memunculkan sengketa yang berkepanjangan. Sengketa waris seringkali dapat memecah belah hubungan persaudaraan sedarah dan penyelesaiannya bisa bertahun lamanya.
Pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa waris, masih berlaku dan tampak di Indonesia. Seseorang dalam penyelesaian sengketa waris di Indonesia terikat pada beberapa sistem hukum secara bersamaan, antara lain rezim hukum waris barat yang berdasarkan pada Burgerlijk Wetboek (BW), hukum waris adat yang mendasarkan ketentuan hukum adat serta hukum waris Islam yang mendasarkan pada ketentuan hukum agama Islam. Pluralisme hukum sendiri secara sederhana dipahami sebagai berlakunya beberapa sistem hukum dalam satu lapangan kehidupan masyarakat.
Forum penyelesaian sengketa waris di Indonesia secara hukum barat penyelesaian sengketanya melalui Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam BW (Burgelijk Wetboek) dan HIR/RbG. Sedangkan, penyelesaian sengketa secara hukum adat dapat melalui pengadilan adat atau melalui pengadilan negeri. Sedangkan penyelesaian sengketa waris secara agama Islam dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama.
Di Indonesia sendiri masih berlaku peraturan mengenai penggolongan penduduk peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang belum dicabut hingga saat ini, yaitu Pasal 163 Jo. Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling) dimana di dalamnya mengatur mengenai penggolongan penduduk di Indonesia serta diatur pula hukum-hukum yang berlaku terhadapnya. Berdasarkan pasal 163 Jo.131 IS, membagi penduduk yang ada di Indonesia dalam beberapa golongan penduduk, setiap golongan penduduk diperlakukan hukum serta peradilan yang berbeda, untuk golongan Eropa, Tionghoa, Timur Asing lainnya serta golongan yang dipersamakan diperlakukan BW dengan Raad Van Justitie sebagai pengadilan sehari-harinya, sedangkan untuk penduduk asli diperlakukan hukum adat dengan Landraad sebagai pengadilan sehari-harinya.1 Di samping itu untuk sebagian penduduk lainnya di perlakukan hukum Islam yang telah diresipiir oleh hukum adat, atas hal tersebut mengakibatkan berlakunya apa yang dinamakan pluralisme hukum dalam bidang hukum perdata di Indonesia.2
Dengan adanya pluralisme hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, terutama dalam hal waris. Terdapat isu yang kemudian menarik dibahas yaitu terkait penyelesaian sengketa waris bagi penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia. Bagaimana negara ikut serta dan campur tangan dalam penyelesaian
sengketa warisnya. Karena jika melihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang merupakan Undang-Undang yang pertama tentang Peradilan Agama, pada penjelasan angka dua nya membuka kesempatan yang dinamakan Choice of Law atau hak opsi, yaitu hak bagi pihak yang sedang bersengketa mengenai waris untuk dapat menentukan sendiri pilihan hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan perkara warisnya di Pengadilan Agama.
Terdapat hal yang berbeda dari Undang-Undang Peradilan Agama sebelumnya apabila melihat paragraf kedua penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara eksplisit dan tegas menyatakan di dalamnya menghapus choice of law atau hak opsi dalam penyelesaian sengketa waris melalui Pengadilan Agama.
Sesuai dengan kompetensi absolut dari Pengadilan Agama yang berdasarkan pada pasal 2 Jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan perkara waris diantara orang-orang yang beragama Islam dan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengakibatkan penghapusan Choice of Law atau hak opsi dalam penyelesaian sengketa waris, mungkin akan timbul pertanyaan, bagaimana konsekuensinya kemudian jika terdapat penduduk di Indonesia yang beragama Islam dan ingin menyelesaikan sengketa warisnya berdasarkan pada Hukum Adat? Atau bagaimana jika terjadi perselisihan antara ahli waris dalam pembagian harta waris, akan menggunakan hukum adat atau hukum Islam?
Mengingat masih eksisnya pluralisme hukum di bidang waris di Indonesia dan apabila terdapat pembatasan dimana orang-orang yang beragama Islam dipaksakan untuk menyelesaikan sengketa warisnya melalui Pengadilan Agama dengan menggunakan hukum Islam, justru dapat bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mana dalam peraturan tersebut memberi hak dan kebebasan bagi masyarakat sekaligus mengamanatkan kewajiban kepada negara agar menjamin kebebasan masyarakat untuk dapat menjalankan agama dan kepercayaanya, negara juga wajib menghormati eksistensi hukum adat yang ada dan hidup di masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak untuk mendapat akses terhadap hukum dan keadilan. Ini sebenarnya yang menarik dibahas dalam penelitian ini, karena peran negara yang terlalu besar untuk ikut campur dalam penyelesaian sengketa waris dan memaksa penduduk yang beragama Islam di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa warisnya melalui Pengadilan Agama yang menggunakan hukum Islam justru rawan melanggar ketentuan yang ada pada UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
Dari yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah ini, maka akan dibahas serta diulas lebih lanjut pada jurnal ini dengan mengambil judul Penyelesaian Sengketa Waris Adat Bagi Masyarakat Beragama Islam Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.
Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah sebelumnya, maka rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana konsekuensi hukum dengan dihapuskannya choice of law atau hak opsi dalam sengketa waris untuk masyarakat beragama Islam? Dan Bagaimana kekuatan eksekutorial keputusan Adat mengenai sengketa waris adat terhadap masyarakat beragama Islam di Indonesia.
Adapun beberapa jurnal yang memiliki tema serupa mengenai hak opsi atau choice of law dalam waris adalah dengan judul Pencabutan Hak Opsi dalam Perkara Waris Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam oleh Leliya yang dimuat dalam Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol.2(1) tahun 2017. Yang membedakan dengan jurnal ini adalah dalam jurnal ini mencoba menjelaskan konsekuensi keadilan apabila hak opsi dicabut dan bagaimana eksekusi terhadap keputusan adat terkait waris adat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah konsekuensi hukum apa yang dihadapi apabila choice of law atau hak opsi dalam penyelesaian sengketa waris bagi penduduk yang beragama Islam di Indonesia dihapuskan dan untuk mengetahui apakah suatu keputusan adat mengenai waris dapat memiliki kekuatan eksekutorial.
-
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana fokus kajian bermula dari adanya norma hukum yang bertentangan atau konflik norma hukum secara vertikal maupun konflik norma secara horizontal.
Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan yaitu dengan menelusuri dan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat, antara lain hukum adat, hukum waris Islam, kekuasaan kehakiman dan hak asasi manusia. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, dimana mempelajari konsep-konsep dan pandangan dari para ahli terkait dengan isu yang permasalahan yang diangkat, antara lain mengenai pluralisme hukum, hukum Islam, hak asasi manusia dan hukum waris Islam.
Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.3 Adapun bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan.
Bahan hukum sekunder yang dipakai pada penelitian ini antara lain penjelasan dari bahan primer dan pendapat dari ahli-ahli hukum mengenai sengketa waris, hukum adat, pluralisme hukum dan hukum Islam dimana bisa didapatkan dari buku, tesis, hasil penelitian dan jurnal yang mempunyai kaitan untuk menjawab permasalahan yang diangkat.
Bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode penelusuran dokumen yaitu melalui studi kepustakaan maupun penelusuran melalui internet.
Seluruh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan dianalisis secara kualitatif dan dari bahan-bahan hukum tersebut akan diinterpretasikan atau ditafsirkan dengan menggali makna yang ada dalam di tiap kata yang ada pada
peraturan perundang-undangan dan mengkaitkannya juga dengan pendekatan konseptual hukum dari pendapat pada ahli untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada.
-
3. Hasil dan Pembahasan
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai permasalahan dalam penelitian ini, baik kiranya untuk dapat dibahas terlebih dahulu konsep maupun teori hukum yang dapat mendukung pembahasan ini nantinya. Pertama, yaitu konsep pluralisme hukum, yang mana Werner Menski dalam bukunya Comparative Law in a Global Contex: The Legal System of Asia and Afrika mendefinisikan pluralisme hukum (legal pluralism) yaitu pendekatan dalam memahami pertalian antara hukum negara (positive law), aspek sosial-masyarakat (socio-legal approach) serta hukum alam (moral/ethic/religion)4 atau jika secara sederhana mungkin dapat dijelaskan yaitu berlakunya beberapa tatanan atau sistem hukum (sistem hukum negara, sistem hukum adat dan sistem hukum agama) yang berlaku secara bersamaan di dalam suatu lapangan sosial yang sama.
Kedua, yaitu teori tujuan hukum, dimana hukum selalu mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Tiga hal itulah yang harus tercermin dalam suatu hukum. Namun, yang paling utama adalah keadilan di sana, baru kepastian lalu kemanfaatan. Hal tersebut yang harus dikedepankan dalam peraturan hukum. Kemudian, menurut seorang guru besar dari Universitas Airlangga, Peter Mahmud Marzuki, tujuan dari hukum tidak lain adalah untuk menciptakan keadaan damai sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat yang mana keadaan damai sejahtera bisa terwujud apabila hukum dapat memberikan pengaturan yang adil dimana kepentingan-kepentingan yang ada dilindungi dengan seimbang sehingga setiap orang sebanyak mungkin dapat memperoleh apa yang menjadi bagiannya.5
-
3.1 Konsekuensi Hukum Pasca Dihapusnya Choice of Law atau Hak Opsi dalam Sengketa Waris untuk Masyarakat Beragama Islam
Dalam konteks hukum adat, waris adat adalah bagian dari hukum adat yang berkaitan dengan norma atau aturan dalam menetapkan besaran harta kekayaan, baik yang berwujud materiil atau immaterial yang dapat diserahkan kepada keturunannya dan mengatur pula kapan, cara dan bagaimana proses peralihan harta tersebut, baik yang materiil maupun immaterial. 6 Secara sederhana, waris juga dipahami sebagai hak maupun kewajiban terkait harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.7
Soepomo menjelaskan pengertian dari hukum adat waris pada “Bab-Bab tentang hukum adat” sebagai hukum yang berisi ketentuan-ketentuan yang di dalamnya berisi aturan mengenai mekanisme penerusan atau pengoperan harta kekayaan baik benda atau barang berwujud maupun tidak berwujud dari satu generasi ke generasi lain dalam keturunannya8
Pengertian mengenai hukum kewarisan sendiri dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang kerap dijadikan rujukan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di Pengadilan Agama dapat ditemukan di pasal 171 huruf (a) KHI, dimana secara sederhana dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur mengenai peralihan hak atas kepemilikan suatu harta peninggalan seorang pewaris, kemudian dalam hukum tersebut juga diatur mengenai siapa orang yang berhak menjadi seorang ahli waris serta besar bagiannya.
Dapat dipahami bahwa pada hukum kewarisan merupakan suatu aturan atau mekanisme yang dianut untuk melakukan perpindahan, peralihan atau pembagian suatu harta peninggalan dari si pewaris kepada para ahli warisnya yang masih hidup dengan besaran dan tata cara pembagian-pembagian yang telah diatur sedemikian rupa menurut aturan atau hukum yang dianut, yaitu berdasarkan pada hukum waris adat, hukum waris Islam maupun hukum waris barat (BW).
Tiga sistem kewarisan yaitu, hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris barat (BW) masih berlaku di Indonesia. Setiap sistem hukum kewarisan tersebut memiliki aturannya sendiri-sendiri terkait sistem hukum kewarisannya.
Dalam sistem kewarisan adat, maka sistem kewarisannya mendasarkan pada masing-masing aturan hukum adatnya. Misal, dalam adat di Jawa atau yang menggunakan sistem parental/Bilateral, maka pembagian besarnya bagian waris antara lelaki dan perempuan adalah sama yaitu 1:1. Begitu juga jika pada masyarakat hukum adat yang menerapkan sistem materinial, maka kewarisannya menggunakan sistem materinial sesuai adatnya. Bagitu juga dengan yang menganut patrilinial, maka pembagian harta waris menggunakan sistem patrilinial.
Kemudian dalam sistem kewarisan Agama (Agama Islam) Maka, pembagiannya mendasarkan pada hukum Islam, yaitu berdasarkan pada Al-Quran dan As Sunnah, dimana pemahaman yang biasa digunakan adalah besaran pembagian harta antara anak lelaki dengan anak perempuan yaitu 2:1 dan besaran pembagian-pembagian lain yang telah diatur. (Dzawil Furudl, Ashabah, dan Dzawil Arham)
Begitu juga dengan sistem kewarisan barat (BW), hukum kewarisannya adalah sesuai dengan sistem yang diatur di dalam BW. Dimana terdapat penggolongan golongan I, II, III dan IV dan besaran pembagian harta warisan (Legitimie Portie).
Melihat pendapat dari Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa aturan yang ada di Hindia (Indonesia) memiliki keragaman bentuk sejak zaman lampau dan saat ini, hal ini menjadi sumber pengetahuan mengenai hukum yang ada di Bumi ini dan menjadi sumber pengetahuan yang tak akan kering untuk dipelajari.9 Hal yang diungkapkan
oleh Van Vollenhoven tersebut tidaklah keliru karena di Indonesia berlaku berbagai sistem hukum yang dianut oleh masyarakatnya. Saat ini hal tersebut dikenal dengan nama pluralisme hukum.
Werner Menski dalam bukunya Comparative Law in a Global Contex: The Legal System of Asia and Afrika mendefinisikan pluralisme hukum (legal pluralism) yaitu pendekatan dalam memahami pertalian antara hukum negara (positive law), aspek sosial-masyarakat (socio-legal approach) serta hukum alam (moral/ethic/religion).10
Di Indonesia sendiri, pluralisme hukum masih eksis, ini tampak dimana dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam satu tatanan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, seseorang bisa terikat oleh beberapa sistem hukum antara lain sistem hukum adat, hukum agama dan hukum negara. Sistem-sistem hukum ini eksis, bertemu dan saling bersinggungan. Salah satunya contoh kongkret pluralisme hukum adalah dalam hukum kewarisan yang ada di Indonesia. Dalam hukum kewarisan, seseorang bisa terikat pada sistem hukum adat, hukum agama (Agama Islam) dan hukum barat (BW) secara sekaligus. Misal, ada seseorang lahir dari keturunan suku Minang dan menganut agama Islam, maka secara otomatis seorang tersebut terikat untuk mengikuti sistem hukum adat Minang sekaligus terikat juga dengan sistem hukum Islam. Hal inilah yang disebut dengan pluralisme hukum.
Apabila melihat dari pendapat Griffith, dimana Griffths membagi pluralisme hukum menjadi dua macam, yang pertama adalah weak legal pluralism atau pluralisme hukum yang lemah, dimana dalam pengertian ini negara tetap mengakui adanya pluralisme hukum yang ada di masyarakat, namun lemah, karena hukum negara tetap dipandang lebih kuat atau superior ketimbang hukum-hukum yang lain. Sehingga, hukum-hukum di luar hukum negara di satukan di bawah naungan hukum negara. Kedua, adalah strong legal pluralim atau pluralisme hukum yang kuat, dimana semua sistem hukum yang ada dan berlaku di masyarakat mempunyai kedudukan atau hierarki yang sama, tidak ada hukum yang superior atau inferior.11 Dalam perkembangannya kemudian, konsep pluralisme hukum sendiri berkembang dimana lebih menekankan pada keanekaragaman hukum dan bagaimana sistem hukum yang berbeda-beda tersebut dapat saling mempengaruhi satu dengan yang lain.12
Keberlakuan pluralisme hukum baru tampak dan eksis apabila melihat dari sisi subjek hukumnya, dimana apabila seseorang atau subjek hukum tersebut berhadapan dengan berbagai pilihan hukum dalam menghadapi suatu permasalahan hukum.13 Di sinilah sebenarnya tampak apabila berbicara mengenai pluralisme hukum waris di Indonesia, dimana individu atau seseorang sebagai subjek hukum dalam menyelesaikan sengketa waris mempunyai berbagai pilihan hukum, dimana bisa memilih hukum waris adat, hukum waris Islam maupun hukum waris barat (BW). Maka, dapat dikatakan memang benar bahwa terdapat pluralisme hukum dalam hal sistem hukum pewarisan di Indonesia.
-
3.1.3 Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Memeriksa, Memutus serta Menyelesaikan Sengketa Waris.
Dalam ketentuan pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Peradilan Agama merupakan tempat bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam untuk menyelesaikan perkara-perkara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.
Merujuk pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 diatur mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Agama, salah satu kompetensi absolutnya adalah memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris.
Dari hal tersebut, siapakah yang dimaksud dengan “…antara orang-orang yang beragama Islam” dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 itu? Merujuk pada penjelasan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, yang dimaksud pada kalimat “…antara orang-orang yang beragama Islam” adalah orang ataupun badan hukum yang menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan hukum Islam.
Untuk melihat pengertian waris sendiri sebagaimana yang disebutkan di pasal 49 huruf b Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dapat ditemukan pada penjelasannya dimana hakim pada Pengadilan Agama dapat memeriksa, mengadili serta memutus terkait :
-
1. penentuan pihak yang berhak menjadi ahli waris
-
2. penentuan hal-hal terkait harta waris/harta peninggalan
-
3. penentuan besaran atau bagian waris dari ahli waris, dan
-
4. melakukan pembagian harta waris/harta peninggalan tersebut, serta
-
5. memberikan penetapan guna menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan bagiannya masing-masing.
Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan sebelumnya, penyelesaian sengketa waris bagi orang-orang beragama Islam menjadi kompentensi absolut dari Pengadilan Agama, tidak bisa orang yang beragama Islam atau umat Islam untuk membawa serta menyelesaikan sengketa waris melalui badan peradilan lain dengan menggunakan sistem hukum selain hukum Islam.
Kemudian akan timbul suatu pertanyaan, apakah umat Islam terikat penuh untuk menyelesaikan perkara warisnya dengan menggunakan sistem hukum Islam? Atau apakah seorang yang beragama Islam akan kehilangan haknya untuk menyelesaikan perkara waris melalui cara adatnya?
Sebenarnya terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli terkait apakah seorang umat Islam mutlak harus menyelesaikan perkara waris melalui hukum Islam, mengingat ada beberapa hal yang oleh sebagian pihak dianggap tidak mencerminkan nilai dari keadilan apabila harus menyelesaikan perkara melalui hukum Islam.
Dalam Islam, terdapat ayat di dalam Al-Quran yaitu Q.S. An-Nisa’ ayat 13: “(Hukum-hukum waris tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang
besar”. Hal tersebut menjadi dasar bahwa setiap muslim haruslah menyelesaikan perkara waris dengan menggunakan kaidah hukum Islam.
Namun, dalam praktik yang ada di masyarakat, terkadang kaidah umum mengenai waris masih cenderung kaku, sehingga seolah-olah bagi umat Islam haruslah menyelesaikan perkara melalui hukum Islam dan tidak diperbolehkan menyelesaikan perkara waris dengan cara adat atau melalui hukum barat (BW).
Hal yang umum dan secara praktik dianggap tidak adil oleh masyarakat dalam hukum Islam adalah pembagian besaran harta warisan bagi lelaki dan perempuan, dimana perbandingan antara anak lelaki dan anak perempuan adalah 2:1. Hal ini didasari pada Q.S. An-Nisa’ ayat 11: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...”.
Untuk penganut agama Islam yang memiliki pandangan untuk berpegang pada hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As Sunnah sebagai pegangan hidupnya, maka sengketa waris haruslah diselesaikan melalui Pengadilan Agama dengan menggunakan hukum Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah disampaikan oleh Ismail Sunny seorang cendekiawan muslim dari Muhammadiyah dalam pembahasan RUU Peradilan Agama dahulu, bahwa bagi seorang muslim tidak ada pilihan lain untuk menyelesaikan perkara seperti kawin, waris, wasiat dan hibah kecuali melalui Pengadilan Agama. Jika masih terdapat pilihan lain, maka ini kemunduran dan membuka kesempatan bagi umat Islam untuk menjadi munafik terhadap agamanya.14 Selaras dengan hal tersebut, guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, M.Daud Ali juga menyatakan bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal namanya pilihan hukum, bisa-bisa ia keluar dari agamanya jika dimungkinkan adanya pilihan hukum.15
Dari pendapat tersebut, di sisi lain terdapat masalah keadilan yang dirasakan masyarakat jika harus diselesaikan melalui hukum Islam an Sich dan kaku atau negara turut campur untuk memaksa orang-orang yang beragama Islam untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Agama dengan menggunakan Hukum Islam.
Dari hal tersebut nampak, bahwasannya terdapat permasalahan ketidakadilan di masyarakat dalam penyelesaian sengketa waris. Waris memang menjadi ranah yang memiliki tingkat sensitifitas dan kerumitan yang tinggi, dengan masih adanya masalah pada pluralisme hukum di bidang waris dan didukung belum adanya peraturan perundang-undangan terkait waris di Indonesia yang terkodifikasi.
Menarik untuk dilihat apakah hukum Islam perlu untuk dipositifkan dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Karena jika dipositifkan bisa jadi terjadi degrardasi makna dari hukum Islam tersebut dan membuat hukum Islam tersebut menjadi kaku dan sulit untuk dilakukan Ijtihad.
Dalam konteks penyelesaian sengketa waris Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mewajibkan orang-orang yang beragama Islam untuk menyelesaikan sengketa dan pembagian warisnya melalui Pengadilan Agama
dan melalui cara hukum Islam, hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk positifisasi hukum Islam di Indonesia.
Usaha untuk mempositifikasikan hukum Islam pasti akan memunculkan konsekuensi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, karena formalisasi hukum Islam membuat masyarakat tidak lagi mempunyai pilihan kecuali melaksanakan hukum Islam yang telah dipositifikan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia16. Padahal, hukum adalah hasil interpretasi manusia yang mana bisa jadi hasil interpretasi itu termasuk masalah khilafiyah.17
Menarik untuk melihat pendapat dari Abou El-Fadl yang menyampaikan bahwa, Syariah merupakan suatu proses, metodologi dan moralitas. Inti dari moralitas itu adalah keindahan. Peraturan yang ada bisa dikatakan merupakan hasil dari pemahaman manusia terhadap ketentuan Syariah, namun peraturan yang ada tersebut tidak bisa mengartikulasikan secara substantif inti dari moralitas keislama.18 Hukum Islam sebenarnya merupakan produk penafsiran seseorang terhadap Syariah, sehingga apabila terdapat pihak yang mempositifkan hukum Islam, ia telah terjatuh pada sikap otoritarianisme.19
Positifisasi Hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan dapat memposisikan hukum negara setara dengan Hukum Islam, hal ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mengkonstruksi makna dan teks (Al Quran dan Al Hadist) itu sendiri. Padahal hukum Islam yang sebenarnya adalah tafsiran dari Syariah telah di klaim sebagai produk hukum yang otoritatif dan mengikat pihak lain. Dengan begitu, berarti positifisasi hukum Islam dapat dikatakan telah “memperkosa” teks.20
Otoritarianisme sendiri adalah perilaku mengunci suatu teks dan bisa jadi juga mengurung kehendak Tuhan atau kehendak teks (Al Quran dan Al Hadist) ke dalam suatu penetapan makna, lalu penetapan suatu makna itu dianggap sebagai suatu hal yang pasti, absolut dan menentukan. 21 Tindakan positifisasi hukum Islam bisa dikatakan sebagai tindakan mengunci dan mengurung teks (Al-Quran dan Al-Hadist) karena seakan tidak memberi kesempatan untuk pemaknaan lain. Penetapan hukum Islam dengan cara selektifitas teks yang otoritatif akan berubah menjadi teks yang otoriter setelah hukum Islam itu dipositifkan.22
Oleh para pemeluknya, agama Islam dipahami secara plural atau berbeda-beda, maka jika agama Islam dipahami melalui logika positifistik yang cenderung kaku dan mengikat akan dirasa tidak tepat.23 Menarik melihat pendapat dari Nurcholis Madjid, dimana seharusnya menempatkan Agama Islam bukan sebagai agama yang legal-formalistik yang membentuk suatu formalisme susunan hukum dan struktur politik kenegaraan, karena agama Islam sendiri pada tingkat yang lebih abstrak dipahami sebagai agama yang memiliki nilai etis yang memberi panduan atau pemahaman
kepada umatnya. Sehingga, Islam haruslah memunculkan jiwa demokratis yang kemudian dapat menghargai nilai-nilai serta prinsip dari pluralisme yang sesuai dan selaras dengan arus modernisasi.24
Sehingga, menurut penulis dalam hukum waris Islam baiknya diserahkan kepada pemeluk-pemeluknya untuk menyelesaikan perkara melalui pilihan hukum yang mana. Bisa jadi, pemaksaan negara bagi orang Islam untuk menyelesaikan perkara waris melalui hukum Islam malah mencederai makna Hukum Islam itu sendiri. Karena kita semua saat ini hanya melakukan penafsiran atas ketentuan-ketentuan yang ada pada Al-Quran maupun As Sunnah. Negara seharusnya menjaga jarak untuk tidak masuk terlalu dalam pada konteks menafsirkan Hukum Islam, negara dalam hal ini harus menempatkan diri pada posisi menghormati dan bertindak pasif.
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa dengan dihapuskannya choice of law atau hak opsi untuk penyelesaian sengketa waris pasca munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengakibatkan hilangnya hak bagi para pihak untuk melakukan pemilihan hukum dalam sengketa waris, padahal, dalam hukum waris di Indonesia masih terdapat pluralisme hukum waris. Konsekuensinya, bagi orang-orang yang menganut agama Islam mau tidak mau dan suka tidak suka haruslah menyelesaikan dan membawa sengketa warisnya melalui Pengadilan Agama dan harus menggunakan prinsip Hukum Islam, maka, hal ini menimbulkan masalah keadilan yang ada di masyarakat dan ini tentu akan menjauhi dari tujuan hukum yang paling utama sebagaimana dicetuskan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan.
Masalah keadilan merupakan hal yang abstrak untuk dijelaskan secara baik. Adil pada satu pihak bisa jadi tidak adil pada pihak lainnya, bahkan terdapat adagium terkenal dari Cicero yang berbunyi Summun Ius Summa Iniuria yang berarti keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.
Terkait masalah pewarisan ini, juga terdapat masalah yang akan dihadapi apabila kembali dibuka adanya Choice of Law atau Hak Opsi dalam sengketa waris, yaitu seakan membuat umat Islam untuk mengedepankan hukum waris asing dan umat Islam seakan diberi kesempatan untuk meninggalkan hukum waris Islam 25 Kekhawatiran ini muncul karena adanya pandangan yang menganggap bahwa penafsiran atas ayat atau ketentuan yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagaimana apa yang ia anut dan tidak boleh ada penafsiran lain atas hal tersebut dan umat Islam mau tidak mau haruslah menggunakan hukum Islam untuk penyelesaian sengketa warisnya.
Penghapusan hak opsi ini secara filosofis merupakan penerapan dari asas hukum waris Islam, yaitu asas Ijbari atau keharusan, kewajiban.26 Maksud dari keharusan atau kewajiban di sini adalah untuk kewajiban untuk menjalankan hukum berdasarkan apa yang ditentukan oleh Allah SWT.
Selain itu, jika choice of law atau hak opsi dibuka kembali, akan muncul permasalahan dalam praktik peradilan dimana para pihak yang bersengketa waris akan saling melakukan gugatan di ranah pengadilan yang berbeda karena hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa waris berbeda, dengan begitu maka permohonan fatwa ke Mahkamah Agung akan meningkat dan atau muncul upaya hukum hingga kasasi hanya untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan yang dapat menangani perkara tersebut. Itulah konsekuensi yang muncul jika choice of law atau hak opsi dalam perkara waris dibuka kembali dan para pihak tidak mau bersepakat dalam menentukan pilihan hukumnya.27
Namun, jika terlalu dipaksakan dimana sengketa waris yang terjadi pada orang beragama Islam harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama dengan Hukum Islam, tentu akan mereduksi rasa keadilan di masyarakat, karena bisa jadi hukum adatlah yang justru lebih diinginkan oleh masyarakat untuk menjawab rasa keadilan karena hukum adat dianggap lebih humanis, lebih dekat dengan keseharian masyarakat dan lebih mendorong penyelesaian secara kekeluargaan.
Sebagaimana diuraikan dalam uraian yang telah penulis uraikan di atas, konsekuensi yang timbul dari penghapusan choice of law atau hak opsi untuk penyelesaian sengketa waris bagi umat Islam di Indonesia adalah timbulnya masalah ketidakadilan, karena umat Islam dipaksa untuk menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama dengan menggunakan hukum Islam.
Kemudian, sebagaimana diuraikan pada bagian 3.1.5. penelitian ini, terkait otoritarian dalam positifisisasi hukum Islam di Indonesia. Dari pandangan yang ada tersebut, menurut penulis ada baiknya pintu choice of law atau hak opsi kembali dibuka kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara kewarisan. Karena negara harusnya tidak ikut campur terlalu dalam mengenai implementasi Hukum Islam, biarkan para pihak untuk dapat menentukan sendiri pilihan hukum mana yang di pilih untuk penyelesaian sengketa warisnya, karena upaya mempositifkan hukum Islam ke dalam Peraturan Perundang-undangan Negara bisa jadi sama saja mendegrardasi makna atau maksud dari Hukum Islam itu sendiri dan mengakibatkan hukum Islam menjadi miskin akan interpretasi lain atau Ijtihad. Selain itu, juga membuat otoritatif terhadap Hukum Islam itu sendiri.
Apabila Choice of Law atau Hak Opsi dalam perkara waris kembali dibuka untuk penyelesaian sengketa penduduk yang beragama Islam di Indonesia, maka akan mendekatkan pada tujuan hukum yang diutarakan oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Masyarakat dapat memilih sendiri pilihan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa warisnya.
Hal lain yang mungkin bisa menjadi solusi apabila terdapat orang beragama Islam yang ingin menyelesaikan perkara warisnya dengan menggunakan hukum adat adalah mencoba mengajukan ke Pengadilan Negeri. Karena jika melihat pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Jo. Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 25 ayat (2) U-Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pengadilan Negeri mempunyai wewenang dan tugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat
pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hakim memiliki kewajiban untuk menggali nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, serta di samping itu pengadilan juga tidak dapat menolak perkara yang diajukan dengan alasan tidak terdapat atau kurang jelas hukumnya. Di sini lah peran hakim untuk penting untuk tidak hanya menjadi corong undang-undang, namun juga wajib menggali nilai-nilai yang ada di Masyarakat untuk menghadirkan keadilan dalam putusan atau penetapan yang ia buat.
Dengan hal tersebut, maka akan mendekatkan pada tujuan hukum itu sendiri yaitu, keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dan pada akhirnya hukum tersebut dapat mendorong terciptanya keadaan yang damai dan sejahtera. Mungkin kaitannya dengan ini, dapat diutarakan pula bahwa hukum itu lahir bukan untuk dirinya sendiri, namun juga untuk sesuatu yang lebih besar dan penting, yaitu keadilan dan kebahagiaan manusia.28
-
3.2 . Bagaimana Kekuatan Eksekutorial Keputusan Adat Terkait Sengketa Waris Adat terhadap Masyarakat Beragama Islam di Indonesia.
Peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengatur dan mengakui secara tegas mengenai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, serta beberapa peraturan perundang-undangan yang lain.
Dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisonalnya diakui oleh Negara, sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyebutkan bahwa masyarakat, pemerintah dan ketentuan hukum yang ada harus memperhatikan serta melindungi masyarakat hukum adat, hal ini harus dilakukan sebagai bentuk dari pemenuhan atas hak asasi manusia. Selain itu, ketentuan yang ada pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menjelaskan mengenai desa dan desa adat dimana di dalam desa adat terdapat kesatuan masyarakat desa adat yang memiliki suatu batas wilayah sendiri dan masyarakat adat yang ada di wilayah tersebut berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus hal-hal mengenai urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal-usul dan/atau hak tradisionalnya.
Desa adat memang mempunyai keotonomianya sendiri untuk mengurus wilayahnya di bahwa naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi di sini dapat dipahami sebagai wewenang serta kewajiban yang dimiliki untuk mengatur desa adatnya sendiri.29 Hal ini sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai apa itu desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa.
Apabila ingin mengetahui kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal-usulnya sendiri, jawabannya ada pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan mengenai hal tersebut, antara lain meliputi beberapa hal seperti pengaturan, pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli desa adat, pengaturan mengenai hak ulayat atau wilayah adat, pelestarian nilai-nilai mengenai sosial budaya kehidupan desa adat, pengaturan serta pelaksanaan penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat, melakukan sidang perdamaian adat, memelihara kondisi teteran dan menjaga ketertiban berdasarkan hukum adat serta mengembangkan kehidupan adat yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
Merujuk pada teori Pluralisme hukum yang diuraikan pada bahasan sebelumnya, mengenai otonomi desa adat bisa dikatakan sebagai weak legal pluralism atau pluralisme hukum yang lemah, dimana otonomi desa adat yang merupakan bagian dari hukum adat kedudukannya lebih inferior ketimbang hukum negara karena masih dipengaruhi oleh hukum Negara (Aturan yang superior). Maksudnya hukum adat ini keberlakuannya ditentukan oleh hukum negara.30
Maka, berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa negara memang mengakui dan menghormati keberadaan desa dan desa adat beserta sistem hukum adat dan kesatuan masyarakat hukum adatnya. Kemudian desa atau desa adat tersebut diberikan suatu otonomi untuk mengatur sendiri kehidupan di wilayahnya dalam bingkai dan naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setiap wilayah adat memiliki aturan dan mekanisme adat sendiri dalam menyelesaikan sengketa waris adanya. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Desa Adat memiliki keotonomian sendiri serta memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa adat berdasarkan pada hukum adat yang berlaku di wilayah desa adatnya.
Pada penyelesaian sengketa waris adat di Indonesia terdapat pengelompokan secara garis besar cara penyelesaian warisnya berdasarkan sistem kekerabatan, yaitu patrilinial, matrinial dan parental/bilateral. Sistem kekerabatan Patrilinial berarti pembagian waris mengikuti penarikan garis keturunan ayah atau nenek moyang yang lelaki31, sedangkan sistem kekerabatan matrilinial adalah kebalikan dari Patrilinial, di sini mengikuti penarikan garis keturunan ibu atau nenek moyang perempuan.32 Untuk yang terakhir adalah sistem kekerabatan parental atau dikenal juga dengan bilateral, di sini berarti mengikuti penarikan garis keturunan dari ayah maupun dari ibu dan tidak ada pembedaan antara pihak ibu dan ayah. 33
Dalam melihat penyelesaian sengketa waris melalui adat, penulis ambil contoh penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Muslim di Donggala. Dalam masyarakat Muslim di Donggala penyelesaian sengketa waris dilakukan dengan
beberapa tahapan yaitu, melalui musyawarah, kemudian jika tidak bisa diselesaikan maka melalui musyawarah Dewan Adat, dan terakhir melalui Pengadilan Negeri di Kabupaten Donggala.34
Kemudian melihat juga pada daerah lain di Indonesia. Masyarakat Adat Karo, di sana mekanisme penyelesaian sengketa waris melalui beberapa tahapan-tahapan yaitu penyelesaian melalui (1) runggun ; (2) Perumah Begu ; (3) Pengadilan Negeri.35
Dari kedua contoh penyelesaian sengketa waris tersebut, terutama dalam bidang adat, tampak terdapat keotonomian pada kesatuan masyarakat desa adat untuk menyelesaikan sengketa yang ada di wilyahnya dengan adanya tata cara penyelesaian secara non-litigasi yaitu melalui musyawarah dan jika musyawarah tidak menyelesaikan secara hukum adat dengan dibawa ke Dewan Adat atau jika untuk masyarakat Karo dibawa ke Runggun dan Perumah Begu untuk menyelesaikannya. Hal serupa juga dilakukan oleh masyarakat hukum adat lain yang ada di Indonesia.
Penyelesaian secara adat ini mungkin akan sulit diterapkan jika ketentuan mengenai penghapusan choice of law atau hak opsi dalam sengketa waris bagi umat Islam pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 masih berlaku, karena penyelesaian sengketanya harus melalui hukum Islam. Hal ini nampaknya beranjak pada teori receptie a contrario yang oleh beberapa pihak menyatakan bahwa untuk orang yang beragama Islam menggunakan hukum Islam dan hukum adat dapat berlaku apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Padahal, pernyataan itu memungkiri kemungkinan lain dimana terdapat masyarakat yang beragama Islam yang masih memegang nilai-nilai dan hukum adatnya yang bisa jadi, nilai adat tersebut dinilai bertentangan dengan hukum Islam oleh beberapa pihak, termasuk dalam masalah penyelesaian sengketa waris adatnya dan hukum apa yang akan dipergunakannya.
Bicara mengenai keotonomian desa adat atau kesatuan masyarakat hukum adat, maka setiap kesatuan masyarakat hukum adat pada umumnya mempunyai lembaga penyelesaian sengketa adat atau dewan adat untuk menyelesaikan sengketa yang ada di wilayahnya. Hal ini dibenarkan serta diakui secara peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana pembahasan sebelumnya.
Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana proses eksekusi keputusan adat terkait sengketa waris. Mengingat lembaga adat tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang memaksa selayaknya pengadilan negara?
Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, suatu putusan hakim adat memang tidak eksplisit diakui, namun pada praktik yang terjadi di lapangan suatu putusan adat tetap diakui serta dihormati kedudukannya selama masyarakat hukum adat tersebut diakui oleh Peraturan Daerah setempat. Maka, putusan adat yang diputus
oleh hakim adat tetaplah berlaku dan mengikat untuk masyarakat hukum adat tersebut.36
Merujuk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada di masyarakat dan merujuk juga pada pasal 103 huruf d,e, dan f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberi kewenangan kepada desa adat untuk menyelesaikan perkara adatnya, melakukan sidang perdamaian desa dan berwenang memelihara ketertiban, ketentraman desa adat sesuai dengan hukum adatnya yang berlaku. Melihat dari ketentuan yang di sebutkan tersebut sudah seharusnya bagi hakim untuk menghargai dan memahami keputusan lembaga adat yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa.
Hilman Hadikusuma di dalam bukunya “Hukum Adat dalam Yurisprudensi” (hal. 85-91) juga memberikan contoh kasus mengenai pengakuan terhadap keputusan Desa Adat, dimana terdapat gugatan dari R.A Darmosewojo selaku Penggugat kepada R.M. Brotodirjo selaku Tergugat terkait masalah pembagian hibah, dimana penggugat mendalilkan bahwa ayah penggugat yaitu R.M. Ng.Djojosasmito telah menghibahkan sebidang tanah pekarangan kepada Penggugat, namun oleh Rapat Desa Plawikan memberikan keputusan bahwa tanah tersebut adalah menjadi warisan dari R.M. Ng.Djojosasmito sehingga oleh karenanya harus dibagi dua antara kedua anak kandung R.M. Ng.Djojosasmito yaitu penggugat dan tergugat. Kemudian, Penggugat membawa hal tersebut ke Pengadilan Negeri Klaten untuk menuntut pengesahan hibah yang ia dalilkan sebelumnya dan meminta Pengadilan Negeri membatalkan Putusan Desa pada tanggal 25 Agustus 1955. Kemudian, akhirnya oleh Mahkamah Agung melalui putusan No.340K/Sip/1958 tanggal 19 November 1958 menyatakan menolak gugatan dari Penggugat dengan pendapat yang kurang lebih adalah Pengadilan Negeri tidak memiliki kompetensi untuk pembatalan keputusan desa dan telah menjadi yurusprudensi di Mahkamah Agung bahwa Hakim Negeri tidak memiliki atribusi untuk meninjau benar atau tidaknya suatu putusan desa.37
Sehingga, dari uraian tersebut di atas, negara dalam hal ini adalah pengadilan secara prinsip mengakui keotonomian kesatuan masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan sengketanya sendiri berdasarkan hukum adat yang ia miliki di wilayahnya melalui lembaga penyelesaian sengketa adatnya. Sehingga, harusnya apabila terjadi sengketa waris yang sudah diputus melalui pengadilan desa adat atau nama lain yang dipersamakan dengan itu. Maka, Pengadilan yang ada dibawah Mahkamah Agung wajib untuk membantu melakukan fiat eksekusi atau membantu melakukan eksekusi atas pengadilan desa adat atau nama lain yang dipersamakan dengan itu.
-
4. Kesimpulan
Konsekuensi yang timbul dari penghapusan choice of law atau hak opsi untuk penyelesaian sengketa waris bagi umat Islam di Indonesia umat Islam dipaksa untuk menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan Agama dengan menggunakan hukum Islam. Hal ini dapat menimbulkan isu ketidakadilan karena membatasi pemilihan hukum dalam penyelesaian sengketa waris, padahal pluralisme hukum dalam hukum waris masih berlaku.
Keputusan adat dari pengadilan adat atau nama lain yang mempunyai tugas yang sama untuk menyelesaikan sengketa adat untuk menyelesaikan sengketa waris melalui hukum adat haruslah mendapat pengakuan oleh negara dan Pengadilan di bawah Mahkamah Agung harus membantu melakukan eksekusi atas keputusan adat tersebut.
Daftar Pustaka
Buku
Abou El Fadl, K. (2004). Atasnama Tuhan. Penerbit Serambi.
Dewi, A.A.I.A.A. (2019). Penyusunan Perda Yang Partisipatif: Peran Desa Pakraman Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Sidoarjo: Zifatama Jawara.
Karim, M. A. (Ed.). (2012). Problematika hukum kewarisan Islam kontemporer di Indonesia. Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum(Edisi Revisi). Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Marzuki, P. M. (2009). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Nadroh, S. (1999). Wacana Keagamaan dan Politik Nurcholis Madjid. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Setiady, T. (2008). Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan). Bandung: Penerbit Alfabeta
Wignjodipoero, S. (1995). Pengantar dan Asas-Asas Hukum adat, Jakarta: PT. Gunung Agung.
Jurnal
Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 13(2).
http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.213
Ardika, I. N. (2016). Pemberian Hak Waris bagi Anak Perempuan di Bali dalam Perspektif Keadilan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 5(4), 639-649. https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p01
Basuki, Z. D. (2017). Perkawinan Antar Agama Dewasa Ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 17(3)
Basuki, Z. D. (2017). Perkawinan Antar Agama Dewasa ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum. Jurnal Hukum & Pembangunan, 17(3), 235-243.
Dewi, A.A.I.A.A. (2014). Eksistensi Otonomi Desa Pakraman dalam Perspektif Pluralisme Hukum. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 3(3). https://doi.org/10.24843/JMHU.2014.v03.i03.p13
Irianto, S. (2017). Sejarah dan perkembangan pemikiran pluralisme hukum dan konsekuensi metodologisnya. Jurnal Hukum & Pembangunan, 33(4), 485-502.
Kaban, M. (2016). Penyelesaian Sengketa Waris Tanah Adat Pada Masyarakat Adat Karo. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 28(3), 453-465. https://doi.org/10.22146/jmh.16691
Kushidayati, L. (2013). Hak Opsi dan Hukum Waris Islam di Indonesia. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 7(1), 53-64. https://doi.org/10.24090/mnh.v7i1.576
Leliya. (2017). Pencabutan Hal Opsi dalam Perkara Waris Bagi Warga Negara
Indonesia yang Beragama Islam. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.2(1)
Muslih, M. (2009). Mombongkar Logika Penafsir Agama. Jurnal Tsaqafah, 5(2)
Muttaqin, L. (2016) Positifisasi Hukum Islam dan Formalisasi Syari’ah Ditinjau Dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl. AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 11(1)
Muttaqin, L. (2016). Positifisasi Hukum Islam dan Formalisasi Syari’ah Ditinjau Dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 11(1), 67-92. http://dx.doi.org/10.19105/al-ihkam.v11i1.859
Sumardi, D. (2016). Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen. ., 50(2), 481-504. http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2016.502-08
Susylawati, E. (2013). Kedudukan Janda dalam Hukum Waris Adat pada Masyarakat Parental. Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 4(2), 257-274.
Online/Website
Kekuatan Hukum Putusan Adat. (2012) tersedia di
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4fbb44750563e/kekua tan-hukum-putusan-adat, diakses 7 Juni 2019
Hukum Waris Mana yang Digunakan, Islam, Adat atau KUHPerdata. (2012) tersedia di https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl1052/pilihan-hukum-waris, diakses 6 Juni 2019
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
91
Discussion and feedback