Formulasi Kebijakan Concreto in Abstracto UU ITE
on
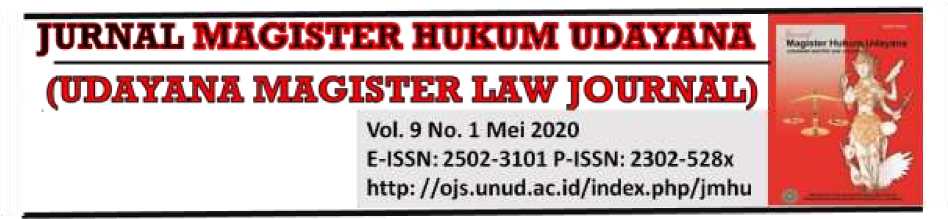
Formulasi Kebijakan Concreto in Abstracto UU ITE
Efendik Kurniawan 1, Ahmad Heru Romadhon 2, Indri Ayu Kusumawardani3,
Zakaria4, Akhmad Rudi Iswono 5
-
1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Bhayangkara Surabaya, E-mail: efendikkurniawan@gmail.com
-
2Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif,
E-mail: ahmad-heru-romadhon@fh.umaha.ac.id
-
3Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Bhayangkara
Surabaya, E-mail: indriayu22@gmail.com
-
4Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Bhayangkara Surabaya, E-mail: jackzakaria887@gmail.com
-
5Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Bhayangkara Surabaya, E-mail: rudish114@gmail.com
Info Artikel
Masuk: 20 Mei 2019
Diterima: 26 Mei 2020
Terbit: 31 Mei 2020
Keywords:
ITE; Formulation; Policy
Kata kunci:
ITE; Formulasi; Kebijakan
Corresponding Author:
Ahmad Heru Romadhon, Email: ahmad-heru-romadhon@fh.umaha.ac.id
DOI:
10.24843/JMHU.2020.v09.i01. p05
Abstract
The focus of this research study aims to reaffirm the contents of article 45 paragraph (5) of the ITE Law related to complain offenses which are considered confusing in providing clear definitions and obscurity of legal certainty which can hinder the law enforcement process for justice seekers if there is a dispute in cyberspace. This type of research is normative legal research, descriptive using deductive reasoning. From the results of the discussion, this study shows that the complaint offense listed in the ITE Law which is abstract in nature is blurred if the complaint does not have a more concrete explanation of the meaning of the complaint. So that the Judicial Review needs to review the contents of the article. Policy formulation UU ITE No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which was last amended by Act No. 19 of 2016 specifically with the interaction of social change and changes in law today address alignments on the one hand in the interests of a group.
Abstrak
Fokus dalam studi penelitian ini bertujuan untuk menegaskan kembali isi pasal 45 ayat (5) UU ITE terkait dengan delik aduan yang dirasa membingungkan dalam memberikan definisi yang jelas serta terkaburnya sebuah kepastian hukum yang dapat menghambat proses penegakkan keadilan hokum bagi pencari keadilan apabila ada sengketa di ruang cyber space. Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, deskriptif dengan mengunakan penalaran deduktif. Dari hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa delik aduan yang tercantum dalam UU ITE yang bersifat abstrak menjadi kabur apabila delik aduan ini tidak mempunyai penjelasan yang lebih konkrit dari arti delik aduan tersebut. Sehingga dirasa perlu Judicial Review mengkaji lagi muatan pasal tersebut. Formulasi kebijakan UU ITE No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 khususnya dengan interaksi perubahan sosial dan perubahan hukum dewasa ini menujukan keberpihakan pada satu
sisi dalam kepentingan suatu golongan.
Konsekuensi dalam kehidupan bernegara yang berorientasi pada suatu keadilan maka segala sesuatunya memiliki batasan yang di atur oleh peraturan atau Undang-Undang (UU) yang berlaku. Indonesia sebagai negara hokum (rechstaat) yang mengedepankan Asas Legalitas (Nullum delictum noella poena sine pravia lege poenali) yang berarti seseorang tidak dapat di nyatakan bersalah jika belum di atur dalam UU yang mengaturnya terlebih dahulu. Melalui proses politik hukum, merupakan syarat yang harus di lewati dalam rangka melahirkan produk hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan memperhatikan kebutuhan hidup di tengah masyarakat saat ini.
Pembentukan hukum nasional adalah sebagai upaya pemerintah dalam mengakomodir perlindungan serta menjamin hak-hak masyarakat dalam interaksi sehari-hari. Maka cukup relevan jika landasan hukum yang sah dan baik merupakan harapan kita semua untuk mencapai suatu kepastian hukum dalam menjamin hak-hak antar sesama. Dalam upaya mewujudkan kepastian hukum yang proporsional sesuai kebutuhan maka dalam pembentukan suatu UU haruslah di dukung terlebih dahulu dengan adanya RUU, dengan melibatkan para akademisi, pakar hukum, tokoh masyarakat, pemerintah dalam merumuskan dan melahirkan sebuah peraturan atau UU yang sejalan dengan aspirasi masyarakat, serta memberikan kewenangan pada lembaga yang berwenang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai badan legislatif pembuat UU.
Legal policy yang di keluarkan oleh pemerintah yang berarti bahwa negara hadir dalam memberikan kepastian hukum, mempunyai kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang secara merata, solutif, aspiratif dan proporsional sesuai kebutuhan saat ini serta dapat mengantisipasi munculnya permasalahan di kemudian hari, dengan terpadunya dan komprehensifnya suatu sistem hukum nasional. Pancasila merupakan landasan tertinggi dalam supremasi hukum dalam penegakkannya yang berarti sebagai cikal bakal suatu landasan hukum bagi terbentuknya suatu keadilan yang di cita-citakan oleh masyarakat. Dalam tataran dewasa ini sebuah keadilan yang di rasa masih ada keberpihakan pada suatu golongan tertentu menjadi pupusnya harapan masyarakat untuk mencari suatu keadilan yang semu begitu fenomena yang ada.
Dalam pembentukan suatu aturan hukum manakalah tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila sebagai dasar Negara dan Ideologi Negara maka dirasa perlu untuk di adakannya judcial review sebelum UU di sahkan dan di implementasikan. Oleh karena itu pentinglah bagi legislator terlebih dahulu memahami konsep pembentukan, tujuan suatu UU lebih mendahulukan kepentingan masyarakat sesuai kebutuhan saat ini. Memasuki era revolusi industry 4.0 dimana masyarakat saat ini hanya cukup berinteraksi dengan sebuah kecanggihan teknologi, informasi elektronik menjadi salah satu faktor yang melandasi terbentuknya UU ITE.
Keadaan tersebut membawa Indonesia sebagai masyarakat informasi dunia merupakan perwujudan bahwa masyarakat Indonesia sedang mengalami transisi
perubahan dunia dalam persaingan yang begitu ketat, sehingga perubahan itu membutuhkan segala sesuatu komponen yang di perlukan termasuk UU. Perubahan UU ITE tentunya harus lebih baik dan lebih kompleks yang di tunjang dengan mudahnya pemahaman masyarakat untuk lebih mengerti maksud dan tujuannya suatu UU. Pemerintah di tuntut untuk lebih memproposionalkan suatu pedoman khusus UU ITE dalam mendefinisikan suatu aturan hukum yang berlaku dalam transaksi elektronik. Kegiatan yang menjadi suatu bagian masyarakat informasi dunia, kini sudah tidak terbendung lagi dalam pemanfaatan transaksi elektronik, pemanfaatan itu saat ini menjadi objek hukum tersendiri. Sehingga kehadiran sebuah peraturan dan kepastian hukum dalam membatasi segala aktivitas di ruang cyber space perlu perhatian khusus yang nantinya dapat merugikan hak-hak orang lain. Tentu kecanggihan teknologi saat ini juga dapat menghidupkan perbuatan-perbuatan hukum baru perbuatan positif maupun negatif yang mau tidak mau harus di perhatikan secara intens oleh negara. Perhatian itu tentu menjadi tanda sekaligus menjadi kekhususan orientasi, serta model, dan suatu sistem informasi di Indonesia, juga menjadi tanda kembalinya suatu pembatasan oleh negara atas informasi, termasuk informasi yang diterima melalui internet.1
Perubahan dalam UU ITE selain mengatur pebuatan-perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana di ruang cyber cpace termasuk perbuatan-perbuatan yang sebenarnya sudah diatur oleh KUHP. Karakteristik dunia cybercrime mempunyai sifat yang lebih universal.2 Misalnya, kejahatan dalam ruang cyber space perjudian online, pornografi, prostitusi online. Kesemuanya itu saat ini di lakukan di ruang cyber space, sehingga harus di atur oleh UU ITE. Lahirnya UU ITE juga di dasarkan pada Konvensi Cyber Crime Dewan Eropa yang ditanda tangani di Budapest tanggal 23 November 2001, yang pada saat itu masih menjadi RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (Selanjutnya disebut RUU PTI).3
Evaluasi dan analisis terhadap sebuah kebijakan legislasi di dalam merumuskan ketentuan pidana dirasakan perlu adanya kajian lebih dalam konkret dan kompatibel, dalam mencantumkan suatu delik, Ius constituendum merupakan hukum yang citakan dengan perubahan yang lebih baik atau yang diangan-angankan di masa mendatang.4 Karena kebijakan yang bermasalah secara yuridis berpotensi dapat menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum yang berlaku. Pada tataran penerapan salah satu pasal yang kabur akan memberikan dampak keadilan yang masih jauh dari harapan yang di inginkan, serta perumusan dalam memberikan sanksi pidana maupun denda pidana dirasa juga masih sangat memberatkan. Pasalnya sanksi yang diberikan tidak sebanding dengan perbuatan. Penelitian ini secara praktis menggambarkan secara nyata konsep dari delik aduan yang tercantum di dalam UU ITE yang secara teoritis, dalam penelitian ini juga bertujuan untuk menambah dan
melengkapi literatur pengetahuan hukum pidana terhadap kebijakan formulasi delik aduan yang masih belum konkret dalam mendefinisikan sebuah delik yang terkandung dalam muatan pasal tersebut.
Metode yang di pergunakan adalah penelitian5 ini bersifat deskriptif, eksploratif, normatif dan juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menganalisis rumusan sebuah permasalahan yang dikaji saat ini. Adapun bahan-bahan yang digunakan penelitian ini dengan menginventarisir bahan primer seperti buku, jurnal, UU yang masih relevan untuk digunakan.
-
3. Hasil dan Pembahasan
-
3.1 Kebijakan Formulasi Delik Aduan di dalam UU ITE
-
Hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan dogmatis, yang bekerja secara tersistematis dalam pemidanaan seseorang. 6 Roeslan Saleh juga menyampaikan, bahwa ilmu hukum pidana merupakan ilmu pengetahuan yang normatif, yang melakukan penelitian sekitar aturan-aturan hukum sampai pada penerapannya. 7 Soedarto memberikan pengertian terkait penelitian yuridis, yang artinya segala interaksi sosial di masyarakat apabila melanggar sebuah peraturan maka secara otomatis sanksi yang termuat dalam hukum yang berlaku. Maka dari sinilah tumbuh nilai kesadaran hukum yang secara alami tumbuh di tengah masyarakat, yang demikian itu disebut metode yuridis dalam arti luas.8 Pedoman di dalam menyusun seperangkat aturan khusus dalam penulisan ini yang membahas permasalahan delik aduan, termasuk dalam ruang lingkup Ketentuan Pidana yang terdapat pada Lampiran II Sub C.3.
Adanya sebuah sanksi yang di maksudkan untuk memuat rumusan yang menyatakan pemberian efek jera atas apa yang sudah menjadi ketentuan pada pasal 45 ayat (5) merupakan perumusan materi yang masih abstrak yang tidak udah di tebak dalam memberikan definisi arah tentang sebuah delik.9 Perbedaan antara KUHP dengan UU ITE terletak pada perumusan delik harus mencantumkan secara jelas dan tegas di dalam setiap perubahan peraturan. Menurut Crimineel Wetbook Nederlandtahun 1809 (pasal 11) opzet (sengaja) itu adalah maksud membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang.10
Rumusan sebuah UU yang bersifat abstrak harus dijelaskan secara rinci dan tegas untuk menghindari pembiasan dalam memberikan penalaran, kualifikasi antara delik yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.
-
3.1.1 Sifat kumulatif
Sebuah penjabaran yang memuat unsur-unsur pada setiap perbuatan yang melawan hukum seperti halnya yang bersifat fundamental dalam sebuah tindakan seseorang dalam melakukan aksi yang ekstrim yang di lakukan secara sengaja seperti penganiayaan secara kejam, penyebaran konten pornografi, dan/atau bersifat adu nasib perjudian.
-
3.1.2 Sifat alternatif
Sifat alternatif yang maksudkan adalah memberikan sebuah terobosan baru dalam mengurai suatu tindak pidana mempunyai solusi yang terbaik dalam penyelesaiannya.
-
3.1.3 Sifat kumulatif alternatif
Gabungan antara kumulatif dengan alternatif adalah sebuah impelementasi pada setiap menjatuhkan sanksi baik berupa pemidanaan maupun sanksi administratif pada setiap pelaku perseorangan atau secara bersama-sama yang dengan sengaja melawan hukum.
Delik aduan termuat dalam hukum pidana materiil yang dapat di jumpai pada Pasal 72-75 KUHP. Tetapi UU diluar KUHP, misalnya UU ITE hanya mengatur pada sudut pandang hukum formalnya. Pemahaman yang keliru oleh lembaga legislatif memaknai bahwa delik aduan itu kualifikasi yuridis, tetapi yang benar ialah kualifikasi teoritik/ilmiah. Pernyataan Barda Nawawi Arief bahwa di dalam KUHP tidak ada istilah yang menyebutkan suatu tindak pidana sebagai delik aduan, tetapi menyatakan bahwa delik tersebut sulit untuk di proses, jika tidak ada pengaduan dari orang/subjek sebagai korbannya langsung.11 Misalnya, pada Delik Perzinahan (Pasal 284 KUHP), yang pengaturan delik aduannya diatur padal Pasal 284 ayat (2) KUHP.
Hans Kelsen menyatakan, bahwa ‘jiwa di dalam undang-undang’ pada dasarnya merupakan sebuah fiksi yang digunakan untuk membantu mendukung sebuah ilusi di dalam peristiwa hukum, yang dalam konteks tersebut aparat penegak hukum harus menerapkan hukum yang ada (existing law), meskipun dalam konteks tersebut dapat dikatakan, bahwa ia sebenarnya menciptakan hukum untuk kasus peristiwa hukum tersebut. 12 Di dalam muatan UU ITE istilah delik aduan masih di adopsi sebagai jebakan yang sulit terdeteksi dalam proses penegakan hukumnya. Penjelasan terhadap konsep dari delik aduan juga tidak di jelaskan oleh UU ITE. Hal tersebut sangat membingungkan di dalam penegakan hukumnya, konsekuensi yuridis dengan mencantumkan istilah delik aduan seperti halnya pasal karet yang tidak semestinya layak di sebutkan dalam pasal.
Kebijakan sanksi yang termuat di UU ITE, dirasa sangat berat sehingga sering kali di manfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Sanksi yang tercantum di dalam UU ITE tersebut sangat keras di bandingkan dengan yang tercantum pada KUHP, yakni paling lama 9 (sembilan) bulan. Politik hukum pidana di dalam UU ITE ini sangat keras, tetapi belum bisa membawa kepada tujuan hukum yakni ‘kepastian hukum’.13 Dengan kata lain, penderitaan korban yang di berikan kepada pelanggar hukum pidana (dader) termuat di dalam hukum positif (UU ITE), tidak sesuai dengan keadilan. Tetapi, menjadi alat penjajahan semata bagi golongan ‘rulling class’. Penegakan hukum tentang kejahatan cyber crime menjadi pembahasan yang ideal untuk dikaji lebih dalam di Indonesia tentu itu sangat dipengaruhi oleh lima factor diantaranya UU, mental aparat penegak hukum, sikap masyarakat, sarana prasarana dan kultur/budaya masyarkat.14
Pada saat UU ITE ini masih menjadi RUU PTI, ada beberapa pandangan ahli hukum.15 Yang di antaranya Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa, sebaiknya upaya kriminalisasi kejahatan di cyber space ini di integrasikan dengan KUHP dan tidak dalam UU tersendiri. Pengaturan yang dilakukan tidak mengubah nilai-nilai pemidanaan yang ada di dalam ilmu hukum pidana. Tetapi, setelah RUU PTI ini menjadi UU ITE, khususnya pada ketentuan pidana banyak menimbulkan persoalan, khususnya di dalam pengaturan delik aduan ini.
-
3.2 Konsep Delik Aduan
Istilah delik aduan atau suatu pengaduan seseorang atas sebuah tindak pidana kepada aparat penegak hukum adalah sebuah istilah yang mengandung konsep, tidak hanya kata yang mengandung makna. Istilah delik aduan tergolong dalam bahasa buatan yang dibuat oleh seorang ilmuwan yang disusun dan di terjemahkan sedemikian rupa, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan akal yang rasional dengan maksud tertentu. 16 Konsep delik aduan adalah penuntutan sebuah kejahatan yang dirasa merugikan seseorang dan hanya korbanlah yang berhak mengadu. 17 Kepentingan hukum yang hendak di lindungi dengan adanya laporan maka kepentingan pribadi yang di rugikan berhak mendapatkan perlindungan daripada kepentingan publik. Meskipun hukum pidana bersifat publik. Dengan kata lain, alasan beberapa delik digolongkan dalam delik aduan adalah bahwa kepentingan seseorang yang berhak mengadu lebih dirugikan, jika perkara tersebut di proses pada peradilan pidana di bandingkan dengan kepentingan umum.
-
3.3 Unsur-unsur Delik dan Pertanggung jawaban Pidana
-
3.3.1 Actus Reus (Delictum)/Perbuatan Kriminal
-
-
1. Unsur yang konstitutif merupakan usnur yang sesuai uraian suatu delik (bestanddelen; Tatbestanmassigkeit)
-
2. Unsur diam-diam (kenmerk)
-
a. Perbuatan yang di katagorikan aktif atau pasif
-
b. Perbuatan atau sifat yang melawan hukum obyektif atau subyektif;
-
c. Tidak ada korelasi suatu dasar pembenar (rechvaardig-ingsground, justification).
-
3.3.2 Mens Rea/Pertanggungjawaban Pidana
-
1. Kemampuan seseorang untuk mempertanggung jawabkan suatu akibat tindakan (Teorekeningvatbaarheid)
-
2. Kesalahan yang diartikan luas
-
a. Dolus/kesengajaan
-
1) Sengaja merupakan tindakan hukum dengan akal sehat yang memang menjadi niat pelaku (oogmerk)
-
2) Sengaja dalam kontek sadar hukum memberikan kepastian atau keharusan untuk berbuat (zekerheidsbewustzijn) sengaja sadar hukum yang di mungkinkan (Dolus eventualis, mogelijkeheidsbewustzijn).
Syarat-syarat pemidanaan (Strafyoridussetzungen) A + A= A dan A + B = C Syarat Obyektif + Syarat Subyektif = Syarat Pemidanaan dengan arti lain bahwa kebernaran tidak bisa di gabungkan dianatara keduanya.
Jika melihat dari sejarah delik aduan, pada permulaannya tercantum dalam Pasal 22 Wetboek van Strafvordering Belanda terhadap beberapa tindak pidana, misalnya perzinahan, penghinaan atau penggelapan barang titipan. Selanjutnya, pada tahun 1886 dalam Wetboek van Strafrecht Belanda mencantumkan siapa yang berhak mengajukan aduan, dengan jangka waktu untuk mengadukan, dan menarik kembali aduannya. 18 Selain itu, delik aduan juga termasuk dalam peraturan hukum yang memberikan kekuasaan hukum kepada setiap individu/pribadi. Dengan kata lain, kapasitas dan kualifikasi atas individu tersebut diatur lebih spesifik.19
Dalam perspektif Teori Hukum, kebijakan legislasi di dalam menetapkan beberapa delik tergolong dalam delik aduan, termasuk perwujudan dari Teori Hukum Aristoteles. Hukum menurut Aristoteles adalah ‘Rasa Sosial-Etis’.20 Dengan maksud, bahwa hukum ditujukan untuk keadilan. Prinsip keadilan ini berpatokan pada equality before the law, sebagai perwujudan yang menjadikan delik aduan terbagi menjadi dua yakni, delik aduan absolut dan delik aduan relatif.
-
3.4 Hukum Pidana Materiil/Delik-Delik
Hukum pidana materil dalam arti sempit sebuah delik dalam KUHP (UU No. 1 tahun 1946).
-
1. I : Memuat penjelasan sebuah Ketentuan Umum
-
2. II : Memuat penjelasan sebuah Kejahatan
-
3. III : Memuat penjelasan sebuah Pelanggaran
Hukum pidana materil dalam arti luas sebuah delik diluar kuhp yang keseluruhannya di atur di luar kuhp seperti:
-
> Pidana Korupsi
-
> Pidana Ekonomi
-
> Pidana Imigrasi
-
> Pidana Perpajakan
-
> Pidana Pencucian Uang
-
> Pidana Terorisme
-
> Pidana Narkotika
-
> Pidana Psikotropika
-
> Dll
UUD 1945 merupakan sebuah sebagai alat penguji juga merupakan pedoman di dalam pembentukan UU. Latar belakang pemikirannya di dasarkan pada sebuah berdirinya Negara Hukum. Sebagai negara hukum, maka konsekuensi kehidupan bermasyarakatan, kebangsaan, dan bernegara termasuk pemerintah harus di dasarkan dan patuh untuk menjalankan suatu aturan yang termuat dalam hukum nasional yang berlaku. 21 Kebijakan legislasi yang mengatur tindak pidana sebagai delik aduan, seharusnya mengatur tentang hal-hal yuridis yang berkaitan dengan masalah pengaduan, antara lain:
-
a. Subjek yang di berikan hak untuk melakukan pengaduan;
-
b. Subjek pengganti dari yang berhak mengadu (misalnya meninggal atau belum dewasa);
-
c. Batas waktu pengaduan dan penarikan kembali pengaduan;
-
d. Akibat-akibat yuridis dari adanya pengaduan
Dalam pembentukan UU maka harus di dasarkan pada asas kepastian hukum dan juga dua asas yang menjadi dasar sebagai proses pembentukan sebuah UU22, supaya sesuai dengan pedomannya yang berlaku dalam pembentukan perundang-undangan. Asas ini terbagi menjadi 2 (dua), yakni asas formal dan asas material. Dalam asas formal tersebut, seharusnya pencantuman delik aduan di dalam UU ITE harus mempunyai tujuan yang jelas. Maksudnya adalah pengaturan suatu delik menjadi delik aduan, pengaturannya bukan hanya menyebut suatu delik, menjadi delik aduan. Tetapi, lebih mengatur kepada subjek hukum yang berhak mengadu, subjek pengganti, dan batas waktu mengadunya.
Konteks yang dapat dilihat di dalam UU ITE, sebuah kegiatan yang menstransmisikan, mendistribusikan, menyebarkan konten yang sifatnya mengandung unsur melawan hukum disebut delik. Perihal tersebut justru menimbulkan persoalan secara yuridis, karena konten di dalam KUHP merupakan judul, sub, bab, tindak pidana, yang di dalamnya terbagi menjadi beberapa tindak pidana. Salah satunya ialah tindak pidana. Tetapi, KUHP tidak mendefinisikan secara detail rumusan itu bagaimana, KUHP hanya merumuskan bagian unsur perbuatan yang dapat di memungkinkan memenuhi unsur delik Pasal 310 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, pencantuman delik aduan di dalam UU ITE tidak di dasarkan pada suatu asas tujuan yang jelas (beginsel van duidelijke doelstelling).
Sedangkan di dalam asas material, terdapat sebuah asas yang memuat terminologi dan sistematika sebagai perumusan yang benar (het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek). Di dalam konteks ini, pencantuman delik aduan di dalam UU ITE tidak tepat, karena delik aduan termasuk dalam kualifikasi teoritik/ilmiah. Seperti delik formil dan delik materiil. Seharusnya yang di cantumkan ialah subjek hukum yang berhak mengadu, subjek hukum pengganti mengadunya dan batas waktu pengaduannya. Jika merujuk pada KUHP bisa dilakukan secara sistematis dengan menganut ketentuan pada KUHP, yakni Pasal 72 sampai dengan Pasal 75. Dengan demikian, maka dasar pada proses pembentukan UU tersebut tidak di dasarkan pada suatu asas terminologi dan sistematika yang benar sebagai landasannya.
Sebagai akhir dari kesimpulan penelitian ini, pencantuman delik aduan (klacht delict) di dalam UU ITE dengan menyebut suatu delik menjadi delik aduan begitu saja, tidaklah tepat secara ilmu perundang-undangan. Dikatakan demikian, karena materi muatannya yang terkandung tidak di dasarkan pada keterbukaan konteks yang masih abstrak dalam pasal tersebut, yakni tidak secara gambling dan eksplisit untuk menjelaskan rumusan suatu delik yang mendasari tentang terminologi dan sistematika yang relevan. Seharusnya yang di cantumkan di dalam UU ITE ialah subjek hukum yang berhak mengadu, subjek hukum pengganti, dan batas waktu mengadunya. Jika memang harus merujuk di dalam KUHP, yakni Pasal 72 sampai dengan Pasal 75, maka perihal pengaduannya mencantumkan dengan jelas dan tegas menggunakan ketentuan umum di KUHP.
Saran di tujukan kepada Judicial Review kiranya dapat mengkaji ulang pasal 45 ayat (5) UU ITE dalam memberikan definisi yang jelas terkait delik aduan yang di maksudkan.
Ucapan terima Kasih (Acknowledgments)
Terima kasih di sampaikan kepada Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, rekan-rekan perkuliahan yang selalu memberi kehangatan dalam mencari ilmu, tidak lupa rekan-rekan Komunitas Umaha Publikasi (Kubik). Serta rekan-rekan penulis dalam karya ilmiah ini. Semoga atas kontribusi dan perjuangan dalam open sains ini menjadi catatan amalan ilmu yang bermanfaat. Amin.
Daftar Pustaka
Buku
Arief, B. N. (2013). Kapita selekta hukum pidana. Citra Aditya Bakti.
Arief, B. N. (2013). Kapita Selekta Hukum Pidana, Cet-III, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Arief, B. N. (2016). Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan, Cet. Ke-3, Semarang: Pustaka Magister.
Arief, B. N. & Muladi. (2010). Bunga Rampai Hukum Pidana, Cet. Ke-3, Bandung: Alumni.
Farida Indrati S., Maria. (2007). Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, Materi Muatan), Yogyakarta: Kanisius.
H. L. A. Hart. (2016). The Concept of Law. Diterjemahkan M. Khozim. Konsep Hukum, Cetakan ke-8, Bandung: Nusa Media.
Kelsen, H. (2013). Essays in Legal and Moral Philosophy. Diterjemahkan B. Arief Sidharta.
Hukum dan Logika, Cet. Ke-5, Bandung: Alumni.
Saleh, R. (1988). Dari lembaran kepustakaan hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
Sianturi, S. R. (1986). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni Ahaem.
Soedarto. (2007). Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan ke-5, Bandung: Alumni.
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). Teori Hukum Strategi Tertib Manusia, Yogyakarta: Genta Publishing.
Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM. (2016). Filsafat Ilmu, Cet. Ke-7, Yogyakarta: Liberty.
Utrecht, E. (1957). Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet. Ke-4, Jakarta: Ichtiar.
Utrecht, E. (1965). Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Bandung: Universitas.
Jurnal
Febriansyah, F. I. (2016). Konsep pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jurnal Perspektif, 21(3), 220-229.
Atmaja, A. E. (2014). Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satipto Rahardjo. Jurnal Opinio Juris, 16, 48-91
Sumarwani, S. (2014). Tinjauan Yuridis Pemidanaan Cybercrime Dalam Perpektif Hukum Pidana Positif. Jurnal Pembaharuan Hukum, 1(3), 287-296.
Wicaksono, A. S., Sularto, R. B., & Asy'ari, H. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Formulasi Perbuatan Pencemaran Nama Baik Presiden Sebagai Perlindungan Simbol Negara. Diponegoro Law Journal, 5(2), 1-9.
Leuwol, T. (2018). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyber Crime yang Menyebarkan Isu Suku, Ras, Agama Dan Antar Golongan (SARA) Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Ite Nomor 19 Tahun 2016. LEX CRIMEN, 7(2). 27-34.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Trasnsaksi Elektronik
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
73
Discussion and feedback