Penerapan Distinction Principle Dalam Perundang-Undangan di Indonesia
on
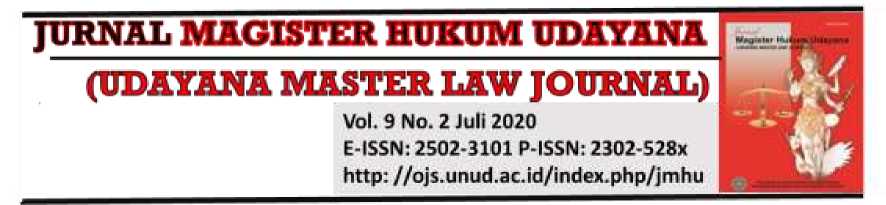
Eno Prasetiawan1, Lina Hastuti2
1Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, E-mail: eprasetiawan555@gmail.com 2Fakultas Hukum Universitas Airlangga, E-mail: linahastuti@gmail.com
Info Artikel
Masuk: 1 Pebruari 2019 Diterima: 12 Juli 2020
Terbit: 31 Juli 2020
Keywords:
International Humanitarian Law; Distinction Principle; Civilian Objects; Military Objects
Kata kunci:
Hukum Humaniter
Internasional; Prinsip
Pembedaan; Objek Sipil; Objek
Militer
Corresponding Author:
Eno Prasetiawan, Email: eprasetiawan555@gmail.com
DOI:
10.24843/JMHU.2020.v09.i02.
p.16
Abstract
The ratification of the 1949 Geneva Convention implies that Indonesia must obey and implement international humanitarian law, specifically the distinction principles. One of the distinction principle relates to the separation of civilian objects and military objects, where attacks are only passed on to military objects. civilian objects and military objects in Indonesia are practically not separated and close together. This has the potential to become a threat if it does not follow the rules in international humanitarian law. The purpose of this study is to find out the importance of applying the distinction principle regarding civil objects and military objects in legislation in Indonesia. This writing uses a normative legal research method, the approach is carried out through a legislative approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the separation of civilian and military objects is a preventive effort in protecting civilians and civilian objects in the event of war or armed conflict. Although it has been a party to the 1949 Geneva convention, the application of the principle of differentiation has not yet been fully implemented by Indonesia, there are no specific regulations regarding the separation of civilian and military objects in its national legislation.
Abstrak
Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 berimplikasi adanya kewajiban Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan hukum humaniter internasional, khsusnya prinsip pembedaan. Salah satu prinsip pembedaan terkait pemisahan objek sipil dan objek militer, di mana ketika berperang serangan-serangan hanya dibenarkan ke objek-objek militer saja. Objek sipil dan objek militer di Indonesia secara praktik tidak dipisahkan atau berdekatan. Ini berpotensi menjadi ancaman khususnya bagi keselamatan penduduk sipil apabila tidak mengikuti aturan di dalam hukum humaniter internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pentingnya penerapan distinction principle terkait objek sipil dan objek militer dalam perundang-undangan di Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan melalui perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemisahan objek sipil dan militer merupakan upaya preventif dalam melindungi penduduk sipil dan objek-objek sipil
jika terjadi perang atau konflik bersenjata. Meskipun telah menjadi pihak dalam konvensi jenewa 1949, penerapan prinsip pembedaan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Indonesia, belum ada peraturan khusus terkait pemisahan objek sipil dan militer dalam legislasi nasionalnya.
-
1. Pendahuluan
Perang bukanlah sesuatu yang dilarang, namun yang diperhatikan adalah bagaimana berperang yang adil serta mampu melindungi korban akibat perang. 1 Pembatasan dalam berperang berawal dari kebiasaan internasional yang berasal dari negara-negara barat di mana perkembangan hukum perang/hukum humaniter internasional itu lahir. Dari kebiasaan itu dibuatlah suatu aturan tentang hukum perang yang diantaranya dituangkan di dalam Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag mengatur mengenai cara dan alat berperang, sedangkan Hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang. Kedua ketentuan hukum tersebut merupakan sumber hukum humaniter international yang utama.
Aturan internasional yang ditetapkan oleh perjanjian atau kebiasaan internasional membatasi hak-hak dari para pihak yang terlibat konflik dalam penggunaan metode atau sarana berperang, serta melindungi orang dan objek yang bisa berpotensi terkena dampak akibat konflik.2 Terkait perlindungan terhadap orang sipil pada masa perang, diatur dalam Hukum Jenewa/Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol-Protokol Tambahan 1, 2, dan 3, di mana keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan aturan yang tidak dapat dipisahkan. Saat ini sudah 196 negara yang telah meratifikasi atau menjadi pihak dalam Konvensi Jenewa 1949.3
Ketika terjadi perang atau konflik, para pihak yang terlibat dalam konflik harus selalu membedakan antara penduduk sipil (civilian) dan kombatan (combatant) agar dapat menyelamatkan penduduk sipil dan harta benda sipil. Penduduk sipil (civilian) adalah mereka yang tidak (boleh) turut serta dalam pertempuran, mereka harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sasaran serangan.4 Sementara kombatan adalah orang-orang yang berhak ikut serta secara langsung dalam pertempuran atau medan peperangan. Penduduk sipil secara keseluruhan tidak boleh diserang, penyerangan hanya boleh dilakukan terhadap kombatan dan objek-objek militer. Objek militer atau sasaran militer yaitu objek yang karena sifatnya, lokasinya, atau tujuan penggunaannya dapat memberikan kontribusi yang efektif pada operasi militer, apabila dihancurkan (seluruhnya maupun sebagian), dikuasai atau dinetralisir, maka dapat memberikan
keuntungan militer yang pasti. Adapun objek-objek sipil adalah semua objek yang bukan merupakan sasaran militer. Ketentuan tentang pembedaan orang dan objek ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam hukum humaniter internasional yang disebut distinction principle (prinsip pembedaan), yang merupakan salah satu asas yang melandasi hukum perang. 5 Tujuan utama dari distinction principle adalah untuk melindungi penduduk sipil, dengan membedakan apa dan siapa saja pihak yang boleh diserang dan tidak boleh diserang.6
Hukum humaniter internasional mengamanatkan kepada negara untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap akibat-akibat serangan. Salah satunya mengatur negara untuk berusaha memindahkan penduduk sipil dan objek sipil dari daerah yang dekat sasaran-sasaran militer. Selain itu perlu untuk menghindari penempatan objek-objek militer didalam atau daerah yang berdekatan dengan penduduk padat. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan/preventif apabila terjadi perang atau konflik bersenjata dimasa mendatang, penduduk sipil dan objek sipil tidak terkena dampak serangan akibat perang atau konflik bersenjata tersebut.
Melihat kondisi nyata saat ini khususnya di berbagai daerah di Indonesia, objek sipil dan objek militer pada umumnya berdekatan dan cenderung tidak dipisahkan oleh negara. Melihat bagaimana pesatnya pembangunan di berbagai daerah, banyaknya gedung, perumahan, objek wisata, tempat ibadah, dan lain sebagainya mendekati markas/basis militer, sehingga apabila dulunya markas militer yang mungkin berada di daerah yang jarang penduduk, kini banyak ditemukan pada umumnya berada ditengah kota, mulai terintergrasi dengan aktifitas warga sipil dan berdekatan dengan objek-objek sipil. Tidak hanya itu, fasilitas umum juga bersatu antara objek sipil dan militer, contohnya, beberapa bandara di Indonesia, pada umumnya landasan yang digunakan untuk pesawat sipil juga digunakan oleh pesawat militer. Meskipun banyak tidak disadari, namun hal ini justru bisa membahayakan keamanan suatu negara bila terjadi perang atau konflik bersenjata. Para kombatan atau musuh biasanya akan mengarahkan serangan-serangan itu ke objek/sasaran militer saja sesuai dengan prinsip hukum perang. Apabila objek/sasaran militer berdekatan atau bahkan menyatu dengan objek sipil, serangan-serangan musuh akan berdampak pada penduduk sipil dan tentunya mengakibatkan banyak korban dan kerusakan pada objek-objek sipil.
Pemisahan objek sipil dan militer seyogyanya dilaksanakan pada masa damai sebagai upaya pencegahan agar negara dapat mengantisipasi bila di masa mendatang terjadi perang atau konflik bersenjata dengan negara lain, selain itu juga mustahil melakukan pembedaan terhadap orang dan objek sipil atau militer pada masa konflik. Sebagai jalan terakhir, perang memang tidak diharapkan oleh seluruh masyarakat internasional namun sebagai langkah antisipasi negara juga harus siap akan kondisi terburuk di masa yang akan datang. Persaingan-persaingan antar negara dewasa ini dalam semua aspek dan berbagai bidang tentunya bisa berpotensi terjadi gesekan antar negara. Bila terjadi perang, negara harus siap dengan segala kondisi baik militer maupun upaya perlindungan bagi objek sipil dan warga sipilnya.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan terhadap Penduduk Sipil pada Masa Perang dan mengundangkannya dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Aksesi Negara Republik Indonesia terhadap Konvensi Jenewa 1949. 7 Secara normatif Indonesia mengakui dan menjadi pihak dalam perjanjian internasional itu sehingga terikat hak dan kewajibannya untuk mematuhi hukum Jenewa. Hal yang menjadi permasalahan adalah belum ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai pemisahan objek sipil dan objek militer. Seharusnya jika Indonesia menghormati prinsip demi melakukan perlindungan pada penduduk sipil, peraturan perundang-undangan di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan terkait pemisahan objek sipil dan militer yang diamanatkan oleh hukum humaniter internasional.8 Selain terus melaksanakan pembangunan sesuai polanya, tetapi juga tetap memperkirakan potensi-potensi ancaman kedepannya jika objek sipil dan militer tidak dipisahkan. Hal ini tentunya sebuah permasalahan dimana secara internasional Indonesia telah terikat, sementara tidak melaksanakan amanat konvensi untuk mengatur lebih khusus dalam perundang-undangan Indonesia.
Baik negara yang meratifikasi ataupun tidak meratifikasi, ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional ini merupakan kebiasaan internasional yang mestinya dipatuhi oleh negara-negara. 9 Meskipun tidak ada satu negara pun yang mengharapkan akan terjadinya perang, namun perlu untuk di tinjau sejauh mana perhatian negara khususnya Indonesia terhadap ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 ini. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah penerapan distinction principle dalam hukum humaniter internasional terkait pemisahan objek sipil dan objek militer dalam perundang-undangan di Indonesia.
Penelitian-penelitian yang mengangkat topik tentang distinction principle/prinsip pembedaan yang selanjutnya digunakan sebagai orisinalitas dalam tulisan ini antara lain Ispancius Ismail dan Danial.10 Ispancius Ismail menulis artikel hukum berjudul “Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi Tentang Urgensi dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977”, tulisan tersebut mengkaji urgensi dan penerapan Konvensi Jenewa dalam hukum nasional dari perspektif hukum perjanjian internasional. Adapun artikel yang ditulis Danial berjudul “Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern”, tulisan yang mengkaji konsep prinsip pembedaan dan urgensi implementasi hukum humaniter internasional dalam kerangka konflik bersenjata modern.
Tujuan penulisan ini untuk mengkaji urgensi distinction principle terkait objek sipil dan objek militer serta implementasinya di Indonesia. Penelitian ini menekankan konsep
pentingnya penerapan hukum humaniter internasional dan prinsip pembedaan terkait pemisahan objek sipil dan objek militer dalam perundang-undangan di Indonesia sebagai langkah pencegahan dalam melindungi penduduk sipil jika terjadi konflik di masa mendatang.
-
2. Metode Penelitian
Penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Fokus kajian berangkat dari kekosongan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). 11 Bahan hukum yang diuji diantaranya Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil pada Masa Perang, Protokol Tambahan 1 1977, dan beberapa instrumen peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang berkaitan dengan implementasi hukum humaniter internasional. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi literatur. Bahan hukum yang diolah dari penelitian ini dianalisa dengan menafsirkan dan mengkonstruksi pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan dengan metode deduktif, yakni menganalisis hal-hal yang sifatnya umum kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.
-
3. Hasil dan Pembahasan
Indonesia yang merupakan anggota dari masyarakat internasional menurut hukum internasional terklasifikasi sebagai subjek hukum internasional, sehingga memiliki apa yang disebut dengan kedaulatan atau souvereignity. Setiap negara yang merdeka berdaulat untuk mengatur segala sesuatu yang ada di wilayahnya. Kedaulatan negara bermakna negara memiliki kewenangan dalam penetapan ketentuan-ketentuan dalam hukum nasionalnya terhadap suatu peristiwa, kekayaan dan perbuatan.12
Indonesia sebagai negara hukum13 yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disbut UUD 1945) sebagai konstitusi negaranya. Dalam penyelenggaraan bernegara Indonesia tentu harus taat dan menghormati aturan dan amanat yang diberikan oleh konstitusinya. Di dalam konstitusi berisi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum di Alinea 4 pada Pembukaan UUD 1945.
Penjabaran dari Alinea 4 salah satunya bahwa Indonesia ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia demi menciptakan perdamaian. Sebagaimana dalam Pasal 11 UUD 1945 menjelaskan Indonesia sebagai negara yang berdaulat melaksanakan politik luar negeri, dan memiliki hak sepenuhnya menentukan sikap dan kehendak sendiri. Mempunyai hak atau kemandirian untuk menentukan sikap sebagai negara yang berdaulat berimplikasi Indonesia bebas memilih untuk terikat
pada perjanjian internasional. Salah satu sikap Indonesia adalah mengikatkan diri pada Konvensi Jenewa 1949 terkait hukum perang yang mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil.
UUD 1945 jelas mengatur agar negara memberikan prioritas dalam melindungi warga negara Indonesia dalam keadaan apapun, terutama memajukan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Dalam kaitannya dengan terikatnya Indonesia dengan Konvensi Jenewa 1949, hal ini selaras antara aturan konvensi yang mewajibkan bagi negara untuk mematuhi Konvensi berupaya melindungi penduduk sipil dalam konteks perang, juga aturan UUD 1945 mewajibkan negara untuk melindugi seluruh warga negara dalam keadaan apapun.
Selain UUD 1945 mengamanatkan perlindungan warga negara dalam pembukaannya, beberapa Pasal di dalam UUD 1945 juga mengatur khusus terkait HAM. Pada BAB XA tentang HAM mengatur terkait hak-hak warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 28A mengatur tentang hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan, hak ini wajib dimiliki bagi setiap manusia. Pasal 28G yang menyatakan hak-hak setiap orang unutk dilindungi secara diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu. Hal ini menegaskan bahwa negara harus mengantisipasi setiap perihal yang berpotensi mengancam keselamatan warga negaranya. Oleh karenanya perlu ada upaya pencegahan dari negara untuk melindungi warga negara dan setiap ancaman yang berpotensi membahayakan keselamatan warga negaranya.
Dari beberapa aturan tersebut dapat disimpulkan ada kewajiban negara dalam upaya perlindungan HAM warga negaranya. Kewajiban Indonesia terkait pemenuhan HAM terdapat dalam Pasal 28I Ayat (4) UUD 1945, di mana negara atau pemerintah bertanggung jawab terkait HAM. Langkah kongkrit untuk melakukan pemajuan dan perlindungan HAM melalui langkah pencegahan dan diatur lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan nasionalnya.
Konstitusi Indonesia jelas memberikan prioritas terkait perlindungan warga negara dari setiap ancaman yang ada. Hal ini selaras dengan semangat Konvensi Jenewa 1949 terkait upaya perlindungan warga sipil dari konflik. Oleh karenanya, aturan dan prinsip-prinsip dalam hukum humaniter internasional harus diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia sebagai upaya penghormatannya terhadap hak asasi warga negaranya.
Hukum internasional berlandaskan prinsip dasar yang dinamakan pacta sunt servanda, hukum nasional berlandaskan prinsip dasar untuk mentaati setiap peraturan perundang-undangan. Hukum internasional dan hukum nasional keduanya bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan.14 Indonesia meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil pada masa perang ke dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958 tentang Aksesi Negara Republik Indonesia Terhadap Konvensi
Jenewa 1949. Artinya secara normative Indonesia mengakui dan menjadi pihak dalam perjanjian internasional itu sehingga terikat hak dan kewajibannya untuk mematuhi Hukum Jenewa. Sebagai negara peserta, ada kewajiban bagi Indonesia untuk mengimplementasikan ketentuan hukum humaniter internasional ke dalam legislasi nasional.
Menurut Mochtar Kusumaatmadja ketika perjanjian internasional itu disepakati, maka akan menjadi akibat hukum bagi para pihak. 15 Salah satu perjanjian internasional terkait hukum humaniter internasional adalah Konvensi Jenewa 1949. Keberlakuan Konvensi Jenewa 1949 ini berbeda dengan perjanjian internasional yang lainnya. Aturan di dalam Pasal 1 ketentuan yang sama pada keempat Konvensi Jenewa 1949 (common article) mengatur bahwa negara-negara berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap konvensi ini dalam keadaan apapun. Penempatan ketentuan ini dalam Pasal 1 menunjukkan betapa pentingnya arti ketentuan ini menurut para peserta konferensi. Selanjutnya ditegaskan bahwa para pihak peserta agung tidak hanya berjanji untuk menghormatinya, tetapi juga akan menjamin penghormatan konvensi. Ini berarti bahwa negara harus menjamin para petugas militer atau sipil untuk mentaati konvensi, serta pemerintah juga wajib mengawasi bahwa perintahnya itu benar-benar dilaksanakan.16 Menurut Draper, kewajiban negara menghormati dan melaksanakan konvensi bersifat unilateral/sepihak, tidak bersifat timbal balik (reciprocity) dan lebih bersifat legislasi dan kontraktual.17
Ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 berimplikasi Indonesia harus tunduk kepada hukum humaniter internasional dan punya kewajiban untuk mengimplementasikan aturan-aturan dan prinsip di dalamnya. Implementasi dari isi perjanjian internasional berkitan juga dengan norma hukum nasional suatu negara. Ini didasarkan dengan teori kedaulatan yakni teori yang menekankan pada prinsip kedaulatan dan yurisdiksi negara. Dalam kaitan ini Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan sikap dalam upaya implementasi dari suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. 18 Salah satu cara mengimplementasikan hukum humaniter internasional adalah dengan langkah pencegahan (preventif), yaitu:19
-
1. Menyebarluaskan pengetahuan terkait hukum humaniter internasional. Penyebarluasan dapat ditujukan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan peraturan, militer sebagai organ penting dalam pertahanan dan keamanan negara, palang merah, serta kalangan akademik/universitas;
-
2. Melatih personil-personil yang memiliki kualifikasi untuk memfasilitasi pelaksanaan hukum humaniter internasional. Melatih dalam artian bukan hanya dalam segi teknis, tetapi juga dapat berupa pemberian pengetahuan dan materi;
-
3. Mengadopsi dan memasukkan ke peraturan perundangan nasional untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional;
-
4. Menerjemahkan naskah Konvensi-konvensi Jenewa.
Di samping berusaha melindungi korban konflik bersenjata, hukum humaniter internasional juga mencoba untuk membatasi pelaksanaan operasi militer dengan cara kemanusiaan. Dalam menganalisis aturan-aturan yang terkandung dalam Hukum Den Haag, penting untuk diingat bahwa perlu dipertahankan keseimbangan atau proporsionalitas antara kebutuhan militer dan pertimbangan kemanusiaan. Meski prinsip ini kedepannya tidak selalu dihormati dalam praktik, namun hal yang paling utama adalah tetap untuk mengupayakan perlindungan warga sipil dari dampak suatu konflik.20
Prinsip pembedaan tidak hanya mengatur tentang membedakan penduduk menjadi dua golongan ketika terjadi konflik, tetapi juga mengatur tentang pemisahan objek sipil dan objek militer. Sebagaimana telah dipaparkan Pasal 48 Protokol Tambahan 1 1977 bahwa adanya perintah untuk memisahkan objek sipil dan objek militer, dan melakukan serangan yang hanya boleh ditujukan kepada objek militer saja demi menjamin penghormatan terhadap kemanusiaan. Artinya warga sipil yang berada di objek sipil sekalipun tidak boleh menjadi sasaran militer ataupun menjadi korban akibat serangan musuh.21
Membedakan objek sipil dan objek militer ketika konflik atau perang terjadi tidaklah mudah. Secara pengaturan ada perbedaan antara objek sipil dan objek militer menurut Protokol Tambahan 1 1977. Pasal 52 Ayat (1) Protokol Tambahan 1 1977 memberikan defenisi objek sipil, menyatakan bahwa objek sipil bukan merupakan sasaran serangan. Praktiknya, benda-benda bersejarah dan tempat-tempat ibadah juga dilindungi, sama halnya benda-benda yang dianggap penting untuk kelangsungan hidup penduduk sipil. Berikut contoh objek sipil menurut hukum humaniter internasional:
Tabel 1. Objek Sipil dan Pengaturan
|
No |
Objek Sipil |
Dasar Hukum |
|
1 |
Bangunan keagamaan, seni, ilmu, monumen-monumen sejarah, rumah-rumah sakit (tempat perawatan bagi korban luka dan sakit) |
Pasal 27 Konvensi Den Haag IV 1907 |
|
2 |
Pelabuhan, kota, desa, tempat tinggal, atau bangunan. |
Pasal 1 Ayat (1) Konvensi Den Haag IX 1907 |
|
3 |
Bahan makanan, daerah-daerah pertanian yang memproduksi bahan makanan, hasil-hasil panen, ternak, instalasi air minum dan perbekalan |
Pasal 54 Ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 |
20 M. N Shaw. (2008). International Law. New York: Cambridge University Press. p. 1184.
21 K. J Heller. (2015). Disguising a Military Object as a Civilian Object: Prohibited Perfidy or Permissible Ruse of War?. Stockton Center for the Study of International Law: International Studies, 91, 517-539.
|
bangunan pengairan, lingkungan alam. | |||
|
4 |
Lingkungan alam. |
Pasal 55 Tambahan I |
Protokol 1977 |
|
5 |
Bangunan yang mengandung yang membahayakan, bendungan, tanggul dan pembangkit tenaga listrik nuklir. |
tenaga Pasal 56 Protokol seperti, Tambahan I 1977 pusat | |
Sumber: diolah dari berbagai sumber
Defenisi Objek militer menurut Pasal 52 Ayat (2) Protokol Tambahan I 1977 adalah Objek-objek atau sasaran militer dibatasi pada objek-objek yang menurut sifat, letak, tujuan atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer, apabila dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, didalam keadaan yang berlaku pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti. Artinya Serangan-serangan dibatasi hanya pada objek-objek militer.
Berikut contoh objek/sasaran militer menurut hukum humaniter internasional:
Tabel 2. Objek/Sasaran Militer dan Pengaturannya
No Objek/ Sasaran Militer Dasar Hukum
1 pekerjaan militer, militer atau Pasal 1 Ayat (2) Konvensi Den perusahaan angkatan laut, Haag IX 1907 depot senjata atau peralatan perang, bengkel atau pabrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan armada atau tentara musuh, dan kapal perang di pelabuhan.
|
2 |
Persenjataan, |
peralatan, Protokol Tambahan I 1977 |
|
transportasi, |
perbentengan, | |
|
depot militer, |
markas dan | |
|
markas besar, komunikasi. |
pusat-pusat |
Sumber: diolah dari berbagai sumber
Prinsip pembedaan pada awal mula diatur mulai dari Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, hingga Protokol Tambahan 1 1977 cenderung lebih banyak pengaturan terkait pembedaan orang, yakni antara kombatan dan penduduk sipil. Pengaturan tentang pembedaan atau pemisahan terhadap objek sipil dan militer baru ada pada Protokol Tambahan 1 1977.22 Oleh karena tidak banyak aturan yang spesifik dan mendetail terkait pemisahan objek, bukan berarti bahwa pemisahan objek sipil dan militer tidak penting untuk dilaksanakan. Negara dimanatkan untuk memisahkan objek sipil dan militer oleh hukum humaniter internasional. Setiap terjadi perang atau konflik, selalu ada potensi bahwa penduduk sipil berada di kawasan objek militer, atau mungkin berada di kawasan objek sipil yang juga berdekatan dengan objek militer. Pada Pasal 57 Ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 jelas menyatakan bahwa di
disamping melaksanaan operasi-operasi militer, juga harus terus memperhatikan upaya menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil. Artinya dalam keadaan apapun, prioritas perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil juga tidak bisa dikesampingkan. 23 Pasal 58 Protokol Tambahan 1 1977 menjelaskan terkait tindakan-tindakan terhadap akibat-akibat serangan, negara pihak dalam konflik harus sejauh mungkin melakukan pemindahan penduduk sipil dan objek-objek sipil yang berada dibawah kekuasaan mereka dari daerah yang berdekatan dengan objek-objek militer, menghindari penempatan objek-objek militer di dalam atau di dekat daerah yang berpenduduk padat, serta perlu untuk mengambil tindakan-tindakan untuk melindungi penduduk sipil objek-objek sipil dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh operasi-operasi militer.
Ketentuan perlindungan terhadap penduduk sipil dan objek sipil mengikat bagi seluruh negara, dan negara berkewajiban memisahkan orang sipil dan objek sipil jauh dari daerah yang berdekatan dengan sasaran militer atau objek militer. Pemisahan objek sipil itu ditempatkan harus sejauh mungkin dari daerah berpenduduk padat. Oleh karena aturan itu, negara wajib mengambil tindakan preventif untuk melaksanakan pemisahan objek sipil jauh dari daerah sasaran militer. Pada saat konflik atau perang terjadi, bisa saja orang atau bangunan-bangunan milik sipil menjadi sasaran militer dikarenakan berada di kawasan militer, atau paling tidak terkena dampak dari serangan yang ditujukan kepada objek militer. Oleh karena itu, tindakan pemisahan merupakan suatu amanat hukum humaniter internasional yang bertujuan melindungi orang atau objek sipil menjadi korban atau dampak serangan.
Tujuan utama pembedaan terhadap objek, pemisahan objek sipil dan militer adalah demi melindungi penduduk sipil dari bahaya dan ancaman yang kemungkinan timbul dari operasi militer sebagai mana ketentuan Pasal 51 Protokol Tambahan I 1977. Agar perlindungan ini dapat dirasakan hasilnya, ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional yang dapat diterapkan harus dipatuhi dalam segala keadaan.
Penghancuran merupakan bagian yang sudah melekat dari sebuah konflik bersenjata. Tidak ada perang yang dilakukan tanpa merusak objek seperti properti milik pribadi atau milik umum, hal itu sudah pasti terjadi. 24 Melihat bagaimana dampak yang diakibatkan dari Perang Dunia Pertama dan Kedua sangat luar biasa menyengsarakan, maka masyarakat internasional berusaha membatasi perang atau konflik yang terjadi di kemudian hari dengan cara dan batasan yang lebih manusiawi. Pembatasan ini menjadi upaya untuk menghindari terulangnya kehancuran objek-objek dan kesengsaraan penduduk sipil yang telah terjadi di masa lampau.25 Prinsip pembedaan sebagai prinsip utama yang mengatur apa saja objek yang dapat diserang dan siapa saja orang yang boleh ikut berperang, menjadi penting untuk diterapkan oleh negara dalam hukum humaniter internasional.
Setiap negara mempunyai kewajiban yang ditegaskan oleh hukum humaniter internasional. Kewajiban-kewajiban itu bersifat luas, dan memerlukan panduan untuk mengimplementasikannya. 26 Meskipun saat ini tidak terjadi perang atau konflik bersenjata dalam lingkup yang luas dan tidak seorangpun yang mengharapkan hal itu terjadi, langkah pencegahan menjadi upaya yang harus dilakukan negara untuk melindungi umat manusia di masa mendatang. Protokol Tambahan I 1977 memiliki banyak klausul yang menitikberatkan pada upaya pencegahan agar penduduk sipil tidak menjadi korban atau bagian dari dampak hasil serangan musuh.27
Selain adanya aturan yang mewajibkan negara untuk mengimplementasikan prinsip pembedaan di situasi apapun dalam hukum humaniter, alasan lainnya yang sangat kuat terkait pentingnya prinsip pembedaan ini dilaksanakan adalah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Salah satu instrumen dasar HAM yaitu pada Universal Declration of Human Rights 1948 (selanjutnya disebut DUHAM). Hukum humaniter internasional dan hukum HAM saling melengkapi. Dua instrument ini memberikan perhatian terhadap perlindungan kehidupan, kesehatan, dan martabat individu dengan sudut pandang yang berbeda. Hukum humaniter internasional berlaku pada masa konflik, sedangkan hukum HAM memberikan perlindungan terhadap individu setiap saat, baik pada situasi konflik maupun di masa damai.28 Dapat disimpulkan bahwa hukum HAM menjadi dasar bagi setiap individu sebagai perlindungan mereka dari kekerasan dan dampak serangan musuh ketika perang terjadi. Atas alasan HAM, maka penduduk sipil dan objek-objek sipil tidak boleh menjadi korban dan sasaran ketika berperang.
Penghormatan terhadap HAM dari penduduk sipil menjadi prioritas yang telah diatur oleh HAM. Ketika terjadi perang, maka yang menjadi pihak yang konflik adalah kombatan, sebagaimana telah diatur oleh Konvensi-konvensi dalam hukum humaniter internasional. Sementara penduduk sipil yang tidak menjadi pihak dalam konflik, harus dijamin kehidupannya dan keselamatannya sebagaimana melekat hak-hak asasi pada tiap-tiap diri mereka. Oleh karena itu, negara memegang andil yang besar untuk melaksanakan perlindungan HAM pada penduduk sipil, baik ketika konflik maupun di masa damai.29 Upaya pencegahan diperlukan agar hak-hak tersebut dapat terus melekat pada mereka, salah satu upaya itu ialah di mana negara melaksanakan ketentuan hukum humaniter internasional yang juga dilandasi oleh penghormatan terhadap HAM.
Kewajiban untuk melaksanakan hukum humaniter internasional dan HAM terletak di tangan negara. Hukum humaniter internasional mewajibkan kepada negara untuk mengambil tindakan secara praktis dan langkah-langkah hukum, seperti merancang dan menerapkan peraturan perundang-undangan nasional terkait pidana dan terus memberikan sosialisasi terkait hukum humaniter internasional. Hukum HAM juga perlu untuk disebarluaskan melalui pendidikan dan pengajaran,30 selain itu penting
secara hukum untuk menyesuaikan hukum nasional dengan kewajiban-kewajiban negara dalam lingkup internasional.
-
3.4. Ius Constituendum Terkait Distinction Principle di Indonesia
Ketika Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, ada keharusan bagi negara untuk menyesuaikan aturan perundang-undangan nasionalnya dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam hukum humaniter internasional. Terkait aturan pemisahan objek sipil dan objek militer dalam Protokol Tambahan I 1977, itu merupakan upaya pencegahan yang diatur dalam hukum humaniter internasional, maka Indonesia seyogyanya melaksanakan aturan itu.
Misalnya dalam konteks penerbangan, bandara sipil dan pangkalan udara militer dipisahkan sebagai upaya melaksankan prinsip pembedaan. Penataan kawasan perumahan sipil dan kawasan militer, membedakan rumah sakit sipil dan militer, dan terutama menjauhkan objek-objek sipil dari objek-objek yang dapat menjadi sasaran militer. Sebagai upaya kepatuhan terhadap penerimaan Konvensi Jenewa 1949 dalam legislasi nasional, seharusnya aturan-aturan hukum di Indonesia terkait objek sipil dan objek militer mengatur pemisahan kedua kawasan itu.
Dalam Program Legislasi Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut Prolegnas RI), belum ada perencanaan pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan hukum humaniter, 31 sehingga belum ada aturan khusus lebih lanjut untuk melaksanakan prinsip pembedaan dalam Konvensi Jenewa 1949. Undang-Undang Tentang Kepalangmerahan yang sebelumnya masuk prolegnas, baru saja diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, namun aturan itu hanya mengatur terkait penyelenggaraan kepalangmerahan dan aksi-aksi kemanusiaan di Indonesia.
Meskipun dewasa ini negara-negara di berbagai belahan dunia mayoritas berada dalam keadaan damai, namun bagi negara penting untuk memperkirakan potensi terjadinya konflik atau perang di masa mendatang, serta upaya menghadapinya. Jika suatu negara harus menghadapi perang hari ini, negara hanya dapat menghadapi dengan apa yang saat ini tersedia dalam hal sumber daya dan kondisi pertahanannya. 32 Dengan perencanaan itu, maka negara siap untuk menghadapi perang atau konflik dan juga siap dalam melindungi penduduk sipil dan objek-objek sipilnya.
Hukum humaniter internasional mengatur siapa dan apa yang mungkin menjadi sasaran sah dari aksi militer selama konflik bersenjata. Jantung dari aturan-aturan ini adalah prinsip pembedaan, yang melawan gagasan perang membabi buta dan mengharuskan penduduk sipil dan objek sipil harus dibedakan dari sasaran militer,
dan operasi diarahkan hanya terhadap objek atau sasaran militer.33 Pembedaan adalah satu-satunya prinsip paling penting untuk perlindungan korban konflik bersenjata dan merupakan prinsip hukum kebiasaan yang berlaku untuk semua jenis konflik bersenjata.34 Prinsip ini salah satunya tertuang dalam Konvensi Jenewa 1949.
Pada prinsipnya, ketika suatu negara terikat dan mengikatkan diri pada perjanjian internasional, maka negara harus tunduk dan melaksanakan kewajiban yang ada di dalam perjanjian itu sesuai asas pacta sunt servanda. 35 Ketika negara tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian internasional, maka akan menimbulkan konsekuensi bagi negara. Indonesia punya kewajiban melaksanakan aturan dan prinsip di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan protokol-protokol tambahan sebagai implikasi telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949. Kewajiban yang diberikan dalam hukum humaniter internasional salah satunya negara melaksanakan prinsip pembedaan. Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur kewajiban negara memisahkan objek-objek sipil dan objek militer. Kewajiban ini belum dilaksanakan oleh Indonesia apabila dilihat dari segi praktik maupun aturan perundang-undangan yang ada. Pada dasarnya tujuan dari prinsip pembedaan adalah:
-
1. Melindungi kombatan dan penduduk sipil
-
2. Memberikan jaminan HAM yang sangat fundamental
-
3. Mencegah terjadinya perang tanpa batas yang tidak berperikemanusiaan
Salah satu upaya pencegahan dalam prinsip pembedaan itu adalah dengan memisahkan objek sipil dan objek militer pada masa damai. Suatu objek militer oleh hukum humaniter internasional diklasifikasikan sebagai sasaran yang dibenarkan untuk diserang pada saat perang atau dapat disebut sasaran militer. Sebagaimana praktik di Indonesia di mana ada perumahan sipil di kawasan komplek militer, bandara sipil menyatu dengan pangakalan udara militer, dan lain sebagainya yang merupakan hal yang sudah umum di mana objek sipil dan objek militer berdekatan dan bersatu. Jika dinilai, objek-objek tersebut memberikan kontribusi yang berarti bagi militer. Berdasarkan asas kepentingan militer yang berlaku pada saat perang, objek-objek tersebut dibenarkan untuk dijadikan sasaran perang.36
Hal yang akan menjadi permasalahan adalah jika Indonesia belum melaksanakan prinsip pembedaan itu, apabila terjadi perang atau konflik bersenjata, maka bisa jadi objek-objek sipil yang berada dekat objek militer akan terkena dampak serangan oleh musuh. Implikasinya adalah semakin banyak korban dan kerugian yang tidak bisa diperhitungkan nantinya. Jika kondisi ini terjadi, musuh tidak bisa secara mutlak untuk disalahkan dan Indonesia sebagai negara bertanggung jawab atas hal ini.
-
4. Kesimpulan
Penerapan distinction principle dalam hukum humaniter internasional belum sepenuhnya dilaksanakan Indonesia dalam perundang-undangan nasional. Adapun secara praktik masih terdapat banyaknya objek-objek sipil dan objek militer yang belum dipisahkan walaupun adanya keterikatan Indonesia dengan Konvensi Jenewa 1949. Meskipun saat ini tidak terjadi perang atau konflik bersenjata, pemisahan objek sipil dan militer di Indonesia seyogyanya perlu dilaksanakan pada masa damai sebagai upaya pencegahan untuk perlindungan penduduk sipil bila terjadi perang atau konflik bersenjata dimasa mendatang. Sebagai Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949, sudah seharusnya Indonesia menghormati prinsip-prinsip didalam hukum humaniter internasional dan melaksanakan implementasi khususnya mengatur lebih lanjut terkait pemisahan objek sipil dan militer.
Daftar Pustaka
Buku
Brownlie, I., & Brownlie, I. (Eds.). (1972). Basic documents in international law. Oxford: Clarendon Press.
Duffy, H. (2015). The ‘War on Terror’ and The Framework of International Law. United Kingdom: Cambridge University Press.
Effendi, M. (2007). HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, dan Politik & proses penyusunan/aplikasi HA-KHAM (hukum hak asasi manusia dalam masyarakat). Bogor: Ghalia Indonesia.
Jacques, M. (2012). Armed Conflict and Displacement: The Protection of Refugees and Displaced Persond Under International Humanitarian Law. United Kingdom: Cambridge University Press.
Haryomataram, K. (2005). Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
ICRC. (2008). Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan Anda. Jakarta: Delegasi Regional ICRC untuk Indonesia & Timor Leste.
Istanto, S. (1992). Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional. Yogyakarta: Andi Offset.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Pratomo, E. (2016). Hukum Perjanjian Internasional: Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Shaw, M. N. (2008). International Law. New York: Cambridge University Press.
Sujatmoko, A. (2016). Hukum HAM dan Hukum Humaniter. Jakarta: Rajawali Pers.
Sunyowati, D., Narwati, E., & Hastuti, L. (2011). Buku Ajar Hukum Internasional.
Surabaya: Airlangga University Press.
Jurnal
Abtahi, H. (2001). The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict: The Practice of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia. Harvard Human Rights Journal, 14: 1-32.
Adwani. (2012). Perlindungan Terhadap Orang-Orang dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Dinamika Hukum. 12(1): 97-107. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.109
Danial. (2013). Eksistensi Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional Sebagai Upaya Perlindungan Korban Konflik Bersenjata. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, 21(1): 13-28.
Finkelstein, D. M. (2007). China's National Military Strategy: An Overview of the" Military Strategic Guidelines". Asia Policy, 4(1), 67-72.Finkelstein, D. M. (2007). China’s National Military Strategy: An Overview of the Military Strategic Guidelines. Asia Policy, 4: 99-144.
Hastuti, L. (2012). Wajib Bela Negara dan Prinsip Pembedaan Dalam Hukum Humaniter Internasional (Kajian Pasal 30 UUD 1945). YURIDIKA, 23(1), 1-21.
Heller, K. J. (2015). Disguising a Military Object as a Civilian Object: Prohibited Perfidy or Permissible Ruse of War?. International Law Studies, 91, 517-539.
Indrawan, J. (2018). Status Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (Private Military and Security Companies) dalam Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Pertahanan & Bela Negara, 4(1), 115-136.
http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v4i1.325
Ismail, I. (2013). Penerapan Konvensi Jenewa 1949 Dan Protokol Tambahan 1977 Dalam Hukum Nasional Indonesia (Studi Tentang Urgensi dan Prosedur Ratifikasi Protokol Tambahan 1977). Jurnal Dinamika Hukum, 13(3): 367-378. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.243
Plaw, A. (2010). Upholding the Principle of Distinction in Counter-Terrorist Operations: A Dialogue. Journal of Military Ethics, 9(1): 3-22.
Soniardhi. (2017). Kewenangan ANKUM Terhadap Tawanan Perang Dalam Hukum Disiplin Militer. Jurnal Magister Hukum Udayana, 6(4): 464-477.
https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p05
Saefulah, T. (2002). Hubungan Antara Yurisdiksi Dengan Kewajiban Negara
Berdasarkan Prinsip Aut Dedere Aut Judicare dalam Tindak Pidana
penerbangan dan Implementasinya di Indonesia. Jurnal Hukum Internasional FH Universitas Padjajaran, 1(1): 42.
Yuliantiningsih, A. (2009). Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Dinamika Hukum, 9(2), 110-118.
http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.219
Tesis/Disertasi
Stefanik, K. M. (2019). Improving Civilian Protection during War through Conflict-Specific Behavioural Regulation of Combatants. The University of Western Ontario: 1-403.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169).
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956)
Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Orang Sipil Pada Masa Perang
Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang Perlindungan Terhadap Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional
Website
Anonim, “Indonesia Berniat Ratifikasi Protokol Konvensi Jenewa 1949”, Available from http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17528/indonesia-
berniat-ratifikasi-protokol-konvensi-jenewa-1949 .
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Program Legislasi Nasional.
Available from http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas .
ICRC. State Parties to the Following International Humanitarian Law and Other Related
Treaties as of 28-Jan-2020. Available from https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/ .
463
Discussion and feedback