Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh
on
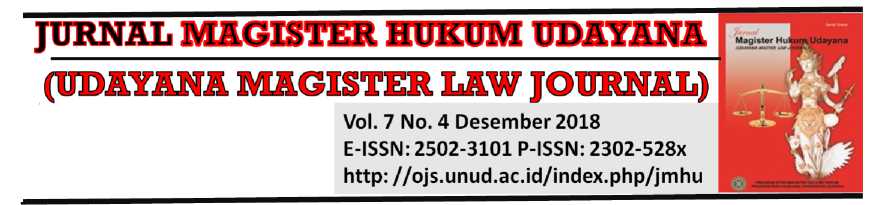
Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh
Muhammad Natsir1, Andi Rachmad2
1Fakultas Hukum, Universitas Samudra-Langsa, Email: munatsir_1966@unsam.ac.id
2Fakultas Hukum, Universitas Samudra-Langsa, Email: andrapunge@gmail.com
Info Artikel
Masuk: 8 Oktober 2018
Diterima: 17 Desember 2018
Terbit: 31 Desember 2018
Keywords:
Adoption; Criminal Policy; Local
Wisdom; Aceh
Kata kunci:
Adopsi; Kebijakan Pidana;
Kearifan Lokal; Aceh.
Corresponding Author:
Muhammad Natsir, E-mail:
DOI:
10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p
05
Abstract
Aceh is a special autonomous region that was established based on Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. Based on the regulation, Aceh was given specialization in the implementation of Islamic shari'a. One of them is environmental management as stipulated in Aceh Qanun Number 2 of 2011 concerning Environmental Management (PLH). The principle of environmental management in Aceh is specifically based on local wisdom, including in the implementation of a settlement of environmental crime. In the Islamic Shari'a, there are several methods for resolving criminal cases, namely diyat, sayam and suloh (peace). The purpose of this study was to explain the criminal law policy adopted in the PLH Qanun. The next objective of this research was that the Qanun for environmental management could adopt adopting the principles of local wisdom in Aceh. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study that the PLH Qanun made local wisdom a part of the substance of the Qanun. Local wisdom that must be adopted is diyat or dheit and sayam and Suloh (peace) as a dispute resolution technique that can be considered in resolving environmental disputes in Aceh Abstrak
Aceh adalah daerah otonomi khusus yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan regulasi tersebut, Aceh diberikan kekhususan dalam pelaksanaan syari’at Islam. Salah satunya adalah pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). Asas pengelolaan lingkungan hidup di Aceh dikhususkan berbasis kearifan lokal, termasuk dalam penerapan penyelesaian tindak pidana lingkungan. Dalam syari’at Islam dikenal beberapa metode penyelesaian perkara pidana yaitu diyat, sayam dan suloh (perdamaian). Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai kebijakan hukum pidana yang dianut di dalam Qanun PLH Tujuan selanjutnya penelitian ini adalah agar Qanun pengelolaan lingkungan hidup dapat mengadopsi mengadopsi asas kearifan lokal di Aceh. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil
penelitian bahwa Qanun PLH menjadikan kearifan lokal sebagai bagian dari substansi Qanun tersebut. Kearifan lokal yang harus diadopsi adalah diyat atau dheit dan sayam serta Suloh (perdamaian) sebagai teknik penyelesaian sengketa yang dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Aceh.
-
1. Pendahuluan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana disebutkan oleh Faisal Nasution: “Dengan dianutnya sistem desentralisasi yang selanjutnya melahirkan asas otonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, maka setiap pemerintahan daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan-urusan pemerintahan yang menjadi otonomi daerahnya.” 1 Provinsi Aceh memiliki kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam bingkai NKRI berdasarkan UUD 1945. 2 Mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie, bahwa pemberlakuan Qanun3. dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan Otonomi Khusus bagi Propinsi Aceh dapat menyampingkan peraturan perundang undangan lainnya yang lebih tinggi, yang dalam keadaan biasa tidak dapat disingkirkan oleh peraturan daerah. Akan tetapi, sebagai konsekuensi diberikan otonomi khusus bagi daerah tertentu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, mencakup segala segi, sehingga setiap daerah dapat menuntut suatu kekhususan, semata-mata berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa suatu kriteria umum yang ditetapkan dalam Undang-undang.4
Dalam perkembangannya, setiap aktivitas lingkungan, pada umumnya memiliki kemungkinan terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami, sehingga mutu kualitas lingkungan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.5
Maka setiap aktivitas dalam pembangunan yang bersentuhan dengan lingkungan hidup, memerlukan suatu standar mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML). Baku Mutu Lingkungan diatur dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan demikian, Baku Mutu Lingkungan merupakan instrumen yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya aktivitas atau kegiatan produksi yang tidak sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan yang ada, berarti telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Pada tingkat tertentu, jika terjadi pencemaran lingkungan, maka hal tersebut dapat diklarifikasikan sebagai suatu tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Hal ini dapat diproses secara hukum ke pengadilan. Adanya keinginan masyarakat melalui LSM lingkungan atau perorangan yang diinformasikan melalui media masa untuk membawa pelaku tindak kejahatan lingkungan ke pengadilan, makin memberi alasan agar pelaku tindak kejahatan terhadap lingkungan harus dibuat jera, agar diproses menurut ketentuan hukum yang ada.6
Undang-undang ini mengatur adanya penguatan mengenai prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.
Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan delik materil. Menurut Sukanda Husin menyebutkan delik materil dan delik formil dapat didefinisikan sebagai berikut:
-
a. Delik materil (generic crime) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
-
b. Delik formil (specific crime) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.7
Setiap peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di Aceh harus diqanunkan disesuaikan dengan jiwa dan semangat UUPA sebagaimana kajian ini adalah untuk menjalankan UUPPLH lahirlah Qanun No 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan lingkungan hidup (selanjutnya disebut Qanun PLH) diantara asasnya adalah kearifan lokal. Namun berdasarkan hasil penelitian Qanun PLH belum mengadopsi asas kearifan lokal sebagaimana ketentuan Pasal 69 ayat (1) huruf h dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-
masing8 sebagai bagian dari Qanun tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas yang menjadi permasalahan adalah: 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam Qanun PLH? 2) bagaimana mengadopsi asas kearifan lokal dalam Qanun pengelolaan lingkungan hidup.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai kebijakan hukum pidana yang dianut di dalam Qanun PLH. Tujuan selanjutnya penelitian ini adalah agar Qanun pengelolaan lingkungan hidup dapat mengadopsi asas kearifan lokal di Aceh.
-
2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai norma9 dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta doktrinal, bahan hukum yang dipergunakan adalah sebagai bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, KUHP, Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampong, Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang kehidupan adat dan adat istiadat, Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, disertasi, jurnal terkait dengan penelitian. Bahan hukum tersier terdiri dari Ensiklopedi hukum pidana Islam, kamus hukum. Keseluruhan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan permasalahan penelitian kemudian dikaji secara mendalam untuk menggambarkan kebijakan hukum serta hukuman berkenaan dengan pidana dalam Qanun PLH.
Substansi hukum nasional yang meliputi nilai-nilai dasar yang bersumber dari pembukaan UUD 1945, yaitu hukum berwatak mengayomi/melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, bersifat kerakyatan, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan yang maha Esa sebagai dasar pengakuan terhadap adanya hukum Tuhan, hal ini merupakan pegangan konkrit dalam membuat ketentuan hukum, tidak dibenarkan pengingkaran terhadap Tuhan, Indonesia tidak dibentuk berdasarkan perjanjian tetapi atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa sebagaimana tersimpul dalam Pancasila yang mengandung nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat10 sebagai cerminan hukum yang baik,11baik hukum pidana, perdata maupun hukum administrasi.
Menyangkut ketentuan pidana dijelaskan dalam Qanun PLH Bab. XVIII bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan perusakan lingkungan atau karena kelalaiannya, diancam pidana dan denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta pemulihan kembali lingkungan hidup, sedangkan denda merupakan pendapatan Aceh atau pendapatan Kabupaten/Kota dan harus disetor ke kas umum Aceh atau kabupaten/Kota.12
Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang tercantum dalam Qanun PLH, bermakna sanksi pidana merujuk kepada Undang-undang, dalam hal ini UUPPLH yang menganut prinsip dalam pemidanaan adalah ultimum remedium merupakan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir,13di mana keberadaan asas tersebut dalam sistem hukum lingkungan khususnya acara pidana merupakan aturan khusus karena menyimpang dari ketentuan hukum acara umum KUHAP,14 yaitu sebelum menerapkan pidana pada delik formal harus ditegakkan terlebih dahulu penegakan hukum administrasi,15 ketika hukum administrasi sudah dinyatakan tidak efektif atau gagal, barulah hukum pidana dilanjutkan, timbul persoalan baru dalam tataran aplikatif, yaitu instansi mana yang berwenang menyatakan penegakan hukum administrasi tidak efektif atau gagal. 16 Kelemahan tersebut berpengaruh kepada penetapan hukuman dalam Qanun PLH Provinsi Aceh yang tidak berani tampil beda dari KUHP yang belumlah mencapai salah satu tujuan hukum yaitu keadilan, khususnya keadilan bagi korban17 menuju tatanan hukum sesuai dengan kearifan lokal.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup
lain.18 Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.19
Dalam Qanun ini juga membahas tentang jasa lingkungan yang merupakan imbalan yang dilakukan/diberikan oleh orang, masyarakat, dan/atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup, yaitu pemerintah,20 walaupun jasa lingkungan yang didapati di atas tanah hak milik masyarakat juga akan beralih dengan jalan ganti kerugian sehingga masyarakat melepaskan hak miliknya dengan dalih kepentingan pemerintah atau pengembang lainnya. Prinsip ini bertentangan dengan etika hukum nasional berkenaan dengan memelihara keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan.
Apabila diperhatikan Qanun PLH telah mempertimbangkan etika hukum tersebut dengan mengatur UKL-UPL, terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang merupakan persyaratan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, sehingga dapat dikeluarkan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, yang diterbitkan oleh instansi terkait. Keizinan yang dikeluarkan harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. 21 Namun realita substansinya tidak mengakomodir secara nyata dalam tatanan kepidanaan kepentingan perorangan.
Pengelolaan lingkungan hidup wajib memperhatikan hak-hak masyarakat untuk kesejahteraan rakyat Aceh meliputi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), rencana tata ruang wilayah Aceh, pengurangan resiko bencana, sumberdaya alam hayati, sumberdaya alam nonhayati, sumberdaya buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, cagar budaya, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan limbah dan pengelolaan sampah, 22 serta wajib menyediakan dana jaminan pengelolaan lingkungan hidup.23Namun dalam pasal yang lain menegaskan pengelolaan lingkungan hidup yang pemanfaatannya dilakukan secara sektoral diatur dengan Qanun tersendiri,24 hal ini menunjukkan Qanun PLH merupakan peraturan yang masih global dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup sehingga memerlukan kepada Qanun-Qanun lain untuk mengelola lingkungan hidup dan Qanun PLH kurang jelas peruntukannya.
Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan pola kemitraan antara pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku
kepentingan lainnya, walaupun pola kemitraan diatur dalam peraturan gubernur 25 sampai saat ini belum ada, namun dapat dipahami bahwa pengelolaan lingkungan hidup akan dilaksanakan secara bersama antara pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, hal ini akan menjadi kendala ketika penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran lingkungan hidup, walaupun badan lingkungan hidup, selanjutnya disingkat BLH mempunyai kewajiban untuk melakukan pemantauan secara periodik terhadap usaha/kegiatan yang berdampak lingkungan,26sedangkan BLH juga sebagai pengelola usaha lingkungan hidup. Qanun PLH memberikan insentif kepada setiap orang yang dinyatakan berhasil melakukan pengelolaan lingkungan hidup, walaupun ketentuannya masih menunggu peraturan gubernur.27
Tahapan proses penerapan hukuman bagi pelanggar izin lingkungan dimulai dari sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, sanksi administrasi terdiri atas teguran lisan, peringatan tertulis, paksaan pemerintah, pembekukan izin operasi, dan pencabutan izin lingkungan dan/atau izin usaha.28
Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu yang merupakan kaedah sebagaimana tersebut di atas. Adapun prinsip-prinsip yang dapat dijadikan landasan/kaedah pembentukan peraturan perundang-undangan tingkat daerah adalah landasan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis sebagai berikut :
-
a. Landasan Yuridis
Setiap produk hukum, haruslah mempunyai dasar berlaku secara yuridis (juridische gelding). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk perda ataupun Qanun. Adanya kesesuaian bentuk atau jenis produk hukum dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau dapat dibatalkan (vernietihbaar) produk hukum tersebut. Misalnya Qanun PLH lahir karena perintah UUPA Tahun 2006. Mengikuti tata cara tertentu, apabila tata cara tertentu yang diharuskan tidak diikuti, maka produk-produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dibatalkan demi hukum, setiap Qanun untuk berlakunya dan mempunyai kekuatan mengikat harus diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah. Qanun PLH disahkan di Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2011 dan diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2011, Lembaran daerah Aceh tahun 2011 Nomor 07.
-
b. Landasan sosiologis
Sosiologis mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, serta sesuai dengan kondisi sosial di mana hukum itu diterapkan. 29 Dalam suatu masyarakat agraris dan agamis, hukumnya harus sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat agraris dan agamis tersebut. 30 Qanun PLH belum sepenuhnya melaksanakan ide-ide tersebut walaupun dalam tatanan asasnya telah ada namun dalam substansi pengaturannya belum diadopsinya.
-
c. Landasan filosofis
Filosofis berkaitan dengan “cita hukum” yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan perlindungan. Cita hukum tersebut tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik atau buruk, pandangan terhadap hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan dan sebagainya. Semuanya itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Nilai-nilai ini ada yang dibiarkan dalam masyarakat, sehingga setiap pembentukan hukum atau peraturan perundang undangan harus dapat menangkapnya setiap kali akan membentuk hukum atau peraturan perundang undangan. Merujuk ke landasan sosiologis di atas perlu ada harmonisasi/sinkronisasi/konsentrasi antara aspirasi sosio filosofis dan sosiokultural yang ada dalam masyarakat, juga mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku secara nasional yaitu nilai yang terkandung dalam Pancasila.31
Paling sedikit ada dua sila yang berkaitan erat dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada umumnya. Pertama, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Sila kedua Pancasila ini mendukung terwujudnya konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup (sustainable development), yang hendak mencapai tujuan pembangunan tidak saja untuk manusia yang hidup sekarang ini, tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Kedua, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila ini memuat tujuan idiil negara untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam konteks perdagangan karbon/REDD, keadilan sosial demikian dapat diwujudkan melalui, antara lain, pengaturan yang mencerminkan adanya keadilan dalam distribusi hasil penjualan karbon tersebut, yang peruntukannya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, terutama kepada mereka yang kehidupan pencahariannya selama ini tergantung pada hutan tersebut, baik di KEL maupun KEUM, Provinsi Aceh.32
Landasan formil konstitusional merupakan landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum kewenangan membentuk peraturan perundang undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam peraturan perundangan sebagai landasan yuridis formal, suatu lembaga/badan
adalah tidak berwenang mengeluarkan peraturan. Dalam hal ini, sebagaimana Qanun PLH di Aceh telah melalui landasan formil pembentukan peraturan perundang-undangan namun belum menyentuh landasan kearifan lokal.
Dalam landasan yuridis formal selain menetapkan lembaga/badan yang berwenang membentuk, juga secara garis besar ditetapkan proses dan prosedur penetapannya oleh Kepala Daerah dalam hal ini gubernur, setelah mendapat persetujuan bersama DPRD khusus di Provinsi Aceh dikenal dengan singkatan DPRA dan DPRK.
Secara formil Qanun PLH sesuai dengan kearifan lokal di Aceh mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2011. Qanun ini secara vertikal berkaitan dengan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945, serta sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA Tahun 2006 Pasal 148, 149, dan 150.
Dalam rangka memenuhi hak masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam UUPA Tahun 2006 maka pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur lingkungan yang baik dan sehat bagi warga negara, serta terlindungi hak haknya dari rekayasa lingkungan yang baik, bernilai ekonomi dan sehat berasaskan keislaman, kearifan lokal, tanggung jawab, kelestarian, keberlanjutan, berkeadilan, keterpaduan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan kemanfaatan.
Sesuai amanat UUPA Tahun 2006 setiap peraturan daerah di Aceh harus sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA Tahun 2006 yaitu pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di setiap pengaturan kehidupan termasuk dalam hal pengaturan lingkungan hidup. Karena itu, untuk melaksanakan UUPPLH, lahirnya Qanun PLH, sebagai payung hukum pengelolaan lingkungan hidup sesuai kearifan lokal secara Islami yang dapat memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat terutama yang terkena imbas dari rekayasa lingkungan hidup. Secara horizontal, Qanun PLH, ini berkaitan dengan Undang-undang lain dalam pelaksanaannya dan menjadi landasan formil konstitusionalnya yaitu 1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. 2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang. 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan landasan formil konstitusional tersebut, bahwa Qanun PLH secara yuridis belum mempunyai payung hukum yang kuat. Asas pengelolaan lingkungan hidup sebagai mana Pasal 2 huruf a, “kearifan lokal,” namun tidak menjadikan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, dan Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. 33 Kemudian mengenai wewenang yang
diberikan Undang-undang untuk Aceh dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana Pasal 1 Undang-undang No. 24 tahun 1956 menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat ataupun “kearifan lokal” sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan pasal 1 huruf (h) Undang-undang No. 22 tahun 1999 jo pasal 1 angka (7) Undang-undang No. 44 tahun 1999).
Qanun PLH secara materiil berkenaan dengan revitalisasi asas kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup juga termasuk ketentuan umum dan tujuan, landasan materiil konstitusional peraturan perundang undangan Qanun PLH adalah a) melindungi wilayah Aceh dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, b) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, c) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, d) menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, e) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, g) menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, i) mewujudkan pembangunan berkelanjutan, j) mengurangi risiko bencana, k) mengantisipasi isu lingkungan hidup global dan l) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam sebagai sumber ekonomi.
Asas Pengelolaan lingkungan hidup di Aceh adalah asas keislaman, kearifan lokal, tanggung jawab, kelestarian, berkelanjutan, berkeadilan, keterbukaan, keterpaduan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan kemanfaatan. Asas-asas yang ada mencerminkan landasan dan paradigma kebijakan yang harus dipertimbangkan dalam pengaturan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana dalam kajian ini adalah “Asas kearifan lokal” berarti menjadikan gagasan-gagasan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh masyarakat34 sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun Qanun PLH tetapi asas ini diabaikan 35dalam substansi penyusunan Qanun PLH. Seharusnya Qanun PLH harus mengangkat hukum setempat sebagai “the living law” menjadi hukum positif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh. Hal ini dapat dibuktikan, bahwa dalam pengaturan sanksi dalam Qanun PLH hanya mengadopsi sanski yang diatur di dalam UUPPLH, yaitu penjara, denda, dan sanksi yang bersifat administratif.
Tujuan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya adalah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.36
Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersangkutan, apabila telah dipilih penyelesaian di luar pengadilan, namun tidak mencapai kesepakatan, maka dapat dilakukan gugatan melalui pengadilan. 37 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana yang telah diatur dalam Qanun PLH, karena tujuan penyelesaian di luar pengadilan hanya untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup. Dalam penyelesaian di luar pengadilan para pihak dapat menggunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak untuk membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup.38
Penyelesaian perkara di dalam peradilan adat di Gampong dilaksanakan perangkat gampong adapun susunan perangkat tim peradilan secara adat di Gampong adalah oleh tokoh-tokoh adat yang terdiri atas: Keuchik; imeum meunasah; tuha peut; sekretaris gampong; dan ulama, cendekiawan dan tokoh adat lainnya di gampong atau nama lain yang bersangkutan, sesuai dengan kebutuhan.39
Pada umumnya penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat dilakukan oleh Lembaga yang disebut Gampong dan Mukim. Hal yang sama berlaku untuk seluruh Aceh. Hanya saja, di beberapa daerah tertentu, seperti Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, mereka menggunakan istilah lain. Namun, fungsinya tetap yang sama, yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau perkara adat.40
Prinsip penyelesaian tindak pidana dalam UUPPLH adalah ultimum remedium, 41 sebagaimana Pasal 85 ayat (2) menyangkut penyelesaian sengketa lingkungan hidup menyatakan “penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.” Prinsip ini yang menjadi salah satu landasan penyusunan Qanun PLH, sedangkan lahirnya Qanun PLH merupakan perintah UUPA Tahun 2006 sebagaimana Pasal 148, 149 dan 150. dari segi asas antara UUPPLH dengan UUPA Tahun 2006 sedikit berbeda.
Dalam bab penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat diperhatikan lebih mengarah kepada penyelesaian sengketa sistem hukum perdata, dimana respon pihak penegak hukum apabila telah ada pengaduan dari masyarakat, sedangkan pengaduan sampai ke penyelesaian membutuh waktu panjang, apalagi melalui lembaga tertentu yang memerlukan biaya yang tidak mungkin ringan bagi masyarakat yang terkena imbas perusakan lingkungan hidup. Pola penyelesaian tersebut bertentangan dengan asas kearifan lokal di Aceh dimana dalam menangani sengketa tidak memisahkan antara kasus pidana, perdata dan administrasi,
Berdasarkan uraian di atas bahwa Qanun PLH belum sepenuhnya mengadopsi asas kearifan lokal secara substansi tentang ketentuan hukuman atau ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 46, 47, 48 dan Pasal 49, ancaman pidananya sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu merujuk ke UUPPLH dengan hukuman penjara dan/atau denda.
Selain itu Qanun PLH yang dibuat pada masa pasca konflik lebih banyak mengandung unsur politisnya daripada kebijakan hukum pidana, dan ini perlu dilakukan rekonstruksi terutama perhatian kepada korban tindak pidana lingkungan hidup dengan menjadikan ganti kerugian sebagai kebijakan umum pimidanaan, agar tercapai keadilan yang responsif guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Qanun PLH yang diharapkan dapat berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan sesuai dengan harapan dunia Internasional,42sesuai juga dengan perintah UUPA, namun hal ini belum terwujud ataupun Qanun PLH kurang mengacu kepada harapan tersebut, sehingga Qanun tersebut tidak diikuti oleh masyarakat maupun penegak hukum, sesuai dengan pepatah Aceh yang disebut dengan hadih maja, yaitu “hukom meunyo hana adat tabeue, adat menyo hana hukom bateue”43 ( hukum kalau tidak ada adat hampar tidak bermakna, kalau adat saja tidak ada hukum batal tidak punya kekuatan), sehingga memerlukan pembaharuan substansi sesuai dengan hukum yang dicita-citakan oleh masyarakat.
Masyarakat Aceh terkenal dengan ketaatan religiusnya memiliki budaya yang identik dengan Islam. Masyarakat Aceh memiliki suatu budaya yang mengutamakan penyelesaian sengketa apa saja melalui perdamaian sehingga ada ungkapan “ yang rayeuk tapeubit, yang ubit tapeugadoh,” maksudnya bahwa persoalan yang besar dikecilkan, yang kecil dihilangkan.” Ungkapan lain yang menggambarkan masyarakat Aceh cinta perdamaian yaitu “ menyo tatem tamogot-got, harta bansot syedara pihna, maksudnya bila mau berbaik-baik harta tidak habis persaudaraan tetap terpelihara.44 Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dalam perspektif Islam dilakukan dengan pola perdamaian (shulhu), pola ini sangat fleksibel dan menjadi sarana dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia secara menyeluruh serta mendatangkan manfaat dan tidak terputus silaturrahmi, apabila tercapai perdamaian antara pihak yang bersengketa.
Menarik untuk dipaparkan bahwa hampir semua konflik vertikal dan horizontal yang terjadi di Aceh semua diselesaikan melalui proses damai. Sebagaimana bukti yaitu pada masa perjuangan DI/TII Teungku Daud Beureueh diselesaikan dengan damai yang dikenal pada masa itu yaitu Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Puncak penyelesaian adat dengan damai dilaksanakan pada tanggal 18-21 Desember 1962 di
Blang Padang Banda Aceh.45 Setelah itu juga dapat dilihat dalam peristiwa perang cumbok antara kaum ulama dengan ulee balang yang berakhir dengan damai dan dikenal dengan ikrar lamteh tahun 1946. Terakhir, terkait konflik di Aceh melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berakhir selama 30 tahun melawan pemerintah Indonesia dan diselesaikan dengan MoU Helsinki pada tahun 2005.46
Mengenai sengketa lingkungan yang diselesaikan secara perdamaian, yaitu yang terjadi di Kabupaten Aceh Timur antara PT Ensem Sawita dengan warga yang bertempat tinggal di sekitar PT. Dalam hal ini, PT Ensem Sawita mengabulkan permintaan ganti rugi warga karena telah mengakibatkan polusi udara serta limbah.. Ganti rugi yang diberikan kepada warga berupa PT Ensem Sawita melakukan penghijauan atau reboisasi, atau meninggikan cerobong asap, memberikan bantuan untuk Posyandu sebesar Rp 300.000 setiap bulan yang diberikan melalui geuchik, serta pemberian satu kaleng susu cair per jiwa atau uang senilai Rp 100.000/KK mulai dari Januari sampai Februari 2016. 47 Dalam kasus ini, penulis menjelaskan bahwa pemberian ganti rugi yang diberikan PT Ensem Sawita kepada warga adalah merupakan bentuk sayam atau diyat. Hal ini berarti sayam atau diyat yang dilakukan oleh PT Ensem Sawita dapat diterapkan dalam kasus-kasus lingkungan lainnya.
Konsep penyelesaian secara damai apabila dirujuk kepada Qanun Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 13 huruf p bahwa wewenang lembaga adat pencemaran lingkungan skala ringan sehingga dapat dikatakan bahwa wewenang peradilan berkenaan dengan pencemaran lingkungan skala kecil. Apabila pencemaran yang berdampak besar dan destruktif akan diselesaikan melalui peradilan Negeri namun apabila dilihat dari penyelesaian perdamaian yang telah dilaksanakan secara umum menyangkut permasalahan besar maka tidak tertutup kemungkinan penyelesaian pencemaran yang berdampak besar dan destruktif dengan konsep kearifan lokal yang telah terlebih dahulu berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan sebelum gerakan-gerakan peduli lingkungan bermunculan.48
Berkenaan dengan kearifan lokal, dalam Qanun bahwa kearifan lokal tidak diimplementasikan di dalam Qanun PLH. Hal ini dibuktikan bahwa di dalam Pasal 46 Qanun PLH, ketentuan pidana yang diatur hanya pidana dan denda sesuai dengan UUPPLH.
Secara filosofis kultur hukum yang sudah disepakati dan sudah dicatat dalam lembaran daerah yaitu Qanun PLH tepatnya pada poin “menimbang” poin b) bahwa lingkungan hidup merupakan anugerah Allah Yang Maha Kuasa dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan, oleh karena itu perlu dikelola secara adil, bijaksana, dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestarian fungsinya, c) Pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana dengan memperhitungkan kebutuhan
generasi masa kini dan masa mendatang sehingga tetap mampu menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, d) bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA, di antaranya sebagaimana tercantum dalam Pasal 148 ayat (1) Pemerintah, pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi serta menegakkan hak masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup dengan memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan. (2) Masyarakat berhak untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan berdasarkan keislaman dan kearifan lokal.
Aceh merupakan daerah provinsi yang masyarakat hukumnya bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. Pelaksanaan hukum adat istiadat di Provinsi Aceh secara yuridis berdasarkan Undang-undang No. 44 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi daerah istimewa Aceh dan Undang-undang No. 18 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang telah diganti dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (LN 2006 No. 62, TLN 4633).
Pasal 1 ayat (8) UUPA, 2006, disebutkan pengertian Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang di wilayah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintahan Aceh diberikan kekuasaan dan wewenang yang lebih dari daerah lain di Indonesia untuk membuat peraturan daerah yang disebut dengan Qanun sesuai dengan syariat Islam sebagai kearifan lokal masyarakat Aceh untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan diberikan kebebasan membuat Qanun sebagai pelaksanaan dari UUPA Tahun 2006. Qanun merupakan peraturan setingkat dengan Peraturan daerah yang khusus dibuat sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam setiap pengaturan hukum, dan hal-hal yang menyangkut dengan kewenangan pemerintah yang diatur dalam undang-undang otonomi khusus ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sebagaimana wewenang mengatur peraturan juga berwenang mengatur sanksi, sanksi yang diharapkan sesuai dengan asas pengaturan hukum di Aceh yaitu kearifan lokal, keislaman serta adat istiadat Aceh. Sebagai revitalisasi kearifan lokal masyarakat Aceh dengan menjadikan sistem suloh sebagai teknik penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang diatur dalam Qanun PLH.
Kata suloh berasal dari kalimat Arab as Sulhu yang berarti perdamaian, maksudnya upaya perdamaian antara para pihak yang bersengketa, dalam masyarakat Aceh suloh lebih diarahkan pada kasus perdata, menurut Abidin Nurdin kasus yang diselesaikan dengan suloh berkenaan dengan perebutan sentra-sentra ekonomi seperti batas tanah, tali air, daerah aliran sungai tempat menangkap ikan.49Apabila dicermati lebih jauh
bahwa suloh tidak hanya terbatas pada kasus perdata saja tetapi juga kasus pidana karena suloh merupakan cara penyelesaian berdasarkan kearifan lokal masyarakat aceh, kearifan lokal masyarakat Aceh identik dengan Islam dan hukum Islam, hukum Islam tidak memisahkan secara tajam antara pidana perdata maupun administrasi, dapat dilihat beberapa penyelesaian dengan suloh berdasarkan kearifan lokal menyangkut dengan kasus pidana Perjuangan DI/TII Teungku Daud Beureueh diselesaikan secara damai dikenal dengan nama Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh, puncak penyelesaian dilaksanakan pada tanggal 18–21 Desember 1962 di Blang Padang, Banda Aceh. Perang Cumbok antara kaum ulama dengan uleebalang
(aristokrasi) diselesaikan dengan damai yang dikenal dengan ikrar lamteh, 1946. Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang berjuang selama 30 tahun lebih melawan pemerintah Jakarta berakhir dengan perdamain MoU Helsinki, 2005. Konflik antara pelajar dan mahasiswa Aceh Tengah dan Aceh Selatan juga berakhir dengan perdamaian di Stadion Harapan Bangsa, 2013.50
Hukuman bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan adalah qishash dan diyat merupakan hukuman pokok dari hukum pidana Islam yang merupakan harta yang wajib diserahkan kepada korban atau kepada walinya. 51 Harta yang diserahkan merupakan ganti rugi akibat pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan kemaafan dari keluarga korban atau pembunuh yang tidak sengaja atau pembunuh yang tidak ada unsur membunuh dan wajib dibayar oleh pelaku kepada keluarga korban. Diat disebut juga ‘aql, karena seseorang yang telah membunuh akan mengumpulkan unta kemudian membawa ke rumah keluarga terbunuh dengan aqadnya, saya membayar diyat kepada di fulan”.52
Dasar hukum diyat adalah al-Qur-an Surah al-Baqarah ayat 178: “...diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh... kecuali yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,...hendaklah (yang diberi ma'af) membayar diyat kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik. yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Dalam hal terjadinya tindak pidana yang tidak memenuhi syarat untuk di qishash sebagaimana ayat tersebut ataupun terjadi kemaafan dari ahli waris maka akan beralih ke hukuman diyat dengan proses negosiasi, sedangkan bentuk diyat akan berpariasi sesuai dengan kebutuhan korban itu sendiri atau orang yang menjadi korban akibat terjadinya korban. Tercapainya negosiasi sehingga terjadi kemaafan dalam tindak pidana lingkungan hidup sangat diharapkan apalagi korbannya melebihi satu orang, akibat dari kemaafan maka timbul kewajiban lain bagi yang dimaafkan yaitu membayar diyat.
Dalam ayat 92 Surah an-Nisa’: “.....barang siapa membunuh mukmin karena tersalah hendaklah ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga kecuali keluarga bersadaqah. Jika terbunuh dari kaum yang memusuhi kamu padahal ia mukmin, maka diyatnya memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Apabila terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai
dengan kamu, maka pembunuh membayar diyat kepada keluarga si terbunuh serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa tidak memperoleh hamba sahaya maka hendaklah pembunuh berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Difahami dari ayat tersebut di atas bahwa hukuman diyat tidak ada perbedaan antara yang dibunuh itu muslim atau orang kafi zimmi atau kafir yang ada perjanjian damai, dalam membayar hukuman diyat dengan memerdekakan hamba, pada saat ini tidak ada lagi hamba sahaya maka digantikan dengan berpuasa dua bulan berturut-turut”.
Abdul Qadir Audah dalam kitabnya “al-Tasyri’ al-jina’i al-Islami,diyat “sebagai ganti kerugian yang diserahkan oleh seorang pelaku pidana terhadap korban atau ahli warisnya dalam tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan orang lain bukan kepada bendahara negara, dari sisi ini lebih mirip dengan ganti kerugian namun diyat lebih tepat diartikan sebagai gabungan antara hukuman dan ganti kerugian, dikatakan hukuman karena diyat ditetapkan sebagai balasan terhadap tindak pidana jika korban atau ahli warisnya mengampuni pelaku dapat dijatuhi hukuman takzir, dikatakan sebagai ganti kerugian karena diyat itu murni diterima oleh korban dan apabila korban merelakannya diyat itu tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku. 53 Takzir yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan hukum dari hakim.54Konsep diyat merupakan ajaran dasar Islam yang berasal dari al-Qur-an dan Hadis telah diadopsi oleh para ahli, agar dapat difahami dan dilaksanakan oleh masyarakat muslim dalam kehidupan sosialnya.
-
a. Diyat atau dhiet
Hukuman bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan adalah qishash dan diyat merupakan hukuman pokok dari hukum pidana Islam yang berupa harta yang wajib diserahkan kepada korban atau kepada walinya.55 Harta yang diserahkan merupakan ganti rugi akibat pembunuhan dan atau penganiayaan yang mendapatkan kemaafan dari keluarga korban atau pembunuh yang tidak sengaja atau pembunuh yang tidak ada unsur membunuh dan wajib dibayar oleh pelaku kepada keluarga korban, untuk mendapatkan kemaafan tentu terjadi negosiasi yang akhirnya mendapat kesepakatan tertentu. Diat disebut juga ‘aql, karena seseorang yang telah membunuh akan mengumpulkan unta kemudian membawa ke rumah keluarga terbunuh dengan aqadnya, saya membayar diyat kepada di fulan”.56
Al-Qur-an Surah al-Baqarah ayat 178: menjelaskan tentang diyat “...diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh... kecuali yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya,...hendaklah (yang diberi ma'af) membayar diyat kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik. yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Dalam hal terjadinya tindak pidana yang tidak memenuhi syarat untuk di qishash sebagaimana ayat tersebut ataupun terjadi kemaafan dari ahli waris maka akan beralih ke hukuman diyat dengan proses negosiasi, sedangkan bentuk diyat akan bervariasi sesuai dengan kebutuhan korban itu sendiri atau orang yang menjadi korban akibat terjadinya korban. Tercapainya negosiasi sehingga terjadi kemaafan dalam tindak pidana lingkungan hidup sangat
diharapkan, akibat dari kemaafan maka timbul kewajiban lain bagi yang dimaafkan yaitu membayar diyat , langkah-langkah yang ditempuh tentu melalui suloh.
Abdul Qadir Audah dalam kitabnya “al-Tasyri’ al-jina’i al-Islami,diyat “sebagai ganti kerugian yang diserahkan oleh seorang pelaku pidana terhadap korban atau ahli warisnya dalam tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap anggota badan orang lain bukan kepada bendahara negara, dari sisi ini lebih mirip dengan ganti kerugian namun diyat lebih tepat diartikan sebagai gabungan antara hukuman dan ganti kerugian, dikatakan hukuman karena diyat ditetapkan sebagai balasan terhadap tindak pidana jika korban atau ahli warisnya mengampuni pelaku dapat dijatuhi hukuman takzir, dikatakan sebagai ganti kerugian karena diyat itu murni diterima oleh korban dan apabila korban merelakanya diyat itu tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku.57 Konsep diyat merupakan ajaran dasar Islam yang berasal dari al-Qur-an dan Hadis telah diadopsi oleh para ahli, agar dapat difahami dan dilaksanakan oleh masyarakat muslim dalam kehidupan sosialnya adalah hukum adat Aceh dikenal dengan istilah dheit.
-
b. Sayam
Sayam adalah “bentuk kompensasi berupa harta yang diberikan kepada korban ataupun ahli warisnya dalam hal anggota badan rusak atau tidak berfungsi.” Apabila dilihat dari peruntukannya antara diyat dan sayam adanya perbedaan adalah diyat lebih cendrung kompensasi kepada korban jiwa, sedangkan sayam hukuman terhadap perusakan anggota badan atau tidak berfungsi akibat penganiayaan atau cara lain yang berakibatkan orang lain rusak anggota badan atau tidak berfungsi.
Pembayaran kompensasi sayam yang telah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Aceh adalah satu ekor kerbau atau sapi, satu ekor kambing dan sejumlah uang serta beberapa helai kain yang diserahkan kepada korban atau ahli warisnya, diperhitung menurut berat ringan kerusakan yang dialami korban. Suloh akan menghasilkan bermacam kemungkinan sesuai dengan kebutuhan serta derita korban diantaranya:
-
a. Alih tanggung jawab;
Alih tanggung jawab berbeda dengan teori pertanggungjawaban pidana pengganti dimana “suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain”, yang menjadi pengganti di sini adalah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan, atau kesalahan, atau perbuatan dan kesalahan orang lain, seperti majikan adalah pihak yang utama yang bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh di mana perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.58 Yang ingin dikembangkan dalam penelitian ini adalah “alih tanggung jawab” mencoba menggunakan teori tanggung jawab, Pada hakekatnya, teori tanggung jawab adalah, subjek hukum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang dapat membebaskannya.
Alih tanggung jawab yang dimaksudkan di sini adalah setiap orang ataupun korporasi yang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan hilang nyawa ataupun cacat seumur hidup, maka orang ataupun korporasi tersebut harus menanggung beban hidup keluarga sebagaimana beban korban ketika ia hidup atau sebelum ia cacat, jadi bebannya dialihkan kepada pelaku tindak pidana. Sebagai contoh sebuah perusahaan perkebunan di hulu setelah menebang pohon membersihkan lahan terjadi banjir bandang, beberapa orang meninggal dunia katakanlah kepala keluarga, maka perusahaan tersebut harus bertanggung jawab terhadap kelanjutan kehidupan keluarga tersebut pasca ditinggal mati oleh kepala keluarganya sesuai kebutuhan.59
-
b. Menyambung asa;
Menyambung asa atau menyambung harapan sama dengan alih tanggung jawab yang dimaksudkan di sini adalah setiap orang ataupun korporasi yang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan hilang nyawa ataupun cacat seumur hidup, maka orang ataupun korporasi tersebut harus menanggung beban hidup anak-anak yang ditinggali oleh orang tuanya, sedangkan anak-anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tuanya, jadi beban kasih sayang, penyapihannya dialihkan kepada pelaku tindak pidana.60
-
c. Pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu;
Pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu, 61 korban di sini bukanlah dalam bentuk fisik tetapi dalam bentuk materil seperti hancurnya tempat usaha ataupun lahan tempat melakukan rutinitas usaha sebagai contoh lahan pertanian yang ditutupi oleh sampah longsor akibat penebangan serta perambahan hutan untuk keperluan perusahaan tertentu hal ini masuk dalam katagori memelihara harta62;
-
d. pemberdayaan korban
Dalam Pengaturan hukum di Indonesia terkesan, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik, maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekontruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan hak istimewa kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban, walaupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi
dan korban telah diberlakukan. 63 Arief Gosita mengatakan korban tindak pidana kejahatan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari konsepsi korban tindak pidana kejahatan, korban tindak pidana kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.64
Selanjutnya Muladi mengatakan korban (victims) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.65
Pemberdayaan korban dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup bertujuan untuk mencari penyelesaian kasus secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan korban dan pelaku secara seimbang, tidak menimbulkan korban lebih lanjut, tidak terjadi pembalasan.66Menjadikan perlindungan korban sebagai salah satu tujuan pemidanaan memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat yang multi kultur.67
Pembayaran kompensasi ataupun bentuk lain dalam pencapaian melalui suloh diiringi dengan upacara adat pesijuk ( tepung tawar) serta peumat jaro (jabat tangan), hakikat dari upacara adat ini adalah untuk menjalin hubungan yang baik antara pihak pelaku pidana dengan korban, sehingga pemaafan yang tulus akan terbangun hubungan yang baik sehingga tidak ada dendam diantara mereka dan lebih jauh lagi akan menjadi saudara sebut atau anak sebut.68 Teknik penyelesaian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk penyelesaian bagi tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam Qanun PLH.
-
4. Kesimpulan
Qanun pengelola Lingkungan Hidup di Aceh merupakan peraturan pelaksana UUPA yang diantara asasnya keislaman dan kearifan lokal, namun substansi Qanun PLH belum menjadikan kearifan lokal sebagai bagian dari pengaturan Qanun tersebut. Kearifan lokal yang sangat penting untuk dimasukan dalam pengaturan Qanun PLH adalah diyat atau dheit dan sayam, teknik penyelesaian dengan menggunakan suloh oleh peradilan adat Aceh dan diakhiri dengan acara adat peusijuk dan peumat jaro.
Daftar Pustaka
Buku
Arief, B. N. (2005). Pembaharuan hukum pidana dalam perspektif kajian perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Audah, AQ. (tt.). Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Jld. III, Jakarta: Kharisma Ilmu.
Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Dualisme penelitian hukum normatif dan
empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Arif, G. (1985). Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan.Jakarta: Akademika Pressindo
Echols, J. M., & Sadily, H. (2000). Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. Ke XXIV.
Husin, S. (2009). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Machmud, S. (2012). Penegakan hukum lingkungan Indonesia: penegakan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana menurut Undang-Undang no. 32 tahun 2009. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Muhammad Natsir. (2018). Membangun Hukum Pidana Lingkungan Berbasis Syariah di Aceh. Yokyakarta: Deepublish.
Jurnal
Nurdin, A. (2017). Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat. ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, 13(1), 135154. http://dx.doi.org/10.42042/analisis.v13i1.645
Apryani, N. W. E. Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM: Studi tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(3), 359-374.
https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i03.p07
Baharudin, B. (2016). Desain Daerah Khusus/Istimewa dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi. Masalah-Masalah Hukum, 45(2), 85-92. https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.85-92
Surya, F. A. (2017). Tinjaun Mediasi Penal Dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. Jurnal Jurisprudence, 5(2), 118-126.
https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v5i2.4229
Ari Permadi, I. M. Kewenangan Badan Lingkungan Hidup Dalam Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Pencemaran Lingkungan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 5(4), 650-660.
https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p02
Jalil, H., Yani, T. A., & Yoesoef, M. D. (2010). Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 12(2), 206-234.
Kamarusdiana, K. (2016). Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 16(2), 151-162.
Mabrur, A., Muhammad, R. A., & Din, M. (2017). Konsepsi Pidana Hudud dalam Qanun Jinayat Aceh-Indonesia dan Brunei Darussalam. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 19(1), 19-44.
Mukhlishotin, M. N. (2017). Cyberbullying perspektif Hukum Pidana Islam. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, 3(2), 370-402..
https://doi.org/10.15642/aj.2017.3.2.370-402
Umar, M. N. (2017). Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Sanksi Pidana bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan. LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam, 6(1).128-155.
Mutmainnah, I. (2015). Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat dan Menyengsarakan. Jurnal Al Qadau. 2(2). 209-221
Nurdin, A. (2017). Revitalisasi Kearifan Lokal Di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat. ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman, 13(1), 135154. https://doi.org/10.42042/analisis.v13i1.645
Ritaudin, M. S. (2011). Damai Di Tengah Masyarakat Multikultur Dan Multiagama. Al-Adyan, 6(2), 29-52.
Syafa'at, R., & Yono, D. (2017). Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir. Arena Hukum, 10(1), 40-60.
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01001.3
Sanusi, S., Mujibussalim, M., & Fikri, F. (2013). Perdagangan Karbon Hutan Aceh: Analisis Hukum Pada Tahapan Perencanaan. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 41-63.
Saragih, D. J. W. (2014). Kebijakan Pidana Penjara Seumur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis Dalam Kerangka Tujuan Pemidanaan Di Indonesia. Unnes Law Journal, 3(2). 34-41.
Subyakto, K. (2015). Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jurnal Pembaharuan Hukum, 2(2), 209-213.
Susilowati, C. M. I. (2016). Pancasila sebagai Sumber Segala Sumber Hukum dan Kekerasan Atas Nama Agama di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 45(2), 93100. https://doi.org/10.14710/mmh.45.2.2016.93-100
Syahrul, M. Problematika Penerapan delik Formal pada Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia. Jurnal Varia Peradilan. Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia. XXVI (303).
Tajalla, S., & Rinaldi, Y. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Perusakan Barang Yang Dilakukan Bersama-Sama. Syiah Kuala Law Journal (SKLJ), 2(1), 39-56.
https://doi.org/10.24815/sklj.v2i1.10575
Natalia, S. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK). Lex Crimen, 2(2).
Widayati, L. S. (2015). Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 22(1), 1-24.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1
Amdani, Y. (2014). Proses Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Di Lembaga Peradilan Adat Aceh Tingkat Gampong (Desa).Asy Syir’ah. 48(1). 231-260. http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2014.%25x
Ulya, Z. (2014). Refleksi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh. Jurnal Konstitusi, 11(2), 371-392.
Desertasi
Natsir, M. (2017). Takzir terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Perlindungan Korban sesuai dengan Hukum Pidana Islam di Aceh. (Desertasi Doktor). Pasca Hukum USU, Medan
Website/lain-lain
M Syafrizal. (2016, Pebruari 20). Ensem Sawita Penuhi Tuntutan Warga Aramiah.
Diakses pada http://www.
medanbisnisdaily.com/news/read/2016/02/20/217474/ensem-sawita-penuhi-tuntutan-warga-aramiah/
Om Makplus. (2005, Nopember 5). Definisi dan Pengertian Korban. Diakses pada http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-dan-pengertian-korban.html
,Sofyan M. Saleh. (2009, Juli 6) Memahami masyarakat Aceh dalam Pencarian keadilan, https://revoluthion.wordpress.com/2009/06/06/memahami-budaya-masyarakat-aceh-dalam-pencarian-keadilan/
Nasution, F.A. (2006), Peluang Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Syariah dalam Sistem Hukum Tata Negara Republik Indonesia, makalah disampaikan pada Komisi Fadwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara, Muzakarah Ilmiah Rutin, Edisi Khusus Ramadhan 1427 H. Medan 08 Oktober 2006.
489
Discussion and feedback