Transformasi Tri Hita Karana dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Bali
on
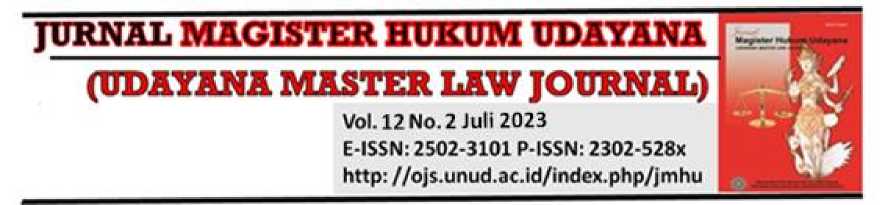
Transformasi Tri Hita Karana dalam Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Bali
I Wayan Novy Purwanto1
1Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: novy_purwanto@unud.ac.id
Info Artikel
Masuk: 30 April 2023 Diterima: 27 Juli 2023
Terbit: 29 Juli 2023
Keywords:
Transformation; Tri Hita
Karana; Consolidation; Land
Kata kunci:
Transformasi; Tri Hita Karana;
Konsolidasi; Tanash
Corresponding Author: I
Wayan Novy Purwanto, e-mail
DOI:
10.24843/JMHU.2023.v12.i0
2.p10
Abstract
The purpose of this study is to explore land consolidation arrangements in Bali and explore in depth the transformation of Tri Hita Karana in land consolidation arrangements in Bali. This research method uses normative legal research. The approach used is the statutory approach, the concept approach and the facts approach. The sources of legal materials in this study are primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this research is that land consolidation arrangements in Bali must still refer to the Bali RTRWP Regional Regulation and the Regulation of the Head of the National Land Agency Number 4 of 1991 concerning Land Consolidation. In relation to the transformation of Tri Hita Karana, the regulation of land consolidation in the BPN regulation must pay attention to the philosophical values adopted by the community in each region. Thus, land consolidation in Bali is inspired by Tri Hita Karana.
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali dan menelusuri secara mendalam tentang transformasi Tri Hita Karana dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan fakta. Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali harus tetap mengacu pada Perda RTRWP Bali dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. Terkait dengan transformasi Tri Hita Karana, maka pelaksanaan konsolidasi tanah dalam peraturan BPN tersebut wajib memperhatikan nilai falsafah yang dianut oleh masyarakat di masing-masing daerah. Dengan demikian, konsolidasi tanah di Bali dijiwai oleh Tri Hita Karana.
menguasai tanah untuk kepentingan rakyat. Penguasaan tanah oleh negara ini dituangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) yang menentukan bahwa hak menguasai negara atas tanah ini sebagai kewenangan negara untuk:
-
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
-
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dengan bumi, air dan ruang angkasa,
-
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Konsep hak menguasai negara sesungguhnya berasal dari konsep hukum adat yang telah lama dijalankan oleh penduduk asli jauh sebelum terbentuknya Indonesia sebagai negara. Dalam hukum adat, kepentingan publik lebih didulukan daripada kepentingan pribadi atau individual. Dengan kata lain, hukum adat didasarkan pada konsep perlindungan kepentingan publik atau kepentingan komunal.1 Dasar diberlakukannya hak menguasai negara atas tanah adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.
Berdasarkan UUPA, hak menguasai negara atas tanah berarti hak negara untuk mengatur dan mengelola tanah, bukan hak untuk memiliki tanah.2 Konsep UUPA ini dipengaruhi oleh konsep hukum adat yang tidak mengakui hak milik individual yang absolut atau mutlak atas tanah, dan hanya mengakui hak komunal atas tanah.3 Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama. Dalam ketentuan ini, UUPA memang mengakui bahwa hukum yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa di Indonesia adalah hukum adat sebagai hukum asli rakyat Indonesia. UUPA juga menerima konsep hak adat atas tanah yang disebut sebagai hak ulayat. Hak ulayat menurut UUPA sama dengan beschikkingsrecht yang menurut Van Vollenhoven dan para ahli hukum adat lainnya dimaksudkan sebagai hak komunal/bersama dari masyarakat adat untuk mengatur dan mengolah tanah mereka seisinya.4
Peraturan pelaksanaan dari Pasal 2 ayat (2) tersebut diatas, terkait dengan pemanfaatan tanah, diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (selanjutnya disingkat dengan UU Penataan Ruang) yang menentukan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
-
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
-
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
-
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Berdasarkan tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang tersebut, maka penataan ruang menghendaki terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. 5 Salah satu wujud dari lingkungan buatan tersebut adalah konsolidasi tanah. Dengan demikian, konsolidasi tanah atau LC (Land Consolidation) wajib mengacu pada penyelenggaraan penataan ruang. Konsolidasi tanah diadakan dalam rangka mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan rakyat.6
Berkaitan dengan penggunaan tanah, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah menyatakan bahwa penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Pasal ini menunjukkan adanya penatagunaan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah. Konsolidasi pemanfaatan tanah merupakan bentuk perwujudan dari penatagunaan tanah untuk kepentingan masyarakat secara adil. Sampai pada peraturan pemerintah ini masih terlihat sinkron dengan UU Penataan Ruang terkait dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat.
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah (selanjutnya disebut dengan Permen Konsolidasi Tanah) menyatakan bahwa konsolidasi tanah adalah kebijakan penataan kembali penguasan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan ruang sesuai rencana tata ruang serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pasal ini memberikan pengertian bahwa konsolidasi tanah tersebut merupakan kebijakan penataan kembali. Sebagai kebijakan, maka permen ini harus mengacu pada PP Penatagunaan Tanah dan UU Penataan Ruang agar terjalin harmonisasi antar peraturan perundang-undangan.
Sehubungan dengan itu, Pasal 2 ayat (1) Permen Konsolidasi Tanah menentukan bahwa peraturan menteri ini dimaksudkan untuk:
-
a. mewujudkan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal melalui Konsolidasi Tanah;
-
b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang;
-
c. meningkatkan kualitas lingkungan; dan
-
d. memberikan kepastian hukum hak atas tanah dan ruang di atas dan/atau di bawah tanah.
Maksud yang disampaikan dalam permen ini merupakan bentuk perwujudan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal serta mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Selanjutnya, dalam ayat (2)nya menentukan bahwa peraturan menteri ini bertujuan agar:
-
a. penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui Konsolidasi Tanah dapat menciptakan lingkungan hidup yang baik sesuai rencana tata ruang; dan
-
b. tersedianya tanah untuk kepentingan umum dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Mencermati ketentuan ini, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui konsolidasi tanah wajib mengacu pada rencana tata ruang. Apabila konsolidasi tanah diselenggarakan di tingkat provinsi, maka kebijakan konsolidasi tersebut wajib mengacu pada rencana tata ruang. Pada tingkat nasional diatur dalam UU Penataan Ruang, PP Penatagunaan Tanah dan Permen Konsolidasi Tanah. Sedangkan pada tingkat provinsi diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Pengaturan rencana tata ruang yang dimaksudkan dalam Pasal 2 di atas dapat diartikan rencana tata ruang wilayah provinsi karena pada tingkat nasional hanya mengenal penataan ruang bukan rencana tata ruang. Dengan demikian, rencana tata ruang tersebut terdapat di wilayah provinsi.
Provinsi Bali memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (selanjutnya disingkat dengan Perda RTRWP Bali). Pasal 1 angka 20 Perda RTRWP Bali menyatakan bahwa rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang. Ketentuan ini memberikan arti bahwa rencana tata ruang tersebut merupakan hasil perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang tersebut telah berbentuk hasil dari perencanaan tata ruang. Selanjutnya, Pasal 1 angka 17 perda ini menentukan bahwa perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Pengertian ini menekankan pada adanya suatu proses dari rencana tata ruang yang ditentukan dalam struktur dan pola ruang.
Rencana tata ruang yang ditentukan pada struktur dan pola ruang dalam Perda RTRWP Bali terdapat keunikan. Keunikannya tercermin pada kearifan lokal yang dijadikan asas dalam perda. Asas tersebut dicerminkan pada Pasal 2 Perda RTRWP Bali yang menentukan bahwa RTRWP didasarkan asas:
-
a. Tri Hita Karana;
-
b. Sad Kertih;
-
c. keterpaduan;
-
d. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
-
e. keberlanjutan;
-
f. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
-
g. keterbukaan;
-
h. kebersamaan dan kemitraan;
-
i. perlindungan kepentingan umum;
-
j. kepastian hukum dan keadilan; dan k. akuntabilitas.
Sesuatu yang menarik dalam perda ini adalah adanya penyerapan nilai filosofi Tri Hita Karana dan Sad Kertih kedalam perda. Nilai Tri Hita Karana berasal dari ajaran Agama Hindu. Nilai tersebut ditranformasi kedalam perda. Transformasi nilai filosofi Agama Hindu ini menjadi keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Perda RTRWP Bali.
Tri Hita Karana sebagai salah satu pedoman yang fundamental dalam perda tersebut dikarenakan Tri Hita Karana itu merupakan falsafah orang Bali. 7 Dalam perkembangannya, Tri Hita Karana diserap oleh masyarakat sehingga sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Bali dan menjadi kearifan lokal masyarakat Bali. Oleh karena Tri Hita Karana itu dijadikan asas dalam Perda RTRWP Bali, maka seluruh peraturan yang berkaitan dengan RTRWP Bali wajib mengacu pada Tri Hita Karana termasuk pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali. Kewajiban bagi pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali untuk mengacu pada RTRWP Bali karena didasarkan pada Pasal 1 angka 1 Permen Konsolidasi Tanah sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa konsolidasi tanah tersebut wajib mengacu pada rencana tata ruang.8 Dengan demikian, konsolidasi tanah di Bali wajib mengacu pada RTRWP Bali. Rencana tata ruang di Bali menganut asas Tri Hita Karana. Oleh sebab itu, maka Konsolidasi Tanah di Bali wajib mengacu pada asas Tri Hita Karana.
Secara yuridis, pengaturan Tri Hita Karana ini hanya tercermin dalam peraturan daerah saja. Asas Tri Hita Karana sebagai kearifan lokal tidak dimuat dalam Permen Konsolidasi Tanah. Dalam Permen Konsolidasi Tanah, tidak mencantumkan nilai kearifan lokal. Pasal 14 ayat (1) Permen Konsolidasi Tanah menentukan bahwa Perencanaan Konsolidasi Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memperhatikan:
-
a. Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, atau Rencana Detail lainnya yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
-
b. daya dukung dan daya tampung lingkungan serta perlindungan terhadap sumber daya alam, keanekaragaman hayati, lanskap (pusaka saujana/ heritage) dan situs budaya;
-
c. usulan masyarakat di lokasi Konsolidasi Tanah;
-
d. kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas;
-
e. program pemberdayaan masyarakat; dan
-
f. kebijakan pembangunan daerah.
Ketentuan Pasal 14 ayat (1) tersebut tidak secara tegas mengatur tentang penyerapan nilai kearifan lokal dalam konsolidasi tanah. Ketentuan itu hanya mewajibkan konsolidasi tanah itu harus memperhatikan keenam hal tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Permen Konsolidasi Tanah tidak mengatur tentang kebolehan untuk menyerap nilai kearifan lokal di masing-masing daerah. Tidak diaturnya nilai kearifan lokal tersebut, maka adanya kekosongan norma dalam Permen Konsolidasi Tanah. Kekosongan norma tersebut menjadi permasalahan dari segi struktur hukum. Dilihat dari struktur hukumnya, antara penataan ruang dengan rencana tata ruang wilayah telah sesuai dengan struktur hukum dalam konsolidasi tanah. Akan tetapi dari segi substansinya mengalami kekosongan norma terkait dengan nilai kearifan lokal yang dianut di masing-masing daerah. Terlebih lagi dari segi budaya hukumnya sudah dipastikan mengalami kekosongan norma karena substansi norma dalam konsolidasi tanah tidak mencerminkan nilai kearifan lokal, maka budaya hukumnya juga tidak mencerminkan kearifan lokal. Budaya hukum tersebut merupakan cerminan pelaksanaan konsolidasi tanah termasuk konsolidasi tanah di Bali yang menganut asas Tri Hita Karana.
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan antara lain: Bagaimanakah pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali dan Bagaimanakah transformasi Tri Hita Karana dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menelusuri pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali dan menelusuri secara mendalam terkait dengan transformasi Tri Hita Karana dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ida Ayu Karina Putri dan Made Suardika Jaya pada tahun 2021 dengan judul “Implementasi Tri Hita Karana Dalam Pelestarian Tradisi Budaya Masyarakat Lokal Di Samsara Living Museum, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali” 9 . Adapun penelitian tersebut secara empiris mengkaji terkait implementasi tri hita karana dalam pelestarian tradisi budaya masyarakat local di Samsara Living Museum, Desa Jungutan, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali yang mana konsep tri hita karana tidak hanya berkaitan dengan konsolidasi tanah di desa tersebut tetapi juga berkaitan dengan tradisi budaya dalam masyarakat tersebut, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis secara mengkhusus mengkaji terkait pengaturan konsolidasi tanah di Bali dikaitkan dengan konsep Tri Hita Karana.
-
2. Metode Penelitian
Penelitian hukum merupakan suatu proses yang ditempuh untuk menemukan guna dapat menjawab isu-isu hukum yang ada. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis isu-isu hukum tersebut melalui bahan-bahan hukum, buku-buku dan kamus-kamus hukum sebagai upaya penyelesaian masalah dari isu hukum.10 Penelitian ini mengkaji norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali serta transformasi Tri Hita Karana dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisa isu-isu hukum dalam penelitian ini yang berhubungan dengan pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali serta transformasi Tri Hita Karana dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali. Pendalaman terhadap bahan-bahan hukum dengan menggunakan studi dokumen dan kajiannya menggunakan analisis kualitatif.
Pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali mengacu pada Permen Konsolidasi Tanah dan RTRWP Bali. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Permen Konsoldasi Tanah merumuskan bahwa yang dimaksud dengan Konsolidasi Tanah adalah kebijaksanaan pertahanan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Secara yuridis, pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali, pertama-tama didasarkan pada Pasal 6 Permen Konsolidasi Tanah yang menentukan bahwa berdasarkan pada dimensi pemanfaatan tanah, pelaksanaan konsolidasi tanah dibedakan menjadi:
-
a. Konsolidasi Tanah Horizontal; dan
-
b. Konsolidasi Tanah Vertikal
Konsolidasi Tanah Vertikal adalah Konsolidasi Tanah yang diselenggarakan untuk pengembangan kawasan dan bangunan yang berorientasi vertikal. Skema Konsolidasi Tanah vertikal memungkinkan untuk masyarakat menggabungkan dan menata beberapa lahan bersama untuk dibangun ulang dengan mengoptimalkan lahan yang terkumpul. Optimalisasi ini akan menghasilkan lebih banyak jumlah hunian di lahan yang sama. Hal ini juga bisa diterapkan di lokasi kumuh sehingga masyarakat tidak perlu digusur namun hanya perlu ditata huniannya. Untuk meningkatkan jumlah hunian, penggabungan dan penataan ini harus dilakukan secara vertikal (rumah susun atau apartemen). Pembagian unit sarusun ditentukan berdasarkan luasan rumah lama atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Dengan pengaturan baru, pasti akan ada kelebihan ruang yang bisa dimanfaatkan untuk ruang komunal, seperti taman atau tempat berdagang. Ruang yang tersedia di Bali, sebenarnya masih memadai untuk mengadakan konsolidasi tanah vertikal, artinya belum banyak gedung bertingkat. Kepadatan horizontal tentu tidak akan mampu menampung banyak penduduk mengingat tanah yang tersedia di Bali khususnya di wilayah Kota Denpasar sangat terbatas. Dengan demikian, maka diperlukan Konsolidasi Tanah secara vertikal untuk memenuhi kebutuhan rumah yang sangat tinggi.
Secara konseptual, dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa lahan horizontal (terbangun/kosong) untuk di bangun menjadi rumah susun dengan memanfaatkan jumlah maksimal ruang yang bisa dibangun. Konsep ini memungkinkan terbangun lebih banyak unit rumah susun. Rumah susun ini juga harus menggunakan konsep multifungsi dan multi penghasilan (mixed-used and mixed income). Gedung bisa memiliki nilai tambah dengan berbagai macam kegiatan komersial dan juga bisa menampung para pekerja berpenghasilan rendah lebih dekat ke tempat kerja mereka tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Dengan adanya rumah susun, akan menambah
banyak unit rumah dan mengakomodir permintaan hunian di Bali. Apabila permintaan terakomodir atau banyak supply, secara otomatis harga hunian di Bali akan turun.
Selanjutnya, pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali mengacu pada Pasal 21 ayat (1) Permen Konsolidasi Tanah menyatakan bahwa pelaksanaan konsolidasi tanah dilaksanakan oleh Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat (2)nya menyatakan bahwa Pelaksanaan Konsolidasi Tanah meliputi kegiatan:
-
a. pengumpulan data fisik, yuridis dan penilaian objek Konsolidasi Tanah;
-
b. penyusunan desain dan rencana aksi Konsolidasi Tanah;
-
c. pelepasan Hak atas Tanah dan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah;
-
d. penerapan desain Konsolidasi Tanah (staking out); dan
-
e. penerbitan sertipikat Hak atas Tanah dan penyerahan hasil Konsolidasi Tanah.
Pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali, dilakukan di berbagai kabupaten dan/atau kota yang tersebar di beberapa lokasi masing-masing kabupaten dan/atau kota. Berdasarkan data yang diperoleh, pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali di gambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel 1
|
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Bali | ||
|
No |
Kabupaten/Kota |
Jumlah |
|
1 |
Denpasar |
8 lokasi |
|
2 |
Badung |
8 lokasi |
|
3 |
Gianyar |
3 lokasi |
|
4 |
Tabanan |
3 lokasi |
|
5 |
Bangli |
3 lokasi |
|
6 |
Jembrana |
2 lokasi |
|
7 |
Buleleng |
2 lokasi |
|
8 |
Klungkung |
2 lokasi |
|
9 |
Karangasem |
belum ada |
Berdasarkan tabel di atas, pelaksanaan konsolidasi tanah terbanyak dilaksanakan di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung yaitu sebanyak 8 lokasi. Selanjutnya, di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Bangli sebanyak 3 lokasi. Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Klungkung sebanyak 2 lokasi. Sedangkan Kabupaten Karangasem, sampai penelitian ini dilakukan belum pernah melaksanakan konsolidasi tanah. Dari data konsolidasi tanah tersebut, ada yang sudah selesai dan ada yang belum selesai. Konsolidasi tanah yang belum selesai dikarenakan beberapa faktor antara lain:
-
1) banyak lokasi LC yang belum terbentuk badan jalan atau belum dilakukan pengerasan jalan;
-
2) proses pembangunan yang melebihi batas bidang yang seharusnya dimiliki sehingga berakibat mengecil pada bidang tertentu, utamanya pada bidang-bidang yang belum terbangun untuk waktu yang lama;
-
3) terdapat beberapa kekurangan luas tanah dari yang seharusnya diterima/ menjadi haknya;
-
4) belum semua tanah sisa atau TPBP dikuasai oleh pemerintah kota/kabupaten dan terdapat tanah sisa atau TPBP yang dikuasai oleh pihak lain tanpa adanya rekomendasi dari pemerintah/kota atau belum ditindaklanjuti dengan pensertipikatan tanah.
Pelaksanaan konsolidasi tanah yang belum selesai tersebut merupakan tanggung jawab dari pelaksana. Adapun pelaksana konsolidasi tanah yang dimaksud adalah mengacu pada Pasal 21 ayat (1) Permen Konsolidasi Tanah yang menentukan Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah sebagai pelaksana konsolidasi tanah. Sebelum pelaksanaan konsolidasi tanah, Tim Pelaksana wajib melaksanakan penetapan lokasi, penyusunan desain, pemindahan desain dan penerbitan sertifikat. Pada saat ditetapkannya lokasi tanah yang akan dikonsolidasikan, Tim Pelaksana wajib melakukan pengerasan jalan atau menyediakan jalan. Sehingga apabila jalan telah disediakan, maka terlihat jelas desain konsolidasi tanah yang akan dibangun. Setelah adanya jalan, tahapan selanjutnya yaitu penyusunan desain lokasi. Dalam penuyusunan desain lokasi tersebut, Tim Pelaksana wajib melibatkan seluruh peserta konsolidasi tanah. Pelibatan peserta konsolidasi tanah secara aktif mengacu pada Pasal 1 angka 1 Permen Konsolidasi Tanah. Dengan adanya peran serta masyarakat secara aktif ini, maka masyarakat yang dilibatkan akan dapat mengetahui desain lokasi tanah mereka yang akan mengalami perubahan. Apabila perubahan tanah tersebut tidak sesuai dengan keinginan dari peserta konsolidasi tanah, maka dapat diselesaikan secara bersama-sama dengan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah. Penyelesaian permasalahan tersebut telah menjadi bagian dari kegiatan Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah yang sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) huruf b Permen Konsolidasi Tanah.
Khusus untuk pelaksanaan konsolidasi tanah vertikal di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, mengacu pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) Permen Konsolidasi Tanah, menentukan bahwa Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Vertikal dilaksanakan oleh Tim Perencana/Pelaksana Konsolidasi Tanah. Dalam ayat (2)nya menentukan bahwa Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Vertikal meliputi kegiatan:
-
a. pengumpulan data fisik, yuridis dan penilaian objek Konsolidasi Tanah Vertikal;
-
b. penyusunan desain dan rencana aksi Konsolidasi Tanah Vertikal;
-
c. pelepasan Hak Atas Tanah dan penegasan tanah objek Konsolidasi Tanah Vertikal;
-
d. penerapan desain Konsolidasi Tanah Vertikal (staking out); dan
-
e. penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan penyerahan sertipikat tanah bersama.
Pengumpulan data fisik dan penilaian objek Konsolidasi Tanah Vertikal dilaksanakan dengan mendaftarkan subjek dan objek tanah, pengukuran bidang tanah, serta pemetaan topografi dan penggunaan tanah. Hasil pendaftaran tersebut selanjutanya dijadikan dasar untuk pembuatan desain blok, yang kemudian dibawa dalam musyawarah bersama masyarakat.11
Berkaitan dengan subjek konsolidasi tanah yang dilaksanakan, mengacu pada peserta konsolidasi tanah. Adapun peserta konsolidasi tanah yang dilibatkan tersebut wajib mengadakan kesepakatan terlebih dahulu. Mengenai kesepakatan dari peserta
konsolidasi tanah sebagai syarat utama dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah, diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Permen Konsolidasi Tanah yang menyatakan bahwa Konsolidasi Tanah dapat diselenggarakan apabila disepakati oleh paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari peserta Konsolidasi Tanah. Peraturan Menteri ini adalah peraturan yang berlaku dari tahun 2019, itu artinya baru berlaku selama dua tahun. Dapat dikatakan peraturan tersebut merupakan peraturan yang masih baru. Apabila konsolidasi tanah di Bali mengacu pada Pasal 10 ayat (3) Permen Konsolidasi Tanah tersebut, maka hanya dibutuhkan 60% peserta konsolidasi tanah yang setuju, maka konsolidasi tanah itu dapat dilaksanakan. Sedangkan peserta lainnya, sebanyak 40% yang tidak setuju akan tetap melaksanakan konsolidasi tanah. Pasal ini mengandung makna bahwa konsolidasi tanah itu dapat dilakukan apabila sebagian besar masyarakat setuju atau sepakat dilaksanakan konsolidasi tanah. Apabila diartikan demikian, maka timbul permasalahan baru dalam masyarakat yang menjadi peserta konsolidasi tanah. Permasalahan tersebut terletak pada peserta yang tidak setuju dengan pelaksanaan konsolidasi tanah. Bagi peserta yang tidak setuju, tentunya berada pada posisi minoritas. Posisi minoritas tentunya tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan dari peserta yang berada di posisi mayoritas. Peserta yang berada di posisi mayoritas menjadi diuntungkan daripada posisi minoritas.
Secara deskriptif analitis, Pasal 4 ayat (1) Permen Konsolidasi Tanah secara tegas menyatakan bahwa Konsolidasi Tanah dilaksanakan secara partisipatif dan sukarela/berdasarkan kesepakatan diantara peserta Konsolidasi Tanah. Penekanan dalam pasal ini terletak pada partisipasi, sukarela dan kesepakatan. Partisipasi dimaksudkan adanya peran serta dari peserta untuk melaksanakan konsolidasi tanah. Kemudian adanya rasa sukarela dari peserta konsolidasi tanah untuk merelakan tanahnya. Kedua elemen tersebut baik partisipasi dan sukarela itu wajib didasarkan pada kesepakatan. Dengan demikian, kesepakatan wajib diutamakan dalam konsolidasi tanah. Oleh sebab itu, apabila hanya 60% peserta yang setuju, maka belum dapat dilaksanakan konsolidasi tanah karena masih ada 40% yang tidak setuju atau tidak sepakat dilaksanakan konsolidasi tanah. Dengan demikian, ketentuan ini tidak dapat dipaksakan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Apabila ketentuan ini dipaksakan, maka sudah dapat dipastikan akan menimbulkan permasalahan besar dalam pelaksanaannya.
Menurut Burhan Nurgiyantoro, transformasi adalah perubahan, yaitu perubahan terhadap suatu hal atau keadaan. Jika suatu hal atau keadaan yang berubah itu adalah budaya, budaya itulah yang mengalami perubahan.12 Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat dikatakan apabila nilai filosofi yang berubah, maka nilai filosofi itulah yang mengalami perubahan. Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan
mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan.13
Secara hafiah uraian dari tiga kata Tri Hita Karana mengandung suatu pengertian Tri artinya tiga, Hita adalah baik, senang, gembira, lestari dan sebagainya, Karana berarti sebab musabab atau sumbernya sebab. Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa Tri Hita Karana berarti tiga buah unsur yang merupakan sumbernya sebab yang memungkinkan timbulnya kebaikan.14 Konsep kosmologi Tri Hita Karana merupakan falsafah hidup umat Hindu sangat tangguh. Falsafah ini memiliki konsep yang dapat melestarikan keanekaragaman budaya dan lingkungan di tengah arus globalisasi dan homogenisasi. 15 Pada dasarnya hakikat ajaran Tri Hita Karana menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan dunia ini. Ketiga hubungan ini meliputi hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan dengan Tuhan. Setiap hubungan ini memiliki pedoman hidup menghargai sesama aspek sekitarnya. Prinsipnya pelaksanaannya harus seimbang, selaras antara satu dan lainnya. Keseimbangan dan kebahagiaan akan dicapai apabila manusia mengupayakan dan menghindar dari segala perbuatan buruk bagi kehidupan lingkungannya.
Secara yuridis, berdasarkan Pasal 1 angka 6 Perda RTRWP Bali, Tri Hita Karana adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia. Dalam pengertian tersebut, Tri Hita Karana ini mengandung filsafat keseimbangan dan keharmonisan. Keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan alam lingkungannya. Keseimbangan dan keharmonisan itu sesuai dengan ajaran Agama Hindu yang merupakan tujuan hidup sebagai orang Bali. Ketiga unsur dari Tri Hita Karana ini adalah:
-
a) parhyangan merupakan tempat suci pemujaan bagi umat Hindu,
-
b) palemahan adalah lemah berarti tanah. Palemahan berarti tanah tempat tinggal atau alam lingkungan, dan
-
c) pawongan berarti wong sama dengan orang yang segala sesuatu menyangkut masalah kehidupan orang-orang di Bali.16
Ketiga unsur ini menurut Dharmika, dalam Jiwa Atmaja, mengandung unsur-unsur Hyang Widhi/Tuhan Maha Kuasa, unsur manusia, dan unsur alam. 17 Semua unsur tersebut kemudian dipakai sebagai pola oleh masyarakat Bali dalam pembuatan pola pemukiman menjadi:
-
a) parhyangan berupa unit pura sebagai unsur pencerminan Ketuhanan
-
b) pawongan berupa keorganisasian masyarakat adat sebagai perwujudan manusianya, dan
-
c) palemahan berupa perwujudan unsur alamnya.18
Menurut Dharmayuda, ajaran ini mengajarkan pola hubungan yang seimbang diantara ketiga sumber kesejahteraan dan kedamaian. Dengan demikian diharapkan manusia selalu berusaha untuk menjaga keharmonisan hubungan diantara ketiga unsur itu yakni:
-
a) hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan,
-
b) hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam,
-
c) hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia.
Dalam konsep Tri Hita Karana sebagai suatu relasi akan terlihat jelas adanya hubungan
itu. Hubungan tersebut dapat dibedakan ke dalam hubungan yang bersifat menegak (vertikal) dan hubungan yang mendatar (horizontal).19
Secara vertikal terlihat hubungan antara manusia dengan Tuhan (parhyangan) dan hubungan manusia dengan alam (palemahan) dan secara horizontal dapat terlihat dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain maupun kelompok manusia dengan kelompok lainnya (pawongan). Sehubungan dengan konsolidasi tanah di Bali, berkaitan dengan sistem hak milik atas tanah yang dikenal adanya anggota atau krama desa adat sebagai unsur pawongan, tanah atau tanah pertanian sebagai unsur palemahan, dan adanya Pura Kahyangan Tiga sebagai tempat pemujaan merupakan unsur parhyangan.
Secara fakta, sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial di Bali pasti memiliki tanah. Desa adat memiliki bidang tanah yang dijadikan lokasi bangunan milik desa adat sendiri, seperti bangunan pura kahyangan desa sebagai tempat persembahyangan bersama warga desa adat. Terkait dengan konsolidasi tanah di Bali, maka pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali wajib memperhatikan kesediaan tanah bagi masyarakat sebagai peserta konsolidasi tanah. Penyediaan tanah tersebut wajib diperhatikan oleh Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (1) Permen Konsolidasi Tanah. Penyediaan tanah untuk bangunan tempat persembahyangan merupakan kewajiban dari Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah karena Konsolidasi Tanah wajib mengacu pada Tri Hita Karana sebagai asas yang dianut dalam RTRWP Bali. Apabila Konsolidasi Tanah di Bali telah sesuai dengan nilai Tri Hita Karana, maka Konsolidasi Tanah tersebut dikatakan sudah mengacu pada RTRWP Bali. Dalam pelaksanaan nilai parhyangan ini, penekanannya terletak pada hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan demikian, dalam konsolidasi tanah wajib memberikan tempat untuk mengadakan hubungan manusia dengan Tuhan. Hubungan manusia yang dimaksudkan, tidak hanya terbatas pada peserta konsolidasi tanah yang menganut agama Hindu saja, tetapi juga bagi peserta yang beragama Islam, Budha, Kristen dan Kong Hu Cu. Pelaksanaan konsolidasi tanah yang menyediakan tempat ibadah belum
pernah dilaksanakan di Bali, sehingga konsolidasi tanah di Bali belum mengacu pada nilai Tri Hita Karana seperti yang dianut dalam RTRWP Bali.
Nilai pawongan merupakan nilai yang esensial dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Dalam konsolidasi tanah, wajib memperhatikan hubungan harmonis antar peserta konsolidasi tanah. Pelaksanaan transformasi nilai pawongan dalam konsolidasi tanah di Bali, diwujudkan dalam bentuk bangunan yang peruntukannya sebagai tempat pertemuan antar warga. Oleh karena itu, wajib disediakan tanah sebagai tempat balai pertemuan, seperti balai banjar, wantilan desa, dan lain-lain. Setiap desa adat juga pasti memiliki tanah yang difungsikan sebagai tanah kuburan (setra). Beberapa desa adat juga memiliki bidang-bidang tanah yang berupa tanah lapang, tanah pasar, dan lain-lain.20 Secara tradisional, dalam masyarakat adat, ditemukan kepemilikan tanah adat yang memiliki status hak milik komunal. Sehingga tanah-tanah milik desa adat itu lazim disebut tanah druwe desa, artinya tanah milik desa. Studi yang dilakukan oleh Hendriatiningsih menyimpulkan bahwa masyarakat dan pemerintah di Bali sudah lama mengakui keberadaan hak-hak desa adat atas tanah-tanah tersebut. Walaupun demikian, ia menyarankan agar dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum yang berlaku mengenai hubungan desa adat tersebut. 21 Dalam pelaksanaan konsolidasi tanah, sebelum konsolidasi tanah tersebut dilaksanakan atau masih pada tahap perencanaan atau desain konsolidasi tanah, wajib menyediakan tempat bertemunya peserta konsolidasi tanah. Dalam desain tersebut telah tergambar adanya penyediaan bangunan yang dipakai oleh peserta untuk mengadakan pertemuan. Apabila bangunan tersebut dapat diwujudkan, maka nilai pawongan dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi, konsolidasi tanah di Bali hanya sebagian kecil saja yang mampu menyediakan tempat atau balai pertemuan. Oleh sebab itu, konsolidais tanah di Bali kurang mampu menyediakan tanah untuk dijadikan tempat pertemuan oleh peserta. Transformasi nilai pawongan masih dirasakan kurang dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali.
Nilai palemahan dalam konsolidasi tanah juga wajib diperhatikan karena lingkungan menjadi faktor yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup peserta konsolidasi tanah. Dalam nilai palemahan ini, peserta konolidasi tanah diwajibkan menjaga keseimbangan dengan lingkungannya. 22 Peserta konolidasi tanah, dalam menjaga keseimbangan itu diwujudkan dalam bentuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar lokasi konsolidasi tanah tersebut. Nilai palemahan tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali. Nilai palemahan ditransformasi kedalam Perda RTRWP Bali. Oleh karena itu, pelaksanaan konsolidasi tanah wajib melaksanakan nilai palemahan. Selain, peserta konsolidasi, Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah juga berkewajiban menyediakan tanah sebagai tempat pembuangan sampah. Penyediaan
tempat tersebut merupakan perwujudan dari kebersihan lingkungan setempat. Pada prinsipnya, apabila lingkungan di lokasi konsolidasi tanah itu bersih, maka pesertanya pun juga bersih. Dengan demikian, sangat penting menyediakan tanah untuk pembuangan sampah sebagai wujud pelaksanaan nilai palemahan. Perujudan nilai palemahan dalam konsolidasi tanah di Bali masih sangat kurang karena tidak disediakannya tanah untuk pembuangan sampah, sehingga seringkali ditemui dalam lokasi konsolidasi tanah masih kurang bersih. Akan tetapi, saat ini Pemerintah Kota/Kabupaten telah memiliki program pengolahan sampah yang diserahkan kepada desa adat setempat. Program tersebut menciptakan lingkungan yang bersih termasuk di lokasi konsolidasi tanah, sehingga nilai palemahan dalam konsolidasi tanah di Bali sudah dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat.
Menurut Sastrawan dalam kajiannya menyebut kondisi itu sebagai suatu kekosongan hukum mengenai kedudukan tanah milik desa adat. Hal Itu terjadi karena tidak ada ketentuan hukum yang melegalkan hubungan desa adat dengan tanahnya sebagai hubungan hak milik.23 Bidang tanah di mana bangunan pura itu berdiri disebut tanah tegak pura yang luasnya bervariasi tergantung kebutuhan. Beberapa pura mungkin memiliki satu atau lebih bidang tanah lain yang berupa lahan pertanian atau perkebunan (sawah, tegalan, hutan) yang hasilnya khusus dimanfaatkan langsung atau pun tak langsung untuk kepentingan pura yang bersangkutan, baik untuk pembangunan dan pelestarian bangunan pura atau pun untuk keberlangsungan aktivitas-aktivitas sosial keagamaan (ritual) di pura tersebut. Tanah ini lazim disebut tanah laba pura atau pelaba pura. Semua tanah pura, baik tegak pura maupun pelaba pura, telah lama dapat didaftarkan dengan status hak milik menurut UUPA karena berdasarkan SK Mendagri No SK. DJA/1986, pura telah ditunjuk sebagai badan hukum keagamaan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.24 Dengan demikian, apabila konsolidasi tanah itu mengacu pada Tri Hita Karana, maka wajib menyediakan tempat peribadatan atau tempat sembahyang, wajib menyediakan tempat berkumpul dan wajib myediakan tempat pembuangan limbah atau sampah. Semua kewajiban itu harus dipenuhi dalam penyelenggaraan konsolidasi tanah yang berlandaskan Tri Hita Karana.
Peranan Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut. Oleh karena itu, transformasi Tri Hita Karana sangat sulit diwujudkan dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali. Apabila hanya mengacu pada persyaratan formal yang ditentukan dalam perda RTRWP Bali yang terkait dengan kawasan pemukiman saja, maka akan lebih mudah dilaksanakan dibandingkan dengan mengacu pada nilai filosofi Tri Hita Karana. Transformasi nilai Tri Hita Karana mengandung muatan religius sedangkan RTRWP Bali mengandung muatan yuridis. Perbedaan muatan yang terkandung didalamnya membuat pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali menjadi berbeda pula. Konsolidasi tanah yang berbasis yuridis dan konsolidasi tanah berbasis Tri Hita Karana. Demikian pula konsolidasi tanah yang mengacu pada Permen Konsolidasi tanah, maka muatannya sudah jelas muatan yuridis. Berbeda dengan Tri Hita Karana yang sudah menjadi kearifan lokal masyarakat Bali tentunya memberikan makna tersendiri dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Makna
religio magis sangat kental dalam Tri Hita Karana, justru makna yuridinya sama sekali tidak nampak. Demikian pula sebaliknya, RTRWP Bali dan Permen Konsolidasi Tanah memberikan makna yuridis yang sangat kental. Transformasi Tri Hita Karana dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali memang seharusnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Konsolidasi Tanah agar memberikan citra kearifan lokal masyarakat Bali. Sehingga konsolidasi tanah di Bali berwawasan kearifan lokal yaitu Tri Hita Karana. Wawasan kearifan lokal tersebut tentunya menjadi khas tersendiri dan sekaligus menjadi keunikan yang dimiliki oleh Bali. Transformasi Tri Hita Karana adalah ciri khas konsolidasi tanah di Bali.
4. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diberikan beberapa simpulan antara lain Pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali belum mengacu pada Tri Hita Karana sebagaimana yang dianut sebagai asas dalam Perda RTRWP Bali. Sampai saat ini, konsolidasi tanah di Bali dilaksanakan dengan mengacu pada Perda RTRWP Bali dan Permen Konsolidasi Tanah. Dalam konsolidasi tanah di Bali, hanya mengacu Perda RTRWP Bali dalam artian subtansinya bukan dalam artian asasnya. Substansi hukum dari Perda RTRWP Bali telah terpenuhi dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali, namun asas Tri Hita Karana belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Serta Transformasi Tri Hita Karana dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali hanya pada Perda RTRWP Bali saja. Transformasi nilai Tri Hita Karana dalam pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali belum dapat dilaksanakan karena pelaksanaan konsolidasi tanah di Bali belum memenuhi nilai parhyangan dan nilai pawongan, sedangkan nilai pelemahannya sudah terpenuhi, itupun dikarenakan adanya program Pemerintah Kota/ Kabupaten terkait dengan pengolahan sampah yang menyerahkannya kepada masing-masing desa adat.
Daftar Pustaka
Afifah Kusumadara, “Analysis of the Failure of the Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia,” 2000.
Arba, H. M., and M. SH. Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah. Sinar Grafika, 2022.
Ariyani, Ni Made Desy, and I. Wayan Parsa. "Konsolidasi Tanah Sebagai Upaya Meningkatkan Efisiensi dan Produktivitas Pemanfaatan Tanah Perkotaan Secara Optimal." E-Jurnal Universitas Udayana (2019): 1-15.
Aryawan, I Putu Sony, Wayan Windia, and Putu Udayani Wijayanti. “Peranan Subak Dalam Aktivitas Pertanian Padi Sawah (Kasus Di Subak Dalem, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan).” E-Jurnal Agribisnis Dan Agrowisata 2, no. 1 (2013): 1–11.
Atmaja, Jiwa. “Perempatan Agung: Menguak Konsepsi Palemahan, Ruang Dan Waktu Masyarakat Bali.” Denpasar: Bali Media Adhikarsa, 2003.
Dharmayuda. Konsepsi Tri Hita Karana Sebagai Dasar Hidup Harmonis. Denpasar, 1999.
Hadat, Herpin. "Eksistensi Tri Hita Karana dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Bali (Perspektif Filsafat Ilmu)." Jurnal Magister Hukum Udayana 9, no. 1 (2020): 132141.
Hendriatiningsih, S., Budiartha, A., & Hernandi, A. (2008). Masyarakat dan Tanah Adat di Bali (Studi Kasus Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali). Jurnal Sosioteknologi, 7(15), h. 527.
Isnaeni, Diyan. "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara." Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 4 (2020).
Kusumadara, Afifah. “Analysis of the Failure of the Implementation of Intellectual Property Laws in Indonesia,” 2000.
Listyawati, Hery. "Kegagalan pengendalian alih fungsi tanah dalam perspektif penatagunaan tanah di Indonesia." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 22, no. 1 (2010): 37-57.
Mahendra, Putu Ronny Angga, and I Made Kartika. “Membangun Karakter Berlandaskan Tri Hita Karana Dalam Perspektif Kehidupan Global.” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha 9, no. 2 (2021): 423–30.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
Nurgiyantoro, Burhan. Teori Pengkajian Fiksi. UGM press, 2018.
Putri, Ida Ayu Karina, and Made Suardika Jaya. "IMPLEMENTASI TRI HITA KARANA DALAM PELESTARIAN TRADISI BUDAYA MASYARAKAT LOKAL DI SAMSARA LIVING MUSEUM, DESA JUNGUTAN, KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM, BALI." Subasita: Jurnal Sastra Agama dan Pendidikan Bahasa Bali 2, no. 2 (2021): 11-19.
Sari, Ni Luh Ariningsih. "Konsep hak menguasai negara terhadap tanah dalam hukum tanah (uupa) dan konstitusi." Ganec Swara 15, no. 1 (2021): 991-998.
Sardana, I. N., Suwitra, I.M., & Sepud, I.M. (2018). Dispute Of Customary Land Tenure And Domination And The Resolution In Buleleng Regency. Jurnal Hukum Prasada, 5(1),
Sastrawan, I Putu Dody, I Gusti Nyoman Guntur, and Dwi Wulan Titik Andari. “Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa Di Bali.” Tunas Agraria 1, no. 1 (2018).
Sudantra, I.K. “Status Hak Atas Tanah Pura Setelah Berlakunya SK. Mendagri Nomor SK. 556/DJA/1986.” Kertha Patrika 61, no. Tahun XYIII Desember (1992).
Sumardjono, Maria S. W. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Pertanahan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2009.
Waskito, and Hadi Arnowo. Pertanahan, Agraria, Dan Tata Ruang. Jakarta: Kencana, 2017.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
380
Discussion and feedback