Apakah Pendidikan Tinggi Meningkatkan Kemungkinan untuk Bekerja di Sektor Formal?
on
ISSN : 2301-8968
Vol. 13 No.1, Februari 2020
EKONOMI
KUANTITATIF
TERAPAN
Volume 13
JEKT
Nomor 1
Pola Perilaku Komuter dan Stres: Bukti dari Jabodetabek Gema Akbar Riadi, Muhammad Halley Yudhistira
ISSN 2301-8968
Denpasar
Februari 2020
Halaman
1-210
Apakah Pendidikan Tinggi Meningkatkan Kemungkinan untuk Bekerja di Sektor Formal?: Bukti dari Data SAKERNAS
Rizky Maulana
Dampak Pengeluaran Wisatawan Mancanegara terhadap Perekonomian Indonesia: Andhiny Adyaharjanti, Djoni Hartono
Peran Riset dan Pengembangan (R&D) Akademis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Abdul Khaliq
Pekerja Anak di Indonesia : Peran Penawaran dan Permintaan Keternagakerjaan Resa Surya Utama, Dwini Handayani
Kebijakan Fiskal Dalam Trend [embangunan Ekonomi Jangka Panjang di Indonesia I Komang Gde Bendesa, Ni Putu Wiwin Setyari
Analisis Efek Penularan Melalui Pendekatan Risiko Sistemik dan Keterkaitan Keuangan: Studi Pada DualBanking System di Indonesia
Setyo Tri Wahyudi, Rihana Sofie Nabella, Ghozali Maski
Faktor Eksternal dan Internal Penentu Kekuasaan Perempuan Bali Dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga di Provinsi Bali
Putu Ayu Pramitha Purwanti
Elastisitas Permintaan Gandum dan Produk Turunan Gandum di Indonesia Saaroh Nisrina Saajidah, I Wayan Sukadana
Willingness To Pay (WTP) Iuran Pemberdayaan LPD kepada Lembaga Pemberdayaan LPD (LPLPD) di Kecamatan Bangli dan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli (Pendekatan Ekonomi Kelembagaan)
I Nengah Kartika, I Made Jember
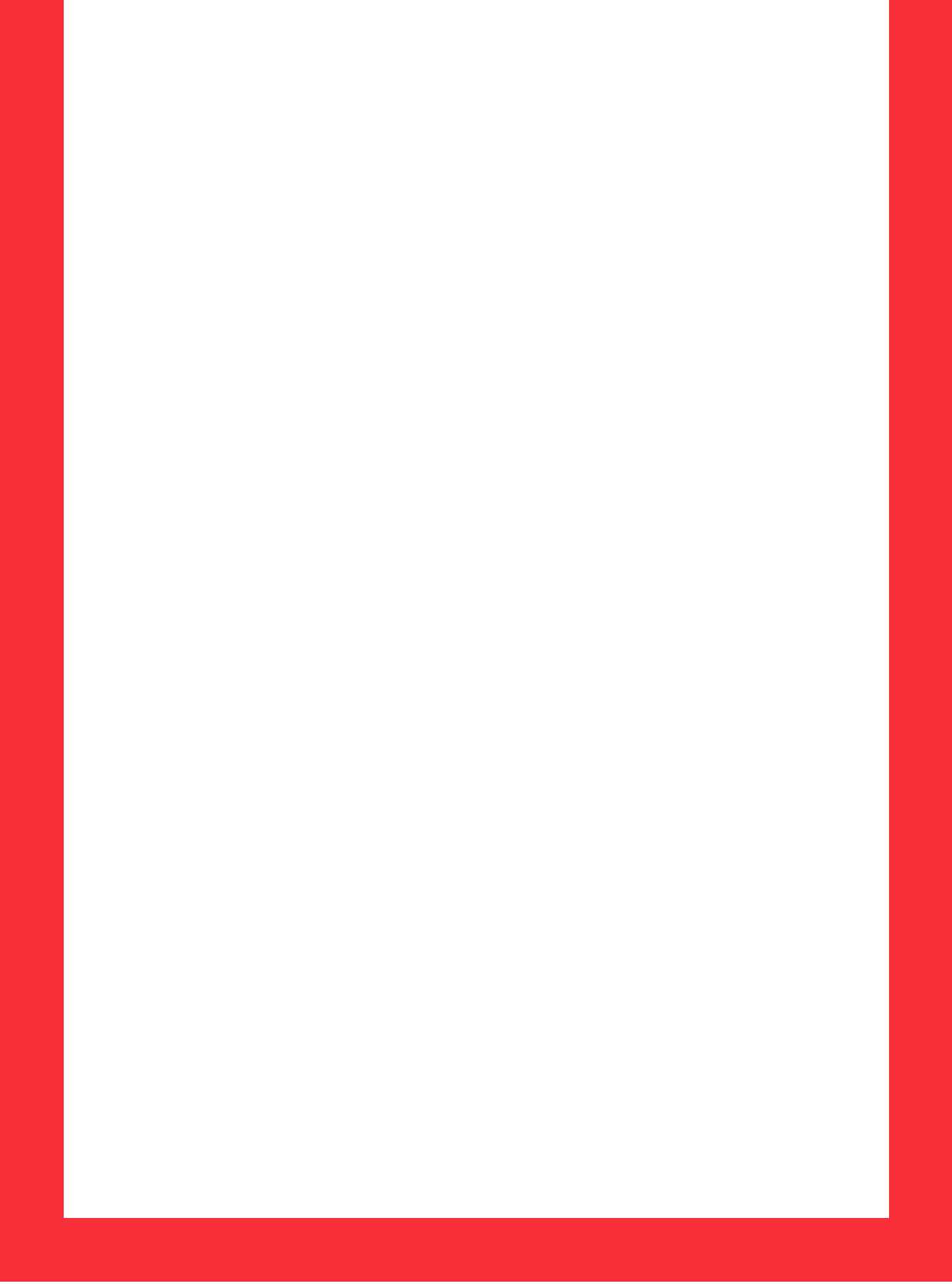
EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN
VOLUME 13 NO.1 FEBRUARI 2020
SUSUNAN REDAKSI
EDITOR
I Wayan Sukadana Ni Putu Wiwin Setyari Anak Agung Ketut Ayuningsasi
DEWAN EDITOR
I Komang Gde Bendesa
Anak Agung Istri Ngurah Marhaeni Luh Gede Meydianawathi
Ni Made Tisnawati
MITRA BESTARI
Adrianus Amheka, Politeknik Negeri Kupang Made Antara, Universitas Udayana Mohammad Arsyad, Universitas Hasanudin Kadek Dian Sutrisna Artha, Universitas Indonesia
Djoni Hartono, Universitas Indonesia
Palupi Lindiasari, Universitas Indonesia Devanto Shasta Pratomo, Universitas Brawijaya Deniey Adi Purwanto, Institut Pertanian Bogor Ni Made Sukartini, Universitas Airlangga Setyo Tri Wahyudi, Universitas Brawijaya Muhammad Halley Yudhistira, Universitas Indonesia
ADMINISTRASI DAN DISTRIBUSI
I Ketut Suadnyana Ida Ayu Made Widnyani
Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan diterbitkan oleh Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dua kali dalam setahun bulan Februari Dan Agustus
ALAMAT
Ruang Jurnal, Gedung BJ lantai 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Jalan PB Sudirman Denpasar
Phone: +62-361-255511/ Fax: +62-361-223344
E-mail: jekt@unud.ac.id
http://ojs.unud.ac.id/index.php/jekt
ISSN : 2301-8968
Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT) adalah jurnal yang menerapkan double blind review pada setiap artikel yang diterbitkan. JEKT diterbitkan oleh Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dua kali dalam setahun yaitu bulan Februari dan Agustus. JEKT diterbitkan sebagai kelanjutan dari Jurnal Input, Jurnal Sosial dan Ekonomi. Input terbit berkala sebanyak dua kali dalam setahun, dengan Nomor ISSN 1978-7871, dan di tahun kelima, INPUT telah terbit sebanyak sembilan edisi, dengan terbitan terakhirnya adalah Volume V, Nomor 1 Februari 2012. Pembaharuan INPUT menjadi JEKT tercetus pada pertemuan antara tim redaksi jurnal jurusan bersama pimpinan kampus, awal Maret 2012. Setelah melakukan beberapa evaluasi dan dengan merujuk kepada Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan Nasional Republik Insonesia Nomor 49/dikti/kep/2011 tentang Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah, maka terbitlah jurnal jurusan : Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan dimulai dari Volume V, Nomor 2 Agustus 2012.
Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan (JEKT) beralamat di Ruang Jurnal, Gedung Program Ekstensi Lantai 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Jalan PB Sudirman Denpasar, Phone: +62-361-255511/Fax: +62-361-223344. Proses registrasi dan submit artikel dapat dilakukan melalui http://ojs. unud.ac.id/index.php/jekt. Untuk bantuan teknis, penulis dapat menghubungi, email: jekt@unud.ac.id, SMS dan WA : +6281338449077.
Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 36a/E/KPT/2016 tanggal 23 Mei 2016, JEKT dinyatakan telah terakreditasi B oleh Dikti. Selain terakreditasi oleh Dikti, JEKT juga telah terindeks pada Google Scholar, IPI, dan DOAJ.
JURNAL
EKONOMI KUANTITATIF TERAPAN
VOLUME 13 NO.1 FEBRUARI 2020
PENGANTAR REDAKSI
Pembaca yang terhormat,
Sampai dengan edisi ini terbit, jika pembaca menelusuri deretan jurnal-jurnal yang terdaftar di Sinta dengan kata kunci penelusuran “kuantitatif”, maka yang akan muncul adalah Jurnal Ekonomi Kuantitatif (JEKT). Dengan menjadi satu-satunya jurnal dengan fokus kuantitatif, maka JEKT dituntut untuk menampilkan terbitan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalangan peneliti ekonomi, pembangunan dan ilmu sosial lainnya di Indonesia tentunya sudah tidak asing lagi dengan penerapan metode kuantitatif dalam melakukan analisis, khususnya analisis empiris. Terlepas dari semua itu, diatas segala kemutakhiran metode kuantitatif yang digunakan, “ceritera” yang mampu menarik pembaca dan tentunya para pembuat kebijakan untuk berpastisipasi aktif dalam membaca dan menulis di JEKT adalah yang utama. Rangkaian “ceritera” yang baik dan metode kuantitatif yang sesuai tidak akan bermakna jika data yang digunakan tidak transparan dan tidak valid.
Slogan menarik mengenai data digunakan oleh BPS, “Data Mencerdaskan Bangsa”, JEKT berkomitmen untuk berperan aktif dalam mewujudkan slogan tersebut menjadi kenyataan. Meskipun tidak selalu data yang digunakan artikel yang dipublikasi oleh JEKT menggunakan data BPS sebagai “menu” utama dalam analisisnya, data BPS pasti hampir selelu menjadi rujukan dalam setipa artikel dalam terbitan JEKT. Pentingnya satu pemahaman dan satu sumber dalam data memegang peran penting dalam analisis dan diskusi yang akan melahirkan implikasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dalam edisi kali ini, JEKT kembali menerbitkan 10 artikel dengan sumber dan jenis data serta metodologi yang beragam.
Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam edisi ini cukup bervariasi mulai sumber data sekunder sampai data primer. Artikel dengan sumber data sekunder sendiri juga memiliki variasi jenis data yang beragam mulai dari data mikro antara lain dari sumber BPS seperti Sakernas, seperti yang digunakan oleh Maulana untuk menjelaskan bagaimana pendidikan menentukan status pekerjaan pekerja dan Susenas serta Podes seperti yang digunakan oleh Utama dalam menjelaskan keberadaan pekerja anak di Indonesia. Sumber data mikro lain, yaitu IFLS digunakan oleh Saajadah dan Sukadana dalam mengungkapkan elastisitas permintaan gandum dan produk turunannya. Data sumber sekunder mengenai keuangan juga ditampilkan dalam edisi kali ini, Wahyudi, et.al, menjelaskan perilaku sistemik dalam industri perbankan dengan menggunakan berbagai data keuangan yang bersumber dari berbagai lembaga keuangan di Indonesia seperti OJK, BI dan sumber online Yahoo finance.
Tidak hanya analisis mikro, edisi kali ini juga menampilkan berbagai analisis makro dengan menggunakan data sumber sekunder. Hartono, menjelaskan efek pengeluaran wisatawan dengan menggunakan data Input-output. Analisis dengan data agregate ditampilkan oleh Bendesa dan Setyari dalam menjelaskan tren pembangunan jangka panjang di Indonesia. Data publikasi BPS lainnya digunakan oleh Riyadi dan Yudhistira dalam menganalisis perilaku komuter di Jabodetabek. Artikel dengan sumber data primer juga diterbitkan dalam edisi kali ini. Purwanti dan Kartika adalah dua diantaranya, kedua penulis ini menggunakan data primer untuk menganalisis ekonomi lokal di Bali. Purwanti, menjelaskan bagaimana peran perempuan Bali dalam pengambilan keputusan rumah tangga, sedangkan Kartika menganalisis willingness to pay masyarakat lokal setempat pada lembaga keuangan lokal Bali, LPD.
Akhir kata, redaksi menyimpulkan bahwa artikel-artikel yang diterbitkan oleh JEKT mulai mengalami pergeseran sejak kemunculannya pertama kali lebih dari 10 tahun silam, utamanya dari sisi data yang digunakan. Semakin banyak artikel-artikel yang menampilkan analisis dengan menggunakan data mikro baik dari sumber sekunder maupun primer. Meskipun demikian JEKT tetap membuka diri untuk artikel-artikel dengan penggunaan data agregate. Kembali ke Alenia pembuka di atas, yang terpenting bagi JEKT dalam terbitannya adalah “ceritera” yang menarik, metode kuantitatif yang sesuai dan data yang valid.
pISSN : 2301 – 8968
JEKT ♦ 13 [1] : 133-144
eISSN : 2303 – 0186
Apakah Pendidikan Tinggi Meningkatkan Kemungkinan untuk Bekerja di Sektor Formal?: Bukti dari Data SAKERNAS
Rizky Maulana
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah lulusan perguruan tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk terserap ke lapangan kerja sektor formal dibandingkan jenjang pendidikan lebih rendah. Lapangan kerja formal memiliki tingkat upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Mahasiswa yang melanjutkan ke pendidikan tinggi memiliki ekspektasi yang tinggi akan taraf hidupnya di kemudian hari, namun masih ada lulusan perguruan tinggi yang bekerja di sektor informal. Untuk menjawab tujuan pada penelitian ini, penulis menggunakan regresi probit. Dari regresi tersebut didapatkan hasil yang signifikan. Pendidikan tinggi meningkatkan kemungkinan seseorang untuk terserap di sektor formal. Demikian juga dengan variabel jenis kelamin dan usia. Tenaga kerja laki-laki memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terserap, sedangkan semakin bertambah usia akan menurunkan kemungkinan seseorang untuk terserap di sektor formal.
Kata kunci: pendidikan tinggi; sektor formal; regresi probit; SAKERNAS.
JEL : I21, J2, C35, C83
Abstract
This research aims to see whether tertiary education graduates are more likely to be employed in a formal sector than lower levels of education. Formal employment has a much higher wage rate than the informal sector. Students who go on to higher education have high expectations for their standard of living in the future, but there are still college graduates who work in the informal sector. To answer the purpose of this research, the writer uses probit regression. From these regressions, significant results were obtained. Higher education increases one's chances of being employed in the formal sector. Likewise, the sex and age variables. Male workers have a higher chance of being employed while the older labor forces have smaller chances of being employed in a formal sector.
Keywords: higher education; formal sector; probit regression; SAKERNAS.
PENDAHULUAN
Manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk dapat bertahan hidup. Kita dapat memenuhi kebutuhan dasar tersebut dengan mengkonsumsi barang-barang dan jasa
yang dibeli menggunakan uang. Namun untuk mendapatkan income seseorang harus bekerja. Orang yang bekerja tersebut disebut sebagai tenaga kerja.
Corresponding email address : rizkymaulanaputra95@outlook.com
Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS mendefinisikan tenaga kerja sebagai individu yang melakukan kegiatan bekerja sekurang-kurangnya satu jam selama seminggu yang lalu dengan maksud untuk mendapatkan pendapatan atau keuntungan. Sementara orang yang bekerja adalah individu yang termasuk dalam angkatan kerja, yaitu penduduk berusia lima belas tahun keatas yang sedang bekerja atau mencari pekerjaan dan tidak sedang sekolah atau mengurus rumah tangga.
Lebih lanjut BPS juga membagi status tenaga kerja ke dalam tujuh kategori, yaitu; (1) berusaha sendiri, (2) berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, (3) berusaha dibantu buruh tetap/dibayar, (4) buruh/karyawan/pegawai, (5) pekerja bebas di pertanian, (6) pekerja bebas di non-pertanian dan (7) pekerja keluarga/tidak dibayar. Ketujuh kategori tersebut dibagi kedalam dua sektor lapangan kerja, yaitu sektor formal dan sektor informal. Menurut studi yang dilakukan oleh Bappenas tahun 2009, status tenaga kerja yang termasuk pada sektor formal adalah nomor (3) dan (4) yaitu berusaha dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya termasuk pada sektor informal.
Menurut studi profil pekerja di sektor informal yang dilakukan oleh Direktorat Tenaga Kerja Bappenas, sektor informal memegang peranan penting pada perekonomian Indonesia dengan menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan sektor formal, yang mana hal tersebut positif dalam mengurangi tingkat pengangguran (2002). Menurut data yang dilansir dari BPS, pada tahun 2000 persentase tenaga
kerja yang bekerja pada sektor informal mencapai 65%, sedangkan pada tahun 2017 mencapai 57.03% dan menurun menjadi 56.84% pada tahun 2018. Angka statistik tersebut membuktikan bahwa sektor informal masih mendominasi pasar tenaga kerja di Indonesia,namunshare tenaga kerja sektor formal juga beranjak naik sedikit demi sedikit. Selain itu, menurut studi yang dilakukan oleh Bappenas, meskipun tanpa didukung sepenuhnya oleh pemerintah, sektor ini mampu bertahan dari serangan resesi sehingga roda perekonomian masyarakat dapat terus berputar (2009).
Terdapat perbedaan pada kedua jenis lapangan kerja tersebut, khususnya dalam hal pendapatan atau gaji yang didapatkan oleh tenaga kerja. Beberapa penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa terdapat ketimpangan antara pendapatan yang diterima oleh pekerja di sektor formal dan informal, yang mana sektor formal memberikan pendapatan yang lebih besar kepada pekerjanya dibandingkan sektor informal, yang berdampak pada kesejahteraan dan taraf hidup kedua jenis tenaga kerja tersebut (Badaoui et al., 2010; Nordman et al., 2016; Kahyalar et al., 2018; Singhari & Madheswaran, 2017). Selain penelitian ilmiah tersebut, studi yang dilakukan oleh Direktorat Tenaga Kerja dan juga Bappenas menyatakan hal yang sama.
Karena sektor formal memberikan pendapatan atau upah yang lebih tinggi dibandingkan sektor informal, maka persyaratan pendidikan yang dibutuhkan pun berbeda. Sektor formal cenderung memilih tenaga kerja yang pendidikannya lebih tinggi dibandingkan sektor informal. Hal ini dapat dilihat dari data survey tenaga
kerja Nasional (SAKERNAS) pada tahun 2018 di bawah ini:
|
Tabel 1. Data Sektor Pekerjaan menurut Pendidikan | |||
|
Pendidika n |
Sektor Informa l |
Sektor Forma l |
TOTA L |
|
Tidak Sekolah |
51,727 |
8,358 |
60,085 |
|
Pendidika n Primer |
142,738 |
79,108 |
221,846 |
|
Pendidika n Tinggi |
5,759 |
32,777 |
38,536 |
|
TOTAL |
200,224 |
120,24 3 |
320,467 |
|
Sumber: Survey Tenaga Kerja Nasional | |||
|
(2018), diolah. | |||
Menurut tabel 1 di atas, sektor formal lebih banyak diisi oleh tenaga kerja dengan pendidikan primer, yaitu individu yang lulus pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK sebesar 79,108 orang, sedangkan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan tinggi setingkat diploma keatas hanya terdapat sebesar 32,777. Namun, apabila dilihat proporsinya, maka terlihat persentase tenaga kerja berpendidikan tinggi adalah yang terbesar, yaitu 85.05%, sedangkan tenaga kerja yang berpendidikan primer persentasenya sebesar 35.65%, dan tenaga kerja yang tidak bersekolah sebesar 13.91% dibandingkan dengan tenaga kerja berpendidikan setingkat yang bekerja di sektor informal.
|
Tabel 2. Pengangguran Lulusan Pendidikan Tinggi tahun 2018 | |
|
Kegiatan |
Jumlah |
|
Bekerja |
38,536 |
|
Menganggur |
11,143 |
|
Angkatan Kerja |
49,679 |
Sumber: Survey Tenaga Kerja Nasional (2018), diolah.
Berdasarkan tabel 1, berarti dapat disimpulkan bahwa masih ada tenaga kerja lulusan perguruan tinggi yang bekerja di sektor informal sebesar 14.95% yang mana sektor tersebut memberikan gaji atau pendapatan yang jauh lebih kecil dibandingkan sektor formal. Selain itu menurut tabel 2 di atas, dari 49,679 angkatan kerja yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi, 11,143 diantaranya menganggur, atau sebesar 22.43%. Meskipun persentase pengangguran lulusan perguruan tinggi pada tahun 2018 lebih kecil dibandingkan persentase pengangguran yang berasal dari jenjang pendidikan yang lebih rendah. Meskipun begitu, harapan mereka saat mendaftar ke perguruan tinggi adalah untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibanding mereka yang tidak berkuliah.
Salah satu masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan tinggi di Asia maupun di Indonesia menurut World Bank adalah karena lembaga pendidikan tinggi tidak mampu merespon keinginan ‘klien’ mereka, yaitu pasar kerja (2014). Terjadi semacam diskonektifitas antara lulusan pendidikan tinggi dan permintaan tenaga kerja di pasar yang menuntut skill set tertentu. Lembaga pendidikan tinggi di Asia lebih cenderung merespon pemiliknya atau regulator, dalam hal ini pemerintah. Yang sering terjadi adalah kerangka regulasi yang rigid tidak memungkinkan lembaga pendidikan tinggi untuk merubah dirinya sendiri seiring adanya respon dari pasar kerja (World Bank, 2014).
Pendidikan berperan kunci dalam meningkatkan modal manusia suatu negara. Di negara berkembang, pendidikan dapat menghancurkan lingkaran setan kemiskinan seseorang
atau vicious circle of poverty dimana mereka terperangkap di dalamnya (Todaro & Smith, 2015). Pendidikan yang tinggi menghantarkan seseorang untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak.
Tabel 3. Rata-rata pendapatan berdasarkan Status Pekerjaan (dalam ribu)
Tahun
|
Status Pekerjaan |
2017 |
2018 |
2019(F eb) |
|
Buruh/karyawan/ |
2,74 |
2,82 |
2,791.5 |
|
pegawai |
2.6 |
9.1 | |
|
Berusaha sendiri |
1,74 |
1,83 |
1,923 |
|
3.3 |
1.7 | ||
|
Pekerja bebas |
1,33 3.8 |
1,44 5.4 |
1,386 |
Sumber: Badan Pusat Statistik (20172019), diolah.
Menurut data pada tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa pekerja yang memiliki status sebagai buruh/karyawan/pegawai yang merupakan pekerja sektor formal memiliki rata-rata gaji atau pendapatan yang jauh lebih tinggi ketibang pekerja dengan status berusaha sendiri dan pekerja bebas yang merupakan pekerja sektor informal. Maka jika dilihat melalui pendapatannya, maka sektor formal dapat dikatakan lebih layak dibandingkan sektor informal. Hal tersebut juga termasuk dalam salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals atau SDGs, lebih tepatnya tujuan kedelapan yaitu pencapaian tenaga kerja penuh (full employment) yang produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua. Mengingat masih sangat sedikit sekali penelitian yang membahas tentang pengaruh pendidikan terhadap pilihan sektor pekerjaan, Maka penting menurut penulis untuk mengisi gap pada percakapan ilmiah mengenai
penyerapan tenaga kerja pada sektor formal.
Faktanya, sektor formal tidak menutup diri bagi tenaga kerja yang berkualifikasi pendidikan rendah atau bahkan bagi tenaga kerja yang tidak mengenyam pendidikan sekalipun. Maka, berdasarkan data-data statistik dan latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dari penulisan penelitian ilmiah ini adalah untuk melihat apakah pendidikan tinggi dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk dapat terserap pada sektor formal. Selain faktor pendidikan tinggi,penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol lain yaitu usia dan jenis kelamin. Dari hasil yang akan dikemukakan pada bagian-bagian selanjutnya, maka penelitian ini akan memberikan alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah terkait lapangan pekerjaan sektor formal yang akan disajikan pada bagian akhir penelitian.
Beberapa penelitian ilmiah telah dilakukan terkait melihat hal tersebut. Penelitian ilmiah tersebut sepakat bahwa pendidikan yang lebih tinggi meningkatkan kemungkinan seseorang untuk masuk ke dalam sektor tenaga kerja formal (Aikaeli & Mkenda, 2014; Bairagya, 2012; Bolang & Osumanu, 2019; Dogrul, 2012; Gezahagn, 2017). Namun penelitian-penelitian tersebut memakai proksi lama sekolah dalam tahun untuk mengukur variabel pendidikan sehingga tidak terlihat bagaimana perbedaan kemungkinan dari berbagai jenjang pendidikan untuk masuk ke sektor formal. Maka penulis dalam penelitian ini membagi variabel pendidikan ke dalam tiga kategori, yaitu individu yang tidak bersekolah, individu yang lulus pendidikan primer yaitu SD, SMP dan SMA/SMK dan individu yang lulus pendidikan tinggi setara diploma
hingga doktor. Tujuannya adalah untuk melihat apakah individu dengan pendidikan tinggi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk masuk ke sektor kerja formal dibandingkan individu yang tidak berpendidikan tinggi.
Faktor lainnya yaitu usia. Menurut Bairagya (2012), Gezahagn (2017) dan Bolang & Osumanu (2019), semakin tinggi usia seseorang, maka akan semakin meningkatkan kemungkinan orang tersebut untuk dapat terserap pada sektor formal. Hasil tersebut terjadi karena individu dengan usia yang lebih tua menginginkan keamanan finansial karena tanggungan yang dimiliki semakin banyak, seperti anak, istri, rumah, kendaraan dan lain-lain. Dogrul (2012) membagi individu ke dalam beberapa cohort atau kelompok usia. Hasilnya kurang lebih sama dengan penelitian sebelumnya. Kelompok usia pertengahan yaitu 25-44 tahun dan usia lanjut atau 44 ke atas lebih memilih untuk bekerja di sektor formal, sedangkan usia muda 15-24 lebih memilih bekerja di sektor informal. Dogrul (2012) melakukan penelitiannya di wilayah perkotaan Turki, hasil tersebut berarti menunjukkan demografi usia muda yang tidak ingin bergantung kepada orang lain dan membuka lapangan kerjanya sendiri dengan membangun usaha-usaha kecil kreatif yang memang menjadi semangat bagi pemuda-pemuda milenial yang berpikir out of the box.
Tabel 4. Persentase Pekerja di Sektor Informal menurut Kelompok Umur
|
Kelompok Umur |
Tahun | |||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 | |
|
15-19 |
37.03 |
39.73 |
38.27 |
42.78 |
|
20-24 |
25.76 |
27.14 |
25.42 |
28.11 |
|
25-29 |
30.61 |
31.52 |
30.25 |
31.04 |
|
30-34 |
38.78 |
39.05 |
38.19 |
37.93 |
|
35-39 |
44.27 |
43.45 |
44.26 |
43.32 |
|
40-44 |
48.35 |
47.83 |
47.74 |
47.30 |
|
45-49 |
48.78 |
48.41 |
49.89 |
50.11 |
|
50-54 |
51.12 |
50.18 |
51.47 |
51.95 |
|
55-59 |
59.72 |
57.08 |
57.00 |
58.06 |
|
60 ke atas |
75.28 |
73.34 |
74.17 |
74.62 |
Sumber: Badan Pusat Statistik (20152018), diolah.
Apabila dicermati melalui data BPS, maka demografi Indonesia berbeda dengan demografi Turki yang dipaparkan oleh Dogrul (2012). Menurut data BPS pada tabel 4 di atas, persentase usia muda 15-29 tahun lebih rendah dibandingkan persentase usia menengah dan lanjut dalam hal partisipasi pada sektor informal. Penduduk usia muda di Indonesia, meskipun ada, namun tidak banyak yang memiliki jiwa enterpreneurship yang mumpuni untuk membangun bisnis-bisnis kreatif sehingga mereka lebih memilih berkerja di sektor formal. Hal ini juga sejalan dengan antusiasme usia muda dalam memasuki pasar tenaga kerja di instansi negara melalui pendaftaran CPNS yang selalu memiliki peminat yang tinggi dari tahun ke tahun.
Selain faktor usia penulis juga memasukkan variabel jenis kelamin dalam penelitian ini untuk melihat pengaruhnya terhadap kemungkinan seseorang untuk terserap ke sektor formal. Aikaeli & Mkenda (2014) menyatakan bahwa individu dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak terserap ke sektor informal dibandingkan wanita. sedangkan Bolang &Osumanu (2019) menyatakan sebaliknya, bahwa laki-laki lebih mungkin untuk terserap pada sektor formal.
Menurut data statistik pada tabel 5 dibawah, sektor formal di Indonesia
mayoritas diisi oleh tenaga kerja berjenis kelamin laki-laki. Trend dari tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan bahwa secara rata-rata tenaga kerja laki-laki berada pada sektor formal sebesar 44-46%, sedangkan tenaga kerja perempuan hanya sebatas kurang lebih 38%.
Tabel 5. Persentase Tenaga Kerja Formal menurut Jenis Kelamin
Jenis Tahun
Laki-laki 44.89 45.05 45.6646.29
Perempuan 37.78 38.16 38.6338.20
Sumber: Badan Pusat Statistik (20152018), diolah.
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini, maka selain melakukan pemaparan data-data statistik dari beberapa sumber, penulis juga menggunakan metode analisis regresi probit untuk melihat potensi dari lulusan pendidikan tinggi untuk terserap pada sektor formal.
Penelitian ini juga hanya akan berfokus pada pulau Jawa. Alasannya adalah karena pulau Jawa memiliki indikator-indikator pendidikan tinggi yang lebih advance dibanding daerah lain.Selain memiliki jumlah lembaga yang terbanyak yaitu 2,230, pulau Jawa juga membuktikan bahwa lembaga pendidikan tinggi yang mereka miliki juga berkualitas, ditandai dengan 57 lembaga pendidikan tinggi yang memiliki akreditasi A. Selain itu pulau Jawa juga memiliki jumlah mahasiswa terbesar yaitu sebanyak 4,670,465 dan jumlah lulusan sebesar 709,543. Data diambil dari publikasi statistik pendidikan tinggi oleh PDDIKTI pada tahun 2018. Maka penulis memutuskan untuk berfokus pada pulau Jawa.
METODOLOGI
Selain memaparkan data-data statistik dari beberapa sumber, untuk melihat kemampuan lulusan pendidikan tinggi untuk terserap ke sektor formal maka penulis akan melakukan analisis menggunakan regresi probit. Model probit adalah model binary outcome, digunakan ketika variabel dependen dalam suatu model bersifat pilihan atau latent variable (Gujarati, 2003). Dalam hal ini pilihannya adalah bekerja pada sektor formal atau informal. Untuk melihat pilihan tersebut, metode ini juga digunakan oleh Aikaeli & Mkenda (2014), Bairagya (2012), Bolang & Osamanu (2019), Dogrul (2012) dan Gezahagn (2017). Model regresi probit diestimasi menggunakan Maximum Likelihood Estimator (MLE), dengan model utama sebagai berikut:
y*i = βixi + ei, dimana i = 1, 2, 3,...,n (1)
dengan:
y*i adalah variabel latent yang merupakan variabel terikat dari x dan error term (ei). Sedangkan yi adalah variabel ordinal yang memiliki nilai 0 sampai dengan 1. Model probit tidak bisa diinterpretasi langsung melalui koefisiennya, melainkan diinterpretasi melalui marginal effect dari setiap masing-masing variabel sebagai berikut:
= ∂Pr (yi=1) = ∂φ(xiβ) , .
j ∂xij ∂xij ...........................' '
Dimana xj terdiri dari x1, x2, x3, dan seterusnya. Maka, model empiris untuk melihat pilihan sektor formal atau informal dapat dituliskan sebagai berikut:
Sektor*i = βo + βιEduci + β2Agei + β3Sexi + μi
Dimana:
Sektor : Dummy sektor perkejaan (formal/informal)
Educ : Kategori pendidikan seseorang
Age : Usia dalam tahun
Sex : Dummy jenis kelamin (laki-
laki/perempuan)
μ : Eror term
Adapun definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 6. Definisi Variabel
|
Variabel |
Definisi |
|
Sektor |
Dummy sektor lapangan kerja. Bernilai 1 jika individu bekerja pada sektor formal, bernilai 0 jika informal. |
|
Pendidikan |
Tiga kategori pendidikan individu. Tidak sekolah, lulus pendidikan primer dan lulus pendidikan tinggi. |
|
Umur |
Usia individu. Dalam tahun. |
|
Jenis |
Dummy jenis kelamin. |
|
Kelamin |
Bernilai 1 jika individu berjenis kelamin laki-laki, bernilai 0 jika |
|
perempuan. |
Sumber: diolah.
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah tenaga kerja di pulau Jawa. Definisi tenaga kerja itu sendiri diambil dari definisi resmi BPS, yaitu orang berusia lima belas tahun atau lebih yang melakukan kegiatan bekerja satu jam tanpa terputus selama seminggu yang lalu. Data yang digunakan untuk regresi model probit diambil dari Survey Tenaga Kerja Nasional atau SAKERNAS periode Agustus 2018. Data SAKERNAS adalah survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik sebanyak dua kali dalam setahun yaitu Februari dan Agustus. Survey ini berisi berbagai hal mengenai ketenagakerjaan. Data tersebut diolah
menggunakan bantuan software STATA 14.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Observasi pada penelitian ini adalah sebesar 92,318 yang merupakan tenaga kerja di pulau Jawa. Dari total tersebut, tenaga kerja yang bekerja pada sektor formal adalah sebesar 41,629 orang sedangkan yang bekerja di sektor informal sebesar 50,689, yang mana sektor informal memiliki persentase yang lebih besar yaitu 54.9%.Penelitian ini membagi variabel pendidikan ke dalam tiga kategori, sebesar 15,123 observasi tidak bersekolah, 66,339 observasi lainnya berpendidikan SD, SMP dan SMA/SMK atau yang sederajat, sedangkan sisanya sebanyak 10,856 berpendidika setara diploma atau yang lebih tinggi, dimana kategori ini memiliki persentase yang lebih kecil dibandingkan kategori lainnya. Jika dilihat melalui jenis kelamin, maka observasi laki-laki lebih besar daripada observasi perempuan, yaitu sebesar
63.87%.
Tabel 7. Statistik Deskriptif
|
Variabel |
Obs . |
Mi n |
M ax |
|
Sektor |
92,3 | ||
|
18 |
0 |
1 | |
|
1 (Formal) |
41,6 29 | ||
|
0 (Informal) |
50,6 89 | ||
|
Pendidikan |
92,3 18 |
1 |
3 |
|
1 (Tidak |
15,1 | ||
|
bersekolah) |
23 | ||
|
2 (Lulus pendidikan primer) |
66,3 39 | ||
|
3 (Lulus |
10,8 | ||
|
pendidikan |
56 |
|
tinggi Jenis Kelamin |
92,3 18 |
0 |
1 |
|
1 (Laki-laki) |
58,9 70 | ||
|
0 (Perempuan) Umur |
33,3 48 9231 8 |
15 |
10 0 |
|
Sumber: Keluaran software diolah. |
STATA 14, | ||
|
pendidikan primer) 3 (Lulus pendidikan tinggi) |
0.000 |
0.576 |
|
Jenis Kelamin |
0.000 |
0.047 |
|
Usia |
0.000 |
-0.010 |
|
Prob>Chi-square |
0.000 | |
|
Pseudo R2 |
0.144 | |
Sumber: Keluaran software STATA 14, diolah.
Berdasarkan hasil regresi probit yang ditunjukkan pada tabel 8 dibawah ini, didapatkan hasil secara keseluruhan, variabel independen berpengaruh terhadap pilihan sektor pekerjaan. Pernyataan ini didukung oleh nilai prob>chi-square sebesar 0.000 yang lebih kecil dari alpha 5% atau 0.05. Nilai pseudo R2 bernilai 0.144, yang berarti kombinasi dari seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 14.4%, sedangkan 85.6% lainnya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model. R2 adalah:
r2 _ [(n)(∑XY)-(∑X)(∑Y)]2
[n(∑X2)-(∑X)2][(n(∑Y2)-(∑Y)2]
(4)
Berdasarkan persamaan (4) diatas, maka sangat wajar apabila R2yang dihasilkan oleh model sangat kecil. Penelitian data mikro menggunakan jumlah observasi atau n yang relatif lebih banyak daripada penelitian yang menggunakan data makro. Observasi yang lebih besar secara matematis berarti memperbesar penyebut atau denominator dari persamaan R2 diatas dan menghasilkan R2yang lebih kecil.
Tabel 8. Regresi Probit dan Marginal Effect-nya
Variabel P>|Z| dy/dx
Base
0.000 0.150
Pendidikan
1 (Tidak bersekolah)
2 (Lulus
Tabel 8 di atas menyajikan hasil regresi probit dan marginal effect-nya. Marginal effect digunakan untuk menginterpretasi persentase probabilitas dipilihnya dummy bernilai 1 pada variabel independen.
Variabel pendidikan berpengaruh signifikan terhadap pilihan sektor pekerjaan. Pernyataan tersebut dilandasi oleh nilai p-value dari variabel pendidikan sebesar 0.000 yang mana angka tersebut lebih kecil daripada alpha 5% (0.000<0.05). Individu yang telah lulus pendidikan primer setara SD, SMP dan SMA sederajat memiliki kemungkinan 15% lebih besar untuk terserap ke sektor formal ketibang individu yang tidak bersekolah. Sedangkan individu yang telah lulus pendidikan tinggi memiliki kemungkinan 57.6% lebih besar untuk terserap ke sektor formal ketibang individu yang tidak bersekolah. Sedangkan individu yang telah lulus pendidikan tinggi memiliki kemungkinan 42.6% lebih besar untuk terserap ke sektor formal ketibang individu yang hanya lulus pendidikan primer. Hasil tersebut sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aikaeli & Mkenda (2014), Bairagya(2012), Bolang & Osumanu(2019), Dogrul (2012) dan Gezahagn (2017). Hasil ini menandakan bahwa lembaga pendidikan tinggi di pulau Jawa cukup menyesuaikan diri
terhadap permintaan dari pasar kerja. Kualitas dan skill set lulusan pendidikan tinggi di pulau Jawa cocok dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja. Selain dibuktikan dengan banyaknya lembaga pendidikan tinggi yang terakreditasi A, perguruan tinggi di pulau Jawa mengisi sembilan dari sepuluh universitas terbaik di Indonesia versi Kemenristekdikti tahun 2019. Dengan fakta tersebut tidak heran jika lulusan pendidikan tinggi di pulau Jawa memiliki kemungkinan lebih besar untuk masuk ke sektor formal.
Variabel jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap pilihan sektor pekerjaan. Pernyataan tersebut dilandasi oleh nilai p-value dari variabel pendidikan sebesar 0.000 yang mana angka tersebut lebih kecil daripada alpha 5% (0.000<0.05). Individu berjenis kelamin laki-laki memiliki kemungkinan 4.7% lebih besar untuk terserap ke sektor formal dibandingkan individu yang berjenis kelamin perempuan. Hasil ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aikaeli & Mkenda (2014), namun berbeda dengan penelitian Bolang & Osumanu (2019) yang mengatakan bahwa perempuan memiliki kemungkinan lebih besar daripada laki-laki.Bolang & Osumanu (2019) melakukan penelitiannya di Ghana, yang mana Ghana merupakan negara yang menganut Matriarki dalam berkehidupan sosial (Takyi & Gyimah, 2007). Artinya, perempuan yang berlaku sebagai pemimpin di keluarga, termasuk kegiatan bekerja juga dilakukan oleh kaum ibu. Sedangkan Aikaeli & Mkenda (2014) mengobservasi Tanzania yang memiliki struktur sosial yang sama seperti Indonesia, yaitu laki-laki sebagai pemimpin di keluarga. Kegiatan bekerja juga dilakukan oleh kaum laki-laki,
sehingga penelitian ini mendapatkan hasil yang sama dengan Aikaeli & Mkenda (2014) terkait dampak dari jenis kelamin.
Variabel usia berpengaruh signifikan terhadap pilihan sektor pekerjaan. Pernyataan tersebut dilandasi oleh nilai p-value dari variabel pendidikan sebesar 0.000 yang mana angka tersebut lebih kecil daripada alpha 5% (0.000<0.05). variabel usia memiliki koefisien yang negatif. Artinya, setiap kenaikan umur sebanyak satu tahun akan menurunkan kemungkinan seseorang untuk terserap pada sektor formal sebesar 1%. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Bairagya (2012), Gezahagn (2017), Dogrul (2012) dan Bolang & Osumanu (2019). Pekerja di sektor formal dituntut untuk memiliki produktivitas yang tinggi. Pekerja dengan usia yang lebih tinggi biasanya memiliki produktivitas yang semakin menurun (Gobel & Zwick, 2011). Maka kemungkinan individu untuk terserap pada sektor formal di pulau Jawa akan menurun seiring meningkatnya usia yang menyebabkan turunnya produktivitas.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Berdasarkan pemaparan hasil pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa individu dengan pendidikan tinggi memiliki kemungkinan lebih besar untuk masuk ke sektor formal di pulau Jawa dibandingkan individu dengan level pendidikan yang lebih rendah. Untuk dapat menikmati taraf hidup yang lebih tinggi maka seseorang dituntut untuk mengenyam pendidikan tinggi sehingga dapat bersaing dengan lebih baik di pasar tenaga kerja. Kemampuan sektor formal dalam menyerap tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi tergantung
daripada kualitas lembaga pendidikan tinggi itu sendiri. Namun menurut World Bank (2014), kondisi akreditasi lembaga pendidikan tinggi di Indonesia masih belum memadai. Calon mahasiswa pendidikan tinggi tidak dapat melihat bagaimana peringkat akreditasi A, B dan C tersebut ditentukan, sehingga mereka tidak mengetahui secara utuh kualitas lembaga yang ingin mereka masuki.
Maka saran kebijakan untuk pemerintah adalah untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia. Masih banyak lulusan SMA sederajat yang tidak bisa menikmati pendidikan tinggi, khususnya mereka yang tidak mampu secara finansial. Menurut data BPS tahun 2018, hanya sebesar 10.19% penduduk dari kalangan termiskin yang bisa belajar di pendidikan tinggi. Anggaran pendidikan adalah satu-satunya belanja yang diamanatkan dalam undang-undang yaitu sebesar 20%. Menurut Rancangan APBN tahun 2019 oleh Kemenkeu, pemerintah Indonesia memberikan bantuan beasiswa bidikmisi atau beasiswa pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari kalangan tidak mampu yang cukup besar jumlahnya, yang dalam lima tahun terakhir selalu meningkat penerimanya, dimana pada tahun 2019 terdapat 471,800 penerima bidikmisi. Selain bidikmisi, beasiswa pada jenjang pascasarjana juga diberikan oleh pemerintah melalui LPDP, yang pada tahun 2019 memberangkatkan 6,000 pelajar Indonesia untuk berkuliah di jenjang magister dan doktor, baik di dalam maupun di luar negeri. Jumlah penerima dan anggaran yang besar sebaiknya digunakan dengan tepat sasaran. Masih banyak penerima bidikmisi yang sebenarnya berasal dari keluarga kaya, maka pemerintah harus memperbaiki sistem distribusi bantuan
tersebut dan memperbaharui data penerima beasiswa tersebut setiap saat.
Dari segi kualitas, lembaga pendidikan tinggi harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya terkait kualitas lembaga tersebut. Website BANPT seharusnya bukan hanya berisi peringkat huruf akreditasi A, B maupun C, melainkan harus berisi informasi tentang mengapa ada lembaga yang berakreditas A sedangkan lembaga lain berakreditasi B dan C, apa keunggulan-keunggulan yang dimiliki sehingga lembaga tersebut mendapatkan
akreditasi A. Dengan kata lain, laman akreditasi harus berisi skor dari beberapa indikator penilaian setiap lembaga, bukan hanya peringkat akhirnya saja. Selain itu proses akreditasi juga harus dilakukan dengan lebih transparan dan kredibel (World Bank, 2014), sehingga calon mahasiswa dapat lebih mengenal dahulu lembaga pendidikan tinggi sebelum ia memasukinya, agar meminimalisir informasi yang tidak sempurna antara calon mahasiswa dan lembaga pendidikan tinggi.
Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mendukung penelitian selanjutnya untuk
menyempurnakan tulisan ini lebih jauh dengan menambahkan ruang lingkup penelitian yang semula hanya pulau Jawa menjadi level nasional, ataupun bisa dengan menelitinya di daerah lain seperti pulau Sumatera, Sulawesi maupun yang lainnya.
DAFTAR PUSTAKA
Aikaeli, J. and Mkenda, B.K. (2014).
Determinants of informal
employment: a case of Tanzania’s construction industry. Botswana
Journal of Economics, 12(2), pp.51-73. Badan Pusat Statistik, (2015-2018).
Proporsi Lapangan Kerja Informal
Sektor Non-Pertanian Menurut Kelompok Umur. [online] Available at: http://bit.ly/36XKeMP
[Accesed 17 Dec. 2019].
Badan Pusat Statistik, (2015-2018). Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan/Laki-Laki di Tingkat Perguruan Tinggi Menurut Kelompok Pengeluaran. [online] Available at: http://bit.ly/2sJuy12 [Accessed 19 Dec. 2019].
Badan Pusat Statistik, (2017). Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama. [online] Available at: http://bit.ly/2s3Z59T [Accessed 17 Dec. 2019].
Badan Pusat Statistik, (2018). Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama. [online] Available at:
http://bit.ly/2Shu78K [Accessed 17 Dec. 2019].
Badan Pusat Statistik, (2019). Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan (rupiah) Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Pekerjaan Utama. [online] Available at:
http://bit.ly/2Mdkkgl [Accessed 17 Dec. 2019].
Bairagya, I. (2012). Employment in India's informal sector: size,
patterns, growth and
determinants. Journal of the Asia Pacific Economy, 17(4), pp.593-615.
Bank, World. (2014) Indonesia’s Higher Education System: How
Responsive is it to the Labor Market?
Bolang, P.D. and Osumanu, I.K. (2019). Formal sector workers’
participation in urban agriculture in Ghana: perspectives from the Wa Municipality. Heliyon, 5(8).
DIKTI, P. D. (2018). Statistik Pendidikan Tinggi.
Doğrul, H. (2012). Determinants of formal and informal sector employment in the urban areas of Turkey. International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 4(2), pp.217-231.
El Badaoui, E., Strobl, E. and Walsh, F. (2010). The formal sector wage premium and firm size. Journal of Development Economics, 91(1), pp.3747.
Göbel, C. and Zwick, T. (2011). Age and Productivity: Sector Differences. De Economist, 160(1), pp.35-57.
Gujarati, D. (2003). Basic econometrics. 4th ed. Boston (Mass.): McGraw Hill.
Kahyalar, N., Fethi, S., Katircioglu, S. and Ouattara, B. (2018). Formal and informal sectors: is there any wage differential?. The Service Industries Journal, 38(11-12), pp.789-823.
Kementrian Keuangan, (2019). RAPBN 2019. [online] Available at:
http://bit.ly/2PHydW0 [Accessed 19 Dec. 2019].
Ketenagakerjaan, D. and Ekonomi, A.
(2002). Studi Profil Pekerja di Sektor Informal dan Arah Kebijakan ke Depan.
Nordman, C., Rakotomanana, F. and Roubaud, F. (2016). Informal versus Formal: A Panel Data Analysis of Earnings Gaps in
Madagascar. World Development, 86, pp.1-17.
Pembangunan, K. E. K. (2009). Peran Sektor Informal Sebagai Katup Pengaman Masalah
Ketenagakerjaan.
Singhari, S. and Madheswaran, S. (2017). Wage structure and wage differentials in formal and informal
sectors in India. The Indian Journal of Labour Economics, 60(3), pp.389-414.
Takyi, B. and Gyimah, S. (2007). Matrilineal Family Ties and Marital Dissolution in Ghana. Journal of Family Issues, 28(5), pp.682-705.
Todaro, M. and Smith, S.
(2015). Economic development. 12th ed. Harlow [u.a.]: Pearson.
Wubeshet, G. (2017). Gender-wise determinant of informal sector employment in Jigjiga town: A cross sectional study. Journal of Economics and International Finance, 9(7), pp.62-67.
144
Discussion and feedback