Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai
on
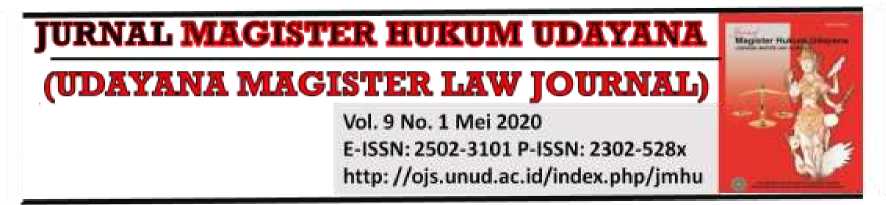
Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai
Ni Putu Pranasari Tanjung1, Muhammad Wiman Wibisana2
1Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: putupranasaritanjung@gmail.com
2Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, E-mail: wiman@abclaw.id
Info Artikel
Masuk: 13 Nopember 2019
Diterima: 10 April 2020
Terbit: 31 Mei 2020
Keywords:
Plastic Waste; internalization of environmental costs
Kata kunci:
Sampah Plastik; Internalisasi
Biaya Lingkungan
Abstract
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal),
Vol. 9 No. 1 Mei 2020, 209-221
DOI:
10.24843/JMHU.2020.v09.i01. p15
produsen kantong plastik. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tujuan yang hendak dicapai dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai serta mengetahui biaya lingkungan sebagai solusi terhadap pencemaran sampah plastik sekali pakai. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa dasar pertimbangan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai merupakan pengejawantahan dari ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan tersebut kemudian dikonkretkan dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik. Tujuannya adalah menjaga kelestarian lingkungan. Biaya lingkungan dapat diterapkan sebagai alternatif dalam penanganan sampah plastik sekali pakai. Melalui internalisasi biaya lingkungan pelaku usaha kantong plastik tetap dapat menjual kantong plastik namun, harga kantong plastik dinaikkan dari harga semula. Keuntungannya tidak diambil seluruhnya oleh pelaku usaha, namun masuk ke kas daerah yang akan digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk penanganan sampah plastik sekali pakai untuk tujuan pemeliharaan lingkungan.
-
I. Pendahuluan
Tujuan Indonesia sebagai negara berkembang adalah menyejahterakan masyarakatnya. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi dan informasi yang lengkap dan memadai merupakan langkah Pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi dijadikan langkah penting Pemerintah di dalam mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat karena langkah ini dapat merubah pola pikir serta gaya hidup masyarakatnya. Namun, secara tidak sadar hal tersebut berdampak pada budaya konsumtif masyarakat. Memang tidak setiap semua budaya ini dimiliki oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan memiliki pola hidup konsumtif yang tinggi. 1 Tingginya tingkat konsumtif masyarakat perkotaan mengakibatkan banyaknya jumlah barang yang dibeli. Barang – barang tersebut umumnya dibungkus dalam wadah plastik. Pola hidup konsumtif menjadi suatu permasalahan yang serius mengingat pola ini menyumbang sampah plastik sekali pakai yang berdampak pada pencemaran lingkungan.
Jumlah sampah yang meningkat merupakan salah satu dampak dari adanya pertambahan jumlah penduduk di perkotaan. Apabila tidak didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana, maka peningkatan jumlah sampah ini
menimbulkan permasalahan yang kompleks seperti sampah yang tidak terangkut dengan disertai pembuangan sampah yang dapat menyebabkan penyakit.2
Di lansir dari tribunbali.com, jumlah sampah plastik sekali pakai yang terbuang ke sungai tahun 2018 sampai akhir tahun 2019 mencapai 3,3 ton. Jika dirinci, timbulan sampah per harinya rata-tata 4.281 ton. 3 Ini menandakan sampah menjadi permasalahan yang rumit dalam penyelesaiannya. Jenis sampah yang selalu menjadi perbincangan karena rumitnya penanganannya adalah sampah plastik sekali pakai. Penyelesaian sampah jenis ini menimbulkan dilema. Apabila dibiarkan dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, maupun udara karena sampah ini dapat bertahan bertahun–tahun, namun di sisi lain sangatlah tidak bijak apabila sampah plastik sekali pakai dibakar karena sampah ini dapat mencemari lingkungan dengan memproduksi gas dan berdampak tercemarnya udara dan mengganggu pernapasan manusia.4
Perkembangan pembangunan sebagai akibat dari gaya hidup konsumtif masyarakat permadani yang pada umumnya bermukim di perkotaan berbanding lurus dengan sampah plastik sekali pakai yang ditimbulkan. Kota adalah tempat pusatnya pemerintahan. Sebagai pusat pemerintahan, kota memberikan gambaran seolah masa depan bangsa berada di kota yang pada akhirnya mengakibatkan ketergantungan masyarakat desa terhadap kota. Masyarakat di desa pindah ke kota dengan harapan bahwa kota menyediakan lapangan pekerjaan yan layak. Ketergantungan ini membawa pada persoalan seperti kemacetan, banjir, tata ruang yang tidak baik dan berimbas pada kerusakan lingkungan akibat pencemaran. 5
Sampah plastik sekali pakai memiliki dampak yang cukup serius. Dampak tersebut berupa kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global. Perubahan iklim terjadi dipengaruhi oleh gas rumah kaca yang meningkat konsentrasinya yang salah satu disebabkan oleh tumpukan sampah perkotaan. Gas-gas ini menyebabkan panas yang tersimpan di bumi, sehingga menyebabkan ketidakstabilan dalam lapisan atmosfer, dan akhirnya menyebabkan perubahan iklim.6
Pada tataran global, muncul inisiatif penyelamatan lingkungan hidup dengan Polluter Pays Principles. Dalam tataran legislasi nasional, telah mengadopsi Polluter Pays Principles yang ditemukan dalam ketentuan Pasal 87 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan secara prinsipnya penanggung jawab kegiatan mengakibatkan pencemaran lingkungan serta terhadap hal itu menimbulkan kerugian bagi orang lain, wajib membayar ganti kerugian. Tujuan dari Polluter Pay Principle adalah internalisasi biaya
lingkungan.7 Polluter Pays Principles menghasilkan konsep yang berkorelasi dengan konsep Good Corporate Governance yang menjadi ciri dan acuan pengelolaan korporasi modern. Nilai responsibility atau tanggung jawab merupakan salah satu komponen terkait dengan pelestarian lingkungan.
Perkembangan pengaturan Polluter Pays Principles diatur Pasal 45 yang mana ketentuan pasal ini mengandung konsep green legislation yang pada prinsipnya setiap perumusan peraturan wajib memperhatikan lingkungan. Adanya perubahan dalam ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menunjukkan adanya perubahan paradigma politik hukum Negara kearah perkembangan hukum lingkungan.
Politik hukum merupakan kehendak Negara terhadap tujuan, fungsi maupun arah suatu ketentuan hukum yang dibuat. Politik hukum dikatakan sebagai legal policy yang pembuatan maupun pembaharuan substansi hukum sesuai kebutuhan serta pengimplementasian substansi tersebut. 8 Teuku Muhammad Radhie menyatakan bahwa politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan.9
Bali sebagai bagian dari wisata global tidak terlepas dari permasalahan sampah. Penelitian terbaru mengungkapkan bahwa sampah pantai mencapai 125 ton setiap harinya. 10 Fenomena ini menggambarkan permasalahan sampah terutama sampah plastik sekali pakai harus segera diatasi. Di daerah, sebagai tindak lanjut penanganan dari kondisi sampah tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang disusul dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Dikeluarkannya peraturan daerah tersebut menjadi dasar hukum dalam pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai yang sekaligus menujukkan tindakan agresif Pemerintah dalam menanggulangi lingkungan yang tercemar karena sampah plastik sekali pakai. Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai disebutkan bahwa Setiap produsen dilarang memproduksi Plastik Sekali Pakai. Kemudian dalam Pasal 9 ayat (1) nampaknya semakin menegaskan bahwa tidak bolehnya penggunaan Plastik Sekali Pakai oleh setiap orang dan pelaku usaha.
Pelarangan atau pengurangan penggunaan plastik sekali pakai menimbulkan perbedaan sudut pandang. Sudut pandang pertama, pelarangan dan/atau pengurangan sampah plastik sekali pakai memberikan ruang pelestarian lingkungan. Pada sudut pandang kedua, kebijakan larangan penggunaan plastik sekali pakai berdampak pada berkurangnya pendapatan pelaku usaha kantong plastik. Hal ini
menjadi suatu dilema bagi Pemerintah yang mana wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan, sedangkan di lain hal juga harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang muncul dapat dirumuskan sebagai berikut pertama, Apakah tujuan yang hendak dicapai dengan pembatasan sampah plastik sekali pakai? Kedua, Apakah biaya lingkungan dapat dikenakan terhadap sampah plastik sekali pakai?
Mengenai tujuan penelitian ini adalah untuk memahami tujuan yang hendak dicapai dengan pembatasan sampah plastik sekali pakai, serta untuk memahami dan mengkaji biaya lingkungan yang dapat dikenakan terhadap sampah plastik sekali pakai.
Berdasarkan hasil penelusuran beberapa penelitian pada ruang lingkup nasional, terdapat beberapa penelitian yang meneliti persoalan yang hampir sama diantaranya Nurhenu Karuniastuti, pada tahun 2013 melakukan penelitian tentang Bahaya Plastik Terhadap Kesehatan dan Lingkungan. Kemudian Rosita Candrakirana, pada tahun 2015 melakukan penelitian tentang Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Kota Surakarta. Dari dua penelitian di atas, belum ada tulisan yang membahas tentang Politik Hukum Penanganan Sampah Plastik Sekali Pakai dengan permasalahan pertama yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam pembatasan sampah plastik sekali pakai dan permasalahan kedua yaitu biaya lingkungan yang dapat dikenakan terhadap sampah plastik sekali pakai.
-
2. Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sampah khususnya sampah plastik sekali pakai, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian hukum, artikel ilmiah hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
Perkembangan perekonomian Indonesia dan perubahan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia sejak kemerdekaan mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini kemudian mengantarkan Masyarakat Indonesia pada kebutuhan akan hukum yang mengakomodir kepentingannya yang dinamis. 11 Lebih jauh diungkapkan bahwa perkembangan masyarakat yang pesat membawa dampak perlu dipertimbangkan untuk dibenahi hukum terkait dengan pengelolaan sampah khususnya sampah plastik sekali pakai. Aspek yang perlu dipertimbangkan adalah tidak hanya terkait dengan ekonomi saja, namun korelasi politik dengan lingkungan dan kebijakan–kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah
plastik sekali pakai mengingat sampah ini menimbulkan malapetaka yaitu menyebabkan lingkungan tercemar baik itu pencemaran sumber air maupun pencemaran tanah.12
Indonesia sebagai negara berkembang mengadopsi isu–isu kesadaran lingkungan ke dalam hukum positifnya. Indonesia pernah memberlakukan Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga terakhir Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah melalui teknik pengelolaan sampah berwawasan lingkungan yang nantinya diharapkan dengan berlakunya legislasi ini memberikan tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam suatu pengelolaan sampah, memberikan kejelasan tanggung jawab pengelolaan sampah, sehingga nantinya dapat memberikan suatu kepastian hukum. Perkembangan legislasi lingkungan menunjukkan adanya sikap politik hukum Pemerintah kearah pelestarian lingkungan.
Dikeluarkannya regulasi penanganan sampah sebagai upaya untuk mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan serta melestarikan lingkungan dari timbulan sampah khususnya sampah plastik sekali pakai. Dari segi substansi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini mengikuti instrument – instrument penegakan hukum modern seperti terdapat perubahan kelembagaan, perubahan kewenangan Menteri Lingkungan, impor bahan berbahaya dan beracun, hak – hak prosedural dan pencantuman dasar hukum bagi representative action.13
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan secara prinsipnya bahwa dasar dari pembangunan ekonomi adalah pembangunan berkelanjutan yang disertai dengan wawasan lingkungan. Legislasi ini mengadopsi prinsip Good Corporate Governance dan memperkuat aspek penegakan hukum perdata, pidana, dan administratif. Di samping itu juga ketaatan dan kepatuhan dipastikan secara elaboratif dalam aspek pengawasan yang berupa pengawasan berkala, pengawasan insidentil, dan pengawasan yang dipicu oleh pengaduan masyarakat.14 Mengacu pada pemikiran tersebut, Nampak jelas bahwa lahirnya Undang – Undang ini didasari oleh Good Corporate Governance (GCG) yang menunjukkan komitmen keberpihakan Pemerintah terhadap lingkungan hidup yang diperkenalkan konsep green legislation yaitu pengelolaan lingkungan wajib diperhatikan dalam setiap pembuatan peraturan. Indonesia juga memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Di tataran peraturan daerah, Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian disusul dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
Mengacu pada legislasi terkait dengan penanganan sampah plastik sekali pakai, nampak jelas bahwa adanya kepentingan Pemerintah di dalam menanggulangi sampah plastik sekali pakai agar dapat mengadopsi Polluter Pays Principle dalam tataran legislasinya, sehingga dengan kata lain politik hukum Indonesia mengarah pada penanggulangan pencemaran lingkungan melalui regulasi larangan pemakaian plastik sekali pakai sebagaimana tercermin dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.
Kantong plastik adalah kantong yang digunakan untuk mengangkat atau mengakut barang. Namun dengan adanya aturan mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai membawa konsekuensi bahwa produsen dilarang memproduksi plastik sekali pakai. Pasal 7 ayat (1) ditentukan produsen dilarang memproduksi Plastik Sekali Pakai. Pasal 9 ayat (1) nampaknya semakin menegaskan bahwa tidak bolehnya penggunaan Plastik Sekali Pakai oleh setiap orang dan pelaku usaha. Pertimbangan dari dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai adalah untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Secara prinsipnya, diaturnya sampah dalam beberapa peraturan baik peraturan nasional maupun peraturan daerah menandakan sampah dapat menyumbang efek negatif bagi ekonomi, sosial, maupun lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Beranjak dari penyataan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dari adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai ini adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan spesifikasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 yaitu:
-
a. Menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup
-
b. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan Plastik Sekali
Pakai.
-
c. Mencegah pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Plastik Sekali Pakai,
-
d. Menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem,
-
e. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan Plastik Sekali Pakai,
-
f. Menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan Plastik Sekali Pakai, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik; dan
-
g. Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.
Tujuan yang hendak dicapai sebagaimana termuat dalam Pasal 2 tersebut memperlihatkan keinginan Pemerintah Daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dari penimbunan sampah plastik. Namun, Pasal 2 dapat disinkronisasikan dengan instrument ekonomi lingkungan melalui pengenaan internalisasi biaya lingkungan. Internalisasi biaya lingkungan sangat berpotensi untuk diterapkan karena melalui
biaya lingkungan, negara mendapatkan pemasukan dan dampak lingkungan dapat ditanggulangi.
Sampah sebagai sebuah dampak konsumsi diasosiasikan sebagai sebuah ekses negatif dari sisa kegiatan manusia. Dalam terminologi lingkungan, hal ini sering dinisbatkan pada eksternalitas yang sifatnya negatif. Negara menguasai dan mempergunakan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat melalui pembangunan berwawasan lingkungan. Namun faktanya, pada era ini dihadapkan pada 2 (dua) permasalahan antara lain populasi penduduk yang kian meningkat namun sumber daya alam yang terbatas. Hal inilah yang menimbulkan ketidakseimbangan yang mengarah kepada eksternalitas negatif tersebut. Eksternalitas negatif muncul bilamana suatu produksi melebihi level efisiensi sosialnya yang terwujud ketika harapan masyarakat akan suatu produk terlampaui jumlahnya oleh keberadaan produk tersebut. Menurut para ahli ekonomi, pencemaran lingkungan adalah bentuk dari contoh klasik dari eksternalitas.15
Pendekatan Pemerintah dalam menangani pencemaran, cenderung menggunakan pendekatan yang sifatnya command and control atau yang diterjemahkan sebagai pola pendekatan atur dan awasi, hal ini terwujud dari banyaknya peraturan yang terkait dengan pencemaran lingkungan. Hal inilah yang dikritik Otto Soemarwoto yang menyatakan bahwa undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan lingkungan sangatlah lengkap. Namun tidak ada yang menghiraukan, baik aparat penegak hukum pemerintah maupun masyarakat, sehingga kerusakan dan pencemaran lingkungan terus saja terjadi.16
Fenomena ini mempengaruhi pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut membutuhkan biaya dalam mengatasi lingkungan yang sudah tercemar. Terdapat salah satu opsi strategis dalam membiayai pemulihan lingkungan adalah dengan pendanaan lingkungan. Pendanaan lingkungan adalah dana yang dianggarkan untuk pelestarian lingkungan sesuai peraturan yang berlaku. Sampah plastik sekali pakai sebagai salah satu penyebab pencemaran lingkungan dapat dikenakan cukai. Cukai adalah pungutan terhadap barang yang memiliki ciri khas tertentu yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pungutan ini menjadi pemasukan bagi negara dalam membayar biaya yang dikeluarkan negara di samping dari laba BUMN dan sektor pajak.17 Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang pada prinsipnya bahwa cukai dapat dikenakan terhadap barang yang menimbulkan efek negatif bagi lingkungan hidup dan masyarakat dalam pemakaiannya.
Pengenaan cukai terhadap plastik sekali pakai memiliki tujuan sebagai penerimaan negara.18 Ini berarti plastik sekali pakai berperan terhadap masuknya uang ke kas daerah sebagaimana arti penerimaan negara dalam Pasal 1 angka 9 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Cukai dinaikkan oleh Pemerintah hampir setiap tahunnya sebagai langkah kebijakan fiscal, sehingga adanya kenaikan pada tarif cukai dapat memberikan peningkatan dalam penerimaan negara. Tindakan ini merupakan serangkaian kebijakan pemerintah dalam mengurangi efek yang ditimbulkan dari barang – barang yang memenuhi kriteria pengenaan cukai tersebut.
Dikaitkan dengan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kantong plastik sekali pakai dapat mengadopsi kebijakan fiscal cukai. Internalisasi Biaya lingkungan dapat dikenakan terhadap penanganan jumlah sampah plastik sekali pakai. Biaya lingkungan adalah biaya sukarela perusahaan dalam mentaati kebijakan Pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dimana perusahaan menjalankan bisnisnya.19 Biaya lingkungan juga dapat didefinisikan sebagai pengeluaran perusahaan sebagai dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan berupa pencemaran dengan menurunnya kualitas lingkungan akibat proses produksi bisnis yang dilakukan.20 Biaya ini menjadi transformasi dari Polluter Pays Principle.
Internalisasi biaya lingkungan inheren dengan konsep Polluter Pays Principle. Prinsip ini menggema dalam beberapa peraturan lingkungan yang berarti kewajiban pencemar untuk membayar kerugian terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan.21 Prinsip ini menjadi konsep penting yang tertuang dalam Deklarasi Rio dinyatakan prinsipnya bahwa Pemerintah wajib untuk melakukan internalisasi biaya lingkungan melalui pendekatan pencemar dimana perusahaan wajib untuk membayar biaya akibat polusi produksi yang ditimbulkan dengan memperhatikan kepentingan publik tanpa mengganggu investasi dan perdagangan internasional. Bentuk manifestasi dari Polluter Pays Principle adalah extended producer responsibility. Konsep ini dinyatakan bahwa Produsen dalam memproduksi barang bertanggung jawab penuh terhadap setiap hasil produksinya.22
Metode Instrumen pendekatan pasar dapat memberikan suatu peluang kepada perusahaan untuk berpartisipasi dengan caranya sendiri untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan.23 Instrument pasar yang dapat membantu mengontrol polusi
yang diakibatkan oleh sampah plastik sekali pakai adalah pajak polusi, subsidi, dan sistem uang muka/kembalian (Deposit/Refund).
Pajak polusi adalah pungutan yang dikenakan kepada perusahaan sumber polusi yang besarnya bervariasi tergantung pada jumlah pengotoran lingkungan yang dilakukannya.24 Pemberian harga pengotoran ini dapat diterapkan dengan dua cara yaitu pungutan limbah yang dinilai secara langsung terhadap pengotorannya, pungutan produksi yang dikenakan pada produksi yang menimbulkan polusi, pungutan pemakai (user change) yang dikenakan pada pemakai sumber alam, dan biaya administrasi yang digunakan untuk jasa lingkungan seperti bahan kimia yang berbahaya. Indikator dari pengenaan pajak polusi ini adalah tergantung pada lingkungan yang dipengaruhi dan sifat permasalahannya.
Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan untuk mengurangi jumlah polusi atau untuk merencanakan pengurangan di masa depan. 25 Subsidi memberikan stimulus kepada perusahaan sumber polusi untuk meningkatkan kegiatan pengurangan polusi. Metode subsidi ini dilakukan dengan pembayaran langsung, program bantuan, pinjam dengan bunga rendah atau pembebanan pajak.
Sistem Uang Muka/Kembalian (Deposit/Refund) mempunyai 2 (dua) komponen. Mengenakan uang muka untuk kerusakan lingkungan potensial. Uang muka ini kemudian dikembalikan untuk tindakan yang positif seperti mengembalikan produk untuk dibuang dengan cara yang semestinya atau di daur ulang.26
Internalisasi biaya lingkungan hidup pada prinsipnya adalah biaya lingkungan yang diintegrasikan dengan biaya sosial di dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan sumber alam. 27 Pengenaan internalisasi biaya lingkungan hidup dapat digunakan sebagai langkah dalam penanganan sampah plastik sekali pakai. Alasan dari pentingnya internalisasi biaya berangkat dari fakta penggunaan sumber daya alam berdampak pada kegiatan pasar, sehingga terdapat pihak yang dirugikan dari kegiatan penggunaan sumber daya tersebut. Dampak ini di istilahkan sebagai ekternalitas negatif (negative externality).
Internalisasi biaya lingkungan sepatutnya dimasukkan dalam setiap produksi kantong plastik sekali. Dengan pengenaan biaya lingkungan, harga setiap kantong plastik dinaikkan. Di dalam memproduksi plastik sekali pakai, produsen bertanggung jawab penuh, sehingga out put plastik sekali pakai yang dihasilkan adalah plastik yang mudah di daur ulang. Dalam selembar kantong plastik sekali pakai yang diproduksi, terdapat hak asasi atas lingkungan yang sehat. Dengan kata lain bahwa keuntungan dari penjualan kantong plastik sekali pakai tidak diambil sepenuhnya oleh produsen atau pelaku usaha, namun dimasukkan dalam pajak penerimaan daerah untuk biaya pengelolaan lingkungan. Dengan pengenaan biaya lingkungan, diharapkan sampah plastik sekali pakai dapat dikelola dengan baik, sehingga lingkungan yang sehat sebagaimana yang dijewantahkan di dalam UUD NRI 1945 dapat tercapai.
-
4. Kesimpulan
Dasar pertimbangan dikeluarkannya Pergub Bali Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai merupakan pengejewantahan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Dikeluarkannya kebijakan pengelolaan sampah tersebut melihat pada dampak negatif yang ditimbulkan apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Dikeluarkannya aturan daerah mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai menunjukkan politik hukum yang mengarahkan produk hukumnya ke ranah pelestarian lingkungan.
Internalisasi biaya lingkungan dapat digunakan sebagai sarana dalam penanganan sampah plastik sekali pakai. Biaya lingkungan sepatutnya dimasukkan dalam produk kantong plastik. Dengan memasukkan biaya lingkungan, harga kantong plastik dinaikkan dari harga sebelumnya. Keuntungan dari penjualan kantong plastik sekali pakai tidak sepenuhnya diambil oleh pelaku usaha, namun dimasukkan dalam pajak penerimaan daerah yang akan digunakan untuk pengelolaan sampah plastik sekali pakai dengan tujuan pemeliharaan lingkungan.
Daftar Pustaka
Buku
Erwin, M. (2015). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama.
Irawan, C. (2011). Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.
Joga, N. (2017). Gerakan Kota Hijau 2.0: Kota Cerdas Berkelanjutan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Nehen, K., (2017). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Denpasar: Udayana University Press.
Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2015). Microeconomics. Boston: Pearson
Santosa, M., A., (2016). Alam Pun Butuh Hukum & Keadilan. Jakarta Timur: As@-Prima Puskata.
Soemarwoto, O. (2001). Atur-diri-sendiri: paradigma baru pengelolaan lingkungan hidup: pembangunan ramah lingkungan: berpihak pada rakyat, ekonomis, berkelanjutan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Jurnal
Agustia, D. (2010). Pelaporan biaya lingkungan sebagai alat bantu bagi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 1(2), 190-214. http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v1n2.p190-214
Darma, M. E., & Redi, A. (2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 127. http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2236
Gunawan, E. (2012). Tinjauan Teoritis Biaya Lingkungan Terhadap Kualitas Produk dan Konsekuensinya Terhadap Keunggulan Kompetitif Perusahaan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 1(2), 47-50.
Karuniastuti, N. (2013). Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan. Swara Patra, 3(1), 6-14.
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal),
Vol. 9 No. 1 Mei 2020, 209-221
Muhdar, M. (2009). Eksistensi polluter pays principle dalam pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 21(1), 67-80. https://doi.org/10.22146/jmh.16247
Puteri, I., Aliya, R., & Muhammad, S. A. (2018). Penerapan Plastic Deposit Refund System sebagai Instrumen Penanggulangan Pencemaran Limbah Plastik di Wilayah Perairan Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 4(2), 129-150. http://dx.doi.org/10.38011/jhli.v4i2.64
Qodriyatun, S. N. (2014). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008. Jurnal Aspirasi, 5(1), 21-33.
https://doi.org/10.22212/aspirasi.v5i1.450
Radhie, T., M. (1973) dalam Hakim, D., A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), April-Juni. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592
Triono, D. (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal), 1(1), 124-129.
Wibisana, W. (2018). Perspektif Politik Hukum Dan Teori Hukum Pembangunan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 4(1), 96-113. http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13663
Wijayanti, W. P. (2013). Peluang pengelolaan sampah sebagai strategi mitigasi dalam mewujudkan ketahanan iklim kota Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota, 9(2), 152-162. https://doi.org/10.14710/pwk.v9i2.6531
Disertasi
Artiningsih, N. K. A. (2008). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang) (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
Lestari, P. (2010). Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sebagai Upaya Pemerintah dalam Pencapaian Target Penerimaan Cukai Negara di Wilayah Surakarta (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
Online/World Wide Web:
Beritabali.com. (2018). Badung Produksi 286 Ton Sampah Per Hari, 40% dari Sektor Pariwisata. Retrieved from
https://beritabali.com/read/2018/11/23/201811230007/Badung-Produksi-286-Ton-Sampah-Per-Hari-40-dari-Sektor-Pariwisata.html diakses 20 Agustus 2019.
Maulana, A. (2018). Sampah dan Perilaku Konsumtif. Retrieved from https://www.kompasiana.com/akmal37114/5beabc6b6ddcae22b8366f83/sam pah-dan-prilaku-hidup-konsumtif?page=all diakses 30 Agustus 2019.
Tribun Bali. (2019). Hasil Penelitian Sampah Plastik di Bali, 33 Ton Terbuang ke Aliran Sungai. Retrieved from https://bali.tribunnews.com/2019/11/19/hasil-penelitian-sampah-plastik-di-bali33-ton-terbuang-ke-aliran-sungai?page=2 diakses 7 Maret 2020.
Yusuf, N., F. (2019). 1000 Personel DLHK Badung Bersihkan Sampah Pantai. Retrieved from https://bali.antaranews.com/berita/136970/1000-personel-dlhk-badung-bersihkan-sampah-pantai diakses 30 Agustus 2019.
Peraturan Perundang – undangan
Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059
Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851
Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5
Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 97
221
Discussion and feedback