Dual Mediation : Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice
on
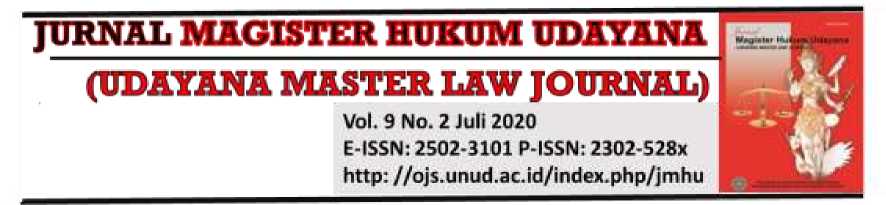
Dual Mediation : Penyelesaian Perkara Lingkungan Hidup yang Melibatkan Korporasi Sebagai Pelaku Melalui Pendekatan Restorative Justice
Ach. Faisol Triwijaya1, Yaris Adhial Fajrin2, Chintya Meilany Nurrahma3
1Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Email: achfaisolt@yahoo.com
2Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Email: yarisroyaadhifa@gmail.com
3Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Email:
chintya.meilany.nurrahma-2018@fh.unair.ac.id
Info Artikel
Masuk: 26 Oktober 2019
Diterima: 12 Juli 2020
Terbit: 31 Juli 2020
Keywords:
Environmental Crime;
Corporation; Penal Reform;
Restorative Justice; Mediation
Kata kunci:
Tindak Pidana Lingkungan, Korporasi; Pembaruan Hukum Pidana; Mediasi
Corresponding Author:
Ach. Faisol Triwijaya, Email: achfaisolt@yahoo.com
Abstract
The use of the environment today is very important in order to provide benefits to the community. Utilization must also be balanced with good management and avoid damage. Anomaly in the use of the environment that causes widespread damage occurs where there is a role of the corporation as the main actor. The presence of the PPLH Law has not been able to be a solution amid the chaotic environment utilization that is in line with the damage because the existing legal instruments are not able to overcome the problem. This paper has a purpose to analyze the weakness in the resolution of criminal acts of the environment and the extent to which restorative justice is able to overcome the conflict due to environmental criminal act between the corporation and the community. This research method uses normative legal research methods with a conceptual approach. This study obtained the first result, the legal instrument in the PPLH Law has not shown success where there is still widespread environmental destruction today. Second, through the restorative justice approach it is expected to be able to reduce the number of environmental criminal acts by corporations using the dual mediation pattern, namely the merging of the concepts of civil case mediation and penal mediation so as to create a balance pattern that is in line with the direction of the renewal of national criminal law.
Abstrak
Pemanfaatan lingkungan hidup dewasa ini amat penting dilakukan guna memberikan manfaat terhadap masyarakat. Pemanfaatan harus pula diimbangi dengan pengelolaan yang baik dan menghindari kerusakan. Anomali pemanfaatan lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan marak terjadi, di mana terdapat peran korporasi sebagai aktor utama. Kehadiran UU PPLH masih belum mampu menjadi solusi di tengah carut marutnya pemanfaatan lingkungan yang sejalan dengan kerusakan karena instrumen hukum yang ada tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisa kelemahan dalam penyelesaian tindak pidana
DOI:
10.24843/JMHU.2020.v09.i02.
p.14
lingkungan hidup dan sejauh mana restorative justice mampu mengatasi konflik akibat tindak pidana lingkungan hidup antara korporasi dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini memperoleh hasil pertama, instrumen hukum di UU PPLH belum menunjukkan keberhasilan di mana masih maraknya kejadian pengrusakan lingkungan hidup hingga saat ini. Kedua, melalui pendekatan restorative justice diharapkan dapat menekan angka tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi menggunakan pola dual mediasi yaitu penggabungan konsep mediasi perkara perdata dan mediasi penal sehingga dapat menciptakan pola keseimbangan yang selaras dengan arah pembaruan hukum pidana Nasional.
Indonesia sebagai negara yang memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan, berpengaruh terhadap potensi-potensi besar dari alam yang dimilikinya. Tak salah jika Indonesia dijuluki sebagai negeri zamrud khatulistiwa, karena tidak hanya keindahannya yang menawan tetapi juga memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang besar, mulai dari sumber daya hutan, laut, mineral, dan udaranya. Kekuatan SDA yang melimpah ini merupakan faktor yang menguntungkan sekaligus menjadi faktor pengancam bagi kehidupan masyarakatnya. Menguntungkan karena itu menjadi modal untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat jika dapat dimanfaatkan sebaik dan seoptimal mungkin. Tetapi menjadi faktor pengancam jika dalam hal pemanfaatannya tidak dilakukan secara bijaksana dan tanpa memperhitungkan kelanggsungannya untuk kepentingan generasi selanjutnya. Secara prinsip pemanfaatan kekayaan alam Indonesia harus ditujukan kepada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat pada masa sekarang hingga generasi mendatang, dan itu tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 33 ayat (2).
Seiring berjalannya waktu, usaha pemanfaatan SDA tidak dapat dipisahkan dari keberadaan korporasi sebagai eksekutor pemanfaatan di samping keberadaan negara/pemerintah sebagai regulator atau pembuat kebijakan. Tidak dapat dinaikkan korporasi menjadi aktor utama memanfaatkan SDA sebagai anugerah bangsa Indonesia yang nantinya digunakan untuk kepentingan orang banyak. Korporasi memiliki tugas untuk mengeskstraksikan SDA ke dalam bentuk pendapatan agar mudah dinikmati.1 Selain itu, korporasi juga memiliki peran penting dalam proses pembangunan di bidang ekonomi dan sistem kehidupan lainnya, melalui pendapatan negara dalam bentuk pajak dan devisa, serta semakin membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat luas.2
Potensi SDA yang melimpah secara logika sederhana, akan berpengaruh juga kepada kesejahteraan rakyatnya. Akan tetapi sebuah anomali terjadi saat ini ketika negara
kaya akan SDA justru hidup dalam belenggu kemiskinan. Negara dan corporate seolah menjadi “predator” yang mematikan di mana praktik eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam ketika sudah berakhir yang tersisa hanyalah rusaknya alam dan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. 3 Kerusakan-kerusakan akibat pemanfaatan SDA juga melibatkan korporasi, sehingga memunculkan pendapat bahwa korporasi memiliki manfaat dalam pemanfaatan SDA namun korporasi juga berperan dalam rusaknya lingkungan sebagai ekses dari pemanfaatan SDA.
Tujuan berdirinya suatu corporate pada umumnya adalah untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi, termasuk corporate yang memanfaatkan kekayaan alam sebagai bagian dari usahanya juga bertujuan mencapai keuntungan secara ekonomi. Tujuan corporate mencapai keuntungan ekonomi berdampak kepada pemanfaatan kekayaan alam yang menyebabkan kerusakan. Hardin dalam karyanya the tragedy of the commons memperlihatkan ekonomi menjadi alasan keputusan manusia baik individu maupun kelompok dalam memanfaatkan common property. 4 Pemanfaatan common property karena sifatnya bebas untuk memenuhi kepentingan setiap orang termasuk corporate berakibat kepada pemanfaatan yang sewenang-wenang dan sebanyak mungkin untuk memenuhi hasrat memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Pada akhirnya fokus dan tujuan semata hanya keuntungan ekonomi akan menjadi pemacu eksploitasi common property secara berlebih yang merusak lingkungan.
Faktor ekonomi juga menjadi alasan corporate memilih jalan pintas dalam pemanfaatan lingkungan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, misalnya pembukaan lahan pertanian kelapa sawit melalui pembakaran lahan karena dianggap secara biaya lebih murah. Corporate seolah tidak memikirkan dampak yang dialami masyarakat sekitar. Contoh corporate yang merusak lingkungan hidup terjadi pada kasus eksploitasi emas di Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya, disertai sistem pembuangan limbah langsung ke laut tanpa pengolahan terlebih dahulu, yang berdampak pencemaran dan kerugian masyarakat berupa wabah penyakit minamata. 5 Kasus tersebut telah menyita perhatian sebagaian besar masyarakat Indonesia karena dampak yang sistemik. Adapula pembakaran hutan yang bertujuan pembukaan lahan baru yang menyebabkan kebakaran hutan. Tercatat Pada tahun 2017 di Provinsi Riau telah terjadi kebakaran hutan seluas 1.053 hektar, kemudian di Kalimantan lebih besar seluas 11.127,49 hektar.6 Beberapa contoh kasus pengrusakan lingkungan demi kepentingan korporasi telah berdampak sistemik yang merugikan bagi masyarakat sehingga diperlukan instrument hukum untuk menertibkan hal tersebut.
Pemberlakukan Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH) adalah amanat UUD 1945 pasal 28H bagi masyarakat menikmati lingkungan hidup yang baik. Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan :
“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”
Kehadiran UU PPLH merupakan kebijakan hukum sebagai reaksi atas kualitas lingkungan hidup yang saat ini menunjukkan trend menurun yang mengancam kehidupan masyarakat dan mahluk hidup lainnya.7 Lingkungan hidup yang sehat dan terjaga merupakan aset jangka panjang khususnya bagi keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang. Dikenal beberapa asas dalam UU PPLH yang bertujuan untuk kelanjutan hidup masyarakat Indonesia. Materi muatan UUPLH pada prinsipnya lebih baik daripada materi muatan undang-undang lingkungan hidup sebelumnya dengan pengaturan sejumlah asas-asas hukum, menyesuaikan dengan perkembangan konvensi-konvensi Internasional yang diratifikasi oleh Indonesia. Di sisi lain UU PPLH pun masih memiliki kelemahan dari segi ketentuan pidana. UU PPLH masih dijiwai oleh tujuan-tujuan pemidanaan yang berhaluan pembalasan, sehingga berimplikasi kepada perlindungan masyarakat melalui instrumen hukum pidana tidak tercapai. 8 Terlebih permasalahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dirasakan sangat luas dampaknya oleh masyarakat termasuk yang tidak berada di sekitar lingkungan hidup yang tercemar. Fakta masih banyak terjadi pengrusakan lingkungan hidup demi kepentingan korporasi menjadi gambaran bahwa UU PPLH masih belum efektif dan memiliki kelemahan.
Dewasa ini perkembangan pembaruan hukum pidana Nasional telah mengarah kepada gagasan restorative justice sebagai ekses dari retributive justice. Gagasan restorative justice merubah cara kerja sistem peradilan pidana yang sebelumnya tersentral kepada pelaku menjadi lebih seimbang dengan terlibatnya korban dan masyarakat dalam pola komunikasi. Pola komunikasi yang terbangun memposisikan sistem peradilan pidana sebagai sistem penyelesaian konflik. 9 Gagasan restorative justice menekankan kepada upaya pemulihan atas dampak yang disebabkan oleh tindak pidana. Tetapi, pendekatan restorative justice dalam perkara tindak pidana lingkungan tersebut terbentur oleh ketentuan Pasal 85 ayat (2) di mana tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dilakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemudian adapula ketentuan pada bagian Penjelasan Umum angka 6 yang menasbihkan UU PPLH menganut asas premum remidium. Tentunya perlu disadari bahwa ketentuan undang-undang tersebut kontradiktif dengan semangat pembaruan yang mengarah kepada restorative justice. Memperhatikan kontradiktif antara hukum yang belaku sekarang dengan semangat pembaruan hukum pidana tersebut, maka
perlu untuk dipikirkan konsep-konsep terbaru guna menyelesaikan permasalahan yang berkembang saat ini.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisa kelemahan yang masih ada di dalam prosedur penyelesaian tindak pidana lingkungan yang menggunakan instrumen UU PPLH. Kemudian menilai sejauh mana konsep restorative justice mampu menyelesaikan konflik antara pelaku dan masyarakat yang timbul karena tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mengkaji peraturan terkait lingkungan hidup yaitu UU PPLH. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu UUD 1945 dan UU PPLH. Kemudian menggunakan pendekatan konseptual yaitu konsep-konsep terkait penyelesaian konflik akibat pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Sumber bahan hukum primer didapatkan dari peraturan perundang-undangan terkait dan sumber bahan hukum sekunder dari literatur-literatur hukum terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum lakukan menggunakan metode inventarisasi bahan hukum yang terkait penelitian ini. Metode analisis yang gunakan adalah metode interpretasi secara sistematis dan gramatikal.
-
3. Hasil dan Pembahasan
-
3.1 Kelemahan Penyelesaian Tindak Pidana Lingkungan Oleh Korporasi di Indonesia Saat Ini
-
-
1) Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana, Khususnya di Bidang Lingkungan
Secara prinsip subjek hukum pidana hanya dapat dimiliki oleh manusia (naturlijk person) karena hal ini berhubungan dengan pelaksanaan sanksi pidana terhadap subjek hukum pidana. Selain masalah pelaksanaan pidana, subjek hukum pidana hanya dapat dimiliki oleh manusia berhubungan juga dengan pertanggungjawaban pidana, kaitannya dengan mens rea atau dapat juga disebut criminal responsibility. Perancang undang-undang pada awalnya menempatkan hanya manusia sajalah yang dapat ditempatkan sebagai subjek hukum suatu perbuatan pidana. Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah perumusan Pasal 59 KUHP, dan dengan adanya frasa “hij die” yang berarti “barang siapa”. Akan tetapi perkembangan kejahatan hingga saat ini menunjukkan bahwa tidak hanya manusia yang melakukan tindak pidana, melainkan korporasi pun juga bisa melakukannya. Hingga saat ini di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan (yang memiliki ketentuan pidana didalamnya) telah menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, meskipun redaksional yang digunakan untuk merujuk korporasi sebagai subjek hukum berbeda-beda antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. UU PPLH sendiri menggunakan istilah badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
Korporasi ditempatkan sebagai subjek hukum pidana didasarkan kepada relitas di mana korporasi sering memiliki peran dalam skema kejahatan. Steven Box 10 mengemukakan terdapat tiga ruang lingkup keterlibatan corporate dalam kejahatan dilihat dari seberapa jauh peran corporate yaitu :
-
1. Crimes for corporation : Perusahaan ini dibentuk untuk suatu usaha, namun di tengah berjalannya usaha korporasi melakukan tindak pidana guna memperoleh keuntungan secara instan;
-
2. Criminal corporation : Perusahaan dengan tipe seperti ini semata-ata memang dibentuk untuk melakukan kejahatan;
-
3. Crimes against corporation : Tipe seperti ini bukan korporasi sebagai pelaku akan tetapi korporasi sebagai korban tindak pidana seperti penggeleapan keuangan perusahaan;
Crimes for corporation sebagaimana yang dikemukakan oleh Steven Box di atas, yang kemudian popular disebut dengan istilah corporate crime (kejahatan korporasi), di mana oleh Munir Fuady11 diartikan sebagai suatu tindakan yang berupa tidak berbuat atau berbuat oleh badan hukum atau perkumpulan melalui organ-organnya, yang diharapkan membawa keuntungan atau membawa keuntungan bagi kelompok atau badan hukum tersebut, tetapi dilakukan dengan cara melanggar hukum, yang membawa kerugian untuk masyarakat secara meluas.
Suatu kejahatan korporasi memiliki karakteristik, diantaranya yaitu kejahatan tersebut berakibat negatif kepada masyarakat atau membawa akibat negatif yang meluas kepada orang lain. 12 Kejahatan tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengambil keuntungan sebanyak banyaknya dengan pengorbanan/pengeluaran yang sedikit-dikitnya. Mardjono Reksodipuro menggolongkan kejahatan korporasi ini sebagai bagian dari White Collar Crime (WCC), di mana WCC tersebut diperkenalkan oleh Sutherland yang diartikan sebagai kejahatan yang pelakunya berasal dari orang/kalangan tingkat/kelas sosial ekonomi pada tataran atas, dan berhubungan dengan jabatan yang diembannya. 13 Mengenai akibat/korban kejahatannya pun bersifat luas, artinya tidak hanya masyarakat saja tetapi dapat pula menjadikan negara sebagai korbannya.14 Melihat luasnya cakupan korban dari kejahatan korporasi atau WCC tersebut, maka negara-negara internasional beberapa kali membahas persoalan tersebut dalam beberapa pertemuan, misal pada kongres PBB ke-5 dan ke-6 mengenai The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders, yang mengungkap bahwa Crime As Business dalam bidang bisnis atau industri merupakan bentuk kejahatan yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir serta pelakunya mempunyai kedudukan sosial yang terpandang.
Selain itu, memperhatikan Article 1 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000 (TOC) yang ditujukan untuk memajukan kerjasama pemberantasan dan pencegahan tindak pidana transnasional terorganisasi secara lebih
efektif. Bahkan khusus untuk kejahatan di bidang lingkungan, kejahatan dalam bentuk illegal disposal of dangerous waste sudah menjurus di berbagai negara ke arah kejahatan transnasional yang terorganisir dan telah dibahas secara serius dalam The World Ministerial Conference on Organized Transnational Crimes di Napoli pada 21-23 Nopember 1994. 15 Memperhatikan penjelasan singkat tersebut, maka kejahatan korporasi dalam perkembangannya saat ini memiliki kualifikasi: terorganisir, lintas negara, korban yang luas, dan dilakukan oleh pelaku dari kalangan menengah ke atas.16
Hukum pidana positif Indonesia sebagaimana yang secara umum tertuang di KUHP, belum mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, tetapi di luar KUHP ada berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengakui dan mendudukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana selain manusia. 17 Muladi dan Diah Sulistyani 18 menyebutkan ada sekitar 62 perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi. Terdapat ada beberapa peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup yang memasukkan korporasi sebagai subjek hukum, yaitu diantaranya adalah:
Tabel 1 : Korporasi sebagai subjek hukum pidana di berbagai undang-undang
|
Peraturan |
Pasal |
|
UU. No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
Pasal 1 angka 32 jo. Pasal 116 |
|
UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan |
Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) serta Penjelasannya |
|
UU. No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan |
Pasal 1 angka 21 dan angka 22 |
|
UU. No. 36 Tahun 2016 tentang Perkebunan |
Pasal 1 angka 15 |
|
UU. No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. UU. No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU. 31 Tahun 2004 |
Pasal 1 angka 14 dan angka 15 |
|
UU. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi |
Pasal 56 |
|
UU. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara |
Pasal 163 |
|
UU. No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan |
Pasal 1 angka 38 |
Sumber: Diolah dari berbagai Undang-undang yang masih berlaku di Indonesia
Tabel di atas menggambarkan bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana, tidak hanya berlaku di UU PPLH saja, tetapi beberapa undang-undang terkait bidang
lingkungan lainnya juga sudah mengaturnya. Bahkan diantaranya telah secara jelas merinci, definisi “setiap orang” yang diartikan sebagai tidak hanya orang
perseorangan, tapi juga korporasi, serta definisi “korporasi” sebagai badan hukum dan/atau badan usaha. Rumusan tersebut dipandang telah diakomodir juga oleh cita-cita pembaruan hukum pidana Indonesia, sebagaimana tertuang di dalam Rancangan KUHP (RKUHP) Nasional draft tahun 2019 Pasal 46 yang berbunyi:
-
(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana;
-
(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hal tersebut paling tidak memberikan gambaran bahwa usaha memperluas subjek hukum pidana hingga korporasi masuk didalamnya, telah menjadi bagian dari cita-cita pembaruan hukum pidana nasional, atau dengan kata lain searah dan relevan dengan arah pembaruan. Sehingga dalam pidana dan pemidanaannya pun tidak boleh terlepas dari arah pembaruan hukum pidana nasional, termasuk diantaranya adalah mengenai tujuan pemidanaan, dan juga mengenai bagaimana cara penyelesaian perkaranya (tidak terkecuali pula dalam penyelesaian perkara di bidang lingkungan hidup).
Ditinjau dari filsafat hukum, menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari “untuk apa” hukum itu ada, khususnya regulasi tentang korporasi sebagai subjek hukum. Kerangka berfikir filsafat “untuk apa” suatu aturan dibuat atau lazimnya disebut dengan aksiologi, yang berkutat kepada pertanyaan untuk apa aturan/regulasi itu dibuat. Terkait “untuk apa”/tujuan regulasi tentang korporasi sebagai subjek hukum, pengklasifikasikan tujuan tersebut sebagai berikut :
-
a) Memberikan efek pencegahan dan perlindungan masyarakat secara luas: Mudzakkir, mengemukakan pendapatnya bahwa memidana korporasi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, mencegah terjadinya viktimisasi akibat pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi, serta meningkatkan pendapatan negara, yang itu selaras dengan tujuan pemidanaan menurut teori relatif.19
-
b) Sebagai sarana penyelesaian konflik: Diketahui bahwa masyarakat Indonesia dengan falsafah Pancasila-nya memandang kejahatan sebagai gangguan terhadap keseimbangan (evenwichtstoring), keserasian, dan keselarasan, dalam kehidupan masyarakat yang berakibat pada kerusakan, baik yang bersifat individual maupun komunal. Sehingga pemidanaan dalam hal ini diidentifikasi sebagai bentuk reaksi masyarakat sebagai upaya pemulihan rusaknya keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sebagai akibat dari
adanya suatu tindak pidana.20 Sehingga mendudukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dewasa ini, merupakan sebagai upaya penyelesaian konflik akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh korporasi.
Menempatkan korporasi sebagai salah satu pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, didasarkan pada beberapa doktrin, diantaranya:
-
1) Teori Direct Corporate Criminal Liability; artinya bahwa segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan korporasi yang dilakukan oleh organ-organnya, maka itu dipandang sebagai tindakan korporasi itu sendiri.21
-
2) Strict liability; yang berpandangan bahwa suatu tindak pidana cukup mensyaratkan adanya perbuatan saja, tidak memerlukan adanya mens rea. L.B. Curzon menjelaskan bahwa dasar doktrin ini salah satunya karena melihat tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukan.22
-
3) Vicarious liability; yang dapat diartikan sebagai konsep perluasan atau pengalihan pertanggungjawaban pidana, di mana seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban secara pidana atas kesalahan yang dilakukan oleh orang yang lainnya, seperti tindakan seseorang yang berada dalam ruang lingkup pekerjaannya. 23 Sebab secara struktur korporasi memiliki kuasa penuh atau control terhadap orang atau organ yang ada didalamnya. Selain itu, keuntungan yang didapat oleh orang atau organ-organ tersebut, sejatinya merupakan milik korporasi itu sendiri.
Menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, khususnya tindak pidana bidang lingkungan hidup, untuk saat ini dan di masa mendatang sudah tepat, mengingat bahwa jenis dan modus operandi kejahatan semakin lama semakin serius dan itu memberikan dampak/korban yang luas, khususnya adalah masyarakat bahkan negara. Sebagaimana dalam bingkai sejarah, pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup yang melibatkan korporasi terlihat dalam beberapa kasus, seperti pembakaran lahan dan pembuangan limbah B3 24 tanpa di olah terlebih dahulu sehingga menyebabkan baku mutu lingkungan hidup terganggu. 25 Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat, selama kurun waktu 2017-2018 ada belasan perusahaan yang bergerak di bidang minyak, gas bumi (migas) dan tambang melakukan pencemaran terhadap lingkungan, seperti PT. Chevron, PT. Total E&P, PT. Exxon Mobil Indonesia.26
Walaupun menempatkan korporasi sebagai salah satu pihak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pidana merupakan kemajuan dan hal yang positif, tetapi dalam hal memidana korporasi harus lah secara bijaksana dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang searah dengan cita-cita pembaruan hukum pidana Indonesia, sebab mengingat adanya peran penting korporasi terhadap perkembangan ekonomi negara dan masyarakat luas sebagaimana yang telah dijabarkan di bagian pendahuluan. Memperhatikan adanya sisi positif dan negatif keberadaan korporasi khususnya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan SDA, maka menurut dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggarannya tetap memperhatikan prinsip subsidaritas serta menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remidium, guna memberikan ruang keadilan bagi masyarakat yang terdampak terhadap adanya suatu pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup.
-
2) Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Pencemaran Lingkungan Menurut Hukum Positif Indonesia
Terdapat tiga bentuk masalah lingkungan menurut Stewart dan Krier, yaitu pencemaran lingkungan (pollution), pemanfaatan lahan secara salah (land missuse) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (natural resource depletion).27 Sedangkan dalam UU PPLH, membedakannya menjadi dua bentuk yaitu pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan, yang terdapat di Pasal 1 angka 14 dan angka 16. Mengenai ketentuan pidana diatur pada Bab XV mulai Pasal 97 s/d Pasal 119, di mana salah satu yang menarik perhatian dari kesemuanya itu adalah mengenai ketentuan Pasal 97 yang berbunyi: “Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.” Ketentuan tersebut menurut didasarkan pada pengembangan hukum lingkungan yang mengacu pada teori hak yang dipengaruhi oleh etika atau filsafat moral, yang memandang pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan jahat (evils). Berdasarkan pada pandangan itu lah maka suatu pencemaran dan perusakan lingkungan harus lah mendapatkan sanksi oleh masyarakat maupun negara.28
Proses penegakan hukum terkait pencemaran dan pengelolaan lingkungan hidup berpedoman kepada undang-undang PPLH, melalui beberapa upaya penegakan hukum dalam menyikapi terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, yaitu melalui gugatan pengadilan tata usaha negara, gugatan perdata, dan proses hukum pidana. Terhadap ketiganya itu menganut asas subsidaritas, sebagaimana tertuang dalam bagian Penjelasan Umum UU PPLH mengenai prinsip ultimum remidium dalam penegakan hukum pidana, untuk tindak pidana tertentu (terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan). Jika mengacu pada peraturan sebelum berlakunya UU PPLH (yaitu Undang-undang 23 Tahun 1997), pendayagunaan hukum pidana dalam penyelesaian perkara lingkungan adalah ketika tidak efektifnya sanksi hukum lain (sanksi administratif, sanksi perdata) dan alternatif
penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Selain itu, hukum pidana dapat didayagunakan jika tingkat kesalahan pelaku relatif berat, atau pun akibat negatif yang ditimbulkannya relatif besar serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Secara prinsip mengenai asas subsidaritas di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tidak lah berbeda jauh. Hanya saja prinsip hukum pidana sebagai ultimum remidium hanya diperuntukkan terhadap tindak pidana tertentu saja, sehingga untuk tindak pidana lainnya dapat dimungkinkan menggunakan prinsip premum remidium (hukum pidana sebagai pilihan pertama).
Terlepas dari persoalan asas subsidaritas, ketiga instrumen penegakan hukum tersebut memiliki isu hukum yang sama yaitu pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, namun dengan objek yang berbeda yaitu:
-
1. Penegakan hukum administrasi berhubungan dengan objek penyalahgunaan izin;
-
2. Penegakan hukum perdata terkait objek perbuatan melawan hukum
-
3. Penegakan hukum pidana menyangkut objek kejahatan yang berdampak luas
Ketiga bentuk instrumen penegakan hukum tersebut bukan lah tanpa celah, karena masing-masing terdapat kelemahan khususnya dalam kaitannya pelaku korporasi. Misalnya penegakan hukum administrasi yang memiliki sanksi berupa pencabutan izin, pembekuan izin, dan paksaan pemerintah (bestuursdwang). Penegakan hukum administrasi dalam isu lingkungan hidup melibatkan peran serta masyarakat dalam hal melakukan gugatan atas keputusan tata usaha negara (bisa berbentuk izin lingkungan). Gugatan masyarakat atas keputusan tata usaha negara merupakan upaya masyarakat mempengaruhi kebijakan pemerintah apabila menimbulkan kerugian bagi masyarakat.29
Perlu menjadi catatan instrumen penegakan hukum administrasi memiliki kelemahan yang terletak pada dimungkinkannya pemerintah menerbitkan kembali izin atas perusahaan yang izin telah dicabut menggunakan nama usaha baru seperti yang pernah dilakukan oleh gubernur jawa tengah yang melakukan penerbitan izin lingkungan terbaru terhadap PT. Semen Indonesia setelah izin yang digugat oleh masyarakat telah digugat dan memiliki putusan untuk mencabut izin tersebut. 30 Penerbitan kembali izin lingkungan padahal telah ada perintah pengadilan untuk melakukan pencabutan izin rentan dipengaruhi lobi-lobi politik yang membawa kerugian. Lobi-lobi mempengaruhi kebijakan oleh pengusaha menurut Didik J.
Rachbini merupakan ciri dari rent seeking behaviour yang berdampak kerugian bagi masyarakat.31
Begitu juga dalam hal penegakan hukum perdata melalui mekanisme pengajuan gugatan ke pengadilan (litigasi). Hukum acara perdata mengenal suatu asas yang berbunyi Actori Incumbit Probatio di mana secara hukum positif dikenal dalam HIR Pasal 163. Keberadaan asas tersebut merupakan titik lemah dalam upaya gugatan perdata yang dilakukan oleh masyarakat terhadap korporasi, karena penggugat (dalam hal ini adalah masyarakat) diminta untuk membuktikan mengenai bentuk pencemaran, serta kaitan pencemaran tersebut dengan kerugian yang dideritanya. Adanya pembebanan pembuktian suatu peristiwa hukum dalam perkara lingkungan hidup, hal tersebut membutuhkan teknologi dan juga sumber daya manusia yang baik, sehingga berimplikasi terhadap rumit dan mahalnya penyelesaian perkara lingkungan hidup. Implikasi instrumen tersebut memberatkan masyarakat karena beberapa alasan yaitu:32
-
1) Penyebab pencemaran atau pengrusakan dapat berasal dari berbagai sumber (multisources), atau tidak bersumber dari satu sumber saja;
-
2) Mengikutsertakan disiplin-disiplin ilmu lainnya di luar ilmu hukum, dan membutuhkan keterlibatan berbagai pakar sebagai ahli di persidangan;
-
3) Akibat pengrusakan dan pencemaran lingkungan tersebut dapat muncul di kemudian hari (long period of latency), atau dengan kata lain akibat perbuatan tersebut tidak seketika/langsung timbul.
Kendala-kendala tersebut diperparah dengan timbulnya ketidakpastian gugatan dapat diterima yang berakibat kerugian masyarakat semakin bertambah. Terdapat beberapa putusan terkait gugatan perdata dengan amar putusan yang tidak berpihak kepada masyarakat akibat dari kendala-kendala yang dihadapi masyarakat di lapangan. Salah satu putusan tersebut yaitu putusan pengadilan Negeri Palembang Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.PLG di mana hakim dalam putusan tersebut yang hanya mengabulkan 1% dari petitum penggugat karena tidak ada dasar penghitungan lepasnya zat berbahaya ke udara. Terlihat bahwa masalah pembuktian yang rumit telah menjadi kendala instrumen gugatan perdata lingkungan hidup.
Tidak luput pula dalam hal penegakan hukum pidana. Kelemahan instrumen pidana, seperti yang telah sedikit disinggung pada latar belakang menunjukkan bahwa ketentuan pidana dalam udang-undang lingkungan hidup masih bernuansa retributive. Tentunya kenyataan ini bukan merupakan kenyataan yang menguntungkan, terlebih terhadap masyarakat. Nuansa retributif dalam hukum pidana telah membawa konsekuensi tersendiri yaitu penegasian terhadap korban yang berada di luar sistem peradilan, sehingga hanya menempatkan korban sebagai partisipan yang pasif. Secara tidak langsung, berakibat pada kurang maksimalnya tujuan perlindungan masyarakat melalui instrumen hukum pidana. 33 Terlebih permasalahan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup dirasakan sangat luas dampaknya oleh masyarakat
termasuk yang tidak berada disekitaranya. Nuansa retributif semakin terasa dengan adanya pasal 85 ayat (2) UU PPLH yang memuat ketentuan tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Artinya menutup kemungkinan perdamaian antara pelaku dan korban. apabila terjadi tindak pidana penyelesaian hanya dilakukan dengan menghukum pelaku. Lebih lanjut, Muladi dan Sulistyani memberikan beberapa kendala sehubungan dengan kejahatan korporasi yaitu :
-
1. Korporasi memiliki kekuatan finansial maupun politik;
-
2. Kualitas dan kuantitas penegak hukum yang kurang;
-
3. Korban kurang sensitif;
-
4. Pembuktian yang rumit;34
Penegakan hukum pidana dalam perkara lingkungan hidup sepanjang penelusuran masih minim dilakukan. Korporasi yang diproses secara hukum pidana diketahui terakhir dilakukan pada tahun 2016 terhadap PT. Indobarat yang divonis pidana denda 2 Milyar rupiah karena membuang limbah B3 tanpa diolah terlebih dahulu. Minimnya penegakan ini karena masyarakat lebih memilih melakukan gugatan secara perdata dengan berbagai persoalan yang mengiringinya.
Pada dasarnya UU PPLH yang berlaku saat ini memiliki perbedaan dengan undang-undang sebelumnya (UU No. 23 Tahun 1997), salah satunya dalam hal penerapan prinsip ultimum remidium. Prinsip tersebut hanya berlaku untuk tindak pidana terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan, sehingga hal tersebut dapat ditafsirkan di luar tindak pidana tersebut berlaku prinsip premum remidium (mendahulukan hukum pidana dibandingkan mekanisme hukum yang lainnya). Tafsir tersebut kiranya tidak ada salahnya jika menggunakan tafsir a contrario, walaupun di dalam UU PPLH sendiri tidak menjelaskan mengenai prinsip premum remidium secara tersurat. Mengingat pula tuntutan internasional terhadap penyelesaian tindak pidana lingkungan (echo-crime) tersebut salah satunya adalah dengan memfungsikan hukum pidana sebagai premum remedium, sebagaimana penegasan mengenai peran hukum pidana sebagai upaya perlindungan lingkungan hidup yang tertuang di The Council of Europe Resolution 77 (28). Selain itu, UN General Assembly Resolution No. 45/121 tahun 1990 juga menerima resolusi mengenai upaya perlindungan lingkungan hidup melalui sarana hukum pidana yang diajukan oleh The Eighth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders. Demikian pula penegasan mengenai kebutuhan penggunaan hukum pidana dalam rangka pelestarian lingkungan hidup, sebagaimana yang direkomendasikan The AIDP Preparatory Colloquium on the Apllication of Criminal Law to Crime Against the Environment di Ottawa, Kanada (1992). Lebih lanjut, pada Maret 1994 diselenggarakan International Meeting of Experts on Environmental Crime di Portland, Oregon, Amerika Serikat, yang pada intinya pun mendorong penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu upaya proteksi lingkungan hidup dalam ruang lingkup global.35
Walaupun ada peluang menempatkan hukum pidana sebagai premum remidium dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup, tetapi hal tersebut haruslah dilakukan
secara hati-hati dan bijaksana. Mengingat pendapat Herbert Pecker,36 bahwa pidana berorientasi dan bermuara pada sanksi pidana, yang dapat menjadi penjamin utama/terbaik (primer guarantor), sekaligus sebagai pengancam utama (primer threatener), serta merupakan sarana terbaik menghadapi kejahatan. Memperhatikan adanya dampak buruk pidana dan pemidanaan, maka dalam pembaruan hukum pidana Indonesia (sebagaimana yang tergambar di dalam RKUHP Nasional) telah mengatur mengenai tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Tujuan pemidanaan menurut RKUHP Nasional draft tahun 2019 meliputi:
-
(1) Pemidanaan bertujuan:
-
a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
-
b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
-
c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
-
d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
-
(2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.
Jika menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka dalam memidana korporasi haruslah mengacu pada cita-cita pembaruan. Tidak terkecuali dalam tindak pidana bidang lingkungan hidup, terlebih lagi persoalan lingkungan hidup pasti bersinggungan dengan hak masyarakat sebagai warga negara, sehingga dalam penegakannya tidak hanya mengedepankan persoalan kepastian hukum tetapi yang lebih utama persoalan keadilan sosial masyarakat yang terdampak serta mengenai perlindungannya.37
Ketika berbicara persoalan keadilan masyarakat Indonesia, maka tidak akan terlepas dari nilai-nilai keadilan yang bersumber dari Pancasila. Nilai-nilai keadilan Pancasila yang menjunjung prinsip keseimbangan, yang oleh Barda Nawawi Arief menyebutnya dengan istilah keseimbangan monodualistik, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. 38 Jika dikaitkan dengan keberadaan suatu tindak pidana yang dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, maka hukum pidana harus difungsikan sebagai sarana untuk memperbaiki rusaknya keseimbangan akibat adanya suatu kejahatan. Konsep tersebut dipandang relevan dalam penegakan hukum pidana bidang lingkungan hidup, sebab hukum pidana idealnya difungsikan untuk memperbaiki rusak atau hilangnya suatu
tatanan ekosistem 39 akibat adanya kejahatan baik yang bernilai materiil maupun imateriil. Pendapat tersebut didasarkan pada definisi kejahatan lingkungan (ecological/environmental crime) menurut Kongres PBB ke-7, yang dinyatakan sebagai perbuatan yang berpengaruh negatif terhadap upaya pembangunan bangsa (had a negatif impact on the development effforts of nations), atau terganggunya kualitas lingkungan hidup (impinged on the quality of life), atau terganggunya kesejahteraan masyarakat secara material (impinged on material well-being of entire societies).40
Mendasarkan pada cita-cita untuk mewujudkan keadilan masyarakat Indonesia tersebut, maka sejatinya membuka kemungkinan penyelesaian perkara pidana lingkungan hidup dengan pendekatan restorative justice, melalui sarana alternative dispute resolution (ADR). Tetapi hal tersebut terbentur ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU PPLH yang berbunyi: “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”, yang itu justru menutup ruang penyelesaian perkara pidana lingkungan hidup di luar pengadilan, sehingga mutlak penyelesaiannya melalui jalur pengadilan. Padahal jika ketentuan pasal 85 ayat (2) tersebut dihilangkan, maka ada kemungkinan penggabungan penyelesaian perkara perdata dan pidana di luar jalur pengadilan (dalam perkara perdata disebut dengan istilah non-litigasi).
-
3.2 Konsep Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Melalui Pendekatan Restorative Justice terhadap pelaku korporasi.
-
1) Korelasi Restorative Justice dengan Arah Pembaruan Hukum Pidana Indonesia (Urgensi Pendekatan Restoratif Justice Terhadap Tindak Pidana Lingkungan)
Memperhatikan pendapat Pecker seperti yang telah dijelaskan di atas, maka hukum pidana sejatinya memiliki kelemahan. Titik tekan kelemahan tersebut pada persoalan dehumanisasi jika sanksi pidana dan pemidanaannya tidak dilakukan secara hati-hati dan bijaksana, yang itu justru semakin diperparah oleh sistem peradilan pidana yang cenderung kaku dan legal formal. Sistem peradilan melalui pendekatan legal formal justru tidak berhasil memberi ruang yang cukup pada kepentingan para korban dan para terdakwa, atau dengan kata lain, sistem peradilan pidana yang konvensional kerap menimbulkan ketidakpuasan dan kekecewaan. 41 Sehingga nilai-nilai dehumanisasi hukum pidana ini sejatinya tidak hanya untuk si pelaku semata, tetapi juga kepada korban kejahatan juga sebagai akibat penjatuhan sanksi maupun dalam proses peradilan yang harus dijalani.
Menurut pandangan Pecker sistem peradilan pidana memiliki 2 model, yaitu crime control model dan due process model, di mana antara keduanya memiliki karakter yang saling bertolak belakang dalam hal prosedur penegakan hukum pidana. Perbedaan keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:42
Tabel 2: Perbandingan CCM dan DPM
|
Crime Control Model (CCM) |
Due Process Model (DPM) |
|
Represif : Bersifat keras yang menimbulkan pengingkaran terhadap HAM |
Preventif : Menghindari kesalahan procedural |
|
Efisiensi : Setiap terjadi kejahatan harus segera di proses |
Efektivitas : Setiap proses dilakukan sesuai prosedur guna efektifnya proses enegakan hokum |
|
Presumption of guilt : Terdakwa dianggap bersalah ketika ditetapkan sebagai tersangka |
Presumption of innocent : setiap orang yang ditetapkan sebagai tersangka dianggap tidak bersalah |
|
Factual guilt : Penetapan tersangka tanpa prosedur hukum |
Legal guilt: menetapkan tersangka harus sesuai ketentuan hukum acara (lex strcta) |
|
Informal fact finding : Pencarian alat bukti tidak memerlukan prosedur |
Formal adjudicative : Pencarian alat bukti harus sesuai prosedur hukum acara |
Sumber: Lilik Mulyadi, 2007.43
Bahwa sesungguhnya Indonesia saat ini menggunakan kedua sistem tersebut, baik itu dalam aturan hukumnya maupun dalam prakteknya. Kedua model tersebut dipandang sudah tidak tepat lagi jika diperuntukkan untuk Indonesia, terlebih lagi saat ini Indonesia dalam atmosfer pembaruan hukum pidana. Pendapat tersebut didasarkan pada pendapat Muladi, di mana CCM yang bersifat represif cenderung berpotensi melanggar hak asasi manusia, padahal hukum pidana ditujukan untuk mencegah kesewenang-wenangan negara kepada warganya. Sedangkan menurut Muladi, DPM juga tidak cocok, karena bersifat anti-authoritarian values (terlalu bebas atau offender oriented). 44 Melihat adanya berbagai macam kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana (seperti kepentingan individu, masyarakat, negara, dan juga korban maupun pelaku kejahatan) maka menurut beliau sistem peradilan yang cocok untuk Indonesia adalah daad-dader strafrecht atau model keseimbangan kepentingan. 45 Mengingat pula pendapat Mardjono Reksodiputro 46 yang mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, yang ditujukan untuk: pertama, mencegah masyarakat
menjadi korban kejahatan; kedua, menyelesaikan setiap perkara kejahatan yang terjadi, sehingga keadilan ditegakkan dan memuaskan masyarakat; dan ketiga, sebagai upaya perbaikan pelaku, sehingga ia tidak mengulangi kejahatannya kembali.
Dari berbagai pandangan-pandangan para ahli hukum pidana di atas mengenai sistem peradilan pidana Indonesia, selaras dengan arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Pendapat tersebut terlihat dari bagian konsideran huruf C rancangan KUHP Nasional draft tahun 2019 yang berbunyi:
“bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.”
Walaupun KUHP tersebut masih dalam taraf rancangan, tapi paling tidak terlihat mengenai landasan arah hukum pidana nasional di masa mendatang, yaitu penekanan pada nilai-nilai keseimbangan. Sehingga terdapat keserasian antara tujuan hukum pidana dan Sistem peradilan Indonesia di masa mendatang.
Cita-cita rehumanisasi hukum pidana Indonesia melalui sistem peradilan pidana sudah mulai terlihat dari penegakan hukum yang dilakukan melalui pendekatan restorative justice. Konsep restorative justice menurut Dignan, dapat dilihat dalam dua arti. Pertama, Keadilan Restoratif sebagai konsep proses, dan kedua Keadilan Restoratif sebagai konsep nilai. Jika dipandang sebagai konsep proses maka keadilan restoratif adalah mempertemukan para pihak yang termasuk dalam sebuah tindak pidana/kejahatan (pelaku, korban, maupun masyarakat) guna mengutarakan penderitaan serta langkah-langkah yang dilakukan untuk memulihkan. Sedangkan jika dipandang sebagai konsep nilai, maka keadilan restoratif ini mempunyai nilai-nilai yang tidak sama dengan keadilan biasa, dimana keadilan restoratif ini menitikberatkan pada pemulihan, bukan pada penghukuman. 47 Operasionalisasi restorative justice memiliki 4 (empat) model yaitu:48
-
a. Victim Offender Mediation (VOM); b. Family Group Conferencing (FGC); c. Circles;
-
d. Reparative Board / Youth Panel;
Pendekatan restorative justice saat ini diwujudkan dalam penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan atau yang disebut dengan istilah (alternative dispute resolution/ADR), dan yang telah dikenal di Indonesia saat ini dalam bentuk mediasi
penal dan diversi. Lilik Mulyadi49 menerangkan, bahwa aturan terkait ADR saat ini di Indonesia masih diatur secara parsial dan terbatas serta gradasi pengaturannya diatur pada level di bawah undang-undang, seperti:
-
a) Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
-
b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
-
c) Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).
Munculnya restorative juctice ke permukaan dalam semangat pembaruan hukum pidana Nasional pada prinsipnya merupakan instrumen atau dalam bahasa teknis sebagai alat memperoleh keadilan. Keadilan restoratif merupakan keadilan yang sifatnya pemulihan melalui jalan kekeluargaan yang bertujuan menyelesaikan konflik para pihak. Sebagaimana yang disampaikan oleh Natangsa Surbakti 50 mengenai cerminan penyelesaian perkara pidana yang bertujuan restoratif, yang meliputi: (1) penganalisaan dan pengambilan langkah guna perbaikan kerusakan; (2) mengikutsertakan seluruh pihak yang berperan (stakeholders); dan (3) memberdayakan hubungan masyarakat dan pemerintah yang bersifat tradisional sebagai upaya penanggulangan kejahatan. Nilai-nilai keadilan sebagaimana yang terkandung di dalam konsep restorative justice tersebut, palin tidak juga tertuang di bagian konsideran draft rancangan KUHAP Nasional berikut ini: “bahwa pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum”. Rumusan tersebut menggambarkan eratnya kaitan antara nilai keadilan bagi masyarakat maupun bagi para pihak yang berperkara.
Keadilan restoratif pada prinsipnya merupakan konsep keadilan yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia dengan Pancasila-nya. Menurut Notonagoro, Pancasila mengandung tiga nilai yaitu material, vital, dan kerohanian.51 Ketiga nilai tersebut terkandung dalam Pancasila sebagai kristalisasi nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Menurut Tommy Leonard filsafat Pancasila adalah hasil pemikiran yang dalam dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai sesuatu kenyataan paling benar, paling adil, serta paling bijaksana sesuai bangsa Indonesia. 52 Membahas mengenai prinsip keadilan menurut Pancasila, maka akan kembali lagi pada gagasan Barda Nawawi Arief mengenai prinsip keseimbangan monodualistik sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, yaitu hukum pidana Indonesia di masa mendatang haruslah dijiwai oleh nilai-nilai “kerakyatan yang dipimpin hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan” (antara lain mengutamakan kepentingan/kesejahteraan rakyat, penyelesaian konflik secara bijaksana/
musyawarah/kekeluargaan), serta haruslah ber-”keadilan sosial”.53 Pelibatan peranan negara, masyarakat, dan individu (pelaku dan korban) dalam pendekatan restorative justice, merupakan wujud usaha pencapaian keadilan Pancasila yang menganut prinsip monodualistik. Hal tersebut tidak berbeda jauh dengan pendapat John Rawls, bahwa prinsip keadilan merupakan hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang fair. Lebih lanjut Rawls menjelaskan, “manusia sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuannya, mereka akan mengenali rasa keadilan yang sesuai bagianya”.54 Mengaitkan pendapat dua ahli tersebut, maka didapat sebuah konklusi bahwa pendekatan restorative justice yang menuntut adanya keterlibatan negara, masyarakat, dan individu (pelaku dan korban) melalui musyawarah mufakat dapat menciptakan kesepakatan bersama sebagai nilai keadilan yang paling tinggi. Sebab kesepakatan tersebut memiliki kemanfaatan bagi seluruh pihak, sebagaimana konsep keadilan yang dikemukakan Justinian: “kebajikan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya (haknya-pen.)”.55
Melihat korelasi antara pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dengan nilai-nilai keadilan Pancasila dan prinsip pembaruan hukum pidana maupun acara pidana Indonesia, maka tidak ada salahnya jika pendekatan tersebut dipakai dalam upaya penegakan hukum bidang lingkungan hidup. Adanya hubungan subsidaritas antara tiga rumpun ilmu hukum dalam penegakan hukum bidang lingkungan sebagaimana yang tertuang di dalam UU PPLH, maka gagasan mengenai penyelesaian perkara bidang lingkungan hidup di luar pengadilan perlu diberikan, melalui penggabungan prinsip non-litigasi dalam hukum perdata dengan prinsip ADR dalam hukum pidana. Terlebih jika perkara pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup tersebut melibatkan korporasi sebagai pelakunya.
-
2) Konsep Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Melalui Pendekatan Restorative Justice terhadap pelaku korporasi
Prinsip subsidaritas yang digunakan oleh UUPLH dapat dimaknai sebagai upaya penyelesaian perkara lingkungan secara holistik antara tiga bidang hukum, yaitu administrasi, perdata, dan pidana. Beranjak dari pendapat Muhammad Akib 56 mengenai paradigma holistik dalam penegakan hukum lingkungan, yang mana paradigma tersebut memiliki prinsip: Pertama, penggunaan semua bagian hukum (hukum administrasi, pidana dan perdata) secara komprehensif. Ketiganya tidak termasuk alternatif, tetapi bisa diaplikasikan secara bersamaan secara sinergis, sehingga sanksinya pun bersifat kumulasi. Sehingga prinsip dasar holistik tersebut menghendaki adanya penegakan hukum secara utuh dengan memakai ketiga sarana hukum tersebut secara komprehensif, serta adanya kerjasama sinergis diantara penegak hukum. Kedua, paradigma holistik ini tidak hanya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan kepastian hukum semata, tetapi yang lebih utama adalah mencapai nilai-nilai keadilan. Paradigma holistik tidak hanya untuk menegakkan peraturan
(kepastian hukum), tetapi yang lebih utama adalah untuk menegakkan kebenaran dan mencapai keadilan bagi masyarakat dan lingkungan hidup, sehingga yang diutamakan dalam paradigma ini tidaklah kepastian hukum, melainkan kebenaran dan keadilan. Mendasarkan pada paradigma holistik tersebut, serta dengan memperhatikan tujuan pencapaian nilai keadilan yang dapat didekati melalui pendekatan restorative justice, maka dalam tulisan ini akan diberikan gagasan mengenai ADR dalam perkara pelanggaran lingkungan hidup terhadap pelaku korporasi.
Seperti yang telah dipahami bersama, bahwa dalam hukum perdata mengenal adanya alternatif penyelesaian sengketa (APS) melalui sarana non-litigasi, yang secara prinsip tidak berbeda jauh dengan ADR dalam hukum pidana, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan. Kedua bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut sejatinya dapat dilaksanakan dalam satu bentuk tahapan sebagai bentuk pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Bahkan keduanya pun dapat dilaksanakan bersamaan dengan penegakan hukum administrasi yang sedang atau yang akan berjalan. Terlebih lagi konsep tersebut juga dapat mewadahi nilai-nilai kearifan lingkungan lokal yang ada di masyarakat, sebagai ciri dari penegakan hukum lingkungan yang progresif. Konsep tersebut dipandang oleh sebagai suatu hal yang baru, karena UUPPLH saat ini mengatur dua hal yang justru menjauhkan dari konsep restorative justice bidang lingkungan hidup, yaitu:
-
a) Ketentuan Pasal 85 ayat (2), yang menentukan bahwa “penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”; dan
-
b) Penjelasan Umum angka 6, yang mengkhususkan penerapan asas ultimum remedium hanya untuk tindak pidana formil tertentu, yaitu hanya terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.
Keberadaan pasal 85 ayat (2) dan Penjelasan Umum angka 6 yang menganut asas premum remidium (penegakan hukum pidana sebagai “obat” pertama) memiliki kedalaman makna jika UU PPLH sangat bercorak keadilan retributif yang saat ini cenderung untuk ditinggalkan. Ketentuan tersebut berimplikasi “negatif” terhadap penegakan hukum pelanggaran di bidang lingkungan hidup secara umum, di mana tidak adanya penyelesaian perkara tersebut di luar pengadilan dan penggunaan hukum pidana yang mendahului proses hukum yang lainnya. Hal tersebut dikhawatirkan justru menjauhkan penegakan hukum lingkungan hidup dari tujuan kemanfaatan dan keadilan sosial masyarakat dan lingkungan hidup (ekosistem). Terlebih lagi jika penegakan hukum administrasi tidak dilakukan secara profesional dan rentan akan upaya-upaya lobbying yang dilakukan oleh pelaku (yang sebagian besar merupakan korporasi atau orang yang datang dari kalangan menengah ke atas dan memiliki posisi politik dan ekonomi/bisnis yang kuat).
Pendekatan restorative justice menurut Howard Zehr dan Barb Toews bukan dimaksudkan untuk mengabaikan peran formal dari sistem peradilan pidana maupun penegakan bidang hukum formal yang lainnya. Justru pendekatan tersebut menghendaki adanya penyelesaian perkara yang dilengkapi dengan usaha-usaha untuk merestorasi atau memperbaiki dampak negatif dari timbulnya kejahatan serta mengembalikan kepada keadaan semula hubungan antara pihak korban dan pihak pelaku tindak pidana, sehingga membuka kesempatan kepada pihak korban untuk
menerima pertanggungjawaban dan permohonan maaf pelaku. 57 Pendapat Zehr tersebut relevan jika dikaitkan sebagai alasan pembenar pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup. Pendapat mengenai relevansi tersebut didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:
-
a) Hal yang utama dan tidak kalah pentingnya dalam penyelesaian perkara pelanggaran bidang lingkungan hidup adalah mengenai upaya pengembalian atau perbaikan akibat pelanggaran berupa rusaknya atau tercemarnya lingkungan hidup. Memidana pelaku (termasuk korporasi) justru dapat menghambat upaya merestorasi dampak pelanggaran di bidang lingkungan hidup tersebut. Ursula Caser mengatakan keuntungan mediasi sebagai bagian dari operasionalisasi paradigma restorative justice akan menghasilkan solusi terbaik yang berkelanjutan bagi para pihak (sustainable solutions that best serve the interests and needs of all involved stakeholders).58
-
b) Penyelesaian melalui pendekatan restorative justice dapat memulihkan hubungan antara pelaku/pelanggar hukum bidang lingkungan hidup dengan korbannya, yang sebagian besar korbannya merupakan masyarakat luas. Pemulihan hubungan tersebut penting kedudukannya, karena dalam hal upaya pemulihan maupun pemberian ganti rugi kepada korban, diperlukan suatu hubungan diantara keduanya (pelaku dan korban). Pemberian sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam bentuk pencabutan izin dapat berimplikasi putusnya hubungan diantara keduanya, sehingga tujuan pemulihan atau pemberian ganti rugi dapat gagal diwujudkan.
-
c) Tujuan pemulihan melalui pendekatan restorative justice, tidak hanya diperuntukkan dalam hal pemulihan dampak negatif dari terjadinya pelanggaran bidang lingkungan hidup. Pemulihan juga ditujukan bagi korporasi, di mana pendekatan restorative justice tersebut mampu memulihkan nama baik korporasi pelaku kejahatan/pelanggaran khususnya, dan pandangan buruk terhadap korporasi dan pelaku usaha/bisnis pada umumnya. Mengingat peranan penting korporasi dalam perekonomian negara dan pentingnya nama baik bagi suatu korporasi, maka pendekatan restorative justice tersebut menjadi jalan utama dan yang paling tepat.
Mengutip pendapat Muladi mengenai korban akibat pelanggaran lingkungan hidup, di mana menurut beliau dalam tindak pidana lingkungan hidup, ada dua kategori mengenai korban, yaitu korban yang bersifat konkrit dan korban yang bersifat abstrak.59 Pengkategorian tersebut didasarkan pada konsep tentang kerusakan dan kerugian lingkungan, berupa kerusakan dan kerugian yang nyata (actual harm/actual victim) dan ancaman kerusakan (threatened harm/potential victims). Dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan tidak hanya alam, flora, dan fauna, tetapi juga masa depan kemanusiaan (generasi yang akan datang) akibat degradasi lingkungan.
Memperhatikan mengenai potensi generasi yang akan datang sebagai threatened harm/potential victims, maka penjatuhan sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi pelaku/pelanggar hukum bidang lingkungan hidup, khususnya korporasi, harus lah dilakukan secara hati-hati, karena terputusnya hubungan pelaku korporasi dengan korban masyarakat dapat berdampak terhadap tidak kembalinya kondisi lingkungan hidup di masa mendatang yang itu berdampak terhadap kehidupan generasi selanjutnya. Terlebih lagi jika mengacu pada pendapat Barda Nawawi Arief, bahwa akibat pencemaran lingkungan meliputi fisik dan juga nonfisik, termasuk sosial budaya. Tetapi, penafsiran tentang tipe dampak negatif terhadap sosial budaya sangat terbatas dan dogmatis, sehingga belum sampai menyentuh kepada persoalan hancurnya nilai masyarakat lokal akibat pencemaran atau perusakan lingkungan.60
Memperhatikan penjabaran di atas, maka model penyelesaian perkara di luar pengadilan untuk pelanggaran hukum bidang lingkungan hidup memiliki keunggulan dibandingkan jika perkara tersebut diselesaikan melalui pendekatan legal formal (di dalam pengadilan). Secara garis besar, keunggulan konsep tersebut meliputi:
-
1) Lebih cepat dan tepat dari segi waktu dan biaya. Tidak menggunakan prosedur formal yang berjangka waktu secara otomatis akan mengurangi jangka waktu dan biaya para pihak.
-
2) Memulihkan dampak pelanggaran. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, bahwa pemulihan dalam hal ini dapat dimaksudkan untuk dua belah pihak, yaitu pelaku korporasi dan korban masyarakat. Pemulihan korban masyarakat, dalam hal ini baik itu sebagai factual victims maupun sebagai potential victims akibat dampak pelanggaran lingkungan hidup berupa rusak atau tercemarnya lingkungan atau terganggunya ekosistem. Sedangkan pemulihan terhadap pelaku korporasi adalah memulihkan nama baik korporasi dan kepercayaan publik terhadapnya.
-
3) Mengurangi sanksi pidana yang diberikan kepada subjek hukum orang, sebagai pengurus atau organ di dalam suatu korporasi. Salah satu masalah hukum pidana (pidana dan pemidanaan) dan sistem peradilan pidana Indonesia saat ini adalah mengenai over capacity di lembaga pemasyarakatan. Dampak dari over capacity menimbulkan pertanyaan apakah tujuan pemidanaan akan tercapai? Tentu pertanyaan tersebut masih bisa diperdebatkan, namun beberapa kajian menunjukkan kondisi demikian bukan kondisi yang kondusif mencapai tujuan pemidanaan. Sehingga pendekatan restoratif di sini dapat meminimalisir adanya penjatuhan pidana, baik itu terhadap orang sebagai organ korporasi maupun terhadap korporasi sendiri. Sekalipun penjatuhan sanksi (pidana maupun administrasi) tidak dapat dihindari, maka hasil upaya penyelesaian perkara melalui pendekatan restorative justice tersebut dapat mengurangi hukuman bagi pelaku pelanggaran.
-
4) Melibatkan masyarakat adat. Keberadaan dan kegiatan korporasi dalam mengolah dan mengeksplorasi sumber daya alam, sangat besar kemungkinan bersinggungan dengan sistem dan kepentingan masyarakat adat. Sehingga pendekatan restorative justice yang ditempuh nantinya, tidak menutup
kemungkinan adanya pelibatan fungsi dan sistem hukum masyarakat adat sebagai bagian dari wilayah yang terdampak dari pelanggaran hukum lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.
-
5) Mendekati nilai-nilai keadilan. Keadilan tertinggi adalah keadilan yang diperoleh dari kesepakatan. Komunikasi yang terbangun dalam mediasi memungkinkan para pihak mengajukan keinginan-keinginan kemudian diikuti dengan tawar-menawar hingga tercapai kesepakatan. Tercapainya kesepakatan sebagai hasil dari proses komunikasi merupakan keadilan yang diinginkan para pihak.
Guna lebih melengkapi keunggulan pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara lingkungan, mengutip pendapat Eman Rajagukguk dan Gatot Soemartono.61 Menurut beliau, masyarakat bisnis lebih memilih penyelesaian perkara di luar prosedur pengadilan karena: pertama, perkara lingkungan dapat diselesaikan secara tertutup, tanpa diketahui publik; kedua, adanya keterbatasan kemampuan hakim dalam menyelesaikan perkara lingkungan. Ketiga, penyelesaian secara prosedural ditujukan mencari pihak yang salah/benar, sedang penyelesaian sengketa melalui pendekatan non-prosedural dapat membuka peluang penyelesannya secara kompromi.
Mengenai sinergitas antara penyelesaian perkara/pelanggaran lingkungan hidup melalui tiga mekanisme hukum (administrasi, perdata, dan pidana), maka diperoleh konsep sebagai berikut:
-
a) Proses penyelesaian perkara perdata dan pidana di luar pengadilan (non-litigasi dalam perkara perdata, dan ADR dalam perkara pidana) dapat dilakukan secara bersamaan, dan dapat pula dilakukan bersamaan dengan proses penyelesaian perkara melalui jalur hukum administrasi.
-
b) Penyelesaian dua jalur hukum tersebut di luar pengadilan, ditujukan untuk menyepakati persoalan ganti rugi (materiil dan immaterill) kepada korban masyarakat, upaya-upaya pemulihan kondisi lingkungan hidup dan sosial masyarakat akibat pelanggaran tersebut di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, dan upaya pemaafan dari masyarakat terhadap pelaku.
-
c) Hasil penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut, akan menjadi dasar pengurangan atau meringankan penjatuhan sanksi administrasi terhadap korporasi maupun sanksi pidana terhadap orang yang menjadi bagian dari korporasi tersebut; serta hasil kesepakatannya menjadi dasar tidak dilanjutkannya perkara tersebut melalui jalur formal baik secara keperdataan maupun secara pidana terhadap korporasi.
-
d) Hasil penyelesaian perkara di luar pengadilan dalam bentuk kesepakatan, akan ditetapkan dengan penetapan pengadilan agar memiliki daya paksa kepada para pihak khususnya pelaku/pelanggar;
-
e) Apabila penyelesaian perkara di luar pengadilan tersebut tidak berhasil menemukan kesepakatan, maka baru lah memakai jalur legal formal secara keperdataan, kepidanaan maupun administratifnya; di mana penyelesaian
perkara pidana tetap menjadi ultimum remidium setelah adanya putusan terhadap perkara perdata maupun administratifnya.
Gagasan tersebut di atas, tidak serta merta mengesampaingkan asas premum remidium dalam hukum pidana lingkungan yang sudah ada saat ini. Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara/pelanggaran lingkungan hidup yang notabene bertolak belakang dengan prinsip premum remidium, jelas tidak dapat dijadikan/diterapkan dalam satu prosedur penyelesaia perkara. Bahwa asas premum remidium lah yang harus dikhususkan terhadap tindak pidana lingkungan hidup tertentu (bukan asas ultimum remidium yang dikhususkan sebagaimana yang terdapat di UUPPLH saat ini), atau dengan kata lain asas premum remidium perlu diberikan batasan penerapannya yaitu apabila ketentuan sinergi tiga mekanisme hukum di atas tidak tercapai dan terjadi pengulangan kembali tindak pidana oleh korporasi.
Sinergi dari beberapa mekanisme hukum telah selaras dengan paradigma restorative justice yang diwujudkan melalui mediasi. Mediasi sendiri dibangun dari prinsip kerugian materil yang diderita oleh korban faktual dan kerugian imateril yang diderita oleh korban potensial. Dengan demikian melihat dua variable korban yang masing-masing berbeda kerugiannya namun terjadi secara bersamaan, maka mediasi yang dapat diterapkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara pelanggaran lingkungan hidup yaitu dengan memadukan mediasi dalam hukum perdata sebagai solusi penyelesaian sengketa dari sisi kerugian materil dan mediasi penal dari sisi kerugian immaterial. Pulihnya aspek kerugian dari dua variabel korban yang berbeda melalui pendekatan restorative justice selaras dan seirama dengan Pancasila yang telah disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum. Apabila gagasan dalam tulisan ini diakomodir dalam aturan hukum maka hal tersebut selaras dengan Pancasila yang mana hal tersebut akan memiliki potensi kebergunaan yang sangat tinggi mengingat keberhasilan suatu hukum bekerja tergantung dari mana hukum itu berasal. Gagasan yang ditawarkan tulisan ini didasarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Indonesia yang telah dikristalisasi, maka potensi keberdayagunaanya relatif tinggi.
Evolusi korporasi saat ini menempatkan korporasi dapat memperoleh keuntungan, baik itu menggunakan cara yang sah menurut hukum maupun melalui cara-cara yang illegal. Kondisi demikian memaksa semua elemen berpadu menyelesaikan persoalan tersebut. Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan korporasi menggunakan instrumen hukum yang diakomodasi oleh UU PPLH masih belum mampu menyelesaikan konflik yang timbul. Ketiga instrumen hukum meliputi administrasi, perdata, dan pidana, masing-masing memiliki kelemahan menghadapi superioritas korporasi yang melakukan pelanggaran hukum lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan perbaikan demi tercapainya cita hukum. Pembaruan hukum terutama instrumen hukum pidana perlu dilakukan dalam rangka merespon pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi melalui alternatif dispute resolution guna melindungi masyarakat, terlebih korporasi saat ini dapat dipertanggungjawabkan pidana secara pribadi. Perubahan fundamental penyelesaian perkara pidana lingkungan hidup bisa menjadi solusi kelemahan instrumen hukum khususnya pidana dalam UU PPLH.
Lemahnya instrumen hukum dalam UU PPLH membawa dampak kerugian sangat luas yang dialami oleh masyarakat, sehingga memerlukan alternatif (cara) guna menekan angka pengrusakan lingkungan hidup. Dalam penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup pendekatan Restoratif Justice bisa menjadi alternatif. Keuntungan dari pendekatan tersebut adalah dapat menciptakan nilai-nilai keseimbangan antara pelaku dan korban serta masyarakat, sebab dehumanisasi hukum pidana berpotensi dialami oleh korban dan masyarakat apabila tidak diciptakan pola perlindungan yang tidak seimbang. Keseimbangan antara pelaku, korban dan masyarakat merupakan arah/pedoman dalam pembaruan hukum pidana Nasional. Demikian pula halnya terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dapat dipikirkan penggunaan pendekatan restorative justice agar tercipta keseimbangan antara pelaku (korporasi), korban dan masyarakat. Mewujudkan restorative justice dilakukan melalui konsep dual-mediasi yang menggabungkan antara mediasi penal dan mediasi dalam hukum perdata.
Pembentuk undang-undang diharapkan segera melakukan kajian yang tujuan akhir untuk perbaikan UU PPLH yang sampai saat ini masih memiliki kelemahan karena masih banyak ditemukan pelanggaran UU PPLH dalam tataran implementasi. Menyertakan konsep restorative justice sebagai “ruh” dalam materi muatan UU PPLH menggantikan paradigma retributive justice akan menjadikan UU PPLH di masa mendatang akan lebih efektif serta akan menciptakan keseimbangan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Selain itu, paradigma restorative justice merupakan langkah menanamkan Pancasila ke dalam jiwa UU PPLH di masa mendatang.
Daftar Pustaka
Buku
Ali, M. (2013). Asas-asas Hukum Pidana Korporasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Fuady, M. (2013). Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Jakarta: Kencana.
Kristian. (2014). Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia.
Muladi dan Diah Sulistyani. (2013). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: PT Alumni.
Muladi, Demokratisasi. (2002). Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center.
Mulyadi, L. (2010). Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan. Bandung: CV. Mandar Maju.
Mulyadi, L. (2015). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: PT Alumni.
Mulyadi, L. (2016). Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Yogyakarta: Genta Publishing.
Prasetyo, T. (2015). Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum. Bandung: Nusa Media. Rahmadi, T. (2013), Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
Rawls, J. A. (2006). Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik unutk Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial dalam Negara. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Reksodiputro, M. (2007). Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan
Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
Wahid, W. (2009). Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana. Jakarta: Universitas Trisakti.
Yulia, R. (2013). Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Zehr, H. dan Barb Toews (2004). Critical Issues in Restorative Justice. New York: Criminal Justice Press.
Jurnal
Abildanwa, T. (2016). Mediasi Penal Sebagai Upaya Dalam Rangka Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Keseimbangan. Jurnal Pembaruan Hukum, 3(1), 138. https://doi.org/10.26532/jph.v3i1.1353.
Akib, M. (2014). Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Lingkungan: Dari Mekanistik-Reduksionis Ke Holistik-Ekologi. Masalah-Masalah Hukum, 43(1), 125–131. https://doi.org/10.14710/mmh.43.1.2014.125-131.
Basuki, A. (2011). Pertanggungan Jawab Pidana Pejabat Atas Tindakan Mal-Administrasi Dalam Penerbitan Izin Di Bidang Lingkungan. Perspektif, 16(4), 252-258. https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.88
Candra, S. (2013). Pembaruan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. JURNAL CITA HUKUM, 1(1) 39-56. https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979
Fajrin, YA & Ach. Faisol Triwijaya (2019). Arah Pembaruan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan, 18(1), 734–740. https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361
Fatoni, S. (2015). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Berorientasikan Pendekatan Religius. Ahkam: Jurnal Hukum Islam, 3(1) 41-64. https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.1.41-64.
Flora, HS, (2015). Penal Mediation As An Alternative Model of Restorative Justice in The Criminal Justice System of Children. International Journal of Business, Economics and Law, 6(4), 6–10.
Gunarto, MP. (2012). Asas Keseimbangan Dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mimbar Hukum, 24(1), 83–97.
https://doi.org/10.22146/jmh.16143
Haryadi, H. (2017). Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 14(1), 124-149.
https://doi.org/10.31078/jk1416.
Hikmawati, P. (2017). Kendala Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan 8(1), 131–150.
https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.941.
Jati, WR. (2012) Manajemen Tata Kelola Sumber Daya Alam Berbasis Paradigma Ekologi Politik. Politika: Jurnal Ilmu Politik, (3)3, 98-111
https://10.14710/politika.3.2.2012.
Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum Lingkungan Hidup Dan Sumber Daya Alam Dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan (The Law Dynamics on the Environmental and Natural Resources in order to Sustainable Development). Rechts Vinding: Media Pembangunan Hukum Nasional, 4(2), 181–197.
Kim, S.W. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Dinamika Hukum, 2(4), 415–427
http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.247.
Kristian, (2014). Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jurnal Hukum & Pembangunan, 44(4), 575-621. https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no4.36
Ma’arif, S. (2011). ”Rent Seeking Behaviour” dalam Relasi birokrasi dan Dunia Bisnis. NATAPRAJA. 263-276. https://doi.org/10.21831/jnp.v0i0.3264
Praja, C.B.A. et.al (2016). Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan. Varia Justicia, 12(1) 42–62
Prayitno, K.P. (2012). Restorative Justice Untuk Peradilan Di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto). Jurnal Dinamika Hukum, 12(3) 407-420. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116
Roup, A, Muridah Isnawati, dan Sudarto. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Koorporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016. JUSTITIA JURNAL HUKUM, 1(2), 294-322.
https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1163.
Satria, H. (2018). Restorative Justice : Paradigma Baru Peradilan Pidana. Media Hukum, 25(1), 111–123. https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111-123.
Shanty, L. (2017). Aspek teori hukum dalam Kejahatan Korporasi. Jurnal Pakuan Law Review, Volume 3, 56–72. https://doi.org/10.33751/.v3i1.401
Suhariyanto, B. (2016). Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara. Rechts Vinding, 5(3), 421– 438.
Surbakti, N. (2011). Mediasi Penal Sebagai Terobosan Alternatif Perlindungan Hak Korban Tindak Pidana, Jurnal Ilmu Hukum, (14) 1, 90-106.
Sodikin. (2010) Penegakan Hukum Lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, 12(3), 543–563.
Widayati , LS. (2015). Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(1), 1–24.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1
Website
Amelia, A.R. "11 Perusahaan Migas dan Tambang Terkena Sanksi Pencemaran Lingkungan" Available from https://katadata.co.id/berita/2019/01/21/11-perusahaan-migas-dan-tambang-terkena-sanksi-pencemaran-lingkungan.
Erdianto, K. "Soal Penerbitan Izin Baru Pabrik Semen di Rembang, Ganjar Dinilai Membangkang",
Availablefrom https://nasional.kompas.com/read/2017/02/24/19222541/so al.penerbitan.izin.baru.pabrik.semen.di.rembang.ganjar.dinilai.membangkang ?page=all.
Utomo, Y.W. "Kasus Kebakaran Hutan dalam 3 Tahun Terakhir, Tak seperti Klaim Jokowi", Available
from https://sains.kompas.com/read/2019/02/17/205720723/kasus-kebakaran-hutan-dalam-3-tahun-terakhir-tak-seperti-klaim-jokowi.
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118) jo. Undang-undang nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan undang-undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154)
Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308)
428
Discussion and feedback