Budaya Hukum sebagai Faktor Pendorong Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerah di Indonesia
on
JURNAL BmGISTER HUKOM ¾ΓDAYANA
(Udayanamaster lew journal)
Vol. 7 No. 1 Mei 2018 E-ISSN: 2502-3101 P-ISSN: 2302-528x http: //ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu
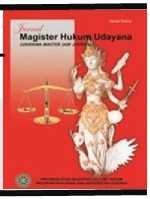
Budaya Hukum sebagai Faktor Pendorong Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerah di Indonesia
Jamiat Akadol1
1 Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Kalimantan Barat
E-mail: jamiatakadolsambas@gmail.com
|
Info Artikel Masuk : 4 Maret 2018 Diterima : 18 Mei 2018 Terbit : 28 Mei 2018 |
Abstract The purpose of this research is to know the legal culture as the driving factor of the realization of regional bureaucracy reform in Indonesia. The method used is the method of normative juridical research with conceptual approaches, legislation, and case |
|
Keywords : Culture, Law, Reform, Bureaucracy |
approach. Various cases of corruption and very bad service in investment activities have hindered and even damaged the image of the Indonesian nation even in today's highly dynamic world. The bureaucratic legal culture is considered the main factor causing such bad bureaucratic behavior. The legal culture of the royal heritage that is only devoted to highways is difficult to remove from bureaucratic behavior. Cultural heritage, was fertile in the new order era, even in the current reform era. Through the optimization of local culture combined with the autonomy and decentralization policy implemented with the principle of autonomy as widely as possible, it can be attempted to overcome the negative culture of bureaucratic culture into a bureaucracy that eventually can be realized good governance. Abstrak |
|
Kata kunci: Kultur, Hukum, Reformasi, Birokrasi |
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui budaya hukum sebagai faktor pendorong terwujudnya reformasi birokrasi daerah di Indonesia. Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan |
|
Corresponding Author: Jamiat Akadol, E-mail: |
pendekatan-pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berbagai kasus korupsi dan |
|
pelayanan yang sangat buruk dalam kegiatan investasi telah menghambat dan bahkan merusak citra bangsa Indonesia bahkan di tingkat dunia yang sangat dinamis saat ini. Budaya hukum birokrasi dianggap sebagai faktor | |
|
DOI : 10.24843/JMHU.2018.v07.i01. p02 |
utama yang menyebabkan perilaku birokrasi yang buruk tersebut. Budaya hukum warisan kerajaan yang hanya mengabdi kepada raya ternyata sulit untuk dihilangkan dari perilaku birokrasi. Kultur warisan, ternyata subur di zaman orde baru, bahkan di zaman reformasi saat ini. Melalui optimalisasi kultur lokal yang dipadukan dengan kebijakan otonomi dan desentralisasi yang dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, kiranya dapat diupayakan dapat mengatasi budaya negatif kultur birokrasi menjadi birokrasi yang pada akhirnya dapat |
diwujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Otonomi daerah yang digulirkan sejak reformasi dibidang pemerintahan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang diberlakukan sejak tanggal 1 januari 2001 benar-benar dirasakan telah mempengaruhi pola pikir dan indakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Dan benar-benar terpacu untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu untuk meningkatkan pelayanan umum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan meningkatkan daya saing daerah.1
Terpecah daerah untuk mewujudkan tujuan otonomi karena didukung oleh kebijakan prinsip otonomi yang ditetapkan adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan yang luas (diluar kewenangan pemerintah pusat) untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Daerah diberikan keleluasaan untuk membuat kebijakan sendiri sesuai dengan kemampuan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang yang tujuannya adalah untuk memberikan peningkatan terhadap pelayanan publik, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Namun, ternyata kebijakan yang luas tersebut tidak serta merta menjadikan daerah maju dan berkembang sesuai dengan tujuan otonomi daerah tersebut. Ada sejumlah daerah yang berhasil memaknai penyelenggaraan otonomi daerah yang ditujukan dengan pencapaian prestasi pembangunan daerah. Namun, ada juga yang gamang dan belum berbuat banyak untuk memajukan daerahnya. Perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut memerlukan dukungan yang kuat dari birokrasi daerah karena kemampuan aparatur yang rendah dapat menimbulkan risiko dalam pelaksanaan desentralisasi, dimana daerah gagal penyelenggaraan pelayanan publik.2
Betapa penting dan strategisnya peran aparatur (birokrasi) di daerah dalam mengembang tugas dan kewenangan daerah yang sangat luas tersebut. Untuk mengujudkan dibutuhakan terciptanya birokrasi pemerintahan yang mampu mendorong upaya pembelajaran sebagai suatu kebiasaan bagi aparat daerah, baik dalam mencermati rangkaian peran birokrasi yang dibutuhkan maupun dalam mengusahakan aktualisasi diri untuk mendukung peran birokrasi tersebut.3Peran aparatur (birokrasi) sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dilepaskan dari penataan tatalaksana yang tercakup dalam aktivitas analisis kebutuhan, yaitu pengelolaan pelatihan yang mencakup aktivitas perancangan, implementasi, pemberlakuan, monitoring dan evaluasi. 4
Harapan yang begitu besar atas peran birokrasi dalam menindaklanjuti kebijakan otonomi daerah ternyata tidak disertai dengan penciptaan kultur hukum birokrasi yang memadai bagi kelan caran tugas birokrasi yang terkesan sangat revolusioner tersebut. Ketika kebijakan desentralisasi yang tidak disertai dengan reformasi aparatur (birokrasi) daerah yang tidak seiring sejalan dan tidak ditempatkan dalam kerangka
kebijakan nasional yang menyeluruh dan terintegrasi dengan baik, maka ketidakharmonisan, konflik dan kekosongan regulasi menyediakan peluang kepada aparatur dan pemangku kepentingan di daerah untuk memiliki dan menginterpretasikan pengaturan yang sama dengan kepentingannya.5 Akibatnya, apabila birokrasi mengalami disfungsi, maka kondisi itu menjadi bahan ajar yang merusak bagi masyarakat.
Realita penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana digambarkan di atas, sangat menarik untuk diamati dan di diskualifikasi lebih lanjut sekedar untuk mengetahui bahkan sangat mungkin untuk mencari solusi terbaik bagi optimalisasi peran birokrasi dalam mendukung tugas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan di daerah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan dan literature hukum yang relevan dengan permasalahan yang di teliti.
Penelitian ini memiliki kesamaan topik dengan penelitian lainnya akan tetapi terdapat perbedaan dalam objek pembahasan. Adapun penelitian yang terkait dengan topik penelitian yang penulis teliti antara lain:
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Happy Susanto, dengan judul Remunerasi dan Problem Reformasi Birokrasi dii Indonesia. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa remunerasi muncul sebagai solusi terhadap isu korupsi yang menimpa sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat di birokrasi. Remunerasi diharapkan bisa meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik, namun nyatanya sebaliknya terjadi. Di sejumlah laporan media, banyak orang yang bekerja di pemerintahan yang tidak absen dari praktik korupsi, meski mereka memiliki gaji tinggi. Remunerasi, yang dalam studi literatur juga disebut sebagai sistem bayar-untuk kinerja, penggunaan pengukuran kinerja yang terkait dengan reward (kompensasi) yang sesuai. Dengan kompensasi yang tepat, karyawan tidak lagi berpikir untuk mencari keuntungan finansial dengan cara yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Di sisi lain, rendahnya tingkat kompensasi akan mempengaruhi kinerja pegawai juga rendah. Pelaksanaan remunerasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, ditambah dengan reformasi birokrasi. Ada kaitan kuat antara kompensasi dan kualitas pelayanan publik. Meningkatkan kualitas pelayanan publik juga ditentukan oleh motivasi mereka, namun pertumbuhan motivasi yang besar adalah karena tingginya kompensasi. Dalam perkembangannya, remunerasi tidak terlepas dari kritik. Padahal, bisa dibilang kebijakan dan tujuan remunerasi seringkali salah arah. Oleh karena itu, pemerintah perlu memasukkan kebijakan ini dengan sanksi tegas jika ada karyawan atau pejabat yang melakukan kesalahan, disiplin, dan melanggar peraturan.6
Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Namlis penelitian tersebut menghasilkan gagasan bahwa terciptanya birokrasi melalui proses politik berdampak pada kepentingan yang sering kali saling bertentangan. Kesulitan dalam menerapkan perubahan barangkali karena konsensus politik tidak mudah didapat. Peraturan sering dibuat dengan lebih banyak harapan untuk mengatur perilaku organisasi dan
birokrasi. Namun, kebanyakan peraturan saling bertentangan satu sama lain, jadi peraturan nya berubah bahkan sebelum diimplementasikan dan perubahannya juga bertentangan dengan yang lain. Perubahan seringkali sulit karena perubahan permintaan tidak hanya untuk aturan, tapi juga birokrasi yang erat kaitannya dengan sikap mental atau orang di balik sistem. Jika birokrasi publik dalam pelayanan publik tidak memenuhi syarat, birokrasi akan ditinggalkan oleh pengguna (warga negara), dan itu berarti telah gagal misi memberikan pelayanan kepada publik. Inilah yang terjadi dalam pemerintahan transisi Indonesia memasuki era reformasi, oleh karena itu legislasi perlu diciptakan secara lebih rinci untuk mengatur perilaku organisasi dan birokrasi pemerintah.7
Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Erisandi Arditama tentang Mereformasi Birokrasi Dari Perspektif Sosio-Kultural: Inspirasi Dari Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Masalah administrasi dan manajemen kerja bukanlah satu-satunya masalah kompleksitas birokrasi. Namun, di Yogyakarta juga tentang internalisasi kepentingan budaya istana ke dalamnya. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan perspektif sosio-kultural sebagai alternatif dalam mempelajari reformasi birokrasi kota dan semoga bermanfaat untuk ruang lingkup birokrasi Indonesia yang lebih luas. Dengan mem-prakarsai gagasan kerangka kerja dekonstruksi, penelitian ini menganalisis strategi walikota Yogyakarta saat ini dalam menguangkan nilai-nilai priyayi di birokrasi kota. Akhirnya, penelitian ini menekankan bahwa contoh kepemimpinan yang baik adalah kunci utama untuk mewujudkan misi birokrasi dan pelibatan yang terbuka pada saat bersamaan.8
Budaya hukum birokrasi pelayanan publik dalam tulisan ini diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, persepsi, anggapan dan harapan yang mendasari sikap dan perilaku birokrasi terhadap hukum yang berlaku dalam kegiatannya memberikan pelayanan kepada masyarakat.9 Sementara itu yang dimaksud dengan birokrasi adalah birokrasi pemerintahan10 yaitu dapat dibaca sebagai birokrat, yaitu para pejabat pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemerintahan dalam arti sempit (eksekutif). Birokrasi pemerintahan sebagai fokus dalam pembahasan tentang budaya hukum birokrasi pelayanan publik adalah unsur yang penting dan menentukan karena kewenangan yang dimilikinya dan harapan perbaikan pelayanan dari masyarakat.
Kewenangan birokrasi dalam memberi kan pelayanan publik sebagai konsekuensi negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai negara kesejahteraan sebagaimana diamanahkan dalam pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-undang Dasar 1945. Negara yang dalam hal ini adalah birokrasi pemerintahan wajib memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Semua kebutuhan dasar masyarakat menjadi
tanggung jawab negara, yaitu kebutuhan dasar seperti pelayanan kesehatan dan kebutuhan administrasi dasar yang berhubungan dengan identitas diri, infrastruktur seperti jalan, irigasi maupun penyediaan sarana transportasi.11 Jadi, pelayanan publik bukan sekedar menggugurkan kewajiban negara untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi lebih sebagai bukti kepercayaan (trust) warga negara terhadap adanya negara, bukti bahwa negara ada di dekat rakyatnya dan peduli dengan berbagai kepentingan rakyatnya. Begitu pentingnya pelayanan publik bagi masyarakat suatu negara, Haryatmoko12 mendefinisikan pelayanan publik sebagai semua kegiatan yang pemenuhannya harus dijamin, diatur, dan diawasi oleh pemerintah karena diperlukan untuk perwujudan dan perkembangan kesalingtergantungan sosial dan pada hakikatnya perwujudannya sulit terlaksana tanpa campur tangan kekuatan pemerintah. Dengan demikian, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.13
Penelitian hukum merupakan segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang berkenaan dengan kenyataan hukum dan masyarakat. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
Birokrasi di Indonesia dinilai sangat korup. Bahkan, penilaian birokrasi yang demikian itu dianggap telah mencoreng bangsa Indonesia dimata dunia. Pemerintah yang berkuasa (Pemerintah SBY-Budiono) dinilai dengan raport yang “merah” karena gagal menekan apalagi menghapus korupsi yang terbukti telah merugikan rakyat dan merusak moral para pejabat di negeri ini. Kasus “Gayus Tambunan” hampir setiap saat dibicarakan diberbagai media, bahkan dalam percakapan serius maupun santai dimana-mana, tidak terkecuali di warung kopi.
Berbagai cara dan perundang-undangan telak dilakukan dan dibentuk untuk mengatasi korupsi, akan tetapi tetap saja seorang Gayus Tambunan yang hanya PNS golongan IIIa tersebut tidak mampu diatasi. Dia bisa dengan leluasa meninggalkan rumah tahanan untuk liburan ke Bali, bahkan ke Hongkong dan sejumlah nagara lain. Tidak sedikit orang atau pejabat yang terlibat dan dilibatkannya dalam kasusnya, akan
tetapi justru dia (Gayus Tambunan) terkesan semakin “sombong” karena pernyataannya yang menyeret berbagai pihak, bahkan pihak luar negeri (CIA).14
Apapun yang telah dan akan diungkap dalam berbagai tindakan korupsi di negara ini, belum mampu mengangkat citra birokrasi dan pemerintah berkuasa saat ini. Bahkan, kinerja birokrasi Indonesia mendapat predikat terburuk nomor dua di Asia, setelah India dalam hal efisiensi pelayanan masyarakat dan iklim investasi asing.
Dengan skala 1 terbaik dan 10 terburuk, Indonesia mendapat nilai 8,59 dan India 9,41, sementara Malaysia dengan nilai 6,97, Cina 7,93 dan Singapura 2,53. Bahkan dengan negara baru bangkit dari perang saudara seperti Vietnam yang dinilai 8,13, berarti kita masih tertinggal. Hal itu juga diakui oleh Pemerintah Indonesia, bahwa indeks persepsi korupsi yang dicapai Indonesia mengalami perbaikan (sedikit) yaitu dari 2,0 pada tahun 2004 menjadi 2,6 pada tahun 2006 dan 2,8 pada tahun 2009. Dengan indeks persepsi korupsi skala 1 terburuk sampai dengan 10 paling baik, bararti Indonesia telah bangkit dari negara dengan tata kelola pemerintahannya dianggap buruk menjadi sebuah negara dengan tata kelola pemerintahannya yang membaik dan perlu terus ditingkatkan melalui reformasi birokrasi secara terencana, komprehensif dan bertahap terus dimantapkan pelaksanaannya. Hal itu bermakna bahwa reformasi birokrasi mutlak dilakukan secara sungguh-sungguh. Reformasi birokrasi yang bersifat melayani dan dinamis sangat dibutuhkan dan peran serta partisipasi masyarakat akan sangat mendukung reformasi birokrasi salah satunya dalam bentuk pembuatan kebijakan .15 Keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya ditentukan oleh pihak internal yaitu pihak birokrat itu sendiri, namun juga dibutuhkan peran serta dari pihak eksternal, yaitu turut serta berpartisipasi, memberikan aspirasi serta kritik yang membangun sehingga pada akhirnya akan tercipta tatanan yang teratur dan memberikan kepastian hukum.16 Jika reformasi birokrasi tidak dilakukan secara baik, terencana dan dilaksanakan dengan sepenuh hati dan terus menerus, bukan mustahil nilainya justru menurun, dan mungkin menjadi negara dengan tata kelola pemerintahan terpuruk di dunia. (Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembanggunan Jangka Menengah Nasional.17
Membahas reformasi birokrasi sama artinya dengan mengupayakan bagaimana melakukan restrukturisasi dan reposisi sistem dan perilaku birokrasi pemerintah menuju tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Sementara itu menurut Arbi Sanit bahwa sesungguhnya arah reformasi birokrasi pemerintahan secara nasional yang dirumuskan dan ditegaskan oleh presiden SBY sejak tahun 2004 merupakan menerapkan prinsip clean government dan good governance sebagaimana diyakini secara universal, merupakan kondisi bagi pelayanan prima pemerintah
melalui birokrasinya kepada masyarakat.18 Untuk itu, perubahan sikap dan tingkah laku birokrat, dikondisikan melalui pembaharuan organisasinya berdasar tatanan yang tepat bersama pengetatan sistem reward and punishment, sehingga terbangun cara kerja dan disiplin serta komitmen pada kinerja yang efektif, efisien dan produktif. Dengan demikian, melakukan reformasi birokrasi itu ternyata tidak sederhana karena menyangkut berbagai aspek yang harus diperbaiki karena birokrasi Indonesia yang memandang terbukti sangat buruk, baik dalam hal pelayanannya maupun perilaku korupsinya sebagai mana telah disinggung di atas.
Reformasi birokrasi di Indonesia diperlukan setidaknya disasarkan pada kondisi nyata: (1). Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih terus berlangsung hingga saat ini; (2). Tingkat kuali tas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan publik; (3). Tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang belum optimal dari birokrasi pemerintahan dan (4). Tingkat trasnparansi dan akuntabilitas birokrasi Indonesia yang masih rendah, serta (5). Tingkat disiplin dari etos kerja pegawai yang masih rendah.19(PER/15/M.PAN/7/2008).
Beberapa penelitian menunjukan bahwa fenomena pelayanan publik adalah potret yang sangat menyedihkan. Hasil penelitian Governance Assessment Survey menunjukkan akses masyarakat dibidang kesehatan, pendidikan, dan permodalan masih rendah. Kualitas pelayanan terhadap tiga bidang itu baik menyangkut prosedur dan biaya masih dirasakan belum memuaskan. Rendahnya kualitas pelayanan publik di daerah sebagaimana disebutkan diatas adalah fakta yang tidak mungkin dapat ditutup-tutup lagi. Semua orang sudah tahu dan tidak perlu dipermasalahkan lagi, “siapa yang salah “karena hal tersebut hanya akan hanya akan menyebabkan bertambah ruwetnya persoalan birokrasi yang padahal kondisi sangat diragukan bila dikaitkan dengan berbagai tantangan perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin luas dan variatif saat ini.20
Berbicara tentang kultur hukum birokrasi, tidak dapat dipisahkan dari kultur masyarakat dan kondisi pemerintah dimana birokrasi itu berada. Demikian pula halnya dengan kultur (budaya) birokrasi yang ada di Indonesia. Birokrasi publik di Indonesia yang berakar pada birokrasi kerajaan yang bersendirian para priyayi (kerabat raja) yang kemudian berlanjut menjadi pilar utama birokrasi kolonial (pangreh praja) sebagai instrumen utama penerapan politik indirect rule dengan berbagai pengaruhnya: sistem politik dan pemerintahan yang dianut, gaya hidup dan cara mereka di didik tentunya sangat membekas dalam budaya birokrasi modern Indonesia saat ini.21 Penggunaan istilah atau sebutan sebagai pangreh praja bagi birokrasi pada masa pemerintahan kolonial sebenarnya memberikan makna pada kedudukan birokrasi yang hanya berperan sebagai alat pemerintahan kolonial. Pengertian pangreh praja (bestuur), dalam pemerintahan kolonial memberikan batasan
terhadap peran dan fungsi lembaga birokrasi. Birokrasi lebih dominan ditempatkan hanya sebagai pemberi perintah kepada rakyat (fungsi regulasi dan kontrol) dari pada sebagai lembaga yang memiliki fungsi pelayanan publik. Dengan fungsi tersebut maka tugas utama birokrasi hanyalah sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang hanya mematuhi tugas-tugas yang di instruksikan atau diperintahkan oleh atasannya. Akuntabilitas birokrasi tentulah hanya ditujukan kepada pejabat atasannya, bukan kepada publik. Demikian pula loyalitas dan pertanggungjawaban aparat ditingkat bawah semata-mata hanya ditujukan kepada pejabat di atasnya. Terlebih lagi, prestasi kerja seorang aparat birokrasi di mata pimpinan hanya dilihat dari kriteria seberapa besar loyalitasnya kepada pimpinan.22 Senada dengan birokrasi seperti itu yang berorientasi semata-mata pada pimpinan, dapat dikemukakan struktur birokrasi dengan sistem nilai budaya patronase dengan pemahaman aparat pelayanan yang lebih rendah harus loyal kepada pimpinan sebagai pribadi, bukan kepada visi dan misi institusi birokrasi serta tujuan pelayanan kepada publik.23
Terlebih lagi bahwa loyalitas itu dibuktikan dari perilaku bawahan yang selalu ingin atau dipaksa untuk menyenangkan hati pimpinan melalui antara lain membuat laporan yang baik-baik saja (ABS = Asal Bapak Senang). Perbuatan menyenangkan pimpinan adalah wajib se-bab dianggap sebagai wujud terima kasih bawahan atas kebaikan hati pimpinan yang telah mengangkatnya menduduki jabatan tertentu dalam birokrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, budaya pelayanan dan menganggap “upeti” yang berupa sogok dan suap sebagai hal biasa untuk menggerakan birokrasi dalam memberikan pelayanan.. Budaya (kultur) birokrasi pada dasarnya adalah nilai-nilai, norma-norma dan jiwa yang mendasari gerak langkah dan tindak tanduk birokrasi.
Budaya birokrasi menjadi faktor yang penting dalam menjelaskan kegagalan birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Praktek-praktek, simbol-simbol dan nilai-nilai serta perilaku birokrasi dalam mem berikan pelayanan publik yang terkesan lamban, berbelit-belit, mahal bahkan terkesan dibuat-buat agar kelihatan memang ruwet adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah lagi. Namun demikian kondisi yang demikian itu dianggap wajar dan bahkan memiliki kekuatan normatif dalam arti telah diakui oleh masyarakat bahwa pelayanan publik di Indonesia sudah seperti adanya dan memang harus seperti itu.
Kultur birokrasi yang telah menginstal sebagai kekuatan-kekuatan sosial yang terus menerus menggerakkan hukum merusak disini, memperbaharui disana; menghidupkan disini, mematikan disana; memilih bagianmana dari hukum yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak mengganti, memintas, melewati apa yang muncul; perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam menurut L.Friedman adalah dapat dikatakan sebagai kultur hukum birokrasi.24Lebih lanjut disebutkan dan dijelaskan bahwa kultur hukum adalah elemen sikap sosial, mengacu pada bagian yang ada pada kultur umum adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu. Jadi, istilah kultur hukum adalah
menggambarkan sikap-sikap mengenai hukum yang akan mengenai kehidupan mesin sistem hukum, sehingga bergerak atau sebaliknya akan menghentikannya di tengah jalan.
Kultur hukum sebagai kekuatan sosial, yakni kekuasaan dan pengaruhnya, akan meng hasilkan tekanan kepada sistem hukum dan akan menimbulkan tindakan hukum apabila kultur hukum mengubah kepentingan menjadi tuntunan atau memungkinkan terjadinya perubahan itu. Kultur hukum birokrasi dengan demikian adalah pola-pola sikap dan perilaku birokrasi terhadap sistem hukum atau bagai mana pemahaman mereka (masyarakat) mengenai tindak tanduk birokrasi dalam menjalankan hukum dan bagaimana sikap masyarakat terhadap hukum secara umum. Satu jenis kultur hukum kelompok yang amat penting adalah kultur hukum para professional hukum nilai-nilai, ideologi dan prinsip-prinsip para pengacara, hakim dan lain-lain yang bekerja dalam lingkaran ajaib sistem hukum.25
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa kultur hukum birokrasi dipengaruhi oleh kultur suatu bangsa dan sistem politik dan pemerintahan dimana birokrasi itu bekerja. Birokrasi Indonesia yang pernah besar sebagai sebuah kerajaan, kemudian dijajah oleh Belanda lebih kurang 300 tahun. Ketika telah menjadi negara merdeka, sistem pemerintahan yang dijalankan secara lebih tersentralisasi sehingga sangat mempengaruhi budaya hukum birokrasi. Birokrasi hanya sebagai pelayan penguasa bukan sebagai pelayan rakyat. Terlebih lagi dimasa orde baru, simbol-simbol “penguasa tunggal, stabilitas nasional, kepentingan negara untuk pembangunan telah menjadi basis dan kriteria dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.26
Orde baru memperlakukan birokrasi sebagaimana birokrasi kerajaan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1). Penguasa menganggap dan menggunakan administrasi publik publik sebagai urusan pribadi; (2). Administrasi adalah perluasan rumah tangga istananya; (3). Tugas pelayanan ditujukan kepada pribasi sang raja; (4). Gaji dari raja kepada pegawai (birokrasi) adalah anugerah yang sewaktu-waktu dapat ditarik sekehendak raja; dan (5). Para pejabat kerajaan dapat bertindak sekehendak hatinya kepada rakyat, seperti halnya yang dilakukan oleh raja.
Pola hubungan antara bawahan dengan pimpinan dalam birokrasi dikatakan oleh Kausarsebagai pola hubungan yang penuh emosional antara orang yang mengabdi dan memperabdi yang sangat berpengaruh pada sistem birokrasi. Pola hubungan patron-klien yang memposisikan seorang bawahan dan atasan disamakan dengan posisi hubungan antara anak dengan bapaknya dalam konsep jawa. Seorang anak harus menghormati bapaknya yang secara praktis termanifestasi dalam perasaan sungkan dan berbahasa halus (kromo) dalam berbicara dengan bapak. Anak melayani orang tua untuk mencari perhatian dan orang tua harus dapat memberikan perhatian atas sesuatu yang lain yang dapat menunjukkan sebuah perhatian.27Dalam rangka reformasi birokrasi, sudah saatnya mengubah paradigma berpikir dilayani, pangreh
praja, dan menguasai menjadi paradigma melayani, pelayan masyarakat, memfasilitasi dan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan publik. Birokrasi melayani menumbuhkan hubungan harmonis antara pemberi pelayanan dengan publik yang dilayani, serta sikap birokrasi menjadi lebih terbuka, jujur, transparan, serta tidak diskriminatif.28
Budaya patron-klien terlepas dari unsur positif dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap perilaku birokrasi di daerah, sebenarnya dapat disiasati dengan mencoba mempertemukannya dengan budaya lokal tempat birokrasi itu dijalankan dan diterapkan. Nilai dasar kejujuran yang dikembang atas dasar pemahaman terhadap norma, agama dan budaya setempat paling tidak akan membuat mereka menjalankan birokrasi pemerintahan dapat mempertemukan ide profesionalisme dan bersikap profesional dalam memahami kepentingan individu, kepentingan kelompok atau kepentingan masyarakat yang memperoleh pelayanan birokrasi tersebut. Pengembangan budaya lokal dalam rangka membangun kultur hukum birokrasi daerah sangat terbuka lebar.
Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, yaitu otonomi yang seluas-luasnya. Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan kepada rakyat dan meningkatkan daya saing daerah. Daerah hendaknya belajar dari Jepang yang mana budaya birokrasinya mengutamakan integritas moral yang tinggi, dedikasi tanpa diragukan lagi oleh bangsa dan negaranya dan memiliki rasa malu yang tinggi apabila melakukan kesalahan menjadi faktor pembeda mengapa birokrasi Jepang menjadi instrumen efektif untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan di negaranya. Bahkan budaya Paunganderung menjadi nilai dan sebagai pedoman bagi orang-orang Bugis dan mempunyai sifat luwes, terbuka atas dinamika masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan anasir-anasirnya yang ada, yang justru di dalamnya terkandung prinsip assituruseng (persepakatan), sebagai kaidah tertinggi. Menurut Fukuyama, elemen-elemen sosiokultural sangat potensial mendorong perubahan birokrasi meskipun disadari bahwa tidak mudah dan bahkan merupakan faktor tersulit dalam melembagakan sosiokultural ke dalam rangka merubah birokrasi.29 Kiranya nilai budaya sebagai kaidah tertinggi.30 Kiranya nilai budaya yang luhur tersebut dapat dikembangkan dengan terencana dan terus menerus maka bukan mustahil budaya hukum birokrasi yang tadinya sangat tidak memihak kepada rakyat, dapat berubah menjadi budaya yang mendukung penegakan hukum, berpihak pada keadilan dan ketertiban dan dapat dijadikan contoh bagi rakyat. Pada akhirnya, kekuasaan birokrasi benar-benar sangat bermanfaat bagi peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bagi upaya meningkatkan daya saing daerah.
4.Kesimpulan
Reformasi adalah kebijakan nasional yang saat ini sedang diupayakan pelaksanaannya. Berbagai peraturan perundang-undangan telah ditetapkan untuk
mendukung kebijakan tersebut, tetapi ternyata reformasi birokrasi sulit untuk dilaksanakan. Berbagai kasus korupsi dan pelayanan yang sangat buruk dalam kegiatan investasi telah menghambat dan bahkan merusak citra bangsa Indonesia di dunia global yang sangat dinamis saat ini. Kultur hukum birokrasi dianggap sebagai faktor utama yang menyebabkan perilaku birokrasi yang buruk tersebut. Kultur hukum warisan kerajaan yang hanya mengabdi kepada raja ternyata sulit untuk dihilangkan dari perilaku birokrasi. Kultur warisan, ternyata tumbuh subur di zaman orde baru, bahkan di zaman reformasi saat ini. Melalui optimalisasi kultur lokal yang dipadukan dengan kebijakan otonomi dan desentralisasi yang dilaksanakan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, kiranya dapat diupayakan dapat mengatasi budaya negatif kultur birokrasi menjadi sebaliknya adalah budaya birokrasi yang sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Daftar Pustaka
Buku
Dwiyanto, A. dalam Wahyudi, K. & Ambar, W.(editor) (2010). Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali. Jakarta: GAVA Media.
Haryatmoko. (2011). Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
Saleh, K. A. (2009). Sistem Birokrasi Pemerintah di Daerah: Dalam Bayang-Bayang Budaya Patron Klien. Bandung: Alumni.
Friedman, L. M. (1975). The Legal System: A Social Science Perspective, diterjemahkan oleh M. Khozion, 2009. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.
Muchlis. (2009). Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 30. Jakarta: MIPI.
Puspitosari, H., Khalikussabir, Kurniawan, L. J., & Lutfi, M. (2011). Filosofi pelayanan publik: buramnya wajah pelayanan menuju perubahan paradigma pelayanan publik. Malang: Setara Press
Ridwan, J., & Sodik, A. (2009). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa Cendekia.
Thoha, M. (2010). Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Jurnal
Akhmaddhian, S. (2012). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Perizinan Penanaman Modal di Daerah (Studi Kasus di Pemerintahan Kota Bekasi). Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), 464-478. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.120
Arditama, E. (2013). Mereformasi Birokrasi dari Perspektif Sosio-Kultural: Inspirasi dari Kota Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 17(1). 85-100.
https://doi.org/10.22146/jsp.10895
Desiana, A. (2014). Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance. Jurnal Manajemen Pemerintahan. 1(1),19-47.
Mahmud, F. (2017). Implementasi Kebijakan Diklat Teknis pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo. Jurnal Administrasi Publik, 13(2), 95-106.
Malau, H. (2009). Menyoal Pelayanan Publik yang Berkualitas di Era Otonomi Daerah. Jurnal Demokrasi, 8(1), 1-16.
Namlis, A. (2015). Reformasi Birokrasi suatu usaha untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Humanus. 14(1). 49-55.
https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5401
Caesaringi, I., Harsasto, P., & Manar, D. G. (2017). Reformasi Birokrasi Kota Tegal (Studi Kasus Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih BP2T dan RSUD Kardinah). Journal of Politic and Government Studies, 6(03), 541-550.
Susanto, H. (2016).Remunerasi dan Problem Reformasi Birokrasi dii Indonesia. Jurnal Publisia (Jurnal Ilmu Administrasi Publik), 1(1), 54-60.
Tanjung, I. (2013). Kearifan Lokal dan Pemberantasan Korupsi dalam Birokrasi. MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan, 29(1), 101-110.
Disertasi
Akadol, Jamiat. (2016). Rekonstruksi Budaya Hukum Birokrasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Hukum Progresif (Studi Tentang Budaya Hukum Birokrasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi pada Puskesmas dan RSUD di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat). Disertasi. Semarang. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Negara
Peraturan Pemerintah Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembanggunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2010, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2010, BPK-RI.Jakarta.
23
Discussion and feedback