Pertimbangan Rasa Keadilan Masyarakat dalam Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi
on
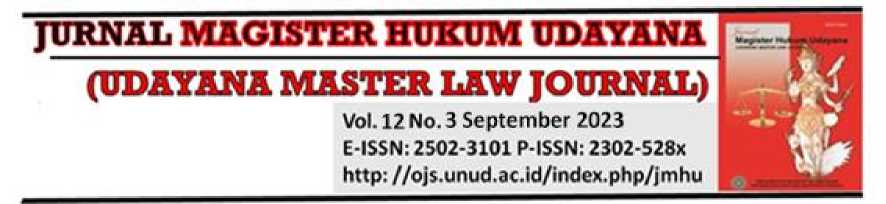
Pertimbangan Rasa Keadilan Masyarakat dalam Putusan Ultra Petita Penanganan Kasus Korupsi
Y. Sri Pudyatmoko1, G. Aryadi 2
-
1 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, E-mail: pudyku07@gmail.com
-
2 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, E-mail: g.aryadi@uajy.ac.id
Info Artikel
Masuk:12 Juli 2023
Diterima:26 September 2023
Terbit: 28 September 2023
Keywords:
Judge's consideration; Ultra petita decisions; Corruption cases; Community justice
Kata kunci:
Pertimbangan Hakim; Putusan ultra petita; Kasus korupsi;
Keadilan masyarakat
Corresponding Author:
Y. Sri Pudyatmoko, E-mail :
DOI:
10.24843/JMHU.2023.v12.i0
3.p14
Abstract
This study aims to analyze ultra petita decisions in corruption cases with consideration of the community's sense of justice. The research method used in this study is a normative legal research method, using a case approach. The research was conducted by analyzing several ultra petita decisions in corruption cases. The results of the study show that in the ultra petita decisions against convicts in corruption cases, some explicitly consider the community's sense of justice. There is a problem raised in the consideration of the judge's decision between prioritizing the application of the formal definition of unlawful which uses the size of the law according to the principle of legality, or applying material teachings in accordance with the people's sense of justice even though it is not regulated in law. In dealing with corruption cases, judges refer not only to laws but also to regulations from the Supreme Court. In accordance with these guidelines, judges in making decisions use comprehensive considerations. Some considerations of community justice are not used as the basis for imposing ultra petita sanctions, but in other sanctions.
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan ultra petita kasus korupsi dengan pertimbangan rasa keadilan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan ultra petita kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan ultra petita terhadap terpidana kasus korupsi sebagian mempertimbangkan secara eksplisit rasa keadilan masyarakat. Ada persoalan yang dikemukakan dalam pertimbangan putusan hakim antara mengedepankan penerapan pengertian melawan hukum secara formil yang menggunakan ukuran undang-undang sesuai asas legalitas, atau menerapkan ajaran materiil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat sekalipun tidak diatur dalam undang-undang. Hakim dalam menangani kasus korupsi selain mengacu undang-undang juga mengacu pada regulasi dari Mahkamah Agung. Sesuai pedoman tersebut hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan pertimbangan yang komprehensif. Pertimbangan keadilan masyarakat ada pula yang tidak digunakan untuk menjadi dasar pengenaan sanksi ultra petita, melainkan dalam sanksi lainya.
-
I. Pendahuluan
Tugas utama pengadilan adalah untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Menurut Ismail Rumadan tugas utama pengadilan untuk mewujudkan keadilan dan kedamaian di tengah masyarakat masih jauh dari harapan. 1 Sebagai Lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, pengadilan bertugas dan berwenang menangani perkara untuk membawakan keadilan bagi masyarakat. 2 Keadilan dimaksud dicerminkan dari bagaimana Lembaga ini bersikap dan bertindak selama menangani perkara, dan terutama terlihat dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim. 3 Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan hakim yang baik dan mempunyai integritas dengan sistem peradilan yang baik pula. Salah satu hal yang dinilai merupakan cerminan dari hal tersebut adalah ketika hakim keluar dari kecenderungan umum dengan menjatuhkan putusan ultra petita, termasuk dalam kasus korupsi.
Menurut Issha Haarruma, secara umum, ultra petita dapat diartikan sebagai penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang diminta.4 Ultra petita diambil dari kata Ultra yakni lebih, melampaui, ekstrim, sekali, dan Petita yakni permohonan.5 Hal senada juga disampaikan oleh Ranu Handoko. Menurut Ranu Handoko, Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta.6
Putusan ultra petita dalam bidang Hukum Pidana seringkali dikaitkan dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa mengenai musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya yang dijadikan dasar oleh hakim dalam membuat putusan adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka menurut Yahya Harahap bahwa Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.7
Menurut Yagie Sagita Dalam Hukum Acara Pidana, putusan ultra petita dikarenakan dakwaan jaksa penuntut umum kurang sempurna, dan sebagai wujud pengembangan hukum progresif dimana hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, tetapi merupakan corong keadilan yang mampu memberikan putusan yang berkualitas dengan menemukan sumber hukum yang tepat.8
Putusan ultra petita dalam kasus korupsi sering kali menarik perhatian masyarakat, karena menyimpang dari kebiasaan dalam penjatuhan pidana yang cenderung di bawah tuntutan JPU sekaligus menyangkut kerugian negara dan kepentingan publik. Public acapkali mempunyai harapan tertentu dan penilaian sendiri terhadap kasus yang sedang diproses di pengadilan, termasuk dalam soal keadilan. Ayala dan Wilcox sebagaimana dikutip David Seetsa Makateng dalam tulisanya berjudul: The Conceptualization of the Study of Social Justice: A Systematic Review, menyatakan bahwa Social justice is generally defined as the fair and equitable distribution of power, resources, and obligations in society to all people, regardless of race or ethnicity, age, gender, ability status, sexual orientation, and religious or spiritual.9 Keadilan masyarakat dalam kaitanya dengan hukum menurut Satjipto Rahardjo merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Menurut beliau Setiap pembicaraan mengenai hukum (baik secara jelas maupun samar) senantiasa merupakan pembicaraan tentang keadilan. Membicarakan hukum tidak cukup hanya sampai wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, tetapi perlu juga melihatnya sebagai ekspresi dari cita- cita-cita keadilan masyarakat. 10
Dalam setiap putusan hakim di Indonesia pada bagian kepala selalu dimuat frasa: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.11 Filosofi makna keadilan dalam kepala putusan inilah sebenarnya untuk mewujudkan keadilan yang sebenarnya.12 Namun dalam kenyataannya, karena dalam praktik di pengadilan pada umumnya dilandaskan pada aliran positivisme yang menekankan pada prosedur dan memandang hukum sebatas aturan belaka, sehingga yang terwujud adalah keadilan prosedural, bukan keadilan substansial.13 Tidak mudah memang untuk mewujudkan rasa keadilan masyarakat. Menurut Fence, terdapat kendala baik secara internal yang datangnya dari diri hakim itu sendiri, maupun eksternal dari luar hakim yang yang mesti dihadapi hakim dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kendala internal bisa berupa pengangkatan hakim, pendidikan hakim, penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, moral hakim, kesejahteraan hakim. Sementara kendala eksternal datangnya dari luar diri hakim itu sendiri. Kendala eksternal hakim
bisa menyangkut kemandirian kekuasaan kehakiman, pembentukan undang-undang, sistem peradilan yang berlaku, partisipasi masyarakat, pengawasan hakim.14
Penelitian ini dilakukan terhadap Putusan Nomor: 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, dan Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai putusan ultra petita hakim kasus korupsi dan mencari jawaban argumentatif mengenai dasar pertimbangan putusan kasus korupsi, khususnya dari aspek keadilan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan esensi penelitian hukum adalah untuk menyelesaikan atau memecahkan persoalan hukum yang ada,15 maka penting untuk mencermati peraturan terkait dengan penjatuhan putusan, khususnya terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dari penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil pemikiran yang baik berkait dengan pertimbangan yang digunakan hakim secara komprehensif, khususnya berkait dengan keadilan masyarakat dalam menangani kasus korupsi.
Perihal state of the art, di dalam proses penyusunan penelitian ini, ditemui beberapa penelitian terdahulu yang membahas persoalan hukum mengenai putusan ultra petita. Pertama, jurnal dengan judul Penerapan Prinsip Ultra Petita dalam Hukum Acara Pidana dipandang dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana,16 yang menekankan penelitiannya dari aspek filosofis yuridis pertimbangan putusan hakim kasus pidana secara umum. Kedua, jurnal dengan judul Keadilan Substantif Dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi, 17 yang meneliti putusan-putusan Mahkamah Konsitusi yang konstitusional bersyarat untuk menemukan apakah dalam putusan tersebut benar-benar untuk menegakkan keadilan yang mana keadilan tersebut tidak bisa terwujud jika hanya menghapuskan pasal yang dimohonkan.
Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus (case approach) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap sejumlah putusan pengadilan atas kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dalam hal ini putusan ultra petita kasus korupsi yang telah dijatuhkan oleh hakim.18 Putusan dimaksud yakni: Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, Nomor
11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, 17/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG, dan putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.
Hakim dalam perkara pidana menjatuhkan putusan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Dasar hukum kekuasaan kehakiman saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Pasal ini memberikan arahan kepada hakim dalam melaksanakan tugasnya menyelesaikan berbagai permasalahan hukum tidak semata-mata terbatas kepada hukum tertulis saja. Ketentuan tersebut menghendaki sikap aktif dan kreatif hakim dalam mengadili dan menyelesaikan perkara hukum, dengan menggali dan memahami nilai-nilai di tengah masyarakat merupakan langkah untuk mengadili, mengikuti dan sesuai nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.
Menurut ketentuan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan bahwa mengenai musyawarah hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. 19 Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya yang dijadikan dasar oleh hakim dalam membuat putusan adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Hakim dapat menjatuhkan putusan berupa sanksi sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Yahya Harahap berpendapat bahwa hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana (strafmaat) yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas. 20 Undang-Undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana berkait dengan tindak pidana yang bersangkutan. Pasal 12 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan hukuman pidana penjara selama waktu tertentu itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.21 Dalam hal ini pembuktian di persidangan dapat menentukan putusan, karena hakim memperhatikan apa yang dibuktikan dalam pemeriksaan perkara.22
Sekalipun hakim sebenarnya bebas dalam menjatuhkan putusan, akan tetapi bukan berarti tanpa batas sama sekali. Batasan tersebut dapat berupa: putusan tidak boleh
melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan. 23 Tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya (strafsoort) tidak ada acuannya dalam KUHP. 24 Untuk saat ini juga termasuk di luar KUHP mestinya, mengingat ketentuan pidana tidak hanya di dalam KUHP. Putusan pemidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti.25
Secara normatif untuk mengenakan sanksi, Hakim dalam menangani kasus korupsi juga dipandu dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut diatur bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut:26
-
a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
-
b. tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
-
c. rentang penjatuhan pidana;
-
d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
-
e. penjatuhan pidana; dan
-
f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.
Ketentuan tersebut mengarahkan bahwa bagi hakim dalam menangani perkara korupsi mesti mempertimbangkan secara komprehensif dari berbagai hal tersebut. Dari a sampai f tersebut sifatnya kumulatif, bukan alternatif. Artinya semuanya keenam hal tersebut harus dipertimbangkan secara berurutan, tanpa ada yang terlewatkan. Aturan ini tidak menyebut secara eksplisit soal keadilan, yang selama ini dinilai sangat penting. Rasa adil kiranya dapat diperoleh dengan mewujudkan pertimbangan tersebut dengan baik, seperti misalnya bila hal tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi keuangan negara maka tentu hukumanya lebih berat bila dibandingkan dengan kerugian yang sangat kecil. Apabila tindakan korupsi tadi dilakukan untuk keuntungan pelaku yang melakukan berulang kali dengan skala besar tentu berbeda bila hal tersebut ternyata hanya karena terdesak untuk menyambung hidup. Hal seperti itu tentu juga dirasakan oleh masyarakat.
Sebagaimana dikemukakan Bell, Social justice is commonly viewed as a guiding principle to achieve a just society, understood both as a means as well as an end. Social justice includes a wide variety of social goals, including full and equal participation of individuals in all social institutions; fair, equitable distribution of material and nonmaterial goods (otherwise known as distributive justice); and recognition and support for the needs and rights of individuals. Social justice is also associated with a variety of processes which challenge dominance and oppression,
recognize the interconnectedness and interdependence of all human beings, and champion collaboration and solidarity.27
Sementara menurut Ana Suheri keadilan sosial dapat diartikan sebagai: (1) Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak. (2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha. (3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.28 Keadilan dari masyarakat merupakan bagian dari rasa keadilan yang ada di dalam setiap perasaan individu yang menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. 29 Menurut Pandit sesungguhnya hakekat dari keadilan itu adalah memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak dan kewajibannya.”30
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 ini memiliki dua peran penting utama. Pertama, memberikan penafsiran dan penyempurnaan rumusan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan dan mengkuantifikasi antara lain kategori kerugian negara beserta kerugian ekonomi negara, dan skala minimal dan maksimalnya. Unsur kalimat sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut. Kedua, memberikan para hakim pedoman yang harus diterapkan oleh mereka dalam proses pengadilan.31 Dengan adanya Perma tersebut hakim dalam menangani kasus korupsi ada pegangan yang relatif jelas. Akan tetapi bagaimanapun juga hakim tetap mempunyai ruang kebebasan, yang mana rasa keadilan dan kepastian digunakan dengan melihat dan mempertimbangkan berbagai hal yang melingkupi kasus konkrit.
Pembentukan Perma Nomor 1 Tahun 2020 berdasarkan politik hukum sebagai upaya MA untuk mengisi kekosongan hukum akibat absennya pedoman pemidanaan yang menyebabkan terjadinya disparitas. Meskipun demikian, substansinya belum sepenuhnya mampu mewujudkan kepastian hukum disebabkan terbatasnya ruang lingkup pengaturan dan absennya sanksi bagi hakim yang tidak mengikutinya. 32 Pedoman tidak menjangkau semua kasus secara sangat rinci dan detil karena varian kasus memang beragam. Hakim bukanya tidak mungkin keliru, oleh karena itu dalam menjalankan tugasnya mesti mendapatkan kontrol, akan tetapi jangan sampai gara-gara
kontrol tersebut maka keberanian hakim untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran menjadi terhambat.
Soal implikasi Perma Nomor 1 Tahun 2020 terhadap kemandirian hakim menurut Ketut Ria Wahyudani Oktavia,dkk. ditetapkannya Perma No. 1 Tahun 2020 ternyata tidak mendegradasi kemandirian hakim dalam memutus perakra korupsi mengingat ontologis dari Perma No. 1 Tahun 2020 yakni sebagai suatu pedoman yang memberikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringan penjatuhan pidana. 33 Pedoman memang seringkali dimaknai sebagai sebuah instrumen yang digunakan untuk rambu-rambu melakukan sesuatu. Akan tetapi dalam praktek justru pedoman ini lebih memaksa daripada peraturan perundang-undangan. Pedoman tersebut akan menjadi sesuatu yang tidak pas apabila sampai mengurangi kebebasan dan kemandirian hakim dalam berupaya mewujudkan keadilan. Hal tersebut mengingat keadilan dan kepastian hukum itulah yang juga ingin dituju dalam pembentukan Perma dimaksud.
Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 34 ditentukan bahwa pidana terdiri atas: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. Sementara pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 202335 hal tersebut mengalami perubahan, di mana ditentukan bahwa Pidana terdiri atas: a. pidana pokok; b. pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang. Pidana pokok terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial. Pidana tambahan terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti nrgi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat. Pidana yang bersifat khusus merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.
Ada kecenderungan umum bahwa hakim menjatuhkan sanksi pidana di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum. oleh karena itu bila ada putusan yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (ultra petita) seringkali menjadi menarik perhatian. Putusan yang bersifat ultra petita dalam Hukum Pidana terdiri ada beberapa jenis: a. Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini hakim mengacu fakta persidangan sekaligus memperhatikan hukuman maksimum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
-
b. Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum. Putusan ultra petita ini seringkali dianggap bertentangan dengan ketentuan Pasal 182
ayat (4) KUHAP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana),36 yang menentukan bahwa musyawarah hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang, sehingga seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum bukan mendasarkan pasal yang lain yang tidak didakwakan terhadap perbuatan terdakwa.
-
c. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman maksimal yang ditentukan. Dalam putusan seperti ini ada kemungkinan bahwa hakim menilai kasus konkrit yang ditanganinya tidak cukup memadai bila dikenakan sanksi yang disediakan oleh Undang-Undang, sekalipun dengan sanksi maksimum.
-
d. Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh Jaksa penuntut umum dan menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum pasal yang didakwakan. Hakim dalam menangani suatu perkara dapat melihat dengan jelas, mempertimbangkan dengan jernih bahwa suatu kasus tertentu mengenai kesalahan terdakwa dan hal yang meringankan sangat dominan, sehingga sampai pada putusan bahwa yang bersangkutan tidak layak bila dikenakan sanksi tersebut, bahkan sanksi minimum sekalipun.
-
e. Putusan yang menjatuhkan sanksi yang tidak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dapat terjadi misalnya adanya pengenaan uang pengganti yang sama sekali tidak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Selain itu juga dapat digunakan contoh misalnya pemberian sanksi berupa pencabutan hak politik, yang tidak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.
-
f. Putusan berupa denda ataupun uang pengganti yang melebihi yang dituntut Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus korupsi, putusan seperti ini seringkali terjadi.
Agak berbeda dengan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, di mana putusan ultra petita bisa menjadi alasan untuk pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali sementara dalam Hukum Acara Pidana tidak. Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 67 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 198537 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 38 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Putusan ultra petita dalam kasus korupsi bisa terjadi pada kasus yang melibatkan pejabat di tingkat pusat, akan tetapi juga dapat menyangkut kasus korupsi di daerah. Dalam penelitian ini dicoba untuk diangkat keduanya. Dalam Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, kasus suap IMB Royal Kedhaton dan Hotel Iki Wae/Aston Malioboro, dengan terdakwa seorang mantan walikota Yogyakarta, majelis
hakim memutuskan sanksi lebih berat dari tuntutan JPU dalam hal pidana pokok, yakni penjara 7 tahun sementara tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah penjara selama 6 tahun. Dalam putusan tersebut majelis hakim mempunyai sejumlah pertimbangan, di antaranya bahwa tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan putusan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik yang dipilih (elected officials) selama 5 (lima) tahun sejak selesai menjalani pidana, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat demi terwujudnya rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini mengingat perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut saat Terdakwa menduduki jabatan sebagai seorang kepala daerah, sehingga hal tersebut dirasa sangat melukai rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 39
Majelis mempunyai pertimbangan bahwa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dirasa memenuhi rasa keadilan dan merupakan konsekuensi logis dari terciderainya amanah yang telah diberikan masyarakat karena perbuatan Terdakwa. Pertimbangan tersebut digunakan untuk menjadi landasan dalam penjatuhan sanksi tambahan yang secara eksplisit menggunakan dasar rasa keadilan yang ada di masyarakat. Dalam putusan tersebut terhadap pidana pokok yang di dalamnya terdapat ultra petita tidak disebutkan mengenai rasa keadilan masyarakat dalam pertimbangan hakim.
Dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk, kasus korupsi Renovasi Stadion Mandala Krida, majelis hakim memutuskan sanksi lebih tinggi dari tuntutan JPU dalam hal pidana pokok, yakni berupa denda Rp.400 juta sementara tuntutan JPU adalah denda sebesar Rp.250 juta. Dalam putusan tersebut majelis hakim mempunyai sejumlah pertimbangan, di antaranya bahwa pengertian "secara melawan hukum"dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil dengan mengutip pendapat Darwan Prins yang menyatakan bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar /bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana.
Majelis juga mempertimbangkan bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tipikor menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.” (Salinan Putusan Halaman 942).40 Dalam putusan ini dipertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku lagi. Di sisi lain majelis hakim juga
mempertimbangkan bahwa Mahkamah Agung pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 mengeluarkan Putusan MARI No.996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan Putusan MARI N0.1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006, yang tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 41 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001. 42 Hakim mencoba untuk mengakomodir perkembangan dari diterapkannya pengertian melawan hukum secara formil sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dan juga penerapan pengertian melawan hukum secara materiil sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung.
Menurut Shinta Agustina dkk, dari keseluruhan peraturan yang pernah berlaku dan yang sekarang masih berlaku, dapat ditegaskan bahwa menurut sejarah pengaturan tindak pidana korupsi, unsur ‘melawan hukum’ selalu dimaknai dalam arti yang luas (formil dan materiil). Dalam pengertian yang luas itu, ‘melawan hukum’ dimaknai bukan saja sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan tertulis, tetapi juga perbuatan yang tercela, karena bertentangan dengan rasa keadilan, atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. 43 Ajaran melawan hukum dalam arti luas sebenarnya tidak lepas dari makna melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam hukum perdata yang dahulu menurut peraturan penguasa perang pusat dianggap sebagai bentuk perbuatan korupsi lainnya (selain tindak pidana). Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana penafsiran itu tetap ada. Sekalipun dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut ditentukan adanya asas legalitas, akan tetapi dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa asas legalitas tersebut tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
Eksistensi "melawan hukum"dalam sebuah tindak pidana merupakan hal yang penting. Hal tersebut terlihat jelas misalnya dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk tersebut mempunyai hubungan dengan putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk,44 dan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2022/PN Yyk. 45 Ketiga putusan tersebut menyangkut tindak pidana korupsi renovasi Stadion Mandala Krida di Yogyakarta. Ketiga putusan itu masing-masing dengan terdakwa yang berbeda, namun majelis hakim yang menangani perkaranya
adalah sama. Dari ketiga putusan ini terdapat kesamaan dalam soal ultra petita, yakni menyangkut sanksi denda yang melebihi tuntutan dari JPU. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis juga mempunyai persamaan di antara ketiganya.
Untuk kasus yang lain, dalam putusan Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2022/PT SMG, 46 majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana yang lebih berat dari tuntutan JPU, yakni penjara 2 tahun yang melebihi tuntutan JPU yang menuntut penjatuhan sanksi penjara 1 tahun 6 bulan. Majelis hakim dalam putusanya antara lain mempertimbangkan pemberlakuan Perma No.1 Tahun 2020. Terkait dengan rasa keadilan masyarakat, majelis antara lain mempertimbangkanya bahwa: Mengingat tujuan dari pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Pengadilan kepada Terdakwa, akan tetapi dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat dimana bagi Terdakwa agar dapat menyadari kesalahannya dan selanjutnya tidak mengulangi perbuatannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif, edukatif dan korektif, untuk tidak melakukan perbuatan serupa sehingga Majelis Hakim memberikan putusan yang dipandang lebih tepat, layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.
Hakim dalam kaitanya dengan keadilan masyarakat antara lain dengan mengutip pendapat Roeslan Saleh mempertimbangkan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela karenanya (garis bawah dari penulis), sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian(Salinan putusan hlm.624).47 Hakim dalam putusan tersebut antara lain mempertimbangkan adanya rasa keadilan masyarakat yang menjadi salah satu pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Bahkan seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela karenanya.
Dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.,48 majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 12 tahun, lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara 11 tahun. Dalam salah satu pertimbanganya majelis mengurai bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif maka diambil salah satu yang sesuai dengan kasus tersebut, yakni alternatif pertama Pasal 12 huruf b jo.Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(Salinan putusan hlm 565-566).
Dasar pemberat pidana penyalahgunaan kewenangan Pasal 52 Pada korupsi bantuan sosial menurut Adinda dapat dilakukan, sehingga mestinya hukuman dapat diperberat karena delik-delik pada Pasal 52 KUHP telah terpenuhi. Namun Hakim tidak mengakomodir Pasal tersebut sehingga hukuman ringan yang dijatuhkan dan memicu masyarakat kecewa. Hakim dalam menafsirkan dan mempertimbangkan hukuman
tidak memperhatikan unsur kerugian yang diderita masyarakat dan negara.49 Hakim malah menjadikan respon kecewa masyarakat terhadap korupsi ini sebagai alasan meringankan hukuman sehingga keadilan bagi masyarakat tidak tercapai.50
Berbeda dengan pendapat tersebut, Mahfudz Harahap dan Reski Anwar menilai bahwa terdapat permasalahan yang menghambat penerapan pidana mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan covids-19 sebagai bagian dari unsur delik “keadaan tertentu”. Keppres menyatakan covid-19 sebagai bencana non alam nasional, sementara UU Tipikor menyatakan bahwa keadaan tertentu yang menjadi salah satunya adalah bencana alam nasional. Selain itu Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu apabila tidak dijerat dan dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (2) maka tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana mati. 51
Putusan tersebut sebenarnya merupakan putusan ultra petita, akan tetapi masih belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat karena dinilai belum adil. Kasus ini merupakan kasus korupsi dengan skala nasional dan menarik perhatian public yang sangat besar. Hal seperti ini mesti mendapatkan perhatian luas di kalangan masyarakat termasuk oleh penegak hukum.
Persoalan bahwa seorang pelaku tindak pidana korupsi mendapatkan cemoohan dan sikap yang kurang baik dari masyarakat selayaknya menjadi sebuah konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Apalagi itu menyangkut kepentingan umum berupa bantuan sosial yang mestinya menjadi perhatian dari pemerintah dalam situasi yang sangat khusus seperti saat covids-19. Pelaku tindak pidana yang merupakan aparat pemerintah mesti harus memperhatikan hal seperti itu. Perspektif yang dipegang oleh hakim mestinya juga memperhatikan posisi sebaliknya yakni terampasnya hak dari mereka yang mestinya mendapatkan bantuan untuk menyambung dan menopang kehidupan mereka melalui bantuan sosial. Pembelaan terhadap kepentingan publik mestinya menjadi sebuah pertimbangan yang diberikan secara utuh. Seperti yang dikatakan Bell di atas bahwa keadilan publik menuntut adanya solidaritas. Dalam situasi pandemi solidaritas diperlukan dari semua elemen masyarakat, terlebih pemerintah yang memang diberi amanah untuk mengusahakan kesejahteraan bersama. Adalah sebuah hal yang wajar dan sepatutnya pemerintah yang dilengkapi dengan kewenangan itu menggunakanya untuk mewujudkan solidaritas dan kesejahteraan umum, bukan sebaliknya.
Putusan ultra petita dalam menangani kasus korupsi sebagian mempertimbangkan secara eksplisit mengenai rasa keadilan masyarakat. Ada yang di dalamnya memuat
secara komprehensif baik ajaran melawan hukum formil yang menekankan bahwa melawan hukum sama dengan melawan undang-undang, dan ajaran materiil yang memperluas ajaran formil yakni bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat sekalipun tidak diatur undang-undang. Kedua ajaran tersebut mempunyai konsekuensi yang berbeda. Ajaran formil mengikuti asas legalitas, bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali melanggar undang-undang yang dibuat sebelum yang bersangkutan melakukan perbuatan itu, meski kadang kurang mengakomodir rasa keadilan yang ada di masyarakat. Di sisi lain ajaran materiil lebih mengakomodir rasa keadilan masyarakat, meski bertentangan dengan asas legalitas. Pada posisi ini hakim seperti diposisikan dilematis, mengikuti ajaran formil lebih memberikan kepastian dan sesuai dengan asas legalitas sementara mengikuti ajaran materiil lebih menekankan keadilan masyarakat dengan mengesampingkan asas legalitas yang merupakan pilar hukum pidana. Oleh karena itu sebenarnya apabila semua undang-undang bisa mewakili rasa keadilan masyarakat, maka persoalan tersebut bisa terakomodir. Akan tetapi seperti diketahui bahwa kecepatan dalam menyusun undang-undang seringkali terlambat bila dibandingkan dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Dari penelitian ini juga terlihat ada putusan yang di satu sisi memberikan putusan yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi di sisi lain ada pertimbangan yang dirasa belum memenuhi harapan masyarakat, seperti pertimbangan yang meringankan terdakwa dengan alasan tertentu. Pertimbangan soal keadilan masyarakat tidak senantiasa eksplisit, melainkan dapat juga dilihat dari pertimbangan yang di dalamnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat, seperti soal besar kecilnya kerugian negara, motif dari tindakan pelaku, perlakuan pengadilan terhadap terdakwa, dan sebagainya. Yang diinginkan masyarakat tentu bukan sekedar dimuatnya rumusan keadilan masyarakat dalam pertimbangan putusan, melainkan lebih dari itu yakni terpenuhinya rasa keadilan bagi masyarakat luas setelah putusan pengadilan dijatuhkan.
Daftar Pustaka
Agustina, Shinta, Roni Saputra, Alex Argo Hernowo, and Ariehta Eleison Sembiring. Penafsiran Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: LeIP Puri Imperium Office Plaza, Ground Floor, Unit G1A, 2016.
Darmawan, Defarai Qarima, and Hery Firmansyah. “ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAMBI NOMOR 516/PID. B/2019/PN. JMB DITINJAU DARI PRINSIP ULTRA PETITA.” Jurnal Hukum Adigama 5, no. 1 (2022): 682–704.
Hambali, Azwad Rachmat, Rizki Ramadani, and Hardianto Djanggih. “Politik Hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum Terhadap Pemidanaan Pelaku Korupsi.” Wawasan Yuridika 5, no. 2 (2021): 200. http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i2.511.
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali. Edisi kedu. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
Harahap, Mar’ie Mahfudz, and Reski Anwar. “Supreme Court Regulation (Perma) Number 1 Year 2020: Solutions In The Guidelines For Determining Death Penalty For Corruption Criminal Acts In Certain Conditions.” Jurnal Cendekia Hukum 7, no. 2 (2022): 257–71. https://doi.org/ttp://doi.org/10.33760/jch.v7i2.474.
Hariyanto, Diah Ratna Sari, and Dewa Gede Pradnya Yustiawan. “Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim.” Kertha Patrika 42, no. 2 (2020): 180–91.
Ketut Ria Wahyudani Oktavia, and I Dewa Gede Dana Sugama. “Kemandirian Hakim Dalam Memutus Perkara Tipikor Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020.” Kertha Semaya 9, no. 8 (2021): 1433.
https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p15.
M. Adams, L. A. Bell, and P. Griffin. Theoretical Foundation for Social Justice Education. 2nd Editio. New York: Routledge/Taylor & Francis Group, 2007.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Revision. Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2017.
Marzuki, Peter Mahmudz. “The Essence of Legal Research Is to Resolve Legal Problems.” Yuridika 37, no. 1 (2022): 37–58. https://doi.org/DOI:
10.20473/ydk.v37i1.34597.
Muammar, Helmi, Wawan Kurniawan, Fuad Nur Fauzi, Y Farid Bambang T, Aryo, and Caesar Tanihatu. “Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Kaitanya Dengan Asas Kebebasan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.” Widya Pranata Hukum 3, no. 2 (2021): 75–97. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.412.
Muhammad Yasin, S.H., M.H. “Batasan Ultra Petita Dalam Putusan Perkara Pidana.” Hukum Online, May 2017.
Mulyadi, Lilik. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya. Bandung: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2010.
Oetari, Adinda Anisa Putri Noor, and Ade Mahmud. “Kebebasan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan Dengan Asas Keadilan Dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan.” Jurnal Unisba 1, no. 2 (2021): 96–103.
https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526.
Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2020).
Putra, Yagie Sagita. “Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana.” Jurnal UBELAJ 1, no. 1 (2017): 14–28. https://doi.org/10.33369/ubelaj.2.1.14-28.
Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Cet.8. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014.
Ritonga, Alex Al Fadlani, Ladeta Simanjuntak, and Gomgom TP Siregar. “PENERAPAN PRINSIP ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN.” JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 4, no. 1 (2022): 331–43.
Rumadan, Ismail. “Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian.” Rechtsvinding 6, no. 1 (2017): 69–87. http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.128.
Setiawan, Peter Jeremiah, Xavier Nugraha, and Luisa Srihandayani. “Konsep Penegakan Hukum Yang Sistematis Dalam Perselisihan Pra-Yudisial Di Indonesia.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 29, no. 1 (2022): 68–92.
Sudharmawatiningsih. PENGKAJIAN TENTANG PUTUSAN PEMIDANAAN LEBIH TINGGI DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUMNo Title. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, 2015.
Suheri, Ana. “Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional.” Jurnal Morality 4, no. 1 (2018): 66.
Sukadi, Imam. “Substansi Kedaulatan Tuhan Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia.” Mimbar Keadilan 13, no. 2 (2020): 152–62.
Tardjono, Heriyono. “Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia.” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 2, no. 2 (2021): 51–64.
Wantu, Fence M. “Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata.” Mimbar Hukum 25, no. 2 (2013): 206–17. https://doi.org/10.22146/jmh.16092.
Yasin, Ikhsan Fatah. “Keadilan Substantif Dalam Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitus.” Justicia Islamica 15, no. 1 (2018): 13–26.
https://doi.org/10.21154/justicia.v15i1.1252.
Yunanto. “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim.” Jurnal Hukum Progresif 7, no. 2 (2019): 192–205. https://doi.org/10.14710/hp.7.2.192-205.
Yunus, Nurul Fuadi, and Ilham Abbas. “Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Perkara Cerai Talak No. 30/Pdt. G/2016/PA. Prg.” Journal of Lex Generalis (JLG) 2, no. 2 (2021): 622–37.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (1981).
Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pub. L. No. 1 (2023).
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pub. L. No. 31 Tahun 1999 (n.d.).
Undang-Undang tentang Peraturan Hukum Pidana (1946).
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001).
Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (2009).
Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2020).
713
Discussion and feedback