PENGEMBANGAN KOMIK FABEL UNTUK MEDIA KOMUNIKASI DAN SUPLEMEN PENDIDIKAN LINGKUNGAN DALAM RANGKA KAMPANYE PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KAWASAN PENYANGGA TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS-LAMPUNG
on
PENGEMBANGAN KOMIK FABEL VNTUK MEDIA
KOMUNIKASI DAN SUPLEMEN PENDIDIKAN LINGKUNGAN
DALAM RANGKA KAMPANYE PELESTARIAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI DI KAWASAN PENYANGGA TAMAN NASIONAL WAY IGtMBAS-LAMPUNG
IdaNurliaidari1AKus Scliawan".Samsul Bjkri111GdtA-B. Wlranata'1 dan PirirukSyuIi'' "Jutusan Hmu Komunikasi FakulUs IImuSosialdan Ilmu Politlk(FlSIP)Vnivcnitns Ijinpung1 Lanipunji nJurusan Kekutanan Fakultas Pcruntan Untvcnitas I ampung, Ijtnpung ' Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian UnivcrsiUs Lampung. Lampung " Bagtan Hukum Λdat dan Misyarakat Fekultas Hukum UnivCfiitax Lanipung1 Ijmpung "JuntsanSosiologi FakultasIlmu Soniulclan Ilmu Puliliktf ISIPJ Universitas Lumpung11 nmpung ∙c-r∣Mil.ιdαnι⅛unila,ΛC.id
AbitlVCl
Thtuvcritycijhuntan-WildUfeconflict in buffer sanrnflhr Wuv Kumbat National Path (WKNP) Lampung IndoneJio Is a symptom of the Mndivrrtity deterioration undergoing in the region. The absentia of local knowledge, lack of migrants knowledge about the intangible relation between land productivity degradation and biodiversity loss, the Stagtuilion of ecological knowledge Cascmiing to their migrants off spring are the speet.il challenge both for communication development planners and educators to design commUnicMion medium or teaching material so that the cascading process works well. This research was objected to develop fable as communication medium ar teaching material for elementary-si haul Upcnullyfor the local issues compatibility. This research consisted of field work and laboratory exercises from Apr il to September 200$, The fieldwork was conducted in three villages in buffer tone OJ the District of East Lumpung i.e: Brujayekti. Braja Luhur, and Brafa Asri villages as the representation of Baliκcse. Javanese, and Sundancsc respectively. The laboratory activities were conducted at the Lab of Photography and Lab of Multimedia if the Unisvrsity of Lampung. Die essential messages contents were Cttraetcd from the previous research results (Nurhaidct Ct al. 2007a and JMVa) The development of story setting, story boarding, graphical sketching, lettering typographic and lay outing for Inefable design were conducted by brain Jtorming and discussion among us. the researchers. Whcrcasfor graphical drawing was ordered to a professional painter. The graphical .symbols were reproduced by digital camera then manipulated using computer -software of Adobe Pnotoshop Vciyfirstly Bahasa Indnncsia was applied as the language then we translated to Bulinese. Javanese and Sundanese languages Draft of u-40pogt of comic fab!c was printed on glossy white papers ofAf dimension The media pre testing conducted by following Bertrand (1978 as adopted by Nurhaida. 2001 and 20O7a) tn measure thefabeU' Cffectiveess (their Uitiacrlon. their self-involvement, their acceptability and their Comprehensionffor the elementary students. The results show ed thaι the media reliability in conveying those messages w ere 7$.4%: 7$ 7%: 79.O⅛ and 79.9⅛ for edition nf the Bahasa Indtmexiu. the Javanese, the Sundanese. and the Ralinese respectively Because the readability of the student wus, tn low COntinum Le. 61. S (Sd~ I S B/ words per minute, the media were considered as reliable for conveying the messages. It is strongly recommend thut use media for extension program and teaching truιlerιulfor the aim at promoting biodiversity in NPWK Buffcrtnne Adaintng the media for applying in ike 2} other deteriorated Indonesian national parks' buffertone is strongly recommended 03 well
Key words ■ comic fable, biodiversity campaign, Ccimmunuution media. crιvir(Himen!al education material
-
1. Prndehulunn
Kelimpihan populasi dan jenis mamalia besar «pert: harimau dan gajah merupakan indikator dari mantapnya kesetimbangan ekologi di suatu SenMiing alam. Dalnm keadaan ι!u, jaring-jaring kehidupan (peristiwa Iiuugraniciiuiigra di alam) Oiaclh berlangsung baik, Ieblnggn mamnlin besar yang menjadi pucuk piramida rantai makannn melimpah populasinya maupun jenisnya. Sehubungan dengan Hu, idealnya kawasan penyangga dan Cuatu kawasan konservasi yang sangat ketat (seperti taman nasional ataupun cagar alam) adalah berupa I Iutan Prodului Tctbatai (HPT) dan relatif jauh dari kaw asan pemukiman (zona ekologi manusia) sehingga intensitas penetrasi manusia sangat rendah Lcbih dari itu. bahwa menurut Xyhus and Tilson (2004) suara kawasan konservasi haruslah Icnnregrasi secara baik dengan kawatan* kawasan konservasi Lun melalui pengembangan dan PetneIiKiraan koridor-koridor lintasan satw a, baik itu berupa hutan-hutan produksi, hutan lindung, maupun berupa sabuk-sabuk hijau yang dikembangkan di dalam zona-zona ekologi numusin Sehingga untuk kon∙.eks Provinsi Lampung, iiunulia besar bisa hidup bebas dan punya ruang bermigrasi dan Iaman Xaiional Way Kambas (TNWK; yang berada di pantai I intut Provinsi Lampung) menuju Taman Nasiunal Bukit Bariran Scht-ui (TNBSS)di pantai Barat. Begitu pula rute sebaliknya, ataupun dengan kawasan-kawasan konservasi lain di luar Provinsi Lcmpung Bahkan dengan sistem itu mamalia besar Iiams bisu hidup bebas dalam kawasan-kawasan hutan suaku dan koridor-koridornya dan bergerak beban di seluruh P. Surnatera Dengan begitu, maka kesetimbangan ekologi (yang merupakan indikator kuat bagi Lcbersinambungan sistem kehidupan) tersebut dapat diwujudkan
Namun kajian ∣ιkn∣tcι∣ιi⅛ seperti itu belum ada dan tidak nampak digunakan dalam menggariskan kebijakan pengembangan kawasan-kawasan Lontcrvati yang Ierintcgrasi dengan pengembangan kawasan-kawasan budidaya maupun zona-zona ekologi manusia (Ogrokomplcks dan wilayah wilayah urbannya) Kesalahan itu dapat kiia saksikan sekarang, bahwa kita sudah dalam perangkap kesalahan-kesalahan berikutnya yang jalin-menjalin dengan berbagai permasalahan Cosial-Ckonotni-budaya masyarakat. Keadaan hutan-hutan dt Prrivinsi Lampung semua kini sυdah Icrfragmcnuui
dan tidak saling terhubungkan dengan kawasan hutan satu terhadap lainnya. Tiap ItuUn register sudnh rusuk, sebagian besar malah sudah berupa Inhan pertanian tanaman pangan bahkan ssngai banyak yang telah menjadi pemukiman berapa perdesaan dan kecamatan Icngknp dengan segala fasilitasnya. Meriunii Dephut (2009) dari Iuawn 1.OO-1J75 ha kawasan hutan negara di Provinsi Lampung kini tutupannya hanya tinggal 7,07% saja Sclam itu menurut Dinas Kchuuinan Provinsi Lampung (2005 dalam WataK 2008) kerusakan hutan lindung, huun produksi, hutan produksi terbatas, taman huun rayπ. TNWK1 dan I NBBS masing-masing Ielnh mencapai 80⅛. 76%, 71%, 70%. 36% TNWK1 dan 16% TNBBS- Dalam keadaan seperti iiu, koridor-koridor pergerakan satwa yang Incnghuliungkan antarkawasan hutan register sudah sinu sekali tidak ada Icgi TNWK d∙n TNBBS menurut Nyhus and Tilcon (2001) kini udik ubahnya hany a sebagai Aw ipot seperti "pulau" di tengah-tengah kepungan ekologi manusia yang sering berperilaku Hcdonik <bn miupik pada kebutuhan dan keinginan di mara sekarang saja yang tentu sangat mengancam Lclcitariannya di nusa mendatang.
Kekeliruan (mitt pnllcy) itu berawal pada lambatnya riset-riset yang Ittendacar mengenai Keragaman Iuiyatl pa<U Regtsict ♦ (yααg *cLmju∣6 telah menjadi INWK ini) belum dilakukan waktu itu. Sehingga Register 9 tersebut hanya ditetapkan sebagai hutan produksi Icrbatas(HPT) dan kawasan di bagian Iuar register itu malah hnnyn sebagai kawasan budidaya non hulnn maupun sebagai kawasan hutan produksi dapat dikonversi (HPK). Tetapi kemudian baru ditetapkan Ctatuinya <ebagαi taman nasiotul pada tahun 1989 berdasarkan SK Mcnicn Keliuianaiiaii Nomor 14∕Mcnhut∙ILT989. Kekcliruan iiu makin nyata ketika hasil penelitian Nyhuse/o/., (2000)dipublikasikan, bahwa I NWK merupakan huun hujan tropika Iwah catu-ratunya di dunia yang masih tersua dengan keragaman hayati yangtinggi Namun ItuaudahfcrIambaLkarctupida awal I960 an kawasan penyangga TNWK iiu sudah menjadi wilayah penempatan transmigrasi besar besaran melalui Diro Rckonstnikvi Nasiorul (BRN) dari Jawa Timur, Bali dun Jawa Barat. Karena itu. menurut NyhusduL (2003) di kawasan penyangga TNWK tersebut kini utamanya didiami oleh para Iriimigrun ataupun keturunannya yang berasal dan etnis Jawii1 Sunda dan Bali SciIKnura Ctnb Lampung tidak dominan Dengan demikian, yang disebut
schιgaι etnis lokal di wilayah ini !.Ckatang menjadi kabur. Karena itu absennya kcanfan lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan alnm. telah menyebabkan Kilitnya masyarakat tιntυk Kcrdtiptast maupun dalam memit⅛αsi konflik terhadap utw∏ Itar di knwτutn ini (Nirrhtiidti1 dkk, 2OO7a; 2O08a).
Para warga transmigran di kawasan penyangga ini umumnya berasal dari latar belakang ekologi budidaya tanaman pangan yang berhela din sangat asing dengan ekologi budidayu hutan. Cmuninya mereka melakukan tebas, bakar dan bertanaman -setara intensif. Petilaku seperti itu prevalen di kawasan ini, telah menyebabkan Kemcrosotnn bahan organik tanah (seperti humus dan sernsah) berlangsung cepat akilt.it diisy-.itnyn gaya Iuncuian ik Iim (u Wtheriny') dι kawnsan ini, keragaman Iiayali di dalam tanah (Iretlow ground duenity) juga merosot (lihat Hairiah dkk. 2004). reaksi-reaksi enzimatir oleh mikroba Unah (berbagai reaksi yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan hara bagi tumbuhan) juga merosot, degradasi lahan berlangsung cepat, viabilitas pertumbuhan vegetasi di permukaan Iahanjuga menurun, ynngbcrr.ru supku biomasa kembali berkurang, kesuburan Luinli dan Mlow ground Irimliifniiy kembali menyusut dan diiringi pula dengan penyusutan produktivitas Itasil pertanian. Begitu seterusnya berulang sehingga upper ground Kiodivcrtfty juga merosot Pada akhirnya Iicniiuiiir pinta menggejalanya kcmi*kiιun petani. Balui TNWK (2006) mencatat bahwa lebih dari 60⅞ dari seluruh desa yang berbatasan dengan kawasan TNWK tergolong desa miskin. Sclain itu menurut Nurhaida dkk <20O7a dan 200Sa Isclc Iah IcbA dari 50 tahun penempatan Irasmigraai di wilayah ini Scmesti telah menjadi sistem ekologis masyarakat pertanian modern, berinteraksi sinergis dengan Wilayah-Wilnynh urhnn dan pasar ekspor seperti Iiirnneang semu dengim program Iranianigrasi kala itu Nnrnun pαdιι IMliliiMiya, Inxsyantkal di wila> all ini masih identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, hidup bersifat MabsLstcn. banyak VingbcrurbMiisasi. bahkan ekspitriste sebagai TKl dan yang tetap bertahan setempat banyak yang terlibat dalam perburuan Iinr maupun illegal Iogcr
Keciuili itu, merosotnya keragaman hayati tumbuhan di kawasan penyangga ini pada akhimyn juga menekan keragamnn hayati herbivora dan akhirnya juga menekan keragamnn hnyati Inmivnm kecil. Dengan begitu, herbivora maupun Lamivor kecil yang biasa keluar-matuk ke knwαsan mtra
TNWK menjadi berkurung drastis. Akibatnya Iumivoca besar utsmsnys harimau tidak SCringknIi kekurangan mangsa, sementara di kawatkan penyangga juga telah berkembang berbagai ternak yang dibudidayakan oleh masyarakat Akthat sering mendorong harimau untuk keluni ∣L∣ri Luwaian intra TNWK menuju kuwasan penyangga, maka sering ICTjndi kunllik dengan manusia karena menyerang ternak bahkan banyak mcnimbulknn korban jiwa (Nyhus and Tilson 2004). Kcdua pakar itu, juga menemukan bukti bahwa di Hcbcrapi lagian kawasan penyangga mi yang pola Linamannya identik sistem wnnntani atau Ugroforeklry (suatu pol* tanam HHiItistrata menggunakan berbagai ketinggian tegakan tajuk: StraU pohon kayu, perdu, wmak, dan StraU bawah seperti tumpang san) Icniynia frekuensi konllik manusia u Iuirnruui tersebut sangat rendah. Fenomena tersebut menurut kedua pakar ini disebabkan oleh keragaman hayati pada pola wanntnni cukup tinggi, bahkan Icbih tinggi dibandingkan di kawasan penyangga yang dipertahankan sebagai hutan produkri terbatas (ItPTj Olch karena itu. untuk menurunkun Crekuetru Lixiflik manusia vs harimau tersebut. Leihin pakai itu sangat menyarankan untuk Incmprommikan tingkat keanekaragaman hayati di seluruh kawasan penyangga TNWK melalui penggalakan sistem budidaya Wiinalsni PrmtKisi tingkat keanekaragaman Iuyati tersebut juga diynkini Nyhuv nnd Tilum (IWH) dapat menurunkan Crekucnvi manusia vs gajah sekalipun Wun pnkar tersebut masih memerlukan dukungan bukti untuk menjelaskan bagaimana mekanisme ekologisnya berlangsung.
Sementara itu, sebelumnya Nyhus etal. (2003) telah Oiclaporkan bahwa pengetahuan para Uaiisnugran ataupun keturunannya terhadap satwa Iiar yang ada di TNWK umumnya rendah dan pengetahuan wanita Icbth rendah dari pada pria. Pcngcuhuan tcrwlw.il auhn haik dengan semakin Ungginyu tingkat pendidikan maupun makin lamanya tinggal di kawasan penyangga. Begitu jug*dengan iirtiur, umumnya yang berumur di atas 45 tahun mempunyai pengetahuan Icbih boik Dan penelitian itu pula tersingkap bahwa umumnya pengetahuan anak usia sekolah du⅛ar Icbih rendah dari para orang tuanya Artinyudari laporan Nyhusetal. (2003)yang IiCTkriItaii dengan umur tersebut ada 2 mnsalnh serius yang berkailan dengan pewarisan atau regenerasi tnliadap pengetahuan lokal masayarakiit di kawasan penyangga TNWK ιnι. Pcrtuma, regenerasi
Pcngctahunn Ioknl tidak berlangsung ilengan bαik. Kcdiui, ∣bimριln>'A pan perancang pendidikan dasar kurang memperhatikan muatan lokal, materi pelajaran yang disajikan jauh diri realitas yang dihadapi sehari-hari yang ada di alam kehidupan sekitar
Nurhaida dkk (2OO7n dan 2008a) juga IIieIjJMirkan bahwa isi buku-buku pelajaran SD yang digunakan di kawasan penyangga TNWK ini umumnya tidak berbeda dengan yang dipergunakan dengan wilayah urban atau perkotaan Memang dalam buku sains yang ditemukan di setiap SD banyak yang membahas i»uc lingkungan, tetapi untuk digunakan di wilayah penyangga TNWK ini m maupun Iluitrasinya sangat tidak relevan, tidak menyajikan tcalitas ataupun permasalahan yang sehari-hari dihadapi oleh masyarakat di kawasan penyangga ini. Karena itu peningkatan relevansi dengan menyajikan muatan IiAaI ke dalam bahan* bahan pelajaran SD mendesak untuk dilakukan. Kekowngan mi perlu dijembatani secara baik. Reahttu itu merupakan tentangan besar oleh para ahli komunikasi pembangunan dalam penyediaan SUjitcmcti pendidikan yang dibotoli dengan muatan Iokalyang relevan.
Upaya promosi Iccandarogaman hayι∣t∣ itu makin strategis bila mengambil ceruk pada usia sekolah dasar Nilai strategic itu terletak pada (i) horizon wnktti yang diperlukan untuk memulihkan kemerosotan keanekaragaman hayati di suatu wilayah relatif sangat Lima schinggi cukup waktu untuk melakukan rekayasa sosial melalui imphnι∣msi pcngctahtun Ilminh kepada segmen khaynk urin ini, (It) rcntnng usia ini merupakan g<Mcn age, stutu rentang usia yang tepat untuk menanamkan nilai-nilai diri, termasuk nilai-nilai ideIogi Imgkungan yang bersifat abstrak yang dapat memasuki kawasan bawah sadar di benak sanubari siswa sehingga dapat diharapkan tidak mudah Iererosi IaiuMirm maupun IcrlulupoMl IiiliIi-IiiI ii IicilMiik. (iii) anak sekolah dasar dl kawasan penyangga ini <!x∣mI jembatan kesenjangan informasi bagi Ofangtuanya di rumah nianikate dapat meminjam dan membawa pulang media komunikasi tersebut dan lain-lain.
Karya tubs ini bertujuan untuk mengembangkan media komik fable dalam 4 edisi (Bαl>asn Iiidiiiscvia, Jawn. Sunda dan Bali) «bagai alat bantu komunikasi maupun suplemen Jiendidikan dasar dalam rangka promosi kcaι>ckaragaιι> hayati di zona penyangga kawasan konservasi y ang ketat seperti tenun nasional, lanun hutan raya, cagar alam maupun sejenisnya.
-
2. Metode Pcnclltian
Peoclititxn im dimulai Ajirii sampoi Oktober 2008. terdiri aiaκaktivitas Jierancangan media komik fabel dι Iaboratornimdan Ujiccba mcdia(ιw√⅛pren∙r.∙in.⅛) di lapangan. Pekerjaan perancangan media [media planning)diIakukandi LnboMhiriuiii Fotografi dan Labofutoruni Multimedia, Jurucan Ilmu KofnunQiftSi. FISIP I Inivcmtes Lampung. Sedangkan pekerjaan lapang dilakukan di 3 desa di kaw asan penyangga TNWK. (yang berada dalam wilayah yurisdiksi Ubapfticn Lampung Timur) yaitu Doa Braja I .uhur, RrajaAsri, dan BrajaYckti Etnis Jawa. Etnis Sunda, dan Etnis Bali. Λdap∣rn Uhnpan penelitian ini dapat diringkaskan pada bagian berikut.
-
2.1 Pfruncangun SubMumi Iii Petan
SubMansi isi ∣>esan yang akan dituangkan dalam media komik fabel IliekMrakdaii Iusil penelitian sebelumnya (NurhnidniDck , 2<K>7a. 2008ft). Adapun yang secara esensin! sesuai dengan realitas masalah yang dialami schnri-hari oleh khalayak masyarakat kawasan penyangga ini dan sekaligus harus menjadi Ixihiiriiiiituk menanamkan ideologi Iingkungnn iteJam rangka Jironiori Leanekaragamirt hayati ilu meliputi; (i) informasi jenis-jenis flora dan fauna yang dilindungi oleh peraturan perundungan undangan, (n) pentingnya mcmantitnt Ibnoma suling kebergatungan makluk hidup dalam bentang alam dan dampaknya bagi manusia, (iii) hubungan kerusakan habitat INWK dengan serangan Mtwa Iinr yang menyebabkan konflik dengan manusia, (i v) upaya untuk abolisi terhadap budaya inferior yang masih kuat yaitu mitos-mitos Ientiing berbagai khasiat organ-organ satwa seperti otak kera untuk obat asma, empedu ular untuk berbagai penyakit; kumis macan untuk penahan dingin sewaktu berendam untuk memancing di hutan, cubh badak untuk obat kuat, dan gading gajah untuk mendatangkan kemakmuran; (v) rangkum» iri ρe**n yang intinya bahwa manusia sebagai makhluk yang sempurna harus mampu membiru dan beradaptasi terhadap Iingkungnn alam sekitarnya demi untuk Jcctorliuijutftn hidup anak-cucunya.
-
2.2 Perancangan Setting Ceriia
Substansi tsi pecan yang telah diekstrak tersebut merupakan jwkok-pokok pesan esensial yang harus diuangkan kcdalain media hiburan komik fabel. Untuk Mihuanvi isi yang pertama, bahwa ada fauna dan flora (binatang dan tumbuhan) yang
dilindungi peraturan perundang-undangan. lebih difokuskan kepada fauna sedangkan flora hanyalah menjadi penunjang cerita
Fokus tersebut diperlukan mengingat karakter dan citra dari media komik itu Xendiri awalnya merupakan media dongeng bagi anak-anak yang menggunakan Iokoh-Iokoli peran binatang. Dengan begitu, media Komunikaai menjadi lebih hidup dan lebih menarik bagi anak-anak, dapat digunakan untuk menanamkan empati dalam benak aannhnri mereka, bahwa hak untuk hidup juga merupakan hak binatang (αm⅛αl right) yang juga menjadi penentu Keberlanjuan umat manusia apabila kepunahan hewan dapat dihindari. Kecuali itu. relatif makin banyaknya fauna yang hampir punah, di mana pemulihannya akan jauh Icbih sulit daripada Kciusakan flora. Tetapi kehidupan binatang Itu sendiri secara alamiah tidak pernah terlepas dan keberadaan hutan, y.mg dicirikan oleh dominannya pepohonan dan tetumbuhan Dalam konteks itu pengenalan beberapa flora yang dilindungi juga digunakan untuk menyusun setting cerita.
Menunrt Savitri dan Garsctiani (2001) beberapa fauna yang dilindungi yang ada di TNWK antara lain Gajah Sumatera (Elcphas macimut). Badak Sumatera (Diccrorhinus sumatrensis). Harimau Sumatera (Panthcra Hgriit sumatrensis), Upir (Tapirus Indicus). beruang madu (Hrlarciox malayanus), anjing bulan (Cuon alpinus). rusa (Cervui unirolor), ayam hutan (Gallus gallus). rongkong (Buceros sp.), owa IHylobatcs moloch), lutung merah (Prcsbytis rubicunda). siamang (Hylobates syndactylus). bebek hutan (Cairints scutulata), burung pccuk ular (Anhinga Inclanogasicr) dan sebaguinya. Sedangkan beberapa flora yang dilindungi ιιntnra Uin meranti (Shomtsp. J, minyak (Diptorccarpus gracilis), merbau (Inslista sp). ρutai (Aluonia anguuiloba) dan Scbagainya. Tetap: tirlak semua obyek flora Eni digunakan untuk substansi isi pesan, karena komik fabel salnya merupakan dongeng dnri dunia binatang sehingga penonjolan flora hanya untuk OicmLxuitu Kqicntiitgan perancangan selling cerita saja.
Chyah dan Iuuimau Jijjdikxi tokoh utama dalam setting cerita, mengingat kedua mamah» besar ini merupakan satwa yang sang.it dikenal oleh khahyal. seluruh di kawasan ini dan juga karena merupakan Mtwn yang paling sering konflik dengan masyarakat bahkan sebagian besar sangut membencinya. Bahkan ada yang sengaja membakar hutan lantaran
frustasi karena penanamannya selalu diserang gajah ketika menjelang panen (Tim Unih. 3006χ Radak Sumatcra. tapir, rusa, lutung merah, kera, berbagai burung, own, beruang, siamang dan lain-lain juga dijadikan tokoh-tokoh penunjang sehingga fenomena saling Kcbergantugan Oiitannakluk Iixtup dapat digambarkan sebagai suatu fenomena kesetimbangan alamiah yang bila terganggu akan berdampak burak pada manusiajuga pada akhirnya Gangguan Kcsctimbang alamiah tersebut bisa berupa kerusakan ataupun perusakan Iiahitat seperti perladangan, perburuan liar, penebangan liar, kebakaran hutan dan sebadainya. Berbagai ganggunan tersebut yang akhirnya juga sering bermuara pa<b Konflik manusia dengan Stawa Iiar seperti yang sering Ictjadi di kawasan penyangga INWK ini.
Kecuali itu ganggu*n yang paling membawa akibat terburuk adalah adanya kebiasaan yang berakar dari budaya inferior, yaitu mitos-mitos Icnlang pemanfaatan organ organ dari satwa liar. Rancangan ccnta ini diberikan penonjolan khusus (special exaggeration) mengingat budaya-budaya inferior Ini yang sangat mempercepat kepunahan berbagai satwa yang dilindungi yang ditemukan di TNWK. Sasarannya bukan hanya untuk para anak sekolah, tetapi juga kepada para Orangtiaa mereka, yaitu ketika berinteraksi di rumah ataupun saat komik fabel dibawa atau dipinjam Kc rumah. I Iarapan itu juga makin terbuka maiukala komik fabel Ienwlxit dijadikan sebagai salah satu suplemen dalam penyuluhan oleh Iihak yag berkompeten seperu dinas kehutanan ataupun Otonta Bah: TNWK.
Gaya penceritaan digunakan alur cerita dongeng umumnya. Iaksnna keluarga manusia biasa, berkapak, beribu, beranak, berteman dan sebagainya. Satwa-satwa tersebut juga digambarkan beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan begitu dapat dibangkitkan rasa simpati dan empati terhadap Iierbagai satwa di benak sanubari pita siswa. Dcngan begitu pula dihnrapknn tumbuh sikap ufttuk melindungi satwa maupun tidak nicruMk habitatnya (sikap konservasi.) dalam diri para siswa kelak.
-
2.) PcmbuatanStoryBoard
Tcma cerita, alur, setting, dan gaya penceritaan dikembangkan mchhti hr,H∏ Uorming secara intensif dι Jtnni anggota tim peneliti. Pciigguiuin humor, allusio. Jinditnn, satir dan anekdot dimaksudkan
■.mink ITiciiingkaun daya Mrik dan juga untuk mempertahankan ciw komik fabel sebagai media hiburan Setinp keptitusan dan brain storming tersebut digunakan unluk menuangkan Iictbagai perancangan pesan ke dalam Hury board .Selanjutnya digunakan sebagai pegangan untuk mengembangkan Simbulisari berbagai bentuk pesan.
-
2.4 Runcanyan SimbuI (iamhar, Ximbul Literal dan Tata Letak
Kekuatan utama dari media grafis seperti fwonovt∣j. cergam, komik dan fabel adalah pada penggunaan gambar, ilustrasi ataupun foto sebagai pembawa peun utama (Iihnl Parlalo dkk. 1980; , Gonick dan HuHinan1 IWI; Cioick dan Mark 1992; Ckinick dan Smith, 1993, dan Nuliaida dkk. 2001; iLin 2OO7b) ObscsidaiiparapcrancangkotnuNikaii visual: satu simbu! harus dapat mewakili untuk beribu-ribu kata. Artinya berbagai media grafis tenebut sangat mengandalkan simbul gambar, atau dengan kata lain adalah: "berbicara" dengan mengandalkan gambar Dalam penelitian ini simbul gambar awainya kami sketsa dengan lukisan Ungan disertai dengan deskripsi makna yang ingin dibangkitkan ataupun yang ingin ditonjolkan (rtugyeralrd}. Dcsknpsi makna sekaligus untuk digunakan atau difungsikan sebagai TOR {term of reference) untuk dipedomani oleh pelukis profesional yang di-order untuk melukis gambar-gambir final Vangdigunnkan sebagai Simbul-Mnibul gnrfh dalam media Iiible yang sedang dirancang.
Sekalipun begitu, simbul literal juga tetap penting, apalagi bila dikaitkan media fabel ini juga dimaksudkan sebagai media belajar bukan hanya sebagai media hiburan belaka CNtirhida dkk. 2001. Retnowatidkk. 1995: Satmoko. 1995) Mengmgat simbul literal hanya memiliki mang yang minor di dalam media fabel, karena itu KecCektivaii penggunaan kata harus dicapai. Terlalu banyak menggunakan kat.» akan Iiienyehahkxn timbol kesan perwajahan yang buruk, ruwet dan akhirnya menurunkan daya tarik. Sebaliknya bila terlalu sedikit, maka dikhawatirkan banyak pesan yang esensial bisa terlewatkan. Knrenn itu rancangan simbul literal ini cukup menjadi tantangan dalam penelitian ini dan inakiii tciasa ketika melakukan pe½takιtn dalam setiap bingkai komik yang juga harus memperhitungkan ruang yang tersedia diantara Simbulriinbul gambar.
Kannu Itu diskusi antaranggota tim peneliti telah sangat Iiiciiibantu dalam memutuskan formal Iiweanjtan simbul literal dalam setiap bingkai gambar. Dengan demikian Jccora tidπk Iiingsung perumusan tata Ictak dalam setinp bingkai komik juga terselesaikan bersamaan dengan perancangan kedua macam simbul tersebut. Begitu pula dengan rancangan betuk huruf {typography), narasi centu. serta "balon-balon" simbul percakapan, secara tidak langsung terkait dnn juga terpecahkan pada fate perancangan Mmbul riinhul ini Selain itu. dalam fase ini hanya c<Iim Bnhxu Indonesia yang digunakan untuk Mtnbul-Simbul literal Setelah pada fase pencetakan draft buku fabel, maka JsenerjnnalMn kcdalnm Bnlusa Jawn. Iiahiisa Sunda, dan Bahasa Ball baru dilakukan tim peneliti sesuai dengan Ctnixnya masing-masing, untuk kemudian UikoniuItaM kepada ahli dalam ketiga Kthnw daerah IosebuL
-
2.5 Pelukisan Simbul OraJis
Agar setiap simbul gambar «tau simbul grafis menjadi menarik (Linda dkk. 1996) khususnya bagi dunia anak-anak usia sekolah dasar, maka pelukisannya di-or<⅛r-kan kepada pelukis profesional Ada 229 gambar Icmiasuk gambar untuk sampul Semuanya dilukis secara manual menggunakan cat air pada ItCrtM karton manila putih Srtixp gambar yang sudah selesai, maka didi Jiusikan di antara para anggota tim untuk menilai kecocokannya dengan pesan-pessan yang sedang dirancang BcbcrajM gambar dilakukan pelukisan ulang karena tidak sesuai dengan imajinasi para peneliti Setelah dipandang sesuai, maka semua gambar direproduksi dengan menggunakan scunner agar diperoleh citra digital, ynng memudahkan dalam pemrosesan berikutnya.
-
2.6 Eksekusi Eormat Xomik Pabel
Prmes eksekusi format komik fabel pada prinsipnya mengikuti tata IeUk yang telah diranenng sebelumnya sewaktu meracang SimbuLsimbui gambar dan StmbuLsimbuI literal Nnmun setelah semua simbul gambar uni dilukis dan direproduksi menjadi citra digital, udιι belicrapa Uta letak ynng diubah sesuai dengan Iuril diskusi tim peneliti dnn perkembangan imajinasi. Berbagal perubahan itu Iirainanya IictkaiUn dengan keperluan perhelatan bingkai gambar denu untuk mencapai Jicnonjolan-
penonjolan pcun tertentu. Akftat dari itu. perubahan Mnftul literal baik ,⅛I<xi∙Im⅛" pervakapan maupun narasi srtiing cerita juga diumumkan mengikuti ruang ninng yang tersedia di dahrn setiap bingkai gambar, Uiituknicniudahkancperasionaluasidalani /Inifking format fabel ini. maka digunakan p∣ιa>ti hinak Adnhe Phntntkop.
-
2.7 Pencelakan Draft Kumik Fabfl
Pcricetakan draft dilakukan beberapa kali rampai dicapai kesepakatan tentang Uta letak duri tipografi yang dianggap pas melalui diskusi paru anggota tim peneliti Dnlnm format draft nkhir diperoleh 40 hnlnman selain sampul Pencetnkun draft akhiι dilakukan pada kertas glussy berwarna putih mengkilap menggunakan sparasi warna penuh. Baik edisi Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa. Bahasa Sundn dan Bahasa Bali untuk menghemat hinyu mnkn hanya dicetak dalam jumlah terbatas, yaitu sekitar 50 eksemplar Kcmudinn dilakukan ιιjic<∣hιι media (media pre lctiinχ) ke sekolah-sekolah di 3 desa di kawasan penyangga TNWK seperti yang telah Jiicncanakan.
-
2.S UjtcobaMedfa
Uji coba media (mediapre testing) merupakan fase akhir din setup pekerjaan pengemlungati media komunikasi Pnrfa fase int target utama yang lurus
Jicnpni adalah untuk mencari jawaban terhadap Xrtanyaan apakah media yang telah dikembangkan ⅛mdal Miiuknh tidak dalam menyampaikan pesan-xs»n konservasi keanekoragaman hayati .Iiusu-Snya untuk anak sekolah dasar. Untuk itu Iipilih secara Scngnjn 3 desa yang nusing-masing Jianggap representasi lingkungan etnis dominan Bali. Sumin, dim Jawa yaitu Desa Braja Yckti, I>cιn Brnμ Λ⅛n dun Desa Braja Luhur Masing-masing uji ;ol» dilakukan pada Mtu SD-
-
2.9 PemilihansisxaSnmpel
Pada SDN Ol di Dcsn Hraja Yckti1 ternyata tiswanya tidak homogen dalam hal latar belakang etnis Tctapi du SD ini dijumpai 3-4 siswa yang beremis dan U-l» IV sampoi Kelas VI. Bcgitti pula di SDN Ol di I>oj Braja Asri, di mana hanya diperoleh 28 siswa yang bcralar belakang etnis Sumla untuk ketiga tingkat kias yang sama Akibnt ilari itu, maka siswa contoh atau siswa respondennya tidak Ierdiatribusi secara merata untuk ketiga tingkatan kelas tersebut Namun sebaliknya di Desa Braja Luhur dijumpai siwa berlatar belakang Etnis Jawa yang cukup, sehingga untuk masing∙n∙.aastng kelas dapat diperoleh masing-masing 12 ornng siswa tanpa secara sengaja untuk memilih gendernya Adapun rincian siswa responden ιla1ιιrn penelitian ini SCCira lengkap disajikann pada Tabel I.
1⅛bcl I Distribusi siswa sampel menurut desa (Iatarbclakang etnis), gender, dan kelas di 3 desa tempat penelitian (n~98)
|
Desa Jidisi Bahasa yang Dilraca |
Jumlah Responden |
Kclas IV |
Kelas V |
Kclas VI | ||||
|
L |
P |
L |
P |
L |
P |
L P | ||
|
BrajaYekti(SDNOI) | ||||||||
|
a) Bahau Bali |
13 |
9 |
7 |
2 |
2 |
4 |
4 |
3 |
|
b) Bahasa Indonesia |
6 |
6 |
6 |
I |
0 |
I |
0 |
4 |
|
StibTotal |
19 |
15 |
13 |
3 |
2 |
5 |
4 |
7 |
|
Draja Asn (SDNOJ) o) Bahasa SutxJa |
7 |
8 |
3 |
0 |
0 |
'1 |
4 |
7 |
|
b) Baluisa Indonesia |
7 |
6 |
.3 |
3 |
2 |
1 |
2 |
2 |
|
Sub Total |
M |
14 |
6 |
3 |
2 |
2 |
6 |
9 |
|
Braja Luhur (SDNOl) | ||||||||
|
a) Bahau Jawa |
12 |
10 |
4 |
3 |
3 |
2 |
3 |
2 |
|
b) BuhiiM Indonesia |
R |
6 |
3 |
2 |
3 |
4 |
4 |
3 |
|
Sub Total |
20 |
16 |
7 |
5 |
6 |
6 |
7 |
5 |
Kctcrangan- L: laki-laki
P ■ Perempuan
-
2.10 Pertahuan Percobaan Jan Pcnguhuran HiriaM
Scrnua siiwa di setiap sekolah yang dipilih nιcnjadι rcspoodcn atau caιt)pcl dikumpulkan dalam satu ruang kelas. Disediakan dua macam edisi komik fabel yaitu cdιsι Bahsa Indonesia dan edisi bahasa daerah. Setup siswa sampel dipersilakan untuk Oiegambil semini salah satu edisi, untuk kemudian dipersilakan nscmbacanya. Lamanya waktu yang dipergunakan untuk membaca untuk seuap siswa dicatat.
SctcIah semua siswa sampel sclcsesui membaca maka diberikan kuiscncr Kiiisencr pertama adalah untuk mengukur pemahaman Icrhadap isi pesan. Kuisener ini berisi sebanyak 25 pertanyaan berbentuk pilihan berganda dengan 2 pilihan (B)enar H rsirs (S)alah Kucsioncr ke dua untuk mengukur daya tarik (attraction), keterlibatan diri (self involvement) terhadap substansi isi komik fabel, dan tingkat penerimaan (acceptability) terhadp isi pesan. Untuk ketiga variabel ini masing-masing disidik dengan menggunakan 4 buah pernyataan dengan 3 pilihan jawaban HeskaLs Likert benkut untuk mengukur sikap yaitu: (A) BciiarlXcnuavNetuju. (B)Sctiagian BciUI.' Scbagun SesuarScbagiaii Setuju, dan (C) Tidak Hcnai I ιdak Scsuai1Tidak Setuju
-
2. H Analkh Data
Dalam setiap lembar jawaban dituliskan identitas, umur, kelas dan sekolah. Untuk pengolahan data khususnya untuk Iixnyidik variabel
Iicriinhaiimn IcomfMchenAiOfi), maka jawaban yang Iictur diskor 4 dan jawaban yang salah diskor O Artinya bila seorang siswa menjawab dengan Henar Sclunihnya berani fekomyα IOO Scdangkan imtuk pengolahan data untuk menyidik variabel daya tarik, keterlibatan diri, maupun akseptabilitas, maka jika memilih jawaban (A) diskor 3. jawaban (B) diskor 2 dan jika memilih jawaban (Cjdiskor I Knrcnaketiga variabel ini masing-masing berisi 4 soal. maka nilai harapannya masing-masing niaksimurn adalah 12. Kcniudinn ∣ika nilai nilai yang diperoleh setiap siswa drkonvcrsikcdaUniskalaOsampai 100. Artinyadi sun IiKnuiuiukan satuan persentase
Dalam penelitian Ini keefektivan media fabel sebagai pembawa pesan merupakan agregat dan keempat variabel Icscbut Skor agregat tersebut tidak lain adalah nilai rata-rata kemp.it variabel tersebut (ynιtu <Lιya tarik, LctcrIibaUn diri, pemahaman dnn akseptabilitas Ieiludap iri pesaan). Namun untuk membantu dalam memberikan apresiasi ataupun untuk melakukan evaluasi terhadap keefektivan atau kehandalan media tersebut maka perlu didampingi dengan data variabel kemampuan Iitcrast (readability) dari pembacanya, yang dalam penelitian ini adalah readability siswa-siswa yang menjadi sampel. Kemampuan membaca dalam penelitian ini dihitung dari jumlah atau total kata yang digunakan dalam setrap edisisi komik fabel dibagi dengan lamanya waktu yang diperlukan oleh setiap siswa untuk menyelesaikan membaca kimitk fabel tersebut.
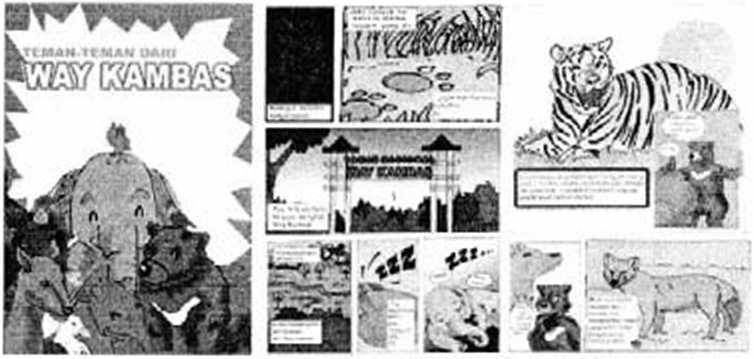
Oambar I. Sampul dan BeberapaContoli Halanun Isi Komik Fabcl Edisi Bnhasa Indnnema
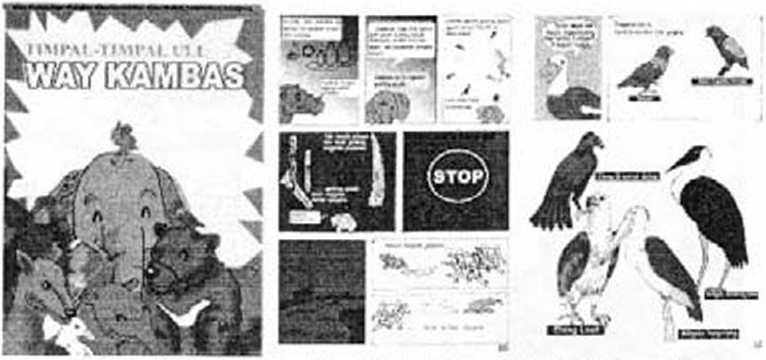
Ganilxu 2. Sainjiul dan Bcbenijxi Contnh Halainan hi Kuinik Fabel EdiM Bahasa Ball
-
3. Hasil dan Peiiibattasaii
Halanun sampul dan bebtrap∣a contoh l∣alanun isi komik fabel dalam Bahasa Indonesia. Baluisa Bah, Bahasa Sunda, dan Bahasa Jawa disajikan pada Gambar I MnipiiiGambar 4.
i I Kekandrtlan Media FaSeI sebagal Pembaua
Peran
Hasil uji Kccfekman atau kehandalan media komik fabel sebagai pembawa pesan tentang manfaat dan f>cncingnya Jconscrxasi keanekaragaman hayati
TNWK Iiipaldiuiigkapkandcniwn melihat 4 variabel penentunya yaitu daya tarik (attraction), rasa keterlibatan diri (StlfinvoIvemcni). pemahaman isi (Iompitikension) dan penerimaan (Occcptabilty) akan kandungan isi pesan dalam komik fabel tenebut
-
3. 2 Iarlabel t>aya TaHk
Payn tarik (attraction) merupakan umur atau vnnahel yang sangat ∣>cntιιιg bagi media Iubuian apapun, apalagi bagi komik fabel yang sasaran utamanya adalah anak usia sekolah. Vanabcl int harus
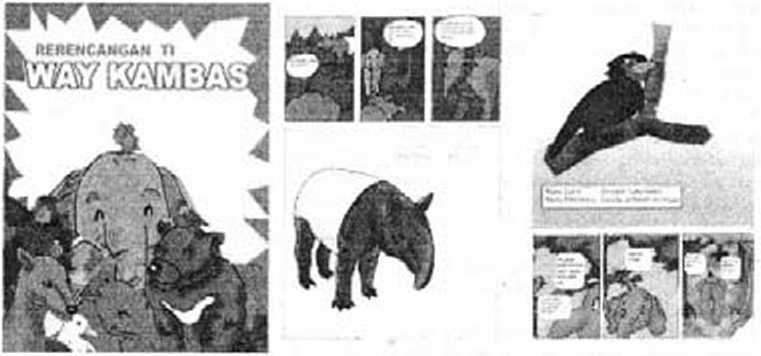
Gambar 3. Sampul dan Bcbcrapa Contoh 1 biaman Isi Komik Fabcl Edisi Bahasa Sunda
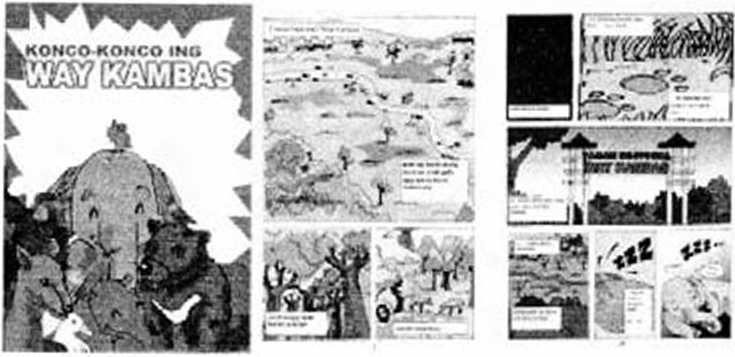
Giinihii r Saitijiul din BcbcnpaConioh Htbnun Im Koniik Fabcl EdtH BahosaJuua
tncnjadι c>v catcher yι∣φ,<⅛ιi menjadi pendorong untuk dibaca Λρabila dorongan ini muncul maka akan menjadi pendorong dalam mengaliri berbagai barriers seperti rendahnya kemampuan membaca, Sulilnya menangkap makna stuiu pesan, untuk mengata» kejemuan dan Imn- lain I >∙∣lanι teori klaiik. Ivrlupi barrier dalam komunikasi ini dikenal dengan βm∣cι (Iilut Sliaainon and Weaver. 1964; Dowse and Elilct. 2001. Cox. 2006). Melalui jxrn.-i|>uan Iici Iugai simbul yang berdaya tank tinggi akan mereduksi berbagai noires tersebut dan nkan sangat mengefektifkan suatu proses komunikasi. Para komikus, Icartvnis (seperti Gntiwk and Huffman. 1991; Gokk and Mark. 1992; Gomck and Smith. 1993; Febrianto dan Rafdinnl1 2006) ataupun Jxiaiieang komunikasi pembangunan Imrinya (IJoiibcrgcr and Gw>n. 1982; Satmoko dkk. 1995; Linda dkk. 1996. Nurhsid dkk. 2001; 2007) sering menggunakan berbagai obyek seperti binatang, penggambaran tempat atau setting yang punya familiar tinggi, Jicnggunaan tokoh idola dan lain-lain untuk tujuan IlKningkatkan daya tank Dalnni komik fable ini juga menggunakan cara-cara yang identik, seperti penggunaan setting TNWK. situasi desn, penggunaan tokoh-tokoh binatang (gajah, Iurimuu, rusa dan lain-lain), pelukisan gaya kartun, penggunaan humor dan liun-lniii
Scbagaimana dapat d∣ Iihal ∣ι*l,ι Tabel 2. bahwa variabel dayn tank dαπ media komik fabel tergolong sangat tinggi yaitu rata rata 82.1(4.4]% atau berkisar 81.7(4.5)% simpai X∖4[ I1Sf/. E<ilsi Baliau Bali kbih
menarik bagi komunitas Ball di wilayah ini dibandingkan dengan editi Bahnsa Iiiduiicsia. Artinya konteks edisi Bahasa Rali Icbib kumjratibcl bagi komunitas siswa etnιr. Bali, balikan jika dibandingkan dengan kedua edisi bahasa daerah Ioinnya Itujuga ditunjukkan oleh keragaman alau standar deviasi yang icaltif rendah. Belum terungkap angka dari Iusil penelitian ini apakah rela1ιl Urigginya daya larik dan rendahnya keragaman (Sd) edisi Bahasa Bali ini memang ada kesesuaian (CoinpariMty) dengan dongeng-dongeng (JoIHor) yang dibawa oleh pura wangtua sewaktu sebelum bertransmigrasi ataukah didapat sesudahnya dt wilayah ini. perlu penelitian lebih lanjut Untuk itu perlu penelitian lebih lanjut
J.J I uriuhcl Kcterlibatan Dlrl
Setelah daya tarik media mampu menggiring JXirn pembaca untuk menekuni medio, maka variabel atau unsur keterlibatan diri (self involvement) uπιumny<∣ mulai bekerja menguatkan daya tarik dalam mengatasi berbagai Barneri komunikasi tersebut Dalam konteksnya terhadap Stmbul-Simhul mutu dan gambar simpul media fabel Utamnnyn gajah, badak, burung, rusa, dan lain-lain (Gnmbarl sampai 4) maupun berbagai satwn lainnya yang terdapat dι >c∏∣u>∣ hahnun m telah mampu membangkitkan Letcribatan din seluip siswa yang ada dt wilayah penelitian alau SCklah sekolah di kawasan pcnyagga INWK ini. Muatan lokal yang sesuai dengan pcrikehidupan sehari-hari siswa sekolah semacam ini merupakan
van>bcl kunci bagi pembungkitun keterlibatan din tersebut. Sclwjutnya peningkatan keterlibatan <l<n ini makin menguatkan daya Urikjusadan membantu dalam mereduksi berbagal barrier pemahaman terhadap tema atau 1st pesan yang diintruduksi melalui media fabel
Seperti dapat dilihat pad* Tabel 2, variabel Vetcrlibarxn diri juga tergolong sangat tinggi dengan nilai rata-rata SI.J∣J,7∣⅝ yaitu berkisar 80,6(3,7)% umpn X2,5[2,6)⅛ Sebagnimwa variabel daya tarik media, ternyata media yang menggunakan CdUt bahasa daerah secara rata-rata juga Icbih besar daripada yang menggunakan Baliasa Indonesia. Kecuali itu. edisi Bahasa Bali merupakan edisi yang paling benar dalam variabel ini. .Mungkin berbagai peristilahan atnu nama-nama hewan (yang menjadi ⅛ma central ) ∣l>l>nι nιcd>a fabel mt Icbih Iamitiar bagi anak-anak daripada penggunaan istilah atau numa Mma dalam Bahasa Indonesia. Begitu pula dengan getting atau suasana tempat cerita juga sangat menunjang Icrtudap keterlibatan dui para siswa di wilayah ini. Aninya ada kompatibilitas yang kuat dengan peri kehidupan siswa-siwa «hari-hari di mana para orangtun mereka masih Trckuentif dalam penggunaan bahasa daerahnya masing-masing.
-
3.4 Prmuhuman hiPryan
Variabel atau unsur pemahaman (comprchcmian) mempunyai peran sentral dalam meningkatkan kesadaran aknn urgensi bagi setiap rancangan pesan. Seperli dilam salah satu segmen cerita yang digunakan dalam fabel int Misnlnya1 Aga Asialah Si Gajali kocil inenuliki orangtua. memiliki teman sesama gajah maupun tcr∣uu∣-tcπιαιι Iainnyn seperti rusa, kancil, kera, siamang d*n Iain-Iain Tetapi
βyah Si Aga tewas dibunuh paru pemburu Iiar dan hanya diambil gadingnya sa∣a Seilangkan ibunya tcrluka ketika konflik dengan manusia di kawasan penyangga. Padahal ibunya sangat terpaksa mencuri daun-daun pisang untuk Si Aga yang kelaparan setelah kebakaran hutan akibat ulah manusia juga. Maraknya perburuan liar dan kebakaran hutan juga lelah menyusutnya Iiwiiiaiia kecil (teman-teman si Agal sehingga harimau yang kekurangan mangsa, keluar menuju ke kawasan penyangga untuk mencuri ternak masyarakat. Tcrjadtlah konflik yang Kring menimbulkan korban di kedua belah Γιhak
Dcngan alur seperti itu. maka kogmsi para sisw a dapat dibangun bahwa ada saling kebergantungan di alam, bila habitat satwa rusak, maka akhirnya akan berdampak buruk juga pada manusia. Kognisi ini juga dapat memperkuat rasa keterlibatan diri khalaynk (lihat Kurtyan1 2002) terutama para siswa terhadap vcmtiii komunitas satwa dan habitatnya dι TNWK Vanahel kognisi ini menjadi semakin penting dalam membangkitkanafeksi(yaitu Ictliadap Si Λga) Ixbih lanjut diharapkan bisa menggerakkan Lonavt para siswa pada sikap maupun perilaku konservasi misalnya dengan mencari informasi Icbih lanjut, melalui bertanya, membaca, memirsa dan Icbih mencermati segala informasi via televisi secara lebih baik dan lain-lain, yang jika tertanam dalam jangka panjang akan menumbuhkan perilaku untuk mencegah kerusakan hutan, melestarikan habitat dan turut menjaga dan mengamankan kelestarian TNWK sebagai bagian dalam hidupnya
Seperti dalam Tuhel 2, sekalipun Iidtik setinggi Sanabcl daya tarik maupun variabel keterlibatan diri, variabel j>c∏ιaluιπιun Ccrmasuk dsαlιn Lalngori soling sampai cukup Iinggi yaitu rata-rata 71,7(6.4]%
label 2. Kataan Hasil Uji Coba Media untuk Mengukur Daya Tarik. Ketcrlibaran Diri. Pemahanun dan Eenernnaan terhadap Isi Pesan Komik Fabel serta Kemampuan Tingkat Literasinyn (n»08)
|
Edtsi Bahasa Daya Tnrik |
Kctcrlibatan |
Pemahaman |
Pcncnmaan |
Kehandalan |
Kemampuan Ijterasi | |
|
% |
Kata per menit | |||||
|
Rali |
83,4 (3,2] |
82.5(2,6] |
74,2 (5,5] |
72.5 (3,4) |
78.1 [Ml |
64,5∣15,l] |
|
Jawa |
82.0 [4.0] |
81.6(3.9] |
70.015.6] |
73,2(3.3) |
76.7 ∣2,7∣ |
59,8(12,S| |
|
Sunda |
82.3 (5.0) |
81.3 (4.4) |
71.7(6.8] |
74.3 [3.7] |
77.4 ∣3.4∣ |
62.4(14.2] |
|
Indonesia* |
81.7 (4.S) |
80.6 (3.7) |
71,5(6.9) |
76.9(3.5) |
77.S ∣3.l∣ |
60,4(13.51 |
|
Rata-rata |
82.1 (4.4] |
81.3(6.4] |
71.7(6.4) |
74.7(3,9] |
76,8 |3,2] |
61,5∣ 13.8∣ |
|
Kelerangan |
• Rataan dari 3 tempat pengukuran, [...] adalah Standar deviasi | |||||
W∣∣5,4)⅛Mmp*i 74,2(5.5]%. Terjadi realita» ini bisa dιfahαmι, knrcs∙ variabel pemahaman relatif Icbih kompleks dai i pula kedua var iabel Icrsrliu! Variabel Pciiuliantan memerlukan rekognisi, pengolahan informasi melalui penalaran, pengingatan kembali !recalling), re t riving to selected memory. menghubungkan, sampai mengevaluasi Cethadap obyek ataupun peristiwa stimuli yang sedang dialami. Scmua proses !crscbu< Ienlu berkaitan dengan kecerdasan, pengalaman belajar ataupun kekayaan informasi sebelumnya dan mungkin juga terkait dengan nilai-nilai yang sudah tertaman sebelumnya. Sedangkan variable daya tank maupun Icetcrtibotan diri tidak memerlukan proses yang kompleks seperu itu Mungkin cukup melihat, memperhatikiin, mendengar ataupun merasakan saja (<iβvw. 1992)
Jika diperbandingkan, ternyata perolehan variabel pemahaman tertinggi adalah pada edisi Bahasa Bali 74.2(5.5]% disusul Rnhasn Sundn 71.7(6,8)%, Rnhasa Indonesia 71.5[6,9f% dan terendah adalah Ctiisi Bahasa Jawa 7O.O[5.6)%. Nampaknya pada siswa yangg berlatar belakang komunitas Jawa lebih terbiasa menggunakan Bahasa Indonesia ketimbang Bnhasa Jnw s utamanya dalam bahasa tulis seperti yang digunakan dalam ujteoba media dalam penelitian ini Scdangknn komumtns Sundn relatif tidak ada perbedaan baik menggunakan Raluvsa Suiula Iisaupun Ralusa Indonesia Namun bagi komunitas berlatar belakang Etnis Bali, nampaknya Icbih kuat jika menggunakan bahasa daerahnya Di dalam komuitasnya. mungkin siswa-siswa yang bcralatnr belakang Icoiminitu Balt di kawasan penyangga ini masih relatif intensif dalam nienggunivakann bahasa daerahnya, soliditas yang relatif lebih tinggi dan Icbih kuat dalam memegang niali∙ni1ni budaya yang dibawa dari asal Orangtuanya sehingga bahasa therahya masih merupakan ulat komunikasi yang masih efektif.
J.S IariaM Penerimaan terhadap Isi Pesan
Tingkat penerimaan (acceptability) terhadap isi pesan bagi keempat edisi media komik fabel ini tergolong sedang sampai cukup tinggi yaitu rata-rata 74,7(3,9) atau berkisar 72,5(5.5]% sampoi 76,9∣J,5∣%. Icrcndaii pada edisi Bahasa Bali dan tinggi pada edisi Bahasa Indonesia. Sckalipun edisi Bahasa Bali merupakan edisi yang dapat mengantarkan kepada pemahaman terbaik bagi
komunitasnya terutama untuk siswa-siswa SD. namun itu tidak sejalan dengan tingkat penerimaan terhadap kandungan isi pesan Regiiu sebaliknya untuk ketiga edisi lainnya yang tingkat pemahamannya lebih rendah, ternyata akseptabilitas terhadap isi pesannya relatif lebih tinggi. Tampok dari hasil penelitian ini bahwa siswa yang menerima gagasan pe*n belum tentu benar-benar mengerti akan isinya. Sebaliknya, mereka yang lebih meinaliami isi pesan-pesan konservasi adalah meteka yang bisa punya sikap menolak
Rcalitos itu mungkin bisa dipahami bahwa tidak semua isi komik fabel sejalan dengan harapan yang diinginkan oleh para siswa, mengingat mereka juga Iudup dalam lingkungan keluarga yang tidak bebas dari nilai-nilai kultural yang dibawa dan daerah asalnya ataupun yang diadopsi dan kultur lain setelah berdiam dt kawasan penyangga TNWK itu. Kemudian ιιιlaι∙nι1a∣ tersebut diteladani atau ditiru oleh anak-ttttknya. Pesan-pesan dalam fabel yang ditujukan untuk mengkoreksi praktek-praktek bυdaya inferior misalnya, jelas banyak yang tidak sexual dengan nilai-nilai yang telah mereka yakini selama ini Kuatnya keyakinan terhadap anggapan bahwa gading gajah bisa mendatangkan kemakmuran, utak kera untuk obat asma, culab badak sebagai obat kuat, empedu ular untuk obat penyakit jantung, kumis Iiaiiiiiau dapat meningkatkan ketahanan orang terhadap dinginnya air sewaktu memancing di dalam TNWK dan lain Um itu semua tidak mudah untuk diabolis dalam waktu sekejab.
Vpayu untuk abolisi Ietscbut mungkin butuh setidaknya satu generasi, Icnitama bila upaya-upaya edukasi tidak dilakukan secara tepat ataupun strateginya kurang kompatibel dengan realitas lokal Perancangan media komik fabel ini dinilai strategis Icrhndnp upaya abolisi itu. Incngingat khalayak sasaran pertamanya adalah anak sekolah dasar. Pada sistem memori anak-anak, masih banyak ruang yang masih relatif kosong dalam susunan saraf pusatnya (HhatGcrow. 1992:1 mine .lkk, 2<)O7) Dahmkeadun Itil upaya untuk melakukan penetrasi ideologi lingkungan ke ihlani benak sanubari dipadang relatif lebih mudah dibandingkan kepada para orang tuanya (Oial Nurhaiifa, 2008b). Diharapkan para Orangtuanyu menjadi sasaran tidak langsung, yaitu ketika anak-anaknya meminjam komik fabel tersebut untuk dibawa pulang ke rumah sehingga para <mιngtua ada yang Ccrinsptrasi setelah membacanya. Lcbih lanjut
jugι d∣hnrapknn diantar* para sι∣wa ini kelak ada yang menjadi ρcjιιαrιg tcrlιndιp pelestarian lingkungan hidup di sekitarnya
Optimitrac itu dinilai Iidak bet Iebtluii mengingat tingkat pemahaman para siswa masih dapat ditingkatkan, terutama bila media komik fabel ini Henar bcnni Iliseliarliiasknn penggilirannya di seluruh kawasan penyangga TNWK oleh otoritas lokal sebagai suplemen pendidikan. Variabel daya tarik maupun variabel keterlibatan diri yang tergolong tinggi menjadi pendorong bagi peningkatan variabel pcnuhnmin untuk kemudian pada peningkatan akseptabilitas isi pesin yang tnluing dalam media fabel. AkspeUbiIiUs yang tinggi akan menjadi indikator bagi bergesernya nilai-nilai Icrulama terhadap mitos-mitos atau budaya inferior tersebut kepada budaya-budaya ilmiah yang kuat. Dengan begitu Ujsaya konservasi terhadap Ixodivcnitai di TNWK dapat diharapkan terwujud untuk waktu yang Iidnk terlalu Iamn. Irnrtiimn biln dibarengi dengan Mncrgi Ierhailap penegakan hukum secara koersif ke∣xnlι para orang tua yang terlibat dalam perburuan liar ataupun illegal logger.
-
1.6 Kehandalan .Media sebagai Pembaua PeMin
Kehandalan media sebagai pembawa pesan (media effretiwnea) merupakan ukuran rata rata dari keempat variabel media yang telah dibilus di atas. Seperti dapat dilihat dalam Tabcl 2. bahwa Leeleklnan media komik fabel whigm pembawa pesan pesan pelestarian keanekaragaman Iuyali Ictguking tinggi yaitu berkisar 76,7∣217∣⅞ umpat 78.1 (2,4 }⅞ tertinggi untuk edisi Hnhau Bali dan Ietctklah edisi Baluu Jawa dengan nihi rata mu 76.8(3,2)⅛. Dari angka-angka ini dapat dipαn<Lιng bahwa media fabel dinilai efektif sebagai medi pembawa pesan Khim ini dipandang tidak berlebihan biln dikonfrontir dengan tingkat Leinamjnian membaca rata-rata khalayak Mtunin yang tergolong rendah yaitu rata rata 61,5 (Sd -13,8] kau per menit (kpm). Angka ini sedikit lebih redih dari angka hasil pengukuran orang dewasa di kawasan Jicnyangga TNWK yaitu 72 kpm (NurhauLi dkk.. 2OO7a. din MWlk maupun Jiara pelani WiuuUni kopi di Lampung Barat yaitu 62.0 (Sd-20.9) kpm (NurhiidadkklMOTb)
Kecuali itu, perlu ditekankan di sini bahwa LeeniJXit macam «Itw bahau komik fabel tersebut relatif tidak berbeda nyata ⅛ebaχnι media pembawa
pesan tentang konservasi keanekaragaman hayati di kawasan ini. Arti penting yang dapat disimpulkan di wni bahwa bagi latar belakang ketiga etnis itu IctnyaU pemakaian Halusa Indonesia sama-sama efektifnya dibandingkan dengan penyampaian bahasa daerah masing-masing Namun di sini Jugn pcτhι IxThiIi-IiaIi wal∣ιu∣ιun Migkn-angkn UchaiiiUlaii media antarhih.ua daerah relatif rami, tetapi tidak berarti sama jika editi bahasa daerah dipettukorkan pemakaiannya
-
4. Siinjiulan dan Saran
-
4.1 Simputan
Adapun simpul yang dapat dibuat dan hasil penelitian ini adalah Mcdin hiburan komik fabel sangat handal bila digunakan untuk meny ampaikan pesan Ientangpcntingnya promosi keanekaragaman hayati kepuh khalayak yang relatif rendah Lemnnipuan IrteraMnya. Klaim itu dapat dibuktikan me!alu> penelitian mi bahwa pada tingkat Iitcrasi rau-rau 6l.5[Sd-13.8] kau per menit, media ini dapat mencapai keefektivan dalam penyampaian pnui rata nita sebesar 76,X(Sd-3.2 J%.
-
4.2 Saran
Bcrdararkan hasil penelitian int ada 2 «ran yang relevan untuk dιbeπkan: (I > kηwh pira pemegang kebijakan publik (utamanya otoritas yang Herkonipcten dalam perlindungan hutan dan pelestarian alam aUupun otoritas yang berkOnipcten dalam pendidikan dasar) disarankan untuk mereproduksi dan Inciiipcthanyak komik fabel yang dihasilkan dan penelitian ini dan kemudian dijadikan supkmen pendidikan di seluruh SD yang berada di kawasan penyangga TNWK. dan (li)diMirankanpula Itnnik melakukan penelitian seπι∣xι path 23 kawasan penyangga taman nasional Iaiiuiya di Indonesia yang mengalami nasib serupa akaibat perambahan yaitu: TN Gunung Lauscr. TN Kerinci Scblat. TN Siberui. TN Bukit Berhak. TN Hukit Diiahelad, TN Hukit Hartsan Selatan. TN Ujung Kulun, ΓN Gcdc-Paiigtaaiigu. TN Hilunun. TN Bromo-Tcnggcr-Scmeru. TN Mctu Bcsin. TN Alos Purwo, TN Bahinui. TN Rali Barat. TN Gunung Rinjani, TN Kclimutu. IN Komodo. TN Tunujven Tanh Daru1 TN Laiwangi Wanggametil TN Nuni WartalMinc. TN Lore Lindu1 <Lιn TN Rawa Aojra Wulurmilui.
Lapan Ieriiita KiimIi
Pcniliiian ini dibiayai okh Direktorat Pcnclitian dan Pengabdian kapada Muyaraknt, Direktorat JmderaJ Penilidtknn Tinggi IJepartctncn Pendidikan Nasional melalui Pιυ>ek PcningkaUn Pcnclitian Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Surat Pcpanjian
Pelakaanaan Pcnclittan Hibah Hersaing XV/1 Taliun Anggaran 2007 dengan Kontrak: Nomor O28'SP2H, l'MWM∕II∣i2OO7 Tanggal 29 Maret 2007 Untuk itu kepada sponsor patut kami sampaikan Kinyak Icrinukasib.
Daftar Pustaka
Dalai TNWK. 2006. Lapnran Kcgfatan Survat Desa Pcnyangga dι Kecamatun IVay Jepara-LaSuftan Raiu Hatai Tainan NuhhmI Way Kauibai. Dirjrn PHKΛ. Departcmcn Kchutsnnn Jakarta
Co*. R. 2006. Ensirimrrital Communiciirloftund the Public Sphere. SagcPub. London. NcwDelhi.
Dcpbut. 2009. Data Srraiegif Kchntanan Bndan PIarnnJogi KcliuUnan. Departemen Kehutanan Bogor
Dowse. R. and M.S. Ehler. 2001. The evaluation of pTaπnauecιιιical pictogram in u Iow-IitcratcofSouth African population. Patient Education and Castifelingi Wl-M
Fcbrinnto. F. dm Rafdinnl 2006 Peningktan Lonranikisi iιιfuιmasi akuntansi menggunakan gambπr kartun Jurnal Akuntanκi dan Kcirangan Indnnciia 3( 1): 128-141.
GerowJR 1992. Psychology, An Introduction. 3u. Ed. IiarpcrCoIIin Publishers Inc. NcwYork
GoniekL-WidA HutTnun. 1991. The Cartoon GuidetoPhyfii f. Hamper ColIiiW Publishers. Inc New York
Gomck L and M Matk 1992 The Carbum Guide to Gcneiief. Hamper Collins Publishers, Inc. New York.
GonickXandWSmith 1993. The Cartoon Giddc to Satiylici HamperCoIlins PubMAeni. Inc. NewYort
Hainan.k u.t>uρrayogo. wtdιanιo.tsernan.t Minara λ. .Maniusiunlng.R.H.w⅛sk-Λ,. ri«>v|.v.d«nS. Rahayu. 2004. Alih gunn Iahan hutan menjadiIxhan Jgroforeitri berbasis kopi, ketebalan seresah, populasi cacing Unah dan Inakrnporositac Unai Agrivitu 26 (I): 68-80.
Kuriyan1 R. 2002. Liking local perception Qfclephanla mid conservation: Samburu Pastorulixts in North Kenya. Society andNanrral resource 15: V4O-¼57.
Linda1A., F. Rohadi1A. Jahi. dan H. Nasution. 1996. Pcngaruh Mode Pakaian Tokoh dm Ketebalm Huruf pada Daya Tarik Buku Ke>mik dan Peningkatan FcngcUiIiuan Ibu Ibu Ientang Gizi Anak BaliU di Dcs Pakubcurcum KabupatcnMajaIengka. ForuinPMcaiarjana 19(1): 13-20.
Lionberger1 H.F. arid PH. Gwin. 1982 Crunmuriuurioii Strategist A GuideforogricuIturuIChangeAgents. The IntersUtc & Publishers lιιc. Daiivillc Illinois.
Linkie. M., Y. Dinatc1 A. Nofrianto. and L William 2007 Putlenis and perceptions of wildlife crop raiding and around Kerinci Scblat National Park. Sumntrra AnimiitCimsenurton 10:127.13$.
Nurhaidxl .Λ Jahi. Ig Kι⅛mot>o.∣ia∣∣ M S PxJmanegara JOOl Pcngaruh PesanyaiigMciiycturigkandan Pesan yang Mcnakutkan dalam Buku CenU Btrgimbor terhndsp Pcningkatan Pciigctaliuan Petani tentang Pertanian Kocisenasi JurnaILingIntngaif dan Pcmhiingunun 21.. 282-296.
Nurhalda I. K Sctinwnn1 GAH Wirnnala. ιian P. Sydi1 2007a. Menanamkan ideologi Itngkungiin pada masynrakiit di kawanan peny angga Iamaii Nasional Way Kimbasdcngnn menggunaknn media Iubuian komik fabel dan buku CCtgamdaIain rangka pelestarian Kcanckaraganu hayati. LiijNirun Penelitian Hthah Rersatng Perguruan Tinggi. (Tidak Dipublikiii). Lcmbagn Pcnclitinn Univcntitas Lampung. Laznpung.
NurhjiAi l.. S.P. Hiriyulo, S. Bakri, A. Junaιdι, dan P. Syah- 2OO7b. MeraiKang Media Hibuian Buku Cergam Mcnjadi AUt Baniu Komunikaai. Meiiirtor. JurnalKomunlkast8(t);5l-4k
Nurhaida l.. A. Sctiawan. GAB. Wiranata. dan P. Syah 200Ka Meny-Ingkitp pertautan akar Iirasalali konflik Htnnuria ISsatwα liar «cbagai Iandatan perancangan strategi kampanye Pelestarian Kcanckargaman Havati dι Knwasan Pcnynnggn Taman Nastttnal Way Knmbat I nmpung Kulctin Pcnrliitan Scrt Sosiul. HuJuya Jan HumunKint 7 (Khticus): 142-160.
Nurhardn I. S P Hanyanio. S. Bakri. A Junaidi, dan P. Syah MiSb f paya menanamkan ideologi Lngkungan pada masyarakat di wilayah resapan melalui diseminasi kultur teknis wanatani kopi menggunakan media hiburan buku cergam Jurnal Waityarakai. Kehuciayaan Jan PcJitik 2∖(∖f2WS
Nyhus. PJ.. R. Ty lson. and Su∣∣∣∣aι>to. 2000. Crup raiding elephanta and Ctmsavalion implication at Way Kambas National Park. Sumatera. Indonesia Orys 34(∙l).262-27∙1.
Nyhus, PJ., Sununnto, and R Tilson 2003. Wildlife Knowledge Among Migrant in Why Knmbns Southern Sumatera Indonctuat Iπιplιc→ι∣ιιιn for Conservation Environmental Conservation 30:192-199
Nyhus1 P. and R. Tilson. 2004. Λgrofoιcst∣y . elephanta, and tigers: Iwlanching conservation theory, and practice in human-dominated landscape of Shouth Asia. Agriculture. Ecwyttcm anJ Environment I GJiIf 7-97.
ParLito. R-M.B. Parlatu, and R J Cnin 1980 FruannvvlaanjCamicKcuitv TheVvr nf Pnpulur(iruphκ in MeJut Development. OIIiceof the Ediiciition and Human Resource, Development Suppotl Beieau Agency foι International Development, Washington DC. USA.
Retnnwaiil D IWS Pengartth bingkai dan gambar kontras komik pada peningkatan pengetahuan anggota kelompok wanita uni tentang agrobisnis bat>y corn dι Kecamntan Hnngun I ipn Kantul Thrstv Magivter. Tidak DipiibIikaMkan Program Studi Komunikasi Pcπιl>aι⅛∙,∣ιt∣.∣n Pcitinian dan Peitesaan, PPS IPB. Bomt.
Sutmoko. S. 1995. Pcngaruhtokohccntadangambarkontriskontikpadapcningkatanpcngctahuanpctcniak tentang Walnkun Ketenink domba di Dcm Kuiur. Kecamntan Majn knhupaien Majalcngkn Ihcsiv Magister. TnUk Ihpubliknsiknn Program Studi Konuinikaii Pembangunan PeTtaniiui ι!arι Pcdcvaan. PPS IPB Bogor
Slunnon1C. and W. Weaver. 1964. TkcMrtkemrtKalThcoryofcommuiucrtion. Thcuivenityoflllinois Press. Urbana
Saviiri1R. danGnnetiali. 2001. Pcndekntiin Model Pengelolaan EkociMcin EvtiMniiiintuk Menipertaluinkaii Keanekaragaman Hαyαtι Ikan di Taman Nasioiul Way Knnihav Rullctin Pcnrlitiun Kchutunun 627: 43-57.
Svotwa1 E.1 J. Ngwcnya10.T. Manyanhairc1 and J. Jiyane. 2007. Resident perception of human wildlife conll>ct tn Kartba Urban. JournalOfSuttaninalJe Development In Africa 9(2): 178-191
Tim UNILA. 2006. Pola Pcngciidaliari KclMkarari Hutan PaitihipitifMcljlui Pcngentbangjn Dcm BrajaYckti Di Kaw jsan Penyangga Tantan Nasional Wjy Kamba* (TNWK). Laporan PcneliMn TinJakan Kcrjaiama Antari’ LPUNILA1 BalaiTbIWKdjnJlCA (Tidak Dipubhkankan)
Watala. 2008. Studi kolaborasi mendukung hutan kemasyarakatan vcv.ua Ictuli adil dan demokratis di Lampung. Luporctn PembcrJyaun Masyvtrakul WataIa Rjridar Lampung
US
Discussion and feedback