Phythoremediasi Chromium Total (Cr-T) menggunakan kayu apu (Pistia stratiotes L.) pada limbah cair batik
on
JURNAL BIOLOGI UDAYANA 24(1): 47-54
P ISSN: 1410-5292 E ISSN: 2599-2856
Phythoremediasi Chromium Total (Cr-T) menggunakan kayu apu (Pistia stratiotes L.) pada limbah cair batik
Study on batik liquid waste: Phythoremediation Chromium Total (Cr-T) using Pistia stratiotes L.
Alif Resti Billah, Anita Dewi Moelyaningrum, Prehatin Trirahayu Ningrum
Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Jember, Jl. Kalimantan 1 no.93 Jember - Jawa Timur – 68121
*Email: anitamoelyani@gmail.com atau anitadm@unej.ac.id
Diterima 7 Januari 2020 Disetujui 30 Mei 2020
INTISARI
Industri batik dalam proses kegiatannya menghasilkan limbah cair yang mengandung logam berat chromium total. Kandungan logam chromium selain dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan juga berdampak keracunan akut dan kronis terhadap manusia. Pistia stratiotes L. termasuk tanaman fitoremediator yang dapat mengikat logam berat pada jaringan akar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kadar logam chromium dalam limbah cair batik. Pada penelitian ini menggunakan true experiment dengan desain penelitan post-only control group design dan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap dengan enam kali pengulangan. Sampel terdiri dari kelompok kontrol (K) 0 gr/6L dan kelompok perlakuan yaitu 300 gr/6L (P1), 350 gr/6L (P2) dan 400 gr/6L (P3). Limbah batik diencerkan menggunakan aquades dengan perbandingan 1:5, lalu dikontakkan dengan tanaman kayu apu selama 10 hari. Pada waktu pengontakan juga diukur pH dan suhu. Data dianalisis menggunakan normalitas data, homogenitas data serta uji statistik one way anova. Antara kelompok K dengan P1, P2, P3 menunjukkan perbedaan yang signifikan (P1=0.007; P2= 0.000 dan P3= 0.000).
Kata kunci: chromium total (Cr-T), fitoremediasi, kayu apu, limbah cair batik
ABSTRACT
The batik industry produce chromium (Cr) waste. The chromium can cause acute dan chronic poisoning in humans and environmental pollution. Pistia stratiotes L is a phytoremediator plant that can bind heavy metals to the root tissue. Analyze the differences of chromium levels wih Pistia stratiotes L as phytoremediation is the purpose of this study. This research is a true experiment with only post control group design and uses a completely randomized design method with six repetitions. The sample were control group 0 gr/6L (K) and a treatment group of 300 gr/6L (P1), 350 gr/6L (P2) and 400 gr/6L (P3). Batik liquid waste was diluted using aquades in 1:5 ratio, then contacted with Pistia stratiotes L. for 10 days. The pH and temperature were measured. Data were analyzed using data normality, data homogenity and continued with one way Anova statistical test. The results between K with P1, P2, P3 show there is significant differences (P1=0.007; P2= 0.000 dan P3= 0.000).
Keywords: chromium total (Cr-T), phytoremediation, Pistia stratiotes L, batik liquid waste
PENDAHULUAN
Industri batik di Indonesia berkembang pesat mendorong meningkatnya perekonomian negara. Namun demikian, industri ini juga memiliki potensi untuk mencemari lingkungan karena limbah cairnya. Pada umumnya limbah ini mengandung logam berat Chromium (Cr). Limbah ini harus diolah dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Jika langsung dibuang ke lingkungan akan menurunkan kualitas lingkungan dan merusak habitat yang hidup sekitar aliran sungai (Andriani & Hartini, 2017).
Proses pembuatan kain batik yang dilakukan industri batik menggunakan bahan-bahan kimia dan air (Sari et al., 2014). Bahan kimia mengandung padatan tersuspensi, zat organik dan anorganik yang mengandung logam berat. Penggunaan kimia biasanya digunakan pada saat proses pewarnaan dan pencelupan kain batik yang mana pada proses tersebut menghasilkan limbah cair. Chromium ditemukan dalam limbah batik (Pridyanti et al., 2018), (Zarkasi et al., 2018).
Logam chromium (Cr) dapat menyebabkan keracunan akut yaitu muntah, diare berdarah, gangguan saluran pencernaan, nekrosis hati, nekrosis ginjal dan keracunan. Sedangkan keracunan kronis juga dapat terjadi yaitu iritasi kulit, gangguan pada hati, syaraf bahkan kanker paru-paru (Nurkhasanah, 2015). Logam chromium juga berdampak pada penurunan kualitas air dan mengganggu organisme akuatik yang dapat berdampak kematian organisme (Setiyono & Gustaman, 2017). Pencemaran logam chromium perlu dilakukan penanggulangan untuk mengurangi dampak berbahaya bagi lingkungan yaitu dengan metode fitoremediasi, karena biaya yang lebih rendah, tidak memerlukan peralatan khusus dan mudah diterapkan karena sumber daya tumbuhan yang melimpah.
Pistia stratiotes L. memiliki kemampuan untuk mengolah limbah,abaik itu berupa logam berat,azat organik maupun anorganik sehingga tanaman ini digolongkan salah satu tumbuhan fitoremediator. Kayu apu berlimpah di alam, mudah ditemukan mengapung di perairan atau
kolam serta tanaman gulma air terutama di tanaman padi. Pistia stratiotes L. juga memiliki kelebihan yaitu berkecambah yang tinggi,apertumbuhan cepat,atingkat absorbsi atau penyerapan unsur hara dan air yang besarrdan daya adaptasi yanggtinggi terhadappiklim (Fachrurozi et al., 2010). Pistia stratiotes L. atau kayu apu terbukti dapat menurunkan logam berat merkuri (Hg) dalam air (Khasanah et al., 2018). Penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya (Raissa & Tangahu, 2017) penambahan kayu apu dapat menurunkan konsentrasi limbahhcair padaalimbah laundry yaitu BOD sebesar 98%, COD sebesar 96% dan fosfat 99%. Menurut (Perwitasari et al., 2018) tanaman kayu apu mampu menurunkan kandungan Pb lebih tinggi dibandingkan tanaman Echinodorus radicans sebesar 92.53% dan 89.59%. Berdasarkanuuraian tersebutt, dalam penelitian ini kayu apu digunakan sebagai tanaman fitoremediasi dalam menyerap logam Cr. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisis perbedaan kadar logam chromium dalam limbah cair batik yang dikontakkan dan tidak dikontakkan dengan tanaman kayu apu dengan variasi berat 300 gr/6L, 350 gr/6L dan 400 gr/6L dalam waktu pengontakan 10 hari
MATERI DAN METODE
Tempat dan waktu penelitian
Penelitian terdiri dari dua tempat yaitu tempat pengontakan limbah cair dengan tanaman kayu apu dilakukan di Laboratorium Fakultas Kesehatan MasyarakattUniversitasJJember dan tempat pemeriksaan kadar chromium dilakukan di LaboratoriummKesehatan Daerah Kabupaten Jember. Waktu penelitian dilaksanakan pada September 2019-Desember 2019.
Bahan dan alat
Alat dan bahan yang digunakan adalah jirigen ukuran 25 liter, bak penelitian dengan ukuran volume > 6 liter sebanyak 24 buah, pengaduk, timbangan analitik, pH meter, thermometer, botol plastik sebanyak 24 buah, limbah cair batik, akuades, dan tanaman kayu apu.
Metode
Penelitianiini adalah TrueeExperimental denganbbentuk Post-test Only Control Group Design dan menggunakan analisis Rancangan Acak Lengkap. Penelitian ini terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu satu kelompok kontrol atau tanpa kayu apu (0 gr/6L) dan tiga kelompok perlakuan yaitu P1 (300 gr/6L), P2 (350 gr/6L), dan P3 (400 gr/6L). Pengulangan dilakukan sebanyak 6 kali pada setiap kelompok sehingga total 24 sampel. Limbah cair batik sebelum dilakukan pengontakan diencerkannterlebih dahulu menggunakan aquadest dengannperbandingan 1:5. Kadar awal Cr-T dalam penelitian ini sama dengan kelompok K yaitu 0,509 dikarenakan metode dalam penelitian menggunakan post-test control design. Tanaman kayu apu yang digunakan yaitu dengan kriteria jumlah daun 7-10 helai, diameter 5-8 cm dan panjang akar 5-7 cm. Kayu apu dalam penelitian ini sebelum dikontakkan dengan limbah, maka dilakukan
aklimatisasi terlebih dahulu selama tujuh hari. Lama pengontakan selama 10 hari dan dilakukan juga pengukuran pH dan suhu dimana diukur 3 waktu dalam satu hari selama 10 hari yaitu pukul 07.00 WIB, 12.00 WIB dann17.00 WIB.
Analisis data
Uji statistik yang digunakan yaitu uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov. Jika hasil berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji one way anova jika berdistribusi tidak normal maka diuji dengan Kruskal Wallis.
HASIL
Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa hasil rerata pH pada kelompok K sebesar 9.9; P1 sebesar 9; P2 sebesar 8.9 dan P3 sebesar 8.6. Rerata suhu limbah cair batik selama 10 hari waktu pengontakan dengan tanaman kayu apu mengalami peningkatan yaitu 26oC menjadi 27oC.
Tabel 1. Pengukuran pH dan suhu kelompok kontrol (K) dan kelompok perlakuan (P1, P2 dan P3)
|
Kelompok |
pH |
Rerata |
Suhu (oC) |
Rerata | ||
|
1 |
10.1 |
1 |
26 | |||
|
2 |
10.6 |
2 |
26 | |||
|
3 |
10.2 |
3 |
26 | |||
|
4 |
9.7 |
4 |
26 | |||
|
K (Kontrol) |
5 6 |
9.6 9.8 |
X = 9.9 |
5 6 |
26 27 |
X = 26oC |
|
7 |
9.7 |
7 |
27 | |||
|
8 |
9.9 |
8 |
26 | |||
|
9 |
9.9 |
9 |
26 | |||
|
10 |
9.9 |
10 |
26 | |||
|
1 |
10.1 |
1 |
26 | |||
|
2 |
9.9 |
2 |
27 | |||
|
3 |
9.3 |
3 |
27 | |||
|
4 |
9.3 |
4 |
26 | |||
|
P11 |
5 |
8.8 |
5 |
26 |
_ | |
|
6 |
8.6 |
X = 9 |
6 |
26 |
X = 26oC | |
|
7 |
8.6 |
7 |
27 | |||
|
8 |
8.5 |
8 |
26 | |||
|
9 |
8.4 |
9 |
26 | |||
|
10 |
8.5 |
10 |
27 | |||
|
1 |
10.1 |
1 |
26 | |||
|
2 |
9.8 |
2 |
27 | |||
|
3 |
9.2 |
3 |
27 | |||
|
4 |
9.1 |
4 |
27 | |||
|
P22 |
5 |
8.8 |
5 |
27 |
_ | |
|
6 |
8.7 |
X = 8.9 |
6 |
27 |
X = 27oC | |
|
7 |
8.5 |
7 |
27 | |||
|
8 |
8.3 |
8 |
27 | |||
|
9 |
8.2 |
9 |
27 | |||
|
10 |
8.1 |
10 |
27 | |||
Tabel 1 (lanj). Pengukuran pH dan suhu kelompok kontrol (K) dan kelompok perlakuan (P1, P2 dan P3)
|
Kelompok |
pH |
Rerata |
Suhu (oC) |
Rerata | ||
|
1 |
10.1 |
1 |
26 | |||
|
2 |
9.9 |
2 |
27 | |||
|
3 |
9.2 |
3 |
27 | |||
|
4 |
8.3 |
4 |
27 | |||
|
5 |
8.1 |
5 |
26 |
_ | ||
|
P33 |
6 |
8.1 |
X = 8.6 |
6 |
27 |
X = 27oC |
|
7 |
8.1 |
7 |
27 | |||
|
8 |
8.1 |
8 |
27 | |||
|
9 |
8.1 |
9 |
27 | |||
|
10 |
8.0 |
10 |
27 | |||
Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa setiap replikasi memiliki hasil yang berbeda-beda. Pada kelompok K hasil kadar Cr tertinggi terdapat pada replikasi ketiga yaitu 0.61 mg/L dan terendah pada replikasi keempat yaitu 0.403 mg/L. Pada kelompok P1 kadar Cr tertinggi terdapat pada replikasi kedua yaitu 0.4 mg/L dan terendah pada
replikasi pertama yaitu 0.34 mg/L. Pada kelompok P2 kadar Cr-T tertinggi terdapat pada replikasi pertama yaitu 0.319 mg/L dan terendah pada replikasi kedua yaitu 0.234 mg/L. Pada kelompok P3 kadar Cr-T tertinggi terdapat pada replikasi pertama yaitu 0.212 mg/L dan terendah pada replikasi keempat yaitu 0.137 mg/L.
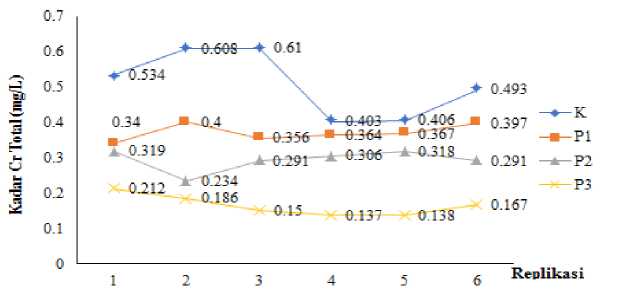
Gambar 1. Kadar Cr-total pada kelompok kontrol (K) dan kelompok perlakuan (P1, P2, P3)
Berdasarkan gambar 2 diketahui bahwa rerata kadar Cr terdapat perbedaan pada masing-masing kelompok. Rerata pada kelompok tanpa kayu apu (K) sebesar 0.509 mg/L. Rerataapenurunankkadar
Cr terjadi pada kelompok. P1 yaitu sebesar 0.371 mg/L, kelompok P2. yaitu sebesar 0.293 mg/L dan kelompokkP3 yaitu sebesarr0.165 mg/L.
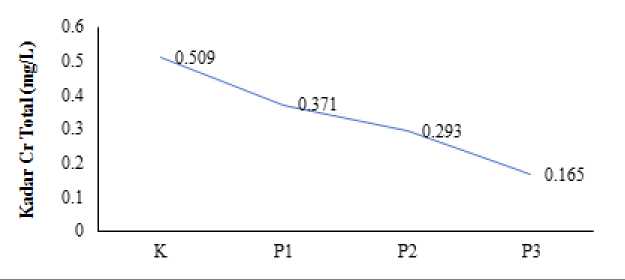
Gambar 2. Rerata kadar Cr pada kelompok kontrol (K) dan kelompok perlakuan (P1, P2, P3)
Berdasarkan tabel 2. menunjukkan persentase penurunan terendah kadar Cr dibandingkan kelompok K yaitu pada kelompok P1 sebesar 27.1%. Sedangkan persentase penurunan tertinggi yaitu pada kelompok P3 sebesar 67.6%.
Tabel 2. Persentase Penurunan Kadar Cr
|
No |
Kelompok |
Penurunan (%) |
|
1 |
K |
- |
|
2 |
P1 |
27.1 |
|
No |
Kelompok |
Penurunan (%) |
|
3 |
P2 |
42.4 |
|
4 |
P3 |
67.6 |
Analisis data menggunakan uji statistik One WayyAnova. Berdasarkan tabel 3 diketahuibbahwa terdapatpperbedaan nilai signifikansi antara setiap kelompok. Hasil uji post hoc menghasilkan nilai P ≤ 0.05 yang mempunyai arti secara statistik bahwa terdapat perbedaan penurunan Cr pada setiap kelompok perlakuan.
|
Tabel 3. Hasil Uji Post Hoc | ||||
|
Kelompok |
K |
X1 |
X2 |
X3 |
|
K1 |
- |
0.007* |
0.000* |
0.000* |
|
P11 |
- |
- |
0.042* |
0.000* |
|
P21 |
- |
- |
- |
0.000* |
|
P31 |
- |
- |
- |
- |
Keterangan: (*) menunjukkan signifikansi pada kelompok K, P1, P2 dan P3
PEMBAHASAN
Pengukuran pH dan suhu bertujuan untuk mengetahui kondisi keasaman dan suhu suatu lingkungan. Pengukuran pH menggunakan alat pH meter dan didapatkan pH limbah cair batik di awal sama yaitu 10.1. Selanjutnya setelah dilakukan perlakuan dengan adanya penambahan kayu apu berkontribusi terjadinya penurunan pH. Penurunan pH disebabkan adanya proses biodegradasi bahan organik. Bagian tanaman yang mati dari tanaman kayu apu akan diuraikan oleh mikroorganisme di dalam air, sehingga dalam proses penguraian bahan organik akan mempengaruhi nilai suatu pH (Sari et al., 2017). Aktivitas mikroorganisme pendegradasi
memungkinkan terjadinya penurunan
pHkkarenassenyawa organic telah diuraikan menjadi asam organik (Purnamawati et al., 2015).
Penyebab penurunan pH juga dapat disebabkan karena terjadinya pembusukan bagian tanaman air oleh kerja mikroba penghasil asam. Nilai pH semakin menurun dapat juga terjadi karenaaion OH- yang menyebabkannpH basa bberikatan dengan ion chromium (Cr3+ dan Cr6+) sehingga ion OH- dalammair limbah berkurang sehingga pH turun (Hapsari et al., 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016, pada penelitian ini pH telah sesuai dengan baku mutu yang seharusnya yaitu rerata 8.6 dilihat dari peraturan bahwa pH perlakuan berada dalam kisaran 6-9. Pengukuran suhu menggunakan alat thermometer. Pada penelitian ini didapatkan suhu di awal sama yaitu 26oC. Namun, setelah perlakuan terjadinya kenaikan yaitu yang semula 26oC menjadi 27oC. Menurut (Raissa, 2017) disebabkan setiap wadah diletakkan pada lokasi yang sama. Rerata suhu pada penelitian ini 26oC-27oC telah memenuhi batas suhu optimum yang diperbolehkan yaitu suhu optimum fitoremediasi berkisar antara 25oC-30oC serta berada pada batas suhu optimum tanaman kayu apu tumbuh yaitu 22oC-30oC (Jamil et al., 2016). Suhu berkaitan dengan proses metabolisme dan fotosintesis, sehingga dengan adanya peningkatan suhu secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan. Menurut Ikawati et al., (2013) semakin tinggi suhu lingkungan tanaman maka semakin tinggi pula tingkat penyerapan oleh tanaman. Namun dengan peningkatan suhu juga dapat menyebabkan toksisitas meningkat sehingga pertumbuhan tanaman terhambat, yang mana pada tanaman kayu apu ditandai dengan memendeknya akar (Henrasarie, 2019).
Berdasarkan hasil laboratorium kadar Cr pada setiap kelompok mengalami penurunan, penurunan tertinggi yaitu 67.6%. Perbedaan penurunan kadar Cr menunjukkan adanya hubungan ataupun pengaruh antara variasi berat kayu apu dengan penurunan kadar Cr pada limbah cair batik. Berdasarkan penelitian (Jamil et al., 2016) dan (Rahayuningtyas et al., 2018) menunjukkan hasil yang sama yaitu semakin banyak pemberian variasi berat tanaman kayu apu berbanding lurus dengan semakin besar
penyerapan logam berat. Menurut penelitian Herlambang & Hendriyanto (2015) menunjukkan variasi berat tanaman atau jumlah tanaman berdampak pada penurunan kadar phosfat. Semakin berat atau bertambah jumlah tanaman akan semakin besar penurunan kadar phosfat. Namun semakin banyaknya jumlah tanaman akan timbul persaingan tanaman yaitu pertumbuhan tanaman dapat terganggu dan semakin lama akan menjadi layu bahkan mati.
Kayu apu termasuk tanaman fitoremediator yaitu tanaman yang dapat digunakan untuk menyerap kandungan logam berat. Kayu apu memiliki potensial yang sangat tinggi untuk kekeruhan dan memperbaiki kualitas air. Tanaman kayu apu dapat memfilter,,mengabsorpsi partikelddan ion-ion logam yang terdapat dalam air limbah melalui akar yang dimilikinya (Wirawan et al., 2014). Tanaman kayu apu memiliki akar serabutyyang berfungsi sebagaittempat menempelnya koloid yang melayang di aair dan juga banyak menghasilkan oksigen hasil proses fotosintesis yang dimanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan zat organik air limbah. Kemudian bahan organik dirombak olehmmikroorganismemmenjadi senyawa lebih sederhana dan digunakan tanaman sebagai nutrient. Menurut Irhamni et al., (2018) terdapat tiga mekanisme penyerapan dalam tumbuhan yaitu penyerapan oleh akar,ttranslokasi logam dari akar kebbagian tumbuhan lainddan lokalisasi logam padaajaringan.
Menurut Handayanto et al., (2017) fitoremediasi memiliki beberapa teknik untuk menghilangkan polutan dari tanah yaitu fitoekstraksi, fitofiltrasi, (rhizofiltrasi), fitodegradasi (fitotransformasi) fitostabilisasi dan fitovolatilizasi. Fitoekstraksi yaitu penyerapan suatu senyawa pencemar dari tanah atau air oleh akar tanaman dan ditranslokasi serta diakumulasikan di dalam bagian atas tanah, yaitu tajuk tanaman seperti akar, batang dan daun. Rhizofiltrasi yaitu penggunaan akar tumbuhan, digunakan untuk menyerap bahan pencemar terutama logam dari air, tanah dan air limbah. Fitodegradasi adalah degradasi pencemar organik
oleh tumbuhan dengan bantuaneenzim dehalogenase dannoksigenase dimana tumbuhan dapat mengakumulasi xenobiotic organik dari lingkungan tercemar sera mendetoksifikasi melalui metabolisme tanaman. Fitostabilisasi yaitu proses yang dilakukan tanaman untuk mentransformasikan polutan di dalam tanah menjadi senyawa yang non toksik tanpa menyerap terlebih dahulu polutan tersebut ke dalam tubuh tanaman. Fitovolatilisasi yaitu tanaman digunakan untuk penyerapan unsur beracun dari dalam tanah lalu menguapkannya dari daun.
Tanaman kayu apu dalam proses pengontakan mengalami perubahan morfologi karena merupakan sebuah bentuk respon tanaman kayu apu diakibatkan kontak langsung dengan air limbah yang mengandung logam berat. Pada penelitian ini terjadi perubahan fisik tanaman yaitu perubahan warna pada daun menjadi kuning dan akar mulai rontok. Hal ini juga terjadi pada penelitian (Khasanah et al., 2018) dimana kayu apu dikontakan dengan limbah cair yang mengandung logam berat merkuri (Hg) mengalami perubahan yang sama yaitu ditandai dengan kondisi daun yang mulai berwarna kekuningan dan akhirnya mati serta akar tanaman juga mengalami kerontokan. Berdasarkan penelitian (Fachrurozi et al., 2010) perubahan warna pada daun disebabkan oleh menurunnya klorofil akibat dari beban polutan yang tinggi. Menurut Purnama et al., (2018) tanaman kayu apu yang ditanam pada konsentrasi tinggi akan berdampak pada penurunan metabolisme sehingga mengakibatkan jaringan sel dalam akar cepat rusak, hal ini akan berdampak pada produksi fitokelatin. Fitokelatin berfungsi sebagai detoksifikasi terhadap tanaman dari logam berat misalnya dengan penimbunan logam di dalam organ tertentu seperti akar dan lateks. Tanaman kayu apu mengandung fitokelatin yang banyak. Fitokelatin pada tanaman kayu apu terdapat pada akar dan daun tanaman (Utami et al., 2017). Penurunan metabolisme ditandai dengan perubahan fisik pada daun yang semakin lama akan berubah warna menjadi kekuningan serta daun akan mengalami kerontokan. Penurunan
metabolisme diakibatkan oleh hiperakumulasi ion logam yang berlebih.
SIMPULAN
Rerata kadar Cr total pada kelompok tanpa kayu apu atau kelompok kontrol adalah sebesar 0.509 mg/L. Rerata kadar kelompok perlakuan dengan penambahan kayu apu yaitu P1 dengan berat tanaman 300 gr/6L sebesar 0.371 mg/L, kelompok perlakuan kedua yaitu P2 dengan berat tanaman 350 gr/6L sebesar 0.293 mg/L dan kelompok perlakuan ketiga yaitu P3 dengan berat tanaman 400 gr/6L sebesar 0.165 mg/L. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jatim No. 52 tahun 2014 kadar Cr-T pada semua kelompok sudah di bawah Baku Mutu Lingkungan yaitu 1 mg/L. Kelompok K dengan kelompok perlakuan memiliki perbedaan kadar Cr-T yaitu dilihat dari nilai signifikansinya. Nilai signifikansi empat kelompok adalah P1 sebesar 0.007, P2 sebesar 0.0042 dan P3 sebesar 0.000. Nilai signifikansi menunjukkan perlakuan yang paling efektif yaitu terdapat pada kelompok P3 dengan penambahan berat paling banyak yaitu 400 gr/6L tanaman kayu apu dengan waktu kontak 10 hari.
UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada Andrei Ramani, S.KM., M.Kes, Ellyke, S.KM., M.KL dan Eka Agustina, S.T. selaku dosen penguji. Terima kasih juga terhadap Industri Batik X yang telah memberikan sampel limbah cair batik dalam penelitian ini serta Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Jember sebagai tempat pengecekan kadar logam chromium total pada limbah cair batik.
KEPUSTAKAAN
Andriani R, Hartini. 2017. Toksisitas Limbah Cair Industri Batik Terhadap Morfologi Sisik Ikan Nila Gift (Oreochomis Nilotocus). Jurnal SainHealth 1(2): 32-40.
Fachrurozi M, Utami LB, Suryani D. 2010. Pengaruh Variasi Biomassa Pistia Stratiotes L. Terhadap Penurunan Kadar Bod, Cod, Dan Tss Limbah Cair Tahu Di Dusun Klero
Sleman Yogyakarta. Jurnal Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health) 4(1): 1–16. https://doi:
10.12928/kesmas.v4i1.1100.
Handayanto E, Nuraini Y, Muddarisna N, Syam N, Fiqri A. 2017. Fitoremediasi dan Phytomining Logam Berat Pencemar Tanah. Malang: UB Press.
Hapsari S, Zaman B, Andarani P. 2016. Kemampuan Tumbuhan Kayu Apu (Pistia stratiotes L.) dalam Menyisihkan Kromium Total (Cr-T) dan COD Limbah Elektroplating. Jurnal Teknik Lingkungan. 5(4): 1-9.
Henrasarie N. 2019. Kemampuan Adsorbsi Pb dari Limbah Industri oleh Tumbuhan Kayu Ambang (Lemna minor), Kayu Apu (Pistia stratiotes) dan Eceng Gondok (Eichhornia crassipes solm). Jurnal Envirotek 11(1): 3945. https://doi:
10.33005/envirotek.v11i1.1368.
Herlambang P, Hendriyanto O. 2015. Fitoremediasi Limbah Detergen
Menggunakan Kayu Apu (Pistia stratiotes L.) dan Genjer (Limnocharis flava L.) Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan 7(2): 115–124.
Ikawati S, Zulfikar A, Azizah D. 2013. Efektivitas Dan Efisiensi Fitoremediasi Pada Deterjen Dengan Menggunakan Tanaman Genjer (Limnocharis Flava). http://jurnal.umrah.ac. id/wp-content/uploads/2013/08/SariIkawati-090254242080.pdf.
Irhamni, Pandia S, Purba E, Hasan W. 2018. Kajian Akumulator Beberapa Tumbuhan Air dalam Menyerap Logam Berat secara Fitoremediasi. Jurnal Serambi Engeneering 3(2): 344–351. https://doi:
10.5281/ZENODO.400012.
Jamil A, Darundiati YH, Dewanti NAY. 2016. Pengaruh Variasi Lama Waktu Kontak Dan Jumlah Tanaman Kayu Apu (Pistia
Stratiotes) Terhadap Penurunan Kadar
Cadmium (Cd) Limbah Cair Batik Home Industry “X” Di Magelang. Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas
Diponegoro 4(4): 763–770.
Khasanah M, Moelyaningrum AD, Pujiati RS. 2018. Analisis perbedaan tanaman kayu apu (Pistia stratiotes) sebagai fitoremediasi
merkuri (Hg) pada air. Sanitasi: Jurnal kesehatan lingkungan 9(3): 105-110.
Nurkhasanah S. 2015. Kandungan Logam Berat Kromium (Cr) Dalam Air, Sedimen, dan Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) serta
Karakteristik Biometrik dan Kondisi Histologisnya di Sungai Cimanuk Lama, Kabupaten Indramayu. [Tesis] Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Institut Pertanian Bogor.
Perwitasari P, Handayanto E, Rindyastuti R. 2018. Penggunaan Echinodorus Radicans dan Pistia Stratiotes Untuk Fitoremediasi Air Tercemar Timbal (Pb) Serta Pengaruhnya Terhadap Tanaman Amaranthus Tricolor. Jurnal Tanah dan Sumberdaya Lahan 5(1): 2549–9793.
Pridyanti DD, Moelyaningrum AD, Ningrum PT. 2018. Pemanfaatan Limbah Cangkang Kupang (Corbula Faba) Teraktivasi Termal Sebagai Adsorben Logam Kromium (Cr6+) Pada Limbah Cair Batik. Jurnal Hibualamo: Seri Ilmu-ilmu Alam dan Kesehatan 2(2): 63–68.
Purnama MS, Kusumawati E, Susanto D. 2018. Fitoremediasi Menggunakan Kayu Apu (Pistia stratiotes L.) dalam Kolam Bekas Tambang Batubara Terhadap Penyerapan Logam Mangan (Mn) dan Kadmium (Cd). Jurnal Bioprospek 13(1): 33-39.
Purnamawati KY, Budiarsa Suyasa I, Mahardika I. 2015. Penurunan Kadar Rhodamin B Dalam Air Limbah Dengan Biofiltrasi Sistem Tanaman. Jurnal ECOTROPHIC 9(2): 4651. https://doi:
10.24843/ejes.2015.v09.i02.p08.
Rahayuningtyas I, Wahyuningsih NE, Budiyono. 2018. Pengaruh Variasi Lama Waktu Kontak Dan Berat Tanaman Apu-Apu (Pistia
Stratiotes L.) Terhadap Kadar Timbal Pada Irigasi Pertanian. Jurnal Kesehatan Masyarakat 6(6): 166-174.
crassipes) dan Kayu Apu (Pistia stratiotes). [Skripsi] Surabaya: Jurusan Teknik
Lingkungan. Institut Teknologi Sepuluh November.
Raissa DG, Tangahu BV. 2017. Fitoremediasi Air yang Tercemar Limbah Laundry dengan Menggunakan Kayu apu (Pistia stratiotes). Jurnal Teknik ITS 6(2): 7-11. https://doi: 10.12962/j23373539.v6i2.25092.
Sari AM, Rachmadiarti F, Fitrihidayati H. 2014. Pengaruh Cekaman Kromium pada Limbah Cair Batik terhadap Pertumbuhan Eichornia crassipes dan Salvinia molesta. Jurnal Lentera Bio 3(1): 67-71.
Sari NWM, Diara IW, Trigunasih NM. 2017. Meningkatkan Kualitas Air Irigasi dengan Menggunakan Tanaman Kayu Apu (Pistia stratiotes L.) dan Tanaman Azolla (Azolla sp.) di Subak Sembung, Peguyangan, Denpasar. Journal of Tropical
Agroecotechnology 6(1): 82-90.
Setiyono A, Gustaman RA. 2017. Pengendalian Kromium (Cr) Yang Terdapat Di Limbah Batik Dengan Metode Fitoremediasi. Unnes Journal of Public Health 6(3): 155-160.
https://doi: 10.15294/ujph.v6i3.15754.
Utami LD, Narwati, Rahayu U. 2017. Kemampuan Tanaman Apu-apu (Pistia stratiotes L.) dalam Menurunkan Kadar Logam Berat Nikel (Ni) Limbah Cair. Jurnal Gema Kesehatan Lingkungan 15(1): 46-51.
Wirawan WA, Wirosoedarmo R, Susanawati LD. 2014. Pengolahan Limbah Cair Domestik Menggunakan Tanaman Kayu Apu (Pistia stratiotes L.) dengan Teknik Tanam Hidroponik Sistem DFT
(DeepFlowTechnique). Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan 1(2): 63-70.
Zarkasi K, Moelyaningrum AD, Trirahayu NP. 2018. Penggunaan Arang Aktif Kulit Durian (Durio Zibethinus Murr) Terhadap Tingkat Adsorpsi Kromium (Cr6+) Pada Limbah Batik. Jurnal Efektor 5(2): 67-73.
Raissa DG. 2017. Fitoremediasi Air yang Tercemar Limbah Laundry dengan Menggunakan Eceng Gondok (Eichhornia
54
Discussion and feedback